Pendahuluan: Membongkar Bias Barat dalam Studi Intelijen
Ketika kita berbicara tentang intelijen, imajinasi publik kerap langsung menuju CIA di Amerika, MI6 di Inggris, atau Mossad di Israel. Narasi besar tentang dunia spionase hampir selalu didominasi oleh Barat, seakan-akan pengetahuan intelijen hanyalah monopoli mereka. Namun, buku Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere yang disunting oleh Philip H. J. Davies dan Kristian C. Gustafson menantang bias ini dengan menghadirkan potret luas tentang bagaimana intelijen tumbuh, beroperasi, dan membentuk dinamika politik di luar lingkaran Anglo-Amerika.
Buku ini hadir sebagai koreksi atas minimnya studi komparatif di bidang intelijen. Jika selama ini literatur akademik lebih banyak menyoroti praktik di Eropa dan Amerika, maka karya ini mengajak pembaca menoleh ke Timur: dari Tiongkok, India, dunia Islam, hingga Asia Tenggara. Dengan pendekatan historis sekaligus kontemporer, Davies dan Gustafson menegaskan bahwa intelijen adalah praktik universal yang selalu terikat pada konteks budaya, sejarah, dan politik masing-masing negara.
Sejak halaman awal, pembaca sudah disuguhi kritik metodologis: mengapa intelijen di luar Anglo-Saxon jarang dikaji serius? Apakah karena kerahasiaan yang lebih ketat, atau karena bias akademik yang melihat Barat sebagai “standar” intelijen modern? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jalan bagi sebuah perjalanan intelektual yang menggugah, di mana kita melihat intelijen bukan sekadar tentang operasi rahasia, tetapi juga sebagai refleksi dari cara bangsa-bangsa membangun identitas dan keamanan mereka.
Intelijen dan Budaya Politik: Dari Arthashastra hingga Bizantium
Salah satu kekuatan buku ini adalah keberaniannya menelusuri akar budaya intelijen. Ralph D. Sawyer, misalnya, menulis tentang tradisi Tiongkok dan bagaimana strategi perang Sun Tzu memberi warna mendalam pada praktik intelijen mereka. Dalam konteks India, Philip H. J. Davies menghidupkan kembali Arthashastra karya Kautilya—sebuah teks klasik yang memandang spionase sebagai bagian integral dari tata kelola kerajaan. Sejak masa itu, intelijen bukan hanya alat perang, tetapi juga mekanisme politik untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan.
Kristian Gustafson kemudian menguraikan bagaimana Rusia membawa warisan Bizantium ke dalam sistem keamanan modern mereka. Alih-alih semata-mata produk komunisme Soviet, intelijen Rusia memiliki akar yang jauh lebih tua: sebuah pola politik yang menekankan kontrol, kerahasiaan, dan ortodoksi kekuasaan. Perspektif ini menantang anggapan bahwa spionase Soviet hanyalah hasil dari ideologi Marxis-Leninis. Justru, ia memperlihatkan kesinambungan historis yang panjang.
Abdulaziz A. Al-Asmari menambahkan dimensi Arab-Islam, menyingkap bagaimana dunia Islam memiliki tradisi intelijen sendiri yang kerap diabaikan dalam kajian global. Di sini, intelijen dipandang sebagai instrumen moral dan politik sekaligus, dengan tujuan menjaga ummah dari ancaman luar. Bab ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana Timur Tengah hingga kini memadukan keamanan dengan identitas religius.
Praktik Kontemporer: Pakistan, Iran, Indonesia, dan Jepang
Memasuki bagian praktik kontemporer, buku ini menghadirkan studi kasus yang membuka mata. Robert Johnson menyoroti peran Inter-Services Intelligence (ISI) di Pakistan, sebuah lembaga yang tidak hanya kuat di dalam negeri tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap geopolitik Asia Selatan. ISI sering dipotret negatif di Barat, namun buku ini mengajak kita memahami konteks internal Pakistan yang menjadikan ISI sebagai aktor politik dan keamanan utama.
Carl Anthony Wege menelusuri intelijen Iran dengan fokus pada bagaimana negara tersebut membangun jaringan yang kompleks antara militer, agama, dan politik. Intelijen Iran bukan hanya alat negara, tetapi juga refleksi dari model teokrasi revolusioner yang unik. Dalam situasi geopolitik penuh tekanan, intelijen Iran menjadi instrumen survival sekaligus ekspansi pengaruh di kawasan.
Menariknya, ada pula pembahasan tentang Indonesia melalui tulisan Peter Gill dan Lee Wilson mengenai reformasi sektor keamanan pasca-Orde Baru. Di sini, kita melihat bagaimana BIN (Badan Intelijen Negara) berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan demokratisasi, meski masih menyisakan problem klasik: kerahasiaan versus akuntabilitas. Sementara itu, Ken Kotani membuka lembaran sejarah intelijen Jepang, memperlihatkan bagaimana negeri tersebut bertransformasi dari kekuatan militer imperialis menjadi negara demokrasi dengan dilema keamanan yang tetap besar.
Reformasi, Perbandingan, dan Masa Depan Studi Intelijen
Selain menyoroti praktik masing-masing negara, buku ini juga menawarkan refleksi teoretis penting. Emmanuel Kwesi Aning menulis tentang Ghana dan bagaimana negara itu berupaya membangun budaya intelijen demokratis di tengah warisan kolonial. Eduardo E. Estévez membahas reformasi komunitas intelijen Argentina, sementara Lauri Holmström menelusuri praktik intelijen di Swedia yang terkenal “jalan tengah.” Semua studi kasus ini menunjukkan bahwa intelijen tidak bisa dilepaskan dari struktur politik yang melingkupinya.
Davies dan Gustafson menutup buku ini dengan refleksi tentang warisan, improvisasi, dan inovasi dalam intelijen global. Mereka menekankan bahwa meski intelijen memiliki fungsi inti yang universal—pengumpulan informasi, analisis, kontra-spionase, dan penyampaian informasi—namun praktik dan budaya di tiap negara berbeda secara signifikan. Justru di situlah letak pentingnya studi komparatif: untuk memahami keberagaman tanpa terjebak dalam bias universalitas ala Barat.
Buku ini, dengan demikian, bukan hanya kumpulan esai, melainkan manifesto intelektual untuk memperluas horizon studi intelijen. Ia mengingatkan kita bahwa memahami dunia tidak cukup hanya dengan mendengar dari satu sumber. Sama seperti diplomasi dan politik, intelijen pun memiliki “aksen lokal” yang perlu dipahami dalam konteks masing-masing bangsa.
Kesimpulan: Membaca Intelijen dengan Lensa Global
Intelligence Elsewhere adalah bacaan yang menantang dan memperkaya, terutama bagi mereka yang terbiasa melihat dunia intelijen hanya dari perspektif Barat. Dengan menggabungkan sejarah panjang, analisis budaya, dan praktik kontemporer, buku ini membuka jalan bagi sebuah studi intelijen yang lebih plural, kritis, dan reflektif.
Bagi saya, buku ini mengingatkan bahwa intelijen bukan sekadar teknik spionase atau operasi rahasia, melainkan cermin dari peradaban. Dari Arthashastra di India, tradisi Sun Tzu di Tiongkok, hingga reformasi intelijen di Indonesia dan Ghana, semua memperlihatkan bahwa intelijen selalu lahir dari rahim sejarah dan budaya lokal. Inilah yang membuatnya relevan dibaca dalam konteks global yang semakin saling terkait.
Melalui review ini, saya ingin menegaskan kembali posisi KBA13 Insight sebagai ruang kajian kritis yang berani melampaui arus utama. Membaca buku ini sama artinya dengan belajar bagaimana dunia luar membangun logika keamanan dan informasi mereka sendiri. Sebuah bacaan penting, terutama bagi siapa pun yang tertarik pada intelijen, geopolitik, dan masa depan hubungan internasional.

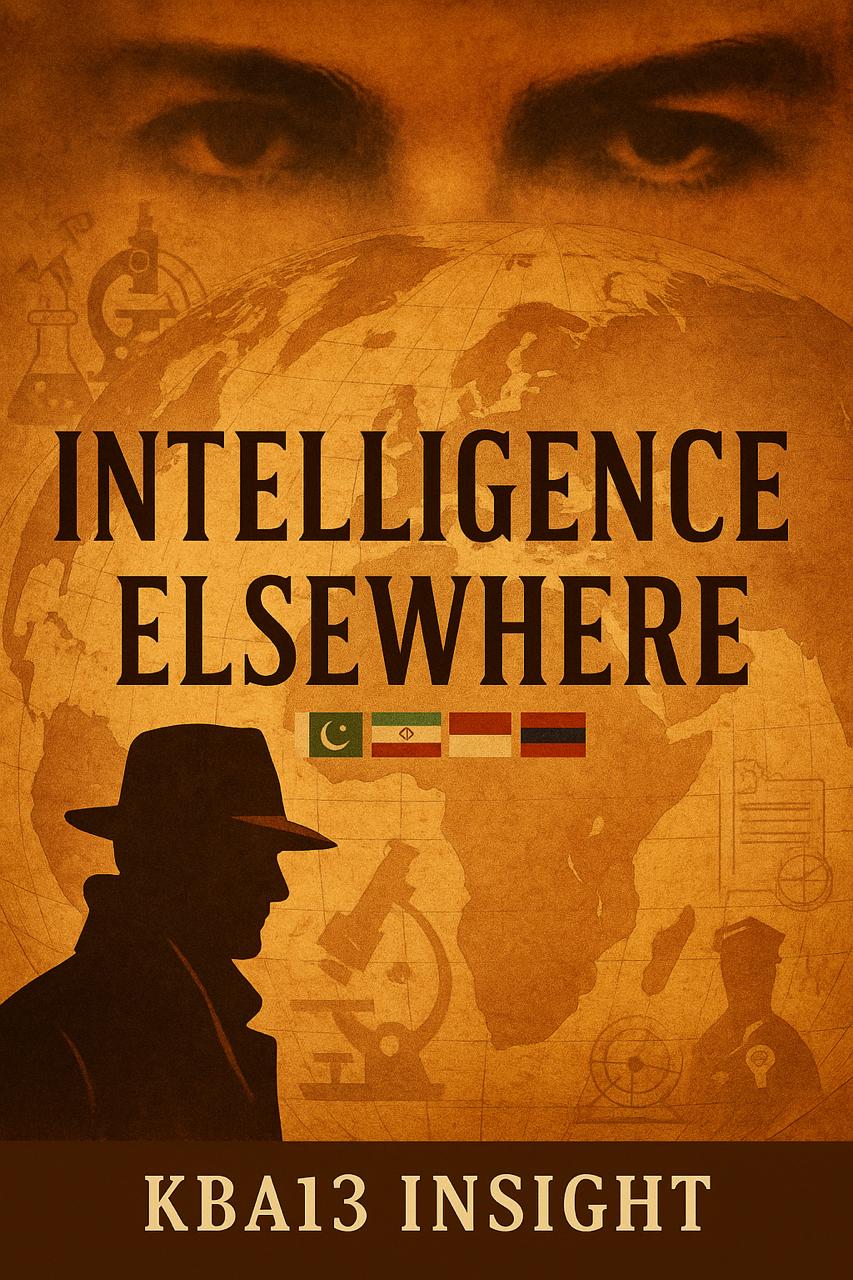

Leave a Reply