Pendahuluan
Karya populer sering kali diangkat menjadi ladang komersial tanpa mempertimbangkan sensitivitas korban. Hafalan Shalat Delisa dan film adaptasinya merupakan contoh nyata bagaimana tragedi tsunami Aceh diubah menjadi produk hiburan yang meraup keuntungan. Narasi yang diusung tidak hanya mengambil latar tempat dan waktu yang identik dengan bencana nyata, tetapi juga menggunakan nama tokoh korban yang masih hidup. Ketika pembaca dan penonton yang tidak paham konteks mempercayai kisah ini sebagai kebenaran, korban dan masyarakat Aceh merasakan kembali luka lama yang diperdagangkan tanpa seizin mereka[1].
Novel dan film Hafalan Shalat Delisa sering dipuji sebagai karya menyentuh yang mengisahkan keteguhan seorang anak dalam menghadapi bencana. Namun di balik narasi haru tersebut, terdapat problem besar yang jarang disorot: bagaimana penderitaan manusia dijadikan komoditas. Karya ini lahir dari tragedi nyata, yaitu tsunami Aceh 2004, sebuah peristiwa yang menelan lebih dari seratus ribu nyawa dan meninggalkan luka kolektif yang dalam. Mengambil latar dan nama korban sebenarnya, cerita ini menimbulkan pertanyaan moral tentang batas antara empati dan eksploitasi.
Dalam masyarakat yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran, karya semacam ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi medium pengingat dan penyembuhan. Namun di sisi lain, tanpa riset dan sensitivitas budaya yang memadai, karya tersebut justru mengulang trauma dan mereduksi tragedi menjadi tontonan sentimental. Novel Hafalan Shalat Delisa dan adaptasi filmnya mencerminkan dilema itu secara gamblang.
Bagi banyak pembaca dan penonton, kisah Delisa adalah kisah spiritual. Namun bagi masyarakat Aceh, terutama mereka yang pernah kehilangan keluarga dalam tsunami, kisah ini menghadirkan luka baru. Nama dan kisah seorang penyintas sungguhan digunakan tanpa izin atau klarifikasi yang memadai. Penderitaan pribadi berubah menjadi bahan promosi, sementara mereka yang kisahnya diambil tidak memperoleh ruang untuk bersuara.
Fenomena semacam ini memperlihatkan wajah lain industri kreatif: bagaimana pasar lebih berkuasa daripada moral. Dalam upaya menciptakan cerita yang “menyentuh hati,” sering kali produser dan penulis lupa bahwa di balik kisah tersebut ada manusia yang benar-benar terluka. Aceh bukan sekadar latar; ia adalah ruang sejarah dan penderitaan nyata yang seharusnya dihormati, bukan diperdagangkan.
Melalui pembacaan kritis terhadap novel dan film ini, tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat ulang praktik representasi tragedi di Indonesia. Karya sastra dan film yang berangkat dari bencana seharusnya menjadi jembatan empati, bukan sarana komersialisasi. Lebih dari sekadar mengisahkan penderitaan, karya yang baik mestinya menegakkan keadilan bagi mereka yang menjadi sumber inspirasinya.
Dengan demikian, pembahasan ini bukan untuk meniadakan nilai spiritual yang mungkin dibawa karya tersebut, tetapi untuk mempertanyakan kejujuran, kepekaan, dan tanggung jawab di baliknya. Tragedi tidak boleh dijadikan panggung keuntungan. Tragedi adalah memori kolektif yang harus dijaga martabatnya dengan penghormatan, kejujuran, dan kebijaksanaan naratif.
Eksploitasi Derita dalam Novel
Sejak awal, Novel ini memulai kisah dengan gambaran indah kehidupan Lhok Nga, Aceh. Adzan subuh, anak-anak belajar mengaji, dan keluarga kecil yang harmonis. Lalu tiba-tiba gempa dan tsunami datang. Penulis menggambarkan kehancuran Banda Aceh dan Lhok Nga secara dramatis—bangunan runtuh, air setinggi sepuluh meter menelan segalanya. Latar ini bukan sekadar latar, melainkan peristiwa historis yang menewaskan ratusan ribu orang. Menggunakan tragedi tersebut untuk efek dramatis tanpa seizin keluarga korban adalah bentuk eksploitasi.
Penderitaan Delisa digambarkan berulang-ulang: kakinya terjepit puing, tubuhnya kelaparan, dan kulitnya terpanggang matahari selama berhari-hari. Adegan ini menimbulkan simpati pembaca, namun ia diubah menjadi komoditas air mata. Alih-alih mengajak pembaca memahami realitas korban, penulis justru mengemasnya menjadi tontonan heroik dengan bumbu spiritual. Tubuh Delisa yang “bercahaya” digambarkan sebagai keajaiban yang memukau prajurit asing. Romantisasi penderitaan seperti ini meremehkan trauma nyata dan menyesatkan pembaca bahwa tragedi memiliki aspek estetis.
Nama “Delisa” bukan nama yang acak; ia merujuk pada Delisa Fitri Rahmadani yang benar-benar selamat dari tsunami dan kehilangan kaki. Dokumentasi MetroTV menunjukkan ia diselamatkan oleh warga lokal bernama Pak Didi[2]. Penulis tetap memakai nama yang sama tanpa memberi klarifikasi dalam novel, sehingga banyak pembaca meyakini kisah fiksi tersebut sebagai kisah Delisa Fitri. Ini melukai korban karena cerita nyata mereka diselewengkan demi kepentingan penulis.
Novel juga hampir tidak menyentuh aspek struktural tragedi, seperti minimnya peringatan tsunami, kegagalan negara, atau kesedihan kolektif. Fokus hanya pada Delisa dan prajurit asing. Dengan demikian, penderitaan massal Aceh diringkas menjadi kisah satu orang, sementara korban lain seolah tidak penting. Pendekatan ini menyingkirkan konteks sosial dan politik yang seharusnya ada dalam karya yang mengambil latar bencana.
Selain itu, penulis menolak membahas inspirasi atau melakukan klarifikasi terbuka mengenai kemiripan kisah fiksi dengan kejadian nyata. Keengganan ini dapat dipahami sebagai strategi untuk menghindari tanggung jawab moral. Tanpa pengakuan publik, penulis dapat terus menikmati keuntungan materi dari karya tersebut. Korban yang cerita hidupnya diambil tidak mendapatkan apa-apa selain beban psikologis ketika melihat penderitaannya dikomersialisasikan.
Banyak pembaca yang menemukan novel ini di toko buku tidak menyadari bahwa latar dan tokoh diambil dari peristiwa nyata. Ketiadaan pengantar atau penjelasan di halaman awal membuat mereka semakin keliru. Ini adalah bentuk misinformasi yang disengaja. Kejelasan seharusnya menjadi tanggung jawab penulis, terutama ketika memanfaatkan tragedi nyata.
Secara keseluruhan, novel ini tidak hanya memanfaatkan tragedi, tetapi juga memutarbalikkan fakta tentang bagaimana Delisa selamat. Penulis memaksakan narasi yang lebih dramatis dan religius demi keuntungan penjualan, tanpa menghormati kisah nyata penyintas atau memperhatikan sensitivitas keluarga korban.
Narasi White Saviour: Menghapus Agensi Lokal
Salah satu aspek paling bermasalah dari novel ini adalah penghapusan peran warga lokal dalam penyelamatan Delisa. Dalam kenyataan, Delisa Fitri diselamatkan oleh Pak Didi, seorang warga Aceh[2]. Namun, novel menggantikan tokoh tersebut dengan prajurit Smith dan Sersan Ahmed, marinir asing dari kapal induk. Mereka digambarkan turun dari helikopter, menyisir puing, dan menemukan Delisa dalam kondisi sekarat. Penggambaran ini menempatkan prajurit asing sebagai pahlawan utama.
Narasi ini sejalan dengan “white saviour narrative”, di mana penyelamat berasal dari Barat sementara korban lokal digambarkan tak berdaya. Penceritaan seperti ini menyesatkan karena mengesankan masyarakat Aceh tidak mampu menolong diri sendiri. Dalam bencana nyata, warga lokal justru aktor utama dalam penyelamatan. Penulis mengabaikan fakta itu demi dramatisasi yang mudah dipahami pembaca umum.
Prajurit Smith tidak hanya menyelamatkan Delisa, tetapi juga mengalami transformasi spiritual. Menyaksikan “wajah bercahaya” Delisa membuatnya menangis, mengingat anaknya sendiri, dan memutuskan memeluk Islam. Kisah pertobatan ini memanfaatkan penderitaan anak kecil untuk menebus duka prajurit Amerika. Penulis seolah menukar penderitaan korban dengan penyadaran moral prajurit asing. Ini merendahkan pengalaman Delisa yang sebenarnya.
Narasi white saviour juga menimbulkan dampak politis. Pembaca yang tidak tahu konteks bisa berpikir bantuan asing adalah penyelamat utama Aceh, padahal peran militer Indonesia dan relawan lokal jauh lebih besar. Bila cerita seperti ini dibiarkan menjadi kebenaran, persepsi publik akan berubah. Hal ini melemahkan penghargaan terhadap ketahanan lokal dan memperkuat ketergantungan kepada kekuatan asing.
Selain itu, white saviour narrative menunjukkan bias orientalis. Aceh digambarkan sebagai daerah terbelakang yang hanya bisa diselamatkan oleh Barat. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa masyarakat Aceh memiliki sistem kekerabatan kuat dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Buku ini justru menyederhanakan Aceh menjadi latar eksotis untuk drama spiritual prajurit asing.
Kritikus film juga menyoroti bahwa film adaptasi menampilkan relawan asing berbicara bahasa Inggris tanpa penerjemah, salah mengucapkan kata-kata Aceh, dan pakaian perawat yang tidak sesuai adat[3]. Adegan ini memperkuat kesan bahwa sutradara dan penulis skenario mengabaikan akurasi budaya. Ketika film ingin mengambil keuntungan dari cerita Aceh, seharusnya budaya setempat dihormati dan direpresentasikan dengan tepat.
Penggantian lokasi syuting ke Sukabumi atau Bangka Belitung dengan alasan “struktur alam Aceh berubah” memperburuk white saviour narrative[4]. Masyarakat Aceh tidak dilibatkan secara langsung, padahal merekalah yang menjadi subjek cerita. Keputusan ini menambah ketidakadilan karena penduduk lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau kesempatan untuk berpartisipasi.
Akhirnya, narasi white saviour dalam novel dan film adalah bukti eksploitasi, bukan hanya terhadap cerita Delisa, tetapi terhadap seluruh komunitas Aceh. Dengan menonjolkan penyelamat asing dan menyingkirkan aktor lokal, penulis dan produser memperkuat stereotip berbahaya dan mendistorsi sejarah.
Komersialisasi Film: Misinformasi dan Keterasingan Aceh
Film adaptasi Hafalan Shalat Delisa memperkaya kontroversi novel. Produser memilih Ujung Genteng, Sukabumi atau Bangka Belitung sebagai lokasi syuting karena “struktur alam Aceh berubah”[4]. Pilihan ini mengandung makna ekonomis: syuting di Aceh mungkin lebih mahal atau rumit. Namun, efeknya jelas: warga Aceh tidak menerima manfaat ekonomi, sementara film menampilkan pemandangan pantai yang bukan Aceh.
Adaptasi film seharusnya bisa memperbaiki kekurangan novel dengan melibatkan penduduk lokal dan riset budaya. Namun, justru sebaliknya. Pengucapan “meunasah” menjadi “munasah” dan busana perawat yang tidak sesuai adat memperlihatkan kurangnya riset[3]. Kesalahan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap detail budaya Aceh, yang seharusnya menjadi inti cerita.
Film juga memuat adegan heroik marinir asing yang mengevakuasi Delisa dengan helikopter Super Puma. Visualisasi ini dibuat dramatis dengan slow-motion dan musik melankolis. Penonton awam terhanyut dan menganggap pahlawan asing sebagai tokoh utama. Narasi heroik ini memperkuat pesan yang sama dengan novel: Aceh diselamatkan oleh kekuatan luar.
Selain lokasi, aspek produksi lainnya menimbulkan pertanyaan etika. Banyak warga Aceh dan keluarga korban tidak diajak berdiskusi atau dilibatkan dalam produksi. Padahal, film yang mengangkat cerita mereka seharusnya memberikan ruang partisipasi. Ketidaklibatan ini menunjukkan produser lebih mementingkan keuntungan daripada penghormatan kepada subjek cerita.
Film adaptasi turut mempromosikan wilayah syuting non-Aceh sebagai destinasi wisata. Jika film memuji keindahan pantai Sukabumi atau Bangka Belitung sementara tragedi Aceh menjadi latar, maka film berubah menjadi iklan pariwisata yang menunggangi tragedi. Ini menambah lapisan eksploitasi: penderitaan korban digunakan untuk mempromosikan daerah lain.
Saat film dirilis, banyak sekolah menjadikannya bahan edukasi. Anak-anak menonton film sambil belajar doa. Namun, isi film penuh misinformasi dan distorsi. Pendidikan seharusnya berdasar fakta, bukan fiksi yang menyesatkan. Film ini justru menanamkan persepsi salah kepada generasi muda.
Kritik terhadap film tidak banyak diangkat media nasional. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan media untuk mendukung industri film tanpa mengkritisi etika. Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus mengisi kekosongan dengan mendiskusikan film secara kritis.
Secara keseluruhan, film adaptasi bukan hanya gagal memperbaiki narasi, tetapi juga memperluas komersialisasi. Aceh tetap terasing, misinformasi meluas, dan industri film mendapatkan keuntungan dari cerita derita.
Evaluasi Etika Sastra
Dalam dunia sastra, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental. Penulis berhak menulis fiksi yang terinspirasi tragedi. Namun, ketika inspirasi itu begitu mirip dengan kisah nyata seseorang—nama, latar, peristiwa—penulis wajib menjelaskan perbedaannya. Novel ini gagal memenuhi standar tersebut.
Etika sastra mensyaratkan penghormatan terhadap subjek dan konteks. Kisah Delisa fiksi melibatkan peristiwa kematian massal. Menangis di atas penderitaan, lalu menjualnya sebagai hiburan, tanpa mengakui korban asli, melanggar norma kemanusiaan. Penulis seolah menganggap tragedi hanya bahan baku dramatis, bukan trauma kolektif.
Beberapa pembaca membela penulis dengan alasan “hak cipta” dan “fiksi bebas”. Argumen ini mengabaikan dimensi moral. Kesusastraan tidak hanya soal hak cipta, tetapi juga tanggung jawab moral. Menuliskan penderitaan orang lain memerlukan sensitivitas dan empati.
Selain itu, novel ini menyebarkan pesan moral tentang keikhlasan dan hidayah. Pesan ini mulia, tetapi cara penyampaiannya problematis. Penderitaan Delisa dijadikan alat dakwah; keikhlasan dibuktikan melalui amputasi dan kehilangan keluarga. Ini menyampaikan pesan implisit bahwa penderitaan fisik diperlukan agar seseorang (atau orang lain) mendapat hidayah. Pesan seperti ini bisa berbahaya karena meromantisasi penderitaan.
Penulis juga menolak berdiskusi tentang validitas cerita. Sikap anti kritik ini bertentangan dengan tradisi sastra yang sehat. Karya besar selalu terbuka untuk kritik. Ketika penulis menutup pintu diskusi, muncul kesan bahwa mereka menyadari ada kesalahan etika, tetapi memilih menghindar.
Dalam literatur global, ada contoh penulis yang berhasil menulis fiksi bencana dengan etis. Mereka biasanya menyamarkan nama, mengganti latar, dan mencantumkan catatan pengantar yang menjelaskan sumber inspirasi. Atau mereka menulis nonfiksi, lalu membagi royalti dengan korban. Langkah-langkah tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab. Sayangnya, penulis Hafalan Shalat Delisa tidak melakukan itu.
Etika sastra juga mencakup keakuratan dan riset budaya. Novel memuat istilah Aceh, tetapi film adaptasi salah mengucapkannya[3]. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara teks dan adaptasi. Penulis dan tim produksi seharusnya berkonsultasi dengan ahli bahasa untuk memastikan keakuratan.
Akhirnya, novel dan film ini menunjukkan bagaimana etika seringkali dikorbankan demi penjualan. Ketika karya sastra menjadi industri, nilai moral cenderung terpinggirkan. Penulis dan produser memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kebebasan kreatif dengan keadilan terhadap subjek cerita.
Kejujuran Penulis dan Respons Publik
Kejujuran merupakan inti dari kepercayaan publik. Penulis novel ini telah menyatakan bahwa cerita Delisa fiksi dan tidak terkait dengan orang nyata. Namun, fakta bahwa novel mencantumkan tempat, waktu, dan nama yang sama dengan tragedi Aceh membuat pernyataan itu tidak meyakinkan. Banyak pembaca menilai penulis tidak jujur dan bersikap defensif ketika dikritik.
Respons publik beragam. Sebagian pembaca menikmati novel dan film tanpa memikirkan implikasi etika. Mereka fokus pada pesan moral tentang sabar dan syukur. Namun, respons ini sebagian disebabkan kurangnya informasi. Ketika orang mengetahui kemiripan novel dengan kisah Delisa Fitri, mereka marah. Mereka merasa penulis memanfaatkan nama korban dan menolak bertanggung jawab[1].
Penulis juga cenderung menutup ruang diskusi. Ketika kritik muncul di media sosial, mereka sering menghapus komentar atau menutup kolom komentar. Sikap ini memperlihatkan ketidakpedulian terhadap perasaan korban. Publik menilai penulis lebih peduli menjaga citra dan keuntungan.
Ada kekhawatiran bahwa penulis dengan reputasi besar bisa lolos dari kritik karena memiliki basis penggemar yang loyal. Penggemar membela idola dengan mengatakan “namanya hanya kebetulan”. Argumen ini lemah karena nama Delisa cukup jarang, apalagi digabungkan dengan latar tsunami Aceh. Kemiripan itu terlalu signifikan untuk dianggap kebetulan.
Sikap penulis kontras dengan para penyair dan penulis lain yang merespons tragedi secara empatik. Beberapa penulis memilih menulis puisi untuk menghormati korban, menggalang donasi, dan mengarahkan royalti ke yayasan amal. Penulis Hafalan Shalat Delisa tidak melakukan hal tersebut.
Di sisi lain, keluarga Delisa Fitri pernah bertemu penulis yang mengatakan cerita itu fiksi[1]. Keluarga merasa kecewa tetapi tidak menuntut secara hukum. Kekecewaan mereka menunjukkan bahwa sekadar klarifikasi pribadi tidak cukup. Publik perlu mengetahui kebenaran agar tidak terjebak misinformasi.
Penulis juga pernah menyebut penjualan novelnya tinggi dan bangga atas film adaptasi. Ia jarang menyebut Aceh dalam promosi, mungkin untuk menghindari kontroversi. Namun, cara ini tidak efektif karena internet memudahkan orang menemukan keterkaitan. Ketiadaan pengakuan justru memperkuat kecurigaan.
Banyak suara publik yang menyerukan boikot. Mereka menuntut agar penulis dan produser meminta maaf kepada keluarga korban dan Aceh. Tuntutan ini bukan sekadar emosional; ini adalah seruan keadilan. Jika penulis ingin mempertahankan reputasinya, mereka sebaiknya mempertimbangkan permintaan tersebut.
Rekomendasi dan Seruan Etik
Bagian ini ditulis sebagai seruan mengalir, bukan daftar kering. Penulis dan produser film harus berhenti bersembunyi di balik klaim fiksi dan membeberkan inspirasi mereka dengan jujur. Klarifikasi publik bahwa nama, lokasi, dan waktu yang digunakan dalam novel diambil dari tragedi tsunami Aceh sangat diperlukan. Catatan pengantar di edisi selanjutnya harus menyatakan bahwa Delisa dalam novel bukan Delisa Fitri, serta memuat permohonan maaf kepada keluarga yang merasa tersakiti[1]. Transparansi semacam ini akan mengurangi kecurigaan publik dan menunjukkan itikad baik.
Kejujuran harus diikuti tindakan nyata. Penghasilan dari buku dan film sepatutnya dialokasikan sebagian untuk penyintas tsunami Aceh. Bantuan ini bisa berupa beasiswa pendidikan, dukungan psikologis, atau proyek pemberdayaan ekonomi. Selama ini, keuntungan mengalir ke kreator, sementara komunitas yang kisahnya dipakai tidak memperoleh apa pun. Menyalurkan sebagian royalti merupakan bentuk kompensasi moral yang wajib dilakukan.
Partisipasi masyarakat Aceh juga harus menjadi prioritas dalam setiap adaptasi atau karya lanjutan. Warga setempat mesti dilibatkan sebagai konsultan budaya, pemeran, atau kru produksi. Pelibatan ini mencegah kesalahan pengucapan dan representasi budaya seperti yang terjadi di film[3], serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh mereka. Tanpa pelibatan, narasi akan selalu terkesan eksploitatif.
Selanjutnya, karya adaptasi memerlukan riset budaya mendalam. Kesalahan mendasar seperti salah menyebut meunasah dan pakaian perawat yang tidak sesuai adat menunjukkan betapa dangkalnya riset[3]. Konsultasi dengan ahli bahasa dan adat Aceh wajib dilakukan agar cerita menghormati budaya yang diambil. Sekolah dan lembaga pendidikan pun harus mengajarkan literasi media kritis, supaya siswa mampu membedakan fakta dan fiksi serta memahami etika di balik karya populer. Dengan literasi yang kuat, masyarakat dapat menolak narasi yang mengeksploitasi tragedi tanpa rasa bersalah.
Industri kreatif Indonesia harus menyusun pedoman etika yang menuntut konsultasi dengan komunitas terdampak dan mekanisme bagi hasil saat mengangkat kisah penderitaan. Tanpa panduan seperti ini, eksploitasi akan terus berulang. Di sisi lain, penulis dan sineas Aceh perlu didorong menghasilkan karya yang merepresentasikan kisah mereka secara autentik. Karya-karya alternatif ini akan memperkaya narasi dan menantang dominasi cerita yang keliru. Publik hendaknya mendukung inisiatif tersebut sebagai bentuk solidaritas dan langkah konkrit untuk mengembalikan kisah Aceh kepada pemiliknya.
Akhirnya, kritik publik harus terus digaungkan. Suara protes yang berlandaskan fakta dan argumen tajam perlu disampaikan melalui media dan jalur hukum. Hanya dengan tekanan publik yang konsisten, penulis dan produser film dapat terdorong untuk berubah. Karya seni tidak kebal dari kritik; justru karya yang menyakiti komunitas harus dikritik demi keadilan dan penghormatan terhadap memori kolektif.
Kesimpulan
Kontroversi Hafalan Shalat Delisa mengajarkan kita bahwa eksploitasi derita untuk kepentingan komersial adalah pelanggaran etika. Novel dan film adaptasinya tidak hanya mengambil latar tsunami Aceh, tetapi juga memutarbalikkan kisah penyintas, menonjolkan prajurit asing, dan meromantisasi penderitaan. Akibatnya, korban merasakan luka ganda: penderitaan yang dahulu dialami kembali dijual tanpa izin.
Narasi white saviour menghapus peran warga Aceh dalam penyelamatan Delisa[2] dan mengangkat prajurit asing sebagai pahlawan. Film menambah masalah dengan memindahkan lokasi syuting ke daerah lain, salah mengucapkan istilah Aceh[3], dan menampilkan budaya secara keliru. Keputusan ini mengasingkan Aceh dari cerita tentang dirinya sendiri.
Penulis menolak mengakui kemiripan tokoh fiksi dengan Delisa Fitri, dan produser film lebih mementingkan keuntungan daripada keakuratan budaya. Tanpa transparansi dan kompensasi, karya ini tetap dipandang sebagai bentuk eksploitasi. Publik berhak untuk marah dan menuntut perubahan.
Etika sastra dan industri kreatif harus ditegakkan. Karya berbasis tragedi membutuhkan sensitivitas, konsultasi dengan korban, dan keterbukaan. Tanpa itu, karya seni hanya akan menjadi komoditas yang mengkomersialisasi penderitaan orang lain. Kritik tajam terhadap Hafalan Shalat Delisa merupakan upaya menuntut keadilan bagi Aceh dan penyintas tsunami serta mendorong standar moral yang lebih tinggi dalam industri budaya.
[1] Ponpes YTP Kertosono | Peradaban Maju dan Mendengarkan
https://www.arroudlotulilmiyah.sch.id/peradaban-maju-dan-mendengarkan
[2] Bangkit dari Tsunami, Delisa Buktikan Disabilitas Bukan Batasan
[3] Hafalan Surat Delisa | HafalanSuratDelisa
https://meitrypangastikaratam.wordpress.com/2012/05/27/hafalan-surat-delisa/
[4] Hafalan Shalat Delisa : Film Tentang Tsunami Aceh Rasa Sukabumi
https://www.beritasatu.com/news/22330/hafalan-shalat-delisa-film-tentang-tsunami-aceh-rasa-sukabumi

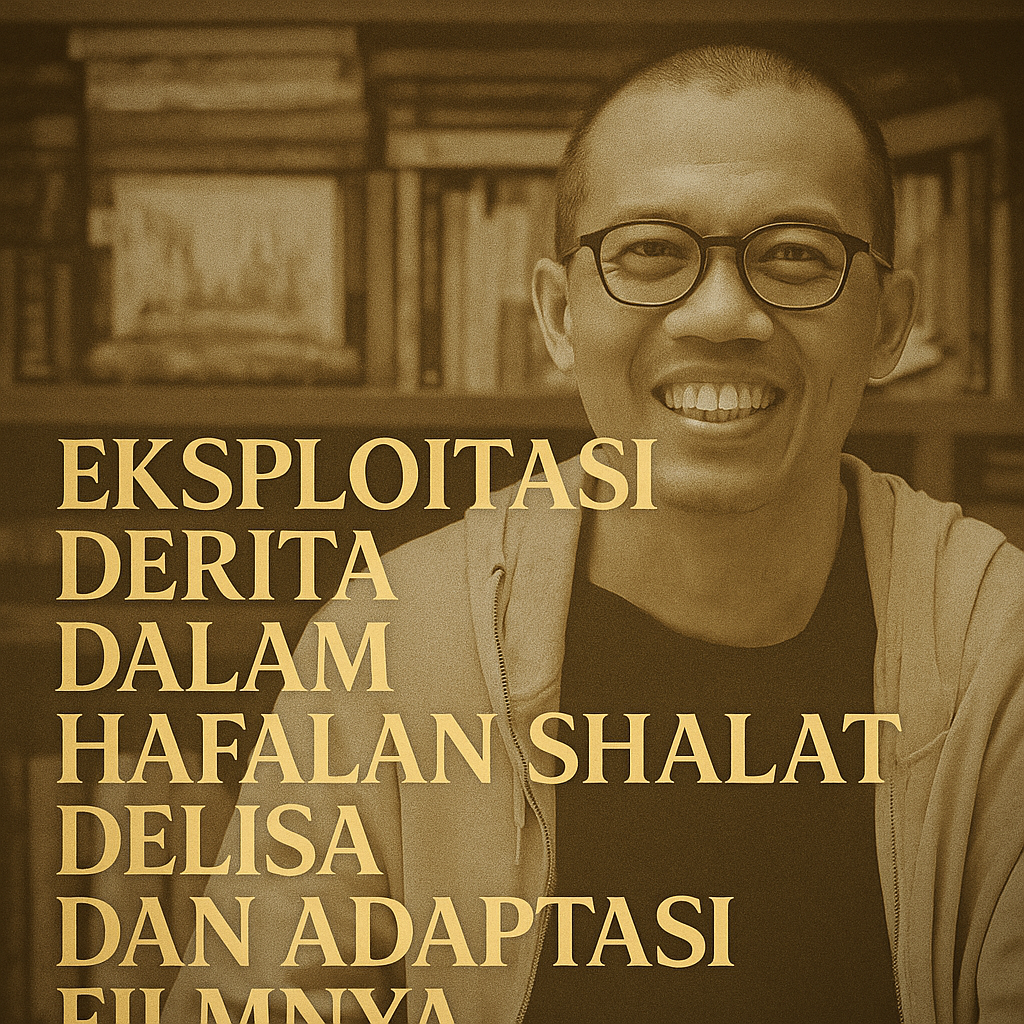
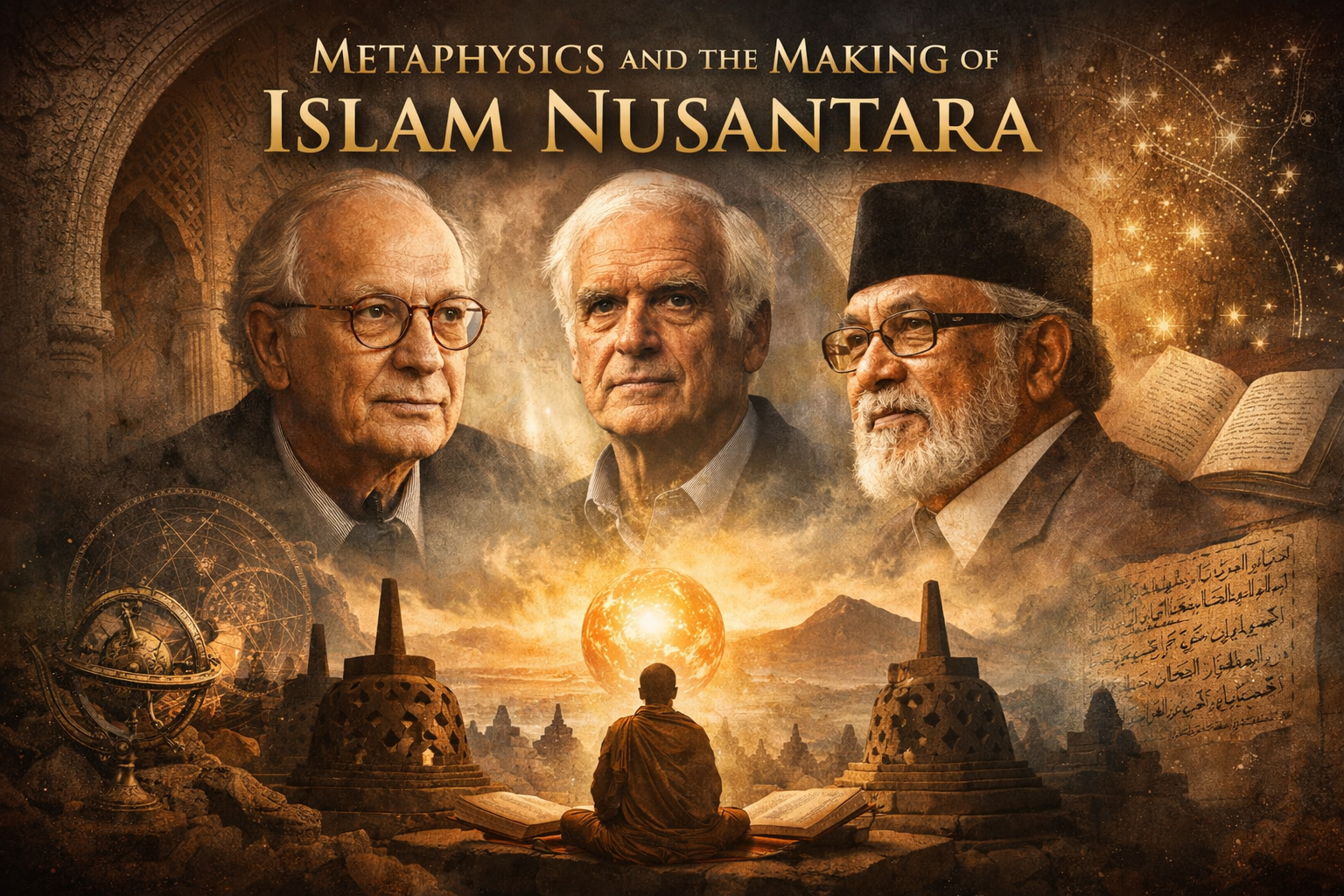
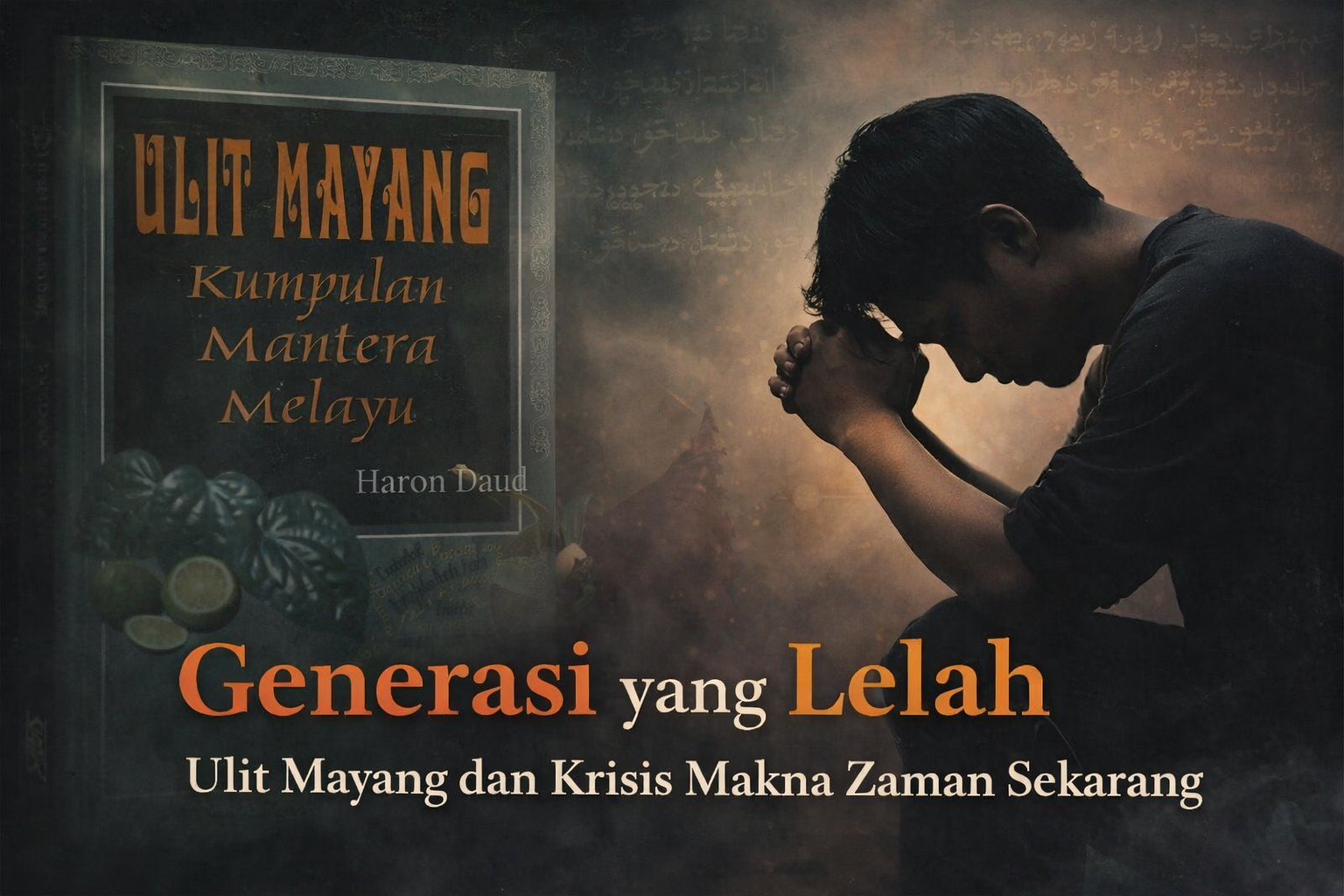



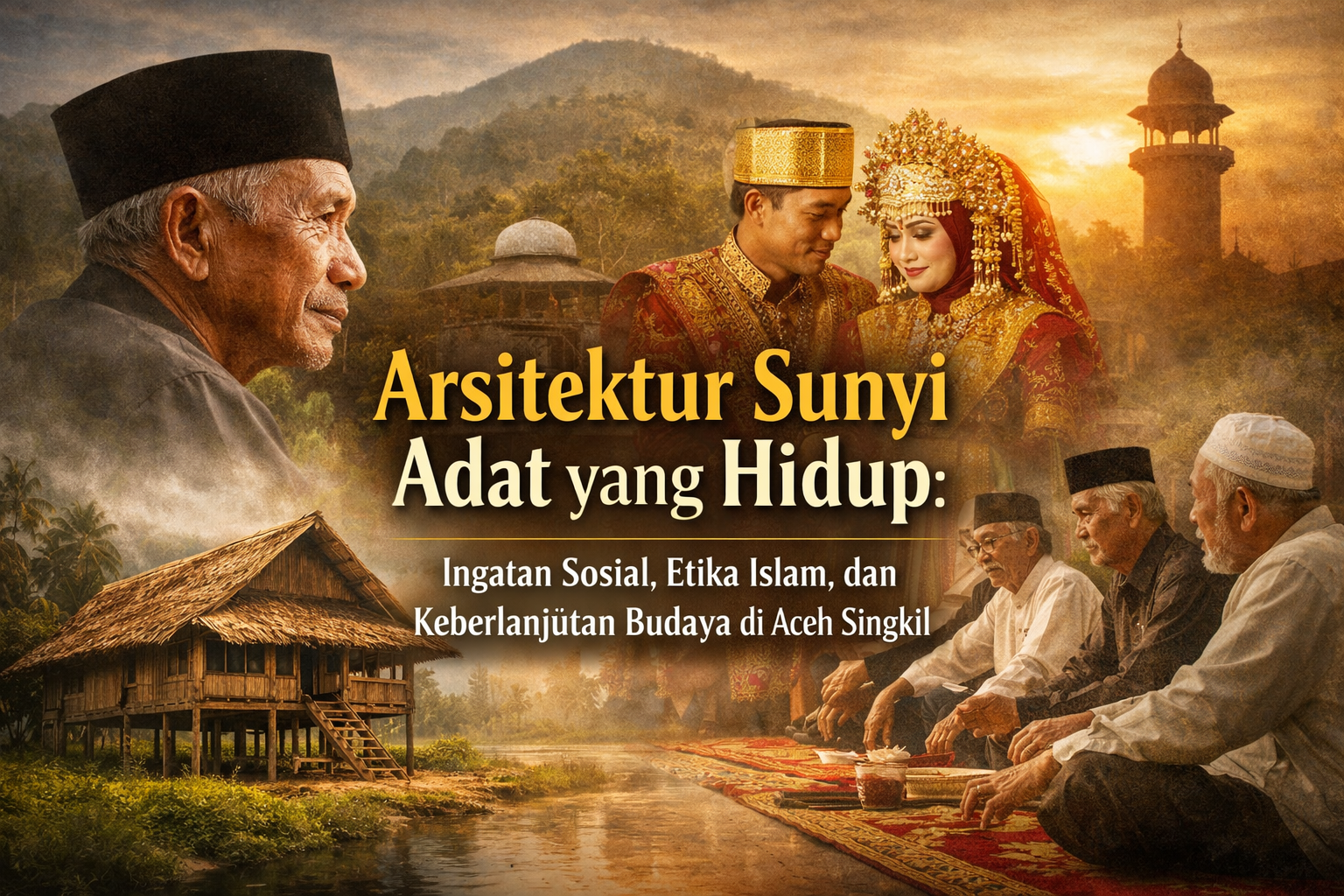
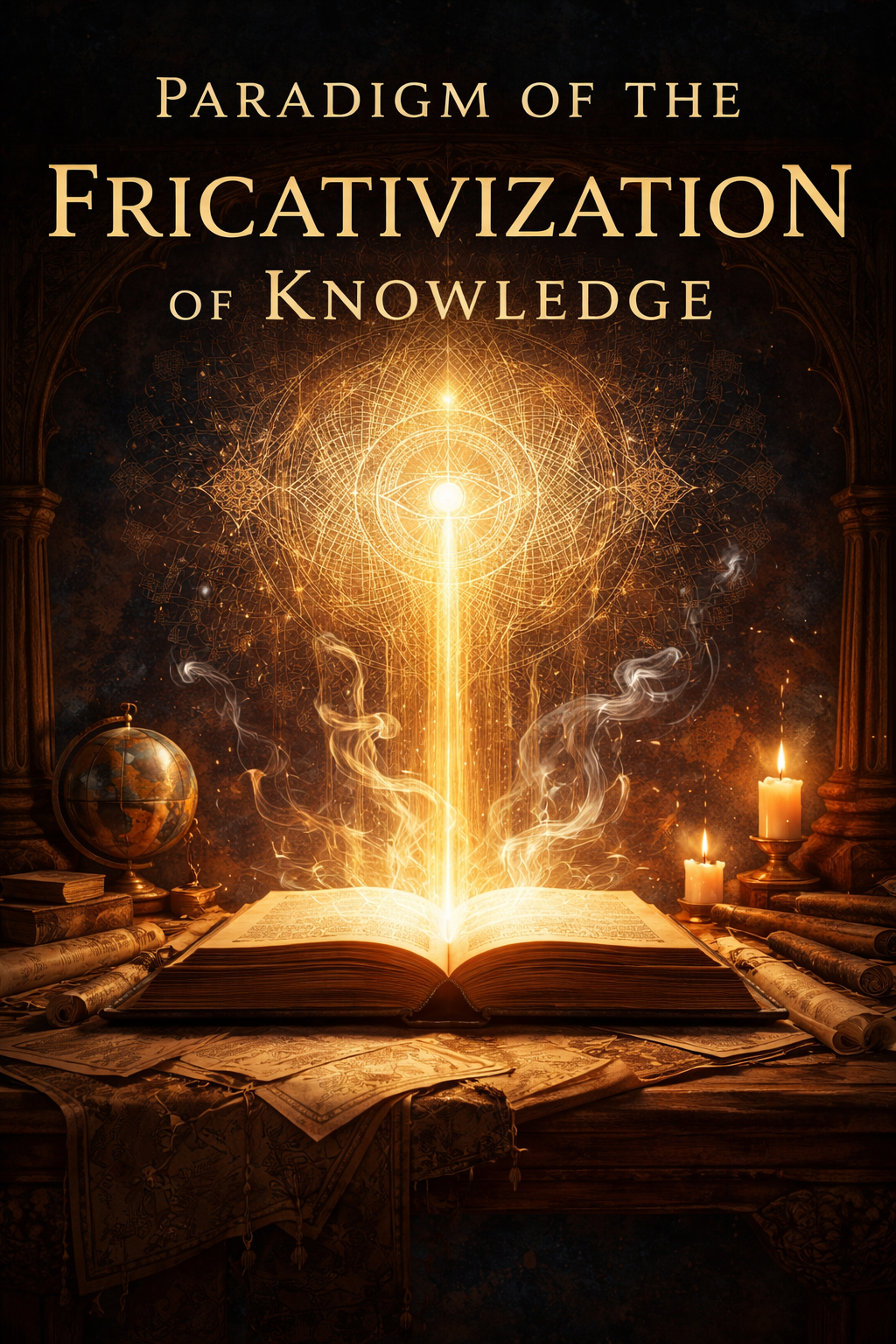
Leave a Reply