Pendahuluan
Di barat Sumatera, terhampar sebuah kota kecil yang namanya pernah bergaung jauh sebelum konsep “Indonesia” terbentuk. Kota itu bernama Barus. Dalam benak banyak orang, Barus mungkin hanya dikenal lewat kapur barus—sejenis rempah yang dahulu digunakan untuk pengawetan jenazah. Namun dalam perspektif antropologi
agama, Barus adalah lebih dari sekadar kota rempah. Ia adalah simpul sejarah spiritualitas dunia, titik temu peradaban lintas agama, serta cermin dari relasi antara tubuh, penyakit, dan kekuatan iman.
Buku Gerbang Agama-Agama Nusantara karya Rusmin Tumanggor adalah sebuah upaya monumental untuk menempatkan Barus kembali ke panggung intelektual sebagai ruang antropologis tempat berbagai sistem kepercayaan bertemu, berbaur, dan membentuk realitas sosial yang unik. Buku ini tidak hanya membicarakan agama, tetapi juga menempatkan tubuh, pengobatan, dan keseharian sebagai pintu masuk menuju pemahaman atas dinamika keagamaan dan kebudayaan yang lebih luas.
Barus: Titik Simpul Kosmopolitanisme Keagamaan
Barus adalah pintu. Dan pintu itu tidak pernah tertutup bagi orang luar. Letaknya yang strategis di pantai barat Sumatera menjadikannya pelabuhan penting bagi para saudagar dari Cina, Arab, Persia,
India, hingga Timur Tengah. Mereka datang membawa barang dagangan, termasuk kapur barus, namun juga membawa sesuatu yang lebih halus dan memikat: keyakinan.
Dalam pengamatan Tumanggor, Barus menjadi tempat pertama di Nusantara di mana agama-agama besar dunia seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Islam, dan Nasrani menjajaki bumi
Asia Tenggara. Di pelabuhan Barus, agama-agama ini tidak hanya mendarat secara fisik, tetapi mulai meresap dalam cara hidup, cara sembuh, dan cara mati masyarakat lokal.
Barus bukan sekadar tempat “singgah” agama. Ia adalah tempat di mana iman menjadi laku, dan kepercayaan menjadi tubuh. Di sinilah pendekatan antropologi agama menjadi sangat relevan: kita tidak membahas agama dari teksnya saja, melainkan dari pengalaman tubuh umatnya, dari relasi sosialnya, dari ritual kesehariannya.
Tubuh, Penyakit, dan Iman: Perspektif Antropologi Kesehatan
Salah satu keunikan buku ini adalah fokusnya pada kesehatan dan sistem pengobatan tradisional, yang justru menjadi titik temu paling konkrit antara sistem kepercayaan dan tubuh manusia. Di Barus, pengobatan tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga spiritual. Penyakit tidak hanya diobati, tetapi juga “disembuhkan” melalui intervensi kosmologis—baik lewat doa, mantra, maupun ritual adat.
Buku ini memperkenalkan sosok “Datu” sebagai penyembuh tradisional yang bukan sekadar herbalis, tetapi juga mediator spiritual. Datu bukan hanya tahu akar-akaran, tetapi juga membaca tanda-tanda alam, memaknai mimpi, dan menafsirkan penyakit sebagai ketidakseimbangan antara tubuh, alam, dan yang transenden.
Dalam pengobatan tradisional Barus, ramuan bukan sekadar hasil racikan ilmiah, tetapi representasi relasi antara manusia dan alam semesta. Banyak ramuan terdiri dari tumbuhan yang hanya bisa dipetik pada waktu-waktu tertentu, dengan syarat-syarat khusus yang diyakini memiliki pengaruh spiritual. Ada juga bagian tubuh hewan, batu, atau unsur-unsur alam lain yang dianggap sakral, membawa “energi” yang bisa memulihkan tubuh yang sakit—atau jiwa yang gundah.
Agama, Sistem Simbol, dan Kosmologi Lokal
Setiap agama membawa sistem simbolnya masing-masing. Namun yang menarik dalam kasus Barus, sebagaimana diuraikan dalam buku ini, simbol-simbol itu tidak hanya berdiri sendiri, melainkan mengalami akulturasi dan transformasi. Masyarakat Barus, dalam kepercayaan lokalnya, telah sejak lama mengenal konsep kosmologi yang mengaitkan penyakit dengan gangguan roh, pelanggaran adat, atau ketidakseimbangan dalam alam. Masuknya agama-agama besar dunia justru memperkaya kerangka tafsir ini, bukan menghapusnya.
Dalam bab kesembilan, buku ini mengulas bagaimana pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan kosmologi masyarakat Barus terintegrasi ke dalam sistem pengobatan mereka. Di sini agama menjadi lebih dari sekadar ajaran moral atau doktrin teologis. Ia menjadi kerangka eksistensial—cara memahami kehidupan, penderitaan, dan harapan akan kesembuhan.
Tradisional vs Modern: Persinggungan atau Ketegangan?
Di bagian akhir buku, Tumanggor mengangkat persoalan penting yang sering kali luput dalam diskursus akademik: bagaimana sistem pengobatan tradisional berhadapan dengan modernitas. Dalam banyak kasus, kedokteran modern sering kali memandang tradisi sebagai takhayul atau pseudo-science. Namun dalam pengalaman masyarakat Barus, keduanya justru hidup berdampingan.
Klinik kesehatan bisa berdiri bersebelahan dengan rumah “Datu”. Antibiotik bisa dikonsumsi berdampingan dengan ramuan akar-akaran. Di sinilah pentingnya pendekatan medical pluralism: masyarakat lokal tidak memilih antara modern atau tradisional, tetapi menggabungkan keduanya secara pragmatis dan spiritual.
Di balik itu semua, yang lebih dalam adalah bagaimana masyarakat memaknai kesehatan bukan hanya sebagai urusan tubuh, tetapi juga sebagai harmoni dengan lingkungan, leluhur, dan Yang Ilahi.
Barus dan Nusantara: Jejak Spiritual yang Terlupakan
Sebagai seorang antropolog agama, saya memandang buku ini sebagai sebuah karya yang sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa sejarah spiritualitas Indonesia tidak dimulai dari Jawa, bukan pula dari pusat-pusat kerajaan besar, tetapi dari pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Barus—yang membuka dirinya terhadap dunia, menyerap agama-agama besar, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa
tradisi lokal.
Kita sering lupa bahwa sebelum Indonesia modern memproklamirkan pluralismenya, Barus telah lebih dahulu menjadi laboratorium hidup bagi multikulturalisme keagamaan. Ia adalah contoh bagaimana perbedaan tidak menghasilkan konflik, tetapi membentuk mozaik kebudayaan yang kompleks, harmonis, dan otentik.
Penutup: Gerbang Masa Lalu untuk Masa Depan
Gerbang Agama-Agama Nusantara bukan hanya karya akademik. Ia adalah “ziarah intelektual” ke masa lalu, untuk memahami siapa kita hari ini. Buku ini mengajarkan bahwa agama bukan hanya warisan doktrin, tetapi juga warisan tubuh, emosi, dan cara kita menyembuhkan diri dari luka—baik fisik maupun eksistensial.
Barus telah memberi kita pelajaran penting: bahwa spiritualitas bukanlah bangunan tertutup, melainkan gerbang terbuka yang selalu bisa dilintasi, ditafsir ulang, dan dihidupi dalam konteks zaman. Di masa ketika keberagaman sering kali menjadi sumber pertikaian, buku ini justru menunjukkan bahwa dari sebuah pelabuhan kecil di pantai barat Sumatera, dunia pernah belajar untuk saling menyembuhkan.
📚 Informasi Buku:
•Judul: Gerbang Agama-Agama Nusantara: Hindu, Yahudi, Ru-Konghucu, Islam & Nasrani
•Penulis: Rusmin Tumanggor
•Penerbit: Komunitas Bambu
•Jumlah Halaman: ±400 hlm
•Fokus Kajian: Antropologi Agama, Sistem Kesehatan Tradisional,
Budaya Lokal Barus
About The Author
Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) has followed his curiosity throughout life, which has carried him into the fields of Sociology of Anthropology of Religion in Southeast Asia, Islamic Studies, Sufism, Cosmology, and Security, Geostrategy, Terrorism, and Geopolitics. Prof. KBA is the author of over 30 books and 50 academic and professional journal articles and book chapters. His academic training is in social anthropology at La Trobe University, Islamic Political Science at the University of Malaya, and Islamic Legal Studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He received many fellowships: Asian Public Intellectual (The Nippon Foundation), IVLP (American Government), Young Muslim Intellectual (Japan Foundation), and Islamic Studies from Within (Rockefeller Foundation). Currently, he is Dean of Faculty and Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

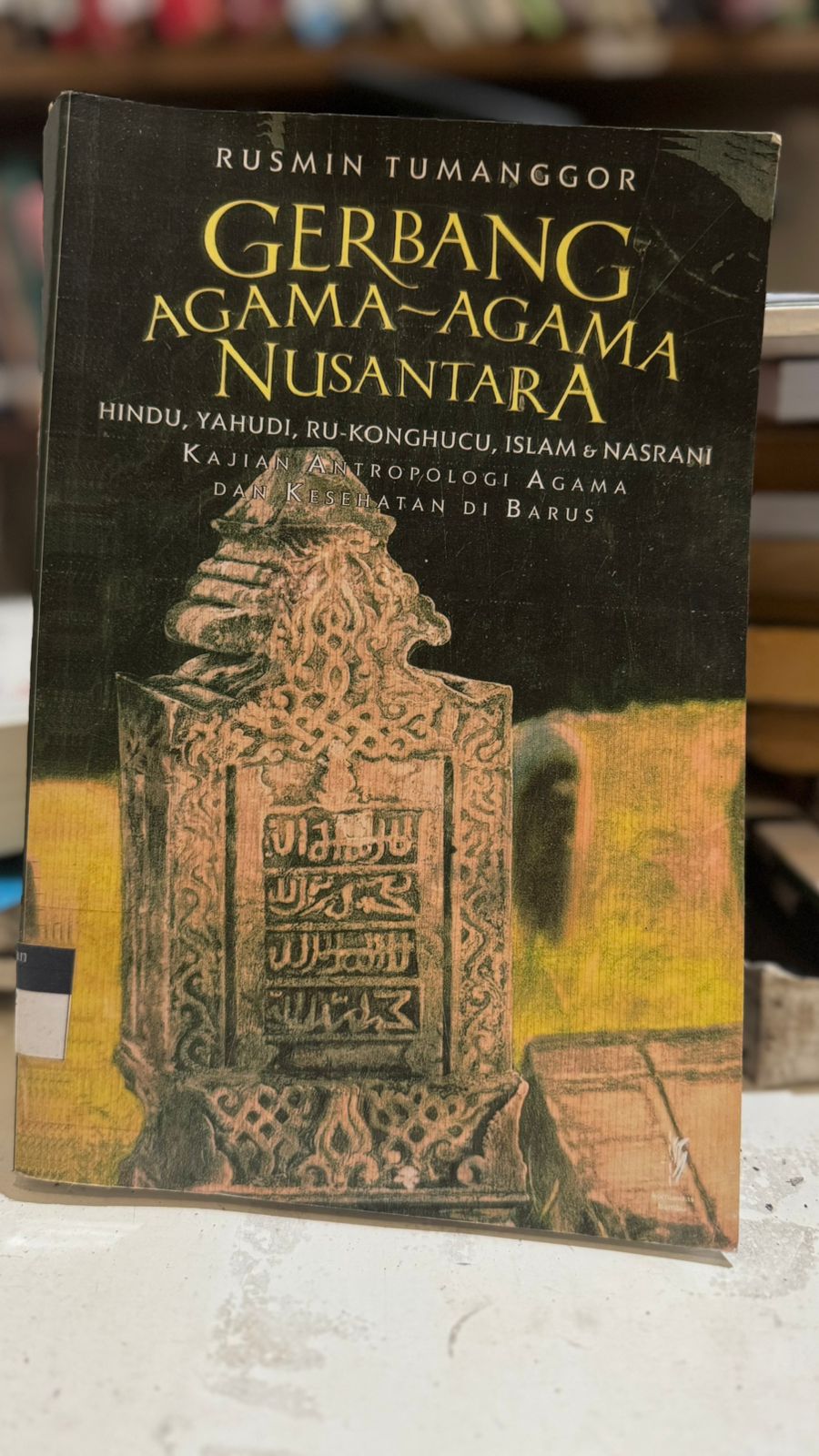
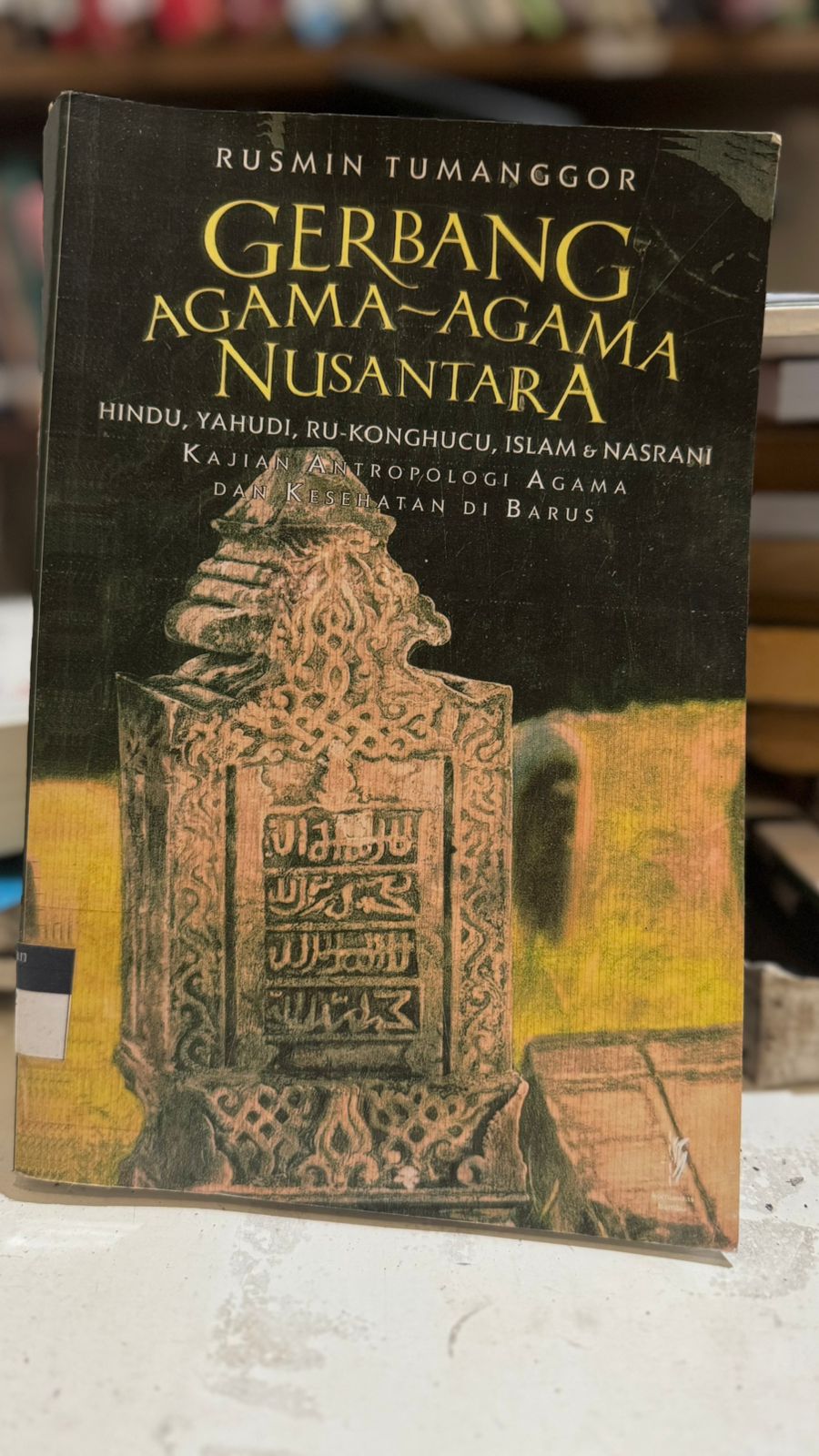
Leave a Reply