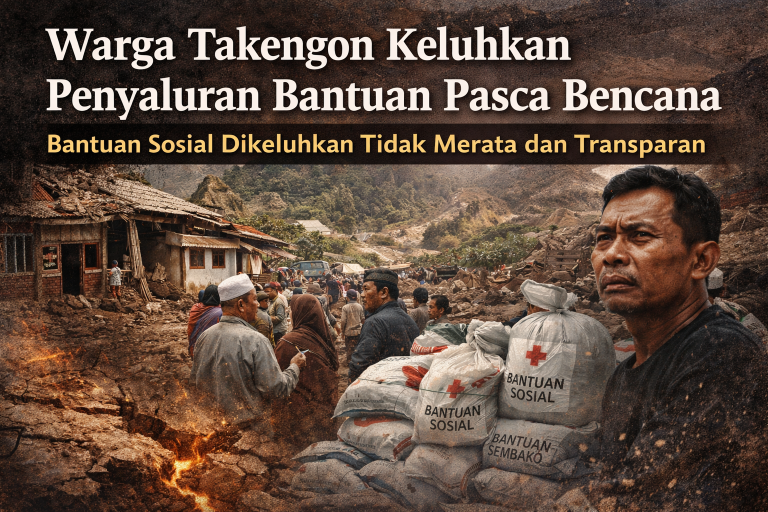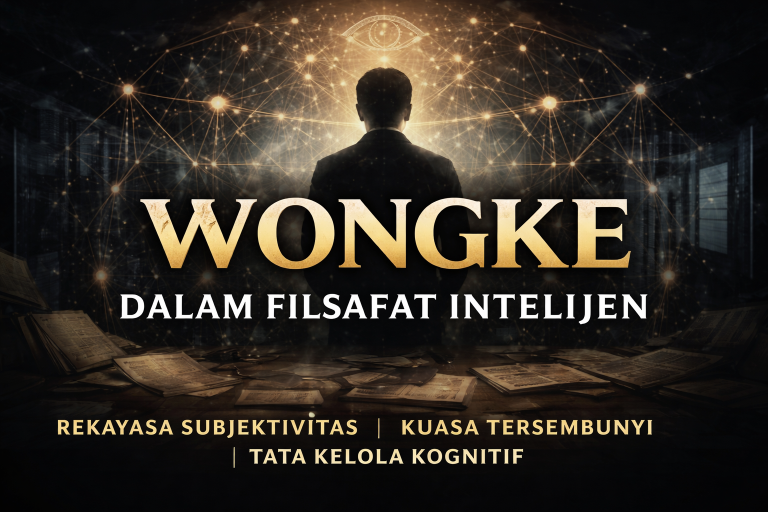Hubungan unik Singapura dan Indonesia, mulai dari peran pembantu rumah tangga asal Indonesia di Singapura, kebiasaan orang Singapura berbelanja di Batam, hingga manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dalam interaksi ekonomi lintas batas.
Pendahuluan
Singapura dan Indonesia punya relasi yang kerap mengalami “tarikan-balik” antara kedekatan struktural dan gesekan kepentingan. Di satu sisi, Singapura adalah simpul perdagangan dan keuangan regional; pelabuhannya termasuk paling sibuk di dunia dan menjadi gerbang kritikal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta Selat Malaka–Singapura. Di sisi lain, Jakarta kerap memandang Singapura melalui lensa interdependensi yang timpang: negara kecil, minim sumber daya alam, tetapi memiliki daya ungkit finansial, teknologi, dan jaringan global. Ketegangan laten ini merembes ke isu keamanan maritim, lingkungan, hingga preferensi kebijakan luar negeri masing-masing. UNCTAD menegaskan vitalitas jalur pelayaran global dan tekanan terbaru terhadap rantai logistik, sementara penilaian keamanan IISS menggambarkan Indo-Pasifik sebagai teater kompetisi yang kian tajam—konteks yang langsung memengaruhi kalkulasi dua negara di Selat Malaka dan Singapura.
Di atas panggung maritim itu, angka-angka berbicara. Laporan tahunan ReCAAP mencatat dinamika perompakan/aksi perampokan bersenjata di Asia, termasuk lonjakan insiden di beberapa perairan sekitar Singapura–Malaka pada 2024 dibanding 2023; IMO juga merekam tren gangguan keamanan pelayaran yang menuntut koordinasi erat antar-litoral. Artinya, kerja sama penegakan hukum laut bukan pilihan normatif, melainkan kebutuhan operasional untuk menjaga arteri perdagangan global.
Namun inti relasi Singapura–Indonesia bukan semata persoalan kapal dan kargo. Ini tentang politik negara kecil yang mengelola kerentanan struktural, berhadapan dengan negara kepulauan besar yang memegang kartu sumber daya, ruang udara/laut, dan pasar domestik. Doktrin “small-state realism” Singapura—kombinasi pragmatisme, jaringan aliansi longgar, dan manajemen risiko—ditantang realitas baru: rivalitas AS–Tiongkok, guncangan rantai pasok, regulasi hijau global (EUDR), serta keamanan non-tradisional seperti asap lintas batas. Survei The State of Southeast Asia 2024 dari ISEAS memperlihatkan kegamangan kawasan di tengah rivalitas besar, dengan preferensi yang dinamis ketika membayangkan “paksa-pilih” antara Tiongkok dan AS; suasana batin regional ini ikut mewarnai kalkulasi Singapura dan Indonesia.
Dalam kerangka inilah perlu dibaca “momen babak baru” di 2022–2024 ketika kedua negara menuntaskan Expanded Framework: Defence Cooperation Agreement (DCA), Extradition Treaty (ET), dan realignment Flight Information Region (FIR). Setelah proses panjang (termasuk kegagalan paket 2007), ketiganya diratifikasi 2022–awal 2023 dan mulai berlaku pada 2024, mengirim sinyal kedewasaan institusional kedua pihak. Pernyataan resmi MFA Singapura menekankan makna pengesahan itu, sedangkan laporan AP menegaskan tiga perjanjian tersebut “mulai berlaku” jelang peralihan kepemimpinan (Lee Hsien Loong–Lawrence Wong; Joko Widodo–Prabowo Subianto).
Relasi juga ditopang arus investasi dua arah. Data Kementerian Investasi/BKPM yang dilaporkan Reuters menunjukkan Singapura konsisten sebagai sumber FDI terbesar ke Indonesia pada 2024, selaras dengan tren beberapa tahun terakhir—menguat terutama di hilirisasi mineral dan manufaktur terkait. Bagi Singapura, ini bukan sekadar ekspansi modal, melainkan mekanisme “de-risking” supply chain dan akses ke ekonomi terbesar di ASEAN.
Di saat bersamaan, kerentanan pangan Singapura adalah faktor pendorong sikap akomodatif yang sering disalahpahami sebagai “cozy policy” terhadap Jakarta. Fakta kuncinya: lebih dari 90% pangan Singapura diimpor, dari >170–180 negara/wilayah; SFA menjadikan diversifikasi sumber sebagai pilar ketahanan, dengan target “30 by 30” untuk memenuhi 30% kebutuhan nutrisi dari produksi lokal pada 2030. Dengan kata lain, ketergantungan Singapura bukan monolit kepada Indonesia, tetapi berjejaring—walau Indonesia/Malaysia tetap menjadi pemasok penting untuk sejumlah komoditas dan bahan baku. Mengabaikan sifat “port hub + jaringan global” ini membuat analisis mudah terjebak pada simplifikasi.
Dimensi lingkungan menambah lapisan kompleksitas. Ekspansi sawit, kebijakan biofuel, dan praktik pembukaan lahan berkontribusi pada asap lintas batas yang berulang, dengan konsekuensi kesehatan, diplomatik, dan ekonomi bagi Singapura serta tetangga lain. Lowy Institute menyoroti dinamika kepatuhan regional terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, sementara analisis kebijakan terbaru menilai risiko asap 2025 pada level sedang—mengaitkan struktur insentif agraria dengan potensi deforestasi. Diskursus akademik dan think tank mendorong pendekatan tata-kelola rantai pasok yang lebih cerdas dibanding sekadar hambatan dagang, sembari mencatat kontroversi EUDR yang memaksa penyesuaian pasar.
Pada ranah keamanan maritim dan hukum laut, posisi Indonesia di Natuna—meskipun bukan “negara pengklaim” SCS—tetap terdampak aktivitas Tiongkok; AMTI-CSIS menempatkan kapasitas tata-kelola maritim Indonesia sebagai prioritas kebijakan. CFR, IISS, dan laporan lain memperingatkan eskalasi risiko salah perhitungan di Laut Tiongkok Selatan yang bisa mengguncang jalur pelayaran dan stabilitas kawasan. Di sini, kolaborasi teknis Singapura–Indonesia—mulai dari deconfliction area latihan laut hingga interoperabilitas keselamatan penerbangan (FIR)—bukan sekadar simbol, tetapi instrumen penyangga agar arsitektur kawasan tetap berfungsi.
Surut-naik politik domestik juga berpengaruh. Transisi kepemimpinan di kedua negara sepanjang 2024–2025 menunjukkan kesinambungan garis besar kebijakan: pragmatis, non-alignment, dan berorientasi hasil. ASPI menegaskan kecenderungan “non-aligned but networked” Indonesia, sementara AP melaporkan prioritas ekonomi-keamanan dalam ritme Leaders’ Retreat terakhir era Jokowi–LHL. Bagi Singapura, perubahan ini menuntut diplomasi yang peka terhadap dinamika elite pemerintahan baru di Jakarta tanpa kehilangan konsistensi pada norma dan kepentingan inti.
Akhirnya, perbedaan soft power dan tata-kelola sosial—dari rezim regulasi ujaran di Singapura hingga pluralitas demokratis Indonesia—menciptakan lanskap narasi publik yang berbeda. Survei persepsi kawasan ISEAS memperlihatkan bahwa isu-isu kesejahteraan, perubahan iklim, dan ketegangan ekonomi antarkekuatan besar kini lebih “mendesak” di mata publik dibanding ideologisasi lama. Ini menjelaskan mengapa retorika “memimpin kawasan” jarang efektif tanpa koalisi isu yang konkret—energi bersih, digital, rantai pasok, dan ketahanan pangan—yang justru menjadi ruang kompromi Singapura–Indonesia beberapa tahun terakhir.
Ringkasnya: hubungan Singapura–Indonesia bukan kisah “ketergantungan sempit” atau “akomodasi tanpa kalkulasi”. Ini manajemen interdependensi di tengah turbulensi geopolitik dan transisi hijau. Paket perjanjian 2022–2024 memberi jangkar institusional; rantai investasi memberi insentif; risiko maritim dan lingkungan memaksa koordinasi operasional. Di kawasan tempat ekonomi adalah keamanan, strategi kedua negara akan dinilai dari kemampuannya menjaga aliran barang, modal, dan data sembari menekan eksternalitas seperti asap dan gangguan pelayaran.
Kerangka Analitik: Bagaimana Menilai “Cozy Policy” Secara Jujur
Untuk menghindari bias, analisis kebijakan “cozy” Singapura terhadap Jakarta sebaiknya diuji melalui tiga lensa:
-
Interdependensi material: data FDI, perdagangan, latihan militer, dan proyek energi bersih. FDI Singapura menjadi pilar penting bagi proyek hilirisasi Indonesia, sedangkan perdagangan jasa dan logistik Singapura menyerap limpahan aktivitas dagang kawasan. DOS/MTI menampilkan besaran perdagangan barang/jasa terkini, termasuk perubahan NODX menurut pasar—memberi gambaran sensitivitas siklus industri terhadap permintaan Indonesia.
-
Arsitektur institusional: bagaimana DCA–ET–FIR mengurangi friksi rutin sekaligus membangun kebiasaan kerja aparat dua negara. Deretan rilis resmi MFA, analisis RSIS, dan komentar kebijakan ISEAS menjelaskan kronologi dan signifikansinya, termasuk pelajaran dari paket 2007 yang gagal.
-
Keamanan non-tradisional & norma: koherensi kebijakan terhadap asap, deforestasi, dan regulasi rantai pasok global. Lowy, LSE, dan think tank regional menekankan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh retorika, tetapi oleh tata-kelola lahan, penegakan hukum, serta diplomasi standar keberlanjutan yang tidak memukul petani kecil.
Melalui lensa ini, “cozy” dapat dipahami bukan sebagai kompromi nilai, melainkan prioritisasi stabilitas dan hasil kebijakan di area yang paling memengaruhi kesejahteraan publik masing-masing negara—sembari mempertahankan ruang manuver pada isu sensitif di forum regional maupun global.
Dari Konfrontasi ke Interdependensi
Hubungan Singapura dan Indonesia tidak pernah sederhana. Sejak Singapura merdeka pada 1965, kedua negara ini terikat dalam sebuah jalinan relasi yang rumit: dekat karena faktor geografi, tetapi sering renggang karena beban sejarah dan sensitivitas politik. Bagi Singapura, Indonesia adalah tetangga besar yang bisa menjadi sumber ancaman maupun sumber daya. Bagi Indonesia, Singapura adalah negara kecil yang sering dianggap “hanya titik di peta”, namun justru punya pengaruh finansial, logistik, dan diplomasi yang melebihi ukurannya.
Narasi hubungan itu bermula dari Konfrontasi 1963–1966, ketika Sukarno menentang keras pembentukan Federasi Malaysia yang kala itu mencakup Singapura. Catatan ISEAS–Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa periode tersebut ditandai oleh lebih dari tiga puluh insiden militer lintas batas, mulai dari penyusupan pasukan, sabotase, hingga serangan bom di jantung kota Singapura. Peristiwa paling traumatis adalah peledakan MacDonald House pada 10 Maret 1965, yang menewaskan dua warga sipil. Dua marinir Indonesia ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum mati di Singapura. Keputusan ini menimbulkan gelombang besar protes di Jakarta, bahkan berujung pada kerusuhan di Kedutaan Singapura. Hingga hari ini, patung kedua marinir itu berdiri di Jakarta sebagai simbol nasionalisme—sebuah penanda bahwa memori konfrontasi tidak pernah benar-benar hilang.
Penelitian Leonard Sebastian dari RSIS menegaskan bahwa warisan konfrontasi itu membentuk “psikologi strategis” kedua negara. Singapura tumbuh dengan perasaan rentan di hadapan tetangga besar yang pernah mengancam eksistensinya. Indonesia, sebaliknya, membawa narasi kedaulatan dan kebanggaan nasional, bahwa bahkan negara kecil seperti Singapura pun harus memahami posisi dominan Indonesia di kawasan. Dengan demikian, sejak awal, hubungan ini bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan sebuah relasi yang dibayangi trauma historis dan perbedaan persepsi tentang siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti.
Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1966, arah hubungan berubah. Orde Baru hadir dengan doktrin stabilitas untuk pembangunan, dan Soeharto memahami bahwa ekonomi tidak bisa tumbuh dalam kondisi konfrontasi. Lee Kuan Yew, yang baru memimpin Singapura merdeka, segera menangkap peluang ini. Hubungan pun dinormalisasi. Singapura membutuhkan pasar, bahan mentah, dan tenaga kerja dari Indonesia. Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan akses global yang dimiliki Singapura. Dalam bahasa akademik, ini adalah fase awal interdependensi asimetris.
Namun interdependensi itu tidak selalu mulus. Studi CSIS Jakarta pada awal 2000-an mengingatkan bahwa sejak 1970-an, elite Indonesia sering menganggap Singapura terlalu banyak mendapat keuntungan. Investasi asing yang masuk melalui Singapura, jasa perbankan yang menampung dana regional, hingga keuntungan dari logistik dan pelayaran, semua itu membuat Jakarta curiga bahwa Singapura menjadi “free rider” dari sumber daya Indonesia. Singapura, di sisi lain, justru melihat hubungan itu sebagai win–win: Indonesia mendapat pembangunan, Singapura mendapat stabilitas. Inilah awal dari paradoks yang hingga kini masih menjadi pola dasar hubungan bilateral.
Pada 1989, eksperimen besar dilakukan dengan meluncurkan SIJORI Growth Triangle (Singapore–Johor–Riau). Konsepnya sederhana: Singapura menyediakan modal dan manajemen, Johor dan Kepulauan Riau menyediakan tenaga kerja murah dan lahan industri. Batam, Bintan, dan Karimun pun disulap menjadi kawasan industri baru, dengan manufaktur elektronik, galangan kapal, dan pariwisata. Bagi Singapura, ini adalah cara cerdas mengatasi keterbatasan lahan dan biaya produksi tinggi. Bagi Indonesia, ini kesempatan membuka lapangan kerja dan menarik investasi.
Namun studi ISEAS yang meneliti Batam sepanjang 1990-an menemukan sisi lain. Industrialiasi cepat di Kepulauan Riau memicu urbanisasi liar, munculnya kantong-kantong kemiskinan baru, serta kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri. Terence Chong menulis bahwa SIJORI pada akhirnya menciptakan “dua realitas”: Singapura yang semakin kaya sebagai pusat jasa, dan Riau yang tertinggal dengan masalah sosial baru. Lowy Institute kemudian menilai bahwa SIJORI adalah prototipe interdependensi asimetris: efisien secara ekonomi, tetapi politis rentan karena menempatkan Indonesia sebagai hinterland bagi Singapura.
Krisis finansial Asia 1997–98 semakin memperumit keadaan. Ketika rupiah runtuh dan ekonomi Indonesia ambruk, banyak elite di Jakarta menuduh Singapura menjadi tempat pelarian modal. Laporan CSIS Washington pada 2000 memperkirakan lebih dari 80 miliar dolar AS keluar dari Indonesia, sebagian besar parkir di Singapura. Di tengah kerusuhan Mei 1998, sentimen anti-Singapura menguat. Media Jakarta menggambarkan Singapura sebagai negara kecil yang menikmati keuntungan di atas penderitaan Indonesia. RSIS mencatat bahwa sejak itu muncul trust deficit yang lama membekas: Indonesia curiga, Singapura defensif.
Meski demikian, hubungan tetap berjalan. Pada 2007, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong, kedua negara mencoba memperbaiki hubungan dengan menandatangani paket tiga perjanjian: Defence Cooperation Agreement (DCA), Extradition Treaty (ET), dan pengaturan ulang Flight Information Region (FIR). Di atas kertas, ini tampak seperti langkah maju: DCA memberi dasar latihan militer SAF di wilayah Indonesia, ET menjanjikan ekstradisi koruptor, dan FIR memberi Indonesia peran lebih besar dalam pengendalian udara di Kepulauan Riau.
Namun, ratifikasi gagal. DPR RI menolak dengan alasan kedaulatan. DCA dianggap memberi keleluasaan berlebihan kepada militer Singapura, ET dipandang tidak seimbang, dan isu FIR menyentuh harga diri nasional. Rizal Sukma dari CSIS Jakarta menulis bahwa kegagalan ini adalah contoh klasik asimetris kepercayaan: Singapura merasa sudah memberi konsesi, tetapi Indonesia merasa belum cukup. Dari perspektif Singapura, kegagalan itu adalah pukulan besar. Dari perspektif Indonesia, ia adalah penegasan kedaulatan. Sejak itu, paket 2007 menjadi luka diplomasi yang membekas selama lebih dari satu dekade.
Kebangkitan baru terjadi pada era Joko Widodo. Melalui mekanisme Leaders’ Retreat, kedua negara mulai merajut kembali benang kusut itu. Pada Januari 2022, paket revisi dari DCA, ET, dan FIR ditandatangani. Berbeda dengan 2007, kali ini pendekatan lebih hati-hati: perjanjian dirancang agar sensitif pada kekhawatiran Indonesia, tetapi juga memberi kepastian hukum bagi Singapura. DPR RI akhirnya meratifikasi pada Januari 2023, dan setahun kemudian, pada Januari 2024, paket itu resmi berlaku. MFA Singapura menyebutnya “milestone bersejarah”. Daljit Singh dari ISEAS menyebut momen itu sebagai tanda kedewasaan diplomasi kedua negara: mampu keluar dari trauma lama, dan berani membangun institusi bersama.
Secara historis, paket 2022–2024 adalah koreksi diplomasi. Bagi Singapura, ia menutup kegagalan 2007. Bagi Indonesia, ia membuktikan bahwa sensitifitas kedaulatan bisa dipertahankan sembari tetap membuka ruang kerja sama. Lowy Institute dalam ulasannya tahun 2024 menyebut capaian ini sebagai transisi dari hubungan personal ke hubungan institusional. Artinya, hubungan Singapura–Indonesia tidak lagi bergantung pada kedekatan individu Lee Kuan Yew dengan Soeharto, atau Jokowi dengan Lee Hsien Loong, melainkan pada mekanisme formal yang bisa bertahan lintas generasi politik.
Sejarah hubungan Singapura–Indonesia dengan demikian tampak seperti siklus: fase konfrontasi yang traumatis, fase normalisasi pragmatis, eksperimen interdependensi lewat SIJORI, krisis dan trust deficit 1998, kegagalan 2007, lalu kebangkitan 2022–2024. Siklus itu memperlihatkan bahwa hubungan ini selalu diuji, tetapi tidak pernah runtuh. Ia rapuh, tetapi resilien; penuh curiga, tetapi terus mencari jalan keluar. Dari perspektif antropologi politik, hubungan ini adalah bentuk negosiasi berulang tentang asimetri: Singapura mengelola kerentanannya sebagai negara kecil, sementara Indonesia mengelola kebanggaannya sebagai negara besar.
Ekonomi Politik Interdependensi—Singapura dan Indonesia dalam Tarikan Ekonomi Global
Ketika kita menengok peta ekonomi Asia Tenggara, salah satu hubungan yang paling rumit dan penuh nuansa adalah hubungan Singapura–Indonesia. Ini bukan sekadar hubungan negara tetangga, tetapi persinggungan antara negara kecil dengan keterbatasan sumber daya dan negara besar dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi. Pasokan modal, pangan, energi, dan bahan mentah menjadi perantara rumit yang mengikat mereka dalam interdependensi—asal jangan saling menekan hingga retak.
Ketergantungan Modal Singapura terhadap Ekonomi Indonesia
Sejak era Joko Widodo mengusung program hilirisasi dan operasionalisasi KEK, Singapura bereaksi dengan menjadi salah satu alat utama dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia. Data BKPM menunjukkan bahwa pada 2024, Singapura menjadi investor asing terbesar ke Indonesia, dengan proporsi sekitar 30% dari FDI tahunan. Investasi mengalir ke wilayah-wilayah industri seperti Batam, Bintan, Kendal, dan ke sektor-sektor strategis seperti energi, logistik, dan fintech. Untuk Singapura, ini adalah mekanisme vital untuk menyuplai peluang bisnis dan diversifikasi. Bagi Indonesia, modal bukan hanya uang—itu adalah jembatan untuk akselerasi pertumbuhan, meski ada sensitivitas mendalam terhadap peran Singapura sebagai pintu masuk modal global.
Ketegangan Ketahanan Pangan
Dalam dimensi pangan, Singapura digambarkan sebagai negara yang sangat rentan. Dengan hampir 90–90% kebutuhan pangan diimpor, negara ini dengan terbuka mengakui krisis potensial bila pasokan terganggu. Pemerintah kemudian merancang program “30 by 30”—upaya mencapai ketahanan 30% dari produksi lokal pada 2030 melalui pertanian urban dan agritech. Namun kenyataan tetap bahwa produk pangan Indonesia menyuplai sebagian besar kebutuhan impor Singapura: dari ayam, sayuran, hingga beras—terutama saat Malaysia menutup ekspor ayam pada 2022, Singapura langsung bergantung ke Indonesia. The Straits Times melaporkan betapa krisis itu menjadi peringatan nyata: hubungan ekonomi ini mudah tergoncang oleh kebijakan domestik tetangga.
Energi Hijau sebagai Jalan Tengah
Ketika dunia mendesak transisi energi bersih, Singapura menemukan mitra di Indonesia. Pada akhir 2024, media internasional dan Straits Times melaporkan bahwa Singapura akan mulai mengimpor listrik rendah karbon dari proyek-proyek surya dan gas terbarukan di Kepulauan Riau dan Batam. Ini bukan hanya strategi diversifikasi energi global, tapi juga diplomasi hijau: Sinergi yang menjembatani kebutuhan energi masa depan Singapura dengan sumber daya alam Indonesia. Namun, lembaga seperti Lowy Institute menganggap bahwa sementara praktik ini menjanjikan, tetap ada risiko bahwa Indonesia dapat memanfaatkan energi terbarukan sebagai alat negosiasi politik yang halus.
Kelamnya Jejak Minyak Sawit dan Regulasi Global
Komoditas minyak sawit adalah sumber gurih bagi Indonesia—70% ekspor global berasal dari sana. Tetapi dampaknya juga serius: deforestasi, pelanggaran hak atas tanah, dan kabut asap lintas batas yang sering menggerus reputasi kawasan. Singapura—sebagai pusat logistik dan finansial—ketiban juga reputasi negatif itu. Eco-Business dan Amnesty sudah menyoroti bahwa rantai pasok sawit mengandung risiko tinggi pelanggaran HAM. Ketika Uni Eropa mengimplementasikan EU Deforestation Regulation (EUDR), Indonesia merasa terdesak. Singapura, di sisi lain, terjepit antara kebutuhan ekonominya dan desakan standar ESG global. Ini bukan hanya soal pasar, tetapi soal norma global yang makin mengatur ekonomi lokal.
Akar Ekonomi Lingkungan: Kabut Asap dan Keamanan Non-Tradisional
Namanya juga ASEAN—non-interference sering menjadi penghalang penanganan asap silang. Straits Times (2013) mendokumentasikan bagaimana kabut asap menyebabkan ratusan PSI dan menekan ekonomi Singapura yang rapat perkembangannya. Lowy Institute menyebut bahwa ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, meski sudah disepakati 2002, sejak awal tidak efektif karena terlalu mengandalkan kerelaan negara anggota. Singapura kemudian menerjemahkan setiap musim kemarau sebagai “test case” atas kemampuan tata kelola Indonesia—dan apa yang berdampak secara lingkungan, juga terasa secara ekonomi.
Finansial dan Kapital yang Merentang
Masuk akal saja kalau ekonomi Indonesia dan Singapura bersinggungan di sektor jasa dan keuangan. Singapura adalah pusat perbankan regional, tempat di mana banyak perusahaan Indonesia melakukan listing. Namun trauma ekonomi melihat Singapura sebagai “bank pelarian” tak mudah hilang. Krisis finansial 1997–98 menjadi simbol: sekitar USD 80 miliar mengalir keluar dan berlabuh di Singapura. Meskipun memberi perlindungan likuiditas, ia juga menciptakan narasi negatif tentang Singapura yang tetap kaya saat Indonesia luka. Insight Brookings dan CSIS menyebut ini sebagai konflik identitas: Singapura adalah penyelamat ekonomi, namun juga sumber iri dan curiga.
Semua lapisan ini—modal, pangan, energi, lingkungan, keuangan—adalah wajah-fisik interdependensi Singapura–Indonesia. Namun, interdependensi ini asal telur rapuh: saat keadaan baik, ia terpatri sebagai stabilitas. Saat krisis, dia berubah jadi senjata negosiasi. ISEAS pernah menyebut hubungan ini sebagai “constant negotiation of asymmetry”. Singapura terus mencari jalan mengelola kerentanannya sebagai negara kecil; Indonesia mencari cara mempertahankan kedaulatan dan memanfaatkan kelebihannya sebagai negara besar.
Contoh yang nyata: Ketika Singapura kekurangan ayam impor dari Malaysia, Indonesia ambil peran—tapi dengan harga tinggi. Ketika Singapura tawarkan energi hijau baru, Indonesia bisa gunakan itu untuk menegosiasi komitmen investasi baru. Ketika EUDR menekan rantai sawit, Indonesia memaksa Singapura berpikir ulang soal platform finansialnya. Semua jadi negosiasi dagang, tapi juga politik dan budaya.
Ekonomi Politik Interdependensi
Hubungan Singapura dan Indonesia, jika ditarik ke ranah ekonomi politik, memperlihatkan wajah interdependensi yang unik: satu negara kota dengan keterbatasan sumber daya tetapi berfungsi sebagai simpul finansial dan logistik global, berhadapan dengan negara kepulauan raksasa yang kaya sumber daya, pasar domestik, dan tenaga kerja, tetapi masih berjuang mengoptimalkan tata kelola ekonominya.
Modal dan Investasi: Singapura sebagai Investor Utama
Sejak 2014, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Data resmi Kementerian Investasi/BKPM (2024) mencatat bahwa Singapura menyumbang hampir 30% dari total FDI masuk ke Indonesia, setara lebih dari US$15 miliar per tahun pada periode 2020–2023. Sebagian besar investasi itu mengalir ke sektor manufaktur, energi, kawasan industri (Batam, Kendal, Bintan), serta keuangan digital.
Laporan Reuters (2024) menekankan bahwa dominasi Singapura bukan hanya karena kedekatan geografis, melainkan juga karena posisinya sebagai “gateway capital” bagi modal global yang masuk ke Indonesia melalui Singapura. Dengan sistem keuangan yang transparan dan infrastruktur hukum yang kuat, banyak investor memilih menyalurkan dana lewat Singapura, lalu diarahkan ke proyek-proyek Indonesia. Bagi Jakarta, hal ini penting untuk pembangunan; namun di sisi lain menimbulkan sensitivitas bahwa Singapura bukan sekadar mitra, melainkan perantara yang kadang dianggap terlalu diuntungkan.
Pangan: Ketergantungan dan Krisis Ayam 2022
Dalam bidang pangan, Singapura berada pada posisi rapuh. Singapore Food Agency (SFA) melaporkan bahwa lebih dari 90% kebutuhan pangan nasional diimpor dari lebih dari 170 negara. Program “30 by 30” diluncurkan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik hingga 30% pada tahun 2030 melalui teknologi agrikultur urban. Namun kenyataan tetap: Indonesia dan Malaysia adalah pemasok kunci.
Kerapuhan itu terbukti pada 2022, ketika Malaysia melarang ekspor ayam demi menjaga harga domestik. The Straits Times (Juni 2022) melaporkan bagaimana Singapura terpaksa beralih ke Indonesia untuk memasok kebutuhan ayam, bahkan harus mempercepat persetujuan impor darurat. Kebijakan domestik negara tetangga langsung mengguncang pasokan Singapura. Channel NewsAsia menulis bahwa insiden itu membuka mata publik Singapura terhadap betapa tergantungnya mereka pada stabilitas politik-ekonomi Indonesia dan Malaysia.
Energi Hijau: Babak Baru Interdependensi
Jika pangan adalah kerentanan lama, maka energi adalah kerentanan baru. Pada September 2024, Reuters melaporkan bahwa Singapura menandatangani perjanjian untuk mengimpor listrik rendah karbon dari Indonesia, terutama dari proyek energi surya dan gas hijau di Batam dan Kepulauan Riau. Proyek ini bernilai miliaran dolar dan menjadi bagian dari transisi energi Singapura menuju net zero emissions pada 2050.
Bagi Singapura, impor listrik dari Indonesia adalah strategi diversifikasi; bagi Indonesia, ini kesempatan mengkapitalisasi sumber daya terbarukan. Namun analisis Lowy Institute (2024) memperingatkan bahwa pola ini berpotensi mengulang ketergantungan lama: energi bersih bisa menjadi kartu tawar politik, seperti halnya minyak sawit dalam dua dekade terakhir.
Sawit, ESG, dan Kabut Asap
Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia, menyumbang lebih dari 55% produksi global. Sebagian besar minyak sawit ini melewati jalur logistik Singapura. Namun, ekspansi sawit sering dituding sebagai penyebab deforestasi dan kabut asap lintas batas.
Amnesty International (2016) mendokumentasikan pelanggaran HAM dalam rantai pasok sawit, dari kerja paksa hingga perampasan tanah. Eco-Business (2023) menulis bahwa kebijakan biofuel Indonesia dapat memperburuk deforestasi, meningkatkan risiko kabut asap. The Straits Times (2023) melaporkan bahwa rencana ekspansi pangan dan energi berbasis sawit di Indonesia dinilai “mengancam percepatan deforestasi terbesar dalam sejarah”.
Di sisi lain, Uni Eropa meluncurkan EU Deforestation Regulation (EUDR, 2023) yang mewajibkan semua ekspor bebas deforestasi. Indonesia menganggapnya diskriminatif, tetapi Singapura sebagai pusat perdagangan tidak bisa mengabaikan standar ESG global. Analisis Chatham House (2023) menyebut Singapura berada di posisi dilematis: harus menjaga hubungan dengan Indonesia tetapi juga menyesuaikan diri dengan norma global.
Kabut Asap: Keamanan Non-Tradisional
Kabut asap akibat kebakaran lahan 2013 dan 2015 menjadi salah satu krisis terbesar hubungan Singapura–Indonesia. The Straits Times (2015) mencatat indeks polusi udara (PSI) mencapai level berbahaya, memicu kerugian ekonomi miliaran dolar.
Meski ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002) sudah berlaku, analisis Lowy Institute (2016) menunjukkan implementasinya lemah karena prinsip non-interference ASEAN. RSIS (2020) menulis bahwa Singapura menggunakan instrumen hukum domestik—Transboundary Haze Pollution Act (2014)—untuk menuntut perusahaan yang berbasis di luar negeri. Langkah ini meningkatkan ketegangan diplomatik, tetapi juga menandai bagaimana isu lingkungan menjadi instrumen politik.
Keuangan dan Capital Flight
Hubungan finansial juga sarat sensitivitas. Singapura adalah pusat perbankan Asia Tenggara, tempat banyak perusahaan Indonesia mendaftar di bursa. Namun krisis finansial Asia 1997–98 memperlihatkan sisi gelapnya. CSIS Washington (2000) mencatat bahwa lebih dari US$80 miliar modal keluar dari Indonesia, sebagian besar mendarat di Singapura. Bagi Jakarta, ini menciptakan persepsi bahwa Singapura mendapat keuntungan dari kehancuran ekonomi Indonesia.
Pasca krisis, isu “capital flight” selalu menghantui narasi publik Indonesia. Setiap kali ada gejolak, kecurigaan muncul bahwa Singapura menjadi “bank darurat” bagi elite. Meski kenyataannya lebih kompleks, sentimen ini menjadi salah satu faktor psikologis yang membuat hubungan finansial bilateral tetap rapuh.
Interdependensi ekonomi Singapura–Indonesia ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin stabilitas: modal Singapura menopang pembangunan Indonesia, sementara pangan dan energi Indonesia menjaga kelangsungan hidup Singapura. Di sisi lain, ia menciptakan kerentanan: krisis pangan bisa terjadi karena kebijakan domestik tetangga; energi hijau bisa menjadi alat tekanan; sawit dan kabut asap bisa memicu krisis diplomatik; capital flight bisa membangkitkan sentimen negatif.
Riset ISEAS (2023) menyebut hubungan ini sebagai “constant negotiation of asymmetry”: Singapura mengelola kerentanannya, Indonesia mengelola kebesarannya. Keseimbangan itu hanya bisa bertahan jika ada kesadaran bahwa interdependensi bukan sekadar soal perdagangan, tetapi juga tentang manajemen risiko bersama—dari ketahanan pangan, energi hijau, hingga lingkungan hidup.
Narasi Interdependensi Ekonomi Singapura–Indonesia
Sejak era Orde Baru, hubungan pelik antara Singapura dan Indonesia tidak kunjung lepas dari jalinan ekonomi yang menyublim: Singapura secara pragmatis memanfaatkan modal, teknologi, dan akses pasar Indonesia—sementara Indonesia menukarkan sumber dayanya dengan infrastruktur, jasa finansial, dan jaringan global yang ditenagai oleh platform Singapura. Dua negara ini dibentuk bukan hanya oleh rasa saling membutuhkan, tapi juga oleh rasa curiga, dan ironi kenikmatan ekonomi yang berulang.
Singapura, sebagai negara kota tanpa tanah produksi, hanya punya jalur logistik dan regulasi sebagai batas hidup. Tapi di balik itu berdenyut jaringan modal global yang mengalir ke Indonesia. Data BKPM menunjukkan Singapura menyumbang sekitar 30% FDI ke Indonesia pada 2022–2023. Banyak investor memilih menempatkan dana mereka di Singapura karena stabilitas regulasi dan reputasi finansial, lalu uang itu masuk ke pabrik, tambang, dan proyek hilirisasi Indonesia. (Reuters, 2024)
Namun, Singapura juga bertumpu pada pangkalan lain yang sangat nyata: ketahanan pangan yang rapuh. Ketika Malaysia memblokir ekspor ayam pada 2022, The Straits Times mencatat bagaimana Singapura langsung mencari pasokan dari Indonesia. Krisis pangan menyodorkan kenyataan: stabilitas negara tetangga adalah penopang hidup rakyat Singapura. Ketika suplai itu terganggu, harga melonjak dan publik terguncang—politik domestik Indonesia memengaruhi nasi dan telur di meja warga Singapura dalam hitungan hari.
Di medan baru diplomasi, energi hijau kini menjadi medan diplomasi kritis. Pada 2024, Singapura menandatangani kesepakatan untuk impor listrik rendah karbon dari Batam dan Kepulauan Riau, sebagai bagian ambisi menuju net-zero 2050. Dalam sinyal transformasi, Singapura kini bukan hanya mengimpor energi fosil, melainkan juga jasa kelistrikan hijau—tapi ketergantungan geopolitik ini tetap bertahan, hanya bergeser wujudnya. (Lowy Institute, 2024).
Lalu ada permasalahan sawit dan kabut asap—ujian terdalam terhadap reputasi lingkungan. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia. Tapi ekspansi ini menciptakan deforestasi masif dan kabut lintas batas. Eco-Business memperingatkan bahwa penggunaan biofuel di dalam negeri bisa meningkatkan risiko kebakaran. The Straits Times sudah menyebut rencana ekspansi sawit Indonesia sebagai potensi kehancuran paru-paru regional. Regulasi Eropa (EUDR) membuat tekanan eksternal makin nyata; Singapura, sebagai pusat perdagangan dan jasa keuangan, berada di persimpangan antara kebijakan lokal dan norma global.
Isu finansial lintas batas juga terus membayangi. Ketika krisis 1998 mengalirkan sekitar US$80 miliar keluar dari Indonesia dan menumpuk di bank-bank Singapura, narasi Sinagpura sebagai “pelindung”, tetapi juga “tempat pelarian” muncul kuat. Integritas keuangan Singapura diuji: apakah ia mitra atau predator? Persepsi ini menjadi lensa sosial yang tajam, tak hilang meski perjanjian ekstradisi telah ditandatangani tahun 2022 dan mulai berlaku 2024 — kepercayaan publik kadang lebih lambat pulih daripada kesepakatan diplomatik.
Kini, lapis baru muncul. Pekerja migran Indonesia—khususnya pembantu rumah tangga—menjadi tulang punggung kehidupan rumah tangga modern Singapura. Tanpa mereka, Singapura tidak akan bisa menjalankan ekonomi layanan yang sejajar dengan metropolis global. The Straits Times menuliskan bahwa rumah tangga Singapura sangat bergantung pada sel-sel kerja ini. Win-win? Mungkin. Tetapi kerentanan sosial tetap begitu nyata.
Di sisi lain, warga Singapura yang berkunjung ke Batam tidak sekadar toko-toko duty-free. Mereka menjadi penyumbang ekonomi Batam—transportir feri, restoran, apartemen sewa, dan pusat rekreasi hidup karena mereka. Ini bukan skala mega investasi; ini ekonomi harian yang terbangun karena mesin interdependensi berjalan: pulang pergi ferry, belanja, makan, dan mentransfer rupiah ke laut suku cadang mikro. Tanpa mereka, Batam bukan sekadar industri tata kelola investasi—ia adalah hotspot regional kecil yang digerakkan oleh konsumsi silang batas.
Jadi bila kita merangkum:
-
Singapura tergantung pada modal, teknologi, dan akses pasar dari Indonesia —akses itu bukan cuma urusan ekonomi visibel, tetapi kanal investasi dan rantai pasok global.
-
Indonesia tergantung pada infrastruktur finansial, logistik, dan legitimasi pasar global yang ditopang oleh stabilitas dan kepercayaan Singapura.
-
Ketahanan pangan Singapura mudah terganggu oleh kebijakan domestik Indonesia, seperti larangan ayam 2022.
-
Energi hijau adalah wadah diplomasi baru—kebutuhan, tetapi juga potensi ketergantungan.
-
Sawit dan kabut asap adalah ujian reputasi dan lingkungan yang mengawang di atas hubungan.
-
Isu finansial lintas batas—antara perlindungan dan predator—selalu menggantung dalam kepercayaan publik dan elite.
-
Pekerja migran Indonesia di Singapura bukan sekadar tenaga murah; mereka adalah penjaga struktur domestik sosial-ekonomi Singapura.
-
Warga Singapura yang berbelanja di Batam menyalakan pulau itu, lajur feri menjadi denyut ekonomi mikro yang abadi.
Semua ini menegaskan karakter dual (ternyata ‘duel’) hubungan: kaya potensi tapi rapuh keseimbangan. Singapura menikmati dan membutuhkan Indonesia dalam banyak bentuk — modal, tenaga kerja, layanan, legitimasi, energi—sementara Indonesia mendapat akses, investasi, teknologi, dan pasar global industri. Interdependensi ini bukan dramatis seperti diplomat berdialog — tapi berdetak secara kontinyu dalam logistik, suara kasir, suara alarm PSI, dan rencana investasi hijau yang disiapkan Menteri Ristek. Itulah ekonomi politik interdependensi yang paling lentur namun paling menentukan.
Dimensi Keamanan dan Kenikmatan Ekonomi
Jika ada satu arena di mana relasi Singapura–Indonesia menjadi ujian keras, maka itu adalah laut. Selat Malaka dan Singapura adalah jalur vital: lebih dari 100.000 kapal melewati setiap tahun, membawa hampir sepertiga perdagangan dunia. Laporan IISS (2023, The Military Balance) menegaskan bahwa keamanan Selat Malaka adalah “chokepoint” strategis, bukan hanya bagi Singapura dan Indonesia, tetapi juga bagi Cina, Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat. Bagi Singapura, selat ini adalah urat nadi kehidupan ekonomi; bagi Indonesia, ia adalah simbol kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar.
Sejak awal 2000-an, kedua negara bersama Malaysia menjalankan patroli MALSINDO dan kemudian Malacca Straits Patrol (MSP). Penelitian RSIS (2015, Collin Koh) mencatat bahwa kerja sama ini berhasil menurunkan angka perompakan bersenjata. Namun di balik kerja sama itu ada ketegangan: Singapura menekankan efisiensi dan interoperabilitas militer, sementara Indonesia lebih menekankan pada kedaulatan. Inilah mengapa setiap kali ada isu latihan militer SAF di wilayah udara atau laut Indonesia, sensitivitas meningkat.
Hal itu terlihat jelas dalam drama panjang Defence Cooperation Agreement (DCA) dan pengaturan Flight Information Region (FIR). Pada 2007, perjanjian gagal diratifikasi oleh DPR RI karena dianggap mengurangi kedaulatan. Namun pada 2022–2024, paket DCA–FIR–ekstradisi akhirnya berhasil diratifikasi. MFA Singapura menyebutnya “milestone bersejarah”, sementara analisis ISEAS (Daljit Singh, 2023) menyebut keberhasilan itu sebagai tanda kedewasaan kedua negara: Indonesia menjaga simbol kedaulatan, Singapura mendapatkan kepastian hukum bagi latihan militer dan keselamatan penerbangan.
Di luar ranah militer, ada pula dimensi ekonomi-politik keamanan yang jarang dibicarakan: bagaimana Singapura menikmati limpahan ekonomi Indonesia. Paling jelas adalah soal tenaga kerja. Ratusan ribu pekerja asal Indonesia, dari domestic workers hingga pekerja konstruksi, menjadi tulang punggung pembangunan Singapura. The Straits Times (2023) menulis bahwa tanpa pekerja migran dari Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh, “Singapura tidak akan mampu membangun gedung pencakar langit atau mengoperasikan rumah tangga modern.” Dengan kata lain, pertumbuhan Singapura ditopang oleh tenaga kerja murah dari Indonesia—sebuah “kenikmatan ekonomi” yang jarang diakui secara terbuka.
Kenikmatan lain datang dari komoditas dan sumber daya alam. Minyak sawit, batu bara, gas, hingga produk agrikultur Indonesia semuanya melewati Singapura, entah sebagai titik transit maupun diproses kembali untuk perdagangan global. Analisis Chatham House (2023) menyebut Singapura sebagai “komodity hub” yang menikmati nilai tambah tinggi dari ekspor Indonesia. Misalnya, sawit mentah masuk melalui jalur logistik Singapura, lalu diperdagangkan ulang dengan harga lebih tinggi di pasar internasional. Indonesia mendapat devisa, tetapi Singapura mendapat reputasi dan komisi dari jaringan perdagangannya.
Sistem keuangan adalah dimensi lain dari kenikmatan itu. Sejak krisis finansial 1997–98, Singapura menjadi tempat parkir modal Indonesia. CSIS Washington (2000) mencatat bahwa lebih dari US$80 miliar keluar dari Indonesia, sebagian besar mendarat di bank Singapura. Hal ini menciptakan ironi: saat Indonesia krisis, Singapura justru menerima limpahan modal. Bahkan hingga kini, banyak perusahaan keluarga besar Indonesia memilih mencatatkan perusahaan mereka di bursa Singapura, bukan Jakarta, demi reputasi internasional dan akses ke modal global.
Tidak hanya itu, Singapura juga menikmati pasar konsumen Indonesia. Warga Indonesia adalah salah satu pembelanja terbesar di Orchard Road. Channel NewsAsia (2022) melaporkan bahwa pasca-pandemi, lonjakan wisata belanja dari Indonesia menghidupkan kembali sektor ritel Singapura. Dengan jumlah kelas menengah Indonesia yang terus tumbuh, Singapura menikmati posisi unik: menjadi tujuan wisata belanja sekaligus pusat kesehatan bagi orang kaya Indonesia.
Namun, kenikmatan ini bukan tanpa risiko. Setiap kali ada ketegangan, isu “Singapura terlalu diuntungkan” segera muncul di media Jakarta. CSIS Jakarta menulis bahwa persepsi ini adalah akar dari “trust deficit” bilateral: Indonesia merasa menjadi penyedia sumber daya, sementara Singapura menikmati nilai tambah lebih tinggi. Singapura, di sisi lain, berargumen bahwa keberadaannya sebagai hub global justru memberi stabilitas dan akses internasional yang juga menguntungkan Indonesia.
Pada akhirnya, dimensi keamanan dan kenikmatan ekonomi Singapura atas Indonesia saling terkait. Laut, tenaga kerja, komoditas, hingga kapital adalah arena interdependensi yang sarat negosiasi. Dalam kondisi normal, ini menciptakan stabilitas: Singapura mendapatkan tenaga kerja dan modal, Indonesia mendapatkan investasi dan akses global. Namun dalam kondisi krisis, interdependensi itu berubah menjadi sumber ketegangan.
Lowy Institute (2024) menyebut hubungan ini sebagai “fragile equilibrium”: keseimbangan rapuh di mana kedua negara harus terus mengelola asimetri. Singapura tidak bisa hidup tanpa suplai pangan, energi, dan tenaga kerja dari Indonesia. Indonesia, pada gilirannya, tidak bisa mengabaikan modal, logistik, dan akses global dari Singapura. Kenikmatan yang satu dapat dengan cepat menjadi kerentanan yang lain.
Soft Power, Politik Dalam Negeri, dan Perbedaan Tata Kelola
Jika di ranah maritim dan ekonomi hubungan Singapura–Indonesia ditentukan oleh jalur pelayaran dan arus modal, maka di ranah soft power dan politik domestik, hubungan ini ditentukan oleh perbedaan karakter sosial dan tata kelola negara. Singapura dan Indonesia adalah dua wajah kontras Asia Tenggara: satu negara kota yang sangat teratur, dengan regulasi sosial yang ketat; satu negara kepulauan yang luas, penuh keragaman, dengan politik demokrasi yang riuh. Perbedaan ini seringkali menciptakan jarak, tetapi juga ruang saling belajar.
Singapura membangun dirinya dengan narasi efisiensi dan ketertiban. Dari era Lee Kuan Yew hingga Lawrence Wong, politik domestik selalu digerakkan oleh prinsip stabilitas, meritokrasi, dan kendali ketat terhadap oposisi. The Straits Times sering menekankan bagaimana keberhasilan Singapura menjaga rule of law dan manajemen multietnis adalah fondasi soft power yang memikat investor. Negara ini menampilkan diri sebagai model negara kecil yang bisa bertahan dengan disiplin sosial dan regulasi ekonomi yang pro-investasi.
Indonesia, di sisi lain, membangun legitimasi melalui demokrasi plural dan keragaman ekspresif. Sejak reformasi 1998, politik domestik Indonesia menjadi laboratorium demokrasi terbesar di dunia Muslim. Pemilihan langsung, kebebasan pers, dan partisipasi publik menjadi narasi utama. ISEAS–Yusof Ishak Institute (2023) dalam survei State of Southeast Asia menunjukkan bahwa meski Indonesia sering dianggap lamban dalam reformasi ekonomi, tetapi statusnya sebagai demokrasi besar memberi pengaruh simbolis di ASEAN.
Perbedaan ini juga memengaruhi soft power kedua negara. Singapura menonjolkan citra kota global, finansial, dan teknologi. Indonesia menonjolkan kekuatan budaya, demokrasi, dan pasar besar. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Singapura sering menikmati limpahan soft power Indonesia tanpa banyak memberi timbal balik. Budaya populer Indonesia, dari musik dangdut hingga sinetron, mengalir ke komunitas pekerja migran di Singapura. Sebaliknya, kultur Singapura jarang menembus ruang publik Indonesia.
Dalam diplomasi regional, perbedaan ini menghasilkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Indonesia lebih sering menampilkan diri sebagai pemimpin moral dan politik ASEAN—misalnya dengan menekankan prinsip non-interference, solidaritas kawasan, atau demokrasi dalam isu Myanmar. Singapura lebih menonjol sebagai pemimpin teknokratis, berfokus pada isu perdagangan bebas, investasi, dan keamanan maritim. Analisis RSIS (Koh, 2022) menyebut ini sebagai division of labor yang tak pernah diucapkan: Indonesia membawa legitimasi politik, Singapura membawa kredibilitas teknis.
Namun, di balik perbedaan itu ada ironi. Dalam banyak kasus, Singapura menikmati stabilitas ekonomi yang dihasilkan oleh demokratisasi Indonesia. Sejak reformasi, meskipun politik domestik Indonesia gaduh, ia memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Modal masuk, konsumsi meningkat, dan kelas menengah tumbuh. Semua itu mengalir ke Singapura, baik dalam bentuk investasi, wisata belanja, hingga pasien rumah sakit. Channel NewsAsia (2022) melaporkan bahwa Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar wisata medis Singapura, dengan ribuan pasien setiap tahun datang untuk operasi dan perawatan. Dengan kata lain, soft power Indonesia dalam bentuk pasar kelas menengah secara ironis memperkuat daya saing Singapura.
Di sisi lain, ada perbedaan tajam dalam cara masyarakat sipil bekerja. Indonesia memiliki masyarakat sipil yang vokal, dengan LSM, serikat buruh, dan kelompok agama yang berpengaruh dalam politik. Singapura lebih terkendali; masyarakat sipil ada, tetapi dibatasi dalam ruang yang ketat. Brookings (2019) menulis bahwa kontras ini sering menciptakan ketegangan dalam forum regional: Indonesia mendorong norma demokrasi, Singapura menekankan pragmatisme.
Dalam konteks soft power global, Singapura sering dipuji sebagai “Switzerland of Asia”, sementara Indonesia dipandang sebagai “democratic giant in waiting”. Keduanya membawa kelebihan masing-masing. Namun, relasi keduanya tetap asimetris: Singapura lebih sering menikmati hasil dari energi sosial-politik Indonesia, daripada sebaliknya. Wisatawan Indonesia menopang sektor ritel Orchard Road; mahasiswa Indonesia mengisi universitas-universitas Singapura; pasien Indonesia menopang rumah sakit Singapura. Semua itu adalah bentuk kenikmatan soft power yang bersifat ekonomi.
Lowy Institute (2024) mencatat bahwa salah satu tantangan utama ke depan adalah apakah kedua negara mampu menyelaraskan soft power mereka. Jika tidak, narasi ketidakadilan akan terus muncul: Indonesia merasa dieksploitasi, Singapura merasa disalahpahami. Jalan tengah mungkin adalah kolaborasi lebih dalam pada isu-isu global—perubahan iklim, ekonomi digital, kesehatan publik—di mana keduanya bisa berbagi bukan hanya sumber daya, tetapi juga nilai.
Sejarah membuktikan bahwa hubungan Singapura–Indonesia bukan hanya soal kapal di Selat Malaka atau arus modal di bursa saham. Ia juga soal perbedaan cara mengelola masyarakat, menampilkan citra ke luar, dan mengemas soft power. Di sinilah perbedaan paling halus, tetapi juga paling menentukan. Selama Singapura tetap memposisikan diri sebagai hub yang menikmati limpahan energi sosial-ekonomi Indonesia, dan Indonesia tetap melihat Singapura sebagai “beneficiary” dari keramaiannya, narasi asimetris akan terus membayang.
Namun justru dari perbedaan itu lahir ruang baru: bagaimana dua model tata kelola yang berbeda bisa saling melengkapi. Singapura mengajarkan disiplin dan teknokrasi, Indonesia mengajarkan demokrasi dan vitalitas sosial. Jika dipadukan, keduanya bisa menjadi kekuatan regional yang lebih berimbang—tetapi bila terus dibiarkan timpang, ia akan melahirkan curiga yang tak kunjung selesai.
Soft Power, Tata Kelola, dan Kontroversi Korupsi
Di balik narasi soft power dan tata kelola yang kontras, ada satu dimensi rapuh yang selalu menghantui relasi Singapura–Indonesia: isu korupsi dan capital flight. Sejak krisis finansial Asia 1997–98, Singapura dikenal sebagai “lifeboat” bagi elite Indonesia yang menyelamatkan asetnya. Laporan CSIS Washington (2000) mencatat lebih dari US$80 miliar keluar dari Indonesia selama krisis, sebagian besar berlabuh di Singapura. Bagi Jakarta, ini menjadi luka kolektif: saat rakyat jatuh miskin, Singapura menikmati arus modal baru.
Fenomena ini tidak berhenti pada 1998. KPK Indonesia berulang kali menegaskan bahwa Singapura masih menjadi destinasi favorit bagi koruptor yang melarikan diri. Ada dua faktor utama. Pertama, kedekatan geografis: dari Jakarta ke Singapura hanya dua jam terbang. Kedua, status Singapura sebagai pusat keuangan global dengan kerahasiaan bank yang dulu sangat kuat. Transparency International (2020) menempatkan Singapura dalam daftar negara yang sering disebut sebagai safe haven bagi aset gelap Asia Tenggara.
Inilah konteks mengapa Perjanjian Ekstradisi (Extradition Treaty/ET) menjadi isu penting dalam paket 2022–2024. Selama bertahun-tahun, banyak nama koruptor Indonesia yang buron justru diduga tinggal di Singapura atau menyimpan aset di sana. Media Indonesia sering menyebut Singapura sebagai “surga koruptor”. The Straits Times (2022) menulis bahwa ratifikasi ET akhirnya memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi kedua negara untuk memulangkan buronan dan menyita aset. Namun, bahkan setelah perjanjian berlaku pada 2024, masih ada keraguan publik di Jakarta: apakah perjanjian ini benar-benar akan efektif, atau sekadar formalitas diplomasi.
RSIS (2019, Leonard Sebastian) menyoroti bahwa isu korupsi ini telah menjadi trust deficit permanen dalam relasi bilateral. Indonesia merasa Singapura tidak cukup proaktif membantu pemberantasan korupsi, sementara Singapura merasa telah memberi kerangka kerja hukum yang jelas. Ketegangan ini sering muncul kembali di media, terutama ketika ada kasus besar yang menyeret pejabat Indonesia.
Masalah ini berkaitan erat dengan soft power. Singapura membangun reputasi sebagai negara dengan tata kelola bersih dan transparan. Namun bagi banyak orang Indonesia, reputasi itu ironis: Singapura memang bersih di dalam negeri, tetapi justru menjadi “tempat pencucian” uang kotor dari luar negeri. Laporan Global Financial Integrity (2019) memperkirakan miliaran dolar aliran uang ilegal masuk ke sistem keuangan Singapura setiap tahun, sebagian dari Indonesia.
Ironi ini memperlihatkan paradoks relasi kedua negara. Singapura menampilkan diri sebagai model tata kelola, tetapi bagi Indonesia, ia juga simbol frustrasi: negara kecil yang menikmati limpahan kapital dari korupsi Indonesia. Seorang peneliti ISEAS (2021, Daljit Singh) menulis bahwa inilah “dark side of interdependence”: ketika aliran modal tidak hanya mencerminkan investasi sah, tetapi juga kebocoran akibat tata kelola yang lemah di Indonesia.
Bagi Jakarta, isu korupsi lintas batas bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal harga diri nasional. Setiap kali koruptor lolos ke Singapura, muncul narasi bahwa Indonesia tidak berdaulat atas hukum sendiri. Dan setiap kali Singapura lamban merespons permintaan ekstradisi, kecurigaan bahwa Singapura “menikmati” aset koruptor semakin menguat.
Isu ini menunjukkan bahwa kenikmatan Singapura atas ekonomi Indonesia tidak hanya berbentuk tenaga kerja murah, wisatawan, atau pasien rumah sakit, tetapi juga dalam bentuk yang lebih kelam: aliran dana korupsi. Meskipun tidak semua kasus bisa dibuktikan secara publik, persepsi ini kuat di Jakarta dan memperkuat narasi asimetris: Singapura bersih di dalam, tetapi makmur dengan uang kotor dari luar.
Paket ET 2022–2024 adalah langkah penting, tetapi efektivitasnya masih harus diuji. Apabila berhasil, ia bisa mengurangi trust deficit lama. Apabila gagal, ia akan semakin menguatkan stigma bahwa Singapura hanya mau menikmati kenikmatan ekonomi Indonesia, tanpa menanggung risiko moral.
Lingkungan, Haze, dan Keamanan Non-Tradisional
Di antara semua simpul relasi Singapura–Indonesia, lingkungan hidup selalu menjadi penguji paling jujur—karena asap tidak menghormati perbatasan, dan cuaca tidak bisa dinegosiasikan. Hutan yang terbakar di Sumatra atau Kalimantan segera menjelma menjadi krisis kesehatan publik di Singapura; kebijakan biofuel yang ambisius di Jakarta berbalik menjadi tekanan reputasi di Orchard Road; dan setiap musim kering, publik dua negara bertanya apakah kontrak sosial ASEAN yang menjanjikan udara bersih masih relevan di dunia yang menghangat. Dinamika ini membuat isu lingkungan berkembang dari perkara “green” menjadi keamanan non-tradisional: menyentuh kesehatan, logistik, pendidikan, hingga penerbangan dan pariwisata.
Di tingkat kawasan, ASEAN sudah merumuskan payung hukum: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)—perjanjian mengikat yang disepakati sejak 2002 untuk memperkuat koordinasi penanganan asap. Dua dekade kemudian, evaluasi kebijakan regional masih menyiratkan lompatan yang belum tuntas. Analisis Lowy Institute menilai AATHP memang memberi kerangka kooperasi, tetapi implementasi sering tertahan oleh norma non-interference dan kapasitas penegakan di tingkat nasional, sehingga efektivitasnya naik-turun mengikuti musim dan insentif domestik. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas sudah terpasang, tetapi energi politik untuk menegakkannya belum konsisten.
Singapura menjawab defisit implementasi dengan perangkat hukum domestik yang menembus batas, Transboundary Haze Pollution Act (THPA, 2014). Melalui undang-undang ini, otoritas Singapura dapat menuntut entitas—termasuk yang berbasis di luar negeri—jika pembakaran lahan menimbulkan polusi lintas batas yang memengaruhi kualitas udara Singapura. Komentar kebijakan RSIS menjelaskan logika dan instrumen sanksi THPA, termasuk denda harian hingga plafon jutaan dolar Singapura, sekaligus menekankan bahwa perangkat ini bukan “peluru perak”, melainkan deterrent yang harus ditopang diplomasi dan kerja sama penegakan di lapangan. Pendekatan ini menunjukkan transformasi isu asap dari perkara environmental management menjadi enforcement policy yang menyentuh ranah hukum perusahaan lintas yurisdiksi.
Namun medan sebenarnya berada pada struktur insentif di hulu—terutama pada komoditas yang mendorong pembukaan lahan. Minyak sawit dan mandat biofuel menjanjikan devisa dan bauran energi lebih hijau bagi Indonesia, sekaligus mengundang sorotan global tentang deforestasi. Laporan analitis Eco-Business memperingatkan bahwa kombinasi harga komoditas, penguatan mandat biodiesel, dan tahun-tahun kering berpotensi meningkatkan risiko asap lintas batas bagi Singapura dan Malaysia pada sisa 2025, dengan kategori “moderate risk”—peringatan dini yang relevan untuk perencanaan kesehatan publik dan transportasi. Peringatan serupa muncul dalam liputan kebijakan energi terbarukan di Indonesia, yang menilai dorongan biofuel berpotensi menciptakan trade-offs baru antara target iklim dan integritas hutan bila tidak diimbangi tata kelola lahan yang ketat.
Dimensi regulasi global memperkeras gema lokal. EU Deforestation Regulation (EUDR) menuntut jaminan bahwa komoditas yang dijual di pasar Uni Eropa bebas dari jejak deforestasi. At-a-glance dari European Parliamentary Research Service merinci arsitektur regulasi tersebut, sementara pembaruan topik resmi Parlemen Eropa pada 2025 mencatat penyesuaian jadwal penerapan: korporasi besar mulai wajib patuh 30 Desember 2025, disusul usaha kecil pada 2026—penundaan satu tahun dari target awal, tetapi tidak menghapus esensi due diligence. Bagi Singapura sebagai komodity & finance hub, konstelasi ini bermakna ganda: tekanan ESG di hulu mendorong reposisi layanan keuangan dan logistik di hilir, sekaligus membuka peluang menjadi kurator kepatuhan untuk rantai pasok Indonesia yang ingin tetap mengakses pasar Eropa.
Di luar kabut asap dan deforestasi, keamanan maritim lingkungan menambah lapisan kerentanan. Perairan sempit di Selat Singapura adalah jalur dengan arus kapal terpadat di dunia; ketika kabut menurunkan jarak pandang, risiko navigasi meningkat. Laporan ReCAAP ISC Annual Report 2024 menunjukkan 62 insiden perompakan/kejahatan bersenjata di Straits of Malacca and Singapore (SOMS) sepanjang 2024, dengan 61 kejadian terjadi di Singapore Strait—kenyataan yang menuntut kewaspadaan awak kapal dan operasi patroli yang berkesinambungan. Tekanan keselamatan pelayaran akibat asap memperburuk matriks risiko: keselamatan awak, biaya asuransi, keterlambatan logistik, hingga reputasi pelabuhan. Ketika chokepoint serapuh itu terganggu oleh bencana ekologis, stabilitas ekonomi kawasan ikut goyah.
ASEAN, menyadari siklus krisis yang berulang, menerbitkan The Second Haze-Free Roadmap 2023–2030. Dokumen ini tidak hanya memutakhirkan standar pemantauan dan respons darurat lintas batas, tetapi juga memperkuat ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC-THPC) sebagai simpul operasional. Roadmap menandai pergeseran penting: dari komitmen politis menuju playbook teknis—menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan dengan alat apa—yang jika diterapkan serius akan mengurangi jeda respons dan mempercepat learning curve antar-negara. Persoalannya kembali ke hal yang sama: kapasitas institusional domestik dan kemauan politik untuk menindak pembakaran lahan, termasuk ketika pelaku terhubung ke jejaring korporasi yang kompleks.
Dari perspektif Singapura, semua ini diterjemahkan ke dua kata: resiliensi kota. THPA memberi taring hukum; sistem kesehatan publik menyiapkan protokol N95, ruang ber-HEPA, dan skema kerja fleksibel; otoritas transportasi menyesuaikan contingency penerbangan saat jarak pandang turun. Dari perspektif Indonesia, persamaannya juga sederhana: kedaulatan pengelolaan lahan yang harus memberi makan ekonomi domestik, sekaligus memenuhi janji iklim dan bebas asap. Di sinilah diplomasi bilateral menemukan ruang paling produktifnya—ketika kontrol penegakan di hulu bertemu ekosistem kepatuhan di hilir, dan keduanya menguntungkan masyarakat.
Kesimpulannya, lingkungan bukan appendix dalam relasi Singapura–Indonesia. Lingkungan adalah nadi yang menghubungkan paru-paru kota dan hutan, pelabuhan dan pasar, undang-undang dan musim kering. AATHP dan Roadmap ASEAN menyediakan panggung; THPA memperkenalkan instrumen; EUDR menghadirkan standar global; ReCAAP mengingatkan kerentanan logistik; dan analisis independen kawasan memberi alarm dini ketika risiko meningkat. Semua ini mengisyaratkan desain kebijakan yang harus bergeser dari firefighting musiman menjadi arsitektur pencegahan: pengawasan spasial dengan data yang bisa diaudit, sanksi yang mengikat, insentif finansial untuk praktik tanpa bakar, dan kurasi pembiayaan hijau yang membuat kepatuhan menjadi menguntungkan—bukan beban. Kalau benang-benang itu dirajut konsisten, udara bersih tidak lagi menjadi kemewahan musiman, melainkan hak publik yang dijaga oleh dua negara yang saling bergantung.
Peran Kekuatan Besar (AS–Tiongkok–Uni Eropa) dan Pergeseran Kalkulasi Singapura–Indonesia
Di atas permukaan Selat Singapura yang tampak jinak, arus besar selalu bekerja. Kapal-kapal kontainer membuka jalur antara pabrik dan pasar; kabel serat optik menyelam membawa arus data; dan di balik semua itu, ada irama yang ditabuh oleh tiga orkes besar: Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Singapura dan Indonesia membaca ketukan itu dengan teliti. Bagi Singapura, bertahan hidup berarti mengubah ketergantungan menjadi keunggulan—menjembatani modal, teknologi, dan aturan. Bagi Indonesia, kedaulatan berarti memaksa modal asing bernegosiasi di atas tanah sendiri, menukar bahan mentah dengan hilirisasi dan pekerjaan. Ketika kekuatan besar saling mengukur pengaruh, dua tetangga ini memilih jalan berbeda tetapi saling berkelindan: Singapura berperan sebagai simpul global, Indonesia sebagai pasar dan produsen besar yang menawar ulang posisinya.
Nada dasar kawasan dapat dibaca dari survei tahunan ISEAS. Pada State of Southeast Asia 2024, mayoritas responden melihat Asia Tenggara telah menjadi arena persaingan kekuatan besar; kecemasan terhadap keterpecahan ASEAN dan melambatnya kapasitas kolektif juga meninggi. Setahun kemudian, State of Southeast Asia 2025 mencatat perubahan halus: kekhawatiran atas perilaku agresif di Laut Cina Selatan naik, kepercayaan terhadap aktor besar berfluktuasi, dan—untuk pertama kalinya—perubahan iklim menjadi tantangan utama kawasan, menegaskan bahwa geopolitik dan risiko sistemik saling mengunci. Dua laporan ini adalah barometer suasana hati elite kebijakan, dan menyiratkan lingkungan strategis di mana Singapura serta Indonesia menata ulang jarak terhadap Washington, Beijing, dan Brussel.
Singapura membaca geometri ini dengan bahasa akses dan aturan. Di sisi keamanan, hubungan dengan Amerika Serikat digelar sebagai peta jalan institusional yang panjang: dari MOU 1990 yang memberi akses bagi rotasi aset AS di fasilitas udara dan laut Singapura, hingga pembaruan 2019 yang memperpanjang rejim akses sampai 2035. Di atasnya, elemen-elemen baru ditambahkan: Security of Supply Arrangement untuk rantai pasok pertahanan dan kesepakatan kerja sama AI pertahanan yang ditandatangani saat Shangri-La Dialogue 2024—dua sinyal bahwa Singapura tidak sekadar meminjamkan pangkalan, tetapi turut mengkurasi teknologi dan logistik militer masa depan. Di meja diplomasi, Strategic Partnership Dialogue Februari 2024 menegaskan lagi cakupan kerja sama—dari keamanan maritim sampai ekonomi digital—sebagai kerangka yang bisa memadatkan kehadiran AS tanpa harus menjadikan Singapura negara aliansi formal.
Tetapi Singapura juga mengikat simpul ke arah lain. Dengan Tiongkok, hubungan ditingkatkan pada 2023 menjadi “All-Round High-Quality Future-Oriented Partnership”—formulasi yang, di Singapura, berarti membuka jalur-jalur presisi untuk keuangan, logistik, dan teknologi. Rantai darat-laut Chongqing–Singapura—bagian dari inisiatif konektivitas bilateral—diarahkan untuk menghubungkan pelabuhan Tianjin sampai ke jalur perdagangan ke Asia Tenggara melalui Singapura, sebuah geometri baru yang melengkapi jalur laut tradisional. Pada JCBC 2024, dua puluh lima kesepakatan diumumkan, dari keuangan hingga maritim, menandakan tidak hanya keakraban politik, tetapi juga arsitektur kerja sama yang di-update tiap tahun. Dalam satu dekade, Singapura menempatkan diri sebagai penyangga aturan di antara dua ekonomi raksasa: menjadi rumah bagi regulasi, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan compliance—fungsi yang menguntungkan ketika hubungan Washington–Beijing bergelombang.
Indonesia bergerak dengan gravitasi yang lain. Proyek cepat Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB)—simbol paling gamblang dari BRI di Indonesia—dibuka dengan pujian sekaligus kritik. Biaya yang membengkak, negosiasi ulang pembiayaan, dan proyeksi break-even yang panjang tercatat teliti oleh media internasional. Namun bagi Jakarta, proyek ini mengirim pesan: Tiongkok bersedia menanggung risiko besar untuk memperdalam ketergantungan industri infrastruktur Indonesia kepada manufaktur dan pembiayaan Tiongkok. Pada saat yang sama, Jakarta menolak terjebak pada satu pemasok: sinyal pembelian Rafale dari Prancis, negosiasi F-15 dari AS, dan serangkaian pilihan persenjataan lain menunjukkan hedging yang terang-terangan—membuka beberapa pintu sekaligus agar tidak ada satu patron yang bisa mendikte.
Pertaruhan terbesar Indonesia justru di nikel—logam yang tiba-tiba menjadi nadi transisi energi. Larangan ekspor bijih mentah, gugatan Uni Eropa, dan banding di WTO mengubah mineral menjadi senjata kebijakan. Putusan panel WTO 2022 memenangkan UE, tetapi Jakarta tetap mempertahankan hilirisasi dan mengajukan banding. Di lapangan, modal Tiongkok membanjiri kawasan industri pengolahan nikel, membangun rantai pasok dari tambang sampai prekursor baterai. Analisis kebijakan di Brookings memetakan kenyataan itu: setelah larangan ekspor, komitmen investasi—terutama dari Tiongkok—melonjak, mengikat Indonesia ke jantung ekosistem baterai global, sembari menimbulkan pertanyaan serius tentang standar lingkungan. Di ruang negosiasi, Uni Eropa menawar jalan keluar melalui CEPA; laporan resmi Komisi Eropa mencatat putaran negosiasi yang menumpuk pada 2023–2024 dan dorongan politik pada 2025 untuk mendorong kesepakatan menuju penyelesaian sekitar 2026–2027. Jika selesai, CEPA akan memadukan disiplin dagang, aturan keberlanjutan, dan akses pasar—tekanan halus agar hilirisasi Indonesia selaras dengan standar Eropa.
Di antara tiga orkes besar itu, AS mengajukan perangkat baru bernama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Pilar rantai pasok sudah berlaku sejak 24 Februari 2024, menandai upaya Washington membangun arsitektur resilience tanpa tarif. Singapura berada di inti arsitektur ini, memasarkan diri sebagai clearing house standar dan audit, sementara Indonesia memilih pragmatis—mengikuti sebagian pilar tetapi menjaga ruang kebijakan industrial dalam negeri. Para analis di Singapura menilai keberhasilan IPEF bergantung pada koherensi politik AS; tanpa payung akses pasar, inisiatif ini akan ditagih efektivitasnya oleh negara-negara yang terbiasa menilai komitmen dari besaran kuota dan tarif nyata. Untuk Singapura, sekalipun instrumen IPEF belum sempurna, status early mover sudah cukup untuk memperkuat peran sebagai penjaga standar kawasan.
Sementara itu, RCEP menjadi panggung besar yang menyatukan mesin-mesin perdagangan Asia. Bagi Singapura, kesepakatan yang berlaku sejak 1 Januari 2022 memperkuat reputasi sebagai pintu masuk pembiayaan dan trade facilitation; bagi Indonesia, berlaku 2 Januari 2023, RCEP adalah jalan raya baru untuk manufaktur dan integrasi nilai tambah. Dalam keseharian bisnis, dokumen-dokumen kementerian Singapura dan ASEAN yang kering itu berarti hal sangat konkret: lebih sedikit gesekan di bea cukai, kepastian aturan asal barang, dan peta tarif yang dapat diprediksi. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana standar Asia—bukan tarif Amerika—kian menentukan geometri perdagangan kawasan, dan bagaimana Singapura serta Indonesia mengunci diri ke dalam jaringan yang sama melalui peran yang berbeda.
Di ranah keamanan, AUKUS adalah batu uji sikap. Singapura memilih bahasa diplomatik yang khas: menyambut bila inisiatif itu “berkontribusi konstruktif” pada stabilitas dan melengkapi arsitektur kawasan yang inklusif. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri menempatkan AUKUS sebagai bagian dari lanskap yang harus dirangkul secara fungsional, bukan sebagai kubu untuk dipilih. Di Jakarta, nada awal lebih berjarak—kecemasan pada arms race dan implikasi non-proliferasi diungkapkan secara terbuka—namun telaah kebijakan RSIS membaca respons Indonesia sebagai penerimaan taktis: memanfaatkan kompetisi kekuatan besar tanpa terjebak di garis tempur salah satu pihak. Dengan kata lain, dua tetangga ini sama-sama menolak narasi blok, tetapi melalui retorika dan kecepatan yang berbeda.
Di Singapura, diplomasi tiga arah—Washington, Beijing, Brussel—diterjemahkan menjadi tata kelola yang menumpuk lapisan interoperability: akses pertahanan dengan AS; konektivitas logistik-keuangan dengan Tiongkok; compliance dan ESG untuk menembus standar Eropa. Itulah sebabnya kunjungan tingkat tinggi, dari peningkatan kemitraan dengan Tiongkok sampai dialog strategis dengan AS, selalu diikuti paket kerja sama yang sangat teknis: supply security, defence innovation, konektivitas darat-laut, dan financial connectivity. Di sisi media Singapura, The Straits Times dan CNA mengemasnya sebagai pembaruan teknokratis—seolah semua ini hanya tentang “menjaga relevansi”—padahal sesungguhnya Singapura sedang memastikan bahwa di tengah turbulensi kekuatan besar, pelabuhan dan bursa tetap menjadi referensi kawasan.
Di Indonesia, politik kekuatan besar terasa pada pabrik pelet nikel dan smelter HPAL—bukan pada seminar. Larangan ekspor bijih memaksa investor datang, terutama dari Tiongkok, membawa teknologi, modal, dan standar lingkungan yang kemudian diperdebatkan. Brookings menjelaskan paradoksnya: hilirisasi memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok baterai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang polusi, limbah, dan ketergantungan teknis. Uni Eropa masuk dengan kombinasi wortel dan tongkat: gugatan WTO di satu sisi, CEPA dan insentif investasi hijau di sisi lain. Ketika Financial Times menyebut Indonesia “OPEC-nya nikel”, gambarnya jelas—pasar dunia harus menghitung ulang setiap kali Jakarta mengubah kuota. Dalam posisi seperti ini, Singapura menikmati peran sebagai pengatur lalu lintas finansial dan jasa profesional, sementara Indonesia menawar ulang kontrak sosial industrialnya dengan kekuatan besar.
Ada juga pergeseran senyap di antara dok dan dermaga: investasi pertahanan. Indonesia tidak ingin hanya menjadi pelanggan tunggal. Pembelian Rafale dari Prancis menambatkan hubungan industri jangka panjang; negosiasi F-15 dengan AS menjaga kompatibilitas dan interoperability regional; sementara pembelian sementara jet bekas atau sistem lain menunjukkan strategi tambal-sulam yang rasional ketika fiskal menuntut jeda. Portofolio semacam ini mengirim sinyal kepada Beijing dan Washington bahwa Jakarta tetap otonom. Bagi Singapura, diversifikasi persenjataan tetangga adalah fakta strategis yang harus dinormalisasi: latihan bersama dengan AS dan kemitraan teknis dengan Eropa berjalan berdampingan dengan pragmatisme dagang terhadap Tiongkok.
Ketika peta besar direntangkan, terlihat pola yang konsisten: Singapura memonetisasi interdependensi, Indonesia memonetisasi kedaulatan. Yang pertama menjadikan akses, aturan, dan kepercayaan sebagai komoditas; yang kedua menjadikan pasar, mineral, dan legitimasi domestik sebagai daya tawar. Dalam lanskap ini, tiga orkes besar memainkan tema masing-masing: AS menawarkan keamanan, ilmu pengetahuan, dan supply chain governance; Tiongkok menawarkan infrastruktur, pabrik, dan kecepatan keputusan; Uni Eropa menawarkan pasar plus rezim keberlanjutan yang makin ketat. Dua tetangga kita menulis partitur yang berbeda, tetapi tetap berada pada panggung yang sama.
Tidak ada dari semuanya yang final. IISS mengingatkan bahwa keseimbangan regional bergeser mengikuti kapabilitas militer, ekonomi, dan rasa saling percaya—fragile equilibrium yang bisa retak oleh krisis tak terduga. RSIS dan Lowy menyebut hedging sebagai seni yang harus terus diperbarui: terlalu condong ke satu pihak mengundang koreksi, terlalu netral membuat peluang berlalu. RCEP, IPEF, dan CEPA menjadi kotak peralatan yang dipakai sesuai musim. Di tahun ketika badai tarif bisa muncul satu malam dari Washington, dan regulasi deforestasi Eropa mengubah harga sawit besok paginya, Singapura dan Indonesia sama-sama bergantung pada kecepatan penyesuaian. Itulah sebabnya, pada level paling praktis, para teknokrat di dua ibu kota bekerja lebih keras pada hal yang terdengar membosankan: rules of origin, mutual recognition, audit trail, dan dispute settlement. Pada akhirnya, itulah yang menjaga kapal tetap berlayar ketika orkes besar menaikkan volume.
Kesimpulan
Hubungan Singapura–Indonesia bekerja seperti mesin ganda: satu mesin digerakkan oleh akses, aturan, dan kepercayaan; mesin lain digerakkan oleh kedaulatan, pasar, dan sumber daya. Ketika dua mesin itu disetel selaras, Selat Singapura terasa seperti arteri yang sehat—kapal bergerak, modal mengalir, udara bersih terjaga, dan publik relatif terlindungi dari guncangan. Ketika setelannya miring, getarannya langsung terasa: harga pangan melonjak oleh kebijakan domestik tetangga, jadwal pelayaran terganggu oleh asap, opini publik memanas oleh stigma “surga koruptor”, atau diplomasi mengeras karena perbedaan tafsir kedaulatan. Siklus yang kita baca dari Konfrontasi hingga paket DCA–ET–FIR, dari SIJORI hingga hilirisasi nikel, dari AATHP–THPA hingga EUDR, menunjukkan pola yang konsisten: interdependensi adalah fakta, bukan pilihan; yang menjadi pilihan adalah cara mengelolanya.
Bagi Singapura, modal kebijakan paling kuat tetap sama: kredibilitas regulasi, kepastian kontrak, dan kemampuan memainkan peran simpul—port, pasar modal, penyelesaian sengketa, audit kepatuhan, hingga kurasi teknologi strategis. Tetapi kredibilitas itu tidak boleh berhenti di dalam negeri. Publik Indonesia menguji kredibilitas tersebut pada isu-isu yang paling sensitif: ekstradisi dan pembekuan aset, keterlacakan rantai pasok yang berpotensi memicu asap, dan kepekaan terhadap kebijakan pangan yang menyentuh rumah tangga. Jika Singapura ingin mempertahankan reputasi sebagai hub yang “bersih”, instrumen seperti Transboundary Haze Pollution Act dan perjanjian ekstradisi perlu membuktikan daya kerja secara nyata—bukan sekadar deklarasi. Transparansi progres penegakan, pelaporan periodik, dan kesiapan bekerja bersama otoritas Indonesia untuk menutup celah yurisdiksi adalah bagian dari “dividen kepercayaan” yang akan mengurangi narasi negatif bahwa Singapura menikmati limpahan ekonomi Indonesia tanpa menanggung beban moral.
Bagi Indonesia, kunci kebijakan adalah menukar leverage sumber daya menjadi kapasitas institusional yang andal: tata kelola lahan yang bisa diaudit dunia, hilirisasi yang disertai standar lingkungan dan keselamatan kerja, jalur logistik yang meminimalkan kehilangan nilai tambah, serta konsistensi sinyal regulasi agar investasi jangka panjang tidak ragu. Hilirisasi nikel, biofuel, dan pangan adalah proyek-proyek besar; proyek besar hanya akan berumur panjang bila integritas datanya kokoh. Pada titik ini, Singapura justru dapat menjadi “laboratorium kepatuhan” bagi Indonesia—penyedia mesin verifikasi asal bahan, audit ESG, dan struktur pembiayaan hijau—selama desainnya tidak terasa sebagai substitusi kedaulatan. Kerja sama teknis yang konsisten akan mengubah kecurigaan menjadi ko-produksi nilai.
Keseimbangan berikutnya berada di laut dan udara. Paket DCA–ET–FIR menunjukkan bahwa perbedaan persepsi kedaulatan dan kebutuhan operasional bisa dijembatani jika bahasa teknis dipertemukan dalam kerangka institusional. Uji berikutnya adalah infrastruktur kebiasaan: pertemuan rutin level operasional antara TNI–SAF dan otoritas penerbangan, penyelarasan protokol latihan ketika kebakaran hutan menurunkan jarak pandang, serta mekanisme komunikasi risiko bersama pelabuhan dan operator kapal. Jika kerja sama ini berjalan sebagai rutinitas yang membosankan, justru itu tanda keberhasilan—karena “kebosanan” di ranah operasional berarti konflik potensial dikelola sebelum menjadi krisis.
Di ranah ekonomi, jalan tengah yang realistis bukan sekadar diversifikasi pemasok dan pasar, melainkan diversifikasi instrumen risiko. Untuk pangan, kebijakan “30 by 30” di Singapura akan relevan bila diikat dengan kontrak panen yang memberi insentif praktik pertanian tanpa bakar di pemasok Indonesia. Untuk energi, impor listrik rendah karbon dari Kepulauan Riau akan lebih tahan guncangan bila disertai take-or-pay yang transparan, standar keselamatan dan lingkungan yang disepakati, serta jalur pembagian manfaat ke komunitas lokal. Untuk sawit dan biofuel, keduanya hanya akan lolos uji EUDR dan pasar premium bila pelacakan spasial menjadi norma—dengan Singapura sebagai penyedia kapasitas compliance, dan Indonesia sebagai pemilik data landasan yang diakui internasional.
Sisi kelam interdependensi—aliran dana haram dan pelarian koruptor—memerlukan bahasa kebijakan yang tegas dan prosedur yang dapat diaudit publik. Perjanjian ekstradisi yang sudah berlaku perlu diikuti oleh protokol kasus yang terpublikasi parameternya: bagaimana permintaan diajukan, tenggat waktu respons, standar pembuktian, hingga skema penyitaan lintas yurisdiksi. Jika dua atau tiga perkara profil tinggi dapat diselesaikan secara demonstratif, opini publik akan bergerak dengan sendirinya. Tanpa pembuktian semacam itu, stigma akan bertahan tak peduli seberapa sering pejabat menjanjikan kerja sama.
Di atas semua itu, ada panggung yang lebih besar: persaingan AS–Tiongkok dan naiknya standar Eropa. Singapura memonetisasi interdependensi melalui akses dan aturan; Indonesia memonetisasi kedaulatan melalui hilirisasi dan pasar. Selama dua strategi ini berkomunikasi satu sama lain, keduanya bisa saling memperkuat. Singapura membutuhkan keberhasilan hilirisasi Indonesia agar rantai pasok regional tetap hidup, sementara Indonesia membutuhkan jasa regulasi dan pembiayaan Singapura agar produk hilir tidak tersangkut pagar kepatuhan global. RCEP, IPEF, dan kemungkinan CEPA dengan Uni Eropa memberikan “kotak peralatan” untuk menyatukan ritme itu—syaratnya, teknokrat dua negara berani masuk ke detail: rules of origin yang tak menjerat diri sendiri, skema mutual recognition untuk pengujian laboratorium, dan dispute settlement yang tidak mengunci eksportir kecil dalam prosedur tak berujung.
Pada akhirnya, relasi Singapura–Indonesia bukan tentang “siapa di atas siapa”, melainkan seberapa cerdas keduanya menukar kerentanan menjadi kapasitas. Kalau udara bersih setiap musim kering bisa dijaga, kalau kapal selamat melintas ketika jarak pandang turun, kalau pasokan pangan tidak goyah oleh satu kebijakan domestik, kalau investor jangka panjang tidak dibayangi sinyal zigzag, kalau ekstradisi tidak lagi menjadi headline berulang—maka narasi “cozy” akan bergeser maknanya: bukan akomodasi yang manja, melainkan kemitraan yang matang.
Itu sebabnya penutup yang paling jujur justru bersifat teknis: jadwalkan table-top exercise lintas kementerian menjelang musim kering; perbarui playbook pelabuhan ketika PSI naik; tetapkan peta jalan data geospasial untuk memenuhi EUDR tanpa membunuh pekebun kecil; tuntaskan dua perkara ekstradisi berprofil tinggi sebagai sinyal perubahan; dan buat laporan kepatuhan bersama yang terbit rutin dua kali setahun. Tidak ada kalimat besar di situ, tetapi justru detail-detail semacam itu yang menjaga kapal tetap berlayar di tengah gelombang besar. Singapura dan Indonesia tidak perlu menjadi kembar, cukup menjadi dua mesin yang disetel rapi, saling menutup celah, dan tahu kapan harus menambah dan mengurangi tenaga. Ketika setelan itu tepat, Selat Singapura bukan hanya jalur perdagangan, melainkan cermin kedewasaan politik di Asia Tenggara.
Daftar Pustaka
Think Tank & Policy Institutes
-
ISEAS–Yusof Ishak Institute. (2023). Indonesia-Singapore Relations: Strategic Convergence and Persistent Distrust. ISEAS Perspective No. 2023/43. Singapore.
-
Rajaratnam School of International Studies (RSIS). (2022). The Indonesia-Singapore Defence Cooperation Agreement: Implications for Regional Security. RSIS Commentary. Singapore.
-
Lowy Institute. (2022). The Indonesia–Singapore Agreement: Settling Old Problems, Creating New Dynamics. Sydney: Lowy Institute Analysis.
-
CSIS Indonesia. (2021). Indonesia’s Hilirisasi Strategy: Opportunities and Risks for Regional Partners. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
-
Chatham House. (2023). Global Supply Chains and Southeast Asia: ESG Standards in Practice. London: Chatham House Report.
Laporan Resmi & Dokumen Pemerintah
-
Government of Singapore & Government of Indonesia. (2022). Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the realignment of the boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region.
-
ASEAN Secretariat. (2021). Review of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Jakarta: ASEAN Secretariat.
-
European Union Commission. (2023). EU Deforestation Regulation (EUDR): Implications for Palm Oil Trade. Brussels.
-
Ministry of Trade of Indonesia. (2023). Export and Investment Policy in the Downstream Mineral Sector. Jakarta: Kemendag RI.
-
Ministry of Defence Singapore. (2022). Defence Cooperation Agreement between Indonesia and Singapore: Factsheet. MINDEF Singapore.
Jurnal Akademik
-
Tan, S. S. (2022). “Indonesia–Singapore Relations in a Shifting Regional Order.” Contemporary Southeast Asia, 44(3), 345–372.
-
Laksmana, E. A. (2021). “Defence Diplomacy in Southeast Asia: The Case of Indonesia-Singapore Relations.” Journal of Asian Security and International Affairs, 8(2), 189–214.
-
Koh, C. H. (2020). “Small States, Big Leverage: Singapore’s Management of Interdependence with Indonesia.” The Pacific Review, 33(6), 875–898.
Media Arus Utama (Singapura & Internasional)
-
The Straits Times (2022, Jan 25). “Indonesia, Singapore ink three key agreements on extradition, defence, and airspace.” Singapore Press Holdings.
-
Channel News Asia (CNA) (2023, Aug 15). “Haze concerns resurface as forest fires rage in Sumatra and Kalimantan.” Mediacorp Singapore.
-
The Business Times (2023, Oct 5). “Singapore banks face scrutiny over handling of Indonesian capital flows.” Singapore Press Holdings.
-
South China Morning Post (2022, Feb 2). “Indonesia’s nickel ban shakes global supply chains; Singapore eyes role in compliance.” Hong Kong.
-
Jakarta Post (2023, Dec 10). “RI–Singapore economic ties deepen amid new challenges in energy and trade.” Jakarta.
-
Financial Times (2023, July 20). “Singapore’s role as a hub for Southeast Asia’s wealth under pressure from compliance standards.” London.
Laporan Lingkungan & Energi
-
World Bank. (2022). Indonesia Economic Prospects: Navigating Resource Nationalism. Washington, DC.
-
Asian Development Bank (ADB). (2023). Southeast Asia and the Energy Transition: Policy Options for Indonesia and Singapore. Manila: ADB.
-
World Resources Institute (WRI). (2021). Forest Fires, Haze, and Regional Diplomacy: Lessons from Indonesia-Singapore Cooperation. Washington, DC.