Your cart is currently empty!
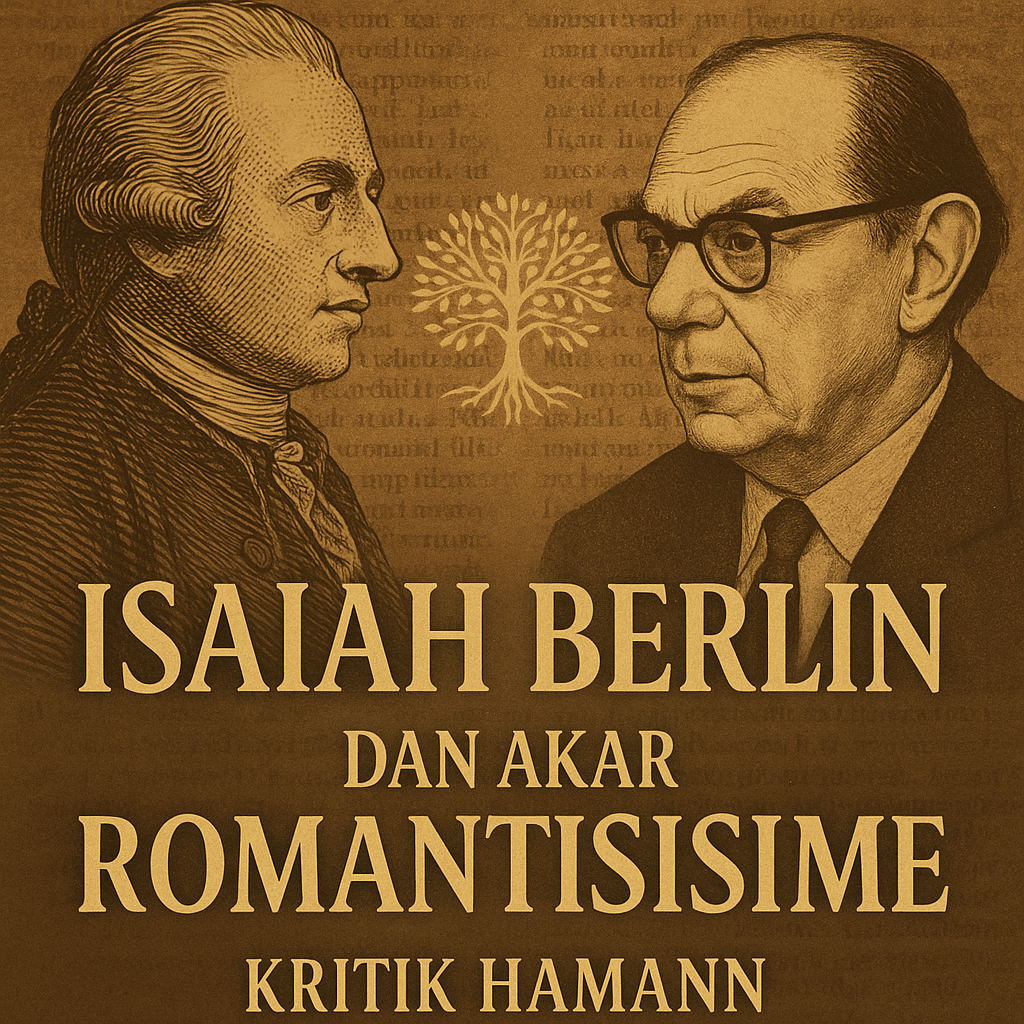
Isaiah Berlin dan Akar Romantisisme: Kritik Hamann terhadap Pencerahan
Pendahuluan: Membaca Ulang Abad ke-18 dalam Bayangan Romantisisme
Isaiah Berlin, dalam karya terkenalnya The Roots of Romanticism, menyingkapkan bahwa romantisisme bukan sekadar gaya seni atau arus sastra, melainkan sebuah revolusi intelektual yang mengguncang fondasi modernitas. Abad ke-18, yang biasanya digambarkan sebagai zaman Pencerahan, penuh dengan kemenangan rasionalitas, keindahan hukum-hukum universal, serta lahirnya negara sekuler, ternyata menyembunyikan ketegangan mendalam. Di balik gemerlap ilmu pengetahuan, terdapat keresahan eksistensial yang mencari ruang bagi perasaan, intuisi, dan misteri.
Dalam konteks ini, Berlin mengangkat sosok Johann Georg Hamann, pemikir Jerman yang radikal dan nyaris terlupakan, tetapi justru menjadi pionir dari perlawanan terhadap dominasi akal. Hamann menolak untuk tunduk pada paradigma Pencerahan yang hendak mereduksi agama dan sejarah menjadi sekadar soal kalkulasi logis. Ia menganggap usaha tersebut sebagai bentuk penghujatan terhadap Tuhan, karena mengukur yang tak terbatas dengan instrumen manusia yang terbatas. Berlin melihat Hamann sebagai “bapak tersembunyi” romantisisme.
Pencerahan menegaskan bahwa alam semesta dapat dimengerti sepenuhnya melalui hukum-hukum rasional. Dalam kerangka itu, manusia dianggap mampu menguasai realitas dengan metode ilmiah. Tetapi Hamann menantang klaim tersebut. Baginya, kenyataan tidak bisa dipersempit menjadi angka, rumus, atau geometri semata. Ada dimensi transenden yang menolak untuk dijinakkan oleh kalkulasi. Kritik ini bukan sekadar keberatan teologis, melainkan protes terhadap reduksi eksistensi menjadi mekanika kering.
Berlin menjelaskan bahwa abad ke-18 bukanlah dunia yang benar-benar harmonis dan elegan, sebagaimana sering dilukiskan. Justru, di balik simetri indahnya, tersembunyi daya tarik terhadap kekuatan gelap, irasional, dan misterius. Banyak fenomena—mulai dari sekte rahasia, eksperimen okultis, hingga tokoh-tokoh eksentrik seperti Mesmer atau Cagliostro—menjadi bukti bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan rasio. Rasionalisme yang terlalu menekan justru memancing kebangkitan irasionalitas.
Di titik inilah romantisisme muncul, sebagai sebuah pemberontakan intelektual. Romantisisme adalah upaya untuk merebut kembali ruang bagi pengalaman subjektif, bagi perasaan, dan bagi misteri. Jika Pencerahan menekankan hukum universal, romantisisme menegaskan keunikan individual. Jika rasionalisme mengedepankan keteraturan, romantisisme merayakan keindahan dari ketidakteraturan. Semua ini, menurut Berlin, berakar pada penolakan Hamann terhadap dominasi sains dan filsafat sistematik.
Dengan demikian, memahami Hamann berarti menelusuri akar terdalam dari gerakan romantik. Ia bukanlah seorang filsuf sistematik seperti Kant atau Wolff, tetapi justru karena sifatnya yang anti-sistem itulah ia menjadi inspirasi bagi revolusi intelektual yang menolak segala bentuk reduksi kehidupan menjadi formula kaku.
Hamann dan Kritik atas Pencerahan
Johann Georg Hamann tampil sebagai sosok yang unik dalam lanskap pemikiran abad ke-18. Ia bukanlah tokoh besar dalam arti pengaruh institusional atau sistem filosofis, tetapi pengaruhnya meluas secara diam-diam. Hamann percaya bahwa Pencerahan telah melakukan kesalahan fatal: berusaha menjinakkan realitas dengan rasio manusia. Menurutnya, hal ini sama saja dengan menutup pintu terhadap misteri kehidupan. Berlin menilai bahwa Hamann adalah pemikir yang berani menentang arus besar zamannya dengan cara yang sangat frontal.
Hamann menolak gagasan bahwa ilmu pengetahuan dapat menguasai seluruh aspek realitas. Ia menganggap bahwa sains, meski penting, hanyalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Ketika sains dijadikan otoritas tunggal, maka manusia kehilangan kedalaman eksistensialnya. Tuhan, bagi Hamann, tidak bisa direduksi menjadi seorang matematikawan agung yang hanya bekerja dengan angka dan hukum mekanis. Upaya untuk memaksakan geometri pada Yang Ilahi dianggapnya sebagai penghujatan.
Berlin menegaskan bahwa Hamann melihat Pencerahan sebagai proyek yang secara fundamental berbahaya. Pencerahan merayakan universalitas hukum rasional, tetapi justru menghapus keberagaman pengalaman manusia. Ia menganggap bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam memahami Tuhan, sejarah, dan alam. Ketika akal dipaksakan menjadi ukuran tunggal, maka pluralitas pengalaman itu dihancurkan. Romantisisme kemudian menjadikan gagasan ini sebagai fondasi: penolakan terhadap universalisme rasional, dan perayaan terhadap keunikan individual.
Kritik Hamann juga menyentuh aspek sejarah. Menurutnya, peristiwa-peristiwa sejarah tidak bisa dipandang hanya sebagai rangkaian fakta empiris yang netral. Setiap kejadian menyimpan makna mistis, sebuah pesan dari Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki “mata rohani.” Sejarah, dengan demikian, adalah wahana komunikasi Ilahi, bukan sekadar objek penelitian ilmiah. Pandangan ini jelas bertentangan dengan semangat historiografi Pencerahan yang hendak mengungkap hukum-hukum umum sejarah melalui analisis rasional.
Hamann juga mengkritik bahasa rasional. Baginya, bahasa bukanlah instrumen netral untuk menyampaikan ide, melainkan simbol yang sarat dengan misteri. Bahasa rasional yang memotong-motong realitas menjadi kategori analitik justru menghancurkan kesatuan hidup. Kata-kata, menurut Hamann, sering kali gagal mengekspresikan kedalaman pengalaman manusia. Oleh karena itu, seni, mitos, dan simbol justru lebih dekat kepada kebenaran daripada wacana filosofis yang terlalu kering.
Dari semua kritik ini, Berlin menyimpulkan bahwa Hamann adalah pionir perlawanan terhadap Pencerahan. Ia menegaskan kembali dimensi yang dilupakan oleh rasionalisme: pengalaman eksistensial, makna transenden, dan simbolisme mitis. Dengan cara ini, Hamann membuka jalan bagi lahirnya romantisisme, yang kemudian berkembang menjadi gerakan besar dalam sejarah intelektual Eropa.
Rasionalisme, Agama, dan Krisis Spiritualitas
Rasionalisme abad ke-18 tidak hanya menyerang tatanan sosial-politik lama, tetapi juga merembes ke dalam agama. Para filsuf seperti Christian Wolff berusaha menyelamatkan agama dengan cara menyesuaikannya ke dalam kerangka rasional. Mukjizat ditafsirkan ulang sebagai fenomena ilmiah yang luar biasa, tetapi tetap bisa dijelaskan. Misalnya, ketika matahari berhenti di Yerikho, Wolff menyatakan bahwa itu hanyalah bentuk pengetahuan astrofisika yang mendalam. Demikian pula, ketika air berubah menjadi anggur, itu hanyalah ekspresi kimia yang dipahami secara lebih canggih.
Berlin menilai bahwa strategi ini justru melemahkan agama. Alih-alih menjaga keajaibannya, agama malah direduksi menjadi fenomena rasional. Mukjizat kehilangan daya misterinya. Iman menjadi sesuatu yang jinak, sesuai dengan hukum alam. Tetapi agama yang kehilangan misteri akan kehilangan daya tariknya. Ketika agama direduksi ke dalam kategori rasional, manusia merasa hampa, karena kebutuhan spiritual yang lebih dalam tidak terpenuhi.
Akibatnya, banyak orang pada abad ke-18 mulai mencari alternatif. Rasionalisme yang kaku membuat manusia beralih pada okultisme, mistisisme, dan bahkan sekte-sekte esoteris. Berlin menyebut bahwa justru pada abad inilah berbagai fenomena irasional berkembang: dari Masonic Lodge, Rosicrucian, hingga eksperimen magnetisme hewan Mesmer. Bahkan kalangan bangsawan terlibat dalam berbagai ritual mistik. Fakta ini memperlihatkan bahwa proyek Pencerahan gagal memenuhi kebutuhan spiritualitas manusia.
Hamann membaca krisis ini sebagai bukti bahwa agama tidak bisa direkonsiliasi dengan rasio semata. Agama hidup justru karena misteri dan transendensinya. Jika iman dijinakkan oleh sains, maka ia kehilangan kekuatannya. Kritik ini memperkuat posisi romantisisme, yang kemudian berusaha mengembalikan ruang bagi keajaiban, imajinasi, dan intuisi dalam pengalaman manusia.
Dengan demikian, krisis spiritual abad ke-18 menjadi salah satu pemicu utama lahirnya romantisisme. Rasionalisme yang menekan sisi batin manusia justru membuka jalan bagi kebangkitan dimensi irasional. Berlin ingin menunjukkan bahwa romantisisme bukanlah pelarian dari realitas, melainkan reaksi terhadap kegagalan proyek Pencerahan yang terlalu menekankan akal dan mengabaikan jiwa.
Pada titik ini, kita melihat bagaimana romantisisme menyelamatkan manusia dari kekeringan intelektual. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk yang membutuhkan makna, misteri, dan kedalaman spiritual. Abad ke-18 dengan segala klaim rasionalitasnya gagal memenuhi kebutuhan ini, dan dari kegagalan itulah lahir sebuah revolusi baru dalam pemikiran.
Lahirnya Gelombang Anti-Rasionalisme
Abad ke-18 sering digambarkan sebagai sebuah era kejayaan harmoni intelektual. Tetapi Berlin menekankan bahwa di balik citra elegan itu, terdapat dinamika yang justru menunjukkan keterpecahan. Ia menulis bahwa ketika rasionalisme mencapai puncaknya, maka muncul pula dorongan menuju irasionalisme. Manusia, kata Berlin, selalu mencari keseimbangan. Bila akal terlalu dominan, maka hati mencari kompensasi. Dengan demikian, muncul berbagai sekte, kultus, dan aliran esoteris yang berupaya memenuhi kebutuhan spiritualitas yang tak lagi bisa dipenuhi oleh agama rasional.
Fenomena ini terlihat jelas dalam meluasnya praktik okultisme dan pseudoscience. Pada abad ke-18, Eropa dibanjiri eksperimen yang menggabungkan sains dengan mistik. Nama-nama seperti Franz Mesmer, dengan teorinya tentang magnetisme hewan, atau Cagliostro dengan praktik ritual rahasia, menjadi populer. Bahkan kalangan elit ikut serta. Para bangsawan, bahkan raja-raja, tertarik untuk mencoba peruntungan dalam eksperimen gaib. Fakta ini menunjukkan bahwa di balik penampilan rasional, Eropa masih haus akan misteri dan keajaiban.
Berlin menegaskan bahwa gerakan-gerakan irasional ini bukan sekadar penyimpangan, melainkan respons struktural terhadap proyek Pencerahan. Rasionalisme yang terlalu kaku justru memunculkan reaksi berupa kerinduan akan pengalaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dengan kata lain, ketika sains menutup pintu bagi misteri, manusia akan mencarinya lewat pintu lain. Gelombang anti-rasionalisme ini adalah bentuk pemberontakan bawah sadar terhadap dominasi akal.
Namun, Berlin tidak berhenti pada fenomena eksoteris ini. Ia menunjukkan bahwa ada pula versi lebih intelektual dari anti-rasionalisme. Tokoh seperti Lavater, dengan teorinya tentang Physiognomik, mencoba membaca karakter manusia lewat bentuk wajah. Ia meyakini adanya kesatuan antara aspek fisik dan spiritual yang tak bisa dijelaskan oleh sains mekanistik. Meski tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gagasan ini mencerminkan kerinduan untuk melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, bukan sekadar objek analisis laboratorium.
Hamann hadir sebagai figur yang menyalurkan kegelisahan ini dalam bentuk yang lebih filosofis. Ia tidak sekadar menolak sains, tetapi menantangnya dari level epistemologis. Baginya, sains hanyalah satu bahasa, dan bukan bahasa tertinggi. Bahasa kehidupan sejati adalah mitos, simbol, dan seni. Di sinilah Hamann berbeda dari para eksperimentalis gaib: ia memberi fondasi intelektual bagi apa yang kemudian berkembang menjadi romantisisme.
Gelombang anti-rasionalisme abad ke-18, baik dalam bentuk mistik populer maupun dalam refleksi intelektual seperti Hamann, menjadi bukti bahwa proyek Pencerahan tidak sepenuhnya berhasil. Justru di saat sains mencapai kemenangan, muncul tanda-tanda perlawanan. Romantisisme lahir bukan di luar zaman Pencerahan, tetapi dari rahimnya sendiri, sebagai anak yang memberontak terhadap orang tuanya.
Hamann dan Doktrin Anti-Ilmiah
Berlin menggambarkan Hamann sebagai sosok yang menolak gagasan bahwa alam semesta bisa dipahami sepenuhnya dengan kalkulasi matematis. Menurut Hamann, klaim semacam itu justru menunjukkan kesombongan manusia. Ia menegaskan bahwa Tuhan bukanlah seorang insinyur kosmik yang tunduk pada hukum mekanik, melainkan sumber kehidupan yang tak terjangkau oleh logika manusia. Dengan kata lain, Hamann melihat sains bukan sebagai musuh, tetapi sebagai ancaman jika ia mengklaim mampu menjelaskan segalanya.
Doktrin Hamann menekankan bahwa ada dimensi kehidupan yang tak dapat dijangkau oleh rasio. Ia melihat Pencerahan sebagai upaya memaksa Tuhan masuk ke dalam kotak logika manusia. Bagi Hamann, ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Sebab, ketika manusia yakin bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan oleh sains, maka hilanglah rasa kagum, misteri, dan iman. Ia menyebut bahwa iman bukanlah soal geometri atau matematika, melainkan soal puisi. Iman adalah pengalaman yang tak bisa direduksi ke dalam proposisi rasional.
Berlin menekankan bahwa dalam doktrin Hamann, ada semacam protes teologis yang mendalam. Hamann menolak konsep bahwa sejarah manusia hanyalah kumpulan fakta empiris. Sebaliknya, ia melihat sejarah sebagai wahana di mana Tuhan berbicara kepada manusia. Setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki makna mistis. Pandangan ini bertentangan dengan filsafat sejarah ala Voltaire atau Gibbon yang berusaha mengungkap hukum universal dari proses sejarah. Hamann menegaskan bahwa sejarah adalah komunikasi Ilahi, bukan laboratorium analisis.
Selain itu, Hamann juga menolak gagasan bahwa pengetahuan dapat bersifat final. Ia menganggap klaim Kant bahwa sains dapat mencapai batas pengetahuan sebagai bentuk kesombongan intelektual. Bagi Hamann, pengetahuan manusia selalu terbatas. Ada ruang misteri yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Justru di ruang itulah iman dan seni berakar. Jika manusia berhenti di sains, maka hidup menjadi kering dan dangkal.
Berlin melihat Hamann sebagai figur yang menghidupkan kembali dimensi religius di tengah dominasi sains. Ia menolak kompromi Wolff yang berusaha menyesuaikan agama dengan sains. Baginya, agama tidak boleh dijinakkan. Iman harus tetap misterius, transenden, dan tidak tunduk pada logika. Inilah doktrin anti-ilmiah Hamann: bukan dalam arti menolak sains secara total, tetapi menolak klaim sains sebagai penguasa tunggal realitas.
Dari sinilah Hamann menjadi inspirasi utama bagi romantisisme. Ia mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, bahwa misteri adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa simbol, mitos, serta seni lebih dekat dengan kebenaran daripada formula ilmiah. Dengan cara ini, Hamann menanamkan benih yang kemudian tumbuh menjadi revolusi romantik.
Mitos sebagai Bahasa Ilahi
Inti dari ajaran Hamann, sebagaimana dicatat Berlin, terletak pada pandangannya tentang mitos. Ia percaya bahwa mitos bukan sekadar dongeng atau kebohongan, melainkan medium di mana manusia berhubungan dengan yang transenden. Mitos adalah bahasa yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, karena ia mampu mengekspresikan misteri yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasional.
Hamann menilai bahwa kata-kata rasional cenderung memotong realitas menjadi bagian-bagian kecil yang kering. Analisis logis, meskipun berguna, justru menghancurkan kesatuan pengalaman manusia. Sebaliknya, mitos mempertahankan kontinuitas antara hidup, alam, dan Tuhan. Mitos bukan hanya cerita, melainkan simbol hidup yang menghubungkan manusia dengan misteri eksistensi. Dengan mitos, manusia tidak sekadar berpikir, tetapi juga merasakan dan mengalami.
Berlin menekankan bahwa bagi Hamann, mitos adalah cara Tuhan berbicara kepada manusia melalui sejarah. Setiap peristiwa, bahkan yang paling biasa, memiliki makna simbolis yang dapat ditafsirkan secara mitis. Sejarah bukanlah sekadar urutan sebab-akibat, melainkan drama kosmis di mana Tuhan dan manusia berinteraksi. Inilah yang membuat Hamann berbeda dari sejarawan Pencerahan. Ia tidak mencari hukum universal sejarah, tetapi makna tersembunyi dalam setiap peristiwa.
Penting pula dicatat bahwa Hamann melihat seni sebagai bentuk tertinggi dari pengetahuan. Jika sains berbicara dengan angka dan proposisi, maka seni berbicara dengan simbol dan imajinasi. Seni, bagi Hamann, lebih dekat kepada kebenaran karena mampu menangkap aspek kehidupan yang tak bisa dijangkau oleh sains. Romantisisme kemudian mewarisi gagasan ini, menjadikan seni dan imajinasi sebagai pusat pengalaman manusia.
Hamann juga memandang mitos sebagai cara untuk melawan hegemoni bahasa rasional. Bahasa rasional terlalu miskin untuk menampung kompleksitas hidup. Mitos, sebaliknya, penuh dengan simbol, ironi, dan lapisan makna. Dengan mitos, manusia bisa merayakan ketidakpastian dan misteri, alih-alih memaksanya menjadi kepastian logis. Inilah yang membuat Hamann begitu berpengaruh bagi generasi romantik setelahnya.
Dengan demikian, mitos dalam pemikiran Hamann bukanlah sekadar cerita kuno, tetapi bahasa ilahi. Ia adalah cara untuk menjaga hubungan manusia dengan misteri, dengan alam, dan dengan Tuhan. Berlin menegaskan bahwa inilah inti dari doktrin romantik: penolakan terhadap reduksi rasional, dan perayaan terhadap simbol, mitos, dan seni sebagai medium kebenaran.
Romantisisme sebagai Pemberontakan Intelektual
Dari Hamann, romantisisme berkembang menjadi gerakan besar yang melampaui batas Jerman. Berlin mencatat bahwa gagasan-gagasan ini menyebar ke Prancis, Inggris, bahkan melahirkan revolusi dalam seni, sastra, dan filsafat. William Blake, misalnya, menjadi eksponen penting di Inggris. Ia melihat Locke dan Newton sebagai musuh besar yang membunuh roh dengan memotong realitas menjadi bagian-bagian matematis. Blake, seperti Hamann, percaya bahwa realitas adalah kesatuan hidup yang tidak bisa direduksi.
Romantisisme adalah pemberontakan terhadap reduksi. Ia menolak universalisme rasional dan menegaskan keunikan individual. Setiap individu, setiap bangsa, setiap peristiwa, memiliki nilai unik yang tak bisa digeneralisasi. Inilah mengapa romantisisme sering dikaitkan dengan munculnya nasionalisme modern. Dari penekanan pada keunikan individu, berkembang pula penekanan pada keunikan bangsa. Semua ini berakar pada penolakan terhadap abstraksi universal Pencerahan.
Berlin menegaskan bahwa romantisisme adalah revolusi intelektual yang sebanding dengan Pencerahan itu sendiri. Jika Pencerahan menegaskan bahwa kebenaran itu satu dan universal, romantisisme menyatakan bahwa kebenaran itu plural dan kontekstual. Jika Pencerahan percaya pada hukum-hukum universal, romantisisme menekankan pengalaman subjektif. Inilah pergeseran yang membuat romantisisme menjadi fondasi banyak pemikiran modern, termasuk eksistensialisme dan relativisme budaya.
Pemberontakan romantik juga menyentuh politik. Jika negara Pencerahan menekankan rasionalitas hukum dan kontrak sosial, maka negara romantik menekankan ekspresi jiwa rakyat. Dari sinilah lahir konsep Volksgeist, semangat bangsa, yang kemudian mengilhami gerakan nasionalis di seluruh Eropa. Romantisisme, dengan demikian, bukan hanya gerakan estetis, tetapi juga politik.
Berlin menunjukkan bahwa romantisisme adalah sumber dari banyak kontradiksi modern. Ia melahirkan kebebasan individu, tetapi juga nasionalisme ekstrem. Ia melahirkan seni yang mendalam, tetapi juga relativisme yang berlebihan. Namun, semua itu menunjukkan bahwa romantisisme bukanlah episode kecil, melainkan fondasi besar dari dunia modern.
Dengan demikian, romantisisme harus dipahami sebagai pemberontakan intelektual yang mengubah paradigma. Ia bukan sekadar mode, melainkan revolusi filosofis yang menggeser pusat gravitasi dari akal ke pengalaman, dari hukum universal ke keunikan individual, dari rasional ke irasional. Dan semua ini, menurut Berlin, berakar pada pemberontakan Hamann terhadap Pencerahan.
Kesimpulan
Isaiah Berlin, melalui telaahnya tentang Hamann, memperlihatkan bahwa romantisisme lahir sebagai respons terhadap keterbatasan Pencerahan. Abad ke-18, meski penuh dengan kemenangan sains, ternyata juga menyimpan krisis spiritual yang mendalam. Rasionalisme yang terlalu menekan justru memicu pencarian akan misteri, mitos, dan transendensi. Hamann menjadi sosok kunci yang pertama kali menolak reduksi agama dan sejarah ke dalam kalkulasi rasional, dan dari penolakannya lahirlah semangat romantik.
Esai ini menunjukkan bahwa romantisisme bukan sekadar estetika, melainkan revolusi intelektual yang menentang klaim sains sebagai penguasa tunggal realitas. Dengan menegaskan peran mitos, simbol, dan seni, romantisisme membuka ruang bagi pengalaman manusia yang lebih utuh. Ia menolak universalisme, dan merayakan pluralitas. Ia menolak keteraturan kaku, dan merayakan keindahan ketidakteraturan.
Berlin melihat bahwa romantisisme memiliki dampak luas, tidak hanya dalam seni dan sastra, tetapi juga dalam filsafat, politik, dan bahkan agama. Dari gerakan ini lahir nasionalisme modern, eksistensialisme, dan relativisme budaya. Dengan kata lain, romantisisme adalah fondasi bagi banyak aspek dunia modern yang kita kenal hari ini.
Namun, Berlin juga menyadari bahwa romantisisme menyimpan kontradiksi. Ia melahirkan kebebasan individu, tetapi juga kolektivitas nasional yang ekstrem. Ia melahirkan seni mendalam, tetapi juga relativisme yang melemahkan klaim kebenaran. Meski demikian, semua kontradiksi itu adalah bagian dari warisan yang tak terhindarkan. Romantisisme adalah revolusi yang membebaskan, tetapi juga mengguncang dasar-dasar stabilitas intelektual.
Dari Hamann, kita belajar bahwa ada dimensi kehidupan yang tak bisa dijinakkan oleh akal. Misteri, mitos, dan seni adalah bagian penting dari pengalaman manusia. Berlin mengingatkan kita bahwa proyek Pencerahan, dengan segala kejayaannya, tidak pernah bisa mematikan kebutuhan ini. Justru, dari kegagalannya lahir romantisisme, yang menjadi pengingat bahwa manusia lebih dari sekadar makhluk rasional.
Dengan demikian, romantisisme bukanlah sekadar episode sejarah, tetapi bab besar dalam perjalanan intelektual manusia. Ia adalah suara perlawanan yang menolak reduksi kehidupan menjadi formula kaku. Dan melalui Hamann, Berlin menunjukkan bahwa akar romantisisme ada pada keberanian untuk mengatakan bahwa ada hal-hal yang tak dapat dijelaskan, bahwa misteri adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan bahwa justru di dalam misteri itulah manusia menemukan maknanya yang terdalam.


Leave a Reply