Pendahuluan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia telah mengalami evolusi paradigma keilmuan yang signifikan sejak pendiriannya. Paradigma keilmuan yang dimaksud merujuk pada kerangka berpikir dan pendekatan dasar dalam mengkaji ilmu pengetahuan di lingkungan PTKIN, khususnya bagaimana ilmu agama Islam berinteraksi dengan ilmu-ilmu modern. Selama beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran dari pendekatan normatif-teologis tradisional menuju upaya integrasi ilmu agama dengan sains modern dan ilmu sosial-humaniora. Hal ini ditandai oleh lahirnya sejumlah gagasan dan paradigma baru – antara lain Islamisasi Ilmu, Integrasi Ilmu, Interkoneksi Ilmu, hingga yang lebih mutakhir Frikatifisasi Ilmu. Masing-masing paradigma ini muncul sebagai respons atas tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat, serta membawa konsepsi berbeda mengenai hubungan antara Islam dan sains.
Sejarah perkembangan paradigma keilmuan PTKIN terkait erat dengan transformasi institusional dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri)[1]. Transformasi ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan mencerminkan pergeseran visi: dari institusi yang semula berfokus pada studi agama secara tradisional, menjadi universitas komprehensif yang mencakup berbagai disiplin ilmu dalam perspektif Islami[2]. Pergeseran tersebut menuntut rekonstruksi kerangka konseptual keilmuan: ilmu agama tidak lagi cukup dipelajari secara dogmatis dalam ruang terisolasi, melainkan harus berdialog dengan ilmu sosial, humaniora, sains alam, dan teknologi. Oleh karena itu, pemetaan dan analisis terhadap paradigma-paradigma keilmuan yang berkembang di PTKIN menjadi penting untuk memahami arah masa depan pendidikan tinggi Islam.
Makalah ini akan membahas secara komprehensif empat paradigma keilmuan utama di PTKIN [3], yaitu: Paradigma Islamisasi Ilmu, Integrasi Ilmu, Interkoneksi Ilmu, dan Frikatifisasi Ilmu. Mula-mula akan dijelaskan latar belakang historis dan landasan teoretis munculnya paradigma-paradigma tersebut. Kemudian, tiap paradigma akan diuraikan secara mendalam mencakup aspek ontologi (pandangan tentang realitas), epistemologi (sumber dan metode memperoleh ilmu), aksiologi (tujuan dan nilai guna ilmu), serta simbolisme ilmu yang diusung. Pembahasan juga akan menyertakan analisis kritis terhadap keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan, disertai referensi pada pemikiran tokoh kunci terkait. Selanjutnya, akan dilakukan komparasi antar paradigma tersebut untuk menyoroti persamaan, perbedaan, dan kemungkinan saling melengkapi. Terakhir, makalah ini ditutup dengan refleksi mengenai arah masa depan pengembangan keilmuan di PTKIN, menimbang implikasi praktis dan filosofis dari setiap paradigma bagi pendidikan tinggi Islam di era kontemporer.
Landasan Teori dan Latar Belakang
Paradigma Keilmuan Tradisional di PTKI
Pada masa awal berdirinya PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) – yang dahulu berbentuk IAIN – pendekatan keilmuan yang dominan bersifat normatif-teologis. Studi Islam difokuskan pada ilmu-ilmu agama klasik (al-‘ulūm al-naqliyyah) seperti fikih, tafsir, hadis, kalam, dengan penekanan pada pendalaman teks dan doktrin agama untuk memperteguh akidah dan syariat. Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam pada periode tersebut antara lain: (1) menyiapkan guru-guru agama di madrasah, (2) meniru tradisi pendidikan Islam di Timur Tengah, dan (3) mencetak lulusan untuk mengisi jabatan di lingkungan Kementerian Agama[4]. Orientasi yang pragmatis ini menyebabkan kurikulum PTKI klasik didesain untuk melahirkan ahli-ahli agama yang siap mengajar atau menjadi birokrat agama, daripada menghasilkan ilmuwan peneliti.
Pendekatan normatif-teologis tersebut ditandai dengan karakteristik doktrinal – ilmu diperlakukan sebagai kumpulan kebenaran sakral yang harus diafirmasi, bukan sebagai sesuatu yang terbuka untuk diuji secara kritis. Proses produksi keilmuan cenderung berpusat pada penafsiran teks wahyu dan tradisi, dengan minim dialog lintas keilmuan[5]. Interaksi dengan disiplin non-keagamaan sangat terbatas; metode ilmu sosial atau sains modern nyaris tidak masuk ke dalam kurikulum PTKI klasik[6]. Kerangka metodologis yang digunakan bersifat internal agama semata, misalnya ushul fikih untuk hukum atau ilmu tafsir untuk studi Al-Qur’an, tanpa melibatkan teori sosial, antropologi, sosiologi, atau pendekatan empiris lainnya. Ancaman “orientalisme” – yakni kajian Islam oleh sarjana Barat – sering dipandang dengan kecurigaan, dianggap dapat mengganggu sakralitas ilmu-ilmu Islam[7]. Alhasil, paradigma keilmuan yang terbentuk relatif tertutup dan defensif; penekanan utamanya adalah memperteguh nilai-nilai agama dan melindungi kemurnian ajaran dari pengaruh luar, ketimbang menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara interdisipliner.
Dampak dari paradigma awal ini adalah kuatnya sakralisasi ilmu. Ilmu agama dipandang sebagai sesuatu yang suci dan mandiri, terlepas dari konteks sosial. Sisi positifnya, pendekatan ini berhasil menanamkan landasan akidah-akhlak yang kokoh pada lulusan dan melestarikan tradisi intelektual Islam klasik. Namun, sisi negatifnya, terjadi jurang antara studi keislaman dan realitas masyarakat yang dinamis. Respon keagamaan terhadap masalah masyarakat sering bersifat normatif dan kurang berbasis penelitian empiris[8]. Dengan kata lain, ilmu yang dihasilkan lebih berorientasi inward looking (ke dalam, untuk komunitas sendiri) dan kurang solutif bagi tantangan sosial-budaya yang berkembang di luar.
Transformasi: Masuknya Pendekatan Sosial-Humaniora
Memasuki dekade 1970-an dan terutama 1980-an, mulai muncul kesadaran di kalangan sarjana Muslim Indonesia akan perlunya transformasi studi Islam di PTKI. Beberapa faktor pendorong transformasi ini antara lain: meningkatnya interaksi intelektual dengan dunia Barat, kebutuhan menjawab persoalan bangsa yang kompleks, dan dorongan internal untuk memodernisasi pendidikan Islam. Sarjana-sarjana Islam Indonesia generasi baru banyak yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Barat atau berkenalan dengan literatur ilmu sosial modern. Mereka mulai mengkritisi pendekatan lama yang murni normatif-doktrinal dan mendorong pembacaan Islam dalam konteks sosial. Salah satu tonggak penting adalah terbitnya jurnal-jurnal akademik progresif seperti Ulumul Qur’an pada akhir 1980-an yang mencoba mengawinkan studi teks dengan analisis sosial[9]. Jaringan guru dan murid pun meluas, tidak hanya terikat pada pesantren dan Timur Tengah, tetapi juga melibatkan pembimbing dan kolega dari disiplin sekuler di dalam maupun luar negeri[10]. Fenomena ini menandai perkenalan studi Islam dengan ilmu sosial secara lebih intens.
Selain itu, para Indonesianis (sarjana Barat pencinta kajian Indonesia) mulai menaruh minat pada khazanah Islam Nusantara[11]. Kajian mereka memberi perspektif baru tentang Islam Indonesia sebagai objek penelitian ilmiah yang kaya, misalnya dalam bidang antropologi agama, politik Islam, dan sejarah sosial. Dampaknya dua arah: di satu sisi, publikasi mereka mengharumkan studi Islam Indonesia di kancah global (pengaruh Barat, transformasi publikasi, dampak paradigmatis keilmuan[12]); di sisi lain, kalangan cendekiawan Muslim lokal merasa tertantang untuk mengkaji sendiri masyarakat Muslim Nusantara menggunakan alat analisis modern agar tidak tertinggal. Maka, pendekatan ilmu sosial-humaniora mulai diadopsi. Misalnya, studi tafsir dan hadis dikontekstualisasikan dengan pendekatan historis dan kritik teks; ilmu fikih mulai disentuh analisis sosiologis; studi akidah dan pemikiran Islam merambah ranah filsafat kontemporer dan hermeneutika.
Pionir-pionir seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, dan lainnya mendorong “dialog” antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Hasilnya, terjadi silaturahmi keilmuan Islam dan Barat di lingkungan PTAI[13]. Kurikulum IAIN mengalami revisi untuk memasukkan matakuliah umum dan metode penelitian empiris. Mahasiswa didorong menulis skripsi yang tidak hanya normatif tetapi juga analitis-kritis. Tren ini berlanjut dan menguat seiring perubahan bentuk IAIN menjadi UIN di awal 2000-an. Integrasi keilmuan menjadi semacam motto di berbagai UIN baru. Setiap UIN berlomba menawarkan model integrasi Islam dan sains, meskipun dengan konsep dan istilah beragam[14][15].
Namun, transformasi ini bukan tanpa resistensi. Sebagian kalangan tradisional mengkhawatirkan “sekularisasi” ilmu di PTKI. Tuduhan bahwa PTAI menjadi “sarang orientalis” sempat mencuat[16] – artinya kampus Islam dikhawatirkan justru menelurkan pemikiran yang terlalu pro-Barat dan kritis terhadap tradisi, mirip tudingan terhadap para orientalis. Meski demikian, arus perubahan tak terbendung karena tuntutan zaman: umat Islam memerlukan solusi atas problem nyata (kemiskinan, ketidakadilan, krisis moral, dsb.), yang tak cukup dijawab dengan doktrin normatif belaka. Pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ajaran Islam dengan sains modern dianggap perlu untuk menjadikan Islam “rahmatan lil ‘alamin” secara konkrit.
Dalam konteks inilah muncul berbagai gagasan paradigma keilmuan baru yang mencoba merumuskan hubungan ideal antara ilmu agama dan ilmu modern. Empat paradigma yang menonjol – Islamisasi Ilmu, Integrasi Ilmu, Interkoneksi Ilmu, dan Frikatifisasi Ilmu – dapat dipahami sebagai spektrum pendekatan dari yang paling menekankan Islam-centric hingga yang paling spirit-centric. Islamisasi ilmu menekankan pentingnya menjadikan Islam sebagai inti dan penyaring segala ilmu. Integrasi ilmu berusaha memadukan ilmu agama dan umum dalam kerangka tawhid yang koheren. Interkoneksi ilmu menekankan keterhubungan multidisipliner dan multikultural dengan etika religius sebagai pengarah. Adapun frikatifisasi ilmu merupakan tawaran terkini yang melihat ilmu bukan sekadar konsep akademik, melainkan getaran ruhani yang memancar dan menghidupkan jiwa. Berikut akan diuraikan secara rinci masing-masing paradigma tersebut.
Paradigma Islamisasi Ilmu
Konsep dan Latar Belakang
Paradigma Islamisasi Ilmu merupakan gerakan intelektual yang muncul sejak akhir 1970-an, dipelopori antara lain oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Isma’il Raji al-Faruqi[17]. Inti konsep ini adalah mengembalikan seluruh ilmu pengetahuan pada kerangka tauhid dan nilai-nilai Islam, dengan cara membersihkannya dari unsur-unsur sekuler Barat yang dianggap merusak. Para pendukung Islamisasi Ilmu berpandangan bahwa ilmu modern yang berkembang di Barat sarat dengan bias filsafat sekularisme, materialisme, dan dualisme yang tidak sejalan dengan worldview Islam. Oleh karena itu, tugas cendekiawan Muslim adalah melakukan reformulasi ulang segala cabang ilmu (sosial, alam, humaniora, teknologi) agar selaras dengan akidah dan syariat.
Menurut definisi ringkasnya, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengintegrasikan ajaran Islam dengan disiplin-disiplin modern, sehingga semua pengetahuan dan metode ilmiah konsisten dengan prinsip Islam[18]. Pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran hakiki bersumber dari wahyu Ilahi; maka ilmu apapun harus berakar pada wahyu atau paling tidak tidak bertentangan dengannya. Al-Faruqi, dalam “Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan” (1982), mengajukan langkah-langkah sistematis untuk melakukan Islamisasi di berbagai bidang[19][20]. Ia menegaskan perlunya menguasai disiplin modern secara kritis, memahami khazanah ilmu Islam klasik, lalu melakukan sintesis kreatif: menyaring teori-teori Barat, membuang unsur yang dianggap tidak islami, dan memasukkan konsep-konsep Islam (seperti tauhid, khilafah, keadilan) ke dalam disiplin tersebut[20]. Al-Faruqi menyebut sekularisasi ilmu di dunia Muslim sebagai “penyakit umat (malaise of the ummah)”, dan mengkritik ketergantungan muslim pada metodologi Barat yang kerap melanggar etika Islam[21]. Ia mendorong revitalisasi ijtihad dan penerapan metodologi ilmiah dalam batasan nilai Islam, sehingga umat Islam bisa unggul dalam sains tanpa kehilangan jati diri[22].
Syed M. Naquib al-Attas dari Malaysia memberikan dasar filosofis yang kuat bagi Islamisasi Ilmu. Al-Attas menekankan konsep tauhid dan adab (etika ilmu) sebagai kunci. Menurutnya, Islamisasi pada hakikatnya adalah dewesternisasi ilmu: melepaskan ilmu dari worldview Barat sekuler dan menanamkan kembali nilai-nilai dan konsep Islami ke dalamnya[23]. Ia menyebut proses ini sebagai penjernihan ilmu dari unsur yang tidak relevan dengan Islam dan mengisinya dengan elemen Quranik. Sebagai contoh, dalam pandangan al-Attas, konsep-konsep dasar seperti pandangan tentang realitas, kebenaran, tujuan hidup, harus diarahkan ulang sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, misalnya, teori evolusi Darwin, filsafat positivisme, atau materialisme historis perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan aqidah Islam. Output akhir yang diharapkan adalah disiplin ilmu “versi Islami” – misalnya Psikologi Islami, Sosiologi Islami, Ekonomi Islami – yang bebas dari bias ideologi Barat dan dijiwai nilai wahyu[24].
Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Paradigma Islamisasi
Secara ontologis, paradigma Islamisasi berpijak pada prinsip keesaan Tuhan (tauhid) sebagai fondasi realitas. Realitas alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang teratur dan bermakna. Tidak ada pemisahan antara yang sekuler dan yang sakral, karena semua eksistensi berada dalam kerangka tauhid[25]. Ontologi Islam menolak dikotomi fakta vs nilai ala Barat; alam materiil maupun fenomena sosial harus dibaca sebagai tanda-tanda (ayat) kebesaran Allah. Dengan kata lain, dunia empiris dan dunia spiritual merupakan satu kesatuan tunduk pada kehendak Ilahi. Pandangan ini melahirkan asumsi bahwa ilmu tidak netral secara nilai – melainkan harus terikat dengan tujuan penciptaan.
Dari segi epistemologi, sumber ilmu utama dalam paradigma Islamisasi adalah wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah) disertai akal yang tunduk pada wahyu. Pengetahuan diperoleh melalui studi mendalam atas nash dengan metode yang benar (ulum al-Quran, ulum al-hadis, fikih, dll.) serta melalui penalaran rasional yang beradab[26]. Keterlibatan akal tetap penting, tetapi akal harus dibimbing oleh adab Islam dan etika tauhid. Dalam pandangan ini, Allah adalah sumber segala ilmu; ilmu agama (naqliyah) dan ilmu empiris (aqliyah) pada hakikatnya terintegrasi dalam satu kesatuan yang bersumber dari-Nya[27]. Segala sesuatu yang benar pada akhirnya akan sejalan dengan wahyu, karena kebenaran ilmiah tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran Ilahi. Epistemologi Islamisasi cenderung menaruh kecurigaan pada metodologi Barat modern yang dianggap memisahkan ilmu dari nilai agama. Para pendukung Islamisasi mengkritik epistemologi Barat yang positivistik dan sekular, karena menyingkirkan peran Tuhan dalam proses ilmiah. Sebaliknya, mereka menganjurkan rekonstruksi epistemologi berdasarkan kerangka tauhid dan warisan intelektual Islam klasik[28]. Proses “islamisasi” sering melibatkan menguji teori-teori modern di bidang apapun (misal ekonomi, sosiologi, fisika) dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan hadis: apa yang sesuai dipertahankan, yang bertentangan ditolak atau direvisi.
Dari aspek aksiologi (nilai dan tujuan ilmu), Islamisasi Ilmu memiliki orientasi keumatan dan keakhiratan. Ilmu digunakan untuk membentuk manusia Islami dan masyarakat Qur’ani[29]. Maksudnya, ilmu harus berkontribusi pada pembinaan akhlak dan iman individu, serta tegaknya tatanan sosial yang memenuhi prinsip Islam. Tujuan keilmuan bukan sekadar pengetahuan demi pengetahuan, apalagi demi keuntungan materi, melainkan sarana ibadah dan pengabdian. Dalam kerangka ini, ilmu yang benar akan mendekatkan manusia kepada Allah dan memperkokoh peradaban Islam. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan ilmu diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip Islam dan akhlakul karimah[30]. Paradigma Islamisasi dengan tegas menolak dikotomi antara ilmu dan agama; ilmu bukan untuk dipraktikkan terpisah dari iman, tetapi justru untuk mewujudkan iman dalam tindakan (amal saleh). Secara praktis, ilmu di PTKIN yang diislamkan diharapkan melahirkan sarjana yang berkepribadian ulul albab – cerdas secara intelektual sekaligus taat secara spiritual.
Simbolisme dan Model Ilmu
Paradigma Islamisasi sering digambarkan melalui metafora pohon ilmu. Pohon ilmu ini memiliki akar berupa akidah, batang berupa syariah (hukum dan tatanan), dan buah berupa akhlak serta ilmu terapan[31]. Metafora ini melambangkan struktur pengetahuan yang berakar kuat pada keimanan (tauhid) dan syariat, sehingga menghasilkan buah kemajuan yang tetap dalam koridor etika. Syed Naquib al-Attas mengajukan kerangka serupa bahwa ontologi ilmu integratif: ontologi berakar pada akidah (tauhid), epistemologi bersandar pada syariat (metode keilmuan islami), dan aksiologi bertujuan pembentukan akhlak[32]. Dengan kata lain, tauhid adalah asas, syariat/akal sehat adalah alat, dan akhlak adalah tujuan akhir ilmu. Pohon ilmu juga mencerminkan konsep “dari tauhid kembali ke tauhid” – artinya seluruh proses belajar dimulai dengan mengakui keesaan Allah dan diakhiri dengan syukur dan pemahaman yang lebih mendalam tentang-Nya[33].
Contoh implementasi metafora pohon ilmu dapat dilihat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadikannya paradigma integrasi mereka. Akar melambangkan dasar-dasar ilmu keislaman (aqidah, bahasa Arab, dll. sebagai pondasi), batang melambangkan disiplin ilmu umum yang diperkokoh nilai agama, dan buah adalah lulusan berakhlak yang memberi manfaat bagi masyarakat[34][35]. Walaupun UIN Malang mengistilahkannya sebagai paradigma integrasi, konsep ini sejalan dengan semangat Islamisasi: menegaskan segala cabang pengetahuan bertumpu pada akar tauhid.
Peran Pendidik dan Implementasi
Dalam paradigma Islamisasi, peran pendidik (dosen, ustaz) sangat sentral sebagai penjaga dan pewaris nilai-nilai Islam. Pendidik dilihat sebagai pemelihara ortodoksi dan penyalur ilmu-ilmu wahyu kepada mahasiswa[36]. Mereka bukan sekadar pengajar materi, tetapi juga agen yang mentransmisikan tradisi keilmuan Islam dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, dosen di PTKIN harus memiliki integritas keislaman tinggi, menguasai ilmu agama mendalam, serta berwibawa secara moral. Transfer ilmu dipandang sejalan dengan transfer nilai: ilmu yang disampaikan harus selalu dibingkai dalam adab dan hikmah agar mahasiswa menyerap semangat keislaman bersama informasi ilmiah.
Orientasi pendidikan dalam kerangka ini adalah menjadikan perguruan tinggi Islam sebagai wadah Islamisasi total. Artinya, kampus bukan hanya tempat belajar ilmu umum lalu ditambal dengan mata kuliah agama, melainkan lingkungan yang secara menyeluruh menanamkan pandangan hidup Islam pada peserta didik[37]. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga setiap disiplin diislamkan, dan aktivitas akademik (perpustakaan, laboratorium, diskusi) syarat dengan budaya Islami.
Implementasi Islamisasi ilmu di berbagai kampus Islam biasanya meliputi pembuatan kurikulum integratif (misal setiap mata kuliah umum diberi perspektif Islam), pendirian pusat studi Islamisasi, penerbitan buku ajar “islami”, hingga kebijakan kampus bernuansa syariah (misal dress code muslim, agenda keagamaan rutin, dsb.). Keberhasilan pendekatan ini ditandai jika lulusan PTKIN mampu menguasai disiplin modern tanpa tercabut dari identitas keislaman, serta menjadi agen dakwah ilmu di tengah masyarakat.
Analisis Kritis Paradigma Islamisasi
Paradigma Islamisasi Ilmu telah memberikan kontribusi penting dengan mengingatkan akan poros tauhid dalam menuntut ilmu. Gagasan ini memastikan bahwa umat Islam tidak kehilangan jatidiri di tengah arus sains modern[38]. Banyak institusi pendidikan Islam di dunia, terutama di Malaysia dan beberapa di Indonesia, terinspirasi untuk mendesain ulang visi akademiknya agar sejalan dengan misi keislaman. Namun, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah kritik:
- Terlalu normatif dan idealistik, sehingga sulit dioperasionalisasikan dalam sains kontemporer yang highly specialized. Kritik ini menyebut bahwa jargon Islamisasi kerap berakhir pada tataran retoris, tetapi implementasinya di laboratorium atau riset empiris tidak jelas. Contohnya, mengislamkan fisika kuantum atau biologi molekuler bukan perkara mudah – seringkali terjebak pada menempelkan ayat pada teori yang sudah ada, alih-alih melahirkan teori baru[39]. Akibatnya, hasil nyata Islamisasi di bidang sains keras masih minim.
- Risiko bias dan tertutup: Beberapa pengkritik, termasuk dari kalangan Muslim sendiri, khawatir Islamisasi justru dapat mempersempit cakrawala keilmuan. Dengan memfilter ilmu Barat secara keras, dikhawatirkan umat Islam menutup diri dari manfaat sains modern. Ada kemungkinan munculnya anti-intelektualisme terselubung – misalnya menolak teori ilmiah yang sudah terbukti hanya karena dianggap “dari Barat”. Ini bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Muslim jika tidak hati-hati[38].
- Mengaburkan batas agama dan sains: Kritikus lain menyoroti bahwa mencampuradukkan metodologi sains dengan doktrin agama bisa menimbulkan problem filosofis. Sains berkembang dengan metode empiris yang bisa diverifikasi, sedangkan agama berdasar keyakinan terhadap wahyu. Jika tidak dirumuskan dengan cermat, program Islamisasi bisa dituduh mempolitisasi agama dalam sains atau mensakralkan ilmu secara berlebihan[38]. Hal ini bisa membatasi kebebasan akademik dan inovasi, karena ilmuwan mungkin enggan mengeksplorasi ide yang “tidak popular secara agama”.
- Keberagaman interpretasi Islam: Paradigma Islamisasi cenderung mengasumsikan satu bentuk tatanan Islam yang monolitik. Padahal, interpretasi terhadap prinsip Islam bisa beragam. Kritik muncul bahwa wacana Islamisasi terkadang didominasi kelompok tertentu dan dapat digunakan untuk menghegemoni wacana ilmu sesuai tafsiran mereka[40][41]. Contohnya, isu diskriminasi terhadap non-Muslim atau kelompok minoritas intelektual pernah dikaitkan dengan implementasi Islamisasi yang terlalu semangat di Malaysia[42]. Hal ini tentu di luar maksud asli para pencetusnya, namun potensi distorsi ini patut dicatat.
Secara keseluruhan, Islamisasi Ilmu merupakan langkah awal penting dalam upaya menyatukan iman dan ilmu. Paradigma ini memberikan basis filosofis adab dan tauhid yang kuat[43]. Kendati pelaksanaannya masih membutuhkan banyak penyesuaian, warisan pemikirannya terus berpengaruh dalam diskursus integrasi ilmu di PTKIN.
Paradigma Integrasi Ilmu
Konsep dan Latar Belakang
Paradigma Integrasi Ilmu di PTKIN lahir seiring transformasi IAIN menjadi UIN sejak awal 2000-an. Jika Islamisasi menekankan rekonsturksi ilmu secara Islamik, Integrasi ilmu lebih menekankan pada penyatuan kembali ilmu agama dan ilmu umum yang sempat terpisah dalam sejarah pendidikan Islam modern. Paradigma ini digawangi di Indonesia oleh sejumlah cendekiawan seperti Azyumardi Azra dan M. Amin Abdullah, yang secara praktis menerapkannya dalam pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta[44]. Ide integrasi juga muncul di berbagai UIN lain dengan metafora berbeda-beda (seperti “Menara Kembar” di UIN Jakarta, “Pohon Ilmu” di UIN Malang, “Jaring Laba-laba” di UIN Yogya, “Roda Ilmu” di UIN Bandung, dll.), namun esensinya serupa: menjembatani dikotomi ilmu naqli dan aqli.
Secara sederhana, integrasi ilmu berarti menyatukan pengetahuan agama dan sains dalam satu kerangka epistemologis yang utuh[45]. Berbeda dari Islamisasi yang cenderung melihat ilmu modern perlu disaring ketat, integrasi ilmu bersifat lebih inklusif: mengakui bahwa ilmu agama dan ilmu umum memiliki sumber kebenaran berbeda namun berasal dari Tuhan yang sama. Dalam Al-Qur’an, dikenal konsep ayat qauliyyah (wahyu/ firman) dan ayat kauniyyah (alam semesta)[46]. Paradigma integrasi bertolak dari premis bahwa kedua “ayat” ini harus dipadukan untuk memperoleh pemahaman utuh. Ilmu agama tanpa sains akan mandul dan tidak kontekstual; sebaliknya sains tanpa nilai agama akan buta moral. Karena itu, integrasi menawarkan “jalan tengah”: ilmuwan Muslim harus menguasai disiplin modern sekaligus mendalami khazanah Islam klasik, lalu mengawinkan keduanya dalam kegiatan akademik.
- Amin Abdullah menyebut pendekatan ini sebagai “pendekatan integratif-interkonektif”. Melalui bukunya Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (2006), ia mengajak agar studi Islam di kampus memadukan teori-teori sosial kontemporer dengan nilai-nilai tauhidik[47][48]. Ia mengkritik pendekatan lama (dikotomis atomistik) dan menggagas bangunan keilmuan integratif yang diilustrasikan sebagai jaring laba-laba[49]. Dalam jaring laba-laba keilmuan, ilmu agama berada di posisi node yang terhubung dengan ilmu sosial, ilmu alam, dan humaniora melalui benang-benang tautan etika dan kemanusiaan. Konsep Amin Abdullah sering disebut teo-antroposentrik integratif: perpaduan antara teosentrisme (berpusat pada Tuhan) dan antropo-sentrisme (berpusat pada kemanusiaan)[49]. Artinya, ilmu dikembangkan dengan kesadaran ketuhanan sekaligus kepekaan kemanusiaan. Agama memberikan orientasi etis-transenden, sementara ilmu duniawi memberikan data empiris dan analisis; keduanya harus berinteraksi konstruktif.
Sementara itu, Azyumardi Azra menekankan pentingnya “tawasuth” (moderat) dalam integrasi. Sebagai rektor UIN Jakarta, ia melihat transformasi IAIN ke UIN harus dibarengi paradigma keilmuan baru: “Integrasi ilmu dan agama: interpretasi dan aksi”[47]. UIN Jakarta mengembangkan konsep integrasi dengan lambang menara kembar: satu menara melambangkan ilmu agama, satu lagi ilmu umum, keduanya menjulang berdampingan dengan fondasi tauhid yang sama. Pesan utamanya, tidak ada pertentangan inheren antara wahyu dan akal. Konflik antara sains dan agama hanya muncul jika salah memahami keduanya. Dengan integrasi, diharap lahir ilmuwan yang menguasai sains modern tanpa kehilangan keimanan, serta ulama yang mengerti sains.
Paradigma Integrasi ilmu juga didorong oleh kebutuhan praktis PTKIN memperluas mandatnya. Saat IAIN menjadi UIN, fakultas-fakultas umum (sains, kedokteran, ekonomi, dsb.) dibuka. Agar tetap memiliki identitas Islam, UIN perlu memasukkan nilai-nilai keislaman dalam pengajaran ilmu-ilmu umum tersebut. Inilah lahan aplikasi konsep integrasi: misalnya, di kelas biologi UIN akan dibahas juga ayat-ayat Al-Qur’an tentang makhluk hidup; di fakultas ekonomi UIN diajarkan juga prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan seterusnya.
Dengan semangat integrasi, semua ilmu dipandang berasal dari Allah (ayat kauniyah maupun qauliyah), sehingga tugas cendekiawan adalah menjembatani “dua kitab” Tuhan: kitab suci dan kitab alam[50]. Integrasi tidak berarti melebur semuanya jadi satu disiplin, melainkan sinkronisasi epistemik: ilmu agama dapat berteori menggunakan data empiris, ilmu umum diberi landasan etika dan spiritual.
Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Paradigma Integrasi
Secara ontologis, paradigma integrasi ilmu mengakui realitas dalam dua dimensi: wahyu dan alam. Keduanya merupakan manifestasi kebenaran Ilahi yang utuh. Realitas dipahami terbagi atas ayat qauliyyah (realitas tekstual ketuhanan, seperti Al-Qur’an) dan ayat kauniyyah (realitas alam ciptaan)[51]. Namun, pembagian ini bukan dualisme yang terpisah absolut, melainkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Ontologi integrasi menolak pandangan Barat yang hanya mengakui realitas empiris-terukur saja, tapi juga tidak setuju pada penolakan realitas empiris (seperti pandangan ultra-skriptural yang menolak sains). Dalam integrasi, tauhid tetap menjadi pandangan mendasar: Tuhan adalah asal-usul segala sesuatu[32], sehingga semua realitas (fisik maupun metafisik) berada dalam Orkestra Ketuhanan yang harmonis. Alam semesta dipelajari sebagai ayat yang menunjuk kepada Yang Transenden, sementara wahyu dipahami untuk memberi makna kepada gejala alam. Realitas bagi paradigma integrasi bersifat terbuka, teratur, namun membutuhkan bimbingan wahyu untuk memahaminya secara utuh.
Dalam ranah epistemologi, paradigma integrasi menggunakan pendekatan jamak: menggabungkan metode naqli (tekstual) dan aqli (empiris) secara berdampingan. Pengetahuan diambil dari Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga dari observasi dan eksperimen ilmiah[52]. Dengan kata lain, wahyu dan akal (ilmiah) dijadikan sumber bersama dalam proses memperoleh kebenaran. Contohnya, dalam studi sosial, integrasi berarti analisis data sosiologis dilandasi nilai Islam; dalam studi fiqh kedokteran, dalil syar’i diperkaya temuan medis terkini. Paradigma ini membuka diri pada teori-teori ilmiah Barat selama tidak bertentangan dengan akidah[53]. Alih-alih menolak mentah-mentah konsep Barat, integrasi cenderung melakukan adaptasi: misalnya, teori evolusi bisa dibahas dalam kelas dengan penekanan bahwa Allah yang Maha Mengatur proses evolusi (bila dipandang tak bertentangan secara tekstual). Para pengusung integrasi ilmu percaya bahwa banyak pengetahuan modern sebenarnya netral dan bisa diberi ruh Islam. Dengan demikian, model epistemologi integratif bersifat komplementer: ilmu agama memberikan visi dan tujuan, sains memberikan cara dan sarana.
Pernyataan resmi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggambarkan epistemologi integrasi sebagai “eklektik: tidak hanya rasional-empiris, namun juga intuitif dan berlandaskan wahyu sebagai sumber pertama dan utama”[54]. Ini menekankan bahwa integrasi mengakui validitas intuisi spiritual (seperti ilham, insight religius) di samping metode ilmiah. Hal ini segaris dengan pandangan M. Amin Abdullah yang memasukkan pendekatan burhānī (rasional-empiris), bayānī (tekstual), dan ‘irfānī (spiritual intuitif) sekaligus dalam studi Islam[55][56]. Integrasi berarti “triangulasi” tiga epistemologi tersebut dalam kajian keilmuan.
Dari segi aksiologi, paradigma integrasi bertujuan membangun harmoni antara iman dan kemajuan modern[57]. Ilmu diorientasikan untuk kemaslahatan umat manusia (humanis), namun tetap berbasis nilai tauhidik. Dengan integrasi, diharapkan lahir inovasi-inovasi sains yang bermoral dan berpihak pada keadilan sosial sesuai ajaran Islam. Misalnya, teknologi dikembangkan dengan pertimbangan etika Islam; kebijakan ekonomi mengikuti prinsip keadilan dalam Islam. Kemajuan umat menjadi kata kunci[58] – artinya ilmu harus memajukan peradaban Islam agar mampu menghadapi tantangan zaman, tetapi tidak mengorbankan iman. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keseimbangan (tawazun) disuntikkan ke dalam pengembangan ilmu. Kriteria keberhasilan ilmu dalam integrasi adalah keseimbangan: ilmu tidak boleh menjauhkan seseorang dari iman, tapi juga iman tidak menghalangi mengejar ilmu setinggi-tingginya. Paradigma ini mengupayakan “jalan dua arah” antara agama dan sains, di mana keduanya saling memperkaya, bukan saling menaklukkan[59].
Simbolisme dan Model Ilmu
Sebagaimana disebut, berbagai UIN mengembangkan simbol masing-masing untuk paradigma integrasi. Tiga yang populer: Pohon Ilmu, Jaring Laba-laba, dan Menara Kembar.
- Pohon Ilmu: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengadopsi metafora pohon ilmu sebagai representasi integrasi[34][60]. Pohon dengan akar-akarnya (dasar agama dan bahasa Al-Qur’an), batang (ilmu pengetahuan terintegrasi), dan buah (output lulusan yang berakhlak dan kompeten) menggambarkan susunan keilmuan integratif. Metafora pohon juga menekankan pertumbuhan yang organik: ilmu agama dan ilmu umum berjalin seperti pohon besar yang kokoh dan terus berbuah. Akar tauhid yang kuat, batang ilmu yang kokoh, buah manfaat bagi umat – inilah inti filosofi integrasi UIN Malang[61][60]. Gambar pohon ilmu sering terpampang di dokumen kampus sebagai pengingat visi integrasi.
- Jaring Laba-laba: Metafora ini diperkenalkan oleh M. Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skema jaring laba-laba menggambarkan jejaring pengetahuan yang luas dan saling terhubung[62]. Dalam skema tersebut, titik-titik simpul jaring merepresentasikan berbagai disiplin (Islamic studies, sains alam, sosial, humaniora), sedangkan benang-benang yang menghubungkan merepresentasikan nilai etika, prinsip tauhid, dan metodologi integratif. Horizon keilmuan teoantroposentris-integralistik divisualisasikan sebagai jaring di mana agama menjadi pusat etika yang mengikat ilmu-ilmu lainnya[49]. Model ini menegaskan sifat multikultural dan transdisipliner paradigma integrasi-interkoneksi[63]. Pengetahuan dari berbagai bidang dapat berinteraksi dalam “ruang bersama” tanpa kehilangan identitas masing-masing, selama diikat kesadaran akan Tuhan dan kemanusiaan.
- Menara Kembar: Model ini dikenal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua menara kembar melambangkan dua kutub ilmu – ilmu agama dan ilmu umum – yang dibangun berdampingan. Pondasi keduanya satu (tauhid), puncaknya bertemu di tujuan sama (kesejahteraan dan keridaan Ilahi). Konsep ini menunjukkan bahwa ilmu agama dan umum dijalankan paralel dan saling mendukung. Mahasiswanya bisa mengambil ilmu umum setinggi mungkin (setinggi menara), namun di menara satunya mereka tetap mendalami ilmu agama. Keduanya tidak boleh pincang: double excellence.
Meskipun berbeda visualisasi, metafora-metafora tersebut menyampaikan pesan inti yang sama: integrasi berarti mengharmonikan dua sumber ilmu (wahyu & alam)[64]. Representasi ayat qauliyah & kauniyah yang disepadankan sangat sentral dalam paradigma ini.
Peran Pendidik dan Implementasi
Dalam paradigma integrasi ilmu, peran dosen bergeser dari sekadar penyampai dogma menjadi jembatan dua alam pengetahuan. Dosen diharapkan berperan sebagai penghubung dua sumber ilmu, yakni wahyu dan bukti empiris[65]. Mereka harus mampu membaca perkembangan modern, menguasai metodologi ilmiah, sekaligus memiliki grounding kuat dalam teologi Islam. Dosen berfungsi semacam mediator integratif: misalnya, ketika mengajar sosiologi, ia mengaitkan konsep sosiologis dengan nilai Quranik; ketika mengajar tafsir ayat sosial, ia menggunakan data riset aktual.
Paradigma integrasi juga mendorong team teaching atau kolaborasi lintas disiplin. Karena menyadari satu orang sulit menguasai semua bidang, kadang metode integratif dilakukan dengan tim: pakar agama berdialog dengan pakar sains dalam mengajar atau riset. Pendidik juga dituntut terus belajar (long life learning) agar tidak tertinggal di salah satu domain.
Dari segi pendidikan, pendekatan integrasi tampak dalam kurikulum yang menyatukan ilmu agama dan umum. Contoh implementasi: di UIN, program studi umum (misal Biologi) biasanya wajib menambah matakuliah agama (studi Quran/Hadis tematik). Sebaliknya, prodi keagamaan (misal Tafsir Hadis) dituntut memberi porsi mata kuliah pendukung umum (seperti metodologi penelitian sosial, statistika). Harapannya, lulusan UIN memiliki dua kompetensi: kompetensi profesional di bidangnya dan kompetensi pemahaman agama yang baik.
Selain itu, integrasi di PTKIN diwujudkan melalui riset integratif. Banyak kampus mendorong topik skripsi/tesis/disertasi yang mengkaji masalah aktual dengan tinjauan agama. Contoh, tesis tentang konsep keadilan gender dikaji dari perspektif fikih dan sosiologi sekaligus. Pusat-pusat studi integrasi juga didirikan, misalnya Pusat Studi Integrasi Sains dan Islam. Bahkan beberapa UIN memiliki unit penggerak integrasi untuk memastikan visi ini terjaga (seperti yang disebut Unit Penunjang Integrasi di UIN Malang, meliputi Ma’had, masjid kampus, dll. untuk mendukung atmosfer integratif[66]).
Orientasi pendidikan integratif dapat dirumuskan sebagai pendidikan Islam terintegrasi dengan sains modern[67]. Artinya lulusan diharapkan mampu hidup di dua dunia: dunia ilmu pengetahuan global dan dunia iman Islam, tanpa konflik batin. Pada skala makro, paradigma integrasi bertujuan “memajukan umat” – mengejar ketertinggalan IPTEK namun mempertahankan identitas religius. Hal ini sejalan dengan slogan “Berangkat dari Basmalah, Berakhir dengan Hamdalah” di UIN Malang[68][69], melambangkan setiap kegiatan akademik dimulai dengan niat suci (basmalah) dan diakhiri dengan syukur (hamdalah) sesuai ajaran Islam.
Analisis Kritis Paradigma Integrasi
Paradigma integrasi ilmu relatif diterima luas di lingkungan PTKIN karena dianggap solusi moderat. Ia menjawab dikotomi lama “ilmu agama vs ilmu sekuler” dengan menawarkan sintesis produktif. Banyak pihak menilai integrasi berhasil mengubah wajah kampus Islam menjadi lebih inklusif dan progresif[2][70]. Namun demikian, beberapa kritik dan tantangan layak disoroti:
- Implementasi Konseptual vs Praktis: Salah satu kritik menyebut bahwa integrasi sering berhenti di tataran slogan. Semua UIN mengklaim paradigma integratif, tetapi di level fakultas sering bingung implementasinya. Penelitian 2019 di UIN Ar-Raniry Aceh dan UIN Sumatera Utara menemukan bahwa meskipun kedua kampus mengusung model integrasi (UIN Ar-Raniry bahkan memakai istilah “Frikatifisasi Ilmu” sebagai model integrasinya), banyak dosen yang tidak memahami konsep tersebut secara definitif, sehingga model integrasi belum berperan efektif dalam proses pendidikan[71][72]. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan operasionalisasi konsep integrasi yang lebih nyata.
- Terlalu pragmatis: Paradigma integrasi kadang dikritik terlalu kompromistis dan pragmatis[73]. Demi mengejar kesepadanan ilmu agama dan sains, ada kekhawatiran nilai-nilai transenden malah dikurangi kedalamannya. Misal, mengajarkan tauhid cukup diselipkan dalam kuliah fisika sekilas, sehingga pemahaman agama jadi dangkal. Integrasi bisa tergelincir menjadi semata “tempelan ayat” dalam sains tanpa substansi mendalam. Ini berbahaya karena justru mereduksi baik agama maupun sains.
- Kurang kritis terhadap epistemologi Barat: Berbeda dengan Islamisasi yang sangat kritis, integrasi cenderung lebih akomodatif terhadap teori Barat. Kritik menyatakan integrasi ilmu kurang tajam dalam menggugat ideologi ilmu modern[74]. Misalnya, integrasi mungkin menerima teori ekonomi kapitalis lalu hanya menambahkan label syariah, tanpa membongkar ketimpangan struktural kapitalisme itu sendiri. Jadi, integrasi dianggap tidak cukup radikal dalam menantang hegemoni epistemik Barat, sehingga outputnya berpotensi sekadar “versi Islami dari status quo” tanpa perubahan fundamental.
- Tantangan metodologis: Menerapkan integrasi seringkali memerlukan metodologi interdisipliner yang rumit. Kolaborasi antar bidang berbeda tak selalu mulus karena perbedaan istilah, pendekatan, tradisi keilmuan. Dibutuhkan kerja ekstra bagi dosen dan mahasiswa untuk betul-betul menguasai dua domain ilmu. Banyak mahasiswa UIN terbebani SKS agama dan umum sekaligus, dituntut excellent di keduanya. Sementara dosen juga harus meluaskan kompetensi. Ini tantangan SDM dan waktu. Tanpa dukungan, integrasi bisa sekadar beban tambahan tanpa menghasilkan kualitas keilmuan baru.
- Evaluasi keberhasilan: Bagaimana mengukur suksesnya integrasi? Apakah dengan munculnya ilmu baru? Lulusan lebih baik? Ini masih perdebatan. Beberapa keberhasilan dapat dilihat dari misal: munculnya program studi unik (Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Sains dan Al-Qur’an, dsb.), atau jurnal-jurnal integratif. Namun kualitasnya masih beragam. Kritik muncul bahwa operasionalisasi integrasi sering kabur dan gagasan luas integrasi belum menjawab detil teknis di laboratorium atau kelas[75].
Sebagai catatan, paradigma integrasi ilmu meski sudah lebih konkret daripada Islamisasi, tetap merupakan “proyek berjalan” di PTKIN. Secara filosofis, integrasi berhasil menegaskan kesatuan sumber ilmu dari Tuhan dan membuka pintu pada teori Barat[53][76]. Secara praktis, butuh pengembangan berkelanjutan. Evaluasi berbagai studi mengindikasikan perlu penguatan strategi dan model integrasi agar tidak sekadar jargon. Bagaimanapun, integrasi ilmu telah membawa perubahan positif: lulusan PTKIN kini lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai religius[77].
Paradigma Interkoneksi Ilmu
Konsep dan Latar Belakang
Paradigma Interkoneksi Ilmu pada dasarnya merupakan perluasan dari paradigma integrasi dengan penekanan lebih kuat pada sifat multidisipliner, kontekstual, dan humanistik. Istilah “interkoneksi” dipopulerkan oleh M. Amin Abdullah dalam upayanya menjelaskan model integrasi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jika integrasi menekankan penyatuan ilmu agama dan umum, interkoneksi menekankan jejaring antarilmu secara menyeluruh – tidak hanya antara agama dan sains, tapi antar semua bidang ilmu saling berdialog. Paradigma ini menekankan bahwa di era pengetahuan sekarang, pendekatan silo (terkotak per disiplin) tidak lagi memadai; persoalan nyata bersifat kompleks sehingga perlu perspektif lintas disiplin yang saling terhubung.
Interkoneksi juga sering dikaitkan dengan semangat multikulturalisme dan teo-antroposentrik tadi. M. Amin Abdullah menggarisbawahi bahwa ilmu di PTKIN harus mencakup dimensi sosial-budaya yang majemuk. Artinya, dalam mengkaji Islam misalnya, perlu melibatkan pendekatan antropologi, sosiologi, sejarah, dan ilmu lainnya, karena praktik Islam di masyarakat sangat beragam. Sebaliknya, ilmu sosial yang dikembangkan pun perlu interkoneksi dengan nilai agama agar tidak reduksionis. Dengan demikian, paradigma interkoneksi berupaya mengintegrasikan wawasan keagamaan, kemanusiaan, dan alam dalam suatu jaringan utuh[78].
Ciri khas paradigma ini adalah penggunaan pendekatan hermeneutik dan transdisipliner. Amin Abdullah mengajak ilmuwan Muslim untuk mengadopsi “hermeneutika sosial-budaya” dalam studi Islam[79]. Maksudnya, memahami teks dan tradisi agama dengan mempertimbangkan konteks masyarakat (menggunakan teori sosial), serta melakukan dialog dengan disiplin lain. Agama ditempatkan sebagai jantung etis dalam dialog ilmu[80], bukan sebagai sumber tunggal pengetahuan seperti pada Islamisasi, melainkan sebagai pemberi orientasi moral.
Paradigma interkoneksi juga menekankan pendekatan interdisipliner dan pluralitas sumber. Selain wahyu dan akal, pengalaman kultural dan lokal dijadikan sumber pengetahuan berharga[81]. Ini berarti dalam memformulasikan ilmu, kearifan lokal, dialog lintas agama, serta nilai transenden universal ikut dihargai. Interkoneksi membuka ruang lebih luas daripada integrasi: misalnya, tidak hanya integrasi Islam dan sains Barat, tetapi juga integrasi Islam dengan budaya lokal Nusantara, dengan tradisi keilmuan agama lain, dll.
Secara ontologis, paradigma ini memandang realitas sebagai sesuatu yang plural dan inter-relasional[82]. Tidak ada satu pun disiplin yang bisa mengklaim menguasai realitas secara tuntas. Realitas manusia khususnya dipahami sangat kompleks – melibatkan aspek material, sosial, spiritual sekaligus. Karena itu diperlukan “jaring laba-laba keilmuan” untuk menanganinya. Setiap disiplin memegang simpul penjelasan tertentu, dan harus terhubung satu sama lain untuk memetakan realitas besar.
Interkoneksi ilmu muncul juga sebagai respons terhadap fragmentasi ilmu di dunia modern. Banyak ilmuwan mulai menyadari bahaya spesialisasi sempit yang mengabaikan implikasi moral dan sosial. Paradigma ini menghendaki agar ilmuwan lintas bidang saling belajar. Misal, ahli teknologi perlu belajar etika agama, ahli agama perlu melek iptek. Dalam konteks PTKIN, paradigma interkoneksi ingin memastikan lulusan tidak hanya pandai agama tapi gagap realitas, atau sebaliknya pandai sains tapi hampa nurani.
Tokoh kunci selain Amin Abdullah adalah ilmuwan Indonesia lain seperti Kuntowijoyo (meski bukan dari PTKIN, ia mencetuskan konsep “Ilmu Sosial Profetik” yang sejalan dengan semangat interkoneksi: menggabungkan ilmu sosial dengan nilai profetik/kenabian). Selain itu, paradigma ini di tingkat global sejalan dengan tren “integrative knowledge” atau “consilience” – upaya menjahit kembali cabang-cabang ilmu menjadi padu. Bedanya, di PTKIN injeksi nilai spiritual tetap jadi agenda utama.
Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Paradigma Interkoneksi
Secara ontologi, paradigma interkoneksi melihat realitas sebagai multikultural, kompleks, dan inter-relasional[82]. Multikultural artinya realitas sosial terdiri dari berbagai latar budaya dan agama yang semuanya punya makna. Kompleks artinya tidak bisa disederhanakan ke satu sudut pandang saja. Inter-relasional artinya setiap aspek realitas berhubungan dengan aspek lain (ekonomi dengan budaya, sains dengan moral, dsb.). Ontologi ini menolak pandangan simplistik. Sebagai contoh, fenomena kemiskinan bukan cuma soal ekonomi, tapi terkait budaya, etika, kebijakan politik, dll. Begitu pula, fenomena keberagamaan bukan hanya urusan ibadah, tapi terkait kondisi sosial, pendidikan, dll. Oleh sebab itu, memahami realitas membutuhkan banyak lensa sekaligus. Paradigma interkoneksi secara ontologis juga bersifat teo-antroposentris, menempatkan Tuhan dan manusia sebagai pusat eksistensi[63]. Maksudnya, realitas dipandang dari sudut hubungan Tuhan-manusia: Tuhan sebagai pencipta segala yang nyata, dan manusia sebagai subjek yang memberi makna dan nilai. Dengan kata lain, yang dipelajari interkoneksi bukan objek mati netral, tetapi realitas yang dialami manusia dalam bingkai Ketuhanan.
Dari segi epistemologi, paradigma ini menekankan jejaring pengetahuan secara hermeneutik dan kontekstual[83]. Artinya, ilmu diperoleh melalui dialog antar disiplin dengan memahami konteks. Metode hermeneutik (interpretasi) diutamakan untuk menjembatani teks dan konteks, teori dan data lapangan. Pendekatan kualitatif-kritis diapresiasi sama halnya dengan kuantitatif-positivis. Sumber epistemologi dalam interkoneksi tak hanya nash dan akal, tapi juga pengalaman empiris, dialog lintas ilmu, dan nilai-nilai lokal[81]. Contohnya, dalam penelitian, seorang cendekia interkonektif mungkin menggunakan data antropologi, wawancara tokoh agama, analisis ayat, sekaligus teori sosiologi modern untuk mendapatkan gambaran utuh. Tidak ada hierarki kaku mana ilmu “tinggi” mana “rendah”; semuanya saling memperkaya.
Epistemologi ini juga mendorong refleksi kritis: pengetahuan selalu dikaji ulang dalam konteks sosial. Berbeda dengan Islamisasi yang cenderung normative atau integrasi yang sering cukup deskriptif, interkoneksi ingin pengetahuan juga mengungkap relasi kuasa di baliknya. Misal, saat mempelajari fiqh poligami, pendekatan interkonektif akan mengajak melihat konteks historis, struktur patriarki masyarakat, interpretasi ulama, dsb., tidak cukup dengan dalil teks belaka. Dengan begitu, muncul pemahaman lebih kritis dan menyeluruh.
Aksiologi dalam paradigma interkoneksi sangat menekankan kemanusiaan dan harmoni sosial. Ilmu diarahkan bagi terciptanya masyarakat majemuk yang harmonis, adil, dan bermartabat[84]. Nilai tauhid tetap menjadi landasan moral, tetapi diartikulasikan dalam semangat inklusif dan etika universal. Misalnya, ilmu di PTKIN harus mampu mendukung dialog antaragama, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Keberagaman dianggap sunnatullah yang harus difasilitasi oleh ilmu, bukan dihilangkan. Oleh karena itu, keberhasilan ilmu diukur salah satunya dari relevansi sosialnya: seberapa jauh penelitian dan pembelajaran di PTKIN menanggapi isu-isu multikultural, HAM, lingkungan, dll., sesuai etika religius[85].
Selain itu, paradigma ini secara aksiologis mengusung nilai keadilan dan pembebasan. Ada kemiripan dengan Epistemologi Teologi Pembebasan di Amerika Latin, walau konteks berbeda. Intinya, ilmu harus berpihak pada yang lemah, menantang struktur penindasan. Karenanya, interkoneksi tak segan menggunakan teori kritis, misal pendekatan Marxian dalam studi sosial, asalkan diimbangi etika tauhidik agar tidak sekularistik murni[47]. Nilai teoantroposentrik menuntut bahwa yang transenden (Tuhan) dan iman, harus diaktualisasikan dalam yang imanen (kemaslahatan manusia di dunia).
Simbolisme dan Model Ilmu
Jaring laba-laba yang telah dijelaskan sebenarnya merupakan simbol utama paradigma interkoneksi. Kita telah bahas bahwa skema jaring laba-laba mengandung horizon keilmuan yang luas, tidak miopik (tidak rabun jauh)[86]. Inti gagasan jaring laba-laba adalah tidak ada satu pun pusat tunggal – melainkan multi-pusat (polisentris). Namun semua simpul dihubungkan oleh benang-benang, merepresentasikan spirit dediferensiasi (meleburkan batas-batas disiplin)[87].
Selain jaring laba-laba, sebagai model representasi interkoneksi[88]. Ini menggarisbawahi bahwa tidak ada isolasi ilmu.
Beberapa UIN lain punya ikon: misalnya, UIN Antasari Banjarmasin memperkenalkan metafora “sungai ilmu” – di mana berbagai aliran ilmu bermuara pada samudera tauhid (mirip ide interkoneksi juga). Intinya, semua mengilustrasikan keterhubungan.
Bisa dikatakan, simbol sentral interkoneksi adalah jejaring dan dialog. Tak ada satu simbol tunggal sekuat pohon atau menara, justru simbolnya adalah keterhubungan itu sendiri. Ini sejalan dengan filsafat *“ilmu bersifat jejaring; saling terhubung lintas disiplin dan nilai”[89]. Representasi konkret di kampus misalnya: di UIN Yogya ada lukisan jaring besar di dinding, di UIN Bandung ada patung “Roda” mengindikasikan saling terhubung bagian-bagian, dsb.
Peran Pendidik dan Implementasi
Dalam paradigma interkoneksi, peran pengajar makin kompleks: tidak hanya penjaga nilai atau penghubung dua sumber, tapi juga semacam fasilitator dialog lintas ilmu. Dosen idealnya menjadi mediator integratif yang mampu mengorkestrasi berbagai perspektif di kelas[65]. Mereka diharapkan mendorong mahasiswa berpikir holistik: misalnya, jika membahas masalah sosial, dosen interkonektif akan mengajak mahasiswa melihat aspek agama, ekonomi, budaya sekaligus.
Dosen juga berperan membumikan agama dalam diskursus kontemporer. Sebagai contoh, menghubungkan ajaran etika Islam dengan konsep HAM global, atau gagasan keadilan sosial Islam dengan teori pembangunan ekonomi modern. Dosen dengan paradigma ini tidak anti-teori Barat, sebaliknya terampil mendialogkannya dengan khazanah Islam. Mereka semacam “penyintas batas” (boundary spanner) antar domain pengetahuan.
Pendidikan berparadigma interkoneksi ditandai dengan kurikulum transdisipliner. Beberapa program studi mulai didesain sebagai kajian kawasan atau tematik yang melibatkan multi disiplin. Misalnya, Studi Timur Tengah di UIN melibatkan sejarah, politik, ekonomi, dan agama sekaligus. Ada juga mata kuliah integratif semacam “Islam dan Ilmu Pengetahuan”, “Metodologi Studi Interdisipliner” di jenjang pascasarjana.
Selain itu, interkoneksi terlihat dari maraknya riset kolaboratif antar fakultas. Misal, proyek penelitian tentang moderasi beragama melibatkan ahli tafsir dan sosiolog. Paradigma ini mendorong penelitian yang lintas sektor: dosen syariah bisa bergabung dengan dosen sains untuk meneliti pangan halal, dsb.
Orientasi pendidikan interkoneksi juga multikultural: kampus didorong membuka diri untuk berbagai latar, membangun toleransi, dsb.[90]. Hal ini tampak dari upaya PTKIN mengarusutamakan moderasi beragama di kurikulum serta kegiatan kemahasiswaan yang merangkul kebhinekaan.
Analisis Kritis Paradigma Interkoneksi
Sebagai pendekatan, interkoneksi ilmu terbilang progresif dan mengikuti semangat zaman ilmu pengetahuan abad ke-21. Ia menjanjikan keluasan pandangan dan kemampuan sintesis. Meski demikian, ada beberapa kritik atau keterbatasan:
- Abstrak dan sulit diukur: Karena cakupannya luas dan cenderung filosofis, paradigma interkoneksi dianggap gagasan besar yang operasionalisasinya sering kabur[75]. Tidak mudah menilai kapan “interkonektif” ini berhasil. Apakah cukup dengan timbre interdisipliner? Atau keluaran kebijakan? Indikatornya belum jelas. Terlebih, mempersiapkan kurikulum dan SDM untuk benar-benar interkonektif memerlukan perubahan mendasar pada struktur fakultas dan departemen yang selama ini terkotak. Resistensi birokrasi bisa menghambat realisasi interkoneksi penuh.
- Butuh SDM Renaissance: Interkoneksi menuntut sarjana serbabisa – memahami beragam bidang plus mendalami nilai spiritual. Ini mendekati ideal “Polymath” zaman Renaissance. Realitanya, sistem pendidikan sekarang melahirkan spesialis. Maka, melatih dosen/mahasiswa menjadi lintas disiplin sangat menantang. Perlu lingkungan belajar yang kolaboratif, infrastruktur riset, dan mungkin perubahan dalam rekrutmen dosen (tidak hanya latar satu disiplin). Tanpa itu, interkoneksi bisa berjalan di permukaan (hanya retorika “mari berdialog” tapi praktis tetap jalan sendiri-sendiri).
- Tantangan Epistemologis: Menggabungkan metodologi berbeda memerlukan kerangka epistemologi baru. Amin Abdullah menawarkan teoantroposentrik integratif, namun membuat metodologi konkritnya masih dieksplorasi. Apakah misal cukup pakai metode mix-method? Atau hermeneutika transdisipliner? Banyak metodologi interdisiplin masih dalam pengembangan (contoh Islamic Indigenization, ethnographic theology dsb.). Kritik menyebut, interkoneksi belum cukup tajam membedah relasi kuasa epistemik dan simbolik[91]. Maksudnya, meski mengusung semangat kritis, seringkali analisis kekuasaan ilmu (dominasi Barat misalnya) belum tergali mendalam – barangkali karena fokusnya menyatukan bukan mengkonfrontasi.
- Perlu dukungan kelembagaan: Agar paradigma interkoneksi benar-benar terwujud, PTKIN perlu mereformasi struktur yang sekat-sekat. Misal memfasilitasi team teaching lintas fakultas, skema pembiayaan riset kolaboratif, penilaian karir dosen yang menghargai publikasi interdisipliner, dsb. Jika tidak, dorongan interkoneksi hanya bergantung pada segelintir pemikir tanpa institusionalisasi. Paradigma ini masih relatif baru dan simbolik, perlu eksplorasi metodologis dan kelembagaan lebih lanjut untuk pembuktian praktis[92].
Secara keseluruhan, interkoneksi ilmu memperluas cakrawala integrasi ke dimensi transdisipliner dan kemanusiaan yang inklusif[93]. Paradigma ini selaras dengan kebutuhan dunia pendidikan modern yang menuntut kolaborasi dan inovasi lintas bidang. Bila integrasi adalah jembatan antara dua bukit (agama dan sains), maka interkoneksi adalah jaringan jalan raya yang menghubungkan banyak kota keilmuan. Keberhasilan paradigm ini akan sangat dipengaruhi oleh kreativitas dan keterbukaan sivitas akademika PTKIN sendiri dalam berinovasi.
Paradigma Frikatifisasi Ilmu
Konsep dan Latar Belakang
Paradigma Frikatifisasi Ilmu merupakan gagasan terkini yang digagas oleh saya [94]. Paradigma ini bisa dikatakan sebagai “lompatan radikal” dalam wacana keilmuan PTKIN karena menawarkan sudut pandang yang berbeda secara metodologis dan ontologis. Istilah “frikatifisasi” diambil dari kata frikatif – dalam linguistik berarti bunyi yang dihasilkan oleh gesekan/hembusan udara melalui celah sempit (contoh: bunyi “s”, “f”). Saya menggunakan metafora ini untuk ilmu, dengan inspirasi tradisi Aceh: “sua” (obor) dan hembusan. Intinya, ilmu dipandang sebagai sesuatu yang dihembuskan, bukan sekadar ditransmisikan atau dibangun konstruksinya.
Paradigma frikatifisasi lahir dari kegelisahan bahwa meskipun integrasi dan interkoneksi sudah diupayakan, ada dimensi ruhani yang belum tersentuh optimal[95]. Saya melihat bahwa dalam benturan berbagai paradigma (Islamisasi, integrasi, interkoneksi), suasana keilmuan PTKIN masih dominan intelektualistik tapi kurang nafas spiritual yang hidup[96]. Maka, ia mengusulkan jalur keempat yang menekankan ilmu sebagai pancaran kosmik yang dapat menyala atau padam tergantung “hembusan epistemik” sang penerima[97].
Maksudnya, ilmu bukan sekadar himpunan teori atau teks, melainkan resonansi batin. Proses memperoleh ilmu bukan hanya membaca atau observasi, tetapi semacam penangkapan getaran Ilahi melalui keheningan, intuisi, dan pengalaman spiritual[98]. Konsep ini dipengaruhi oleh tradisi tasawuf, di mana ilmu dipandang bisa diperoleh melalui kasyf (penyingkapan batin) selain melalui pembelajaran lahiriah. Dapat dikatakan bawa paradigma frikatifisasi tidak sekadar metode, melainkan maqam (tingkatan spiritual)[99]. Artinya, pendekatan ini menuntut kondisi ruhani tertentu: ilmu ditiupkan kepada yang siap secara spiritual, layaknya malaikat Jibril meniupkan wahyu, atau ibarat obor (sua) yang bisa menyala karena ditiup dengan niat dan ruh yang tepat[100].
Paradigma ini juga lahir dari refleksi sufistik Aceh. Sua (obor khas Aceh) dijadikan simbol: obor memberikan cahaya, tetapi bisa padam jika ditiup angin buruk, atau menyala terang jika ditiup dengan benar. Analogi dengan ilmu: ilmu adalah cahaya di jiwa, dapat menerangi (membimbing) atau malah memadamkan (menyesatkan) tergantung niat, adab, dan kualitas ruhani orang yang menanggapnya[101][102]. Dapat disebut “hembusan epistemik” – maksudnya cara seseorang mendekati ilmu, dengan sikap batin seperti apa, akan menentukan apakah ilmu itu menjadi berkah atau petaka baginya[103].
Paradigma frikatifisasi tidak menolak integrasi atau interkoneksi, tapi melengkapinya dengan kedalaman spiritual. Ia seolah mengingatkan: ilmu yang sudah diislamkan, diintegrasikan, diinterkoneksikan, toh masih bisa gersang jika tidak menghidupkan jiwa. Karenanya, frikatifisasi mengajak kembali pada laku spiritual: zikir, tafakur, kontemplasi mendalam sebagai bagian integral dari proses ilmiah[104]. Ini bisa dikaitkan dengan tradisi “ilmu laduni” (ilmu anugerah langsung dari Tuhan) dalam khazanah Islam, atau gagasan “epistemologi ‘irfani” (gnostik spiritual) yang diakui dalam filsafat Islam.
Paradigma ini lahir “dari pengalaman spiritual yang mendalam, keterlibatan emosional, dan kesadaran akan keheningan sebagai tempat ilmu menampakkan diri”[105]. Jadi ini bukan semata konstruksi teoritis, melainkan buah perenungan sufistik penulisnya terhadap kondisi keilmuan saat ini.
Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Paradigma Frikatif
Secara ontologi, paradigma frikatifisasi memandang realitas sebagai emanasi Cahaya Ilahi yang terus bergerak dan bergetar[106]. Realitas bukan entitas statis, melainkan proses pancaran berkesinambungan dari Tuhan. Semua wujud hakikatnya Nur (cahaya) Allah, sebagaimana konsep wahdat al-wujud (kesatuan keberadaan dalam sufisme). Ontologi ini menolak kategorisasi kaku antara ayat qauliyah dan kauniyah; keduanya dilihat sebagai resonansi satu frekuensi ilahi yang meresapi seluruh ciptaan[107]. Artinya, alam dan wahyu sama-sama manifestasi Cahaya Tuhan, hanya beda medium. Bahkan, lebih radikal lagi, realitas adalah getaran Ilahi – semesta bergetar karena “kun fayakun” (firman Tuhan “jadi!” yang terus bergaung). Dalam pandangan ini, ilmu bukan upaya manusia mengerti realitas luar, tapi upaya menangkap getaran ilahi dalam realitas.
Ontologi frikatif jelas dipengaruhi pandangan sufi bahwa Tuhan adalah cahaya langit dan bumi (ayat Al-Nur), dan hati mukmin bisa menangkap percikan cahaya itu. Ilmu lantas dianggap sebagai pancaran ruhani – bukan semata data dan teori, tapi nur yang menyinari hati[108]. Konsep ini mengintegrasikan dimensi spiritual ke pusat definisi realitas.
Epistemologi dalam paradigma frikatif bisa dirangkum: “dari diam menuju cahaya”[109]. Pengetahuan lahir dari keheningan batin, di mana ilham dan inspirasi ilahi datang sebagai hembusan. Maka, keheningan adalah epistemik dasar[110]. Artinya, sebelum belajar melalui buku, seseorang sebaiknya menyiapkan jiwa melalui meditasi, zikir, atau doa. Dalam diam itulah, terjadi tajalli (manifestasi spiritual dalam kesadaran)[111]. Frikatifisasi menolak dikotomi teks vs konteks, sebab keduanya hanyalah satu suara yang harus ditangkap jiwa[112]. Ilmu tidak tumbuh dari data semata, melainkan dari perenungan yang membangkitkan[111]. Alhasil, metode keilmuan frikatif bukanlah sekadar kuantifikasi atau logika deduktif, melainkan tajalli, semacam penyinaran rohani dalam diri peneliti[111].
Epistemologi ini tentu tidak lazim dalam sains modern, namun saya mengajak agar paradigma ilmiah diperluas. Ia ingin dosen bukan sekadar pengisi papan tulis, tapi “penghembus kesadaran”[113]. Mahasiswa bukan sekadar penerima informasi, tapi penerima cahaya yang aktif menyinari diri dan sekitarnya[113]. Ini idealisme tinggi: proses belajar dianggap seperti sesi zikir bersama, di mana ilmu ditularkan melalui getaran semangat dan keteladanan batin pengajar, bukan cuma konten materi.
Secara aksiologi, frikatifisasi menempatkan tujuan ilmu pada kebangkitan kesadaran kosmik dan transformasi batin[114]. Ilmu harus mampu menyalakan ruh dan mendekatkan jiwa kepada Tuhan[114]. Jadi parameter sukses ilmu bukan hanya publikasi atau produk teknologi, tapi apakah hati manusia menjadi lebih tercerahkan, moralnya naik, dan spiritualnya dalam? Ini mendefinisikan ulang kebermanfaatan ilmu dengan kriteria batiniah. Ilmu yang benar akan melahirkan pribadi arif, tenang, penuh kasih (karena tersambung dengan Sumber-nya). Sebaliknya, ilmu yang salah (atau disalahgunakan) bisa memadamkan cahaya batin, membuat sombong atau merusak. Orientasi pendidikan pun berubah: kelas bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi maqam, ruang zikir, dan proses tajalli[115].
Tentu, aksiologi ini tidak meninggalkan nilai sosial. Frikatifisasi tetap mengandaikan resonansi batin itu berbuah dalam etika sosial. Orang yang tercerahkan jiwanya akan peduli lingkungan, adil, dsb. Hanya saja, titik berangkatnya dari dalam ke luar: benahilah batin, maka amal lahir akan baik. Ini semacam inside-out approach dalam memajukan peradaban.
Simbolisme dan Model Ilmu
Paradigma frikatifisasi memiliki simbol unik yang memadukan unsur kosmik dan tradisi lokal Aceh. Saya menyebut “Obor (sua) dan Hembusan” sebagai metafora[102]. Obor melambangkan ilmu sebagai cahaya. Hembusan melambangkan daya rohani yang dapat menyalakan atau memadamkan cahaya itu[102]. Disebutkan bahwa obor bisa menyala atau padam oleh niat, ruh, atau kehendak batin[102]. Ini tepat menggambarkan gagasannya: ilmu sangat bergantung pada kualitas niat dan batin penuntutnya.
Selain obor, ada juga konsep suara frikatif dan zikir. “Ilmu sebagai getaran ruhani – zikir, suara frikatif, cahaya yang menyinari jiwa atau ditiup padam”[116]. Suara frikatif di sini contohnya seperti suara “hsss” atau “fff” yang dalam tradisi zikir terefleksi misal pada lafaz “Allah” yang keluar napas “hh”. Suara ini melambangkan napas hidupnya ilmu – bahwa ilmu hidup dalam denyut zikir dan spiritualitas*. Saat seseorang belajar dalam keadaan mengingat Allah, ilmu itu seperti disertai napas ilahi (ruhul qudus) yang menghidupkan makna. Sebaliknya jika belajar dengan niat salah, zikir hilang, ilmu jadi mati (padam).
Dalam budaya Aceh, sua juga terkait upacara tradisional di mana obor dinyalakan sebagai simbol pencerahan. Kita memanfaatkannya sebagai simbol kosmologi ruhani: malaikat Jibril meniupkan wahyu kepada Nabi, Israfil akan meniup sangkakala akhir zaman – semua lewat perantara hembusan. Ini melambangkan kekuatan vibrasi ilahi dalam memberi atau mengakhiri kehidupan. Ilmu diibaratkan demikian: bisa menjadi hembusan kosmik yang menerangi batin manusia atau menghancurkannya, tergantung hembusan epistemik yang mendasari penggunaan ilmu[117].
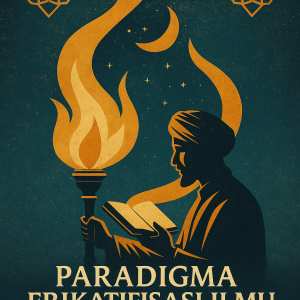
Ilustrasi di atas menggambarkan dengan artistik esensi frikatifisasi: ilmu sebagai cahaya ruhani dalam tradisi keilmuan Islam[118]. Obor kosmik dengan bulan-bintang menunjukkan integrasi langit (wahyu) dan bumi (usaha manusia) dalam nyala ilmu.
Peran Pendidik dan Implementasi
Dalam paradigma frikatif, peran pengajar menjadi mirip mursyid (pembimbing spiritual). Disebutkan bahwa pengajar adalah “mursyid ruhani, yang meniupkan ilmu bukan menyampaikan informasi”[65]. Artinya, dosen idealnya seperti guru sufi yang mentransfer barakah ilmu lewat hubungan hati, bukan sekadar transfer konten. Hal ini tentu menuntut kualifikasi rohani: dosen sendiri harus menjalani laku spiritual agar bisa menjadi penyalur ilmu dengan hembusan bermakna. Figur pendidik di sini menggabungkan intelektual dan sufi.
Implementasinya bisa dalam bentuk perubahan pedagogi: misal, memulai kelas dengan meditasi atau zikir singkat agar suasana batin terbuka. Dosen membangun emosional engagement dengan mahasiswa, sehingga ada chemistry ruhani. Mungkin juga mengevaluasi pemahaman mahasiswa tidak hanya lewat ujian kognitif, tapi terlihat dari akhlak dan getaran semangat yang muncul.
Orientasi pendidikan paradigma ini sangat khas: kelas dilihat sebagai tempat penyinaran jiwa melalui resonansi ruhani[119]. Bukan sekadar transfer ilmu. Jadi pendidikan didekati seperti majelis zikir atau halaqah tarekat di mana ilmu meresap lewat keteladanan dan atmosfer suci. Evaluasi keberhasilan pendidikan bukan semata IPK tapi transformasi pribadi: apakah mahasiswa mengalami pencerahan visi hidup, peningkatan iman, dll. Tentu ini tantangan besar mengukur secara akademik, namun itulah idamannya.
Implementasi formal mungkin terbatas, tetapi bisa dimulai dengan membangun budaya kampus religius yang esensial (bukan formalitas). Misal: mendorong komunitas zikir, retret spiritual mahasiswa, mentoring akhlak oleh dosen, dsb. Sebagian PTKIN memang sudah memiliki program seperti halaqah diniyah di asrama mahasiswa, dsb., ini sejalan dengan semangat frikatifisasi.
Analisis Kritis Paradigma Frikatif
Paradigma frikatifisasi ilmu menawarkan perspektif yang sangat mendalam dan transformatif terhadap keilmuan, namun tentu memancing diskusi kritis:
- Abstrak dan Elitis? Karena bertumpu pada pengalaman spiritual personal, paradigma ini bisa dianggap kurang terukur dan sulit diakses umum. Tidak semua orang punya hal pengalaman spiritual mendalam seperti pencetusnya. Ada risiko, gagasan ini hanya dipahami oleh segelintir yang sepemahaman, sementara bagi dosen/mahasiswa awam terdengar mistis dan membingungkan. Agar dapat diadopsi luas, perlu upaya menjelaskan konsep ini dalam kerangka yang lebih operasional (misal, metode pengajaran spesifik yang menekankan spiritualitas).
- Integrasi dengan Sains Empiris: Frikatifisasi mendapat kritik apakah bisa diterapkan dalam sains murni. Misal, bagaimana fisika frikatif atau biologi frikatif? Pendekatan ini sulit diaplikasikan dalam sains empiris murni[120], karena bahasa spiritual tak terbaca dalam eksperimen laboratorium. Namun, bisa jadi saya mungkin tidak meniatkan ini untuk sains alam, melainkan lebih ke studi sosial-humaniora Islam. Walau begitu, tantangan bridging dengan metode ilmiah baku tetap ada – misal, bagaimana memasukkan elemen zikir dalam riset sejarah? Apakah keheningan bisa jadi metode di laporan penelitian? Ini memerlukan keberanian metodologis yang belum lazim di dunia akademik.
- Keberlanjutan Gagasan: Paradigma frikatifisasi masih baru dan belum teruji. Saya sampaikan dalam presentasi dan tulisan opini [121], tapi belum banyak literatur akademik yang mengulas atau menerapkannya. Butuh eksplorasi lebih lanjut untuk menjadikannya kerangka nyata[92]. Bisa saja, jika tidak segera ditindaklanjuti, gagasan ini tinggal wacana tanpa penerus. Maka, diperlukan upaya sistematis: seminar, penelitian model pendidikan frikatif, buku panduan kurikulum berbasis frikatif, dsb., agar tidak menguap.
- Potensi Anti-Teknokrasi: Menariknya, Saya justru mengkritik keras pandangan teknokratik ilmu. Ia menolak reduksi ilmu jadi instrumen teknokratik, serta menekankan makna batin, keheningan, ruh sebagai inti[122]. Kritik ini valid terhadap komersialisasi pendidikan modern. Namun, efek sampingnya, paradigma frikatif bisa dianggap terlalu menjauh dari realitas pragmatis. Sementara dunia sibuk bicara revolusi industri 4.0, big data, dsb., paradigma ini bicara zikir dan obor spiritual. Ada gap yang harus dijembatani agar tak dianggap utopis. Barangkali dengan menyinergikan: misal, etika spiritual dalam penggunaan teknologi AI – tentang Ethics of AI in Religion).
Singkatnya, Paradigma Frikatifisasi Ilmu menyodorkan lompatan spiritual ke arah kosmologi ruhani – ilmu sebagai getaran kosmik yang menyinari batin manusia[123]. Ini sebuah pemikiran yang mengembalikan sakralitas dan kedalaman makna ke jantung ilmu pengetahuan. Jika berhasil diimplementasikan, ia dapat menjadi penawar bagi kekosongan moral dalam akademia. Namun, tantangannya adalah menjadikan konsep esoteris ini inklusif dan aplikatif tanpa kehilangan esensi.
Komparasi Antar Paradigma Keilmuan
Setelah mengulas keempat paradigma (Islamisasi, Integrasi, Interkoneksi, Frikatifisasi), kita dapat membandingkan mereka di beberapa aspek kunci untuk melihat persamaan, perbedaan, dan potensi saling melengkapi.
Landasan Filosofis dan Ontologi
- Islamisasi Ilmu berlandaskan ontologi tauhid dengan pandangan realitas adalah ciptaan Allah dan kebenaran bersumber dari wahyu. Ia cenderung memandang realitas melalui kacamata agama secara ketat. Ontologi Islamisasi monolitik: apapun yang tidak selaras tauhid dipandang menyimpang.
- Integrasi Ilmu juga bertumpu pada tauhid, tetapi mengakui dualitas manifestasi (wahyu & alam) secara eksplisit. Ontologinya mengakomodasi dua domain realitas yang bersumber satu, sehingga lebih inklusif dari Islamisasi. Ia bersifat monisme moderat – Tuhan satu, pencipta realitas jamak, yang bisa didekati via jalur agama maupun sains.
- Interkoneksi Ilmu ontologinya pluralistik: realitas dilihat kompleks, multidimensi, namun tetap dalam rangka tauhidik (teoantroposentrik). Ada pengakuan terhadap keragaman fenomena (multikultural). Berbeda dengan dua sebelumnya yang agak esensialis, interkoneksi memandang realitas sangat kontekstual dan relasional.
- Frikatifisasi Ilmu ontologinya paling sufistik: realitas sebagai emanasi cahaya Ilahi yang bergetar. Ini semacam monisme panteistik (walau istilah panteisme tidak digunakan langsung). Realitas dipahami bukan melalui struktur atau kategori, tapi melalui metafora getaran – semuanya satu frekuensi Ilahi. Jadi, yang lain-lain seperti wahyu vs alam bukan terpisah, melainkan satu spektrum cahaya.
Epistemologi dan Metode
- Islamisasi: Epistemologi berbasis wahyu dan akal yang diislamkan. Sumber utama Al-Qur’an-Hadis, ditopang akal (dalam koridor adab). Metode: Islamisasi disiplin, kritik ideologi Barat, rekontruksi ilmu dari prinsip Islam[28]. Jadi, ada proses kritis terhadap ilmu modern dan pembuatan framework baru dari tauhid.
- Integrasi: Epistemologi kombinatif – nash dan empiris bersama-sama. Sumber: Allah (melalui nash dan alam)[52]. Metode: tafsir teks bersinergi dengan penelitian ilmiah dan sintesis pengetahuan[124]. Ada keterbukaan pakai teori Barat selama sesuai. Pendekatan cenderung sinkretis kreatif.
- Interkoneksi: Epistemologi hermeneutik-kontekstual. Sumber: multi (wahyu, akal, pengalaman, dialog lintas ilmu)[81]. Metode: hermeneutik, refleksi kritis, pendekatan transdisipliner[125]. Intinya dialogis: memperoleh ilmu lewat interaksi wacana, refleksi mendalam, bukan hafalan. Ada sedikit nuansa kritikal (pembebasan).
- Frikatifisasi: Epistemologi intuisi dan zikir. Sumber: keheningan, intuisi, getaran batin[126]. Metode: kontemplasi sufistik, dialog dalam diam, makna dalam getaran[127]. Ini metode non-tradisional dalam akademik: semacam “meditative inquiry”. Proses knowing = becoming (menjadi terang karena disentuh cahaya)[128]. Sangat personal dan transrasional.
Aksiologi (Tujuan Ilmu)
- Islamisasi: Membangun disiplin Islami bebas pengaruh Barat, menegakkan masyarakat Qur’ani[29]. Tujuan utamanya ke dalam komunitas Islam: kemurnian ilmu dan kepatuhan pada wahyu. Ada semangat kejayaan Islam di sini (victory of Islam melalui ilmu[129]).
- Integrasi: Mencapai keseimbangan iman dan modernitas demi kemajuan umat[58]. Tujuan ganda: memajukan umat di dunia (IPTEK, ekonomi, dll.) sekaligus menjaga iman. Sasarannya pembaruan pendidikan Islam agar umat kompetitif namun bermoral.
- Interkoneksi: Harmony sosial, kemanusiaan, keberagaman berbasis tauhidik[84]. Tujuan ke luar: turut serta menyelesaikan problem kemanusiaan global dengan perspektif Islam. Ada ideal rahmatan lil alamin: ilmu untuk keadilan sosial, dialog antarbudaya, dsb.
- Frikatifisasi: Kebangkitan kesadaran kosmik, penyinaran jiwa, mendekatkan diri pada Tuhan[114]. Tujuan sangat esoteris: transformasi spiritual individu melalui ilmu. Efeknya tentu harapannya ke masyarakat (masyarakat yang tercerahkan), tapi titik berat pada inner transformation.
Hubungan Ilmu dan Agama
- Islamisasi: Agama = sumber utama dan pengarah semua ilmu[130]. Ilmu tunduk pada agama. Ilmu kalau bertentangan agama, harus diubah. Hubungan hierarkis: wahyu di atas, ilmu hasil olah akal di bawah.
- Integrasi: Ilmu dan agama bersatu dalam sumber dan orientasi[131]. Tidak bertentangan. Agama dan ilmu saling melengkapi: ilmu mencari kebenaran detail, agama memberi big picture moral. Hubungan harmonis, mungkin setara namun agama tetap jantung moral[132].
- Interkoneksi: Agama = jantung etis dan moral dialog antar ilmu[133]. Artinya agama bukan mendikte isi semua ilmu, tetapi menjadi hati nurani yang memandu diskusi lintas bidang. Hubungan kooperatif: ilmu berbagai bidang mengambil nilai dari agama sebagai penyeimbang.
- Frikatifisasi: Ilmu dan agama menyatu dalam ruang zikir dan getaran spiritual[134]. Hubungan sangat menyatu, bahkan tak terbedakan: menuntut ilmu = ibadah, ibadah = menuntut ilmu dalam pandangan ini. Agama dilihat sebagai jalan tajalli Ilahi, ilmu sebagai efek tajalli. Jadi keduanya satu proses.
Sumber Otoritas Ilmu
- Islamisasi: Al-Qur’an, Hadis, ulama klasik, nilai Islam universal[135] sebagai rujukan tertinggi. Tradisi intelektual Islam klasik dijunjung tinggi. Sumber Barat diperbolehkan jika telah diislamkan atau mendukung wahyu.
- Integrasi: Wahyu, alam, akal sehat dalam kerangka normatif Islam[136]. Sumber otoritatif kombinasi: ada scripture, ada nature, ada reason. Namun reason dan nature harus dibaca dengan bingkai Islam (norma Islam).
- Interkoneksi: Pengalaman kultural, dialog ilmu, nilai transenden dan lokal[137]. Otoritas ilmu diperluas: tidak melulu teks formal, tapi juga kearifan budaya, konsensus global yang sejalan nilai luhur, dsb. Ini mengafirmasi pluralitas sumber hikmah (wisdom bisa datang dari mana saja, selama sejalan tauhid).
- Frikatifisasi: Ruhani ulama, maqam spiritual, pengalaman batin sebagai sumber getaran ilmu[138]. Ini unik: autoritatifnya adalah orang-orang yang mencapai maqam tertentu, pengalaman ruhaniah (mimpi, ilham) diakui. Tentu bukan untuk hal teknis sains, tapi untuk hikmah dan orientasi. Misal, nasihat seorang wali lebih berbobot daripada teori psikologi dalam memandu jiwa.
Metode Keilmuan
- Islamisasi: Islamisasi disiplin ilmu, kritik ideologi Barat, rekonstruksi tauhidik[139]. Jadi metodenya normatif-kritis. Ada tahapan: kuasai ilmu – kritik – tanam nilai Islam – reformat struktur ilmunya. Boleh dibilang top-down approach (kerangka dari atas diturunkan ke detail).
- Integrasi: Integratif: tafsir nash + penelitian ilmiah + sintesis[140]. Metode campuran. Top-down dan bottom-up digabung: teks ditafsir, fakta dikumpul, lalu disintesakan. Perlu proses kreatif untuk menemukan padanan konsep dll.
- Interkoneksi: Hermeneutik, refleksi kritis, kontekstual, transdisipliner[125]. Metode diskursif. Seringkali kualitatif dan partisipatoris. Bisa pakai metode integratif juga ditambah analisis kritis (mencari struktur tersembunyi). Menekankan relevansi konteks (tak segan modifikasi interpretasi agama sesuai konteks dengan metode ijtihad baru misalnya).
- Frikatifisasi: Kontemplatif, sufistik, dialog dalam diam, makna lewat getaran[127]. Metode non-linear. Belajar melalui riyadah (latihan spiritual), hal (penghayatan), bukan semata diskusi verbal. Mungkin mendekati metode seni atau meditasi, jauh dari tradisi saintifik klasik. Bagi yang tidak terbiasa, ini nyaris bukan “metode” dalam pengertian biasa, melainkan pengalaman pribadi yang tak bisa di-skema-kan.
Kelemahan dan Kritik (Ringkas)
- Islamisasi: Normatif, sulit diaplikasi empiris[120]; kadang terlalu utopia ingin Islam jawab semua padahal praktek saintifik terbatas; riskan menutup diri dari hal bermanfaat non-Islami.
- Integrasi: Berisiko pragmatis, operasionalisasi kerap kabur[75]; tergantung kualitas pelaksana – bisa jadi cuma tempelan tanpa substansi; kritik kurang mendalam ke ideologi sains.
- Interkoneksi: Sangat luas, implementasi rumit; memerlukan perubahan mindset dan struktur; mungkin kurang tajam lawan hegemoni karena sibuk jalin relasi (namun ini debatabel, interkoneksi bisa juga dipakai melawan dominasi dengan memperkuat suara marjinal).
- Frikatifisasi: Baru dan simbolik[92]; rawan dianggap tidak ilmiah; perlu dukungan agar tidak hilang; tantangan metodologi besar.
Tabel ringkas perbandingan bisa dibuat, namun dalam makalah ini penjabaran naratif di atas kiranya cukup menggambarkan posisi masing-masing paradigma.
Secara umum, Islamisasi dan Frikatifisasi cenderung Islam-centric (satu di level syariat, satu di level hakikat spiritual), sementara Integrasi dan Interkoneksi lebih dialogic-centric (satu dialog Islam-sains, satu dialog multi bidang). Islamisasi dan Integrasi masih dalam kerangka mengokohkan disiplin keilmuan formal, sementara Interkoneksi dan Frikatifisasi mencoba menerobos batas formal (interkoneksi ke multi disiplin, frikatif ke dimensi ruhani).
Menariknya, meskipun tampak berbeda arah, keempatnya bisa dilihat sebagai tahapan atau spektrum berkesinambungan. Boleh jadi, sebuah PTKIN tidak harus memilih satu dan meninggalkan yang lain; bisa memetik unsur terbaik dari tiap paradigma. Misalnya, Islamisasi memastikan landasan tauhid kuat, integrasi memastikan kita menguasai sains, interkoneksi memastikan keterbukaan dialog dan kepedulian sosial, dan frikatifisasi memastikan ruh spiritual tidak hilang.
Penutup: Refleksi Arah Masa Depan Keilmuan PTKIN
Kilas balik evolusi paradigma keilmuan di PTKIN menunjukkan perjalanan dinamis dari tradisi normatif menuju pencarian sintesis dan kedalaman baru. Masing-masing paradigma lahir sebagai jawaban atas tantangan spesifik zaman: Islamisasi Ilmu menjawab tantangan sekularisasi ilmu dengan kembali ke tauhid[23]; Integrasi Ilmu merespons kebutuhan muslim menguasai sains modern tanpa kehilangan iman[2]; Interkoneksi Ilmu muncul agar ilmu di PTKIN lebih relevan menyikapi kompleksitas sosial-budaya dan mengatasi fragmentasi disiplin[141]; dan Frikatifisasi Ilmu diusulkan untuk mengisi kekosongan spiritual di tengah kepadatan wacana akademik, membawa dimensi ruhani ke pusat panggung[95].
Arah masa depan keilmuan PTKIN kemungkinan tidak akan terikat secara eksklusif pada satu paradigma, melainkan berupa sintesis kreatif. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap paradigma membawa sumbangan berharga sekaligus keterbatasan. Paradigma Islamisasi memberi kita kebanggaan identitas dan filter akidah yang kuat, tetapi perlu dilengkapi dengan keluasan wawasan integratif agar tidak terjebak eksklusivisme. Paradigma Integrasi telah membuka gerbang kemajuan ilmiah di kampus Islam, namun harus terus dijaga agar tidak kehilangan roh religius – di sinilah pentingnya elemen frikatif (spiritualitas) masuk. Paradigma Interkoneksi mengajarkan kerendahan hati intelektual bahwa kebenaran punya banyak sisi; ini menghindarkan kita dari fanatisme ilmiah maupun agamis. Dan akhirnya, Paradigma Frikatifisasi mengingatkan bahwa ilmu tanpa nurani hanyalah data hampa – ia menawarkan visi ilmu yang menghidupkan jiwa, bukan sekadar mengisi otak.
Masa depan PTKIN idealnya memadukan kekuatan semua pendekatan tersebut menjadi paradigma keilmuan integral yang holistik. Kita bisa membayangkan kerangka keilmuan yang tauhidik-spiritual, namun juga empiris-rasional, kontekstual-humanis, dan transformatif. Misalnya, kurikulum PTKIN di masa datang mungkin akan memasukkan kurikulum spiritual (riyadhah) bagi mahasiswa sains, sebagaimana mahasiswa syariah diwajibkan belajar metodologi penelitian modern. Kolaborasi riset tidak hanya lintas ilmu tetapi juga lintas dimensi – melibatkan analisis data sekaligus tafakkur dan etika. Publikasi ilmiah pun bisa memperhitungkan dimensi kemaslahatan batin, tidak melulu novelty duniawi.
Tentu, tantangan global seperti digitalisasi, kecerdasan artifisial, dan disrupsi lainnya akan menguji paradigma-paradigma ini. PTKIN perlu terus berinovasi. Mungkin akan muncul paradigma baru lagi yang menyesuaikan dengan era (misal Islamisasi 2.0 di era AI, atau eco-theology integration menghadapi krisis iklim). Namun, benang merahnya tetap: menjaga agar ilmu di PTKIN berakar pada nilai Islam, berbuah untuk kemanusiaan. Sebagaimana disinggung dalam makalah Muqowim (2021), seluruh UIN sepakat pentingnya membangun tradisi baru dengan paradigma integratif yang beranjak dari konsep filosofis menuju penerapan praktis[141].
Akhir kata, refleksi ini menunjukkan bahwa paradigma keilmuan bukanlah sesuatu yang stagnan. Ia terus tumbuh, seperti pohon ilmu yang mengembangkan tunas baru[142]. PTKIN sebagai laboratorium intelektual Islam seharusnya tidak gentar bereksperimen meramu paradigma. Selama berpegang pada tauhid dan niat mencari ridha-Nya, berbagai pendekatan dapat saling melengkapi. Paradigma Ilmu di PTKIN masa depan kemungkinan bersifat hybrid, memadukan keunggulan Islamisasi, Integrasi, Interkoneksi, Frikatifisasi, dan mungkin lainnya, dalam suatu ekosistem keilmuan yang unggul secara akademik, kaya secara spiritual, dan relevan secara sosial. Dengan itu, diharapkan PTKIN mampu melahirkan ulama-intelektual dan ilmuwan-ruhaniawan yang benar-benar menjadi lokomotif kemajuan umat di era modern, tanpa kehilangan arah pada cahaya Ilahi sebagai pemandu.
Sekian. Semoga kajian ini menjadi kontribusi bagi perbincangan berkelanjutan tentang arah pengembangan keilmuan di lingkungan PTKIN dan dunia Islam pada umumnya.
Referensi:
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (2025). PKDP 2025: Kilas Balik Paradigma Keilmuan PTKIN. Materi presentasi, 24 Juli 2025[3][31].
- Abdullah, M. Amin (2006). Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar[48].
- Al-Attas, Syed M. Naquib (1978). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ABIM[23].
- Al-Faruqi, Ismail Raji (1982). Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. Herndon, VA: IIIT[22][143].
- Muqowim (2021). “Revisiting Islamic Studies: Cementing Bases for Integrating Science and Religion in Islamic Higher Educational Institutions.” Jurnal Pendidikan Agama Islam, 18(1), 1–20[2][141].
- Tarmizi M. Jakfar et al. (2019). “Model Integrasi Ilmu dan Pengembangannya di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan UIN Sumatera Utara.” Jurnal Islam Futura, 18(2)[71][72].
- Situs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – Filosofi Pendidikan Ulul Albab (diakses 2025)[32][54].
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (2025). “Paradigma Frikatifisasi Ilmu: Hembusan Kosmik dalam Arsitektur Keilmuan Islam.” KBA Official Website, July 28, 2025[95][106].
- Wikipedia (2025). “Islamization of Knowledge.” Wikipedia (accessed Aug 2025)[18][22].
- Parluhutan Siregar (2020). “Integrasi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah.” Jurnal Al-Aqidah, 10(2)[49][86].
[1] [2] [14] [15] [48] [70] [141] Revisiting Islamic Studies: Cementing Bases for Integrating Science and Religion in Islamic Higher Educational Institutions | Jurnal Pendidikan Agama Islam
https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/2021.181-01
[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [16] [17] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [36] [37] [39] [43] [44] [45] [46] [50] [51] [52] [53] [57] [58] [59] [62] [63] [64] [65] [67] [73] [74] [75] [76] [78] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [98] [101] [102] [103] [108] [114] [115] [116] [117] [119] [120] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] PKDP 2025.pdf
file://file-5mS7evepAphr6zWxyxaBjb
[18] [19] [20] [21] [22] [38] [129] [143] Islamization of knowledge – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamization_of_knowledge
[23] [40] [41] [42] iseas.edu.sg
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/06/TRS16_21.pdf
[32] [33] [34] [35] [54] [60] [61] [66] [68] [69] [142] Filosofi Pendidikan – Program Studi Sastra Inggris
https://bsi.uin-malang.ac.id/filosofi-pendidikan/
[47] [71] [72] MODEL INTEGRASI ILMU DAN PENGEMBANGANNYA DI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH DAN UIN SUMATERA UTARA | Jakfar | Jurnal Ilmiah Islam Futura
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3765
[49] Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan | Fathir
https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/13
[55] [56] [79] [86] [87] ISI.pmd
https://media.neliti.com/media/publications/155451-ID-integrasi-ilmu-ilmu-keislaman-dalam-pers.pdf
[77] Gambar 3. Integrasi Keilmuan Pohon Ilmu – ResearchGate
https://www.researchgate.net/figure/Gambar-3-Integrasi-Keilmuan-Pohon-Ilmu_fig1_379239658
[95] [96] [97] [99] [100] [104] [105] [106] [107] [109] [110] [111] [112] [113] [118] [121] [128] Paradigma Frikatifisasi Ilmu: Hembusan Kosmik dalam Arsitektur Keilmuan Islam – Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
https://www.kba13.com/paradigma-frikatifisasi-ilmu-hembusan-kosmik-dalam-arsitektur-keilmuan-islam/


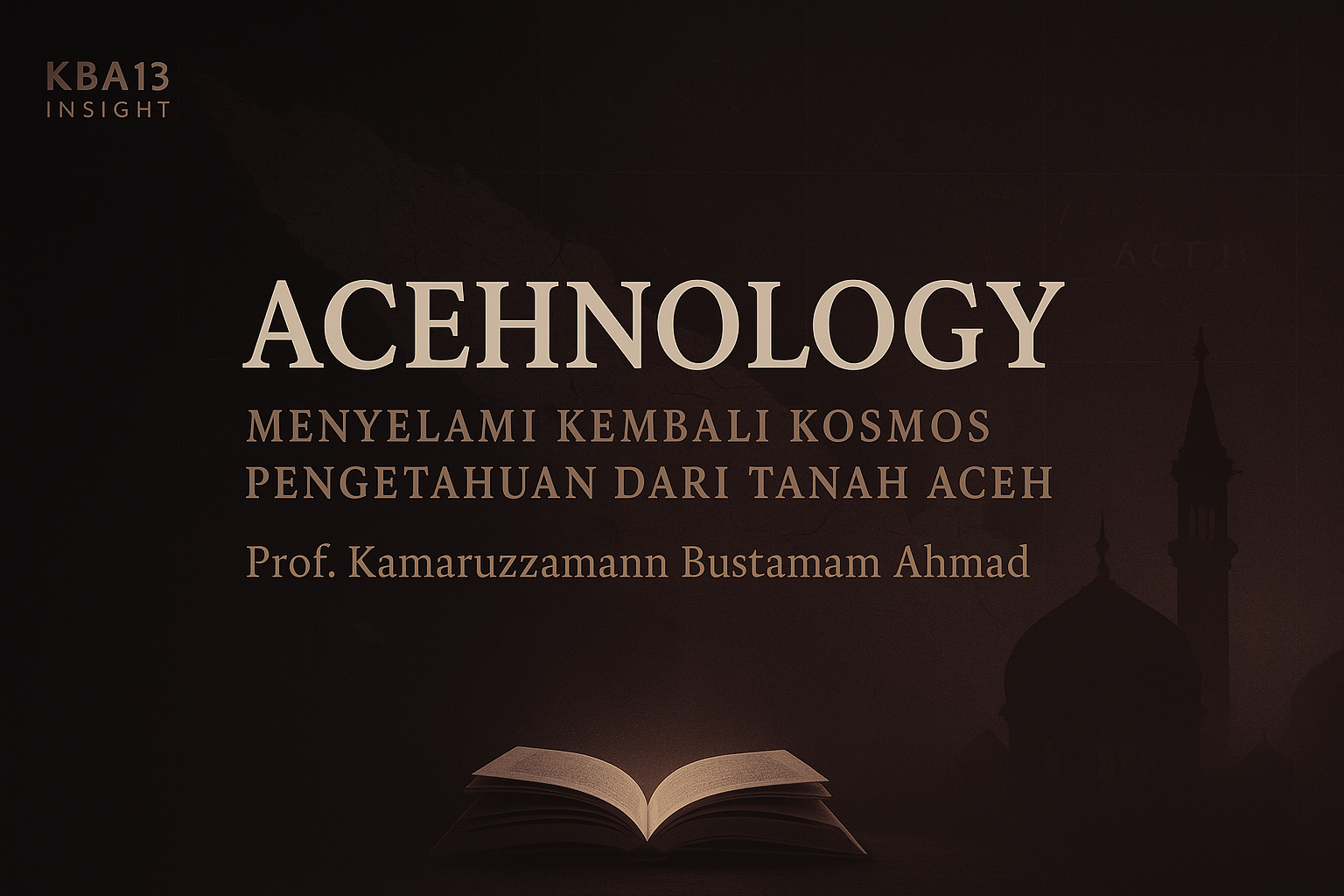
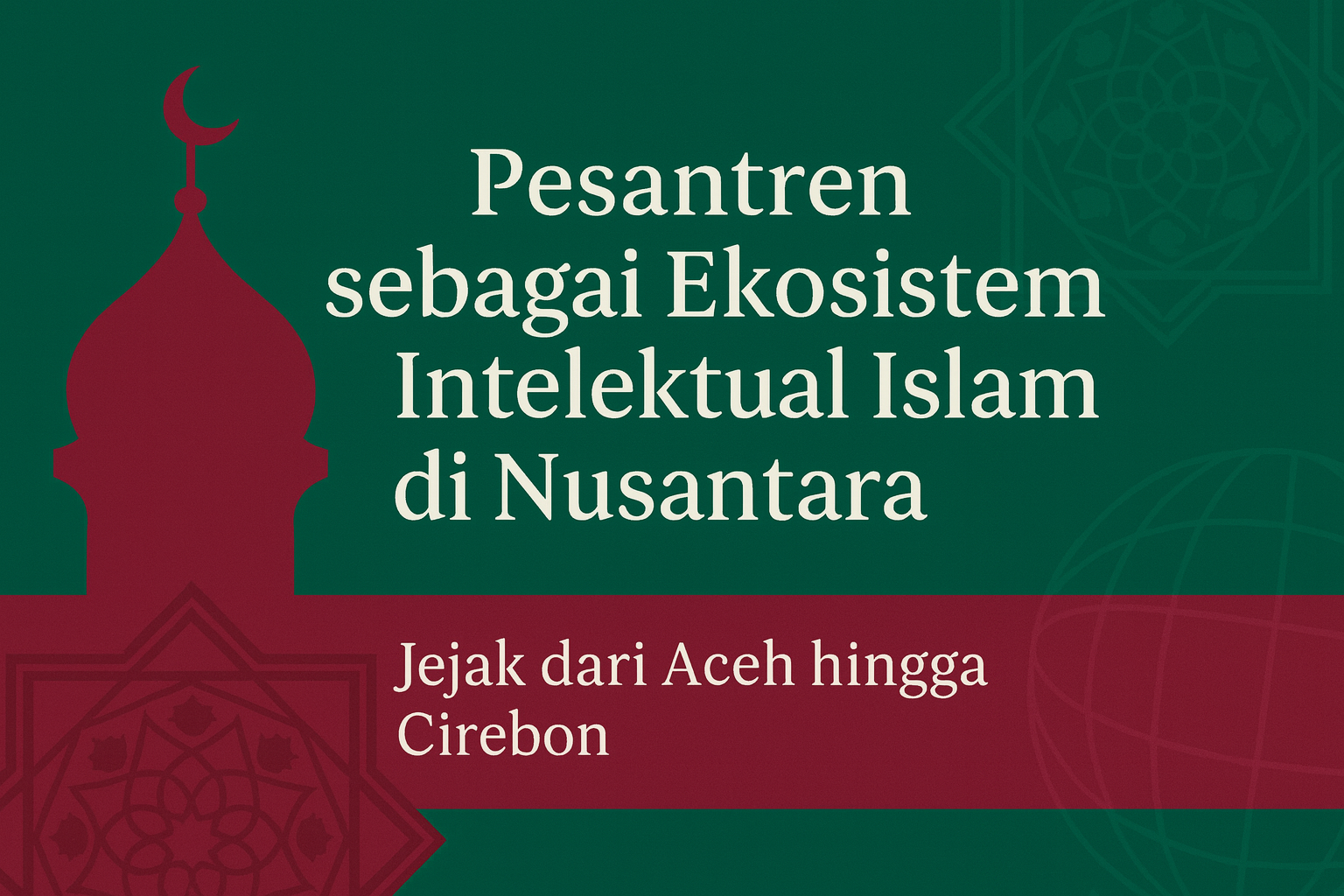
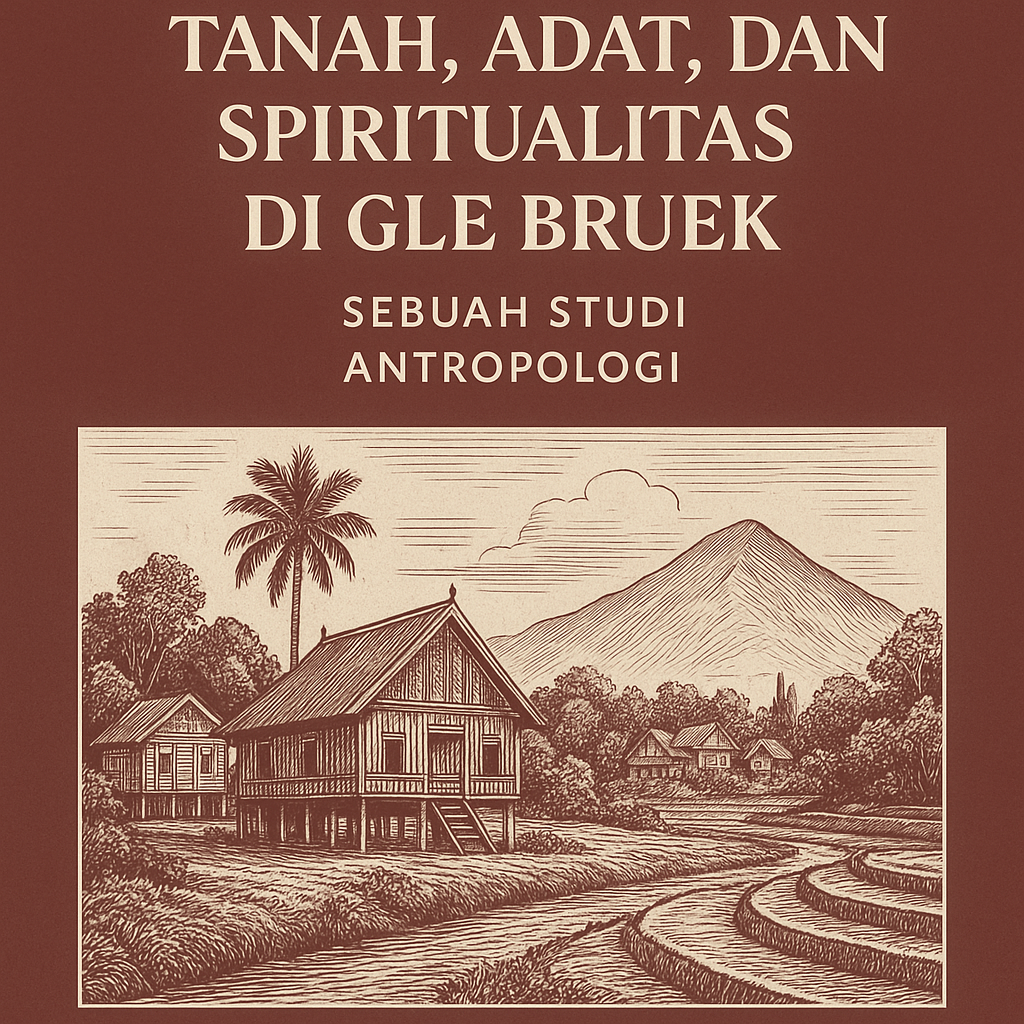


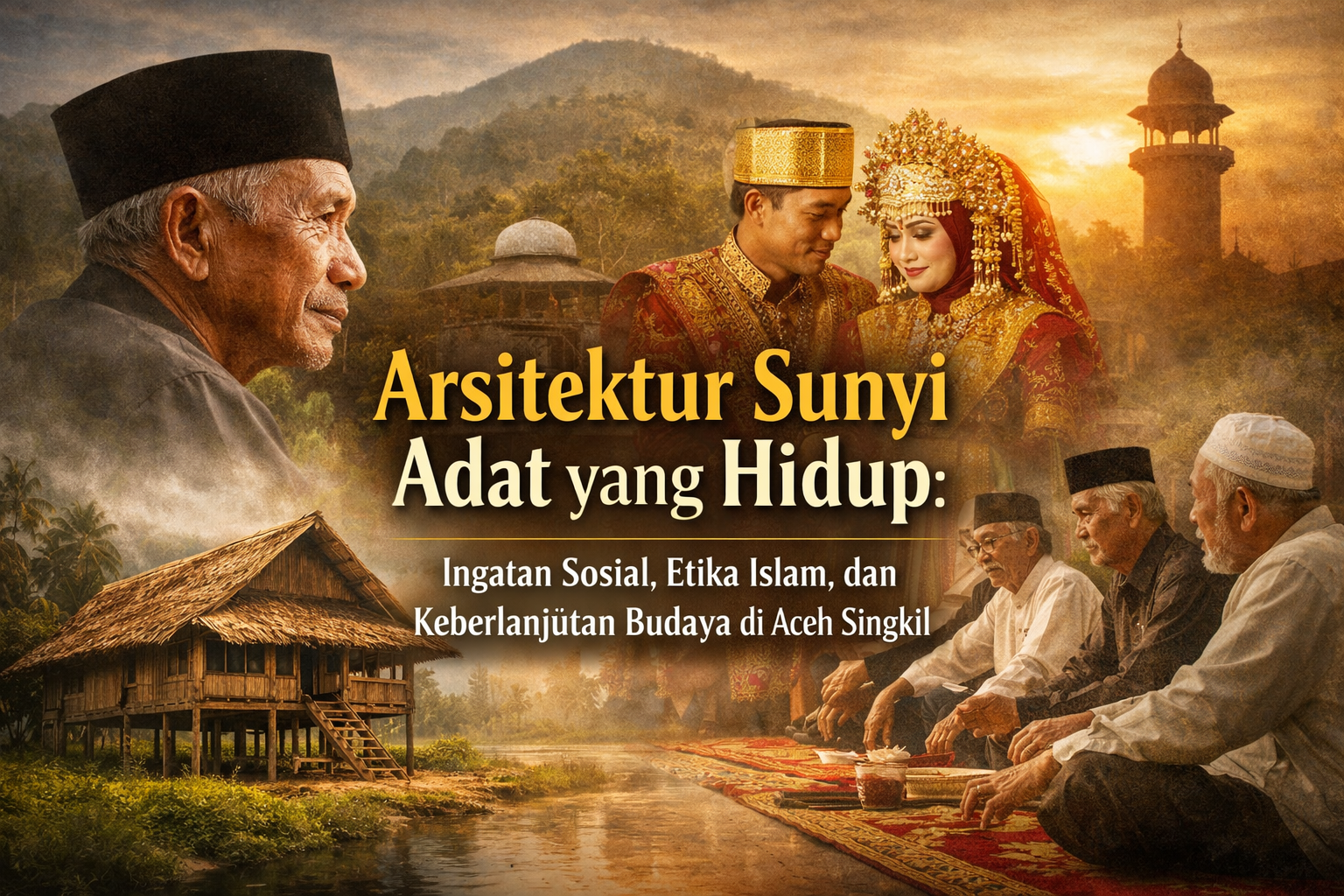
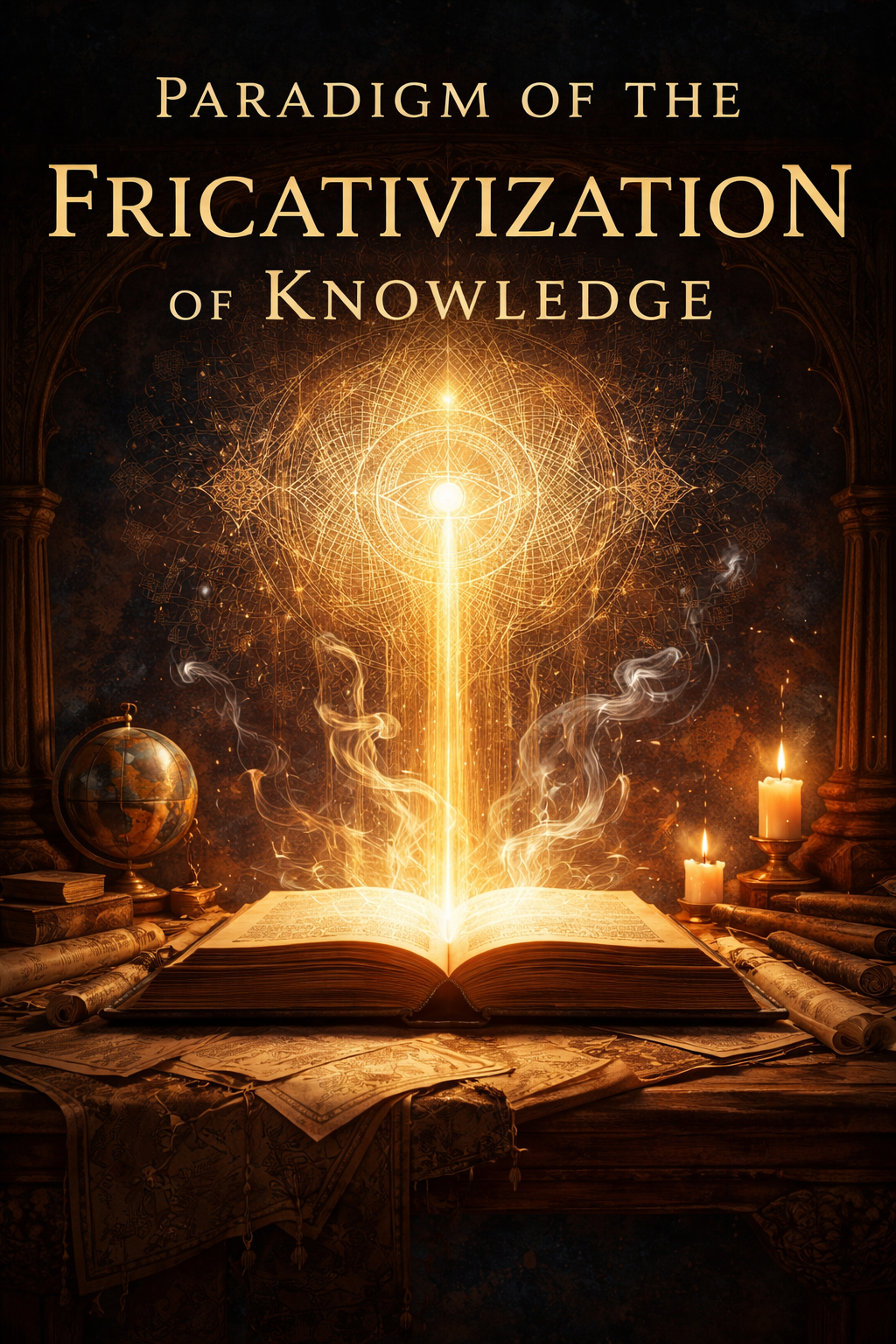
Leave a Reply