Pendahuluan
Dalam lanskap intelektual Indonesia kontemporer, refleksi filosofis tentang identitas nasional dan kebudayaan lokal seringkali dikaburkan oleh tuntutan praktis zaman: efisiensi, pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Namun, di tengah arus deras tersebut, hadir sebuah karya yang mengajak kita untuk sejenak menoleh ke dalam, merenung, dan bertanya: Siapakah kita sebagai manusia Indonesia? Buku “Manusia dan Budaya Indonesia“, hasil dari Simposium Internasional Filsafat Indonesia, bukan sekadar bunga rampai pemikiran. Ia adalah laboratorium diskursif tempat para pemikir, filsuf, dan budayawan berefleksi tentang makna terdalam dari keberadaan manusia Indonesia dalam pusaran sejarah, tradisi, dan modernitas.
Dalam membaca buku ini, saya merasa seakan diajak ke dalam semacam “maqam epistemologis”, di mana setiap bab merupakan stasiun spiritual-intelektual untuk memaknai bukan hanya Indonesia sebagai entitas geopolitik, tapi sebagai ruh budaya yang hidup dan berdinamika.
Filsafat Indonesia: Sebuah Keraguan yang Produktif
Sejak awal buku ini tidak mencoba menawarkan definisi tunggal atau final tentang apa itu “Filsafat Indonesia”. Justru dari keraguan itulah kekuatannya muncul. Kita dihadapkan pada kesadaran bahwa filsafat tidak selamanya harus terikat pada sistem rasionalistik Barat. Dalam konteks Indonesia, filsafat adalah pergumulan antara logos dan ethos, antara rasio dan rasa, antara sejarah dan mitos.
Karlina Supelli, dalam esainya yang reflektif, menunjukkan bahwa berpikir tentang manusia Indonesia berarti masuk ke dalam lanskap paradoks. Indonesia bukan entitas tunggal, melainkan jaringan heterogen dari ribuan budaya, bahasa, dan sistem nilai. Di sini, kita melihat bagaimana filsafat tidak lagi dimaknai sebagai pencarian logis atas kebenaran universal, tetapi sebagai praktik pemaknaan atas keragaman eksistensial.
Filsafat Indonesia, dalam pembacaan saya terhadap buku ini, adalah filsafat dalam pluralitas, filsafat yang tidak malu terhadap irasionalitas, terhadap mitos, terhadap getaran spiritual yang sering kali dilepaskan oleh filsafat modern.
Pramoedya Ananta Toer: Narasi Luka sebagai Sumber Hikmah
Esai pertama karya Dr. Étienne Naveau tentang Pramoedya Ananta Toer adalah sebuah provokasi epistemik yang penting. Kita terbiasa membaca Pram sebagai sastrawan realis, sebagai saksi sejarah. Namun Naveau membongkar lapisan-lapisan teks Pram sebagai ekspresi dari filsafat eksistensial Indonesia.
Pramoedya bukan sekadar penulis. Ia adalah filsuf luka. Dari penjara, dari pengasingan, dari pengkhianatan negara atas warganya, Pram justru merumuskan manusia Indonesia bukan dari puncak ide, tapi dari dasar penderitaan. Dalam konteks ini, Pram menjadi penantang keras terhadap institusi agama yang membungkam, terhadap negara yang membunuh narasi-narasi alternatif, dan terhadap budaya yang terlalu nyaman dalam konservatisme.
Naveau berhasil menunjukkan bahwa filsafat agama di Indonesia tidak harus bersumber dari teks-teks normatif, tetapi bisa tumbuh dari pengalaman historis, dari resistensi kultural, dan dari kesadaran eksistensial yang mengakar.
Heraty dan Arsitektur Etos Nusantara
Nama Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi tidak bisa dilewatkan dalam pembacaan ini. Heraty bukan sekadar akademisi; ia adalah penyair yang berpikir, dan pemikir yang puitis. Dalam esainya, ia memetakan sosok manusia Indonesia bukan dalam kategori sosiologis, tetapi dalam kerangka arsitektural-kultural.
Bagi Heraty, manusia Indonesia hidup dalam lapisan-lapisan kontradiksi: spiritual tetapi hedonis, ramah tetapi penuh kekerasan simbolik, toleran tetapi juga eksklusif. Heraty tidak mengutuk kontradiksi ini. Ia justru menjadikannya sebagai modal epistemik untuk memahami Indonesia sebagai entitas yang tidak pernah selesai.
Dalam filsafat Heraty, perempuan, tubuh, dan budaya menjadi medan artikulasi filsafat. Ia menggugat patriarki epistemologis dan menghadirkan cara pandang yang lebih holistik dan organis.
Baskara Wardaya: Nasionalisme sebagai Proyek Etis
Dr. Baskara T. Wardaya, SJ, melalui pendekatan historis-filosofis, menyelami awal republik dan menyuguhkan tafsir baru tentang etika kebangsaan. Ia tidak sedang berbicara tentang nasionalisme dalam arti formalistik, tetapi tentang habitus berpikir para pendiri bangsa.
Wardaya mengajak kita kembali membaca Soekarno, Tan Malaka, Sjahrir, dan tokoh lainnya sebagai filsuf politis, bukan sekadar aktivis kemerdekaan. Dalam pandangan mereka, republik bukan produk hukum semata, tetapi ruang etik tempat manusia Indonesia bertumbuh, berpikir, dan merdeka.
Namun ia juga menegaskan bahwa republik ini telah kehilangan ruhnya. Demokrasi telah menjadi administrasi, nasionalisme menjadi seremoni. Buku ini, melalui tulisan Wardaya, menjadi napas profetik untuk menghidupkan kembali republik sebagai ruang pembebasan, bukan penindasan.
Islam dan Rasionalitas Nusantara
Kontribusi Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer menjadi sangat penting di tengah arus debat tentang Islam dan keindonesiaan. Ia tidak terjebak dalam dikotomi antara Islam tekstual dan Islam kultural. Sebaliknya, ia menawarkan pembacaan tentang Islam sebagai kekuatan intelektual dan spiritual yang menyatu dalam budaya.
Kautsar menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak harus inferior di hadapan filsafat Barat. Justru melalui tokoh seperti Hamka, Nurcholish Madjid, dan HOS Tjokroaminoto, ia menunjukkan bahwa Islam Nusantara memiliki rasionalitasnya sendiri: rasionalitas yang puitis, mistis, tetapi tetap kritis.
Tulisan ini memperlihatkan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah yang reflektif. Ia bukan Islam politik semata, bukan pula Islam konservatif, tapi Islam yang mencari kebijaksanaan dalam kompleksitas budaya.
Tan Malaka dan Logika Mistika: Rasionalitas Alternatif
Tulisan Dr. Thomas Hidya Tjaya tentang Tan Malaka adalah penutup yang sangat menggugah. Ia menantang pembacaan Tan sebagai sosok kiri ortodoks, dan justru menekankan sisi mistis dan transendental dari pemikirannya. Logika mistika yang dikembangkan Tan adalah titik temu antara pengalaman spiritual dan perjuangan revolusioner.
Dalam hal ini, filsafat Indonesia bukan hanya tentang kebijaksanaan lokal atau nilai-nilai adat, tetapi juga tentang perlawanan epistemologis terhadap modernitas Barat yang hegemonik.
Logika mistika Tan Malaka adalah cara berpikir yang tidak bisa dipetakan oleh Cartesianisme. Ini adalah bentuk lain dari rasionalitas: yang tidak memisahkan antara akal dan intuisi, antara analisis dan keimanan.
Refleksi Penutup: Filsafat sebagai Ziarah Budaya
Sebagai seorang akademisi yang lama bergelut dalam dunia pemikiran Islam, antropologi budaya, dan spiritualitas Nusantara, saya melihat bahwa buku ini tidak hanya penting, tetapi mendesak. Di tengah krisis identitas, di mana generasi muda kehilangan orientasi dan elite akademik terlalu sibuk mengejar indeks sitasi, buku ini hadir sebagai napas kontemplatif untuk mengingat kembali siapa kita.
Manusia dan Budaya Indonesia adalah ajakan untuk bertanya ulang: apakah kita masih mampu berpikir dari dalam, atau kita hanya menjadi pengguna teori dari luar?
Buku ini bukan hanya refleksi, tapi juga perlawanan diam-diam terhadap kolonialisme intelektual.
Menuju Filsafat Nusantara yang Emansipatif
Apa yang ingin saya tekankan dalam ulasan ini adalah bahwa buku ini berhasil membuka ruang baru bagi kita untuk menyusun filsafat yang tidak malu terhadap akar budayanya. Sebuah filsafat yang tidak harus seragam, tidak harus sistematik, tapi mampu menangkap denyut spiritual, sosial, dan historis masyarakatnya.
Filsafat Nusantara adalah filsafat yang lahir dari sawah dan pesantren, dari pura dan pasar, dari zikir dan keris, dari kidung dan hikayat. Ia adalah filsafat yang mendengarkan.
Dan buku ini, dalam segala keragaman penulis dan pendekatannya, telah memberi kita fondasi awal untuk membangun filsafat seperti itu.

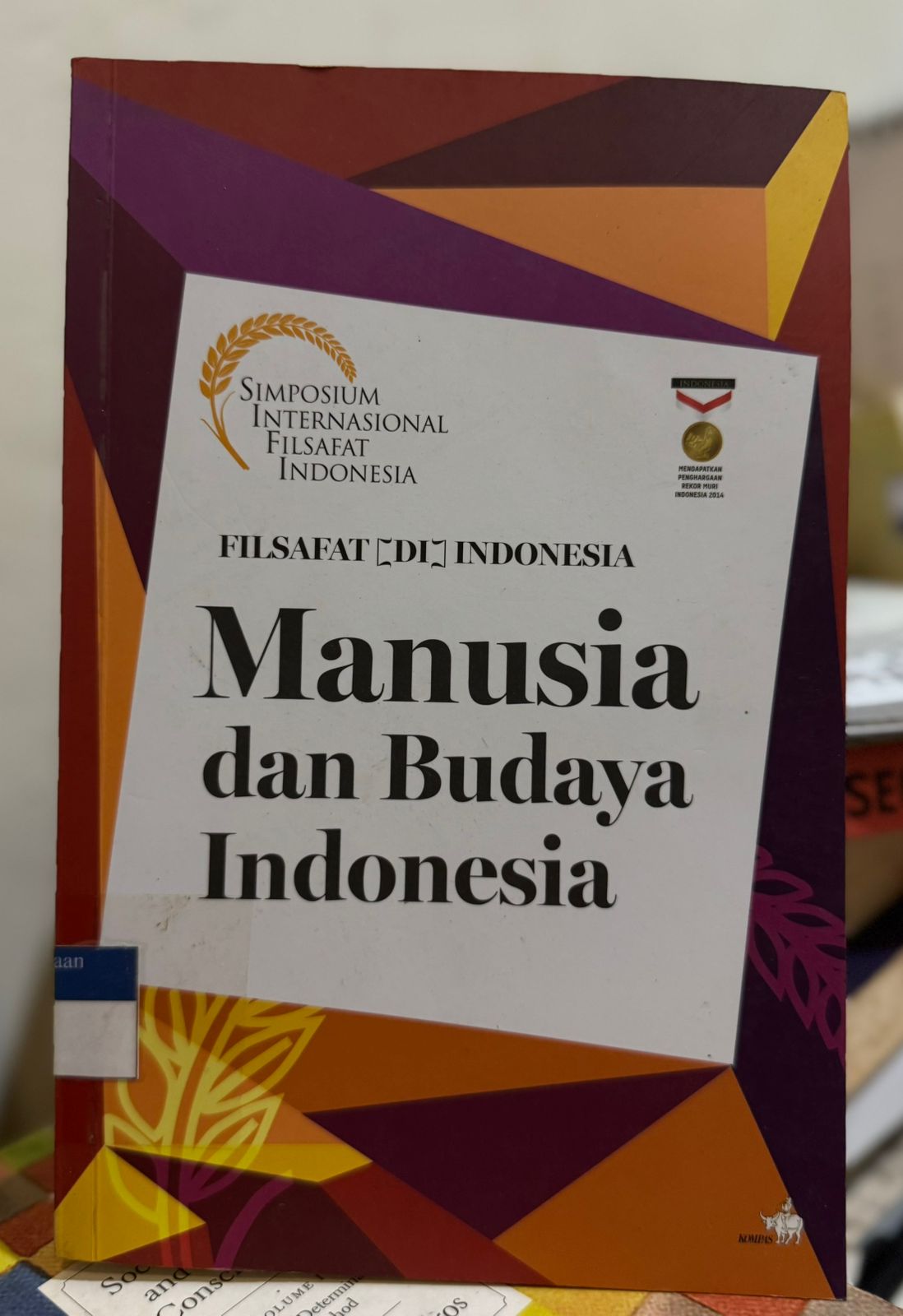

Leave a Reply