Pendahuluan
Kerukunan bukanlah sekadar keadaan di mana konflik tidak terdengar, melainkan kondisi di mana tatanan sosial mampu bertahan, beradaptasi, dan memelihara kohesi dalam tekanan yang terus berubah. Dalam terminologi keamanan manusia (human security), kerukunan adalah stability buffer—bantalan strategis yang mencegah tekanan politik, ekonomi, atau ideologis dari berubah menjadi krisis terbuka. Ia bukan hanya hasil dari tradisi atau kebiasaan, tetapi sebuah arsitektur sosial yang secara sadar dirancang, dipelihara, dan diperbarui sesuai dengan perubahan lanskap ancaman.
Di Indonesia, narasi kerukunan sering dibungkus dalam retorika persatuan dan harmoni, namun sejarah memperlihatkan bahwa harmoni yang tidak dikelola bisa rapuh. Konflik komunal, gesekan identitas, dan rivalitas politik lokal sering kali meletup di titik-titik di mana trust infrastructure lemah. Desa sebagai unit sosial-politik terendah menjadi early warning system—di sinilah tanda-tanda degradasi kerukunan pertama kali dapat terbaca, sebelum merambat ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional.
Program Desa Sadar Kerukunan yang digagas Kementerian Agama bukanlah sekadar proyek sosialisasi nilai, tetapi merupakan intervensi strategis pada simpul terkecil jaringan sosial nasional. Pendekatan ini menempatkan desa bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai hub produksi narasi dan norma kerukunan. Dengan demikian, desa berfungsi ganda: sebagai medan aktual interaksi sosial dan sebagai simpul distribusi nilai yang bisa memperkuat atau melemahkan integrasi bangsa.
Namun, medan kerukunan telah berubah secara fundamental. Ruang interaksi masyarakat kini terbagi antara domain fisik dan domain digital—dua ekosistem yang saling memengaruhi, tetapi memiliki logika dan kerentanannya sendiri. Di domain fisik, hubungan sosial masih diatur oleh hierarki, tatap muka, dan pengawasan sosial langsung. Sebaliknya, domain digital memungkinkan interaksi tanpa batas, tetapi juga memfasilitasi disinformasi, echo chamber, dan polarisasi yang beroperasi di luar kendali norma lokal. Inilah yang disebut oleh Floridi (2014) sebagai infosphere—lingkungan informasi yang kini menjadi ruang hidup manusia, sama nyatanya dengan lingkungan fisik.
Kerukunan desa di era ini berada di persimpangan: di satu sisi, ia dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jaringan sosial, mempercepat koordinasi, dan mengedukasi warga. Di sisi lain, ia berisiko terekspos pada pathogens sosial baru—hoaks, ujaran kebencian, manipulasi identitas—yang dapat membusukkan kohesi dari dalam. Fenomena ini sejalan dengan analisis Sunstein (2017) mengenai information cascades yang dapat membuat informasi palsu mengakar sebagai kebenaran di benak publik, bahkan ketika bukti sebaliknya tersedia.
Oleh karena itu, membangun kerukunan desa pada abad ke-21 memerlukan pendekatan yang melampaui retorika moral atau seruan normatif. Ia harus dirancang sebagai sistem ketahanan sosial adaptif yang menggabungkan tiga unsur pokok: resilience berbasis modal sosial lokal, literasi digital yang memadai untuk memfilter ancaman kognitif, dan kebijakan publik yang memfasilitasi koordinasi lintas domain. Sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (2000), keberhasilan sebuah komunitas dalam mempertahankan kerukunan bergantung pada kekuatan bonding social capital (ikatan internal) dan bridging social capital (jembatan dengan kelompok lain). Desa yang hanya memiliki ikatan internal yang kuat tanpa jembatan eksternal akan rawan menjadi enclave eksklusif yang mudah dimanipulasi.
Makalah ini akan membedah kerukunan desa dari perspektif multidisipliner—menggabungkan sosiologi, antropologi, studi agama, dan teori komunikasi strategis—untuk merumuskan model kerukunan yang relevan dengan tantangan kontemporer. Fokus akan diberikan pada identifikasi ancaman nyata di domain fisik dan digital, pemetaan sumber daya lokal yang dapat diaktifkan untuk membangun ketahanan, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Tinjauan Konseptual
2.1. Kerukunan sebagai Strategic Construct
Dalam wacana publik, kerukunan sering direduksi menjadi kondisi sosial yang “tenang” atau “tidak ada gesekan”. Padahal, dari sudut pandang strategic studies, kerukunan adalah sebuah strategic construct: sebuah tatanan nilai, norma, dan perilaku yang dibangun untuk menjaga stability buffer di tengah arus kompetisi dan perbedaan kepentingan. Kerukunan bukan sekadar keadaan alamiah, melainkan hasil dari rekayasa sosial yang memanfaatkan modal sosial, kontrol narasi, dan manajemen risiko konflik.
Secara teoritis, konsep kerukunan dapat diuraikan dalam tiga dimensi:
-
Kerukunan Struktural – dihasilkan oleh sistem hukum, regulasi, dan kebijakan publik yang mengatur interaksi antarindividu dan kelompok. Ini mencakup keberadaan institusi mediasi, sistem peradilan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus.
-
Kerukunan Kultural – berakar pada norma, adat istiadat, dan nilai-nilai bersama yang membentuk persepsi warga tentang hubungan ideal. Nilai ini sering diwariskan lintas generasi dan dipengaruhi oleh agama, sejarah lokal, dan simbol-simbol budaya.
-
Kerukunan Interpersonal – dibangun melalui interaksi sehari-hari, jejaring informal, dan perilaku kolektif. Inilah tingkat paling rentan, karena bergantung pada dinamika hubungan antarwarga yang dapat berubah cepat akibat provokasi atau disinformasi.
Dalam literatur sosiologi, kerukunan berhubungan erat dengan social cohesion (Chan et al., 2006) yang mencakup rasa memiliki (sense of belonging), partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas, dan kepercayaan antarwarga (interpersonal trust). Tanpa ketiga unsur ini, kerukunan akan rapuh meskipun secara permukaan tampak tenang.
2.2. Desa sebagai Arena Kerukunan
Desa dalam struktur sosial-politik Indonesia bukan sekadar unit administratif, melainkan arena kerukunan. Desa adalah ruang di mana identitas, kekuasaan, dan sumber daya saling bertemu, sekaligus menjadi tempat di mana konflik dan konsensus diuji.
Dalam konteks Desa Sadar Kerukunan, desa berperan sebagai filter sekaligus amplifier. Ia dapat menyaring masuknya ide-ide dan narasi eksternal yang berpotensi memecah belah, tetapi juga dapat memperbesar efeknya jika narasi tersebut sejalan dengan sentimen lokal. Di sinilah pentingnya local wisdom integration—penggunaan nilai dan norma lokal sebagai pagar kognitif.
Kearifan lokal di banyak desa Indonesia mengandung informal early warning systems untuk mendeteksi tanda-tanda disharmoni, seperti berkurangnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, meningkatnya gosip negatif di ruang publik, atau absennya tokoh kunci dalam acara komunitas. Namun, mekanisme ini kini terancam erosi akibat dua faktor utama: urbanisasi yang mengubah struktur demografi desa, dan penetrasi media digital yang mengalihkan interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang maya.
2.3. Pergeseran dari Domain Fisik ke Domain Digital
Kerukunan tradisional dibangun melalui face-to-face interaction yang memungkinkan kontrol sosial langsung. Namun, dengan migrasi sebagian besar percakapan publik ke media sosial, dinamika kerukunan memasuki domain yang kurang dapat diawasi.
Di domain digital, identitas sering kali disamarkan, sehingga akuntabilitas melemah. Menurut studi Oxford Internet Institute (2022), anonimitas dan algoritme platform dapat menciptakan polarisasi yang lebih ekstrem dibandingkan interaksi tatap muka. Konten yang memicu emosi marah atau takut cenderung lebih cepat viral, menciptakan amplification effect terhadap narasi yang memecah belah.
Fenomena online-offline spillover membuat konflik digital dapat dengan cepat masuk ke ruang fisik. Misalnya, perdebatan di grup WhatsApp desa mengenai isu agama atau politik lokal dapat memicu ketegangan nyata di rapat warga. Ini mengubah kerukunan menjadi sesuatu yang harus dijaga secara simultan di dua medan tempur: offline dan online.
2.4. Kerukunan di Era Post-Truth
Era post-truth, sebagaimana didefinisikan oleh Keyes (2004) dan diangkat oleh Oxford Dictionaries (2016), adalah era di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih memengaruhi opini publik dibandingkan fakta objektif. Dalam konteks ini, kerukunan menjadi semakin sulit dicapai karena konsensus fakta yang menjadi basis diskusi publik terfragmentasi.
Isu yang sebelumnya bisa diselesaikan melalui musyawarah berbasis data kini sering terjebak dalam narrative contestation. Pihak-pihak yang berseteru tidak lagi berdebat tentang solusi, melainkan tentang “realitas” itu sendiri. Inilah mengapa literasi kognitif (cognitive literacy) menjadi penting—bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan mengenali manipulasi informasi, bias kognitif, dan strategi framing yang digunakan untuk membentuk persepsi.
Analisis Tantangan Kerukunan Desa di Era Kontemporer
3.1. Patologi Sosial dan Fragmentasi Modal Sosial
Kerukunan desa menghadapi ancaman serius dari patologi sosial yang muncul akibat perubahan struktural dan kultural. Patologi ini meliputi:
-
Erosi Modal Sosial – Robert Putnam (2000) dalam Bowling Alone menunjukkan bahwa penurunan interaksi sosial tatap muka dapat melemahkan kepercayaan dan rasa saling memiliki di komunitas. Di banyak desa, arus urbanisasi, migrasi kerja, dan penetrasi budaya luar telah menggerus ikatan komunal yang dulunya kuat.
-
Segmentasi Sosial – Fragmentasi internal berdasarkan afiliasi agama, politik, atau ekonomi menciptakan micro-tribes di dalam desa. Menurut Fukuyama (2018), dalam masyarakat yang kehilangan kohesi, identitas sektoral menjadi dominan, sehingga kepentingan bersama semakin terpinggirkan.
-
Komodifikasi Relasi Sosial – Hubungan yang dulunya berbasis gotong royong kini cenderung bersifat transaksional. Fenomena ini memunculkan apa yang oleh Bauman (2000) disebut sebagai liquid modernity, di mana ikatan sosial bersifat cair, dangkal, dan mudah putus.
3.2. Jebakan Post-Modernisme dalam Kerukunan
Post-modernisme, dengan penekanan pada relativisme dan dekonstruksi narasi besar, memiliki implikasi ambivalen terhadap kerukunan. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi pluralitas pandangan dan toleransi terhadap perbedaan. Namun, di sisi lain, ia juga dapat melemahkan konsensus normatif yang diperlukan untuk membangun tatanan sosial.
Lyotard (1984) menyebut the death of grand narratives sebagai ciri utama post-modernisme. Dalam konteks desa, ini bisa berarti pudarnya nilai-nilai bersama yang dulunya mempersatukan komunitas—misalnya semangat gotong royong atau penghormatan pada tokoh adat/agama. Ketika tidak ada lagi shared moral horizon, upaya menjaga kerukunan menjadi lebih sulit karena setiap kelompok merasa berhak atas “versi kebenarannya” sendiri.
3.3. Ancaman di Ranah Digital: Polarisasi dan Disinformasi
Perubahan terbesar dalam lanskap kerukunan desa adalah masuknya digital realm sebagai arena baru interaksi sosial. Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok menjadi kanal utama komunikasi warga desa, namun juga menjadi jalur distribusi hoaks dan ujaran kebencian.
Studi Oxford Internet Institute (2023) mengonfirmasi bahwa jaringan disinformasi sering memanfaatkan isu agama, etnis, atau politik lokal untuk memicu konflik. Pola yang ditemukan di banyak kasus meliputi:
-
Amplifikasi Isu Sensitif – pesan provokatif diperkuat melalui forwarding chains di grup pesan tertutup.
-
Framing Bias – berita atau foto lama diolah kembali untuk mengesankan adanya ketegangan yang memerlukan reaksi cepat.
-
Echo Chambers – warga hanya berinteraksi dengan sumber informasi yang mengonfirmasi pandangan mereka, mempersempit ruang dialog.
3.4. Ancaman di Ranah Fisik: Kompetisi Sumber Daya dan Konflik Laten
Kerukunan di ranah fisik terancam oleh kompetisi sumber daya, terutama lahan, air, dan akses terhadap program bantuan pemerintah. Dalam teori resource mobilization (McCarthy & Zald, 1977), ketidakadilan distribusi sumber daya dapat menjadi katalisator konflik, terutama jika diperparah oleh ketidaktransparanan proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Selain itu, konflik laten sering berakar pada sejarah panjang rivalitas antar-keluarga atau kelompok. Konflik jenis ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi dapat dengan cepat muncul kembali ketika ada pemicu, seperti pilkades atau isu pembangunan yang dianggap menguntungkan satu pihak.
3.5. Interaksi Ranah Fisik dan Digital: The Hybrid Threat
Yang semakin mengkhawatirkan adalah munculnya ancaman hibrida (hybrid threat), di mana provokasi di ranah digital segera diterjemahkan menjadi aksi di ranah fisik. Misalnya, unggahan provokatif tentang dugaan penistaan agama di media sosial dapat memicu demonstrasi atau kerusuhan dalam hitungan jam.
Fenomena ini memperkuat argumen bahwa strategi kerukunan desa harus terintegrasi lintas domain, memantau dan merespons isu baik di ruang offline maupun online secara simultan. Tanpa integrasi ini, kebijakan akan selalu tertinggal dari dinamika ancaman yang bersifat real-time.
Model Baru Kerukunan Desa
Gagasan Model Baru Kerukunan Desa ini menempatkan desa sebagai ruang sosial yang dihidupi oleh empat pilar penyangga: aktor, isu, agama, dan budaya. Keempatnya bukanlah elemen yang bekerja sendiri-sendiri, tetapi membentuk jaringan interaksi yang dapat menghasilkan harmoni atau justru memicu konflik, tergantung pada pola relasi yang terbentuk.
Skenario I – Dimensi Aktor
Dalam skema yang disusun, kita melihat variasi posisi aktor yang membentuk lanskap kerukunan desa. Ada desa yang diwarnai oleh “aktor beragam, pikiran seragam”, sebuah kondisi di mana banyak figur berperan tetapi orientasi dan gagasannya serupa. Kondisi ini memudahkan koordinasi karena semua pihak berada dalam satu frekuensi, tetapi berisiko memunculkan groupthink sebagaimana diuraikan Janis (1972)—yakni kecenderungan untuk mengabaikan alternatif demi menjaga konsensus semu.
Berbeda dengan itu, ada pula desa yang dikendalikan oleh “aktor panglima, titahnya diterima”. Ini adalah tipologi otoritarian lokal, di mana satu figur dominan menetapkan arah kebijakan dan aktor lain hanya mengikutinya. Dari perspektif teori elit Pareto (1916), figur ini dapat menjadi stabilisator jika memiliki visi inklusif, tetapi dapat juga menjadi sumber stagnasi atau konflik laten jika otoritasnya tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas.
Skenario II – Dimensi Isu
Kerukunan desa juga dibentuk oleh bagaimana isu dimunculkan, dibicarakan, dan disepakati. Terdapat gambaran “isu bertahta, masyarakat rajin berkata”—yakni situasi ketika sebuah isu menjadi pusat perhatian publik dan mendorong warga untuk aktif membicarakannya. Jika isu itu relevan dan dikelola dengan transparan, partisipasi ini menjadi energi positif. Namun, jika isu hanya dibiarkan menjadi komoditas retorik, maka lahirlah situasi “isu disepakati, masyarakat dikhianati”—di mana konsensus formal tidak diikuti oleh realisasi di lapangan.
Kondisi ini selaras dengan teori agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) yang menegaskan bahwa pihak yang mengendalikan isu publik pada dasarnya mengendalikan prioritas kolektif. Desa memerlukan mekanisme yang memastikan bahwa isu yang dibawa ke ruang publik benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan agenda tersembunyi dari elite lokal.
Skenario III – Dimensi Agama
Agama dalam konteks desa memiliki potensi ganda: menjadi sumber inspirasi moral atau menjadi instrumen politik yang memotret spektrum itu dengan sangat jelas—mulai dari “agama dipakai, masyarakat digadai” hingga “agama diamalkan, masyarakat selamat” dan “agama dilupakan, masyarakat laknat”.
Dalam perspektif civil religion (Bellah, 1967), agama berfungsi sebagai fondasi moral kolektif yang dapat menjaga kerukunan lintas kelompok jika nilai universalnya dihidupkan. Namun, begitu agama direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan, ia dapat memperdalam polarisasi. Di tingkat desa, instrumentalitas agama sering kali terlihat pada masa kontestasi politik lokal, ketika simbol-simbol religius digunakan untuk memobilisasi dukungan tetapi dilepaskan kembali setelah tujuan tercapai.
Skenario IV – Dimensi Budaya
Budaya lokal adalah wadah identitas yang dapat mendorong kemajuan sosial jika dijalankan secara substantif, seperti dalam ungkapan “budaya dianjak, masyarakat mau beranjak”. Artinya, budaya digunakan sebagai motor perubahan yang membawa desa pada keterbukaan, inovasi, dan adaptasi tanpa kehilangan jati diri.
Namun, budaya juga bisa jatuh menjadi sekadar ornamen politik—“budaya dirayakan, masyarakat diabaikan”—ketika perayaan adat dan festival hanya menjadi acara seremonial yang tidak memberi dampak nyata pada kesejahteraan atau kerukunan warga. Perspektif cultural capital Bourdieu (1986) menekankan bahwa budaya memiliki nilai strategis hanya jika diintegrasikan dengan modal sosial dan ekonomi, bukan dipisahkan sebagai “hiburan” semata.
Skenario V – Relasi Antar Dimensi
Keempat dimensi ini—aktor, isu, agama, dan budaya—tidak pernah bekerja dalam ruang hampa yang menegaskan pentingnya membaca pola relasi mereka, karena interaksi negatif dapat mempercepat fragmentasi sosial. Misalnya, ketika seorang aktor dominan menggunakan isu agama yang dibungkus dalam simbol budaya untuk memperkuat posisinya, maka kerukunan dapat berubah menjadi alat mobilisasi eksklusif.
Sebaliknya, jika interaksi antar dimensi ini dikelola dalam kerangka inklusif dan kolaboratif, maka lahirlah sinergi yang memperkuat ketahanan sosial. Dari perspektif complex adaptive systems (Holland, 1992), inilah bentuk desa yang resilien: sistem yang dapat beradaptasi dengan guncangan eksternal tanpa kehilangan fungsi vitalnya.
Skenario VI – Implikasi Strategis
Seluruh skenario ini mengarah pada satu kesimpulan strategis: kerukunan desa adalah produk interaksi yang dinamis, dan keberlanjutannya bergantung pada kemampuan desa untuk mengelola empat dimensi tersebut secara simultan yang memberi pesan bahwa tanpa mekanisme umpan balik cepat—feedback loop—untuk memantau perubahan di setiap dimensi, desa akan selalu berada selangkah di belakang dinamika konflik.
Kerangka seperti ini mengisyaratkan perlunya sistem pemantauan sosial (social monitoring system) di tingkat desa, yang dapat mengidentifikasi perubahan pola interaksi aktor, pergeseran isu, pemanfaatan agama, atau transformasi budaya, lalu meresponsnya sebelum eskalasi terjadi.
Kerangka Implementasi Strategi Kerukunan
Mewujudkan kerukunan desa yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar memahami peta aktor, isu, agama, dan budaya. Ia memerlukan strategi implementasi yang menyatukan seluruh dimensi itu ke dalam sebuah sistem ketahanan sosial yang adaptif. Hal ini dengan jelas menggarisbawahi bahwa keberhasilan kerukunan tidak bisa hanya mengandalkan idealisme; ia harus berakar pada praktik yang konsisten, terukur, dan terintegrasi.
Penguatan dimensi aktor menjadi langkah awal yang krusial. Pemimpin desa, tokoh adat, tokoh agama, dan figur-figur informal harus ditempatkan bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai motor penggerak yang memandu arah interaksi sosial. Namun, kepemimpinan yang efektif dalam menjaga kerukunan tidak boleh bersifat tunggal dan tertutup. Kepemimpinan yang terlalu terpusat pada satu figur cenderung menghasilkan pola komunikasi satu arah yang membatasi partisipasi warga. Sebaliknya, desa yang mempraktikkan forum deliberasi inklusif akan mampu memunculkan kesepakatan yang lahir dari partisipasi aktif semua lapisan masyarakat. Inilah yang dimaksud sebagai transformational leadership—kepemimpinan yang menginspirasi, menggerakkan, dan memberi ruang bagi pembaruan.
Isu-isu yang muncul di tingkat desa harus dikelola secara transparan menegaskan bahaya dari “isu bertahta” yang hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa langkah nyata. Dalam kenyataannya, isu memiliki kekuatan untuk mengarahkan energi kolektif, tetapi kekuatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Desa yang mampu mengelola isu dengan baik biasanya memiliki mekanisme yang jelas untuk menentukan prioritas, memverifikasi informasi, dan menyebarkan perkembangan terbaru kepada warga melalui jalur komunikasi resmi. Sebaliknya, desa yang membiarkan isu mengalir tanpa kendali akan cepat terjebak dalam pusaran rumor, yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk memperkeruh suasana.
Peran agama dalam kerukunan desa juga memerlukan penataan serius. Agama harus dihadirkan sebagai sumber etika publik, bukan sebagai komoditas politik. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama benar-benar diintegrasikan dalam kehidupan sosial—baik dalam gotong royong, musyawarah, maupun mediasi konflik—maka agama menjadi kekuatan pemersatu. Namun, ketika agama hanya digunakan untuk mobilisasi dukungan, ia justru berpotensi menciptakan garis pemisah yang sulit dijembatani. Oleh karena itu, literasi keberagamaan yang menekankan pemahaman terhadap keragaman intra-agama dan antar-agama menjadi kunci untuk mencegah manipulasi simbol religius.
Budaya lokal, seharusnya menjadi cultural firewall—tembok kognitif yang mencegah masuknya narasi disintegratif. Tetapi kenyataannya, tidak jarang budaya direduksi menjadi sekadar perayaan yang indah dilihat namun hampa makna. Untuk mengembalikan budaya ke posisi strategisnya, desa perlu menghidupkan kembali ritual dan simbol yang mampu mengikat warga lintas perbedaan. Lebih jauh, budaya perlu diterjemahkan ke dalam narasi digital, sehingga generasi muda yang hidup di dunia maya tetap merasa memiliki ikatan emosional dengan akar tradisinya.
Integrasi keempat dimensi ini—aktor, isu, agama, dan budaya—memerlukan sebuah sistem pemantauan sosial yang bekerja secara real time. Tanpa sistem seperti ini, desa akan selalu berada dalam posisi reaktif, merespons masalah hanya setelah eskalasi terjadi. Pemantauan harus mencakup interaksi offline dan online, dengan perhatian khusus pada potensi ancaman hibrida yang bermula di media sosial dan berakhir di lapangan. Sistem ini akan lebih efektif jika didukung oleh mekanisme pelaporan warga yang sederhana namun responsif, sehingga tanda-tanda awal ketegangan dapat segera diidentifikasi dan diintervensi.
Yang terakhir, kerukunan harus dipandang sebagai proses belajar kolektif. Setiap insiden disharmoni, sekecil apa pun, harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Proses ini serupa dengan after action review yang digunakan dalam militer: sebuah momen untuk menilai apa yang berhasil, apa yang gagal, dan bagaimana langkah selanjutnya. Dari sinilah akan lahir praktik-praktik baik yang dapat direplikasi, bukan hanya di desa yang sama, tetapi juga di desa-desa lain. Regenerasi nilai-nilai kerukunan pun menjadi penting, sehingga generasi muda tidak hanya mewarisi slogan, tetapi juga memahami dan mampu mempraktikkan makna kerukunan dalam konteks zaman mereka.
Dengan kerangka implementasi seperti ini, enam skenario kerukunan yang telah diuraikan bukan lagi sekadar konsep, melainkan peta jalan yang dapat dioperasionalkan di tingkat desa. Ia menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat daya tahan desa terhadap guncangan sosial, politik, maupun kultural, baik yang datang dari dalam maupun dari luar komunitas.
Kesimpulan
Kerukunan di tingkat desa adalah salah satu aset strategis bangsa yang paling rapuh sekaligus paling menentukan. Dari enam skenario yang diuraikan , jelas terlihat bahwa harmoni sosial tidak lahir dari kebetulan atau sekadar hasil dari tradisi yang diwariskan. Ia adalah produk dari interaksi dinamis antara aktor, isu, agama, dan budaya—empat dimensi yang setiap saat dapat berubah menjadi sumber kekuatan atau sumber krisis, tergantung pada bagaimana mereka dikelola.
Pengalaman lapangan dan temuan teoritis menunjukkan bahwa kerukunan yang bertahan lama adalah kerukunan yang diinstitusionalisasikan. Artinya, nilai, norma, dan mekanisme pemeliharaannya tidak hanya hidup di hati warga, tetapi juga tertanam dalam sistem kelembagaan yang memiliki legitimasi dan daya tahan. Pemimpin desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil harus memiliki ruang deliberasi yang setara, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan konsensus yang lahir dari partisipasi kolektif, bukan sekadar titah satu pihak.
Manajemen isu menjadi kunci kedua. Isu yang dibiarkan berkembang tanpa panduan dapat menjadi percikan api yang membakar kohesi sosial. Sebaliknya, isu yang dikelola dengan transparan—dengan verifikasi fakta, komunikasi terbuka, dan tindak lanjut yang nyata—akan menjadi perekat yang menguatkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, desa perlu membangun kapasitas untuk memilah mana isu yang harus dibawa ke ruang publik, mana yang memerlukan penyelesaian internal, dan mana yang harus ditangani secara preventif sebelum menjadi konflik terbuka.
Agama, sebagai salah satu pilar moral dan identitas, hanya dapat menjadi kekuatan pemersatu jika nilai-nilainya dipraktikkan sebagai etika publik, bukan dijadikan komoditas politik. Manipulasi simbol religius untuk kepentingan sempit tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang dalam. Oleh karena itu, pengarusutamaan literasi keberagamaan dan dialog lintas iman yang berbasis pengalaman nyata menjadi sangat penting, terutama di desa yang memiliki pluralitas keyakinan atau denominasi.
Budaya lokal, dengan segala ritus, simbol, dan tradisinya, adalah kekuatan yang sering kali diabaikan dalam perencanaan kerukunan. Padahal, budaya memiliki kapasitas untuk menciptakan rasa memiliki yang melintasi perbedaan politik maupun agama. Namun, budaya hanya akan menjadi benteng yang efektif jika ia dihidupkan secara substansial, bukan sekadar dijadikan ornamen perayaan tahunan. Integrasi budaya ke dalam narasi pembangunan desa, termasuk melalui media digital, akan memastikan bahwa ia tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Keempat dimensi ini harus dipantau secara simultan melalui sistem pemantauan sosial yang bekerja di dua ranah sekaligus: fisik dan digital. Potensi ancaman hibrida—yang bermula dari provokasi di media sosial lalu memicu aksi di lapangan—menuntut adanya mekanisme deteksi dini yang responsif. Desa memerlukan kapasitas untuk membaca tanda-tanda awal ketegangan, mengintervensi narasi yang merusak, dan menginisiasi mediasi sebelum eskalasi terjadi.
Dari keseluruhan pembahasan ini, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis: pertama, membangun kelembagaan kerukunan yang inklusif dan memiliki legitimasi di mata warga; kedua, memperkuat kapasitas manajemen isu di tingkat desa untuk mencegah eskalasi konflik; ketiga, mengarusutamakan agama sebagai etika publik melalui literasi keberagamaan dan dialog lintas iman; keempat, mengintegrasikan budaya lokal sebagai penggerak kerukunan yang relevan di era digital; kelima, mengoperasionalkan sistem pemantauan sosial yang mampu merespons ancaman di ranah fisik dan digital secara bersamaan; dan terakhir, menjadikan kerukunan sebagai proses belajar kolektif yang terus diperbarui melalui evaluasi dan dokumentasi praktik baik.
Kerukunan desa di abad ke-21 tidak lagi bisa dilihat sebagai urusan moral semata. Ia adalah bagian dari strategi ketahanan nasional yang menuntut desain, eksekusi, dan evaluasi yang setara dengan bidang keamanan, ekonomi, dan politik. Desa yang mampu menjaga kerukunan bukan hanya menciptakan kedamaian lokal, tetapi juga memperkuat fondasi kohesi nasional di tengah dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung.
Daftar Pustaka
Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
Bellah, R. N. (1967). Civil Religion in America. Daedalus, 96(1), 1–21.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). New York: Greenwood.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Dinham, A., & Francis, M. (2015). Religious Literacy in Policy and Practice. Bristol: Policy Press.
Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Geertz, C. (1960). The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press.
Heath, R. L. (2002). Issues Management: Its Past, Present and Future. Journal of Public Affairs, 2(2), 209–214.
Holland, J. H. (1992). Complex Adaptive Systems. Daedalus, 121(1), 17–30.
Janis, I. L. (1972). Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
Lyotard, J. F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.
McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1241.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
Ministry of Defence Estonia. (2020). Cyber Civil Defence Strategy 2020–2025. Tallinn: Estonian Government.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press.
UNDP. (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press.
Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11–17.


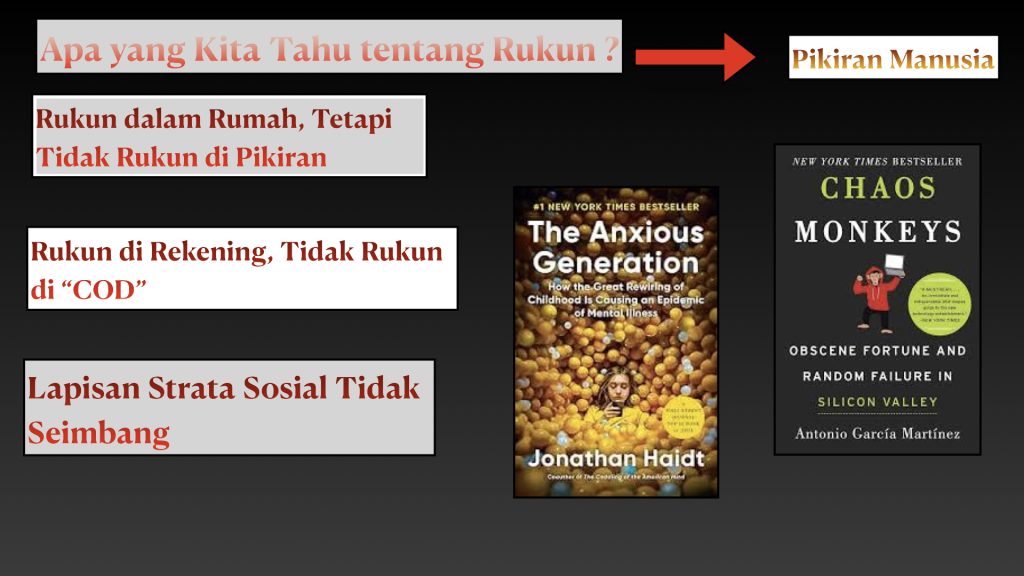



Leave a Reply