Pendahuluan
Kehidupan keluarga di Aceh berdiri di persimpangan antara tradisi lokal yang kuat dan perubahan modern yang cepat. Di provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, norma Islam dan adat Aceh sangat mewarnai perilaku keluarga. Namun, arus globalisasi, teknologi digital, serta dampak sejarah konflik dan bencana alam telah membawa tantangan-tantangan baru bagi keluarga Aceh. Tulisan ini berusaha menggambarkan persoalan-persoalan keluarga di Aceh melalui pendekatan etnografis mendalam ala Clifford Geertz, yaitu dengan “thick description” atau “deskripsi tebal” tentang makna di balik praktik dan pengalaman hidup sehari-hari.
Dalam narasi ini, kita akan menelusuri berbagai tema krusial: mulai dari perkara mahar dalam pernikahan, fenomena pernikahan lintas negara, hingga perceraian yang kian marak. Kita juga akan membahas pengaruh influencer dan budaya media sosial, pilihan hidup childfree, serta isu tragis seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, persoalan “pergaulan bebas” di kalangan remaja, peran lembaga religius seperti pesantren (dayah), ancaman cyberbullying, maraknya penyalahgunaan narkoba, dan praktik nikah siri turut menjadi fokus kajian. Ketiga wilayah – Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Barat – akan menjadi konteks geografis utama, merepresentasikan corak perkotaan hingga semi-perdesaan di Aceh.
Dengan pendekatan antropologis, setiap topik akan dikupas melalui cerita nyata, data lapangan, wawancara, dan studi kasus dari media massa. Harapannya, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial-budaya yang melingkupi keluarga Aceh dewasa ini, beserta nilai-nilai dan konflik di dalamnya. Seperti halnya Geertz menggambarkan makna di balik sabung ayam Bali, kita akan mencoba menangkap makna di balik acara perkawinan, konflik rumah tangga, dan perilaku generasi muda Aceh, sehingga menghasilkan “deskripsi tebal” yang kaya konteks dan refleksi.
Mahar: Simbol Kehormatan dan Beban Sosial
Di sebuah rumah panggung kayu di pinggiran Banda Aceh, seorang ayah mengelus kotak beludru berisi emas perhiasan. Malam itu keluarga besarnya berkumpul untuk musyawarah menentukan jeulameë – istilah lokal untuk mahar emas – bagi lamaran putrinya. Dalam adat Aceh, mahar bukan sekadar hadiah pernikahan, melainkan simbol kehormatan pihak calon istri serta keluarganya. Emas yang diserahkan mempelai pria mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga apabila jumlahnya tinggi.
Tradisi mahar emas di Aceh diukur dengan satuan mayam (sekitar 2,8–3,3 gram tergantung daerah). Nilai dan jumlah mayam bervariasi menurut etnis dan wilayah Aceh. Misalnya, di komunitas Aneuk Jamee (Aceh Selatan), mahar lazimnya relatif rendah, sekitar 3–7 mayam emas. Sementara di kalangan etnis Aceh wilayah Pidie, permintaan mahar dapat mencapai 10–30 mayam atau bahkan lebih. Di Aceh Utara (termasuk Bireuen) bisa saja menembus 50–100 mayam, menjadikan Aceh salah satu daerah dengan mahar pernikahan tertinggi di Indonesia. Adapun di Aceh Besar dan Banda Aceh sendiri, standar mahar umumnya 5–20 mayam, sedikit lebih “terjangkau” namun tetap signifikan nilainya.
Besaran mahar yang tinggi kerap menjadi beban sosial bagi pemuda Aceh. Dalam banyak kasus, pemuda dengan ekonomi pas-pasan merasa gentar melamar gadis pujaannya karena dituntut menyediakan puluhan mayam emas. Penelitian di Kabupaten Pidie mencatat mahar mencapai 50–70 mayam (sekitar Rp90–126 juta) yang harus disiapkan calon suami. Konsekuensinya, sebagian pasangan nekat memilih jalan pintas seperti kawin lari (menikah tanpa restu keluarga) atau menunda pernikahan bertahun-tahun. Bahkan ada fenomena mengkhawatirkan: tingginya mahar ditengarai mendorong perilaku seks pranikah di luar nikah akibat lamanya masa pacaran yang “terkatung” demi menunggu cukup uang.
Para tetua adat Aceh menyadari dilema ini. Mereka memandang jeulameë sebagai adat luhur simbol martabat, namun juga mengkhawatirkan dampak negatifnya. Di satu sisi, kemampuan memberi mahar tinggi dianggap meningkatkan gengsi keluarga mempelai pria. Di sisi lain, makin banyak suara yang menyerukan penyederhanaan mahar agar pernikahan tidak menjadi beban ekonomi berlebihan. Dalam diskusi keluarga di Lhokseumawe, misalnya, kerap muncul anekdot orangtua menasihati: “Daripada menumpuk utang untuk beli emas, lebih baik menantu kami gunakan uang itu untuk modal hidup berumah tangga.” Kenyataannya, negosiasi mahar sering kali alot – calon besan saling menjaga perasaan dan harga diri.
Ritual penyerahan mahar di Aceh berlangsung khidmat. Pada malam akad nikah, emas mayam terangkai dalam bungkahan hantaran dengan hiasan indah. Pihak mempelai perempuan akan mengumumkan jumlah mayam di hadapan undangan, suatu momen yang disambut takbir dan tepuk tangan. Nilai mahar menjadi buah bibir tamu sepanjang pesta – dibicarakan baik dengan nada bangga maupun heran. Dalam perspektif antropologi simbolik, momen ini sarat makna budaya: mahar emas merepresentasikan nilai perempuan dalam adat, bukan sebagai komoditas, melainkan pancaran status sosial dan restu keluarga. Namun, makna simbolik itu kini dihadapkan pada realitas ekonomi. Tak jarang, keluarga mempelai pria harus menjual tanah atau menggadaikan harta demi memenuhi tuntutan mahar. Pergulatan antara ideal budaya dan kemampuan nyata ini menjadi drama keluarga tersendiri dalam masyarakat Aceh kontemporer.
Pernikahan Lintas Negara: Antara Tradisi dan Globalisasi
Pagi itu di kota Sabang yang tenang, warga dihebohkan oleh sebuah acara akad nikah tak biasa. Seorang gadis Aceh setempat, Nabila, menikah dengan pria asing berkewarganegaraan Australia bernama Luai Saeed Mohammed Saif. Sang ayah mempelai wanita bahkan harus mengucapkan ijab kabul dalam Bahasa Inggris demi mengikat janji dengan besan bulenya. Mahar yang disebutkan pun berupa uang tunai AUD 2.000 (sekitar Rp20 juta) – angka yang relatif sederhana dibanding standar emas mayam lokal. Prosesi unik ini berjalan lancar di bawah panduan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), lengkap dengan saksi fasih berbahasa Inggris. Kisah Nabila dan Luai mencerminkan wajah baru pernikahan Aceh di era globalisasi: pernikahan lintas negara yang dahulu jarang, kini mulai muncul seiring meningkatnya interaksi Aceh dengan dunia luar pascatsunami dan damai.
Fenomena nikah campur antara orang Aceh dan warga negara asing dipengaruhi berbagai faktor. Di satu sisi, ada cinta hasil pergaulan global – pemuda Aceh yang kuliah di luar negeri lalu menikah dengan orang berbeda bangsa, atau ekspatriat yang bekerja di Aceh dan jatuh hati pada gadis lokal. Di sisi lain, situasi pascabencana tsunami 2004 dan konflik membuat Aceh “dikunjungi” banyak pihak luar, membuka peluang perjodohan antarbangsa. Akan tetapi, pernikahan lintas negara tidak selalu berjalan mulus. Proses administrasi resmi menuntut syarat dokumen yang tak sedikit: mulai dari Certificate of No Impediment (surat keterangan bebas halangan menikah dari kedutaan), paspor, surat keterangan domisili, hingga bila perlu sertifikat mualaf bagi pasangan non-Muslim. Bagi sebagian pasangan, prosedur ini dirasa rumit sehingga ada yang memilih jalan belakang berupa nikah siri tanpa pencatatan resmi.
Kasus di Meulaboh, Aceh Barat pada Maret 2023 dapat dijadikan contoh. Seorang pria asal Tiongkok berusia 35 tahun diam-diam menikahi perempuan Aceh (23 tahun) secara siri di sebuah gampong tanpa sepengetahuan KUA setempat. Pernikahan diam-diam itu baru tercium setelah beritanya beredar di media lokal. Kepala Kemenag Aceh Barat menegaskan pernikahan tersebut tidak tercatat dan merugikan pihak perempuan. Jika kelak mereka memiliki anak, sang anak berpotensi kesulitan mengurus akta kelahiran dan dokumen kependudukan karena pernikahan orang tuanya tidak diakui negara. Kasus ini mengundang diskusi publik di Aceh: di tengah masyarakat religius, ternyata masih ada yang mengambil opsi nikah siri lintas negara, mungkin demi menghindari birokrasi atau perbedaan status. Namun dampaknya jelas memberatkan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena tanpa legalitas mereka kehilangan perlindungan hukum.
Kontras dengan itu, pemerintah Aceh berusaha memfasilitasi pernikahan campuran secara resmi. Sosialisasi dilakukan agar pasangan WNA-WNI memahami prosedur dan pentingnya legalitas. Misalnya, pihak KUA di Sabang dengan sigap mendampingi Nabila dan suaminya mengurus dokumen dan memastikan syarat terpenuhi, termasuk penerjemahan dokumen asing ke Bahasa Indonesia. Resepsi pernikahan mereka berlangsung meriah, sekaligus menjadi bahan cerita di warung kopi: “Orang Aceh kawin dengan urang puteh (bule),” ujar seorang bapak di Lhokseumawe dengan nada heran bercampur bangga. Kebanggaan muncul ketika pernikahan lintas negara dianggap membuka jaringan keluarga hingga mancanegara; namun keheranan juga nyata karena tradisi kultural berbeda jauh. Masyarakat Aceh umumnya menerima asalkan proses sesuai syariat – misalnya mempelai pria non-Aceh harus mualaf jika sebelumnya beragama lain, sebagaimana diwajibkan dalam aturan menikah di KUA.
Dari kacamata antropologi, pernikahan lintas negara di Aceh adalah contoh tarik-menarik antara universalitas Islam dan identitas lokal. Islam memperbolehkan pernikahan beda suku bangsa sepanjang seagama, sehingga sebenarnya tak ada hambatan teologis. Namun secara kultural, keluarga Aceh terbiasa dengan konsep endogami (menikah dengan sesama orang “sekampung” atau setidaknya sesuku). Kini batas-batas itu meluas: menantu tak lagi harus orang Aceh. Meski demikian, proses negosiasi identitas akan terus berlangsung – apakah menantu asing mau menyesuaikan diri dengan adat Aceh? Bagaimana bahasa sehari-hari di rumah mereka? Apakah anak-anaknya kelak berbahasa Aceh atau bahasa ayahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi menarik. Di Banda Aceh misalnya, sudah ada beberapa “keluarga blasteran” Aceh dengan ekspatriat yang tampak harmonis, meski mungkin menghadapi kompromi dalam hal budaya (pola asuh, makanan, pakaian, dsb.).
Yang jelas, pengalaman keluarga yang melintasi batas negara memberi pelajaran bahwa globalisasi merambah hingga pelosok Aceh. Keluarga tradisional Aceh kini dapat memiliki anggota dari benua berbeda. Dalam beberapa kasus, hal ini memperkaya perspektif keluarga tersebut, namun tak jarang juga memicu komentar sosial dari lingkungan sekitar. Seorang ibu di Aceh Barat mungkin bertanya-tanya, “Bagaimana menantuku yang orang jauh itu menghormati kami? Bisakah dia paham adat di sini?” Kekhawatiran semacam ini wajar mengemuka. Namun seiring berjalannya waktu, pernikahan lintas negara kian menunjukkan bahwa cinta dan keluarga mampu menjembatani perbedaan asal-usul, asalkan dilandasi saling pengertian dan aturan yang jelas.
Perceraian dalam Masyarakat Aceh Kontemporer
Suara ketukan palu terdengar menggema di ruang sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh siang itu. Seorang perempuan muda tertunduk sambil menggendong balita, sementara di depannya suaminya hanya terpaku diam. Mereka baru saja resmi bercerai. Adegan seperti ini kian jamak di Aceh. Perceraian, yang dulu dianggap aib besar dan sebisa mungkin dihindari, kini menunjukkan tren meningkat. Data pengadilan agama (Mahkamah Syar’iyah) se-Aceh mengungkap ribuan kasus cerai diajukan setiap tahun. Bahkan hingga pertengahan 2025 saja, terdapat sekitar 2.923 perkara perceraian yang masuk di seluruh Aceh.
Menariknya, mayoritas besar perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) ketimbang oleh suami (cerai talak). Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, Aceh Besar, misalnya, pada Semester I 2024 terdapat 215 kasus perceraian dan 176 di antaranya diajukan istri. Fenomena istri Aceh menggugat cerai suami ini mencerminkan perubahan posisi perempuan dalam rumah tangga – mereka semakin berani mengambil keputusan keluar dari pernikahan yang dirasa tidak sehat. Para hakim syar’iyah sering mendengar alasan berulang dari para istri: suami tidak memberi nafkah, suami kasar (KDRT), atau suami selingkuh. Namun belakangan muncul pula alasan yang lebih kekinian, seperti suami kecanduan judi online atau terlalu asyik bermain media sosial. Juru Bicara Mahkamah Syar’iyah Jantho mengakui bahwa meski konflik rumah tangga umumnya kompleks, ada kecenderungan faktor pemicu bergeser ke hal-hal digital dan gaya hidup modern.
Salah satu “penyakit baru” dalam rumah tangga Aceh adalah judi online (judol). Banyak istri mengeluhkan gaji suami habis untuk bermain slot atau poker daring, sementara kebutuhan dapur terabaikan. Akibatnya pertengkaran terjadi terus-menerus dan cinta pun pudar. “Uang habis untuk deposit game, kami makan apa?” ungkap seorang ibu di Lhokseumawe yang akhirnya menggugat cerai suaminya pecandu judi online. Selain itu, kecemburuan akibat media sosial juga menjadi alasan perceraian yang kian sering muncul. Kisah nyata di Aceh Besar, seorang istri tak tahan melihat suaminya kerap larut malam live streaming di TikTok memberikan “gift” (hadiah digital) kepada streamer wanita lain. Bagi sang istri, itu sudah melampaui batas dan dianggap perselingkuhan virtual. Sementara di kasus lain, suami cemburu karena istrinya terlalu aktif di media sosial, mungkin berkomunikasi akrab dengan lawan jenis. Fenomena live TikTok hingga larut malam, sesuatu yang dahulu tak terbayangkan, kini menjadi pemicu konflik rumah tangga yang nyata.
Tentu, faktor klasik penyebab cerai masih dominan: ekonomi, ketidakcocokan, dan KDRT. Namun keterlibatan teknologi memperumit persoalan. Perselingkuhan misalnya, kini tak mesti terjadi secara fisik – chat mesra di WhatsApp atau komentar genit di Facebook bisa menyulut prahara. Dari perspektif budaya Aceh yang sangat menjunjung kehormatan istri dan suami, hal-hal semacam ini dianggap mencoreng harga diri pasangan. Maka tak heran perceraian dianggap jalan keluar ketimbang mempertahankan pernikahan hambar penuh curiga.
Perceraian yang meningkat di Aceh menimbulkan kekhawatiran tokoh masyarakat dan ulama. Pada satu sisi, Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir, namun tetap memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Meningkatnya angka cerai bisa dilihat sebagai indikasi rapuhnya ketahanan keluarga. Beberapa ulama di Aceh menduga, dampak perang dan tsunami – di mana banyak keluarga kehilangan figur ayah atau ibu – mungkin berkontribusi pada generasi muda yang kurang memiliki role model keluarga utuh. Ditambah lagi, tekanan ekonomi pascakonflik serta modernisasi bisa memicu konflik suami-istri.
Namun di sisi lain, meningkatnya cerai gugat oleh istri bisa pula dibaca sebagai hal positif: perempuan Aceh makin sadar hak-haknya dan berani keluar dari pernikahan tidak sehat. Dulu, tak sedikit wanita yang memilih bertahan meski disakiti suami demi stigma sosial “janda” yang berat. Kini dengan edukasi dan dukungan hukum, mereka berani melapor KDRT dan menuntut cerai bila diperlukan. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (UPTD PPA) provinsi Aceh mencatat ratusan laporan KDRT setiap tahun, dan banyak berujung pada perceraian untuk menyelamatkan korban.
Dari kacamata sosiologi, perceraian di Aceh kini bukan lagi hal tabu yang disembunyikan. Sidang cerai di Mahkamah Syar’iyah, terutama di kota-kota seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, dipenuhi para pencari keadilan yang datang terbuka. Bahkan, di media massa lokal sering muncul berita perceraian selebritas atau pejabat Aceh. Ini menandakan pergeseran norma: pernikahan tetap dijunjung sakral, tetapi perceraian mulai diterima sebagai bagian dari realitas hidup ketika tujuan rumah tangga tak tercapai.
Bagi komunitas Aceh, tantangannya adalah bagaimana menjaga institusi keluarga tetap kokoh di tengah gempuran pengaruh zaman. Program konseling pranikah di KUA sudah dijalankan untuk membekali calon pasangan tentang ilmu mengarungi bahtera rumah tangga. Juga, peran tokoh agama di gampong-gampong diharapkan aktif mendamaikan pasangan yang berselisih sebelum berakhir di meja hijau. Ungkapan lokal “rumoh thôn kru seunong” (rumah tangga itu ada pasang surutnya seperti arus laut) sering digunakan orang tua menasihati anak agar sabar dan tak gegabah cerai. Namun, ketika perceraian tak terelakkan, masyarakat kini relatif lebih menerima. Bahkan gotong royong untuk membantu ibu-ibu cerai (janda) misalnya melalui pengajian dan kelompok wirid, merupakan bentuk solidaritas baru yang menghangat di komunitas Aceh belakangan ini.
Pengaruh Influencer dan Media Sosial terhadap Keluarga Aceh
Suatu malam di Lhokseumawe, seorang remaja putri asyik menonton video TikTok di ponselnya sambil tersenyum-senyum. Di layar, tampak seorang selebgram hijab asal Aceh berjoget trendi dengan latar musik pop. Sementara itu di ruang tamu, ibunya mengernyit melihat tingkah anak gadisnya meniru gaya tarian dari internet. Pemandangan seperti ini kini jamak di keluarga Aceh: media sosial telah memasuki relung-relung rumah, mempertemukan gaya hidup global dengan nilai-nilai lokal.
Influencer – figur populer di Instagram, YouTube, atau TikTok – memiliki dampak signifikan pada generasi muda Aceh. Mereka menjadi semacam “panutan baru” di luar tokoh agama atau tetua adat. Di Banda Aceh, misalnya, dikenal nama seperti Herlin Kenza, selebgram berjuluk “Barbie Aceh” karena berwajah cantik bak boneka dan gaya hidup glamor. Ia pernah viral karena pergi berbelanja ke supermarket dengan dikawal sembilan ajudan pribadi, sebuah aksi pamer yang mengundang kontroversi nasional[1][2]. Bagi sebagian anak muda Aceh, Herlin menjadi simbol kesuksesan dan modernitas: muda, kaya, berani tampil beda. Namun bagi banyak orang tua dan ulama, gaya hidup yang dipamerkannya dianggap berlebihan dan tidak sesuai budaya kesederhanaan Aceh. Ketika Herlin mengadakan pesta ulang tahun mewah ala resepsi pernikahan di tengah pandemi, komentar sinis bermunculan di media sosial – warganet Aceh menegur bahwa uang lebih baik disedekahkan daripada “dihambur-hamburkan” untuk hura-hura.
Kisah Herlin Kenza hanya salah satu ilustrasi. Banyak lagi influencer, termasuk yang berasal dari Aceh, memengaruhi cara berpakaian, pola konsumsi, hingga aspirasi hidup generasi muda. Remaja putri di Aceh kini mahir mengikuti tutorial hijab modern di YouTube, sehingga gaya busana muslimah mereka makin beragam – dari yang syar’i sederhana sampai yang modis berwarna-warni. Sisi positifnya, media sosial memperluas wawasan dan kreativitas. Namun sisi lain, muncul benturan dengan norma setempat. Budaya komunal Aceh yang menjunjung kebersamaan terkadang berbenturan dengan budaya individualistis dan materialistis yang diusung para influencer. Misalnya, tren pamer barang mewah (flexing) dan berpose bak selebritas bisa menimbulkan rasa iri dan tekanan sosial di antara remaja. Tidak sedikit orang tua di Aceh mengeluh anaknya kini minta smartphone mahal atau barang branded agar “kekinian” seperti influencer idolanya, padahal ekonomi keluarga pas-pasan.
Media sosial juga mengubah pola komunikasi keluarga. Dulu, selepas maghrib keluarga mungkin berkumpul mengaji atau bercerita, kini sering kali masing-masing anggota sibuk dengan gawainya. Kesenjangan digital antara orang tua dan anak terasa – anak terbiasa mengekspresikan diri di dunia maya yang kurang dipahami orang tua. Hal ini kadang memicu konflik atau kecemasan. Contohnya, seorang ayah di Aceh Barat merasa marah ketika menemukan anak lelakinya diam-diam membuat konten video joget karena dianggap “memalukan keluarga”. Bagi sang anak, itu sekadar hiburan dan mengikuti tren, tapi bagi ayahnya, itu melanggar kesopanan adat.
Ada pula fenomena influencer dakwah: generasi muda pendakwah Aceh yang memanfaatkan Instagram/TikTok untuk menyebarkan nilai Islam. Mereka berusaha menjadi tandingan konten hedonistik dengan pesan moral dan nasihat agama. Sebagian keluarga menyambut baik, berharap anak-anak mereka lebih tertarik mengikuti ustaz gaul di Instagram ketimbang artis TikTok tidak jelas. Akan tetapi, tak jarang justru influencer “ustaz” ini terlibat kontroversi, misal memberikan pandangan agama yang keras dan viral, yang lalu memicu debat di masyarakat.
Menarik diamati, relasi suami-istri pun terkena imbas influencer. Ada influencer keluarga muda Muslim yang mengampanyekan kehidupan rumah tangga harmonis di media sosial, memperlihatkan kemesraan dan kesalehan. Hal ini bisa memberi teladan positif, namun bisa juga memberi ekspektasi tak realistis bagi penonton. Beberapa istri di Banda Aceh mengaku iri melihat suami orang lain di media sosial yang tampak romantis atau rajin membantu istri, lalu membandingkan dengan suaminya sendiri. Sebaliknya, para suami ada yang tak suka istrinya terlalu mengidolakan figur pria di internet. Perselisihan kecil semacam ini menjadi warna baru dalam kehidupan rumah tangga era digital.
Dari segi nilai, otoritas tradisional (orang tua, teungku dayah) di Aceh kini bersaing dengan otoritas virtual. Seorang remaja putra mungkin lebih patuh pada saran idolanya di YouTube tentang karier dan passion, ketimbang anjuran ayahnya untuk ikut jejak bisnis keluarga. Ini bisa menimbulkan gesekan. Namun, di sisi lain, internet juga membuka ruang dialog baru antara generasi. Tak sedikit anak muda Aceh justru mengajarkan orang tuanya memakai WhatsApp untuk silaturahmi, atau menonton ceramah agama di YouTube bersama. Dengan demikian, pengaruh media sosial ibarat dua sisi mata uang: bisa menjauhkan, bisa mendekatkan.
Secara umum, keluarga Aceh kini berusaha beradaptasi. Banyak orang tua mulai mengawasi konten yang dikonsumsi anak dengan lebih bijak, berdiskusi tentang apa yang mereka lihat online. Pendekatan kontrol sosial pun ikut bergeser – jika dulu mengawasi pergaulan fisik (bertemu lawan jenis di luar rumah), sekarang juga harus melek “pergaulan maya” anak-anaknya. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat belakangan aktif mengadakan seminar literasi digital, mencoba membekali remaja Aceh agar bijak bermedia sosial dan tidak terseret arus negatif.
Yang jelas, peran influencer dan media sosial dalam keluarga Aceh sudah tak bisa diabaikan. Etnografi keluarga masa kini tak lengkap tanpa menyinggung kehidupan digital mereka. Seperti kata pepatah modern, “Jempol lebih tajam dari lidah.” Keputusan-keputusan keluarga – dari pola asuh, gaya konsumsi, hingga prinsip hidup – kini banyak dipengaruhi apa yang dilihat dan dibagikan di layar 6 inci smartphone. Bagi antropolog, ini menantang kita memahami Aceh tidak hanya dari warung kopi dan meunasah (surau), tapi juga dari linimasa media sosialnya.
Fenomena Childfree dalam Perspektif Aceh
Pada suatu acara arisan keluarga di Banda Aceh, topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke isu tak terduga: seorang keponakan yang sudah dua tahun menikah namun belum juga memiliki anak. Bisik-bisik terdengar bahwa pasangan muda itu sengaja menunda punya anak, konon karena menganut konsep “childfree”. Serentak para uwak dan nenek bergumam heran – dalam budaya Aceh yang sangat familistik, keputusan sukarela untuk tidak memiliki anak adalah konsep nyaris asing dan cenderung dianggap bertentangan dengan fitrah. “Meunyo hana aneuk, bagah geutanyoe sigra that? (Kalau tidak ada anak, bagaimana bahagianya?)” celetuk seorang bibi, tak habis pikir.
Istilah childfree yang merupakan serapan dari diskursus global mulai dikenal di Indonesia melalui media sosial sekitar awal 2020-an. Perdebatan hangat sempat muncul, terutama setelah beberapa figur publik nasional terang-terangan menyatakan memilih tidak mau punya anak. Dalam konteks Aceh, wacana ini menimbulkan kontestasi antara pandangan modern (kendali atas tubuh dan pilihan reproduksi adalah hak individu) versus pandangan keagamaan dan tradisional (anak adalah rezeki dan tujuan alami perkawinan). Kalangan ulama, baik di tingkat nasional maupun Aceh, umumnya bersikap kritis: mereka menilai sikap sengaja menolak keturunan tanpa alasan darurat medis sebagai bertentangan dengan anjuran syariat untuk berketurunan. Sebuah studi menyebutkan para ulama menganggap pilihan childfree tidak sejalan dengan hukum Islam dan kodrat manusia. Artinya, ada kecenderungan mengharamkan keputusan semacam itu, atau minimal mengecamnya sebagai sikap egois yang menyalahi sunnah Nabi.
Dalam norma sosial Aceh sendiri, memiliki keturunan merupakan hal sangat penting. Anak bukan sekadar penerus marga, tapi juga simbol keberkahan rumah tangga. Peribahasa Aceh menyatakan: “Meunyo hana aneuk, hareuta benda hana makna” – tanpa anak, harta benda pun terasa hampa. Tekanan sosial untuk segera punya anak setelah menikah cukup kuat. Maka pasangan Aceh yang lama belum dikaruniai anak biasanya akan mendapatkan banyak saran, bahkan mungkin didoakan khusus dalam kenduri. Dalam kondisi seperti ini, dapat dibayangkan betapa kontroversialnya jika ada pasangan yang justru secara sadar memutuskan untuk tidak mau anak sama sekali.
Meski demikian, pengaruh global dan perubahan pola pikir ikut menjalar ke Aceh. Ada segelintir pasangan muda terdidik, terutama di kota-kota, yang mulai mempertimbangkan childfree lifestyle. Alasannya beragam: khawatir tak mampu memberi kehidupan yang layak, ingin fokus berkarier, trauma masa kecil, atau pandangan ekologis (membatasi populasi demi lingkungan). Beberapa di antara mereka mungkin tidak mengumumkan pilihannya terang-terangan, tetapi tampak dari tindakan – misal aktif menggunakan kontrasepsi jangka panjang walau belum punya anak, atau terbuka mengatakan “kami belum siap punya momongan” meski usia pernikahan sudah cukup lama.
Reaksi lingkungan atas tanda-tanda childfree ini bisa cukup kuat. Di Lhokseumawe, ada cerita sepasang suami istri yang memilih childfree sampai salah satu pindah kerja ke luar Aceh agar terhindar dari tekanan keluarga. Keluarga besar mereka sempat panik dan mendesak tokoh agama setempat untuk menasihati pasangan tersebut bahwa keputusan itu “melawan kodrat”. Hal ini menunjukkan bahwa wacana childfree masih sukar diterima di komunitas Aceh, dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam dan adat yang pro-keluarga besar.
Ulama Aceh pun turut bersuara di mimbar-mimbar pengajian, mengingatkan jamaah muda bahwa menikah itu salah satu tujuannya melahirkan generasi muslim baru. Mereka kerap mengutip ayat Qur’an dan hadis yang menganjurkan umat Islam memperbanyak keturunan saleh. Dalam pandangan sosiologis-keagamaan, konsep childfree ditafsirkan sebagai bagian dari “pengaruh individualisme Barat” yang tidak sesuai semangat kebersamaan masyarakat Aceh.
Menariknya, diskusi mengenai childfree di Aceh juga memunculkan pertanyaan: bagaimana hukum fiqihnya secara spesifik? Beberapa intelektual muslim lokal mencoba mengkaji ulang konsep ‘azl (menunda kehamilan dengan sengaja) dan hak reproduksi dalam Islam. Hasilnya, sebagian berpendapat bahwa bila kedua pasangan ridha dan punya alasan kuat (misal kekhawatiran kesehatan mental), keputusan semacam itu bisa masuk ranah mubah (dibolehkan) walaupun makruh, selama tidak sampai mengingkari keharusan menikah. Namun pandangan moderat seperti ini masih minor dan kalah gaung dibanding pendapat arus utama yang cenderung menolak childfree.
Pada tingkat praksis, hingga kini belum terdengar pasangan Aceh yang secara terang-terangan mendeklarasikan “kami childfree” di ruang publik lokal. Kalaupun ada, kemungkinan disampaikan dalam forum diskusi akademik atau komunitas terbatas. Sementara di ranah keluarga, topik ini mungkin baru berani dibicarakan berdua saja antara suami-istri, itupun dengan risiko kesalahpahaman. Bagi banyak orang Aceh, memilih childfree mungkin dianggap sama dengan menolak rezeki Allah, suatu konsep yang berat secara teologis. Maka alih-alih menyatakan “kami tak mau anak”, pasangan cenderung berkata “belum rezeki” jika ditanya orang – sebuah jawaban normatif yang lebih dapat diterima.
Dari sudut pandang antropologi, respons keras komunitas Aceh terhadap childfree mencerminkan teguhnya nilai anak dalam struktur sosial. Anak di Aceh tidak hanya milik orang tua, tetapi milik komunitas – ada ungkapan “anak ibu jaga, anak tetangga pangku” yang menggambarkan gotong royong dalam membesarkan anak. Maka keputusan tidak punya anak seolah menghilangkan satu elemen penting dalam siklus sosial tersebut. Walau begitu, bukan berarti wacana ini akan hilang. Seperti ide-ide modern lain, ia mungkin akan tetap berseliweran di media (misal Instagram) dan didiskusikan diam-diam oleh generasi muda. Bagaimana pun, keluarga Aceh di masa depan akan terus diuji oleh ide-ide baru yang menantang tradisi, dan cara mereka merespons akan menentukan arah perubahan budaya keluarga itu sendiri.
Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dari Tabu ke Kesadaran
Di sebuah rumah sakit di Meulaboh, seorang wanita paruh baya terbaring dengan lebam di wajah. Ia korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh suaminya, tetapi awalnya ia enggan melapor. “keupu meupakee deuh aib keluarga (takut membuka aib keluarga),” ujarnya lirih. Kisah pilu ini dulu mungkin akan terkubur senyap demi menjaga nama baik, namun kini semakin banyak perempuan Aceh berani angkat suara melawan KDRT. Perubahan ini didukung data: kasus KDRT yang dilaporkan di Aceh menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, jumlah laporan KDRT ke UPTD PPA Aceh pada 2019 sebanyak 1.067 kasus, 2020 sebanyak 905 kasus, 2021 sebanyak 924 kasus, 2022 sebanyak 1.029, dan 2023 menembus 1.098 kasus. “Tren kasus KDRT di Aceh cenderung naik dari tahun ke tahun,” kata Tiara Sutari dari DP3A Aceh.
Dahulu, KDRT di Aceh bagaikan “rahasia dapur”: diketahui terjadi tapi ditutup rapat di dalam rumah. Budaya patriarki dan konsep syariat yang menekankan ketaatan istri mungkin ikut membuat korban merasa harus sabar. Namun perlahan, stigma melapor KDRT mulai terkikis. Lembaga penegak hukum syariat juga menaruh perhatian. Meskipun Qanun Jinayah Aceh tidak mengatur spesifik soal KDRT (karena KDRT diatur dalam hukum nasional UU PKDRT), aparat Polres dan Kejaksaan di Aceh semakin sigap menindak pelaku kekerasan domestik. Misalnya, di Aceh Barat sepanjang 2024, unit PPA Polres menangani 54 kasus kekerasan, dan KDRT bersama pelecehan seksual anak mendominasi dengan masing-masing 16 dan 11 kasus. Ini menunjukkan polisi setempat makin proaktif mengusut kekerasan dalam ranah rumah tangga, yang dulunya mungkin dianggap “urusan internal keluarga”.
Penyebab KDRT di Aceh bervariasi: faktor ekonomi (suami stres lalu melampiaskan ke istri), kecanduan narkoba/judi, cemburu, hingga benturan karakter. Dalam satu wawancara, seorang teungku (ulama) di Pidie mengeluhkan maraknya kekerasan suami terhadap istri karena suami merasa berhak “mendisiplinkan” istri dengan dalih agama. Padahal ajaran Islam melarang kezaliman. Upaya re-edukasi terus dilakukan: kursus pra-nikah di KUA kini memasukkan materi tentang relasi suami-istri yang sehat, di mana kekerasan bukan bagian dari solusi apa pun. Di meunasah-meunasah, ceramah peringatan maulid dan pengajian ibu-ibu juga disisipi pesan anti-KDRT: mengingatkan suami meneladani akhlak Nabi yang lembut pada keluarga.
Dukungan bagi korban pun berkembang. Selain UPTD PPA pemerintah, ada LSM lokal seperti Flower Aceh atau MISPI yang memberikan advokasi hukum dan psikolog bagi perempuan korban kekerasan. Mereka kadang turun ke gampong mengedukasi ibu-ibu bahwa dipukul suami itu bukan hal normal dan bisa minta pertolongan. Sebuah anekdot: di Aceh Besar, ketika seorang istri melapor suaminya yang ringan tangan ke polisi syariat, awalnya para tetangga terkejut karena “membawa urusan rumah ke luar”. Namun setelah mengetahui suami tersebut juga melakukan kekerasan terhadap anak, tokoh masyarakat justru mendukung proses hukum demi efek jera. Ini indikasi perubahan sikap kolektif – nilai kemanusiaan dan perlindungan anak mulai mengungguli rasa malu aib.
Perlu dicatat, KDRT di Aceh bukan hanya fisik. Kekerasan psikis (misal penghinaan terus-menerus), kekerasan seksual dalam pernikahan, hingga penelantaran ekonomi juga termasuk. Banyak perempuan Aceh di pedalaman mengalami kontrol berlebihan oleh suami (tak boleh keluar rumah atau kerja), namun baru belakangan disadari bahwa itu pun bentuk kekerasan psikis. Seiring meningkatnya edukasi hukum, mereka makin tahu hak-haknya. Pemerintah Aceh berkomitmen mencegah dan menangani KDRT dengan melahirkan kebijakan seperti qanun, pergub, dan pembentukan kelembagaan khusus. “DP3A terus melakukan pengarusutamaan isu penghapusan KDRT agar menjadi perhatian bersama,” ujar Tiara Sutari.
Dampak KDRT terhadap struktur keluarga Aceh cukup serius. Anak-anak yang tumbuh di rumah tangga penuh kekerasan rentan mengalami trauma dan masalah mental. Survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN 2021) menemukan 1 dari 4 perempuan Indonesia usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau orang lain seumur hidup. Data itu didukung fakta lokal: di Aceh Barat saja, 16 kasus KDRT ditangani polisi dalam setahun. Artinya, generasi berikut pun terancam mata rantai kekerasan jika tidak diputus. Oleh karena itu, belakangan muncul keterlibatan pesantren dan sekolah dalam kampanye anti-KDRT. Ada dayah yang mengajarkan santrinya fiqih rumah tangga yang adil dan menghormati perempuan. Di beberapa SMA/MA di Banda Aceh, dijalankan program “Sekolah Ramah Anak & Istri” bekerja sama dengan DP3A, mengedukasi remaja putra agar kelak menjadi suami yang baik dan remaja putri agar berani bicara jika diperlakukan buruk.
Transformasi pandangan KDRT di Aceh ini menarik sebagai gambaran perubahan budaya: dari tabu menjadi isu publik. Dulu, mungkin seorang ibu dipukuli suami lalu hanya bisa menangis di dapur ditemani ibu kandungnya tanpa ada yang tahu. Sekarang, semakin mungkin ia mendapat pendampingan, bahkan kasusnya diliput media lokal, dan pelaku dihukum penjara atau cambuk (jika disertai penganiayaan berat bisa dijerat Qanun Jinayah tentang penganiayaan umum). Peran media massa Aceh cukup besar mengangkat cerita KDRT, membuatnya bukan lagi aib yang disembunyikan melainkan problem sosial yang harus dituntaskan.
Tentu, jalan masih panjang. Mengubah mentalitas patriarkal membutuhkan generasi. Sebagian pria Aceh masih menganggap menegur atau bahkan memukul istri “demi kebaikan” adalah hak suami, sebagaimana pernah disalahartikan dari ayat Al-Qur’an (padahal konteksnya bukan membenarkan kekerasan brutal). Namun dengan intervensi pendidikan formal dan nonformal, diharapkan narasi ini bergeser. Keluarga sakinah yang didambakan dalam Islam Aceh tidak akan terwujud jika ada kekerasan di dalamnya – kesadaran inilah yang perlahan tumbuh sebagai konsensus baru di Aceh.
“Pergaulan Bebas” dan Kontrol Sosial dalam Syariat Aceh
Pada suatu malam minggu di taman kota Banda Aceh, dua sejoli muda-mudi duduk berduaan di bangku remang. Mereka bercanda pelan, sang pemuda berbisik sesuatu yang membuat gadisnya tersipu. Namun momen manis itu tak berlangsung lama – sirene Wilayatul Hisbah (WH) alias polisi syariat melengking ketika mobil patroli tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, sepasang kekasih tadi telah dikerumuni petugas dan beberapa warga. Mereka diamankan dengan tuduhan khalwat, yaitu berduaan di tempat sepi tanpa ikatan sah. Wajah malu sang gadis tertunduk ketika mereka digelandang untuk didata.
Adegan penertiban oleh WH ini lumrah terjadi di daerah perkotaan Aceh. Pergaulan bebas – istilah lokal untuk hubungan lelaki-perempuan di luar nikah yang dianggap melanggar norma – menjadi salah satu fokus utama penerapan syariat Islam di Aceh sejak disahkannya Qanun Jinayah. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi perbuatan khalwat (mesum) dan ikhtilath (bermesraan). Hukumannya bisa berupa uqubat cambuk di depan umum. Sudah tak terhitung kasus di mana pasangan muda (bahkan ada yang usia remaja) dicambuk karena tertangkap khalwat.
Salah satu peristiwa yang dikenang publik terjadi tahun 2019: sepuluh remaja (lima pasang) dieksekusi cambuk di halaman masjid di Banda Aceh setelah dinyatakan bersalah melanggar syariat dengan berbuat khalwat (mesum) dan ikhtilath (bermesraan). Eksekusi itu disaksikan ratusan orang, sampai petugas kewalahan membendung kerumunan yang ingin melihat dari dekat. Para pelanggar, sebagian masih belasan tahun, dicambuk antara 4 hingga 22 kali sesuai berat ringannya perbuatan. Safriadi, Kepala WH Banda Aceh ketika itu, menyebut kebanyakan kasus khalwat melibatkan remaja yang ditangkap warga di rumah kosong, mobil parkir, atau penginapan. Ia bahkan meminta orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak, dan masyarakat aktif mencegah sebelum terjadi – sebab sering kali justru warga yang memergoki lalu melapor.
Budaya gotong royong moral ini memang unik di Aceh. Menegur pasangan yang berduaan dianggap tanggung jawab bersama demi cegah maksiat. Bagi pelaku yang tertangkap, sanksi sosialnya lebih berat dari hukuman fisik. Nama baik tercoreng, keluarga malu, dan mungkin sulit menikah di kemudian hari karena aib sudah tersebar. Namun demikian, adanya hukuman formal (cambuk/denda) memperkuat norma tersebut. Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, di Aceh “pacaran” yang kelewat batas bukan cuma urusan pribadi tapi delik pidana syariah.
Bagi generasi muda Aceh, aturan ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka tumbuh dalam kontrol moral yang ketat – jam malam informal bagi gadis, razia rutin di tempat wisata atau hotel, larangan berdua-duaan kecuali ada kawan lain. Hal ini bertujuan melindungi mereka dari zina dan menjaga marwah keluarga. Tapi di sisi lain, hasrat alamiah remaja untuk mengenal lawan jenis kadang mencari celah-celah sempit. Ada anekdot populer: muda-mudi Aceh cenderung memilih “jalan memutar” seperti bertemu diam-diam di luar kota atau berkomunikasi mesra lewat media online untuk menghindari patroli WH. Karena itulah, sebagian kasus khalwat justru terbongkar karena warga (orang ketiga) yang melapor, bukan kepergok di tempat umum. Semakin tersembunyi mereka pergi, semakin riskan jika dipergoki.
Namun tidak semua kasus pergaulan lawan jenis berakhir tragis. Ada banyak pula pemuda-pemudi yang menjaga batas, bertemu di tempat umum dengan sopan, ditemani kerabat, dsb., sesuai anjuran adat peumulia jamee (saling menjaga kehormatan). Tradisi “jah ra’uh” (melamar resmi melalui keluarga) tetap hidup; banyak pasangan yang memilih jalur taaruf atau minimal melibatkan keluarga sejak awal, sehingga menghindari situasi khalwat. Meski begitu, kecenderungan era kini, usia nikah semakin mundur karena alasan pendidikan dan karir. Masa lajang yang lebih panjang berarti interaksi pria-wanita non-mahram tak terelakkan, entah di kampus, kantor, atau organisasi. Di sinilah benturan sering terjadi: norma syariat vs realitas modern. Contoh, di Lhokseumawe tahun 2018, sempat viral aturan wali kota yang melarang pria dan wanita non-mahram duduk berduaan di warung kopi setelah Maghrib. Kebijakan ini dicetuskan untuk mencegah maksiat, tapi sebagian kaum muda mengeluh “kami hanya diskusi tugas kuliah pun dicurigai”.
Antropologi hukum Aceh melihat dinamika ini sebagai proses lokal “pengendalian sosial religius”. Ada semacam kontrak sosial bahwa demi identitas Aceh yang islami, individu rela hak privasinya dibatasi. Banyak pemuda Aceh sebenarnya mendukung prinsip syariat, namun mereka juga menghadapi dilema naluriah. Salah satu contohnya, sejumlah mahasiswa di Banda Aceh yang diwawancarai mengaku setuju khalwat dilarang tapi mereka merasa kurang difasilitasi untuk mencari jodoh secara sehat. Tuntutan ekonomi menghalangi menikah muda, sementara pacaran dilarang – akhirnya beberapa memilih nikah siri diam-diam agar bisa bersama tanpa melanggar hukum (namun memunculkan problem lain seperti kurangnya tanggung jawab jangka panjang).
Kritik terhadap penegakan norma ini juga datang. Kalangan pegiat HAM mempertanyakan apakah menghukum cambuk remaja untuk kesalahan tanpa korban (victimless crime) seperti bermesraan itu efektif atau justru trauma. Ada pula isu ketidakadilan: konon, pasangan dari kalangan berada atau pejabat jarang tersentuh razia, sementara rakyat biasa cepat dihukum – hingga muncul ungkapan sinis “syariat untuk si miskin” saja. Beberapa peristiwa memperkuat kesan itu, misalnya ketika pada 2021 seorang oknum pejabat Aceh tertangkap khalwat tapi proses hukumnya dianggap lamban dibanding kasus rakyat biasa.
Terlepas dari pro kontra, nilai budaya Aceh sangat menekankan kehormatan. Konsep hormat ini erat kaitnya dengan kontrol pergaulan. Bagi keluarga Aceh, memiliki anak gadis yang “tercemar” dalam pergaulan merupakan pukulan martabat besar. Demikian pula sebaliknya, anak bujang yang berbuat malu akan mencoreng muka orang tua. Oleh sebab itu, aturan syariat yang ketat dipandang sebagai cara melindungi keluarga dari malu. Sebelum era formal syariat, sebenarnya mekanisme adat juga ada: pelanggar khalwat dijatuhi sanksi adat (misal dinikahkan paksa atau didenda uang hangus). Yang berubah kini hanyalah bentuk hukumannya dan melibatkan pemerintah.
Dengan penerapan syariat, Aceh mencoba mempertahankan “kesucian” hubungan lelaki-perempuan pra-nikah di tengah zaman yang makin permisif di luar sana. Tantangannya tidak ringan, karena informasi dan pengaruh luar tak bisa dibendung. Remaja Aceh tahu bagaimana gaya pacaran di tempat lain lewat film atau internet. Sebagian mungkin penasaran atau tergoda mencoba. Maka pergulatan terjadi di tingkat individu: kepatuhan vs keinginan. Di sinilah peran keluarga dan pendidikan moral menjadi benteng pertama, sebelum urusan sampai ke WH. Pesantren dan sekolah di Aceh menekankan pendidikan akhlak tentang menjaga diri, sementara orang tua mengawasi dan menasehati.
Akhirnya, potret “pergaulan bebas” di Aceh adalah potret upaya sebuah komunitas merespons modernitas dengan kearifan lokal agama. Bagi antropolog, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya bisa sangat menyatu: ketika sepasang remaja bergandengan tangan di tempat sepi, itu bukan sekadar dua individu melainkan sebuah pelanggaran nilai komunal. Cerita-cerita nyata pelaku khalwat yang dicambuk di muka umum menjadi semacam narasi kolektif yang meneguhkan batas-batas moral di masyarakat Aceh.
Peran Pesantren dalam Menjaga Nilai Keluarga
Dini hari sekitar pukul 4 subuh di sebuah dayah (pesantren) tradisional di Aceh Barat, suara pukulan kentongan membangunkan para santri. Dari bilik-bilik asrama sederhana, ratusan remaja putra bergegas ke sumur wudhu dengan kain sarung tergulung di pundak. Pagi buta itu mereka shalat Tahajud berjamaah, kemudian melanjutkan membaca Kitab Kuning berbahasa Arab Melayu diterangi lampu neon temaram. Pemandangan ini rutin setiap hari – sebuah disiplin ketat yang telah membentuk karakter generasi demi generasi anak Aceh.
Pesantren (dayah) memegang peran sentral dalam pewarisan nilai dan pembentukan karakter keluarga Aceh. Sejak masa Kesultanan Aceh hingga kini, dayah bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi juga benteng moral masyarakat. Banyak orang tua – terutama di kawasan seperti Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat – mempercayakan anak remajanya nyantri di dayah demi memastikan mereka tumbuh di bawah pengawasan ulama dan jauh dari pengaruh buruk. Di dayah, para santri diajarkan adab menghormati orang tua, pentingnya menjaga kehormatan diri, dan tanggung jawab sebagai calon kepala keluarga kelak. Nilai-nilai ini kemudian dibawa pulang saat liburan, mempengaruhi lingkungan keluarga masing-masing.
Dalam konteks tantangan keluarga modern yang telah dipaparkan (dari pergaulan bebas, narkoba, hingga krisis moral di media sosial), pesantren hadir laksana oase ketenangan. Para alumni dayah umumnya menjadi panutan di kampungnya: baik yang jadi teungku imam masjid, guru mengaji TPA, maupun sekadar ayah beranak-istri yang alim. Kearifan lokal Aceh menganggap orang berilmu agama tinggi memiliki “tuah” tersendiri, sehingga nasihat-nasihatnya didengar soal urusan keluarga. Misalnya, kalau ada suami istri konflik di desa, seringkali akan mengundang teungku dayah atau imam untuk menasihati agar rukun kembali. Begitu pula jika remaja kampung mulai nakal, orang tua akan mendorong mereka ikut “pengajian kaffah” di dayah selama beberapa waktu untuk dibina.
Belakangan, peran pesantren bahkan diperluas dalam hal yang tak terduga seperti rehabilitasi pecandu narkoba. Menyadari kian maraknya penyalahgunaan sabu dan ganja di kalangan pemuda, tokoh ulama karismatik Aceh seperti Tu Bulqaini Tanjungan berinisiatif mendirikan dayah khusus rehabilitasi narkoba bernuansa Islami di pedalaman Bireuen. Dayah bernama Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah ini menampung para pecandu layaknya santri – mereka tinggal mondok, mengikuti kegiatan ibadah dan mengaji setiap hari, sambil perlahan dijauhkan dari candu zat adiktif. Uniknya, pendirian dayah rehabilitasi ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat termasuk mantan kombatan GAM dan penduduk sekitar yang bergotong-royong menyediakan lahan dan menjaga ketertiban. Fenomena ini menunjukkan kepercayaan publik Aceh bahwa pendekatan spiritual dan komunitas bisa efektif memulihkan generasi muda yang tersesat, lebih daripada pendekatan medis semata. “Di dayah, para pecandu dapat dengan total merehab dirinya dari narkoba dan juga dapat kembali mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dan pasti ada dayah yang bersedia,” ujar Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2018 Zainal Arifin, mendorong adanya panti rehabilitasi berbasis dayah di ibukota provinsi.
Pesantren juga menjadi agen penjaga tradisi di tengah perubahan. Contohnya, nilai kedermawanan, gotong royong, sopan santun kepada orang tua – hal-hal yang mungkin tergerus arus modern – terus ditekankan dalam kurikulum informal dayah. Di Dayah MUDI Mesra Samalanga (Bireuen) yang terkenal, santri harus melewati pendidikan akhlak ketat: mencium tangan guru, makan berjamaah di talam untuk melatih kebersamaan, hingga membersihkan kamar mandi sebagai latihan rendah hati. Ketika lulusan dayah ini kembali ke keluarga, harapannya mereka membawa aura positif: menjadi anak yang berbakti, suami/istri yang sabar, serta ayah/ibu yang penyayang dan bermoral.
Tak hanya menggembleng remaja, dayah juga aktif dalam menyikapi isu sosial keluarga. Majelis ulama dayah (seperti Himpunan Ulama Dayah Aceh/HUDA) kerap mengeluarkan tausiyah terkait problem keluarga kontemporer. Misalnya soal perceraian tinggi – ulama dayah menyerukan pasangan untuk memperkuat komunikasi dan sabar, sekaligus mengkritik pemerintah agar membatasi akses judi online. Dalam isu pergaulan bebas, dayah mendukung penerapan qanun syariat namun juga mengingatkan pendekatan harus hikmah (bijaksana) agar generasi muda tidak menjauh dari agama karena merasa diawasi berlebihan.
Lebih menarik lagi, sebagian pesantren kini membuka diri untuk kaum ibu. Di beberapa tempat, ada dayah khusus wanita atau “dayah balai pengajian” tempat ibu-ibu berkumpul tiap pekan mendengar ceramah. Ini turut meningkatkan pengetahuan para ibu rumah tangga tentang fiqih keluarga, hak-hak dalam pernikahan, cara mendidik anak secara Islami, dll. Hal ini penting karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Dengan memperkuat peran ibu melalui pesantren, dampaknya langsung ke kualitas generasi mendatang.
Tentu, pesantren Aceh juga menghadapi tantangan modern. Ada anggapan sebagian kalangan muda “hidup di dayah itu ketinggalan zaman”, apalagi dengan fasilitas minim (tidur beralas tikar, jauh dari gawai). Namun banyak orang tua yang sadar bahwa tempaan kehidupan sederhana di dayah justru membuat anak tahan uji. Beberapa alumni dayah bahkan sukses melanjutkan studi tinggi dan memimpin perubahan. Misalnya, Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad – penulis makalah ini – adalah seorang antropolog yang lahir dari tradisi dayah sebelum melanglang buana secara akademis. Ia dan tokoh sejenis menjadi bukti bahwa insan berakar dayah mampu lentur menghadapi dunia modern tanpa kehilangan jati diri.
Kesimpulannya, peran pesantren/dayah bagi keluarga Aceh tak tergantikan: sebagai penjaga moral, solusi sosial, sekaligus jembatan antar-generasi. Ketika keluarga inti goyah oleh gempuran zaman, dayah hadir menguatkan keluarga besar melalui pendidikan iman. Mungkin di kota-kota besar peran ini telah diambil alih institusi lain, tapi di Aceh, cahaya lampu teungku dayah di malam hari masih menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya.
Cyberbullying dan Tantangan Dunia Maya bagi Generasi Muda Aceh
Sore itu, di sebuah ruang tamu rumah di Sigli, seorang ibu tampak cemas menenangkan putrinya yang baru pulang sekolah dengan mata sembab. Sang putri, siswi SMP, menjadi pendiam akhir-akhir ini. Usut punya usut, ia mengalami bullying dari teman-temannya bukan secara fisik, melainkan lewat grup WhatsApp kelas. Beberapa kawan mengejek dan mengisolasinya di dunia maya hingga mentalnya tertekan. Kasus seperti ini menandai munculnya dimensi baru tantangan keluarga Aceh: cyberbullying atau perundungan digital terhadap anak-anak dan remaja.
Aceh mungkin relatif terlambat terekspos internet dibanding kota besar lain, tetapi kini penetrasi gawai sudah meluas hingga pelosok. Mayoritas remaja Aceh aktif di media sosial – Facebook, Instagram, TikTok – dan tak sedikit yang memiliki smartphone sendiri bahkan sejak SD. Kondisi ini membuka potensi konflik sosial di ranah daring. Sebuah penelitian di Banda Aceh menemukan 94,14% remaja yang menjadi partisipan menunjukkan perilaku perundungan siber dalam kategori rendah[3] (artinya, mereka pernah melakukan bullying online hanya 1–4 kali, tidak sering). Bentuk cyberbullying bermacam-macam: ejekan, pengucilan (exclusion), penyebaran rumor, hingga peniruan identitas palsu. Ironisnya, banyak pelaku mengaku sekadar “bercanda” dan tidak sadar bahwa perbuatannya tergolong perundungan siber dan bisa berdampak serius[4][5].
Pada 2023, DP3A Aceh secara khusus memperingatkan bahaya bullying (termasuk cyberbullying) di sekolah-sekolah. Dalam sebuah sosialisasi di MAN 1 Aceh Barat, pejabat DP3A mengingatkan bahwa perundungan anak sangat berbahaya karena bisa berujung pada keinginan korban untuk bunuh diri. “Bullying ini sangat berbahaya karena bisa berujung pada keinginan korbannya untuk bunuh diri,” tegas Chairil Amri dari DP3A Aceh. Program bernama Silaturahmi Sikula (Simila) dijalankan, melibatkan guru dan siswa untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif, apalagi sebagian besar waktu remaja dihabiskan di sekolah (terutama yang berasrama). Pihak sekolah didorong memasang CCTV di titik rawan dan memperkuat pengawasan serta edukasi agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi perundungan.
Cyberbullying di Aceh punya karakteristik khas: kadang berkelindan dengan sentimen agama atau suku. Misal, seorang anak diledek di Instagram karena fotonya tidak pakai jilbab (padahal mungkin masih kanak-kanak) dengan komentar “tidak Islami”. Atau sebaliknya, ada yang di-bully karena dianggap “sok Arab” terlalu agamis. Policing moral oleh teman sebaya di dunia maya dapat terjadi, menciptakan tekanan agar remaja conform demi diterima. Fenomena akun anonim yang mempermalukan orang (semacam “Lambe Aceh” di medsos) pun sempat ada, membongkar aib pribadi dengan motif hiburan. Ini semua menandakan bahwa budaya malu Aceh yang kental bisa dieksploitasi menjadi senjata perundungan digital.
Dampak cyberbullying merambah ke keluarga. Orang tua yang gagap teknologi sering terlambat menyadari anaknya menjadi korban atau pelaku. Tiba-tiba ada kasus anak bunuh diri karena depresi bullying di provinsi lain, dan hal itu membuat para orang tua Aceh ketar-ketir: “Jangan sampai terjadi di sini.” Maka, lahirlah adaptasi gaya parenting baru – beberapa orang tua di Banda Aceh membentuk komunitas parenting digital, saling berbagi tips mengawasi aktivitas online anak. Ada yang memasang aplikasi kontrol orang tua di HP anak, ada pula yang dengan pendekatan religius mengajak anak berdialog soal etika Islam di media sosial (misal mengingatkan dosa gibah, larangan menyakiti orang).
Peran ulama dan pendidik juga penting. Majelis adat Aceh sempat mengeluarkan imbauan bahwa gibah dan fitnah via sosmed hukumnya haram dan melanggar qanun. Di pesantren, para santri diingatkan untuk berakhlak mulia bahkan di dunia maya. Salah satu pimpinan dayah di Aceh Besar, Ustadz Masrul Aidi, bekerja sama dengan BNN menyampaikan pesan anti-narkoba dan bahaya pergaulan menyimpang melalui video Instagram untuk seluruh masyarakat Aceh – contoh bahwa tokoh agama mulai memanfaatkan platform digital demi kebaikan, sekaligus melawan konten negatif termasuk bullying.
Selain itu, penegak hukum turut menyesuaikan langkah. Kepolisian Aceh tak segan memproses kasus cyberharassment jika ada laporan, menggunakan UU ITE. Walau pendekatan hukum bukan solusi tunggal, keberadaannya menandakan perundungan online dipandang serius. Ada contoh kasus mahasiswa di Aceh Timur ditangkap karena menghina tokoh di Facebook – meski itu bukan bullying antarpelajar, tetapi menunjukkan bahwa tindakan di dunia maya bisa berimplikasi nyata.
Secara kultural, Aceh sedang melalui proses pembelajaran menghadapi era digital. Dulu, tantangan remaja mungkin terbatas pada kenakalan konvensional; kini, medan pergaulannya meluas ke jagat maya. Solidaritas sosial Aceh yang dulunya dibangun lewat kontak langsung (majelis, gotong royong) kini harus menerjemahkan diri ke solidaritas online – misal saling menegur kawan yang keterlaluan di grup, atau melaporkan akun anonim jahat bersama-sama hingga ditutup. Nilai islami “amar ma’ruf nahi munkar” mendapat konteks baru di internet: menegur yang melakukan bullying adalah amar ma’ruf, mencegah penyebaran fitnah adalah nahi munkar.
Kesadaran ini pelan-pelan tumbuh. Sudah ada kisah di mana satu kelas sepakat melindungi temannya yang dibully dengan cara melaporkan akun pelaku ramai-ramai hingga kena suspend. Atau alumni sekolah yang datang memberikan seminar dampak bullying dengan membawa korban yang telah pulih untuk berbagi cerita. Hal-hal demikian menandai bahwa Aceh, dengan semangat komunitasnya, dapat merespons ancaman cyberbullying secara komunal pula.
Sebuah keluarga Aceh ideal di era kini tak cukup hanya membimbing anak di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Orang tua perlu menjadi “pendamping digital” bagi anak: mengetahui siapa kawan-kawan online-nya, apa saja yang ia hadapi di internet, dan membangun kepercayaan agar anak mau curhat jika mendapat masalah. Tantangan ini berat bagi generasi orang tua yang tak dibesarkan dalam budaya internet. Namun demi melindungi jiwa anak, banyak orang tua Aceh tak menyerah – mereka ikut belajar mengoperasikan gadget, minimal untuk memantau.
Dari tinjauan antropologis, adaptasi masyarakat Aceh terhadap cyberbullying adalah bagian dari proses lebih besar: adaptasi nilai tradisional ke ranah virtual. Nilai utama seperti kehormatan, sopan santun, semangat kekeluargaan – harus dibawa dan ditegakkan pula dalam interaksi digital. Mungkin akan butuh waktu dan beberapa “benturan” kasus untuk betul-betul tertanam. Namun arah ke sana sudah nampak, ditandai langkah-langkah proaktif berbagai pihak di Aceh.
Narkoba dan Dampaknya terhadap Keluarga Aceh
Di pojok Lhokseumawe, seorang ibu menangis tersedu-sedu menyaksikan anak lelakinya digiring polisi. Pemuda 21 tahun itu ditangkap karena diduga menjadi kurir sabu-sabu jaringan Medan–Aceh. Pemandangan penangkapan pengguna dan pengedar narkoba semakin sering terlihat di Aceh dalam satu dekade terakhir. Narkoba telah menjadi ancaman serius bagi keluarga-keluarga Aceh, merusak tidak hanya individu pemakainya tetapi juga menghancurkan harapan orang tua, pasangan, dan anak-anak.
Provinsi Aceh pernah identik dengan ganja – “ganja Aceh” tersohor sebagai salah satu kualitas terbaik di pasar gelap. Secara historis, tanaman ganja sempat ditoleransi di pedesaan sebagai bumbu masak atau obat tradisional, meski ilegal. Namun skala peredarannya kini mengkhawatirkan, ditambah masuknya narkotika lain seperti sabu (methamphetamine) dari luar. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh pada 2025 mengungkapkan penurunan prevalensi penggunaan narkoba di Aceh dalam dua tahun terakhir – dari 1,95% populasi menjadi 1,73%, setara sekitar 80.000 orang pengguna. “Sekitar 80.000 orang dari seluruh Aceh,” sebut Kepala BNNP Aceh Marzuki Ali Basyah pada Juli 2025. Dari jumlah tersebut, lebih 80% merupakan pengguna ganja, sisanya narkoba jenis lain seperti sabu, ekstasi, dsb.
Meski persentasenya menurun sedikit, angka absolut pengguna tetap tinggi. Program pemberantasan narkoba pun digencarkan. BNNP Aceh meluncurkan Program Berdikari Tani, bagian dari strategi Alternative Development berbasis pertanian produktif di desa-desa rawan narkoba. Contohnya di Gampong Leugeu, Aceh Besar, penduduk dilatih menanam palawija sebagai alternatif ekonomi agar tidak tergiur menanam ganja atau terlibat jaringan narkoba. Program ini dilengkapi pembentukan Relawan Anti Narkoba di tingkat gampong – melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketahanan sosial dari infiltrasi pengedar.
Bagi keluarga, kehadiran narkoba membawa nestapa multi-dimensi. Secara ekonomi, banyak rumah tangga hancur karena kepala keluarga terjerat sabu dan menghabiskan penghasilan untuk beli barang haram. Secara psikologis, istri dan orang tua hidup dalam kecemasan, sedangkan anak-anak sering terbengkalai. Ada kasus di Aceh Tamiang di mana tiga saudara kandung semuanya kecanduan sabu karena orang tuanya juga pemakai – efeknya anak-anak ini drop out sekolah dan keluarga mereka dikucilkan tetangga. Tragedi semacam ini menggerakkan komunitas untuk bertindak.
Budaya Aceh yang komunal mencoba menjawab persoalan narkoba dengan pendekatan komunitas pula. Seperti telah diuraikan, muncul dayah rehabilitasi bentukan ulama yang menawarkan metode “pemulihan jiwa lewat agama”. Pemerintah pun mendukung: BNNP Aceh membuka layanan rehabilitasi gratis di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) provinsi, dan berencana memperluas kapasitas karena banyaknya pecandu yang ingin pulih. Tidak jarang, keluarga terpaksa menyerahkan anaknya ke aparat agar diproses hukum demi efek jera. Langkah pahit ini misalnya dialami seorang ayah di Bireuen yang melapor anaknya sendiri ke polisi karena berkali-kali mencuri barang di rumah untuk beli sabu. Dalam tangis, ia berkata: “Biarlah dipenjara, daripada mati OD (overdosis) atau dibakar massa.” Pilihan sulit seperti ini menandakan putus asanya keluarga menghadapi candu narkoba.
Budaya gotong royong Aceh berperan pula dalam pemulihan. Banyak mantan pecandu yang telah direhab kemudian dibimbing tokoh masyarakat setempat agar kembali produktif. Mereka diajak ikut kegiatan desa, diberi pelatihan keterampilan, bahkan difasilitasi menikah agar punya tanggung jawab baru. Di satu desa di Aceh Utara, misalnya, aparat gampong secara khusus membuat “kelompok usaha bersama” bagi pemuda eks-pengguna narkoba untuk beternak ikan lele. Langkah-langkah ini bertujuan mengikis stigma dan mencegah mereka kambuh.
Bagi komunitas Aceh, perang melawan narkoba dianggap jihad masa kini – upaya menyelamatkan generasi. Ulama-ulama karismatik dalam ceramah mereka menyamakan para bandar narkoba dengan “musuh agama” yang tak kalah berbahaya dari penjajah, karena merusak umat dari dalam. Pesan ini efektif menggerakkan dukungan masyarakat bagi penegak hukum. Ketika Polres atau BNN melakukan penggerebekan ladang ganja di pedalaman, warga setempat sering dilibatkan sebagai penunjuk jalan atau saksi pemusnahan. Begitu juga saat sosialisasi bahaya narkoba, warga hadir berbondong-bondong. Semangat kolektif ini menjadi modal penting.
Namun, tantangan tetap besar. Letak Aceh yang strategis di jalur perdagangan narkotika internasional membuat suplai sukar dibendung. Hampir tiap bulan ada saja penyelundupan sabu via laut yang digagalkan – misal Polda Aceh pernah memusnahkan 226 kg sabu dan 1,2 ton ganja hasil tangkapan dalam setahun. Selama pasar dan permintaan ada, tekanan terhadap keluarga Aceh terus berlanjut.
Tugas berat ke depan adalah menekan demand dari sisi pengguna. Pemerintah dan masyarakat Aceh tampaknya menyadari hal ini: pemberantasan tak cukup dengan penangkapan, tapi juga dengan pendidikan dan pemberdayaan. Kurikulum sekolah di Aceh kini memasukkan bahaya narkoba secara eksplisit. Organisasi kepemudaan Aceh (seperti BKPRMI dan OSIS) aktif menggelar kampanye “Pemuda Tanpa Narkoba”. Bahkan di pesantren, para santri dibekali ceramah tentang dosa narkoba dan cara menasihati teman sebaya yang telanjur pakai. Harapannya, muncul imunisasi sosial sehingga pemuda Aceh sendiri menolak narkoba.
Secara antropologis, respons Aceh terhadap narkoba menunjukkan adaptasi nilai jihad dan gotong royong ke dalam konteks baru. Keluarga-keluarga Aceh, yang dulu bahu-membahu melewati masa konflik, kini bergandeng tangan melawan ancaman dari zat adiktif. Kesedihan ibu-ibu karena anaknya terjerat narkoba telah melahirkan gerakan doa bersama dan pengajian memohon perlindungan generasi.
Akhir kata, narkoba adalah ujian berat, tapi Aceh bukan asing terhadap ujian. Sejarah Aceh penuh contoh daya tahan komunitas menghadapi guncangan. Dengan iman dan ikhtiar kolektif, banyak yang percaya keluarga Aceh mampu melalui krisis narkoba ini. Ibarat orang Aceh berkata: “Udep saree mate syahid” – hidup mulia atau mati syahid – demikian pula dalam perang melawan narkoba, masyarakat Aceh bersatu memilih hidup mulia tanpa barang haram daripada hancur karenanya.
Nikah Siri: Dilema Legalitas dan Tradisi
Di sebuah balai desa di Bireuen, terjadi keributan kecil. Seorang wanita muda bersama bayinya datang mengadu ke aparat gampong, mengaku sebagai istri kedua seorang pejabat yang menikahinya secara siri (tidak tercatat resmi). Ia merasa ditelantarkan dan menuntut pengakuan. Kasus ini membuka kembali perbincangan hangat di Aceh tentang nikah siri – praktik pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa dicatat negara.
Nikah siri sebenarnya bukan hal baru di Aceh. Dulu, dalam masyarakat tradisional terpencil, banyak pernikahan hanya menurut adat dan syariat tanpa administrasi negara karena alasan akses dan birokrasi. Masyarakat menganggap asalkan rukun nikah terpenuhi (wali, saksi, ijab qabul, mahar), maka pernikahan sah di mata agama, urusan surat bisa belakangan. Namun di era modern, dampak nikah siri dirasakan merugikan terutama kaum perempuan dan anak. Istri siri tak punya buku nikah, sehingga hak-hak hukumnya rapuh: ia sulit menuntut nafkah di pengadilan, anaknya susah mengurus akta (perlu isbat nikah dulu), dan rentan ditinggalkan tanpa status jelas.
Salah satu kompleksitas nikah siri di Aceh terkait praktik poligami tersembunyi. Beberapa pria yang ingin beristri lebih dari satu memilih jalur nikah siri agar tak perlu izin istri pertama (sesuai undang-undang). Akibatnya, istri kedua/ketiga ini menjadi “istri rahasia” yang tidak diakui legal. Saat ketahuan, konflik keluarga pun besar, seperti cerita di Bireuen tadi di mana pejabat terkait dicopot dari jabatannya setelah istri sirinya mengadu karena merasa dizalimi[6]. Fenomena ini cukup banyak, sehingga pemerintah Aceh pernah berencana mengatur secara khusus poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga (2019). DPRA Aceh berdalih salah satu alasan perlunya poligami diatur adalah karena maraknya kasus nikah siri di Aceh saat ini[7]. Namun usul qanun poligami ini menuai perdebatan sengit. Kelompok aktivis perempuan menolak; menurut mereka, jika tujuannya melindungi perempuan korban nikah siri, solusinya bukan melegalkan poligami. Isu nikah siri di Aceh dianggap kompleks – banyak terjadi dulu karena masa konflik KUA tidak berfungsi, dan program isbat nikah pun belum tuntas hingga kini[8]. Aktivis menilai rancangan qanun itu justru berisiko semakin merugikan pihak perempuan karena memuat pasal yang multitafsir dan mengabaikan hak istri menolak poligami[9].
Nikah siri juga kerap terjadi dalam kasus hamil di luar nikah sebagai upaya “menutup malu”. Sepasang muda-mudi yang terlanjur melampaui batas akhirnya dinikahkan siri cepat-cepat agar status kehamilan tertutupi. Setelahnya, ada yang menikah ulang resmi di KUA, tapi ada juga yang tidak. Ini menimbulkan implikasi: anak lahir nanti tak mudah memperoleh dokumen karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Masyarakat Aceh cenderung memaklumi nikah “kilat” semacam ini demi menjaga marwah keluarga, namun sedikit yang memikirkan aspek legal jangka panjang.
Dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri (selama memenuhi syarat agama) adalah sah. Namun dari kacamata negara modern, ia tidak diakui. Di Aceh, yang unik adalah adanya penerimaan kultural terhadap nikah siri dalam kasus tertentu, misal untuk duda/janda yang ingin menikah diam-diam agar tidak mengganggu harta gono-gini keluarga sebelumnya. Atau lelaki yang menikahi gadis sangat muda (di bawah umur legal) secara siri sambil menunggu cukup umur untuk dicatat. Kasus semacam ini ditoleransi di level komunitas, tetapi di level kebijakan hal itu berlawanan dengan upaya perlindungan anak dan perempuan.
Pemerintah Aceh melalui Kemenag dan Dinas Syariat Islam terus melakukan edukasi soal pentingnya pencatatan pernikahan. KUA di berbagai kabupaten mengadakan sidang isbat nikah massal untuk melegalkan ratusan pasangan lansia yang dulu nikah siri agar punya akta nikah. Pada 2022 misalnya, di Aceh Utara diadakan isbat untuk pasangan lanjut usia yang sudah puluhan tahun menikah tapi belum tercatat. Hal ini membantu anak-anak mereka mendapatkan akta kelahiran, warisan, dan hak hukum lainnya. Gerakan ini lumayan berhasil di generasi lebih tua, tapi di generasi muda, nikah siri justru muncul dengan motif baru seperti tadi (poligami sembunyi atau kondisi darurat tertentu).
Sikap ulama Aceh terhadap nikah siri terbelah. Ada yang menekankan segi sah agama saja, sehingga cenderung permisif asalkan secara syariat sah. Namun banyak ulama fiqh kontemporer di Aceh mendorong umat melaksanakan pernikahan sesuai aturan negara demi kemaslahatan (maslahah). Bagi mereka, pencatatan itu bagian dari tuntunan “taat ulil amri” (patuh pada pemimpin) selama tidak melanggar syariat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pernah mengeluarkan tausiyah agar setiap pernikahan dicatat negara, bahkan untuk poligami harus sesuai prosedur agar tidak terjadi mudarat.
Dilema nikah siri paling terasa saat terjadi konflik: ketika suami siri meninggalkan istri, sang istri tak bisa menuntut ke Mahkamah Syar’iyah karena ketiadaan bukti dokumen pernikahan. Banyak perempuan akhirnya meminta bantuan perangkat desa atau tokoh adat untuk menekan mantan suami secara kekeluargaan. Jalur informal ini kadang berhasil, kadang tidak. Pada akhirnya, penderitaan ditanggung perempuan dan anak.
Sebuah contoh menggetarkan terjadi di Aceh Selatan: seorang wanita siri ditolak keluarganya sendiri setelah suaminya pergi entah ke mana. Ia dianggap membawa malu karena nikah tanpa sepengetahuan resmi. Stigma sosial terhadap nikah siri memang ambigu – di satu sisi banyak dilakukan, di sisi lain jika gagal, wanita yang menanggung malu dan cemooh. Inilah kenapa kelompok aktivis gender di Aceh menentang pembiaran nikah siri. Mereka mendorong adanya aturan yang memberikan sanksi bagi laki-laki yang sengaja nikah siri untuk poligami tanpa izin, misalnya dijatuhi denda adat besar. Sebab selama ini hukum formal agak sulit menjamah jika tak ada pelanggaran pidana lain.
Di tingkat kebijakan, Pemerintah Aceh sempat mengajukan rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 yang di dalamnya memuat pasal tentang poligami dan nikah siri. Draft itu memicu debat nasional. Komnas Perempuan menilai legalisasi poligami bukan solusi melindungi perempuan dan anak yang selama ini jadi korban nikah siri[8]. Akhirnya rancangan qanun tersebut ditunda pembahasannya. Namun diskursus yang muncul justru positif: masyarakat jadi lebih paham soal risiko nikah siri.
Saat ini, pendekatan utama adalah persuasi dan fasilitasi. Banyak cerita suami istri muda yang awalnya nikah siri akhirnya mau isbat setelah kelahiran anak pertama, karena sadar pentingnya akta untuk sekolah anak. Pemerintah kabupaten kadang memberikan insentif, misal: gratis biaya isbat nikah dan penerbitan buku nikah. Ini cukup efektif.
Secara antropologis, nikah siri di Aceh berada di persimpangan norma agama, adat, dan hukum negara. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat mencoba menyiasati aturan formal demi alasan praktis atau normatif, namun kemudian menghadapi konsekuensi di era modern. Nilai kekeluargaan Aceh kadang membuat mereka menganggap urusan pernikahan “bisa diselesaikan sendiri” tanpa campur tangan pemerintah. Namun di lain pihak, kompleksitas administrasi modern memaksa berubah.
Bagi sebagian keluarga tradisional, pencatatan sipil dianggap sekuler dan kurang penting dibanding restu tokoh agama dan orang tua. Mereka merasa “yang menikahkan kami kan imam kampung, bukan negara”. Tantangannya adalah mensinergikan keduanya: bahwa kepentingan agama dan adat tetap dijunjung, tapi administrasi negara melengkapi demi kebaikan hakiki keluarga itu sendiri.
Konklusi umum di Aceh perlahan mengarah: pernikahan ideal adalah yang sah secara agama sekaligus tercatat legal. Muncul istilah “nikah syar’i sekaligus qanuni (legal)” dalam sosialisasi. Pada akhirnya, meski nikah siri tak akan lenyap sepenuhnya (karena selalu ada kasus khusus), masyarakat Aceh makin memahami bahwa transparansi dalam pernikahan lebih banyak maslahatnya. Toh, Islam sendiri menganjurkan “i’lanun nikah” (mengumumkan pernikahan) agar berkah dan jauh dari fitnah. Secara adat pun, Aceh punya tradisi walimah besar-besaran justru supaya semua tahu si A resmi jadi istri si B. Dengan mengingat ruh itu, bisa diharapkan nikah-nikah sembunyi akan berkurang.
Demikianlah rangkaian “deskripsi tebal” mengenai berbagai persoalan keluarga di Aceh yang telah diuraikan. Dari mahar pernikahan yang sarat makna namun membebani, hingga dilema nikah siri antara adat dan hukum; dari pahit-manis pernikahan lintas bangsa, sampai maraknya perceraian akibat gonjang-ganjing modernisasi; dari pengaruh media sosial dan pilihan hidup childfree yang menguji nilai tradisi, hingga upaya kolektif melawan KDRT, pergaulan bebas, cyberbullying, dan jerat narkoba – semua itu melukiskan sebuah masyarakat yang tengah melakukan tawar-menawar dinamis dengan perubahan zaman. Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Barat sebagai latar memberikan ragam konteks: kota kosmopolitan religius, kota industri dengan tradisi kuat, serta wilayah rural dengan kearifan lokalnya, namun benang merahnya sama yaitu kuatnya identitas Islam-Aceh sebagai landasan merespons persoalan.
Pendekatan antropologis reflektif di atas mencoba menampilkan suara-suara warga Aceh sendiri: kegelisahan orang tua, curahan hati perempuan, petuah ulama, canda tawa remaja, hingga kebijakan pemerintah daerah, semuanya berkelindan membentuk narasi kehidupan keluarga. Clifford Geertz pernah mengajarkan bahwa untuk memahami suatu budaya, kita harus menyelami makna di balik tindakan lahiriahnya. Maka dalam konteks Aceh, setiap fenomena keluarga – apakah itu mematok mahar tinggi, menikah diam-diam, menggugat cerai, mengekang pergaulan, atau mengirim anak ke pesantren – mengandung makna mendalam tentang apa yang dianggap baik, benar, dan perlu oleh masyarakat Aceh.
Akhirnya, keluarga-keluarga di Aceh ibarat perahu dalam dua arus: arus tradisi-syariat di satu sisi, dan arus modernitas-global di sisi lain. Kadang arus itu sejalan, kadang berlawanan. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan agar perahu tidak oleng. Dari paparan di atas, tampak bahwa orang Aceh berupaya keras mempertahankan nilai agama dan adat sebagai jangkar, sembari melakukan penyesuaian kreatif terhadap hal-hal baru. Ada ketegangan, ada inovasi. Di sanalah letak dinamika yang menarik sekaligus mengharukan.
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa studi etnografis ini baru menyentuh permukaan “lautan makna” dalam keluarga Aceh. Setiap tema masih menyisakan pertanyaan dan perkembangan yang terus berjalan. Namun satu hal jelas: keluarga tetap menjadi institusi sentral tempat benturan dan perajutan kembali budaya Aceh terjadi. Melalui keluarga, Aceh akan menentukan wajah masa depannya – apakah nilai-nilai luhur mampu bertahan atau larut, apakah masalah-masalah sosial dapat teratasi atau berulang. Optimisme muncul ketika melihat betapa komunitas Aceh mempunyai ketangguhan historis. Dengan dasar iman yang kuat dan budaya kolektif yang hidup, keluarga Aceh kemungkinan besar akan menemukan jalan untuk bertahan, berubah, dan tumbuh di tengah segala persoalan yang melingkupinya, persis seperti pepatah lokal: “tajak enda beusaree, tajak uba tamita” – yang patah tumbuh, yang hilang berganti, keluarga Aceh akan senantiasa membentuk harmoni baru di atas tantangan zaman.
[1] [2] Selebgram Hijab Aceh Viral Jadi Kontroversi, Belanja Dikawal 9 Ajudan
[6] Diduga Soal Poligami dan Nikah Siri, Pj Bupati Bireuen Copot Kadis Kesbangpol
[7] [8] [9] Rancangan Qanun Poligami di Aceh Diklaim Justru Akan Persulit Pria Berpoligami | Republika Online
Daftar Pustaka
Azhari, R. (2019, Oktober 18). 10 Remaja di Banda Aceh Dicambuk Akibat Khalwat dan Ikhtilath. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/12575991/10-remaja-di-banda-aceh-dicambuk-akibat-khalwat-dan-ikhtilath
Hasan, F. (2023, Maret 7). WNA Tiongkok Nikah Siri dengan Gadis Aceh, Kemenag Minta Ikuti Prosedur. Republika.co.id. https://www.republika.co.id/berita/rq88pa459
Kemenag RI. (2023). Laporan Statistik Bimbingan Masyarakat Islam Provinsi Aceh Tahun 2023. Banda Aceh: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. [diacu melalui statistik Mahkamah Syar’iyah dan KUA]
Marzuki Ali Basyah. (2025, Juli 26). BNNP Aceh: 80.000 Penduduk Aceh Pengguna Narkoba, Mayoritas Ganja. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/4285657
Miswar, M. (2023, Oktober 26). Mahkamah Syar’iyah Aceh: 2.923 Perkara Cerai Diterima Hingga Semester I 2023. Serambinews.com. https://aceh.tribunnews.com
Republika. (2021, Oktober 1). Nikah Lintas Negara di Sabang: Ijab Kabul Menggunakan Bahasa Inggris. Republika.co.id. https://www.republika.co.id/berita/r0mtdb459
Safriadi. (2019, Oktober 18). Komentar Kepala WH Banda Aceh atas Pencambukan 10 Remaja. Dikutip dalam: Azhari, R. (2019, Oktober 18). Kompas.com
Sari, D. (2024, Februari 5). Mayoritas Cerai di Aceh Diajukan Istri, Mahkamah Jantho Catat 176 Cerai Gugat. Serambinews.com. https://aceh.tribunnews.com
Serambinews.com. (2019, November 12). Dari Janda Konflik ke Janda Sabee. Tribunnews Aceh. https://aceh.tribunnews.com/2019/11/12/dari-janda-konflik-ke-janda-sabee
Sutari, T. (2023, Maret 20). DP3A Aceh Catat Kenaikan Kasus KDRT dari Tahun ke Tahun. Tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com
Tiara Sutari. (2023). Statistik KDRT dan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh. Disampaikan dalam wawancara dan laporan DP3A Provinsi Aceh. [Disitir dalam Serambinews.com]
Tribunnews.com. (2022, Juli 2). Tren Nikah Siri dan Rencana Qanun Poligami Aceh Menuai Penolakan. Tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com
Zainal Arifin. (2018, September 11). Wakil Wali Kota Banda Aceh Dorong Pendirian Dayah Rehabilitasi Narkoba. BicaraAceh.id. https://www.bicaraaceh.id/2018/09/11/wakil-wali-kota-banda-aceh-dayah-narkoba


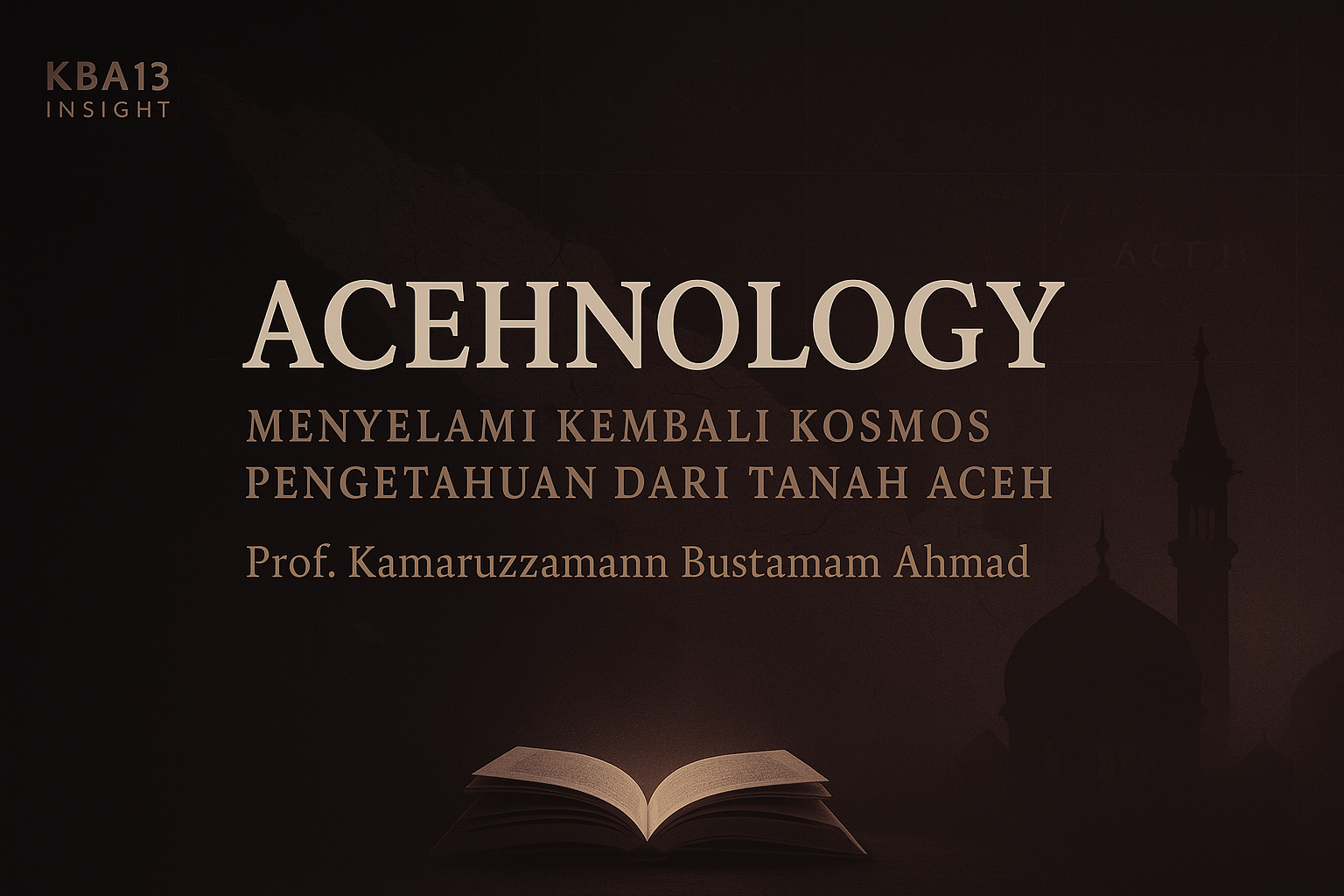
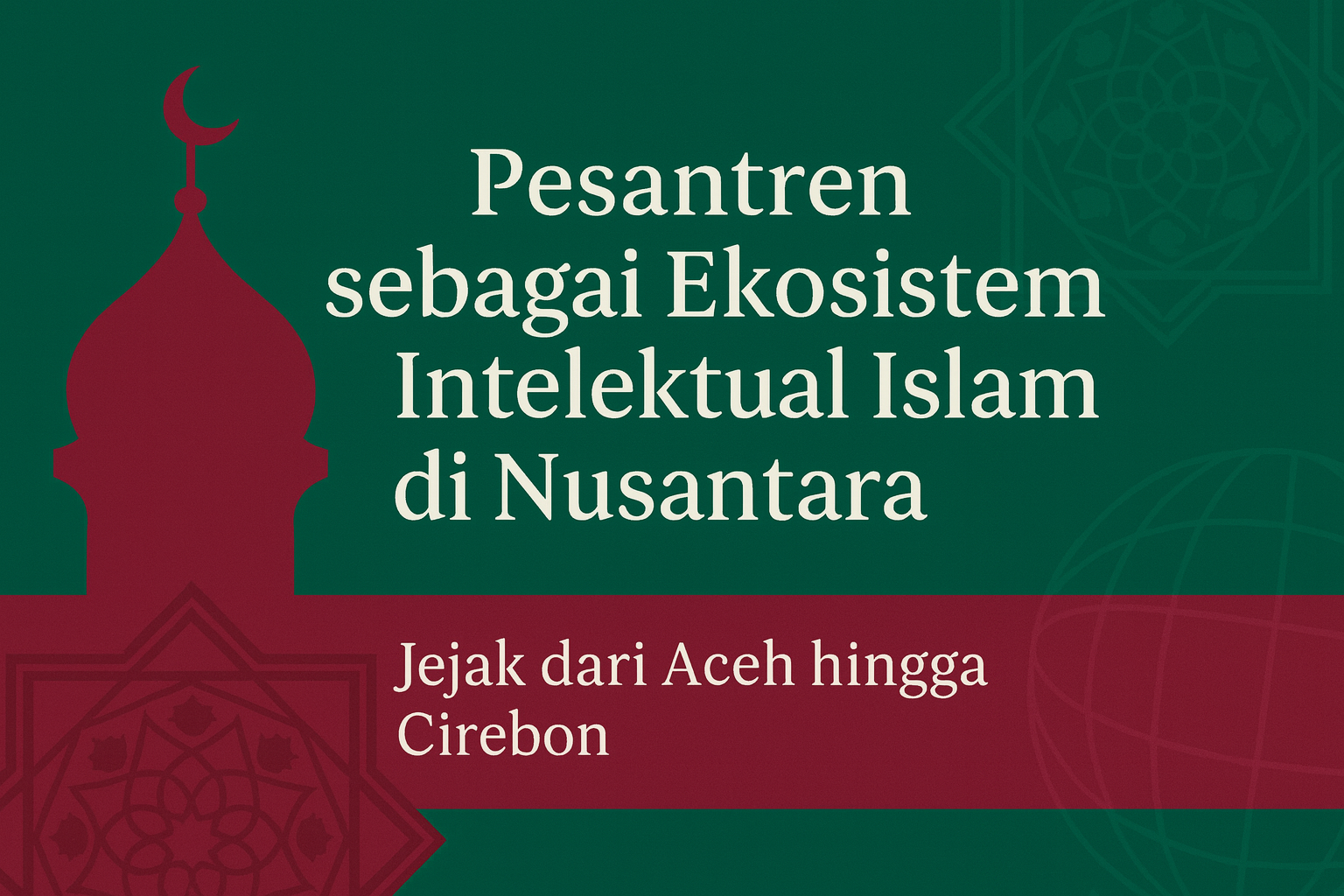
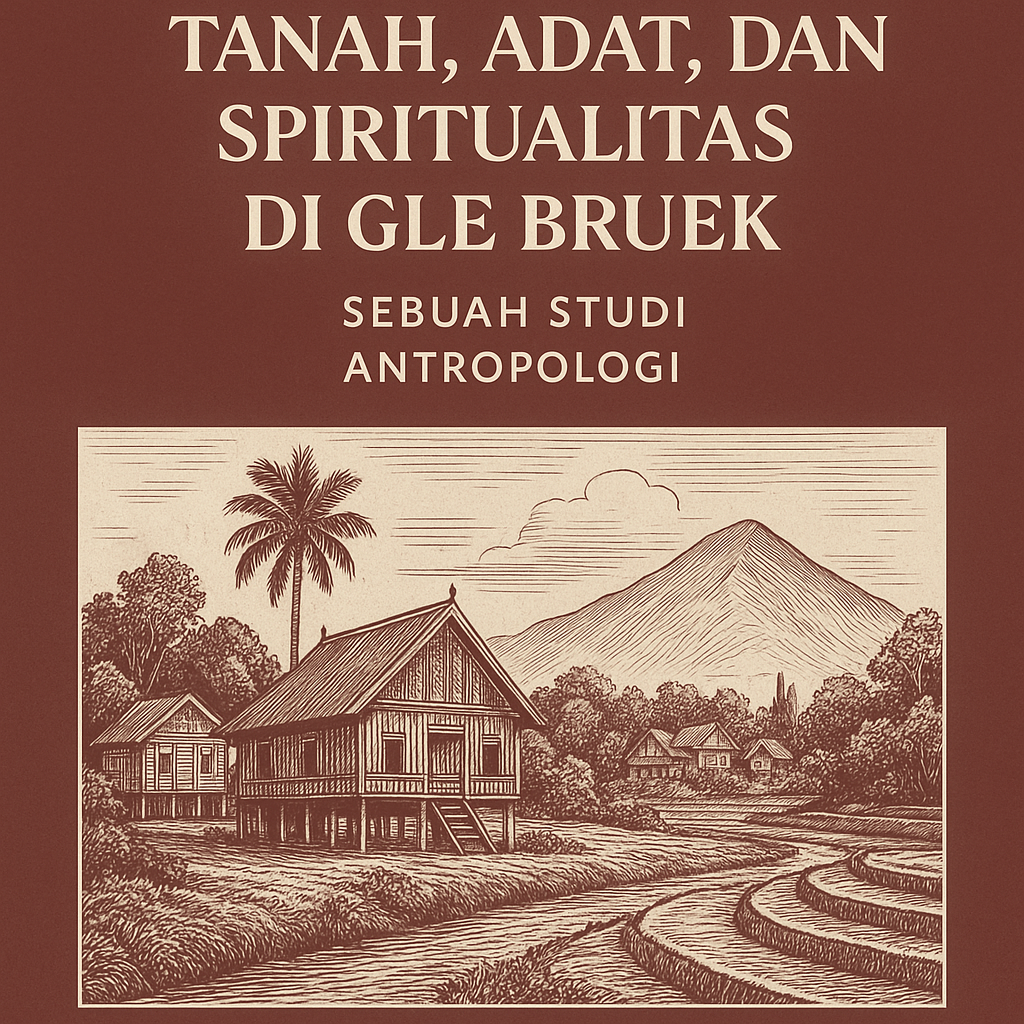


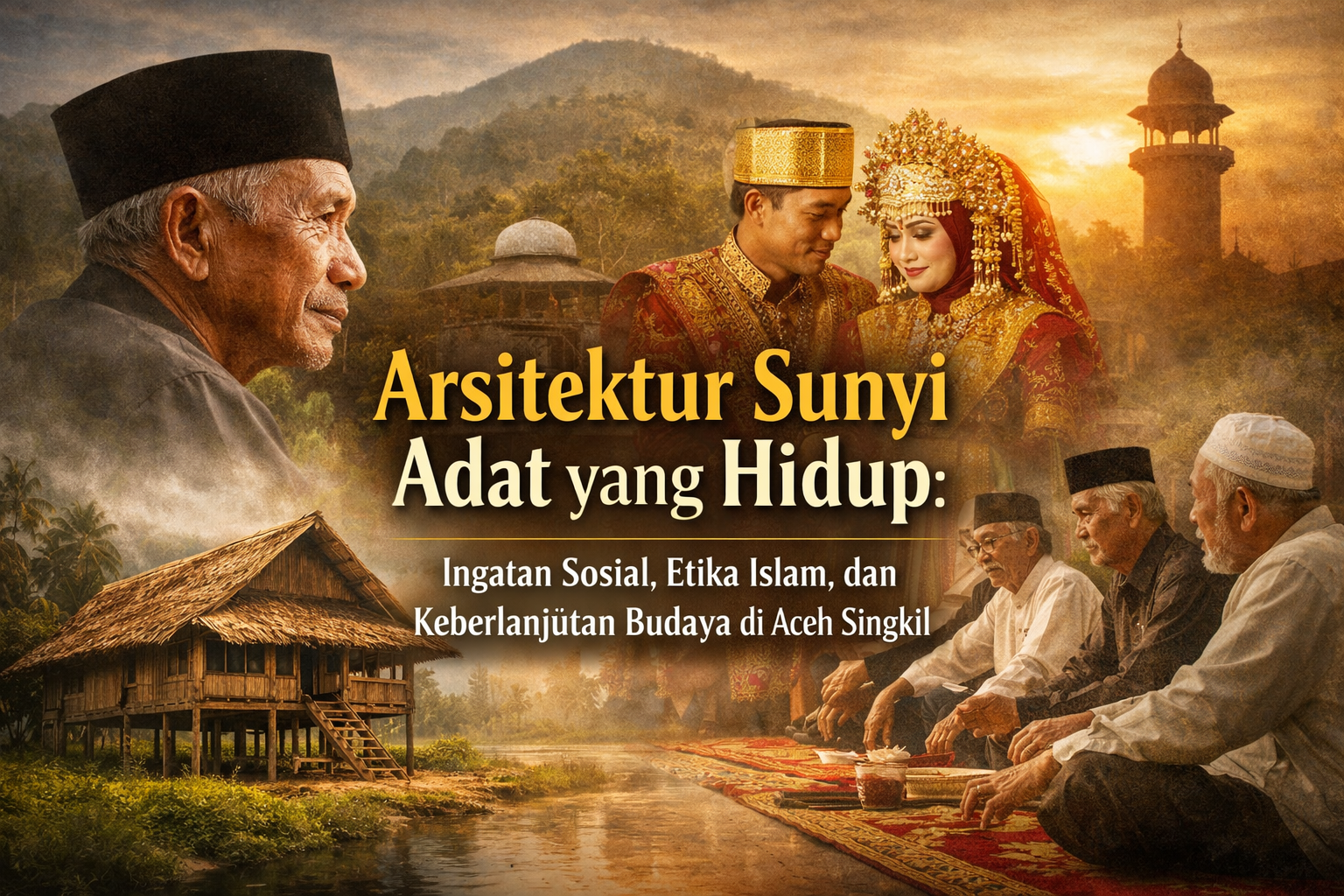
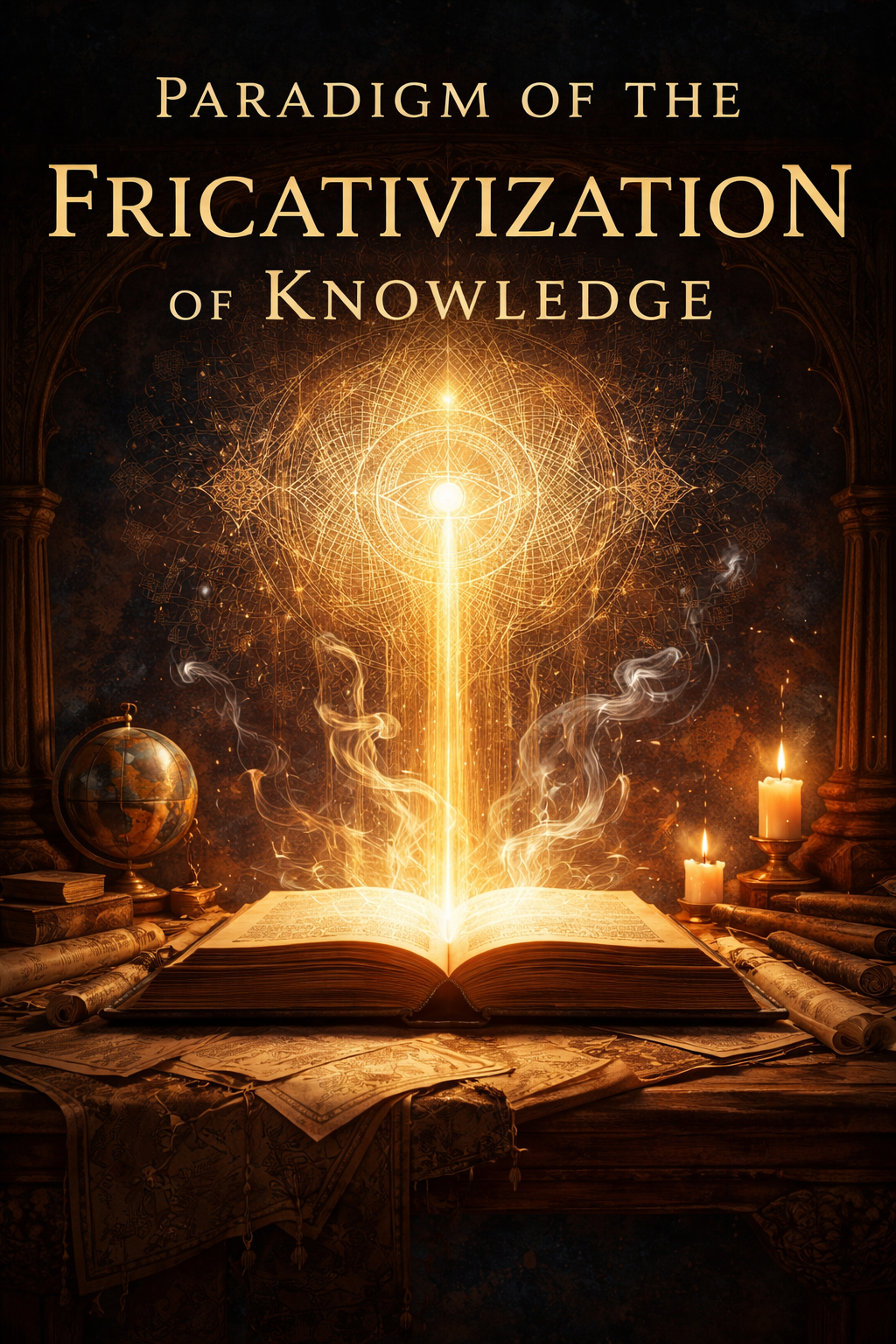
Leave a Reply