Your cart is currently empty!
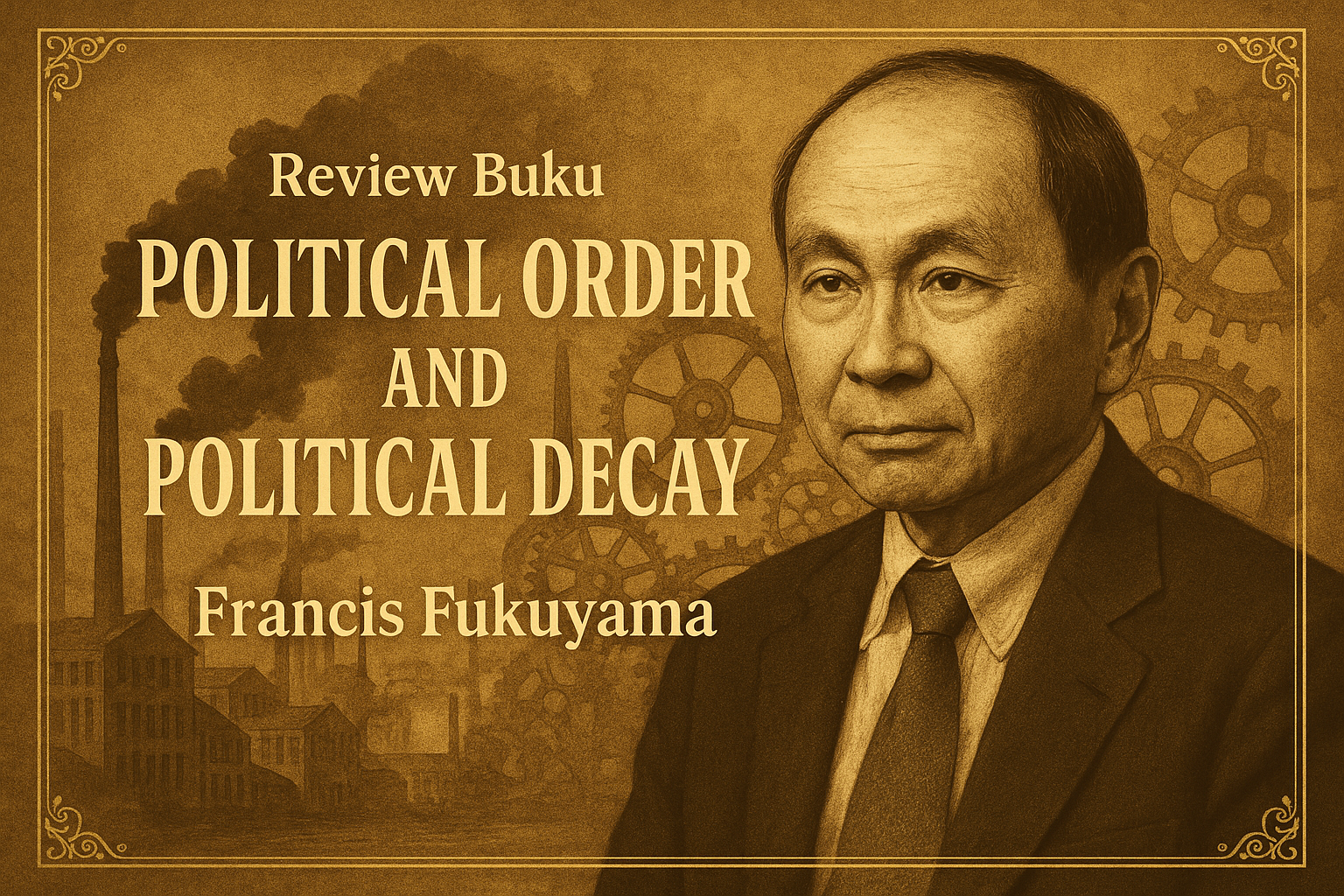
Review Buku Political Order and Political Decay: Analisis Francis Fukuyama tentang Tatanan Politik dan Kemerosotan Demokrasi
Pendahuluan: Menggugat Stabilitas Tatanan Politik
Francis Fukuyama kembali hadir dengan karya yang memprovokasi diskusi global tentang arah politik modern. Setelah sebelumnya mengguncang dunia intelektual dengan tesis The End of History, ia kemudian menulis The Origins of Political Order, yang menguraikan asal-usul institusi politik sejak zaman prasejarah hingga Revolusi Industri. Buku lanjutan ini, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, merupakan kelanjutan dari proyek besar tersebut.
Dalam buku ini, Fukuyama menyoroti paradoks besar dalam sejarah politik: mengapa institusi yang telah berhasil menciptakan stabilitas bisa mengalami kemerosotan? Ia menyebutnya sebagai political decay, yakni proses ketika institusi melemah, kehilangan legitimasi, dan akhirnya gagal melayani kepentingan masyarakat. Buku ini menjadi jawaban atas kebingungan banyak orang tentang mengapa demokrasi yang dianggap mapan bisa runtuh dari dalam.
Fukuyama berangkat dari asumsi bahwa demokrasi liberal lahir bersamaan dengan Revolusi Industri. Perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial yang masif pada abad ke-18 dan 19 melahirkan sistem politik baru berbasis partisipasi rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa kemenangan demokrasi liberal tidak berarti akhir dari sejarah politik. Justru, tantangan baru terus bermunculan, dari polarisasi politik hingga korupsi sistemik.
Dengan gaya historis yang khas, Fukuyama mengaitkan berbagai kasus lintas negara dan zaman. Ia membandingkan pengalaman Eropa Barat, Amerika Serikat, Eropa Timur pasca-Komunisme, hingga Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Analisis ini menunjukkan pola global: order bisa dibangun, tetapi decay selalu mengintai.
Pendekatan Fukuyama menarik karena memadukan sejarah, sosiologi, dan ilmu politik dalam satu kerangka analisis. Ia tidak hanya melihat faktor struktural, tetapi juga menyoroti peran ide, budaya, dan kepemimpinan dalam menentukan arah politik. Dengan begitu, buku ini menjadi panduan penting untuk memahami bagaimana negara-negara bisa maju atau justru runtuh.
Bagi pembaca di Indonesia, buku ini relevan sebagai bahan refleksi. Demokrasi pascareformasi sering dipuji sebagai capaian besar, tetapi tanda-tanda decay juga mulai tampak: korupsi, oligarki, serta menurunnya kepercayaan publik. Melalui kacamata Fukuyama, kita bisa bertanya: apakah demokrasi kita sedang berkembang atau justru membusuk dari dalam?
Konsep Political Order dan Political Decay
Fukuyama memulai bukunya dengan menegaskan bahwa political order adalah kondisi fundamental bagi keberlangsungan masyarakat. Ia didefinisikan sebagai sistem di mana kekuasaan diatur melalui hukum, dijalankan oleh institusi yang kuat, dan diterima oleh rakyat sebagai sah. Tanpa tatanan politik, masyarakat hanya akan terjebak dalam kekacauan, di mana hukum rimba berlaku.
Namun, tatanan tidak pernah abadi. Ketika institusi gagal beradaptasi dengan perubahan sosial, politik mulai membusuk. Fukuyama menyebutnya sebagai political decay. Contoh paling jelas adalah ketika demokrasi berhenti menjadi alat partisipasi rakyat, dan berubah menjadi arena bagi elit untuk melanggengkan kepentingan mereka sendiri. Dalam kondisi ini, legitimasi runtuh dan negara kehilangan kapasitasnya.
Fukuyama membagi elemen tatanan politik ke dalam tiga komponen utama: kapasitas negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas demokratis. Kapasitas negara memastikan bahwa kebijakan bisa dijalankan dengan efektif. Supremasi hukum menjamin semua pihak tunduk pada aturan, termasuk penguasa. Akuntabilitas memastikan bahwa rakyat tetap bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Jika salah satu elemen ini melemah, maka proses decay pun dimulai.
Konsep ini membuat pembaca memahami bahwa demokrasi bukanlah jaminan otomatis bagi stabilitas. Demokrasi memerlukan institusi yang hidup dan berfungsi, bukan sekadar prosedur pemilu. Banyak negara mengadakan pemilu, tetapi tidak otomatis berhasil membangun tatanan. Tanpa birokrasi yang kuat dan hukum yang tegak, demokrasi hanya menjadi ritual formal.
Lebih jauh, Fukuyama menekankan bahwa decay sering kali datang dari dalam, bukan dari luar. Negara bisa tampak stabil, tetapi di dalamnya terjadi pembusukan yang lambat. Korupsi, birokrasi yang mandek, dan politisasi hukum adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Dengan analisis ini, ia menegaskan bahwa demokrasi memerlukan pembaruan terus-menerus.
Konsep order dan decay yang dikemukakan Fukuyama kemudian ia gunakan untuk membaca berbagai pengalaman sejarah. Dengan membandingkan Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika, ia menunjukkan bahwa semua negara, tanpa kecuali, menghadapi dilema serupa: bagaimana membangun tatanan tanpa jatuh ke dalam pembusukan.
Revolusi Industri dan Lahirnya Demokrasi Liberal
Revolusi Industri menjadi titik balik penting dalam sejarah politik modern. Fukuyama menegaskan bahwa antara 1780 hingga 1840, transformasi besar dalam teknologi dan ekonomi menciptakan tuntutan baru bagi tatanan politik. Mesin uap, pabrik, serta urbanisasi massal melahirkan kelas sosial baru yang mendesakkan hak-hak politik. Dari sinilah demokrasi liberal mulai tumbuh.
Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga menyangkut cara masyarakat melihat diri mereka sendiri. Kelas pekerja menuntut keadilan, sementara kapitalis baru menginginkan aturan yang melindungi kepentingan mereka. Negara harus menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Jika gagal, ia akan kehilangan legitimasi. Maka, lahirlah sistem representatif yang membuka ruang partisipasi rakyat.
Namun, Revolusi Industri juga menciptakan kontradiksi. Ketimpangan sosial melebar, konflik kelas meningkat, dan kota-kota penuh sesak dengan kemiskinan. Demokrasi yang lahir di satu sisi memperkuat legitimasi, tetapi di sisi lain membuka jalan bagi instabilitas. Inilah awal dari dinamika order dan decay yang menjadi fokus Fukuyama.
Ia mencontohkan bagaimana Inggris berhasil mengelola transisi dengan memperluas hak politik secara bertahap. Sementara itu, Prancis berkali-kali mengalami revolusi karena elit gagal merespons tuntutan rakyat. Perbedaan jalur ini menunjukkan bahwa tatanan politik sangat ditentukan oleh bagaimana negara beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
Fukuyama menekankan bahwa Revolusi Industri juga melahirkan ideologi-ideologi baru, seperti sosialisme dan komunisme. Ide-ide ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan kapitalisme. Dengan demikian, politik modern tidak hanya dibentuk oleh mesin-mesin industri, tetapi juga oleh gagasan yang lahir dari penderitaan kelas pekerja.
Dari perspektif Fukuyama, Revolusi Industri adalah panggung di mana demokrasi liberal diuji pertama kali. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kekuatan institusi untuk mengatur perubahan sosial. Inilah pelajaran penting yang menurutnya masih relevan hingga kini.
Political Decay di Eropa Abad ke-19
Pada abad ke-19, Eropa mengalami gejolak politik yang luar biasa. Fukuyama melihat periode ini sebagai contoh nyata political decay. Feodalisme runtuh, negara-negara besar kehilangan legitimasi, dan kekacauan melanda berbagai kawasan. Legitimasi para raja hancur, sementara rakyat menuntut bentuk pemerintahan baru.
Salah satu faktor utama decay adalah kegagalan elit untuk merespons perubahan sosial. Ketika industrialisasi memperlebar jurang antara kaya dan miskin, penguasa justru sibuk mempertahankan privilese mereka. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan. Revolusi 1848 di Prancis menjadi simbol perlawanan terhadap elit yang korup dan tidak kompeten.
Selain itu, persaingan antarnegara besar juga memperburuk situasi. Jerman di bawah Otto von Bismarck memilih jalur otoritarian, sementara Prancis mencoba mempertahankan republik. Perbedaan jalur ini menciptakan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya meletus menjadi Perang Dunia I. Bagi Fukuyama, ini adalah bukti bahwa decay bisa membawa dunia ke jurang perang.
Fukuyama juga menyoroti peran media dalam proses ini. Pada abad ke-19, pers mulai berkembang pesat. Namun, alih-alih menjadi alat kontrol, media sering dimanfaatkan oleh elit kaya untuk melanggengkan kepentingan mereka. Manipulasi informasi menjadi salah satu faktor yang mempercepat krisis legitimasi.
Dengan perspektif ini, Fukuyama menunjukkan bahwa Eropa abad ke-19 adalah laboratorium penting bagi teori order dan decay. Ia memperlihatkan bahwa negara-negara yang gagal membangun institusi kuat akhirnya terjerumus dalam konflik. Sebaliknya, mereka yang mampu beradaptasi justru keluar sebagai pemenang.
Pelajaran dari Eropa abad ke-19 sangat relevan bagi dunia modern. Ketimpangan sosial, polarisasi politik, dan manipulasi media bukan hanya masalah masa lalu. Semua itu masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi hari ini. Fukuyama ingin menunjukkan bahwa sejarah selalu berulang, hanya dalam bentuk yang berbeda.
Amerika Abad ke-19: Pertumbuhan, Ketimpangan, dan Konflik
Amerika Serikat pada abad ke-19 sering dipandang sebagai simbol demokrasi yang sedang tumbuh. Namun, Fukuyama menunjukkan bahwa di balik retorika kebebasan dan demokrasi, Amerika mengalami dinamika yang kompleks. Revolusi Industri membawa pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi juga melahirkan ketimpangan yang tajam. Kelas pekerja, terutama imigran, menghadapi kondisi kerja yang buruk, sementara elit industri menguasai perekonomian dan politik.
Fukuyama menekankan bahwa pertumbuhan industri di Amerika tidak dapat dipisahkan dari ekspansi wilayah. Pembukaan tanah baru, pembangunan rel kereta api, serta eksploitasi sumber daya alam mendorong ekonomi berkembang pesat. Namun, ekspansi ini juga disertai dengan konflik, baik dengan penduduk asli maupun antarwilayah, yang pada akhirnya berujung pada Perang Saudara. Dalam pandangan Fukuyama, Perang Saudara adalah cermin dari kegagalan politik untuk menyelesaikan persoalan fundamental: perbudakan dan kesenjangan sosial.
Ketimpangan yang lahir dari industrialisasi juga mendorong lahirnya gerakan sosial. Serikat pekerja, kelompok abolisionis, dan gerakan perempuan mulai menuntut hak yang lebih besar. Di sini terlihat bahwa order tidak pernah statis. Ia selalu diuji oleh tuntutan baru. Jika tuntutan itu diabaikan, maka decay muncul dalam bentuk konflik. Amerika pada abad ke-19 berada di titik kritis ini.
Meskipun demikian, Fukuyama mengakui bahwa Amerika juga menunjukkan kapasitas institusional yang relatif kuat. Konstitusi menjadi pegangan yang kokoh, sementara mekanisme demokratis memungkinkan terjadinya koreksi politik. Setelah Perang Saudara, Amerika berhasil memulihkan tatanan melalui rekonstruksi dan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, meski sempat jatuh ke jurang konflik, Amerika mampu keluar dengan institusi yang lebih matang.
Namun, Amerika tetap menghadapi masalah serius berupa diskriminasi rasial. Meskipun perbudakan dihapus, segregasi rasial tetap berlangsung hingga abad ke-20. Fukuyama menilai bahwa ini adalah contoh decay yang berlangsung secara laten. Demokrasi Amerika memang terus berjalan, tetapi keadilan substantif bagi seluruh rakyat belum sepenuhnya terwujud.
Dengan membaca pengalaman Amerika, Fukuyama ingin menegaskan bahwa demokrasi tidak otomatis kebal dari decay. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan sosial. Bahkan negara yang dianggap sebagai model demokrasi pun menghadapi tantangan berat untuk menjaga legitimasi dan keadilan dalam sistem politiknya.
Eropa Barat Abad ke-20: Konsolidasi, Integrasi, dan Disintegrasi
Abad ke-20 menandai fase baru dalam sejarah politik Eropa Barat. Setelah mengalami decay pada abad ke-19 yang berpuncak pada Perang Dunia I, negara-negara Eropa mencoba membangun kembali tatanan politik yang lebih stabil. Fukuyama menekankan bahwa periode ini penting karena menunjukkan bagaimana institusi internasional lahir sebagai respons terhadap kekacauan sebelumnya.
Salah satu momen krusial adalah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919. Meski akhirnya gagal mencegah Perang Dunia II, organisasi ini menunjukkan kesadaran baru bahwa stabilitas politik tidak bisa hanya dikelola di level nasional. Butuh kerangka global untuk menjaga perdamaian. Dari sinilah, setelah Perang Dunia II, lahir PBB dan berbagai institusi internasional lainnya.
Fukuyama menyoroti bahwa Eropa Barat pascaperang berhasil membangun order baru melalui integrasi ekonomi. Uni Eropa lahir sebagai proyek politik yang berawal dari kerjasama ekonomi batu bara dan baja. Dengan mengikat kepentingan ekonomi, negara-negara yang dulu bermusuhan kini dipaksa untuk bekerja sama. Bagi Fukuyama, ini adalah contoh bagaimana institusi bisa mencegah decay dengan menciptakan kepentingan bersama.
Namun, integrasi juga membawa tantangan baru. Kedaulatan nasional dipertanyakan, dan populisme muncul sebagai reaksi terhadap birokrasi supranasional. Fukuyama melihat bahwa Uni Eropa adalah eksperimen yang menarik: ia berhasil menciptakan stabilitas, tetapi juga rapuh terhadap krisis ekonomi dan migrasi. Dengan kata lain, order selalu dalam posisi tawar-menawar dengan decay.
Eropa Barat juga menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa dipulihkan setelah otoritarianisme. Jerman, yang pernah menjadi sumber kekacauan dunia, berhasil menjadi demokrasi stabil setelah perang. Hal ini hanya mungkin terjadi karena adanya institusi internasional, reformasi internal, dan kesediaan masyarakat untuk menerima tatanan baru. Fukuyama menilai ini sebagai bukti penting bahwa decay bisa dibalik jika ada reformasi serius.
Namun, Eropa Barat juga tidak kebal dari tantangan baru. Krisis migrasi, meningkatnya ketimpangan, dan kebangkitan populisme menandai bahwa decay tetap mengintai. Fukuyama menekankan bahwa keberhasilan abad ke-20 bukan jaminan bagi abad ke-21. Demokrasi Eropa masih harus diuji oleh dinamika global yang terus berubah.
Eropa Timur Pasca-Komunisme: Transisi yang Sulit
Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur menghadapi tantangan besar untuk membangun tatanan politik baru. Fukuyama menyoroti bahwa transisi dari komunisme ke demokrasi pasar bebas tidak berjalan mulus. Banyak negara justru terjerumus ke dalam decay baru, berupa oligarki, korupsi, dan lemahnya institusi.
Polandia, Hungaria, dan Rusia menjadi contoh utama. Meskipun awalnya ada harapan besar, kenyataannya demokrasi di negara-negara ini tidak berhasil berakar kuat. Salah satu penyebabnya adalah karena komunisme telah merusak jaringan sosial dan budaya politik. Ketika sistem lama runtuh, tidak ada institusi alternatif yang siap menggantikan. Kekosongan ini segera diisi oleh elit baru yang memanfaatkan transisi untuk kepentingan pribadi.
Fukuyama menekankan bahwa demokrasi tidak bisa sekadar diimpor. Ia membutuhkan fondasi sosial berupa kepercayaan publik, budaya hukum, dan birokrasi yang berfungsi. Di Eropa Timur, semua fondasi itu rapuh. Akibatnya, yang muncul bukan demokrasi substantif, tetapi demokrasi semu di mana pemilu hanya menjadi formalitas.
Rusia menjadi contoh paling jelas. Setelah era Gorbachev dan Yeltsin yang kacau, Vladimir Putin muncul dengan janji stabilitas. Namun, stabilitas itu dibangun di atas kontrol ketat terhadap media, oposisi, dan lembaga negara. Fukuyama menilai bahwa ini adalah bentuk political decay: institusi negara dikendalikan oleh segelintir elit, sementara rakyat kehilangan ruang partisipasi nyata.
Di sisi lain, Polandia dan Hungaria juga mengalami kemunduran demokrasi. Nasionalisme dan populisme konservatif menguat, sementara kebebasan pers dan independensi peradilan melemah. Fukuyama menekankan bahwa decay tidak hanya terjadi di negara-negara yang gagal sepenuhnya, tetapi juga di negara-negara yang sempat dianggap berhasil.
Pengalaman Eropa Timur menunjukkan bahwa transisi politik adalah proses yang rumit. Demokrasi bukan sekadar mengganti rezim, tetapi membangun institusi yang tahan uji. Tanpa itu, order yang diharapkan hanya menjadi fatamorgana, dan decay akan segera mengambil alih.
Tiongkok Abad ke-21: Antara Konfusianisme dan Komunisme
Tiongkok menjadi salah satu studi kasus paling penting dalam buku Fukuyama. Negara ini memiliki sejarah panjang tatanan politik berbasis Konfusianisme yang bertahan selama lebih dari dua milenium. Dalam sistem ini, elit sarjana berperan sebagai pengatur moral dan administrasi negara, sementara rakyat menjalani peran mereka dalam struktur hierarkis yang ketat. Stabilitas ini bertahan lama, tetapi juga menciptakan rigiditas yang rentan terhadap perubahan.
Setelah 1949, Partai Komunis Tiongkok berusaha membongkar tatanan lama dengan menggantinya menjadi sistem sosialis yang sentralistis. Kelas sarjana dihapus, dan ideologi komunis dijadikan fondasi baru. Namun, sebagaimana ditunjukkan Fukuyama, yang lahir justru sebuah campuran unik antara tradisi lama dan sistem baru. Negara ini tidak sepenuhnya meninggalkan warisan Konfusianisme, melainkan menyerapnya ke dalam otoritarianisme modern.
Fukuyama menilai bahwa Tiongkok pada abad ke-21 adalah contoh nyata dari political order yang stabil tetapi rentan terhadap decay. Negara ini mampu menunjukkan efektivitas luar biasa dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi. Namun, keberhasilan ini dibangun di atas kontrol politik yang ketat oleh elit kecil. Dalam jangka panjang, konsentrasi kekuasaan seperti ini berisiko melemahkan legitimasi.
Salah satu indikator decay yang ia soroti adalah meningkatnya korupsi dalam birokrasi Tiongkok. Meski pemerintah melancarkan kampanye besar-besaran melawan korupsi, akar masalahnya tetap ada: kekuasaan yang tidak terdistribusi secara demokratis. Selama rakyat tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk mengawasi elit, maka sistem rentan runtuh dari dalam.
Tiongkok juga menghadapi dilema globalisasi. Di satu sisi, ia harus membuka diri untuk perdagangan dan teknologi. Namun di sisi lain, keterbukaan ini berpotensi menimbulkan tuntutan demokratisasi dari dalam negeri. Ketegangan antara kontrol politik dan kebutuhan keterbukaan menjadi sumber ketidakpastian dalam tatanan politik Tiongkok.
Dengan demikian, bagi Fukuyama, Tiongkok adalah laboratorium politik masa kini. Ia memperlihatkan bagaimana sebuah negara bisa menjadi kuat tanpa demokrasi, tetapi sekaligus mempertaruhkan masa depannya karena fondasi legitimasi yang rapuh. Pertanyaan besar yang ia tinggalkan adalah: apakah Tiongkok mampu bertahan dengan model ini, atau pada akhirnya akan jatuh ke dalam decay yang menghancurkan?
India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki: Demokrasi dalam Ujian
Selain Tiongkok, Fukuyama juga membahas beberapa negara besar yang mencoba membangun demokrasi di tengah kompleksitas sosial mereka. India, misalnya, sering dipuji sebagai demokrasi terbesar di dunia. Namun, ia juga sarat dengan tantangan berupa sistem kasta, kemiskinan, dan konflik etnis. Fukuyama menekankan bahwa demokrasi India bertahan bukan karena institusinya sempurna, tetapi karena adanya tradisi politik yang cukup kuat dan keberagaman yang dikelola dengan kompromi.
Brasil menjadi contoh lain. Negara ini pernah dipandang sebagai kekuatan baru Amerika Latin dengan potensi ekonomi besar. Namun, sebagaimana ditunjukkan Fukuyama, lemahnya institusi membuat demokrasi Brasil rapuh. Korupsi meluas, ketergantungan pada komoditas menggerus stabilitas ekonomi, dan elit politik gagal memenuhi janji kesejahteraan. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan, dan demokrasi terjerembap dalam krisis legitimasi.
Afrika Selatan menghadirkan cerita berbeda. Negara ini berhasil mengakhiri apartheid dan membangun demokrasi multirasial. Namun, euforia itu segera diikuti tantangan besar: kesenjangan ekonomi yang masih menganga, tingginya angka kriminalitas, serta kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Fukuyama menilai bahwa meski demokrasi formal terjaga, substansinya belum mampu mengatasi warisan ketidakadilan historis.
Turki, di sisi lain, memperlihatkan transisi unik. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan republik sekuler dengan orientasi Barat. Namun, perjalanan Turki tidak pernah lurus. Pergantian rezim, kudeta militer, dan kebangkitan Islam politik menunjukkan tarik-menarik antara demokrasi dan otoritarianisme. Fukuyama menilai Turki sebagai negara yang selalu berada di persimpangan, antara membuka diri ke arah demokrasi liberal atau kembali ke pola politik otoriter.
Dalam keempat kasus ini, Fukuyama menunjukkan satu benang merah: demokrasi bisa lahir dalam berbagai bentuk, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kekuatan institusi. India mampu bertahan karena ada fondasi sosial tertentu, Brasil rapuh karena korupsi yang sistemik, Afrika Selatan terjebak dalam kesenjangan, dan Turki gamang karena tarik-menarik identitas. Semua ini memperlihatkan wajah demokrasi yang beragam sekaligus rapuh.
Pelajaran penting yang ingin ditunjukkan adalah bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu. Ia membutuhkan birokrasi yang efektif, hukum yang independen, dan legitimasi publik. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi topeng bagi oligarki atau kedok bagi otoritarianisme.
Kesimpulan Global: Masa Depan Tatanan Politik Dunia
Fukuyama menutup bukunya dengan refleksi mendalam tentang masa depan tatanan politik global. Menurutnya, demokrasi liberal memang masih menjadi model paling adaptif, tetapi tidak kebal dari krisis. Tantangan utama abad ke-21 adalah bagaimana menjaga institusi tetap kuat di tengah gelombang globalisasi, migrasi, dan revolusi digital.
Ia menegaskan bahwa political decay bukan sekadar persoalan negara berkembang. Amerika Serikat sendiri menunjukkan gejala pembusukan politik: polarisasi ekstrem, dominasi kelompok kepentingan, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ini menjadi peringatan bahwa tidak ada negara yang aman dari ancaman decay.
Bagi Fukuyama, kunci utama adalah reformasi institusi. Negara harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan legitimasi. Supremasi hukum, birokrasi yang bersih, dan akuntabilitas demokratis harus terus diperkuat. Tanpa itu, tatanan yang sudah dibangun dengan susah payah bisa runtuh hanya dalam satu generasi.
Globalisasi juga membawa dimensi baru bagi tatanan politik. Arus informasi yang tak terbendung membuat masyarakat lebih kritis, tetapi juga membuka ruang bagi manipulasi. Media sosial, misalnya, bisa menjadi sarana partisipasi sekaligus sumber polarisasi. Fukuyama melihat bahwa tantangan ini menuntut kreativitas baru dalam menjaga demokrasi tetap sehat.
Buku Political Order and Political Decay pada akhirnya adalah sebuah peringatan keras: demokrasi dan tatanan politik tidak pernah selesai. Mereka selalu berada dalam proses, yang bisa maju atau mundur. Keberhasilan sebuah negara bukan diukur dari klaim sebagai demokrasi, melainkan dari sejauh mana institusinya mampu melayani rakyat dengan adil dan efektif.
Dengan analisis historis dan komparatif yang luas, Fukuyama memberikan kerangka berpikir yang tajam untuk memahami krisis politik masa kini. Buku ini bukan hanya karya akademis, tetapi juga panduan praktis bagi siapa saja yang peduli pada masa depan demokrasi. Bagi pembaca Indonesia, pesan Fukuyama sangat jelas: jika kita tidak menjaga institusi, maka decay akan datang, perlahan tetapi pasti.


Leave a Reply