Ketika berbicara tentang kota Solo, banyak dari kita membayangkan harmoni budaya, ketenangan tradisi, dan reputasi spiritualitas yang mendalam. Kota ini adalah rumah bagi tokoh-tokoh penting nasional dan memiliki peran historis dalam dinamika politik serta kultural Indonesia. Namun siapa sangka, dalam senyap dan kelam, Solo juga menjadi salah satu simpul penting dalam pembentukan jaringan terorisme kontemporer di Indonesia. Fajar Purwawidada, dalam bukunya Jaringan Baru Teroris Solo, menghadirkan fakta yang mengejutkan dan tak terbantahkan: bahwa radikalisme kekerasan tidak tumbuh di tempat asing yang jauh, tetapi berakar kuat di tengah-tengah kita, di ruang-ruang yang selama ini kita anggap tenang dan religius.
Buku ini bukanlah karya yang hanya mengejar sensasi terorisme. Karya ini ditulis dengan pendekatan yang terstruktur, analitis, dan mendalam. Fajar, sebagai perwira menengah TNI Angkatan Darat, menyajikan studinya dengan gabungan antara kecermatan intelijen dan refleksi kebangsaan. Dari halaman awal, kita langsung diajak memahami bahwa terorisme bukanlah semata tindakan kekerasan yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan penyebaran ideologi, formasi jaringan sosial, pelatihan, pendanaan, dan konsolidasi kekuatan. Solo, dalam narasi ini, bukan hanya kota— sebagai panggung strategis tempat radikalisme dirawat, dipupuk, dan disebarkan.
Dalam bagian awal buku, Fajar memaparkan bahwa jaringan terorisme yang berkembang di Solo tidak bisa dilepaskan dari sejarah lama, mulai dari jejak Darul Islam, jaringan pesantren seperti Al-Mukmin Ngruki, hingga hubungan global dengan jaringan radikal transnasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. Fajar menunjukkan bahwa jaringan-jaringan tersebut bukan hanya aktif dalam aksi kekerasan, tetapi membangun sistem ideologi yang berkelanjutan. Mereka menyasar generasi muda, membentuk komunitas berbasis keagamaan yang eksklusif, dan menciptakan “usroh” atau sel-sel kecil yang loyal secara ideologis dan operasional. Buku ini dengan detail menelusuri bagaimana proses hijrah ke Malaysia, pelatihan militer di Afghanistan, hingga kembalinya kader-kader ke Solo memperkuat jaringan dan membuka babak baru dari aksi-aksi teror.
Buku ini sangat penting adalah keberaniannya menyebut nama dan pola keterlibatan kelompok-kelompok seperti Hambali, Ali Ghufron (Muklas), Noordin M. Top, Abu Roban, hingga kelompok yang mengidentifikasi diri dengan ISIS Indonesia. Dalam bahasa yang lugas dan penuh data, Fajar tidak hanya menyebut tokoh, tetapi menautkannya dengan konteks sosial, peta aksi, hingga doktrin yang mereka bawa. Solo tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi markas ideologis dan pusat logistik dari jaringan-jaringan tersebut.
Tidak berhenti di situ, Fajar mengangkat secara kritis penyebab terjadinya terorisme di Indonesia. Penulis buku ini, tidak jatuh pada generalisasi atau stigmatisasi, melainkan mencoba memahami kerangka sosial-politik, keagamaan, dan kultural yang menjadi ladang subur bagi tumbuhnya radikalisme. Ketidakadilan sosial, politik identitas, krisis kepercayaan pada negara, hingga kegagalan pendidikan agama menjadi benang merah yang terurai dengan cermat. Kita diajak menyadari bahwa terorisme tidak bisa dilawan hanya dengan senjata yang harus dihadapi dengan pemahaman yang utuh atas konteks yang melahirkannya.
Salah satu bab paling menarik dalam buku ini adalah penjelasan mengenai fenomena “organisasi tanpa bentuk”. Dalam dunia digital dan algoritma, jaringan teroris tidak lagi mengandalkan struktur formal seperti organisasi konvensional. Mereka beroperasi dalam mode yang fleksibel, cair, dan tidak mudah dikenali. Bahkan, banyak dari mereka tidak lagi mengenal atasan-bawahan secara struktural, tetapi lebih pada afiliasi ideologi dan keterhubungan dalam dunia maya. Konsep ini penting karena memperlihatkan bahwa aparat keamanan tidak bisa hanya mengejar “tokoh utama”, tetapi harus memahami ekosistem digital, bahasa simbolik, serta strategi komunikasi jaringan tersebut.
Fajar juga tidak melupakan sisi manusia dari semua ini. Ia menjelaskan bagaimana jaringan ini memengaruhi keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. Banyak pelaku teror adalah anak-anak muda yang merasa tersingkir, tidak memiliki masa depan, dan menemukan pelarian dalam narasi keagamaan yang simplistik dan konfrontatif. Di sisi lain, keluarga korban, baik dari masyarakat sipil maupun aparat, menanggung trauma yang berkepanjangan. Terorisme di sini dilihat sebagai luka kolektif bangsa yang tidak hanya perlu ditanggulangi, tetapi juga disembuhkan.
Buku ini juga menggugah karena pada akhirnya menawarkan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan terorisme. Mulai dari penegakan hukum yang profesional, upaya pencegahan sejak dini, program deradikalisasi berbasis kultural, hingga disengagement—pemutusan keterikatan ideologis pelaku dari jaringan radikal. Fajar menegaskan bahwa solusi terhadap terorisme tidak bisa berjalan satu arah. Ia harus kolaboratif, melibatkan negara, masyarakat sipil, tokoh agama, pendidik, dan keluarga. Yang lebih penting, pendekatan ini tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus bersifat preventif dan berjangka panjang.
Sebagai penutup, Jaringan Baru Teroris Solo adalah bacaan wajib bagi siapa pun yang peduli pada masa depan Indonesia. Ia bukan hanya tentang Solo atau kelompok tertentu, tetapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa memahami wajah baru kekerasan berbasis agama yang tidak lagi datang dengan bendera, tetapi dengan algoritma dan narasi. Buku ini adalah peringatan, peta, dan sekaligus panggilan untuk bertindak—agar kita tidak lengah di tengah keseharian, dan agar Solo bisa kembali dikenal sebagai kota budaya, bukan sebagai titik awal dari kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan.
-
Judul: Jaringan Baru Teroris Solo
-
Penulis: Fajar Purwawidada
-
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
-
Jumlah Halaman: 355
-
Tahun Terbit: Edisi pertama
-
Kategori: Kajian Terorisme, Intelijen, Keamanan Nasional, Kriminologi
-
ISBN: 978-979-91-0787-8

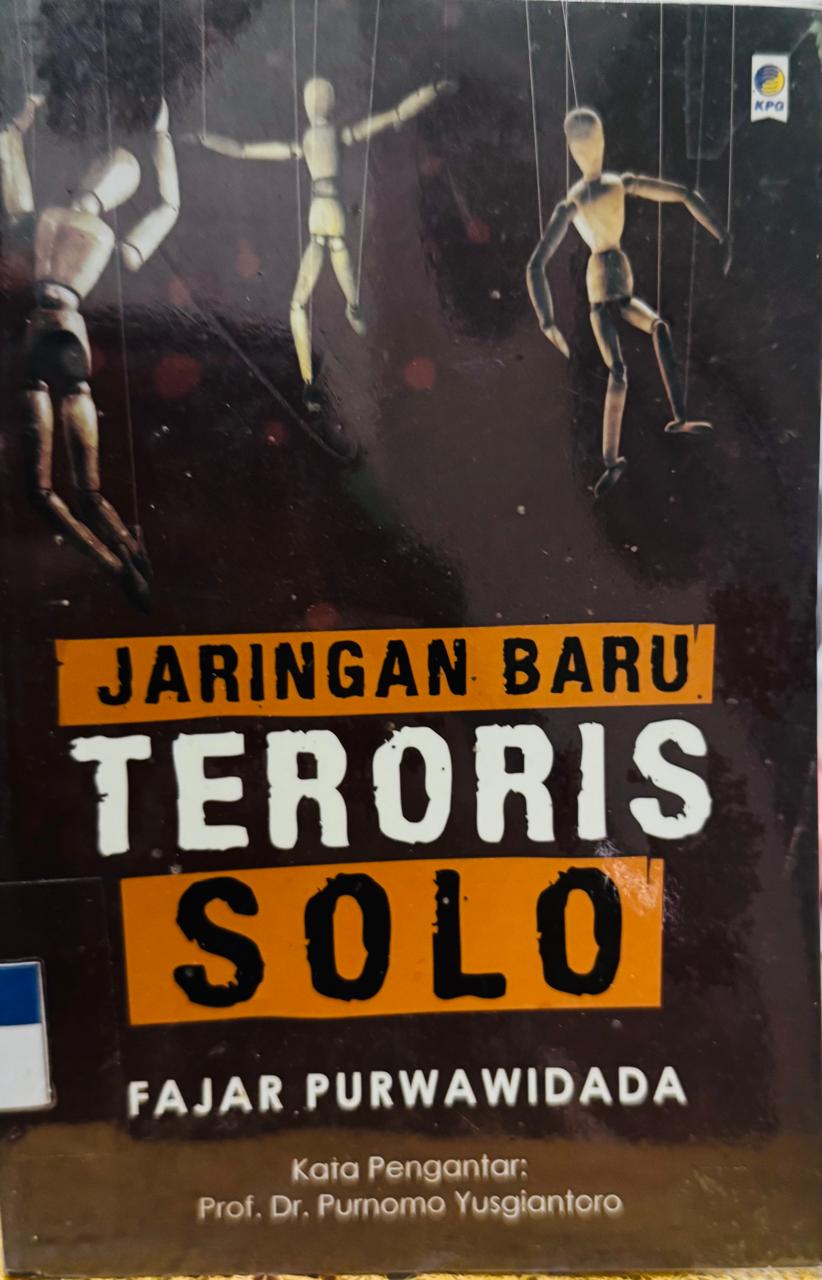
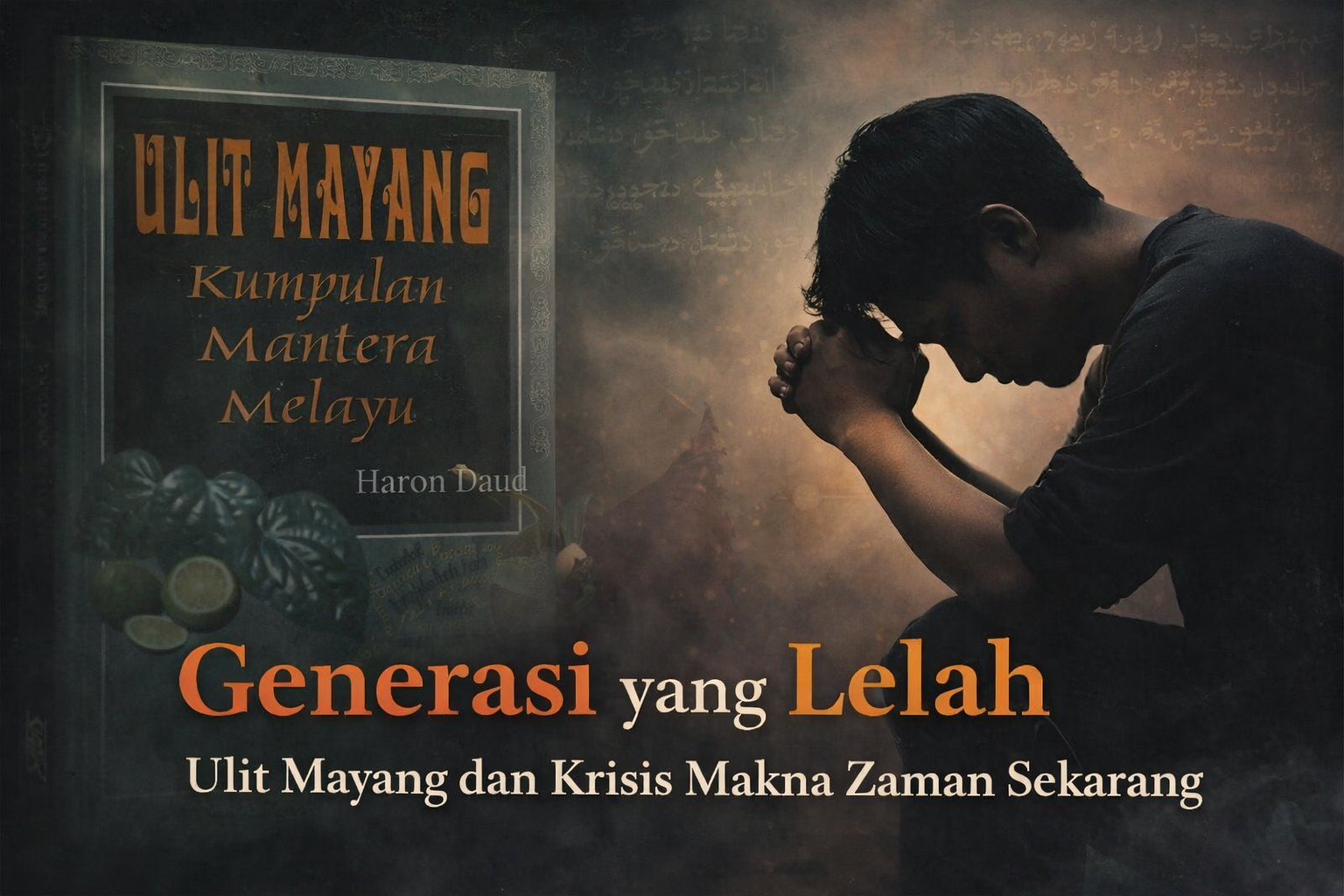




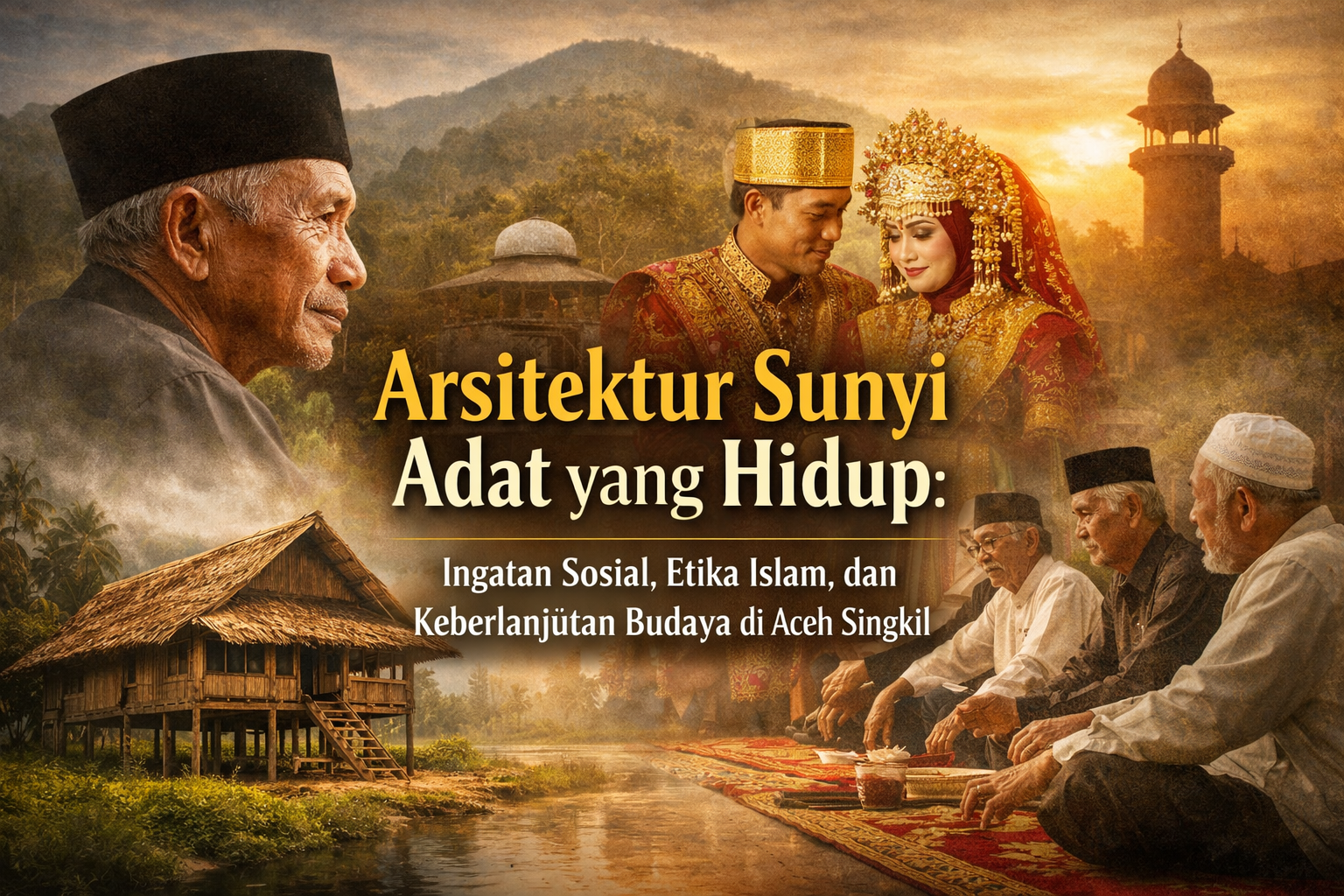
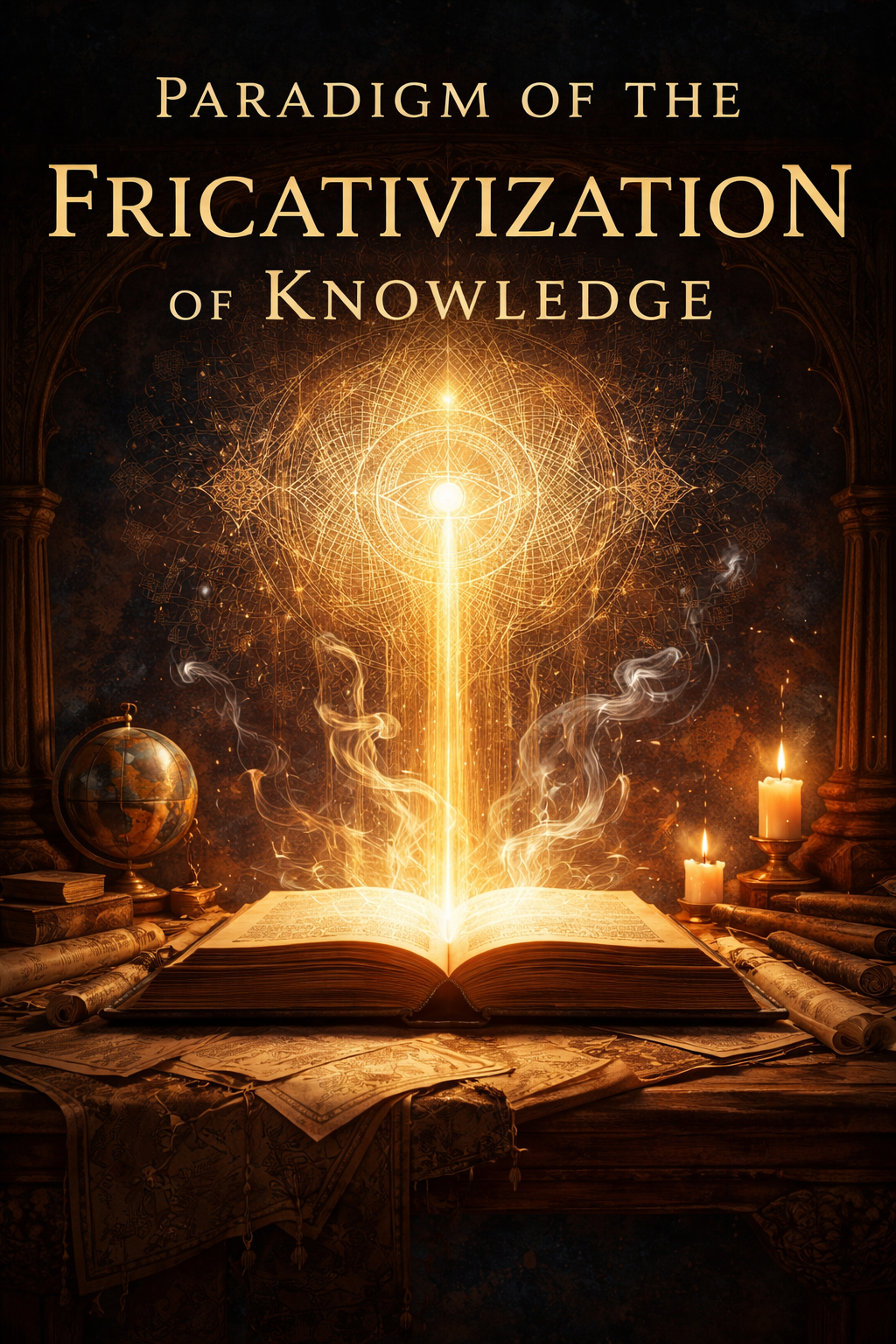
Leave a Reply