Pendahuluan
Isaiah Berlin, dalam karyanya The Sense of Reality, memberikan telaah historis dan filosofis yang mendalam tentang sosialisme sebagai sebuah doktrin politik dan moral. Ia tidak sekadar melihat sosialisme sebagai produk abad kesembilan belas, tetapi sebagai akumulasi dari tradisi panjang kritik terhadap ketidakadilan sosial. Berlin menulis bahwa “Socialism is a body of Western teaching and practice resting upon the belief that most social evils are due to unequal, or excessively unequal, distribution of material resources” (hlm. 77). Dari sini tampak jelas bahwa sosialisme merupakan jawaban atas pertanyaan kuno mengenai sumber kejahatan sosial: kesenjangan materi.
Sejak awal, sosialisme dibangun di atas keyakinan bahwa penyebab penderitaan sosial adalah distribusi yang tidak adil. Solusi yang ditawarkan adalah “the transference, gradual or immediate, total or partial, of the ownership of property and of the means of production, exchange and distribution from private to public control” (hlm. 77). Ini menunjukkan bahwa sosialisme tidak hanya menawarkan moralitas, tetapi juga struktur institusional baru.
Berlin menelusuri akar gagasan ini jauh ke belakang, ke dalam teks-teks keagamaan dan filsafat klasik. Ia menulis, “the concentration of power of a minority in a community leads to the exploitation of, and injustice to, the majority, is almost as ancient as social thought itself” (hlm. 77). Dengan demikian, sosialisme bukanlah “invensi modern,” melainkan kelanjutan dari kritik kuno terhadap keserakahan dan eksploitasi.
Dari Perjanjian Lama, dari tradisi monastik Kristen, hingga Plato dalam Republic, kritik terhadap kepemilikan pribadi telah lama dikemukakan. Plato, misalnya, menolak kepemilikan pribadi bagi para penjaga negara ideal, karena “the possession of, or desire for, private property tends to corrupt the individual” (hlm. 77). Kritik moral ini menjadi fondasi konseptual bagi sosialisme modern.
Sosialisme kemudian berkembang menjadi proyek politik ketika pertanyaan filosofis mengenai hak milik diperdebatkan. Apakah hak milik adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut, ataukah konstruksi sosial yang bisa dihapuskan? Berlin merumuskan pertanyaan mendasar: “Was the right to property an inalienable ‘natural right’ of the individual? Or might the State dispose of it as it wished?” (hlm. 79). Pertanyaan ini menjadi inti kontroversi ideologi.
Sejarah kemudian menunjukkan bahwa gagasan-gagasan radikal, seperti milik Babeuf atau Morelly, mencoba membawa komunisme ke ranah praktik politik. Walaupun gagal, mereka meletakkan fondasi bahwa sosialisme bukan hanya moralitas, tetapi juga gerakan revolusioner. Di sisi lain, tokoh seperti Saint-Simon dan Fourier memperluas cakrawala sosialisme ke arah teknokrasi dan utopia imajinatif.
Pendahuluan ini menunjukkan bahwa pembahasan Berlin bukan sekadar tentang ekonomi politik. Ia adalah upaya untuk memetakan sosialisme sebagai “continuum” intelektual: dari kritik moral kuno, melalui eksperimen revolusioner, hingga gagasan teknokratis dan utopis. Dengan cara ini, sosialisme hadir sebagai refleksi panjang pergulatan manusia tentang keadilan, kebebasan, dan organisasi masyarakat.
Akar Sosialisme dan Kritik atas Ketidakadilan
Isaiah Berlin membuka dengan definisi yang tajam: “Socialism is a body of Western teaching and practice resting upon the belief that most social evils are due to unequal, or excessively unequal, distribution of material resources” (hlm. 77). Bagi Berlin, sosialisme sejak awal meletakkan akar keyakinannya pada ketidakadilan distribusi materi sebagai sumber penderitaan sosial. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah “the transference, gradual or immediate, total or partial, of the ownership of property and of the means of production, exchange and distribution from private to public control” (hlm. 77).
Berlin menekankan bahwa keresahan terhadap konsentrasi kekayaan bukanlah fenomena baru. Ia menulis: “the concentration of power of a minority in a community leads to the exploitation of, and injustice to, the majority, is almost as ancient as social thought itself” (hlm. 77). Dengan kata lain, gagasan inti sosialisme berakar dalam sejarah panjang pemikiran moral dan agama.
Kitab-kitab suci pun tidak lepas dari kritik terhadap keserakahan dan ketidakadilan. Berlin menyinggung “The Old Testament and the sacred and secular writings of other ancient faiths and cultures contain denunciations of the wickedness and rapacity of the powerful rich as well as practical provisions against the growth of excessive inequalities of wealth” (hlm. 77). Pesan moral ini menghubungkan tradisi religius dengan fondasi sosialisme.
Selain agama, filsafat klasik juga berperan. Plato, misalnya, menolak kepemilikan pribadi dalam Republic. Berlin mencatat, “Plato advocates the abolition of private property among the guardians of his ideal State because the possession of, or desire for, private property tends to corrupt the individual, obscure his moral and intellectual vision and make him incapable of pursuing truth” (hlm. 77).
Dengan demikian, sosialisme modern bukanlah produk yang muncul tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari perenungan moral kuno. Kritik terhadap properti pribadi, kesenjangan, dan kerakusan membentuk garis lurus yang menghubungkan Plato, tradisi Yahudi-Kristen, hingga pemikir modern.
Berlin menekankan bahwa keresahan ini muncul berulang kali sepanjang sejarah: “The theme constantly recurs that the pursuit of riches defeats the proper ends of man and perverts his vision of his true condition and purpose” (hlm. 77). Sosialisme hanyalah bentuk artikulasi modern dari keresahan tua ini.
Maka, akar sosialisme terletak pada kesadaran universal bahwa kesenjangan material merusak tatanan sosial, menghancurkan keadilan, dan mengaburkan tujuan luhur manusia.
Hak Milik: Alamiah atau Konstruksi Sosial?
Salah satu pertanyaan besar yang dibahas Berlin adalah status hak milik. Ia menulis, “Was the right to property an inalienable ‘natural right’ of the individual? Or might the State dispose of it as it wished?” (hlm. 79). Pertanyaan ini menjadi garis pemisah antara liberalisme, sosialisme, dan komunisme.
Locke berpendapat bahwa hak milik adalah hasil dari kerja individu: manusia mencampurkan tenaganya dengan alam, maka muncullah hak yang sah. Namun, Berlin menunjukkan bahwa para radikal seperti the Diggers led by Winstanley menuntut penghapusan properti pribadi, “on the ground that the entire community of specific individuals were entitled to the possession of ‘the earth and all the fruits thereof’” (hlm. 79).
Perdebatan Locke dan Winstanley menunjukkan dilema besar: apakah hak milik bersifat ilahi dan tak bisa diganggu, ataukah sekadar kesepakatan sosial yang bisa diubah? Berlin menulis bahwa kritik radikal justru menegaskan: “the only path to happiness and justice lay through the abolition of private property, and communal ownership and control” (hlm. 79).
Pemikir abad ke-18 seperti abbé Mably mengartikulasikan gagasan ini secara eksplisit. Berlin menulis, “private property is denounced as the chief source of the evil that men do to their fellows” (hlm. 80). Dengan demikian, hak milik dipandang bukan hanya sebagai masalah hukum, melainkan sumber kejahatan sosial.
Lebih jauh, Berlin mengutip Morelly yang dalam Code de la nature menyatakan: “the sole source of injustice and misery is the unequal distribution of property” (hlm. 80). Dengan kata lain, semua ketidakadilan bermula dari kepemilikan privat.
Dari sini jelas bahwa sosialisme awal meletakkan dasar moralnya pada kritik atas hak milik. Hak milik bukan dianggap “natural right,” tetapi sumber kejahatan yang harus dihapuskan demi keadilan.
Maka, pertarungan filosofis antara hak milik sebagai hak alami atau konstruksi sosial menjadi fondasi seluruh kontroversi sosialisme.
Revolusi Prancis dan Babeuf
Berlin menegaskan bahwa Revolusi Prancis tidak identik dengan komunisme. Ia menulis: “The French Revolution did not encourage communism” (hlm. 80). Sebaliknya, revolusi justru meneguhkan hak milik sebagai hak sakral setiap warga negara.
Robespierre bahkan mengesahkan hukum yang menegaskan hak milik sebagai dasar kebebasan. Berlin menulis: “among the sacred rights of every man and citizen was that of property” (hlm. 80). Dengan demikian, revolusi tetap liberal, bukan komunis.
Namun, ada kelompok kecil radikal yang dipimpin Gracchus Babeuf, terinspirasi oleh Rousseau dan Morelly. Mereka percaya bahwa revolusi seharusnya melahirkan kesetaraan penuh. Berlin mencatat, Babeuf “had intended to liberate the individual and introduce equality between all sections of society” (hlm. 80).
Upaya Babeuf gagal total. “They were betrayed by one of their number and duly arrested and the ringleaders were executed” (hlm. 81). Konspirasi para egalitarian berakhir dengan tragedi.
Meski gagal, peristiwa ini penting. Berlin menulis, “It was the first attempt to translate communist doctrine … into actual practice” (hlm. 81). Untuk pertama kalinya, komunisme melangkah keluar dari teori menuju politik praktis.
Dari kegagalan Babeuf, publik mulai memandang komunisme bukan lagi gagasan utopis, melainkan ancaman nyata terhadap tatanan sosial. Berlin menekankan bahwa sejak saat itu, “communist doctrine began to be taken seriously as something more than an unworldly idea” (hlm. 81).
Dengan demikian, kegagalan Babeuf justru melahirkan warisan baru: komunisme dipandang serius, bukan sekadar mimpi moral atau fantasi filosofis.
Saint-Simon dan Rasionalisasi Sosialisme
Isaiah Berlin menempatkan Henri de Saint-Simon sebagai perintis sosialisme ilmiah. Ia menulis: “One of the first thinkers with an acute sense of historical evolution, he believed in an alternation of periods of progress and disintegration” (hlm. 82). Saint-Simon percaya sejarah memiliki logika kemajuan yang bisa diatur secara rasional.
Kunci ajarannya adalah “rational organisation of society, and by rational organisation the planning of a social order by those whose technical knowledge best equipped them” (hlm. 82). Artinya, industrialis, ilmuwan, dan teknisi harus menjadi pemimpin masyarakat.
Saint-Simon menolak kepemimpinan tradisional. Berlin menulis: “the natural leaders of contemporary society … were industrialists, bankers, scientists, technicians, artists, international traders” (hlm. 82). Bagi Saint-Simon, kelas baru inilah yang harus menggantikan raja dan bangsawan.
Ia juga menekankan bahwa penderitaan sosial lahir dari ketidakmampuan manusia mengorganisasi diri secara efisien. Berlin menulis: “Misery and injustice sprang from idleness and ignorance and their by-product, inefficiency” (hlm. 82).
Sosialisme Saint-Simon bukanlah komunisme keras. Berlin mencatat: “Saint-Simon, unlike Babeuf, did not advocate the abolition or even curtailment of private property, nor yet the equality of mankind” (hlm. 83). Ia menerima kepemilikan pribadi, tetapi menekankan pengelolaan rasional.
Inti ajarannya adalah penghapusan kelangkaan. “The abolition of economic scarcity would lead to a state of complete economic contentment” (hlm. 83). Dengan demikian, kebebasan politik dan kesetaraan hanya bermakna jika kelangkaan ekonomi dihapuskan.
Saint-Simon menegaskan harapannya pada kepemimpinan teknokrat: “he placed all his hopes upon the rational control of it by men of genius” (hlm. 83). Sosialisme, baginya, harus dipandu oleh kejeniusan rasional, bukan revolusi buta.
Saint-Simonisme: Utopia Ilmiah dan Bahaya Otoritarianisme
Para murid Saint-Simon, seperti Enfantin dan Bazard, mengembangkan gagasannya ke arah yang lebih radikal. Berlin menulis: “They repeated their master’s denunciation of inequality, unchanging, universal human ‘rights’, advocated the rewarding of individuals according to their industry and ability, demanded association and hierarchical organisation of society” (hlm. 84).
Saint-Simonisme menekankan meritokrasi dan hierarki. “State capitalism, rigidly controlled by scientifically trained experts” (hlm. 84) menjadi visi utamanya. Artinya, masyarakat diatur seperti mesin besar yang dikendalikan oleh ilmuwan.
Para pengikutnya juga menuntut penghapusan warisan. Berlin menulis: “They all urged abolition of inheritance, whereby in due course the existing irrational organisation of private property would come to an end” (hlm. 84). Dengan demikian, ketidakadilan dianggap lahir terutama dari warisan kekayaan.
Visi Saint-Simon adalah “a kind of world trust or cartel, regulated by an omniscient, wise, benevolent central planning board in control of all aspects of social and economic life” (hlm. 84). Ini adalah utopia teknokratis yang mengorbankan kebebasan individu.
Namun, ia juga menjanjikan pembebasan manusia dari belenggu takhayul dan kemiskinan. Berlin menulis: “reason is victorious over superstition and prejudice, and material resources are developed to their fullest extent” (hlm. 84). Saint-Simonisme adalah utopia ilmiah yang optimis.
Tetapi bahaya tersembunyi jelas: reduksi manusia menjadi sekadar objek administrasi. Engels mengingatkan bahwa Saint-Simonisme adalah “an administration of things, not of men” (hlm. 84).
Dengan demikian, Berlin menampilkan Saint-Simonisme sebagai utopia ilmiah yang penuh janji, tetapi sekaligus berbahaya karena cenderung otoritarian.
Fourier dan Imajinasi Sosialisme Radikal
Setelah Saint-Simon, Berlin membahas Charles Fourier. Ia menulis: “Scarcely less important was the influence of an even stranger and less realistic system builder than Saint-Simon, Charles Fourier” (hlm. 84). Fourier dikenal eksentrik, penuh imajinasi, dan sering dianggap tidak realistis.
Berbeda dengan Saint-Simon, Fourier berasal dari kelas menengah bawah. Berlin menulis: “Fourier was of lower-middle-class origin, lived in perpetual financial difficulties and had a far more intimate acquaintance with the miseries and iniquities of the social system of his time” (hlm. 84). Pengalaman pribadinya membentuk pandangan yang lebih emosional.
Fourier mengusulkan unit sosial bernama phalanstères sebagai bentuk komunitas ideal. Ia percaya harmoni emosional dan pemenuhan hasrat merupakan kunci kebahagiaan, bukan sekadar efisiensi teknokratis.
Sosialisme Fourier berbeda karena menekankan dimensi psikologis. Ia menolak reduksi manusia menjadi mesin. Alih-alih, ia membayangkan masyarakat yang memberi ruang bagi fantasi, hasrat, dan keragaman kepribadian.
Berlin menegaskan bahwa Fourier, meski eksentrik, menambah warna bagi sosialisme. Ia membawa imajinasi ke dalam doktrin yang sebelumnya didominasi rasionalitas kaku.
Dengan demikian, Fourier menghadirkan alternatif: sosialisme yang menekankan kebahagiaan batin dan imajinasi kreatif, bukan sekadar distribusi material atau perencanaan teknis.
Berlin menutup dengan menegaskan bahwa Fourier, dengan segala keanehannya, tetap bagian integral dari mosaik sosialisme. Tanpa Fourier, sosialisme akan kehilangan sisi utopis dan humanisnya.
Kesimpulan
Dari pembacaan atas Berlin, tampak jelas bahwa sosialisme merupakan doktrin yang tidak bisa direduksi hanya pada teori ekonomi atau ide politik praktis. Sosialisme adalah refleksi mendalam manusia atas penderitaan yang lahir dari ketidakadilan. Berlin menulis bahwa “the theme constantly recurs that the pursuit of riches defeats the proper ends of man and perverts his vision of his true condition and purpose” (hlm. 77). Artinya, kritik terhadap kekayaan berlebih adalah kritik terhadap penyimpangan visi manusia tentang tujuan hidup.
Perdebatan tentang hak milik menjadi pusat dari seluruh gagasan sosialisme. Locke membela hak milik sebagai produk kerja, sedangkan Winstanley dan Mably menolaknya sebagai sumber kejahatan. Morelly bahkan menyatakan: “the sole source of injustice and misery is the unequal distribution of property” (hlm. 80). Perbedaan ini menegaskan bahwa sosialisme lahir dari kritik paling tajam terhadap status hak milik.
Revolusi Prancis menunjukkan ambivalensi: di satu sisi menegakkan hak milik sebagai hak sakral, di sisi lain melahirkan Babeuf yang mencoba mewujudkan komunisme. Walaupun gagal, peristiwa itu membuktikan bahwa komunisme tidak lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah ancaman yang dihadapi negara. Berlin menulis bahwa konspirasi Babeuf adalah “the first attempt to translate communist doctrine … into actual practice” (hlm. 81).
Saint-Simon membawa sosialisme ke arah rasionalitas teknokratis. Ia percaya pada “rational organisation of society” (hlm. 82) dengan ilmuwan dan industrialis sebagai pemimpin. Namun, murid-muridnya mendorong visi ini menjadi utopia otoritarian: “State capitalism, rigidly controlled by scientifically trained experts” (hlm. 84). Bahaya tersembunyi sosialisme teknokratis adalah penghapusan kebebasan individu.
Fourier menghadirkan warna berbeda: imajinasi, hasrat, dan utopia emosional. Berlin menulis bahwa Fourier, meski dianggap eksentrik, adalah “an even stranger and less realistic system builder than Saint-Simon” (hlm. 84). Namun dari keanehannya, Fourier menegaskan bahwa sosialisme juga harus memberi ruang bagi kebahagiaan batin, bukan hanya distribusi materi.
Dari Plato hingga Fourier, sosialisme hadir sebagai mosaik gagasan. Ia tidak seragam, melainkan berlapis: religius, filosofis, revolusioner, teknokratis, dan imajinatif. Justru dari keragaman inilah sosialisme memperoleh daya hidupnya.
Kesimpulannya, Berlin melihat sosialisme sebagai tradisi yang selalu kembali ke satu persoalan utama: bagaimana mencegah minoritas kecil memonopoli kekayaan dan kekuasaan, sehingga mayoritas tidak terjerumus ke dalam eksploitasi. Sosialisme adalah jawaban historis, meskipun dalam berbagai bentuk: utopia Plato, komunisme Babeuf, teknokrasi Saint-Simon, hingga fantasi Fourier. Semua menegaskan bahwa sosialisme, betapapun berbeda bentuknya, tetap lahir dari kerinduan universal manusia akan keadilan.

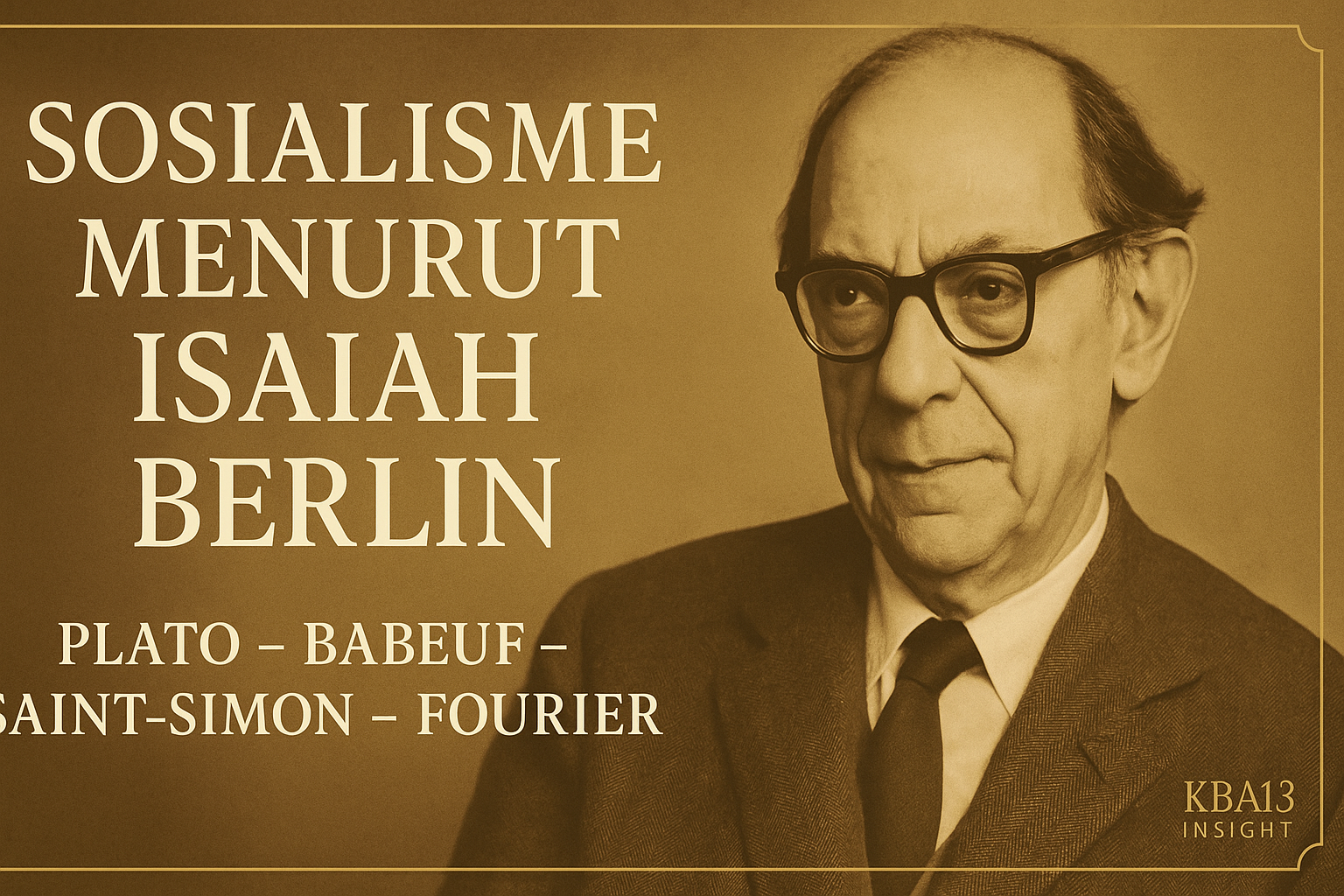

Leave a Reply