Strategi Tiongkok di Laut Cina Selatan (LCS) bersifat bertahap, konsisten, dan multidomain: militerisasi bertopang A2/AD, lawfare untuk mendefinisikan “normal baru”, diplomasi format ganda (bilateral menekan, multilateral mengulur), serta instrumen ekonomi dan kehadiran maritim semi‑negara (coast guard dan militia). Intinya adalah mengubah fakta di lapangan (facts on the sea) menjadi status quo yang sukar dibalik tanpa biaya eskalasi yang tinggi bagi pihak lain.
Pertama, pada lini militer, Beijing mengonversi fitur maritim hasil reklamasi—Fiery Cross, Subi, dan Mischief—menjadi kompleks udara‑laut dengan landasan, radar, rudal SAM/AShM, dan fasilitas ISR yang memperluas jangkauan deteksi serta penyangkalan wilayah (A2/AD). Pembaruan terakhir yang terpantau di Pulau Triton (Paracel)—instalasi radar jarak jauh, termasuk kemampuan kontra‑stealth—menandai penutupan surveillance gaps dan peningkatan maritime domain awareness Beijing atas alur utama LCS. Ini mempertegas transformasi infrastruktur menjadi jejaring sensor‑shooter yang menekan ruang operasi lawan, termasuk aset AEW&C dan kapal permukaan yang beroperasi di jalur sempit dekat chokepoints.
Kedua, lawfare: Beijing menggabungkan perangkat hukum domestik (UU Penjaga Pantai/CCG), peraturan penegakan “zona yurisdiksi”, dan narasi “hak historis” untuk menormalisasi patroli agresif CCG di sekitar Scarborough, Second Thomas/BRP Sierra Madre, hingga Natuna Utara. Pola ini didesain mendorong negara penggugat lain ke spiral kepatuhan administratif (misalnya permintaan prior notification), meskipun bertentangan dengan tafsir arus utama UNCLOS dan putusan arbitrase 2016. Ketika berhadapan dengan operasi FONOPs AS atau patroli mitra (Filipina, Australia, Jepang), CCG dan kapal maritime militia meningkatkan taktik shouldering, water‑cannoning, dan blocking—menciptakan risiko tabrakan yang dapat dieksploitasi sebagai krisis terbatas. Laporan CRS merekam kuantum insiden dan dorongan normatif AS terhadap kebebasan navigasi yang secara implisit menguji narasi hukum Beijing.
Ketiga, diplomasi format ganda. Di ASEAN, Beijing mendorong Code of Conduct (CoC) yang “aspirasional” namun minim mekanisme enforcement, sementara pada level bilateral memanfaatkan asimetri kekuatan untuk mengikat perilaku pihak lawan (misalnya pengaturan fishing moratorium atau tacit de‑confliction)—hasilnya adalah time‑buying, bukan penyelesaian. Analisis ISEAS menunjukkan kebuntuan CoC akibat divergensi strategis, ambiguitas hukum, dan perpecahan intra‑ASEAN—kondisi yang diuntungkan Beijing karena menunda penyetaraan rules of the road yang mengikat.
Keempat, instrumen ekonomi & kehadiran semi‑negara. Pipa state capitalism—investasi pelabuhan/energi—berjalan paralel dengan kehadiran kapal survei, fishing fleets, dan CCG, sehingga konflik yurisdiksi sumber daya (hidrokarbon, perikanan) selalu bisa diaktifkan sebagai pengungkit politik. Data activity mapping SCSPI juga menunjukkan Tiongkok membaca pola operasi lawan dan menyeimbangkannya dengan kehadiran kapal intelijen serta UAV/USV—meningkatkan frekuensi interaksi close‑in reconnaissance dan peluang friksi tak terduga.
Kesimpulannya: dengan ISR lapis‑berlapis (termasuk radar Triton), CCG/militia sebagai ujung tombak, dan narasi hukum domestik yang ditautkan ke “core interests”, Beijing telah memindahkan garis batas de facto. Membalik tren ini tanpa arsitektur deterrence by denial yang kredibel akan mengundang eskalasi berbiaya tinggi bagi pihak mana pun yang mencoba menantang.
Respons Amerika Serikat dalam Bingkai Indo‑Pacific Security
Kerangka berpikir Washington di LCS bertumpu pada Free and Open Indo‑Pacific (FOIP)—memastikan kebebasan navigasi/overflight, supremasi hukum internasional, serta pencegahan konsolidasi hegemoni tunggal. Dokumen U.S. Indo‑Pacific Strategy (Feb 2022) menegaskan networked security, forward presence, dan integrated deterrence bersama sekutu/mitra; LCS diposisikan sebagai medan uji kredibilitas komitmen tersebut.
Operasionalisasinya mengambil beberapa bentuk:
(1) FONOPs, kehadiran berkelanjutan, dan ISR gabungan. Armada Pasifik memelihara ritme operasi yang menguji klaim “straight baselines” dan “regulatory overreach” Beijing. Di saat yang sama, ISR gabungan (AS‑Jepang‑Australia‑Filipina) memperluas maritime domain awareness (MDA) negara‑negara pesisir, mengurangi fog of war pada insiden berisiko tabrakan yang meningkat akhir‑akhir ini—misalnya siklus benturan di sekitar Scarborough dan Second Thomas yang memicu pelayaran surface action group AS di area 30 NM dari shoal sebagai sinyal stabilisasi.
(2) Deterrence by denial melalui Pacific Deterrence Initiative (PDI). PDI mengarahkan investasi pada postur (Guam ‑ Kadena ‑ Yokosuka ‑ Darwin), arsitektur sensor/penembak berpencar, hardening, dan latihan gabungan guna menurunkan ekspektasi sukses lawan bila memaksakan perubahan status quo secara paksa. RAND menekankan bahwa pure denial harus dilengkapi instrumen cost‑imposition untuk skenario berlarut di bawah ambang nuklir; dokumen anggaran PDI 2026 mengafirmasi fokus pada kekuatan combat‑credible di front barat Pasifik untuk mencegah penetrasi A2/AD lawan.
(3) Alliance networking dan minilateralism. AS memanfaatkan tiga cincin: aliansi formal (Jepang, Australia, Filipina, Korea Selatan), minilateral (AUKUS, US‑Japan‑ROK, US‑Japan‑Philippines), dan kemitraan fungsional (India, Singapura, Indonesia, Vietnam). Jepang, melalui NSS 2022, secara eksplisit mengaitkan LCS dengan kebebasan navigasi dan sea lane security, mengisyaratkan kontribusi lebih besar SDF pada MDA dan latihan maritim—sebuah lengan kapasitas yang menambah bobot FOIP di selatan
(4) Lawfare tandingan dan diplomasi normatif. CRS menempatkan LCS sebagai medan kontestasi narasi hukum: AS mendorong UNCLOS‑consistent behaviors (meski Senat belum meratifikasi), mendukung award 2016, dan menegaskan bahwa klaim “hak historis” tidak memiliki dasar hukum internasional arus utama. Ini memperkuat coalition messaging ketika insiden dengan Filipina meningkat—mendorong naming‑and‑shaming pada taktik CCG (water cannon, lasing, ramming) sembari menahan eskalasi kinetik.
(5) Crisis gaming dan kontinuitas rencana kontingensi. Permainan perang tingkat kawasan—termasuk yang disorot media internasional—menunjukkan bahwa konflik di sekitar Taiwan akan beresonansi ke LCS (logistik, sea‑control, evakuasi WN, rute alternatif). Wawasan ini mempertebal argumen bahwa Indo‑Pacific deterrence tak bisa dipisah antara Selat Taiwan dan LCS—keduanya satu teater berkelanjutan dalam kalkulus Beijing dan Washington.
Apa artinya bagi jalur ke depan?
Arsitektur integrated deterrence AS dirancang untuk menurunkan confidence level Beijing bahwa coercion without war akan berhasil (melalui ISR + kehadiran + networking + lawfare), sembari menjaga agar kompetisi tidak melompat ke eskalasi terbuka. Namun model ini hanya efektif bila: (a) ritme FONOPs dan kehadiran dapat dipertahankan; (b) mitra regional melihat biaya reputasi bagi pelanggar norma; dan (c) MDA negara pesisir cukup kuat sehingga insiden tak dapat dinegasikan secara naratif. Itulah mengapa Washington menekankan capacity building dan common operating picture di pesisir ASEAN sebagai force multiplier deteren, bukan sekadar showing the flag.
Analisis Interaksi Cina–AS: Security Dilemma, Eskalasi, dan Skenario
Hubungan tindakan‑balasan di Laut Cina Selatan (LCS) kini terkunci dalam security dilemma: setiap langkah penguatan satu pihak terbaca sebagai ancaman oleh pihak lain sehingga memicu konsolidasi balasan. Bagi Beijing, reklamasi, sensor‑shooter network, dan CCG/militia adalah “defensif” untuk mengamankan core interests dan mengawasi lintasan operasi pihak ketiga. Namun begitu radar jarak jauh berkemampuan counter‑stealth di Triton Island beroperasi, persepsi Washington adalah penyempitan surveillance gaps yang menurunkan ruang manuver dan menaikkan operational risk bagi aset udara‑laut sekutu di seluruh busur Paracel–Spratly. Ini mendorong FONOPs dan kehadiran ISR teratur untuk menegaskan hak lintas yang diakui UNCLOS serta mencegah normalisasi “hak historis” versi Beijing. Siklus respons inilah yang mempercepat action–reaction di lapangan, menekan ruang de‑eskalasi diplomatik.
Di level operasional, komposisi kekuatan menunjukkan asimetrisasi instrumen. Beijing mengandalkan layered ISR, rudal darat‑laut, CCG, dan maritime militia untuk gray‑zone coercion di bawah ambang perang terbuka. Washington menahan eskalasi dengan kehadiran kredibel (FONOPs, combined patrols, ISR) yang disangga investasi Pacific Deterrence Initiative (PDI) pada postur, hardening, dan jaringan sekutu/mitra. Hasilnya adalah kontestasi berlarut: cukup intens untuk mengubah facts on the sea, namun terkelola agar tidak melompat ke konflik konvensional. Bagi keduanya, menjaga kompetisi “di bawah perang” sekaligus mempertahankan kredibilitas menjadi garis haluan yang krusial.
Tiga skenario menonjol ke depan. Pertama, status quo koersi berlarut: CCG/militia melanjutkan shouldering, lasing, water‑cannoning di titik panas (Scarborough, Second Thomas), sementara AS mempertahankan ritme FONOPs dan multi‑ship sails dengan sekutu untuk menutup celah reputasi dan hukum. Risiko utama: insiden tak terkendali akibat close‑in maneuvers yang memicu krisis 72 jam sebelum hotline efektif bekerja. Kedua, krisis terbatas: senggolan fatal terhadap kapal pemerintah Filipina—dengan Perjanjian Pertahanan Bersama 1951—menarik respons AS berupa presence surge, escort, dan operasi MDA gabungan; Beijing menjawab dengan gelar CCG/PLAN untuk cordon sanitaire di area sengketa. Ketiga, theater linkage: krisis Taiwan memantik contested logistics dan sea‑control melebar ke LCS (jalur selatan sebagai lifeline), menguji simultanitas FOIP di dua front. Matriks ini sudah lama menjadi perhatian perencana permainan perang Barat dan Asia.
Inti persoalan: norma versus keterputusan persepsi ancaman. Beijing membaca FONOPs sebagai provokasi politik; Washington membacanya sebagai pemulihan hak lintas universal. Tanpa rules of the road yang tuntas dan de‑confliction yang operasional, setiap manuver penegakan klaim berpotensi menjadi katalis flashpoint.
Dampak bagi Asia Tenggara: ASEAN, Maritim, dan Otonomi Strategis
Bagi Asia Tenggara, LCS adalah barometer otonomi strategis. Negara penggugat (Filipina, Vietnam, Malaysia) menghadapi tekanan simultan: keamanan maritim dan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Di Manila, intensitas insiden 2023–2025—dangerous maneuvers, water cannon, ramming—mendorong policy shift: perjanjian akses basis tambahan bagi AS, patroli gabungan, dan public diplomacy yang menayangkan bukti insiden ke media global untuk membangun koalisi opini. Di Hanoi dan Kuala Lumpur, kalkulus lebih tenang namun konsisten meningkatkan MDA, law enforcement at sea, dan kerja sama diam‑diam dengan mitra eksternal guna mempersempit ruang intimidasi di blocks migas dan perikanan.
Di tingkat regional, ASEAN terbelah antara dorongan CoC yang “aspirasional” dan kebutuhan enforceability. Analisis ISEAS menilai negosiasi CoC berlarut karena ambiguitas hukum (cakupan wilayah, status hak historis, rezim penegakan), divergennya kepentingan anggota, serta preferensi sebagian pihak terhadap bilateralism yang memberikan Beijing keunggulan asimetri. Implikasi langsung: tanpa compliance mechanism, CoC berisiko menjadi payung politis tanpa gigi, sementara gray‑zone coercion berlanjut. Satu‑satunya penyeimbang realistis dalam jangka pendek ialah MDA regional dan transparansi insiden—mencegah narrative capture serta memberi rendezvous fakta bagi third‑party diplomacy
Secara ekonomi, eskalasi berlarut menaikkan biaya asuransi, premi risiko pengiriman, dan volatilitas perikanan‑energi. Bahkan tanpa perang, sengketa yang memanjang mengganggu jadwal offtake LNG, investasi eksplorasi, dan memaksa re‑routing kapal pasokan—semuanya menekan negara pesisir yang bergantung pada sea lanes LCS. Karena itu, game plan yang paling kredibel bagi ASEAN adalah strategi dua jalur: memajukan CoC dengan minimum enforceable clauses (incident reporting, hotline, pemberitahuan aktivitas berisiko) sambil menguatkan kapasitas maritim nasional (radar pesisir, AIS, satelit SAR, fusion centers) lewat kemitraan terbuka dengan AS, Jepang, Australia, India, dan Uni Eropa.
Dalam lanskap ini, kebijakan Washington efektif bila membesarkan kapasitas setempat alih‑alih menggantikan peran negara pesisir. FOIP yang kredibel adalah FOIP yang membuat Manila, Hanoi, Kuala Lumpur, dan Jakarta mampu menegakkan hukum sendiri di perairannya, dengan dukungan situational awareness yang real‑time dan protokol de‑confliction yang dinormalisasi. Itu esensi deterrence by denial pada level kawasan.
Dampak bagi Asia Timur: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Rantai Pasok
Jepang melihat LCS sebagai sea‑lane security yang melekat pada keselamatan energi dan perdagangan. Dokumen keamanan terbaru Tokyo mensinyalir kontribusi yang lebih besar pada MDA, capacity building penjaga pantai kawasan, serta integrasi latihan laut‑udara dengan AS dan Australia. North–South theater linkage (Laut Cina Timur–LCS) membuat Tokyo memandang radar Triton dan jejaring ISR Spratly sebagai tantangan operasional bagi maritime presence Jepang di barat daya Okinawa dan through‑transit ke Asia Tenggara. Maka, US‑Japan alliance diproyeksikan semakin aktif di selatan untuk menutup celah domain awareness dan menyeimbangkan ritme CCG/PLAN.
Korea Selatan lebih berhitung, tetapi stabilitas LCS penting bagi alur pasok industri dan jalur energi. Seoul akan mendukung norma kebebasan navigasi dan memperkuat kerja sama teknologi (satkom, ISR, siber) dalam kerangka trilateral US‑Japan‑ROK, sembari menahan diri dari surface presence yang berpotensi memicu friksi langsung. Pengungkit Seoul berada pada teknologi dual‑use dan interoperability informasi.
Taiwan dan LCS tidak bisa dipisahkan. Simulasi krisis memperlihatkan bahwa blokade atau quarantine terhadap Taiwan akan menjadikan jalur selatan melalui LCS sebagai jalur penopang logistik sekutu/mitra. Dalam skenario demikian, sea‑control di segmen LCS barat‑daya menjadi center of gravity; konsekuensinya, jaringan radar seperti Triton plus runway‑capable reefs memberi Beijing opsi situational dominance di fase awal. Ini menjelaskan mengapa rencana kontinjensi AS menekankan pencitraan bersama (COP) lintas sekutu dan distributed logistics dari Jepang hingga Filipina—agar throughput tetap hidup bahkan ketika jalur utama di utara tertekan.
Bagi rantai pasok global, ketidakpastian LCS menambah risiko single‑node dependency. Pengalihan rute, penjadwalan ulang pelayaran, dan mitigasi asuransi akan memicu biaya yang pada akhirnya menekan inflasi impor di Asia Timur. Dengan kata lain, bahkan tanpa peluru ditembakkan, coercion by delay dan maritime harassment sudah cukup menciptakan supply‑chain tax—suatu bentuk gray‑zone economic warfare berbiaya murah namun berdampak luas. Inilah alasan coalition signaling dan presence harus dipadukan dengan resiliensi logistik: prasarana pelabuhan alternatif, pre‑positioned stock, dan perkuatan pelayaran feeder dari/ke jalur selatan.
Analisis di atas bertumpu pada SCSPI (perspektif dan data aktivitas militer), CRS (kerangka hukum‑strategis dan kronik FONOPs), dokumen FOIP/PDI (kerangka kebijakan serta postur), ISEAS (status CoC dan preferensi ASEAN), serta liputan analitis Chatham House/Business Insider/Breaking Defense tentang radar Triton sebagai capability marker terbaru. Ini memberikan kombinasi data pro‑Beijing, pro‑norma, dan third‑party assessments untuk menjaga keseimbangan sudut pandang.
Skenario ke Depan: Opsi Kebijakan, Indikator Peringatan Dini, dan Off-Ramps
1. Eskalasi Terbatas dan Coercion Without War
Skenario paling mungkin dalam 3–5 tahun ke depan adalah koersi berlarut yang mempertahankan intensitas di bawah ambang perang terbuka. Beijing akan memaksimalkan CCG, maritime militia, UAV/USV, dan gray-zone tactics untuk menekan negara penggugat tanpa memicu Pasal 5 atau perjanjian pertahanan. Indikator peringatan dini mencakup:
-
Lonjakan patroli CCG di luar pola normal (pattern-of-life).
-
Penggelaran sistem ISR baru di fitur Paracel/Spratly.
-
Peningkatan insiden lasing, water cannon, atau pemblokiran jarak dekat terhadap kapal pemerintah ASEAN.
Jika pola ini berakumulasi tanpa respons terukur, Beijing akan menciptakan “normal baru” yang menguntungkan klaimnya.
2. Krisis Memicu Respons Aliansi
Insiden fatal yang melibatkan kapal atau personel negara sekutu AS (terutama Filipina) dapat memicu respons cepat dalam bentuk presence surge, operasi pengawalan, atau penegakan zona aman (safe transit corridors). Tripwire utamanya:
-
Kerusakan serius atau korban jiwa akibat aksi CCG/militia.
-
Penolakan evakuasi medis oleh kapal pengganggu.
Dalam skenario ini, AS akan mengaktifkan contingency planning PDI, sementara Beijing menguji ambang batas eskalasi melalui operasi “pembatasan wilayah” (cordon sanitaire).
3. Linkage dengan Krisis Taiwan
Krisis di Selat Taiwan dapat memicu contest for sea-control di LCS, terutama jalur selatan sebagai lifeline logistik sekutu. AS akan berusaha mengamankan rute Laut Sulu–Selat Makassar sebagai pengganti jalur utara. Beijing kemungkinan memperluas A2/AD envelope dari Spratly untuk menutup celah tersebut. Indikatornya:
-
Penggelaran rudal jarak jauh ke fitur Spratly.
-
Aktivasi patroli udara maritim PLAN dari Hainan hingga Spratly.
4. Stabilisasi Bersyarat
Jalur off-ramp paling realistis adalah kesepakatan rules of the road teknis (pemberitahuan manuver, hotline, larangan penggunaan laser) di luar kerangka CoC yang formal. Mekanisme ini dapat dinegosiasikan melalui ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) atau jalur Track-1.5 yang di-backchannel oleh negara netral. Namun, efektivitasnya hanya akan terjaga jika kedua pihak melihat manfaat langsung dalam mencegah insiden besar.
Kesimpulan Strategis & Rekomendasi Kebijakan
Persaingan Cina–AS di Laut Cina Selatan adalah pertarungan kontrol maritim yang sudah melampaui sengketa kedaulatan semata. Bagi Beijing, ini adalah ujian mempertahankan core interests dan membangun strategic depth di perairan vital. Bagi Washington, ini adalah uji kredibilitas Free and Open Indo-Pacific dan arsitektur aliansi yang menopangnya.
Strategi Tiongkok menunjukkan konsistensi: membangun kapasitas A2/AD, memanfaatkan instrumen semi-negara untuk gray-zone coercion, serta menanamkan narasi hukum domestik yang diulang di forum internasional. Respons AS—melalui FOIP, PDI, dan alliance networking—mencerminkan pendekatan integrated deterrence: menggabungkan postur militer, hukum internasional, dan diplomasi normatif untuk menjaga status quo.
Dampak regional menegaskan bahwa:
-
Asia Tenggara memerlukan kombinasi Code of Conduct yang memiliki minimum enforceable clauses dan peningkatan maritime domain awareness nasional.
-
Asia Timur harus mengintegrasikan keamanan LCS dalam kalkulasi sea-lane security, terutama dalam skenario krisis Taiwan.
-
Rantai pasok global bergantung pada stabilitas perairan ini; bahkan gangguan non-kinetik sudah cukup menciptakan “pajak logistik” bagi ekonomi regional.
Rekomendasi kebijakan:
-
Bagi ASEAN: memprioritaskan incident transparency mechanism dan hotline yang operasional.
-
Bagi AS dan sekutu: fokus pada capacity building maritim negara pesisir, bukan hanya kehadiran simbolis.
-
Bagi Beijing: jika ingin menghindari coalition balancing, harus bersedia menguji mekanisme de-eskalasi teknis di luar kerangka formal CoC.
-
Bagi mitra eksternal: mendukung resiliensi logistik dan alternative routing untuk memitigasi risiko sea-lane closure.
Ke depan, Laut Cina Selatan akan tetap menjadi medan uji utama apakah Indo-Pacific mampu mempertahankan keterbukaan, atau justru bergerak menuju tatanan maritim yang terfragmentasi di bawah pengaruh kekuatan besar.
Daftar Pustaka (APA)
Belfer Center for Science and International Affairs. (2023). U.S.-China competition in the South China Sea: Strategic implications. Harvard Kennedy School. https://www.belfercenter.org
Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2024). Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org
Chatham House. (2024). China’s radar expansion in the South China Sea: Implications for regional security. https://www.chathamhouse.org
Congressional Research Service. (2023). U.S. role in the South China Sea. CRS Report R42784. https://crsreports.congress.gov
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) – Yusof Ishak Institute. (2025). The State of Southeast Asia 2025. Singapore: ISEAS.
International Institute for Strategic Studies (IISS). (2025). Asia-Pacific Regional Security Assessment. London: IISS.
RAND Corporation. (2023). The Pacific Deterrence Initiative and U.S. defense strategy in Asia. RAND Report RR-A100-2. https://www.rand.org
South China Sea Probing Initiative (SCSPI). (2023). Activity tracking and maritime incidents in the South China Sea. Peking University. http://www.scspi.org
U.S. Department of Defense. (2022). Indo-Pacific Strategy of the United States. Washington, DC: DoD.




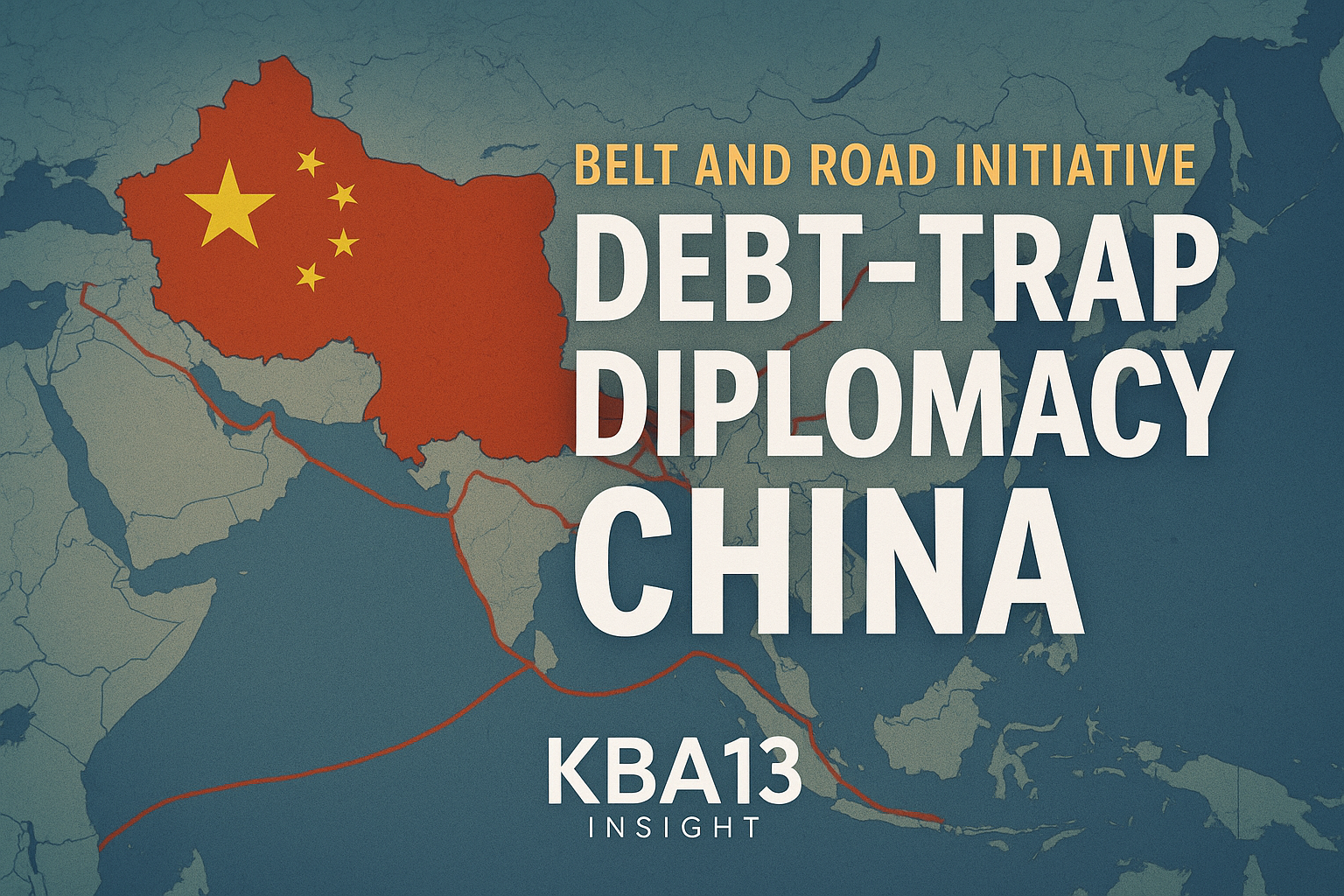
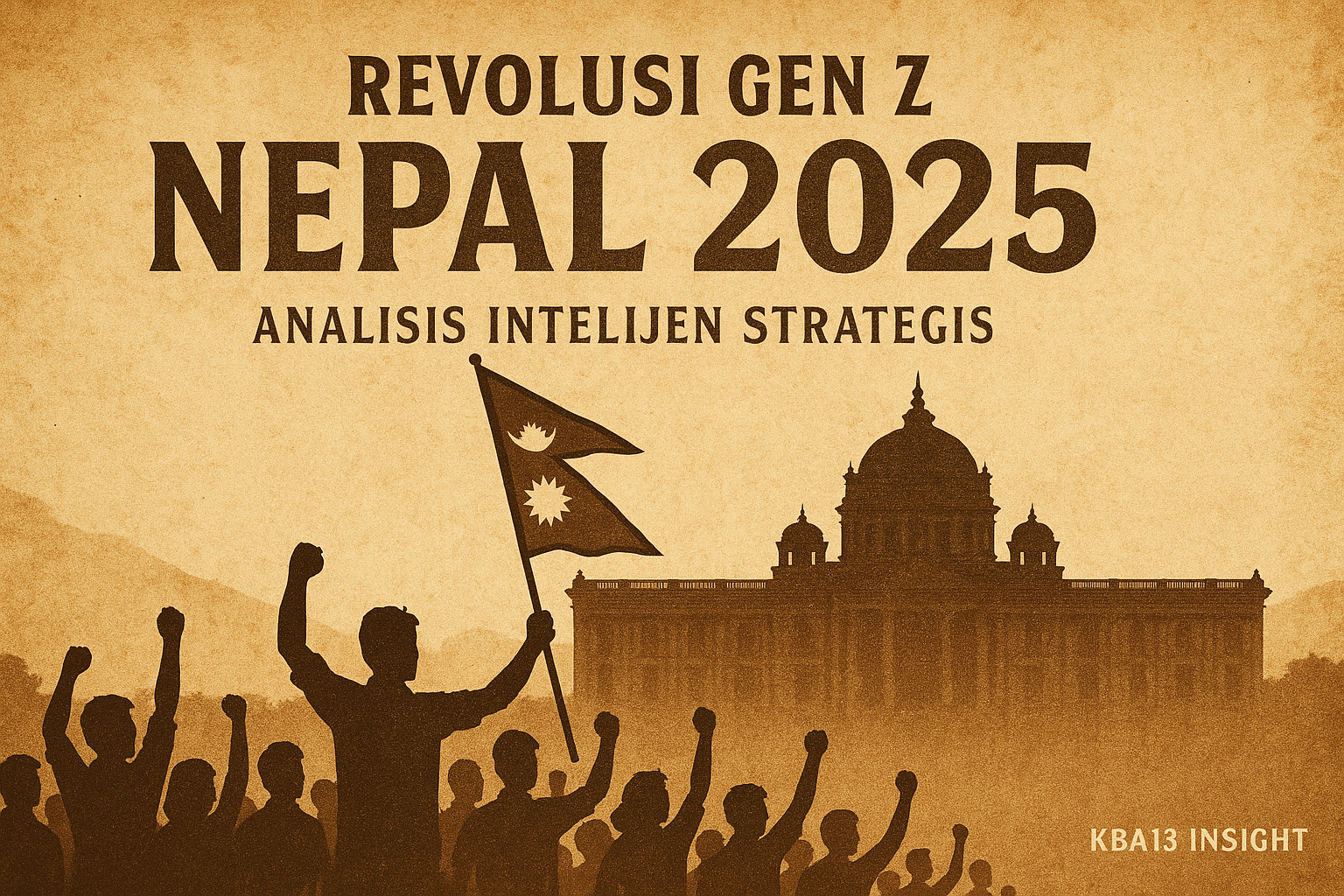





Leave a Reply