Pendahuluan
Bab ini diawali dengan penjelasan bahwa para pemikir Pencerahan pada abad ke-18 dan 19 tidak mengembangkan psikologi individu. Fokus mereka adalah hukum universal yang bersifat mekanistik, mengikuti model Newton. Pikiran manusia dipandang sebagai gabungan ide-ide sederhana yang terbentuk dari sensasi elementer. Dengan cara ini, pengalaman manusia direduksi ke dalam hukum-hukum objektif, bukan ke dalam dinamika batin individu.
Zaretsky menulis:
“Rejecting the idea that the mind was made up of associated ideas built out of elementary sensations, modernist thinkers in philosophy and the social sciences… sought to evoke deep structures of interiority that could be accessed only from within.”
Terjemahan: “Menolak gagasan bahwa pikiran terdiri dari ide-ide yang diasosiasikan dari sensasi elementer, para pemikir modernis dalam filsafat dan ilmu sosial… berusaha membangkitkan struktur dalam dari interioritas yang hanya dapat diakses dari dalam.”
Pergeseran inilah yang melatarbelakangi munculnya psikoanalisis. Freud menolak pandangan atomistik tentang pikiran dan memperkenalkan konsep ketidaksadaran (unconscious). Menurutnya, perilaku, mimpi, dan gejala neurotik tidak bisa dijelaskan oleh hukum rasionalitas, melainkan oleh konflik batin, represi, dan dorongan naluriah yang tidak disadari. Psikoanalisis lahir sebagai alternatif atas rasionalisme Pencerahan.
Pendahuluan ini juga menekankan bahwa psikoanalisis bukan semata teori medis atau psikologis, tetapi sebuah praktik kultural. Psikoanalisis memberikan kerangka untuk memahami bagaimana modernitas memengaruhi kehidupan subjektif manusia. Dengan demikian, ego yang kelak menjadi pusat perdebatan tidak lahir di ruang hampa, melainkan dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang lebih luas.
Zaretsky menulis:
“In this sense psychoanalysis was not only a theory of the mind but a cultural practice, a way of grasping the transformations of modernity through the lens of subjectivity.”
Terjemahan: “Dalam pengertian ini, psikoanalisis bukan hanya teori tentang pikiran, tetapi juga sebuah praktik kultural, suatu cara memahami transformasi modernitas melalui lensa subjektivitas.”
Pendahuluan ini kemudian mengaitkan perkembangan ego dengan munculnya persoalan demokrasi, feminisme, dan krisis otoritas. Freud, Adler, dan Jung menafsirkan ego dari sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya menanggapi perubahan besar yang melanda masyarakat modern. Ego menjadi jembatan antara pengalaman batin individu dan krisis kultural.
Dengan cara itu, bab ini membuka pembahasan bahwa kelahiran ego adalah fenomena multidimensi. Ia bukan sekadar istilah psikologi, tetapi juga metafora untuk memahami transisi besar peradaban. Psikoanalisis muncul sebagai sarana untuk menjelaskan bagaimana individu menavigasi dunia modern yang penuh dengan konflik otoritas, perubahan sosial, dan trauma kolektif.
Psikoanalisis sebagai Kritik atas Rasionalitas Pencerahan
Bagian ini menekankan bahwa psikoanalisis lahir sebagai kritik langsung terhadap rasionalitas Pencerahan yang menekankan universalitas hukum dan model atomistik tentang pikiran. Para pemikir Pencerahan memahami pikiran melalui teori asosiasi, di mana ide-ide terbentuk dari sensasi elementer yang sederhana. Freud menolak pendekatan ini karena dianggap tidak mampu menjelaskan kedalaman batin manusia.
Psikoanalisis muncul sebagai pendekatan yang berfokus pada interioritas. Freud menunjukkan bahwa pikiran bukanlah hasil susunan rasional dari ide-ide, melainkan medan konflik yang digerakkan oleh dorongan naluriah, represi, dan ketidaksadaran. Dengan demikian, psikoanalisis menjadi antitesis dari reduksi mekanistik terhadap pikiran.
Zaretsky menulis:
“Psychoanalysis thus represented not just a theory of unconscious processes but also a rejection of Enlightenment rationalism and its atomistic model of the mind.”
Terjemahan: “Dengan demikian, psikoanalisis bukan hanya teori tentang proses ketidaksadaran tetapi juga sebuah penolakan terhadap rasionalisme Pencerahan dan model atomistik tentang pikiran.”
Freud menekankan bahwa pengalaman manusia harus dipahami dari dalam, bukan dari luar. Gejala seperti mimpi, fantasi seksual, atau gangguan neurotik tidak dapat dijelaskan dengan hukum rasionalitas. Hal-hal tersebut hanya bisa dipahami melalui analisis psikis yang masuk ke dalam struktur ketidaksadaran. Dengan cara itu, psikoanalisis memindahkan titik berat dari hukum eksternal menuju dunia subjektif individu.
Zaretsky mengaitkan pergeseran ini dengan arus modernisme yang lebih luas. Dalam seni, filsafat, dan ilmu sosial pada awal abad ke-20, muncul upaya yang sama untuk menyingkap struktur dalam yang tak kasat mata. Freud berdiri sejajar dengan pemikir modernis lainnya, yang menolak reduksi rasionalitas dan lebih menekankan pengalaman batin.
Psikoanalisis juga terbukti relevan dengan perubahan sosial pada masanya. Demokratisasi, feminisme, dan krisis otoritas agama menuntut pemahaman baru tentang individu. Freud, melalui konsep ego dan ketidaksadaran, menyediakan kerangka untuk menjelaskan bagaimana pengalaman pribadi terhubung dengan pergeseran sosial. Ego dalam konteks ini adalah medan tempat individu menegosiasikan tuntutan batin dan tuntutan masyarakat modern.
Dengan demikian, bagian ini memperlihatkan bahwa psikoanalisis tidak hanya menjadi teori tentang ketidaksadaran, melainkan juga perangkat kritik terhadap rasionalitas Pencerahan. Freud menempatkan ego sebagai pusat pengalaman subjektif yang tak bisa dijelaskan oleh hukum universal. Psikoanalisis menjadi cara untuk memahami bagaimana manusia modern menghadapi dunia yang penuh konflik, bukan dengan logika mekanistik, tetapi dengan menelusuri kedalaman batin.
Freud dan Otoritas Ayah
Freud menempatkan hubungan anak dengan ayah sebagai inti dari psikoanalisis. Dalam pandangannya, Oedipus complex adalah pusat pembentukan ego dan sumber neurosis. Anak laki-laki mengalami cinta terhadap ibu dan permusuhan bercampur rasa takut terhadap ayah. Dari konflik inilah ego terbentuk, melalui represi, rasa bersalah, dan identifikasi dengan figur ayah.
Dalam Totem and Taboo (1913), Freud memperluas konsep ini ke ranah sosial. Ia merumuskan asal-usul masyarakat melalui mitos tentang “pembunuhan ayah primal.” Dari pembunuhan itu lahir tabu inses dan hukum yang melandasi struktur sosial. Freud menegaskan bahwa dasar masyarakat tidak lain adalah hubungan manusia dengan ayah. Zaretsky mengutip pernyataan Freud:
“Finally, in Totem and Taboo, he announced a ‘most surprising discovery’: that social psychology, no less than individual, ‘should prove soluble on the basis of one single concrete point—man’s relation to his father.’”
Terjemahan: “Akhirnya, dalam Totem and Taboo, ia mengumumkan sebuah ‘penemuan paling mengejutkan’: bahwa psikologi sosial, tidak kurang dari psikologi individual, ‘dapat diuraikan berdasarkan satu titik konkret tunggal—hubungan manusia dengan ayahnya.’”
Dengan pernyataan ini, Freud menekankan bahwa otoritas paternal bukan hanya persoalan keluarga, tetapi fondasi simbolik dari otoritas sosial. Ayah menjadi representasi dari hukum, negara, dan agama. Ego terbentuk karena konflik dengan otoritas tersebut, yang kemudian direproduksi dalam skala lebih luas di masyarakat.
Freud juga menolak pandangan bahwa otoritas bersifat rasional atau kontraktual sebagaimana dipahami dalam teori politik klasik. Menurutnya, otoritas lahir dari trauma dan represi. Ego terbentuk dalam suasana rasa takut dan rasa bersalah terhadap figur ayah. Karena itu, otoritas selalu rapuh, karena berdiri di atas represi yang tidak pernah sepenuhnya diselesaikan.
Konsep ini membuat teori Freud relevan untuk memahami modernitas. Otoritas tradisional yang berakar pada figur ayah mengalami krisis pada abad ke-20, seiring dengan demokrasi dan feminisme. Namun, psikoanalisis menunjukkan bahwa meskipun struktur sosial berubah, konflik dengan figur ayah tetap melekat dalam batin manusia. Ego modern terus berhadapan dengan sisa-sisa otoritas paternal.
Zaretsky menegaskan:
“In Freud’s hands, the father became not just a family figure but the symbolic representation of authority itself.”
Terjemahan: “Dalam tangan Freud, ayah menjadi bukan sekadar figur keluarga tetapi representasi simbolik dari otoritas itu sendiri.”
Dengan demikian, Freud menjadikan ego sebagai hasil dari identifikasi dengan ayah sekaligus konflik terhadapnya. Ego tidak pernah bebas dari ketegangan dengan otoritas. Dari sini terlihat bahwa kelahiran ego bukan hanya persoalan psikologi, tetapi juga refleksi dari struktur sosial yang dibentuk oleh otoritas paternal.
Alfred Adler: Inferioritas dan Demokrasi
Alfred Adler menjadi tokoh penting yang menentang reduksi Freud terhadap seksualitas sebagai pusat kehidupan psikis. Baginya, ego dibentuk bukan semata oleh konflik oedipal, tetapi terutama oleh pengalaman inferioritas. Individu, menurut Adler, berjuang untuk mengatasi kelemahan atau keterbatasan yang ia rasakan, baik bersifat fisik maupun sosial. Dari perjuangan inilah ego berkembang.
Adler memperkenalkan istilah organ inferiority untuk menjelaskan bagaimana kelemahan tubuh tertentu dapat mendorong kompensasi psikis. Namun, konsep ini kemudian diperluas sehingga meliputi pengalaman sosial yang lebih luas, seperti penghinaan, kemiskinan, atau diskriminasi. Ego, dengan demikian, dipahami sebagai hasil dari upaya mengatasi rasa rendah diri dan mencari pengakuan dalam dunia sosial.
Zaretsky menekankan bahwa Adler ingin membawa psikoanalisis keluar dari reduksi seksual menuju ranah sosial dan politik. Ia menulis:
“Like the many American thinkers who welcomed his teachings, he viewed modernity as the unfolding of a long-term process of democratization, and he wanted to assimilate psychoanalysis to reformism, social democratic politics, and a results-oriented psychotherapy.”
Terjemahan: “Seperti banyak pemikir Amerika yang menyambut ajarannya, ia memandang modernitas sebagai perkembangan dari sebuah proses jangka panjang menuju demokratisasi, dan ia ingin mengasimilasi psikoanalisis ke dalam reformisme, politik sosial-demokrat, dan psikoterapi yang berorientasi pada hasil.”
Dengan cara ini, Adler menempatkan psikoanalisis dalam kerangka demokrasi. Ego bukan lagi arena konflik intrapsikis semata, tetapi juga medan perjuangan untuk kesetaraan. Adler menolak pemahaman maskulin-sentris yang mendominasi psikoanalisis awal, dan membuka ruang bagi keterlibatan perempuan serta perjuangan sosial yang lebih luas.
Konsep Adler sering kali dipandang sebagai bentuk “demokratisasi psikoanalisis.” Ia menekankan bahwa pengalaman inferioritas dialami oleh semua orang, tetapi manifestasinya berbeda tergantung pada posisi sosial. Dengan demikian, psikoanalisis dapat digunakan untuk memahami hubungan antara individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Ego menjadi representasi dari perjuangan melawan ketidakadilan sosial.
Namun, perbedaan ini membawa Adler ke dalam konflik dengan Freud. Freud tetap menekankan seksualitas sebagai inti dari neurosis, sementara Adler menolak reduksi itu. Perdebatan keduanya semakin memanas hingga akhirnya Adler keluar dari lingkaran psikoanalisis resmi. Perpecahan ini menunjukkan bahwa sejak awal, psikoanalisis mengandung ketegangan antara perspektif seksual dan sosial.
Dengan kontribusinya, Adler memperluas pemahaman tentang ego sebagai sesuatu yang tidak hanya terbentuk oleh konflik keluarga, tetapi juga oleh perjuangan sosial. Konsep inferioritas menjadi kunci untuk menjelaskan bagaimana individu menegosiasikan posisinya dalam masyarakat modern yang sedang menuju demokratisasi. Ego, dalam pandangan Adler, adalah ekspresi dari perjuangan manusia untuk mengatasi keterbatasan dan meraih kesetaraan.
Carl Jung: Ego dan Ketidaksadaran Kolektif
Carl Jung, yang pada awalnya merupakan murid kesayangan Freud, akhirnya menempuh jalan berbeda karena perbedaan pandangan mendasar tentang ego. Jung tidak menganggap ego sebagai pusat kepribadian. Baginya, ego hanyalah lapisan permukaan yang kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan struktur psikis. Ego tidak berdiri sendiri, melainkan dikelilingi oleh wilayah luas dari ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif.
Ketidaksadaran kolektif, menurut Jung, adalah lapisan terdalam dari jiwa yang diwarisi umat manusia secara universal. Ia berisi pola-pola dasar atau arketipe yang muncul dalam mitos, legenda, dan simbol di berbagai kebudayaan. Jung percaya bahwa kehidupan manusia hanya sahih jika dijalani dengan kesadaran akan arketipe ini. Zaretsky menulis:
“Jung believed that a valid life was one lived in the shadowed valleys of what he came to call the collective unconscious, the great cosmic formations that harbor the archetypes—transhistorical structures such as the Great Mother, the Anima, and the Shadow.”
Terjemahan: “Jung percaya bahwa kehidupan yang sah adalah kehidupan yang dijalani di lembah-lembah bayangan dari apa yang ia sebut ketidaksadaran kolektif, formasi kosmik besar yang menyimpan arketipe—struktur transhistoris seperti Ibu Agung, Anima, dan Bayangan.”
Dengan memasukkan arketipe ke dalam teori psikis, Jung menunjukkan bahwa ego bukanlah entitas yang otonom. Ego hanya pintu masuk ke wilayah simbolis yang jauh lebih besar. Menurutnya, modernitas menghadirkan krisis makna karena manusia tercerabut dari simbol dan mitos yang pernah memberikan arah bagi kehidupan. Ego modern, karena itu, menjadi rapuh dan kehilangan orientasi.
Berbeda dengan Freud yang melihat agama sebagai ilusi, Jung memandang agama dan mitologi sebagai medium penting untuk menyalurkan arketipe. Ia menilai bahwa tanpa simbol religius, manusia modern akan mengalami kekosongan spiritual. Ego, dalam hal ini, hanyalah permukaan yang bisa menemukan maknanya kembali dengan menyelam ke dalam ketidaksadaran kolektif.
Pandangan Jung juga menempatkannya berlawanan dengan Adler. Jika Adler menekankan ego dalam konteks sosial dan demokratis, Jung lebih menekankan dimensi kosmik dan simbolis. Ego tidak dilihat sebagai arena perjuangan status, melainkan sebagai titik kontak dengan struktur psikis universal. Ego, dalam kerangka ini, hanya bisa dipahami dengan melihat hubungan manusia dengan simbol-simbol arketipal.
Perbedaan Jung dengan Freud semakin tajam ketika ia mengabaikan penekanan Freud pada seksualitas. Freud memusatkan perhatian pada dorongan seksual sebagai sumber konflik, sementara Jung menekankan simbolisme mitologis. Perbedaan ini akhirnya memicu perpecahan antara keduanya. Ego dalam psikoanalisis Jung menjadi konsep yang jauh lebih transpersonal dibandingkan dengan definisi Freud yang berakar pada konflik keluarga.
Dengan demikian, konsep ego menurut Jung menegaskan bahwa kehidupan psikis manusia lebih luas daripada yang dibayangkan Freud maupun Adler. Ego hanyalah sebagian kecil dari struktur kosmik yang lebih besar, yaitu ketidaksadaran kolektif. Dari perspektif Jung, pemahaman ego tidak bisa dilepaskan dari simbol, mitos, dan arketipe yang membentuk pengalaman manusia lintas zaman.
Perpecahan dalam Gerakan Psikoanalisis
Perbedaan mendasar antara Freud, Adler, dan Jung berujung pada perpecahan dalam gerakan psikoanalisis. Freud menekankan Oedipus complex dan seksualitas sebagai inti psikoanalisis, sementara Adler menekankan rasa inferioritas dan perjuangan sosial, dan Jung menekankan ketidaksadaran kolektif serta simbolisme kosmik. Perbedaan-perbedaan ini membuat psikoanalisis sejak awal bukanlah gerakan yang solid, melainkan rentan terhadap fragmentasi.
Adler adalah tokoh pertama yang keluar dari lingkaran Freud. Ia menolak dominasi seksualitas dalam teori psikoanalisis dan menggantinya dengan konsep inferioritas. Freud menuduh Adler menyimpang dari inti psikoanalisis. Perselisihan ini memuncak dalam perpecahan yang berakhir dengan berdirinya kelompok baru di bawah kepemimpinan Adler, yang dikenal sebagai “psikologi individual.”
Tidak lama kemudian, konflik Freud dengan Jung juga muncul ke permukaan. Awalnya, Freud melihat Jung sebagai penerus potensial dan simbol penting untuk memperluas psikoanalisis ke luar lingkaran Yahudi. Namun, perbedaan teoritis mengenai seksualitas dan ketidaksadaran membuat hubungan keduanya memburuk. Jung menolak pandangan Freud tentang seksualitas sebagai faktor utama, sedangkan Freud menolak ide Jung tentang arketipe dan ketidaksadaran kolektif.
Perpecahan ini mencerminkan ketegangan lebih luas dalam modernitas. Freud menekankan konflik keluarga, Adler menekankan konflik sosial, dan Jung menekankan konflik spiritual. Ketiganya melihat ego dari perspektif berbeda, yang saling bertentangan, namun semuanya menjawab pertanyaan yang sama: bagaimana individu dapat memahami dirinya di tengah modernitas.
Untuk menjaga otoritas, Freud membentuk Secret Committee atau Komite Rahasia. Zaretsky menulis:
“Freud established the Secret Committee to ensure the unity and orthodoxy of the movement, a body of loyal disciples who pledged to protect psychoanalysis against deviation.”
Terjemahan: “Freud membentuk Komite Rahasia untuk memastikan kesatuan dan ortodoksi gerakan, sebuah kelompok murid setia yang berjanji melindungi psikoanalisis dari penyimpangan.”
Komite Rahasia ini berfungsi sebagai penjaga ortodoksi. Para anggotanya adalah murid-murid dekat Freud yang bertekad mempertahankan kemurnian psikoanalisis dari ancaman perpecahan lebih lanjut. Dengan cara ini, psikoanalisis berkembang bukan hanya sebagai teori ilmiah, tetapi juga sebagai gerakan yang diikat oleh loyalitas pribadi dan struktur otoritas yang ketat.
Perpecahan di dalam psikoanalisis ini pada akhirnya memperlihatkan cerminan modernitas. Zaretsky menulis bahwa konflik internal dalam gerakan Freud sejajar dengan krisis sosial yang lebih luas di awal abad ke-20. Ego, yang menjadi inti perdebatan, lahir dari tarik-menarik antara berbagai tafsir dan otoritas yang berbeda. Karena itu, ego dalam psikoanalisis tidak pernah menjadi konsep yang stabil, melainkan selalu dalam ketegangan.
Gender dan Perempuan dalam Psikoanalisis
Bab ini menekankan bahwa persoalan ego tidak bisa dipisahkan dari isu gender. Freud, Adler, dan Jung berbeda pandangan mengenai posisi perempuan dalam psikoanalisis. Freud mengembangkan teori narsisisme perempuan, Adler mengaitkan inferioritas dengan penindasan sosial terhadap perempuan, sedangkan Jung menempatkan feminitas sebagai arketipe penting dalam ketidaksadaran kolektif. Dengan demikian, kehadiran perempuan menjadi faktor krusial dalam diskusi tentang kelahiran ego.
Salah satu tokoh perempuan yang berpengaruh dalam teori Freud adalah Lou Andreas-Salomé. Freud menggunakan gagasan Salomé untuk menjelaskan narsisisme perempuan. Menurut Freud, perempuan cenderung menjadi objek cinta daripada subjek yang memilih, dan hal ini menimbulkan bentuk narsisisme yang khas. Zaretsky mencatat:
“Freud drew heavily on Lou Andreas-Salomé’s account of feminine narcissism in formulating his own views.”
Terjemahan: “Freud banyak mengambil dari penjelasan Lou Andreas-Salomé tentang narsisisme feminin dalam merumuskan pandangannya sendiri.”
Selain itu, tokoh penting lain adalah Margarete Hilferding, yang pada tahun 1910 menjadi perempuan pertama yang diterima dalam Vienna Psychoanalytic Society. Kehadirannya menandai awal keterlibatan perempuan dalam komunitas psikoanalisis. Namun, ia menghadapi resistensi karena dominasi laki-laki masih sangat kuat dalam masyarakat psikoanalitik saat itu. Meski begitu, partisipasi Hilferding memperluas dimensi gender dalam diskusi teori ego.
Perempuan juga berkontribusi secara aktif, bukan hanya sebagai objek kajian. Kehadiran mereka memaksa komunitas psikoanalisis untuk memikirkan kembali konsep ego dalam kaitannya dengan relasi gender. Dengan demikian, psikoanalisis mulai melibatkan dimensi yang lebih luas: bukan hanya hubungan ayah-anak laki-laki, tetapi juga peran ibu, pengalaman perempuan, dan ketidaksetaraan gender.
Adler menekankan bahwa inferioritas yang dialami perempuan sering kali bersumber dari struktur sosial. Ia menghubungkan pengalaman perempuan dengan marginalisasi yang memperburuk rasa rendah diri. Jung, di sisi lain, memperkenalkan konsep Anima sebagai arketipe feminitas dalam jiwa laki-laki, yang menunjukkan pentingnya dimensi perempuan dalam kehidupan psikis kolektif.
Freud sendiri berusaha merumuskan perbedaan gender dalam kerangka narsisisme. Ia menekankan bahwa cinta diri pada perempuan memiliki bentuk yang berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian, gender menjadi kunci penting dalam memahami variasi narsisisme. Perbedaan penekanan antara Freud, Adler, dan Jung memperlihatkan bahwa gender adalah medan utama perdebatan dalam psikoanalisis.
Bab ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan memperluas batas psikoanalisis. Kehadiran tokoh seperti Lou Andreas-Salomé dan Margarete Hilferding membuat ego dipahami tidak hanya dalam kerangka maskulin, tetapi juga dalam kaitan dengan pengalaman perempuan. Dengan cara itu, psikoanalisis mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk perjuangan feminisme pada awal abad ke-20.
Freud dan Teori Narsisisme
Freud memperkenalkan konsep narsisisme secara sistematis dalam esainya On Narcissism (1914). Di sana ia menjelaskan bahwa narsisisme adalah tahap perkembangan seksual di mana individu mengarahkan libido kepada dirinya sendiri. Konsep ini memperluas teori libido Freud, yang sebelumnya lebih menekankan pada objek eksternal. Dengan narsisisme, Freud menunjukkan bahwa energi libido juga bisa diarahkan ke dalam diri.
Bayi merupakan contoh paling jelas dari narsisisme primer. Freud menulis tentang hal ini dengan kalimat terkenal:
“His majesty, the baby.”
Terjemahan: “Yang Mulia, sang bayi.”
Ungkapan ini menggambarkan bagaimana bayi diperlakukan sebagai pusat perhatian dan simbol cinta diri yang absolut pada tahap awal kehidupan. Narsisisme primer inilah yang menjadi dasar pembentukan ego.
Zaretsky menekankan:
“Narcissism, or self-love, was a stage in the development of sexuality.”
Terjemahan: “Narsisisme, atau cinta diri, adalah sebuah tahap dalam perkembangan seksualitas.”
Dengan demikian, Freud menegaskan bahwa ego bukan hanya hasil konflik oedipal, melainkan juga hasil dari dinamika cinta diri yang mendasar dalam perkembangan manusia.
Freud kemudian membedakan antara narsisisme primer dan sekunder. Narsisisme primer adalah tahap awal ketika libido diarahkan kepada ego, sementara narsisisme sekunder terjadi ketika libido yang sebelumnya diarahkan ke objek eksternal ditarik kembali ke ego. Konsep ini penting untuk menjelaskan berbagai fenomena patologis, seperti skizofrenia, di mana libido ditarik dari dunia luar kembali ke dalam diri.
Teori narsisisme juga memberi dasar untuk memahami harga diri dan ideal ego. Freud menekankan bahwa narsisisme berperan penting dalam pembentukan struktur ego, termasuk bagaimana individu menilai dirinya dan bagaimana ia mengidealkan citra dirinya. Dari sini, narsisisme tidak hanya menjadi teori perkembangan seksual, tetapi juga landasan bagi pemahaman tentang identitas dan penghargaan diri.
Freud menggunakan konsep narsisisme untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat diterangkan dengan teori libido tradisional. Narsisisme memperluas jangkauan psikoanalisis, sehingga dapat digunakan untuk memahami gejala neurotik, gangguan psikosis, dan dinamika identifikasi sosial. Teori ini menjembatani dunia intrapsikis dengan dunia sosial.
Dengan memperkenalkan narsisisme, Freud berhasil memperluas teori ego dari sekadar mediator konflik oedipal menjadi pusat cinta diri dan harga diri. Teori ini juga membuka jalan bagi psikoanalisis untuk membahas identifikasi kolektif dan fenomena budaya. Karena itu, bagian ini menegaskan bahwa konsep narsisisme adalah tonggak penting dalam perkembangan pemikiran Freud tentang ego.
Narsisisme dan Identitas Kolektif
Teori narsisisme segera meluas dari ranah individu ke ranah sosial. Freud menegaskan bahwa cinta diri tidak hanya membentuk ego personal, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas kelompok. Individu mengarahkan libido tidak hanya ke dalam dirinya, tetapi juga ke luar dengan mengidentifikasi diri pada bangsa, kelas sosial, atau kelompok tertentu. Dengan cara ini, narsisisme menjadi kunci untuk memahami dinamika identitas kolektif.
Zaretsky menulis:
“The theory of narcissism contributed to a critical approach toward modern democratic society… it paved the way for the psychoanalytic critiques of anti-Semitism, mass culture, and fascism that flourished after World War I.”
Terjemahan: “Teori narsisisme berkontribusi pada sebuah pendekatan kritis terhadap masyarakat demokratis modern… ia membuka jalan bagi kritik psikoanalitik terhadap anti-Semitisme, budaya massa, dan fasisme yang berkembang setelah Perang Dunia I.”
Dengan kerangka ini, Freud menjelaskan bahwa narsisisme kolektif muncul ketika individu mengidentifikasi dirinya dengan pemimpin atau simbol bersama. Ego personal dilebur ke dalam ego kolektif, menciptakan solidaritas kuat namun sekaligus membuka ruang bagi fanatisme. Inilah yang menjelaskan mengapa pemimpin karismatik dapat menarik jutaan pengikut, serta mengapa nasionalisme dan fasisme dapat muncul begitu kuat pada awal abad ke-20.
Freud juga melihat bagaimana narsisisme berhubungan dengan agresi kolektif. Kebencian terhadap kelompok lain, seperti dalam anti-Semitisme, dapat dipahami sebagai proyeksi konflik batin yang diarahkan keluar. Identifikasi positif dengan kelompok sendiri berjalan beriringan dengan permusuhan terhadap kelompok lain. Dengan demikian, narsisisme menjelaskan baik solidaritas internal maupun agresi eksternal dalam kehidupan sosial.
Fenomena budaya massa juga bisa dijelaskan melalui teori narsisisme. Identifikasi dengan figur publik, selebriti, atau tokoh politik memperlihatkan bagaimana ego individu mencari pengganti atas kehilangan ikatan tradisional. Dengan meleburkan diri dalam simbol-simbol budaya, individu merasa menemukan kembali stabilitas identitas. Namun, ini juga memperlihatkan kerentanan ego modern yang mencari makna dalam dunia eksternal.
Freud mengembangkan analisis ini lebih jauh dalam Group Psychology and the Analysis of the Ego (1921). Ia menegaskan bahwa identifikasi kolektif adalah bentuk narsisisme yang terarah keluar. Ego tidak bisa dipahami tanpa merujuk pada kelompok sosial. Karena itu, narsisisme menghubungkan antara dinamika batin individu dan fenomena kolektif.
Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa narsisisme adalah konsep kunci untuk menjelaskan keterkaitan ego dengan masyarakat. Ego tidak hanya lahir dari konflik keluarga atau cinta diri, tetapi juga dari identifikasi dengan kelompok. Teori narsisisme memperlihatkan bahwa ego modern adalah refleksi dari identitas kolektif yang rapuh, yang bisa menghasilkan solidaritas sekaligus konflik sosial.
Perang Dunia I dan Krisis Peradaban
Perang Dunia I menjadi konteks historis yang memperkuat teori Freud tentang narsisisme dan ego. Freud menyaksikan bagaimana Eropa, yang dianggap pusat peradaban, justru runtuh ke dalam kekerasan massal. Perang ini menegaskan bahwa peradaban modern tidak stabil, karena selalu terancam oleh dorongan destruktif yang berasal dari bawah sadar. Ego, baik individu maupun kolektif, terbukti rapuh di hadapan kekuatan itu.
Freud menulis Mourning and Melancholia (1917) untuk menjelaskan dampak kehilangan besar pada ego. Ia membedakan antara duka (mourning) yang sehat, di mana individu mampu melepaskan objek yang hilang, dan melankolia (melancholia), di mana kehilangan justru menjadi serangan terhadap ego sendiri. Analisis ini lahir dari pengamatan Freud terhadap trauma yang dihasilkan oleh perang.
Dalam surat pribadinya, Freud menulis kepada Ferenczi:
“I live in a primitive trench.”
Terjemahan: “Saya hidup di dalam sebuah parit primitif.”
Ungkapan ini menggambarkan bagaimana Freud memandang perang sebagai kemunduran peradaban ke kondisi primitif, di mana naluri agresi mendominasi.
Perang Dunia I juga memperlihatkan bagaimana narsisisme kolektif bisa berubah menjadi kekuatan destruktif. Identifikasi nasional yang kuat memicu solidaritas, tetapi juga kebencian terhadap musuh. Freud melihat bagaimana negara-negara Eropa meleburkan ego individu ke dalam ego kolektif bangsa, dan dari situ lahir agresi yang menghancurkan.
Zaretsky menulis:
“World War I confirmed Freud’s suspicion that civilization was a fragile construct, always threatened by unconscious drives and collective identifications.”
Terjemahan: “Perang Dunia I menegaskan kecurigaan Freud bahwa peradaban adalah sebuah konstruksi rapuh, yang selalu terancam oleh dorongan tak sadar dan identifikasi kolektif.”
Dengan pengalaman perang, Freud semakin yakin bahwa ego tidak bisa dipisahkan dari trauma sosial. Ego tidak hanya menghadapi konflik internal, tetapi juga harus menanggung beban sejarah. Trauma kolektif memperlihatkan bahwa ego modern selalu berada dalam ketegangan antara dorongan batin dan realitas sosial.
Bagian ini menutup dengan kesimpulan bahwa perang menjadi titik balik dalam teori psikoanalisis. Ego terbukti tidak mampu sepenuhnya mengatasi kehilangan dan agresi. Modernitas, yang dibangun di atas rasionalitas, ternyata tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan tak sadar. Psikoanalisis, melalui konsep narsisisme dan trauma, memberi kerangka untuk memahami kerentanan peradaban modern.
Penutup
Bab ini menegaskan bahwa kelahiran ego merupakan fenomena multidimensi. Freud, Adler, dan Jung memberi definisi yang berbeda, tetapi semuanya menanggapi krisis modernitas. Freud menekankan konflik oedipal dan narsisisme, Adler menekankan inferioritas dan perjuangan demokratis, sementara Jung menekankan ketidaksadaran kolektif dan simbol. Perbedaan ini mencerminkan ketegangan sosial, politik, dan budaya pada awal abad ke-20.
Freud menunjukkan bahwa ego terbentuk melalui konflik oedipal, identifikasi dengan ayah, rasa bersalah, dan cinta diri. Namun, ia juga menambahkan dimensi sosial melalui teori narsisisme dan identifikasi kolektif. Ego menjadi rapuh karena harus selalu menegosiasikan antara dorongan batin dan tuntutan masyarakat.
Adler memperluas pemahaman ego dengan menempatkannya dalam kerangka sosial. Ego bukan hanya arena konflik intrapsikis, tetapi juga ekspresi perjuangan melawan inferioritas dalam masyarakat yang sedang bergerak menuju demokrasi. Kontribusinya membuat psikoanalisis lebih relevan dengan reformasi sosial dan feminisme.
Jung menolak menempatkan ego sebagai pusat kepribadian. Ia melihat ego sebagai permukaan tipis yang menutupi ketidaksadaran kolektif, yang dihuni oleh arketipe universal. Baginya, krisis modernitas adalah krisis spiritual, yang hanya dapat diatasi dengan menghubungkan diri dengan simbol dan mitos kolektif.
Zaretsky merangkum:
“The divisions within psychoanalysis mirrored the divisions within modernity itself.”
Terjemahan: “Perpecahan di dalam psikoanalisis mencerminkan perpecahan di dalam modernitas itu sendiri.”
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perdebatan Freud, Adler, dan Jung mencerminkan fragmentasi modernitas. Ego lahir dari ketegangan itu, sehingga ia menjadi refleksi dari kondisi manusia modern.
Perang Dunia I semakin menegaskan rapuhnya ego. Trauma kolektif, kehilangan massal, dan munculnya fasisme memperlihatkan bagaimana narsisisme kolektif bisa menghancurkan peradaban. Freud menjadikan teori narsisisme sebagai alat untuk memahami hubungan antara ego dan identitas sosial.
Dengan demikian, bab ini ditutup dengan kesimpulan bahwa ego adalah produk modernitas. Ia lahir dari konflik keluarga, perjuangan sosial, simbol kosmik, dan trauma sejarah. Ego tidak pernah stabil, tetapi justru karena ketidakstabilannya itulah ego menjadi pusat pemahaman tentang manusia modern. Psikoanalisis memberi bahasa untuk membaca krisis tersebut, sekaligus menjadikan ego sebagai cermin dari peradaban modern.

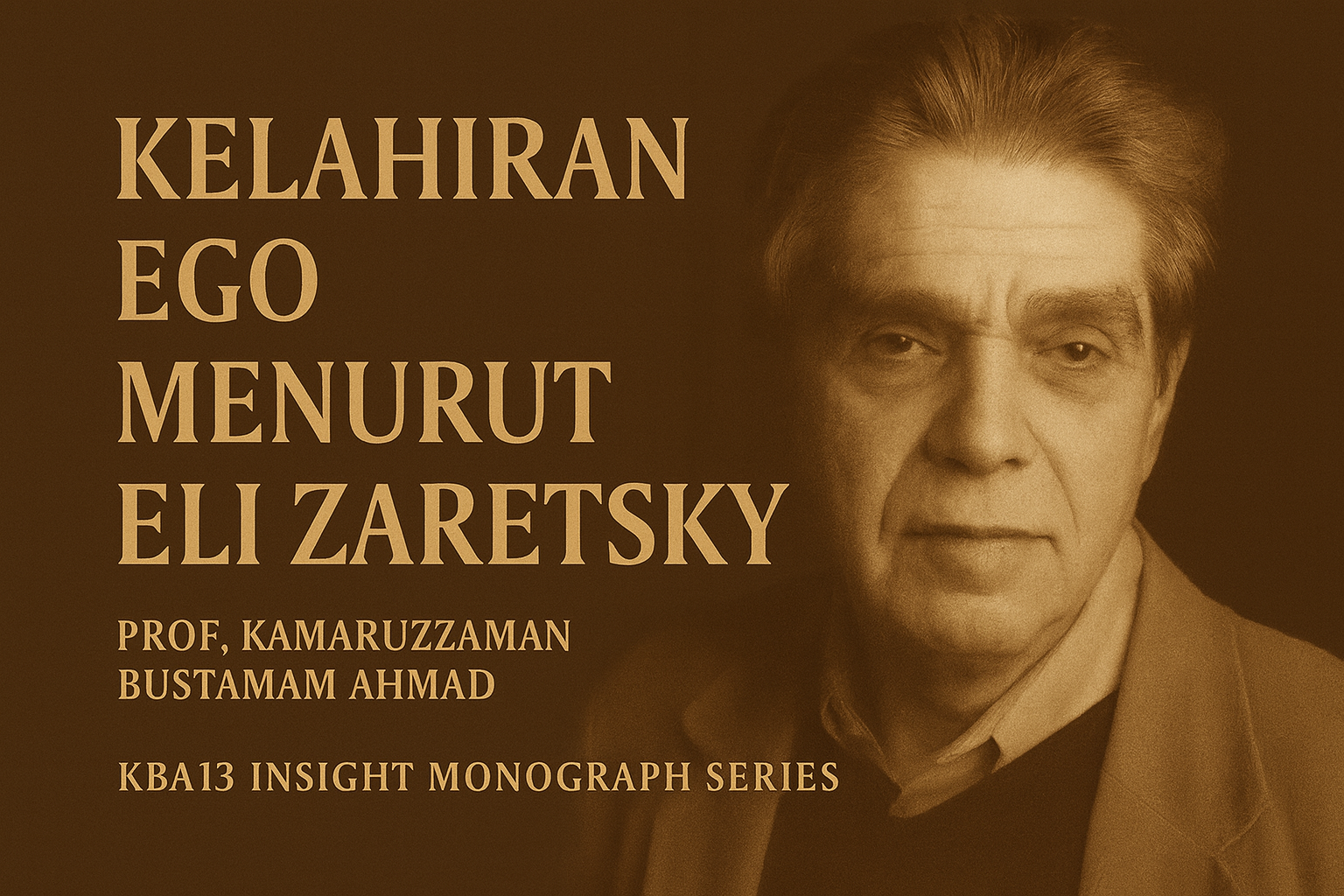

Leave a Reply