Buku Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial-Politik yang disunting oleh Azyumardi Azra dan Saiful Umam ini menghadirkan mosaik sejarah yang jarang disentuh secara serius dalam penulisan politik Indonesia. Dari judulnya saja, kita seolah diajak untuk tidak hanya melihat sosok-sosok yang pernah duduk di kursi Menteri Agama sebagai pejabat administratif, melainkan sebagai figur dengan latar sosial, tradisi intelektual, dan pengalaman politik yang membentuk jalannya republik. Setiap menteri yang diulas dalam buku ini—H.M. Rasjidi, Fathurrahman Kafrawi, K.H. Masjkur, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Fakih Usman, serta lampiran tentang Teuku Moehammad Hasan—dihadirkan dalam bentuk narasi biografis yang menekankan pada keterkaitan antara kehidupan personal mereka dengan dinamika sosial-politik bangsa pada masanya.
Pada bab pertama, Azyumardi Azra menulis tentang H.M. Rasjidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Rasjidi bukan hanya seorang tokoh Muhammadiyah, tetapi juga seorang intelektual modernis yang terdidik di dunia Islam internasional. Kehadirannya di awal revolusi kemerdekaan membuatnya harus menata Kementerian Agama dari ketiadaan. Ia tidak hanya merumuskan struktur kelembagaan, tetapi juga membangun legitimasi kementerian yang saat itu masih dipertanyakan urgensinya. Dalam suasana revolusi, Rasjidi menegaskan bahwa keberadaan kementerian ini bukan sekadar simbol agama, melainkan sebuah instrumen strategis yang menjaga keterhubungan antara agama dan negara. Buku ini memperlihatkan bagaimana Rasjidi membawa visi Islam modernis yang berpadu dengan semangat republik yang baru lahir.
Bab berikutnya membawa kita pada sosok Fathurrahman Kafrawi, yang dibedah oleh A.K.H. Minhaji dan M. Atho Mudzhar. Di tangan Kafrawi, isu pendidikan agama di sekolah umum menjadi perhatian utama. Ia menyadari bahwa republik yang baru lahir tidak bisa membiarkan agama hanya hidup di ranah pesantren atau madrasah. Pendidikan agama harus masuk ke sekolah umum sebagai bagian dari sistem nasional. Kebijakan ini tentu bukan tanpa perdebatan. Ada tarik-menarik ideologi di balik kurikulum nasional, tetapi Kafrawi dengan keteguhan pandangannya mampu memperjuangkan agar agama hadir di ruang kelas, membentuk generasi yang sekaligus religius dan kebangsaan. Dari sinilah akar pengajaran agama di sekolah umum di Indonesia menemukan bentuknya.
Kisah K.H. Masjkur ditulis oleh Ahmad Syafi’i, yang menghadirkan potret kementerian dalam suasana perang kemerdekaan. Masjkur adalah menteri yang bekerja di tengah-tengah gerilya, ketika republik tidak memiliki kepastian arah. Konsep Waliyul Amri, yakni otoritas darurat dalam kondisi perang, menjadi landasan untuk tetap menjaga agar agama tetap memiliki pijakan dalam kehidupan publik. Di masa ketika peluru berdesingan dan kabinet berpindah-pindah, kementerian tetap berdiri sebagai lembaga yang mencoba menjaga kesinambungan spiritual bangsa. Masjkur tidak hanya tercatat sebagai menteri dalam catatan formal, tetapi sebagai sosok yang menunjukkan bahwa kementerian ini bisa bertahan meski negara berada di titik paling kritis.
Narasi kemudian bergeser pada K.H. Wahid Hasyim, yang ditulis dengan cermat oleh Saiful Umam. Putra pendiri Nahdlatul Ulama ini menghadirkan dimensi baru dalam sejarah Kementerian Agama. Wahid Hasyim tidak hanya mewarisi khazanah pesantren, tetapi juga memadukannya dengan visi modernisasi. Di tangannya, tata kelola haji mulai dibenahi, hubungan diplomatik dengan Arab Saudi diperkuat, dan pendidikan tinggi agama Islam mulai dirintis dengan lahirnya PTAIN. Konsolidasi kementerian di era Wahid Hasyim memperlihatkan bahwa kementerian ini bukan lagi lembaga darurat revolusi, melainkan bagian permanen dari struktur negara yang terus bergerak maju. Keberaniannya mempertemukan tradisi pesantren dengan visi modern adalah warisan yang tak ternilai.
Selanjutnya, Didin Syafrudin menulis tentang K.H. Fakih Usman, yang memberi perhatian penuh pada pengembangan pendidikan agama. Fakih Usman dikenal sebagai seorang organisator ulung. Ia memahami betul bahwa tanpa kurikulum yang terstandar, tenaga pendidik yang terlatih, dan sistem administrasi yang rapi, pendidikan agama tidak akan bisa berkembang. Dengan konsistensi yang tinggi, Fakih Usman mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Dari bab ini, kita bisa melihat bagaimana Kementerian Agama membangun peran pendidikan tidak hanya di madrasah, tetapi juga dalam cakupan lebih luas, menyentuh sekolah-sekolah umum, bahkan universitas.
Sebagai pelengkap, buku ini menghadirkan appendix tentang Teuku Moehammad Hasan, Menteri Agama dalam kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dwi Purwoko menuliskannya sebagai bagian dari penegasan bahwa kementerian ini tetap berjalan meski republik berada di bawah ancaman serius dari Belanda. Teuku Moehammad Hasan, tokoh Aceh yang pernah menjabat Gubernur Sumatera, memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan. Dalam konteks ini, jabatan Menteri Agama tidak bisa dipandang kecil, sebab perannya menjaga legitimasi negara tetap hidup di tengah kondisi darurat.
Secara keseluruhan, buku ini menyajikan sebuah rangkaian biografi yang saling terkait, membentuk gambaran besar tentang fondasi Kementerian Agama. Setiap bab memperlihatkan sosok yang berbeda, tetapi mereka semua menghadapi tantangan yang sama: bagaimana menempatkan agama dalam kerangka negara yang baru lahir dan sedang berjuang. Dari Rasjidi yang merumuskan kementerian, Kafrawi yang membawa agama ke sekolah umum, Masjkur yang menjaga kementerian dalam gerilya, Wahid Hasyim yang melakukan konsolidasi, Fakih Usman yang mengembangkan pendidikan agama, hingga Teuku Moehammad Hasan yang memastikan keberlanjutan kementerian dalam kabinet darurat, kita menemukan bahwa sejarah kementerian ini adalah kisah tentang perjuangan, konsistensi, dan visi yang jauh ke depan.
Buku Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial-Politik bukan sekadar kumpulan kisah personal. Ia adalah dokumen sejarah yang menghadirkan dinamika sosial-politik Indonesia melalui tokoh-tokoh yang pernah duduk di kursi Menteri Agama. Dengan gaya penulisan yang akademis sekaligus naratif, buku ini tidak hanya mengajak kita memahami para menteri sebagai figur individu, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa. Inilah yang membuat buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami fondasi awal Kementerian Agama Republik Indonesia.

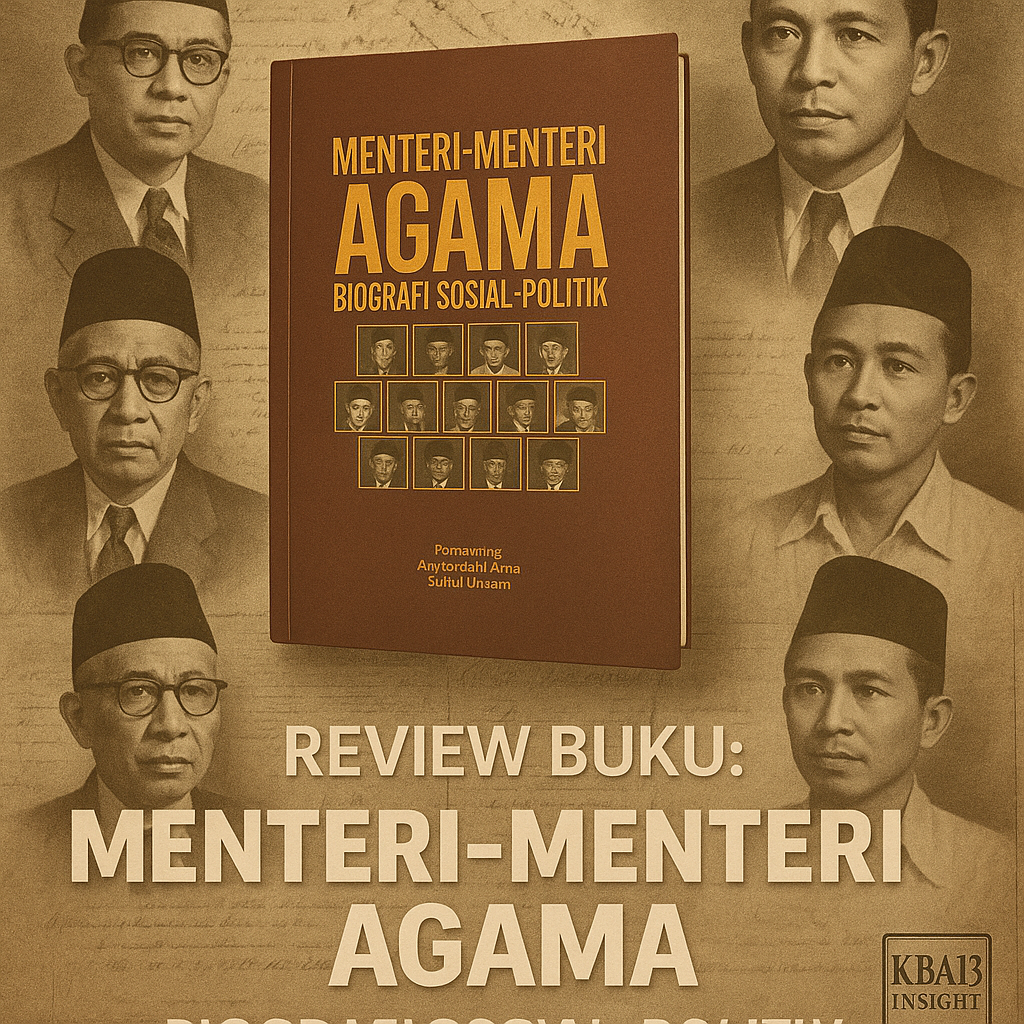

Leave a Reply