Banda Aceh, 2 September 2025 – Hari ini di ruang Memorial Perdamaian Kebang Pol Provinsi Aceh, di Banda Aceh tidak hanya memperingati 66 tahun Hardikda, melainkan juga menjadi saksi perbincangan serius tentang masa depan Aceh. Dalam ruang diskusi yang difasilitasi Kesbangpol Aceh bersama Tim Kajian Perdamaian, para akademisi, peneliti, dan birokrat bertemu untuk membicarakan satu tema besar: transisi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan kaitannya dengan inklusivitas pendidikan serta Syariat Islam.
Moderator Adi Warsidi membuka percakapan dengan mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di ruang-ruang digital. Generasi muda Aceh, katanya, kini menjadikan media sosial sebagai “kurikulum muatan lokal” mereka. Pernyataan itu mengalirkan suasana diskusi yang lebih cair, tetapi juga semakin tajam, ketika Khairul Fahmi tampil sebagai narasumber utama.
Khairul menegaskan bahwa Dana Otsus Aceh tidak boleh berhenti pada 2027. Ia menelusuri sejarah panjang pendidikan Aceh, dari masa kerajaan hingga kolonial, ketika sekolah rakyat pernah dicurigai Belanda sebagai sarang perlawanan. Ia lalu mengajukan pertanyaan kritis: apakah dayah memang bisa dianggap sebagai anak kandung Dana Otsus, atau hanya ditempatkan dalam simbol politik belaka? Lebih jauh, ia mengingatkan adanya ketegangan antara gagasan inklusivitas dan pluralisme dalam pendidikan Aceh. Baginya, pendidikan harus bisa menyapa semua kalangan, termasuk minoritas, penyandang disabilitas, dan anak-anak non-Muslim, tanpa mengurangi keistimewaan Syariat Islam yang telah menjadi roh kehidupan masyarakat Aceh.
Suasana diskusi kian hidup ketika peserta mulai memberikan pandangan. Uswah Hasanah dari UIN Ar-Raniry, misalnya, menyampaikan kegelisahan tentang kejelasan kebijakan di Aceh. Apakah pendidikan dan Syariat Islam akan berjalan terpisah, atau justru menyatu dalam satu kerangka yang kabur? Pertanyaan itu memicu respons lain, seperti dari Mirza yang menyoroti alokasi dana dayah sebesar Rp500 miliar. Baginya, angka itu terlalu besar untuk tidak dipertanyakan. Apa bentuk penyalurannya, bagaimana mekanismenya, dan apakah dayah tetap menjadi prioritas ketika Otsus benar-benar berakhir?
Dari sisi lain, Fuadi mengangkat dimensi HAM yang jarang disentuh dalam diskusi pendidikan Aceh. Ia mempertanyakan apakah anak-anak non-Muslim harus dipaksa mempelajari Islam di sekolah, sementara seharusnya pendidikan Aceh bisa tetap inklusif tanpa kehilangan ruh Syariat. Pandangan ini disambung oleh Imran, yang menilai pembahasan masih terlalu normatif. Ia mendorong agar diskusi diarahkan langsung pada lembaga-lembaga pendidikan konkret di Aceh, sambil mengkritisi akses yang timpang terhadap Baitul Mal dan setoran komite sekolah yang kerap memberatkan orang tua.
Mumtazinur kemudian mencoba merangkum berlapis isu yang berserakan. Baginya, Otsus dan Syariat Islam harus dibaca dalam kaitan yang lebih mendalam. Ia mengingatkan tentang krisis identitas generasi muda Muslim Aceh yang sering merasa terjepit antara regulasi Syariat dan realitas kehidupan sehari-hari. Apakah razia Syariat di ruang publik benar-benar memperkuat nilai, atau justru mengasingkan Syariat dari roh masyarakat? Pertanyaan itu menggema, menyiratkan keresahan yang tak mudah dijawab.
Sementara itu, Khaliza Zahara menuntut data konkret. Menurutnya, klaim bahwa dayah adalah anak kandung Dana Otsus harus ditopang bukti empiris, bukan sekadar jargon. Hal serupa ditegaskan Nailis Wildany, yang menyinggung resistensi sebagian ulama dayah terhadap mahasiswa Aceh yang kuliah di Madinah. Ada ketegangan lama antara tradisi Azharian dan pengaruh Timur Tengah yang lebih puritan.
Suasana menjadi reflektif ketika Dr. Mukhlisuddin Ilyas berbicara. Ia mengaitkan diskusi ini dengan sejarah Hardikda yang diperingati setiap 2 September sejak 1959. Bagi Mukhlisuddin, pendidikan Aceh telah berjalan panjang, namun kualitasnya masih kerap menjadi bahan “meme” di ruang publik. Meskipun dana besar digelontorkan, perilaku elit dan masyarakat tidak banyak berubah. Ia menegaskan bahwa pendidikan Aceh tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, melainkan membutuhkan pembaruan nilai, semangat, dan kualitas yang nyata.
Pandangan yang lebih teknis datang dari Zahlul Fasha, yang menilai metode netnografi tidak relevan untuk mengukur kondisi pendidikan Aceh. Kritik ini menutup rangkaian perdebatan dengan nada skeptis, namun juga menjadi pengingat bahwa kajian metodologi tidak kalah penting dari isu substansi.
Diskusi yang dipandu oleh Adi Warsidi dan dihadiri oleh Dedy Andrian, Kabid Wasnas Kesbangpol Aceh, menghasilkan kesadaran bersama bahwa transisi Dana Otsus bukan sekadar soal teknis keuangan. Di dalamnya terkandung pertanyaan identitas, pluralitas, kualitas, dan arah pendidikan Aceh pasca-2027.
Pendidikan Aceh, sebagaimana ditekankan oleh Khairul Fahmi, harus dirancang ulang agar benar-benar inklusif sekaligus tetap setia pada Syariat Islam. Sementara para peserta mengingatkan, tanpa keberanian politik untuk transparan, tanpa kejelasan peran dayah dan sekolah umum, serta tanpa ruang bagi generasi muda untuk menentukan arah, maka pendidikan Aceh akan terus berjalan dalam lingkaran yang sama.






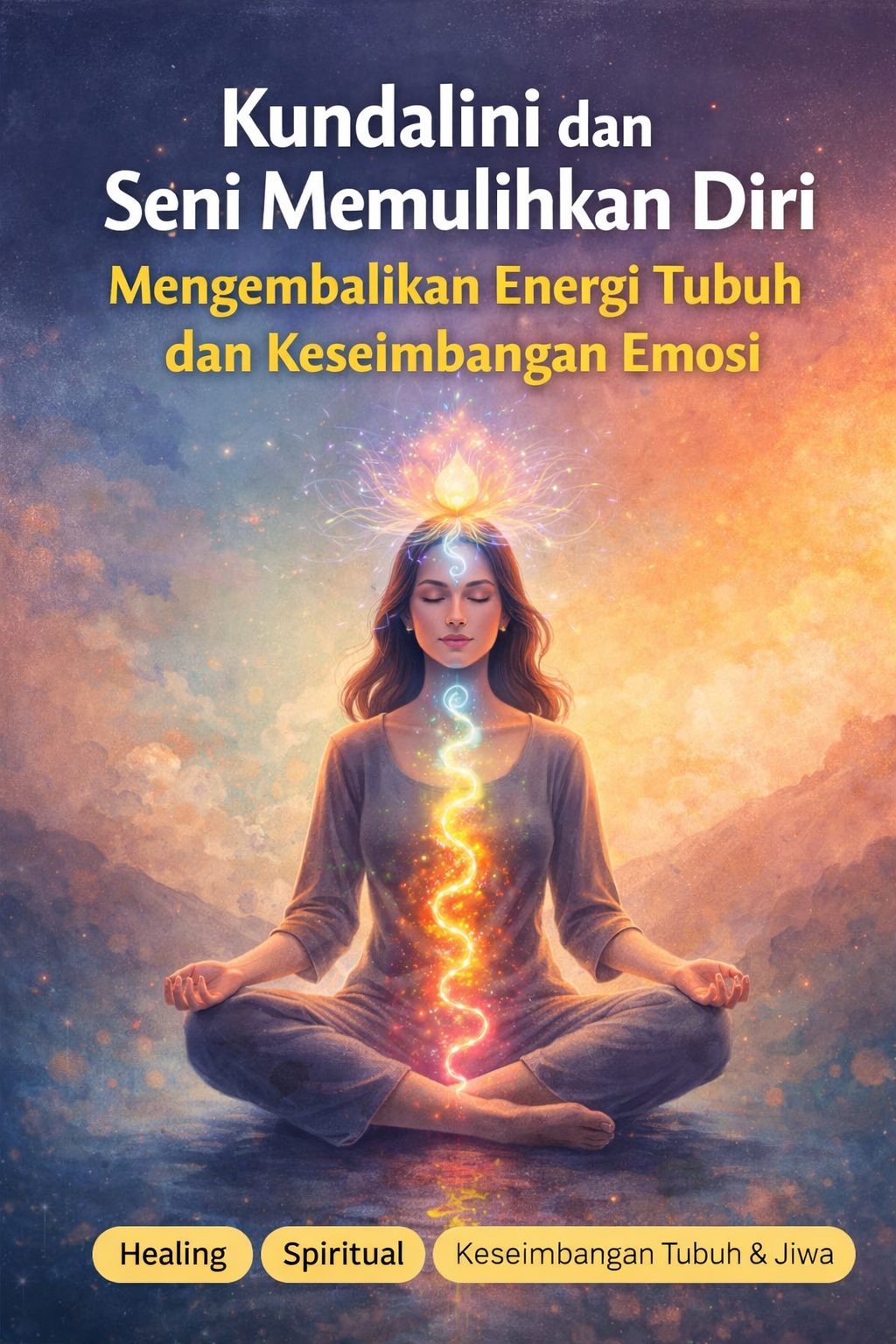

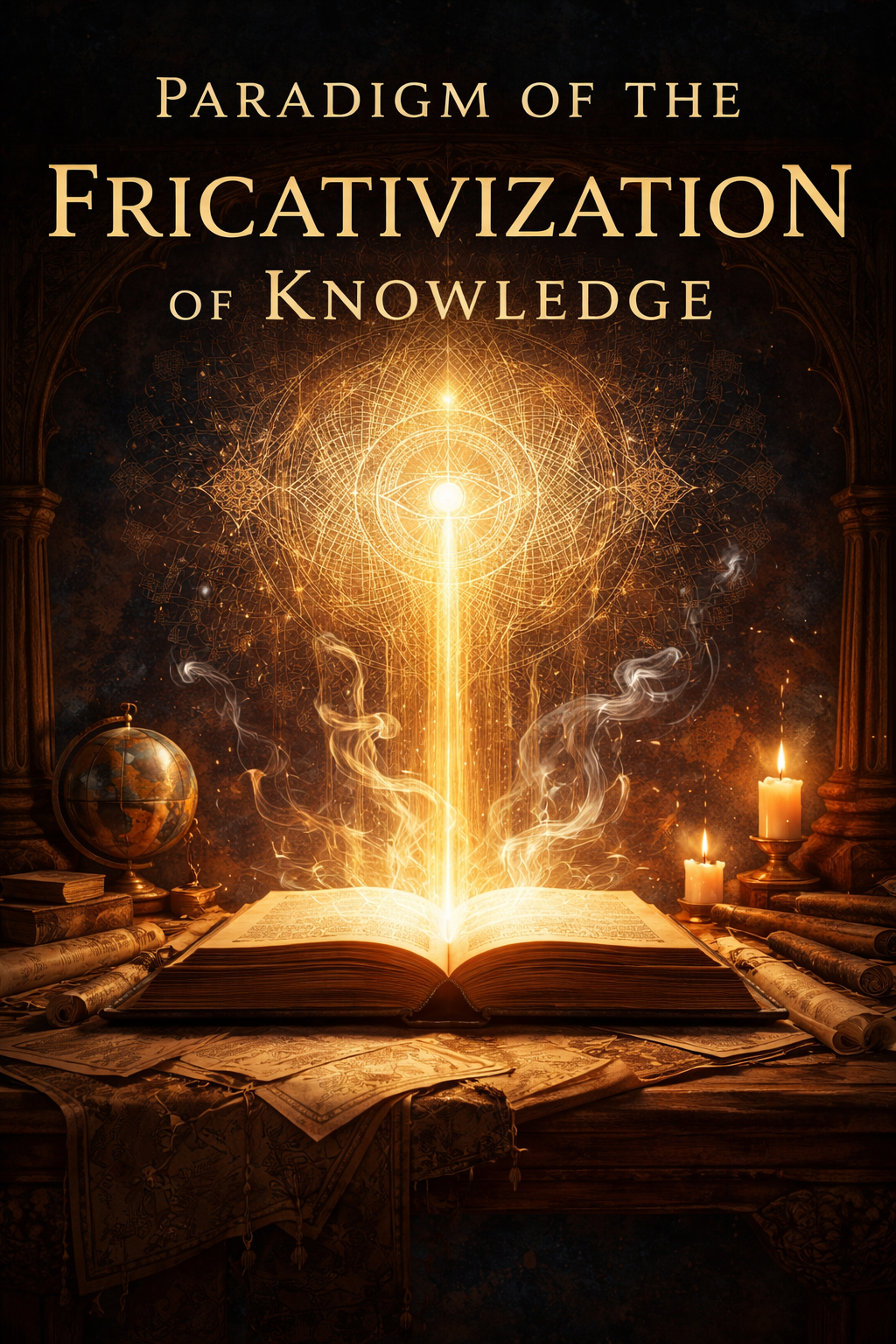
Leave a Reply