Pendahuluan
Fenomena radikalisme telah bertransformasi seiring perkembangan zaman. Pada awal abad ke‑21, wacana radikalisme kerap diasosiasikan dengan jaringan internasional yang bergerak melalui organisasi lintas negara. Seiring kemajuan teknologi informasi, pola penyebaran radikalisme berubah menjadi lebih tersembunyi dan menyusup dalam berbagai ruang kehidupan sosial. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat Indonesia karena paparan informasi mudah ditemukan, tetapi tidak semua konten yang beredar memiliki nilai edukatif. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke‑11 dunia dalam durasi penggunaan internet dengan rata‑rata 7 jam 42 menit sehari serta berada pada posisi ke‑10 untuk penggunaan media sosial dengan durasi 3 jam 18 menit. Tingginya waktu konsumsi media digital ini memperbesar peluang radikalisme untuk merasuki khalayak melalui konten yang dangkal namun menarik.
Radikalisme bukan sekadar gejala keamanan, melainkan cerminan dari kegagalan masyarakat dalam membangun ruang publik yang inklusif dan toleran. Di berbagai daerah, isu radikalisme memicu ketegangan sosial ketika agama dijadikan alat untuk mengukur identitas “kita” dan “mereka”. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi sumber permusuhan ketika tafsir keagamaan dibakukan secara kaku. Kementerian Agama menyadari pentingnya peran moderasi untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Upaya pemerintah terlihat dalam kebijakan penguatan moderasi beragama yang menempatkan komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap keragaman budaya sebagai indikator utama[1]. Melalui pendekatan ini, moderasi dianggap sebagai jalan tengah untuk memadukan ajaran agama dengan nilai keindonesiaan.
Kemajuan teknologi digital memberikan ruang luas bagi radikalisme. Informasi yang dikonsumsi masyarakat cenderung bernilai rendah karena algoritme media sosial mengutamakan konten sensasional sehingga memicu fenomena Fear of Missing Out (FOMO). Ketika konten dangkal mendominasi, kualitas diskursus publik merosot, kemampuan berpikir kritis menurun, dan kecemasan meningkat. Kondisi ini disebut “brain rot”, suatu keadaan ketika fokus, kreativitas, dan pemikiran mendalam terganggu akibat terlalu banyak mengonsumsi konten dangkal. Fenomena brain rot berkaitan erat dengan melemahnya moderasi beragama; orang yang terjebak dalam paparan konten sensasional lebih mudah diprovokasi narasi ekstrem. Karena itu, keseimbangan pola konsumsi informasi dan peningkatan literasi digital menjadi prasyarat menjaga masyarakat tetap rasional.
Moderasi beragama menuntut pendekatan multidimensional yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan negara. Kementerian Agama mendorong setiap lapisan masyarakat terlibat dalam menjaga kebersamaan. Bahkan di tingkat lokal, Kantor Urusan Agama (KUA) didorong untuk mendeteksi potensi konflik dan mengembangkan program kewaspadaan dini[2]. Dengan mendekatkan fungsi deteksi ke level desa, pemerintah berharap ketegangan keagamaan bisa diselesaikan sebelum berkembang menjadi kekerasan. Di samping itu, pemerintah juga membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama yang bertugas mengoordinasikan program moderasi antar kementerian, memantau capaian, dan memberikan evaluasi[3]. Adanya Sekber mencerminkan keseriusan negara dalam menangani radikalisme secara sistemik.
Meski indeks kerukunan beragama nasional meningkat menjadi 76,47 pada 2024[1], kasus intoleransi masih terjadi di beberapa daerah[4]. Angka tersebut menunjukkan bahwa kerukunan relatif stabil, tetapi tidak berarti ancaman radikalisme telah berakhir. Survei-suveri menunjukkan generasi muda cenderung rentan terhadap propaganda ekstremisme karena mereka merupakan digital native yang sering bersentuhan dengan media sosial. Untuk mengatasi problem tersebut, Kementerian Agama merancang buku saku moderasi beragama untuk Generasi Z yang didistribusikan secara digital agar mudah diakses oleh para remaja[5]. Selain itu, pemerintah menyiapkan duta moderasi dari kalangan Gen Z untuk menyuarakan nilai toleransi melalui kanal digital[6]. Inisiatif ini mengingatkan kita bahwa moderasi tidak bisa disosialisasikan dengan cara lama; cara-cara baru harus diterapkan untuk menyapa generasi digital.
Pandangan beragam terhadap praktik keagamaan di ruang publik turut mempengaruhi diskusi moderasi. Artikel perspektif yang menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan salam lintas agama menjelaskan bagaimana Kementerian Agama mempromosikan moderasi sebagai upaya menyeimbangkan keragaman agama dan persatuan nasional. Di satu sisi, ada kelompok yang menolak salam lintas iman karena dianggap bertentangan dengan kemurnian akidah. Di sisi lain, Kementerian Agama melihat salam tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap realitas keberagaman. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kompleksitas moderasi di Indonesia. Moderasi bukan berarti mengaburkan identitas agama, tetapi mengajak masyarakat untuk memahami agama secara lebih luas dan kontekstual.
Para akademisi menekankan perlunya partisipasi aktif setiap komponen bangsa dalam membangun narasi moderat. Studi tentang “brain rot” menegaskan bahwa konsumsi konten dangkal memperlemah kemampuan menganalisis dan cenderung mendorong sikap fanatik. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan agama agar generasi muda mampu memilah informasi dan menolak narasi ekstrem. Seiring waktu, keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada upaya kolektif untuk memadukan kebijakan, edukasi, dan partisipasi masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan radikalisme dan moderasi tidak dapat dilihat secara tunggal. Radikalisme adalah gejala kompleks yang timbul dari ketidakpuasan sosial, keinginan akan identitas yang pasti, serta eksploitasi agama dalam ranah politik. Moderasi, sebaliknya, hadir sebagai strategi yang memadukan nilai-nilai tradisi dengan realitas masa kini. Esai ini akan mengulas lebih jauh evolusi jejaring radikalisme, transformasi pengetahuan agama, kesiapsiagaan menghadapi radikalisme, serta strategi pengentasan berbasis moderasi beragama. Setiap bagian akan menyoroti bagaimana pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat berusaha menavigasi tantangan ini melalui pendekatan yang komprehensif.
Evolusi Jejaring Radikalisme
Konsep jejaring radikal yang dikenal sebagai Tansiq Bayn al‑Jama’ah menggambarkan bagaimana kelompok ekstremis membangun jaringan melalui jalur pekerjaan, pernikahan, pendidikan, kerabat, dan kebetulan. Jaringan ini dirajut sedemikian rupa sehingga identitas pelaku teror tetap tersembunyi sampai terjadi penangkapan atau serangan. Penyusupan ke dalam institusi formal memperlihatkan kecanggihan strategi mereka. Pola ini menunjukkan bahwa radikalisme tidak berkembang secara spontan; ia ditopang oleh struktur sosial yang kompleks. Untuk memahaminya, kita perlu meninjau bagaimana jejaring ini beroperasi dan bagaimana negara meresponsnya melalui kebijakan pencegahan.
Salah satu ciri penting jejaring radikal adalah ketatnya kerahasiaan identitas. Pelaku biasanya menggunakan identitas alternatif dan bahkan memanfaatkan nama palsu untuk menghindari deteksi. Mereka bergerak melalui hubungan kekeluargaan dan perkawinan, sehingga celah keamanan bisa lebih mudah dilalui. Dunia kerja dan lingkungan pendidikan menjadi jalur untuk merekrut simpatisan baru, khususnya ketika individu merasa terpinggirkan atau mencari jati diri. Dalam konteks ini, moderasi agama menghadirkan perspektif seimbang yang menekankan pentingnya membangun komunitas inklusif agar individu tidak merasa terisolasi. Ketika ruang sosial menjadi ramah dan menghargai perbedaan, jejaring radikal kehilangan daya tariknya.
Evolusi jejaring radikalisme juga dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi antarwilayah, sebagaimana dijelaskan dalam konsep Qaidah Aminah. Setiap wilayah memiliki koordinator yang mengatur rekrutmen, pendanaan, dan komunikasi sehingga operasi berjalan efektif. Keberadaan koordinator ini memperlihatkan profesionalisme dalam mengelola jaringan yang tersembunyi. Pola seleksi anggota dilakukan secara cermat agar tidak mudah ditembus oleh aparat keamanan. Di sisi lain, pemerintah mengembangkan model deteksi dini melalui KUA dengan melibatkan penghulu dan penyuluh agama untuk mengawasi dinamika komunitas[2]. Kolaborasi antara aparat, ulama, dan masyarakat lokal diharapkan dapat memotong mata rantai jejaring tersebut.
Peran KUA sebagai garda terdepan pencegahan radikalisme menjadi semakin penting setelah munculnya prakarsa Early Warning System. Sistem ini menempatkan KUA sebagai pusat informasi untuk melaporkan gejala konflik berbasis agama[2]. Dengan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, pemerintah dapat merumuskan langkah cepat sebelum terjadi eskalasi. Pelibatan KUA juga memfasilitasi program moderasi beragama di tingkat desa, karena penghulu dan penyuluh dapat menyampaikan nilai toleransi dalam pernikahan, pendidikan pranikah, dan bimbingan keluarga. Model ini diharapkan mampu mengikis jejaring radikal yang berkembang melalui jalur keluarga dan pernikahan.
Negara menghadapi tantangan serius dalam memutus jejaring radikal yang bersifat lintas wilayah. Keberadaan koordinator di setiap daerah mengharuskan kebijakan pencegahan yang terintegrasi. Pembentukan Sekretariat Bersama moderasi beragama memberikan payung koordinasi antar kementerian, memastikan program pencegahan berjalan sinkron[3]. Sekber tidak hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menyiapkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan[7]. Dengan demikian, upaya menumpas jejaring radikalisme tidak bergantung pada satu lembaga, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif.
Jejaring radikal memanfaatkan celah keterasingan sosial yang dialami individu. Ketika masyarakat kurang merasa diterima, mereka lebih rentan mencari identitas baru melalui kelompok yang menawarkan kejelasan dan solidaritas. Moderasi beragama berusaha merebut ruang tersebut dengan menawarkan narasi keagamaan yang inklusif dan relevan. Para tokoh agama, akademisi, dan aktivis dituntut berkolaborasi untuk membangun jaringan alternatif yang memberikan dukungan sosial. Program pencegahan radikal tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial agar individu merasa terikat dengan komunitas moderat.
Dalam ranah global, jejaring radikal sering terhubung dengan ideologi transnasional. Invasi militer dan konflik di berbagai belahan dunia kerap menjadi sumber inspirasi bagi kelompok ekstrem lokal. Narasi global tersebut disesuaikan dengan konteks lokal untuk memperkuat legitimasi gerakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika internasional penting untuk memprediksi arah baru radikalisme. Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tentang kontra-terorisme dan dialog antaragama menjadi bagian dari strategi memutus aliran ideologi radikal ke dalam negeri.
Secara keseluruhan, evolusi jejaring radikal menuntut respons cerdas dan terukur. Kebijakan harus memanfaatkan data lapangan, memperkuat peran KUA, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Narasi moderasi yang berlandaskan ajaran agama dan nilai kebangsaan diharapkan mampu menyaingi narasi eksklusif yang ditawarkan jaringan radikal. Dengan memadukan pendekatan struktural dan kultural, ruang gerak jejaring radikalisme dapat dipersempit.
Homegrown Terrorism dan Rekrutmen Keluarga
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena homegrown terrorism, di mana proses radikalisasi dan perekrutan dilakukan tanpa kontak langsung dengan jaringan internasional. Individu dapat terekspos konten ekstrem dari media sosial, kemudian secara mandiri mencari jejaring yang lebih dalam. Fenomena ini disebut self‑recruitment; ia memanfaatkan algoritme big data untuk mendeteksi calon simpatisan berdasarkan minat, kata kunci, dan interaksi daring. Kemudahan akses ke materi propaganda menjadikan proses rekrutmen lebih sulit dideteksi oleh aparat. Perubahan pola ini menunjukkan bahwa ancaman radikalisme telah memasuki ranah domestik dengan intensitas tinggi.
Self‑recruitment sering kali berkembang menjadi family recruitment, yaitu perekrutan di dalam lingkungan keluarga. Seseorang yang sudah terpapar ideologi ekstrem lalu membujuk pasangan, anak, atau saudara untuk bergabung. Model ini menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial pertama yang rentan terhadap radikalisasi. Keluarga yang tidak memiliki literasi digital cenderung tidak menyadari perubahan perilaku anggotanya. Dalam konteks ini, Kementerian Agama menekankan peran keluarga sebagai garda terdepan pencegahan. Program model pengentasan radikalisme memasukkan aspek keterlibatan keluarga untuk memperhatikan perubahan perilaku keagamaan dan menyeimbangkan cara berpikir[8]. Pendekatan ini memperkuat penanaman moderasi sejak lingkungan rumah tangga.
Pemanfaatan big data oleh jejaring radikal membuka diskusi tentang etika penggunaan teknologi. Algoritme yang dirancang untuk mempromosikan konten sensasional kerap mengarahkan pengguna ke video, artikel, atau forum yang semakin ekstrem. Studi tentang brain rot menunjukkan bahwa algoritme media sosial memicu konsumsi konten dangkal dan menyebabkan penurunan kemampuan berpikir mendalam. Individu yang terjebak dalam arus ini lebih mudah menerima narasi radikal karena tidak memiliki landasan kritis yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah dan platform digital perlu meningkatkan literasi digital masyarakat, memperbaiki algoritme rekomendasi, dan menandai konten berbahaya untuk melindungi pengguna.
Kementerian Agama merespons fenomena homegrown terrorism dengan inovasi berbasis generasi muda. Buku saku moderasi beragama untuk Gen Z disusun dengan melibatkan perwakilan generasi tersebut agar bahasanya relevan dan mudah dipahami[5]. Buku ini didistribusikan secara digital agar dapat diakses melalui gawai, media sosial, dan aplikasi pesan. Selain itu, Kementerian Agama menyiapkan duta moderasi dari kalangan remaja untuk menyebarkan pesan toleransi di dunia maya[6]. Inisiatif ini diharapkan dapat menyaingi narasi radikal yang marak di media sosial dengan konten moderat yang lebih menarik.
Rekrutmen keluarga memiliki dampak emosional yang kuat karena mengaitkan ideologi dengan rasa cinta dan loyalitas. Keluarga yang terhubung dengan jaringan radikal sering merasa terasing dari masyarakat umum, sehingga menjadi lebih sulit untuk diajak dialog. Oleh karena itu, penanganan homegrown terrorism tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, melainkan memerlukan rehabilitasi sosial dan psikologis. Program deradikalisasi yang melibatkan konseling keluarga, pendidikan agama moderat, dan reintegrasi sosial harus diperkuat. KUA, dengan dukungan penyuluh dan penghulu, dapat berperan memberikan pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme[8].
Homegrown terrorism juga menimbulkan tantangan baru bagi aparat keamanan. Jejaring radikal tidak lagi bergantung pada instruksi dari luar negeri; mereka dapat merencanakan serangan secara independen dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Fenomena ini menuntut koordinasi yang lebih erat antara aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk mendeteksi perubahan perilaku yang mencurigakan. Sekber moderasi beragama menjadi wadah untuk mengoordinasikan berbagai lembaga dalam menghadapi ancaman ini[3]. Keterlibatan masyarakat sipil dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga krusial untuk mempersempit ruang gerak radikalisme.
Kampanye moderasi harus menargetkan lingkungan keluarga sebagai basis perubahan. Penyuluh agama dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk membuat modul pembelajaran yang membahas bahaya radikalisme serta pentingnya toleransi. Pelatihan bagi orang tua tentang literasi digital dan deteksi dini tanda radikalisasi akan membantu mereka mengawasi aktivitas anak di internet. Pada saat yang sama, dukungan psikologis dan sosial perlu disediakan bagi keluarga yang berhasil keluar dari jaringan radikal agar mereka tidak kembali ke lingkungan lama. Upaya ini menciptakan ekosistem perlindungan di tingkat keluarga dan menekan peluang berkembangnya homegrown terrorism.
Secara keseluruhan, fenomena homegrown terrorism menuntut pembaruan strategi pencegahan. Pelibatan keluarga, perbaikan algoritme digital, pembentukan duta moderasi, serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk menahan laju rekrutmen. Dengan memahami dinamika ini, kebijakan dapat dirancang lebih sensitif terhadap perubahan pola rekrutmen dan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi Pengetahuan Agama dan Paradox
Transformasi informasi telah mengubah cara umat memperoleh dan memproduksi pengetahuan agama. Pada masa lalu, pengetahuan keagamaan diperoleh melalui majelis ilmu, pesantren, ataupun rumah ibadah yang dikelola ulama. Kini informasi keagamaan dapat diakses melalui internet, video daring, dan media sosial. Peralihan ini mengubah peran otoritas agama, karena konten dakwah tidak lagi dimonopoli oleh ulama, tetapi juga oleh tokoh populer yang viral. Di satu sisi, demokratisasi informasi memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan agama. Di sisi lain, banyak konten beredar tanpa proses verifikasi yang memadai, sehingga memicu pembacaan literal dan eksklusif. Kementerian Agama menekankan bahwa moderasi tidak berarti mengurangi nilai agama, tetapi menempatkan agama pada konteks sosial yang dinamis.
Perubahan cara pandang masyarakat terhadap agama dipengaruhi oleh perkembangan kecerdasan buatan dan kesadaran digital. Teknologi memungkinkan algoritme untuk menganalisis preferensi individu dan memunculkan konten sesuai minat. Di balik kemudahan itu, ada bahaya bias konfirmasi yang membuat pengguna terperangkap dalam gelembung informasi. Fenomena brain rot menunjukkan bahwa konten yang didesain untuk viral justru menurunkan kualitas berpikir. Ketika orang mengonsumsi konten dangkal, pemahaman mereka tentang agama menjadi superfisial. Mereka lebih mudah diyakinkan oleh argumen sederhana yang emosional, sementara pandangan keagamaan yang kompleks dianggap membingungkan. Untuk itu, literasi digital perlu ditekankan agar masyarakat mampu memilah informasi dan menghindari jebakan algoritme.
Nilai-nilai sosial dan etika juga mengalami pergeseran seiring transformasi informasi. Generasi digital cenderung mengukur kebenaran berdasarkan jumlah “suka” atau pengikut di media sosial. Popularitas menjadi indikator keabsahan sebuah pandangan. Dalam hal keagamaan, fenomena ini melahirkan tokoh baru yang viral di dunia maya tetapi belum tentu memahami kompleksitas sosial budaya. Mereka menawarkan narasi yang mudah dipahami namun simplistis sehingga dapat menimbulkan polarisasi. Keadaan ini dipaparkan dalam presentasi sebagai munculnya “generasi baru pemikir” dan “popularitas sebagai panutan” yang mempengaruhi umat dengan pendekatan baru. Moderasi beragama dihadapkan pada tantangan bagaimana memediasi suara yang beragam tanpa membiarkan narasi ekstrem menguasai ruang digital.
Paradox agama muncul ketika agama semakin sering dibicarakan, tetapi implementasinya dalam kehidupan sehari‑hari justru menurun. Diskusi agama di media sosial kerap terfokus pada perdebatan teologis, sementara praksis sosial dan akhlak mulia diabaikan. Keadaan ini menimbulkan disonansi antara retorika keagamaan dengan perilaku sosial. Fenomena tersebut sejalan dengan observasi para peneliti yang menyatakan bahwa keterpaparan konten dangkal menyebabkan penurunan kemampuan reflektif dan memicu fanatisme. Moderasi beragama berusaha mengembalikan keseimbangan antara ucapan dan tindakan, antara keyakinan dan toleransi, agar agama tidak sekadar menjadi slogan tetapi terwujud dalam kebersamaan sosial.
Dalam konteks produksi pengetahuan, revolusi teknologi menghadirkan tantangan dan peluang sekaligus. Otomatisasi produksi pengetahuan agama dapat mempercepat penyebaran informasi positif, namun juga mempercepat penyebaran informasi menyesatkan. Kementerian Agama merespons dengan mendorong kolaborasi antara ulama, akademisi, dan kreator digital untuk menghasilkan konten moderat yang berkualitas. Buku saku moderasi untuk Gen Z merupakan contoh implementasi di mana konten disusun secara interaktif dan melibatkan generasi muda[5]. Upaya ini menunjukkan bahwa transformasi pengetahuan harus diarahkan pada penguatan literasi dan moderasi, bukan sekadar pada kuantitas informasi.
Meskipun transformasi informasi membawa risiko, potensi positifnya tidak boleh diabaikan. Akses luas terhadap literatur klasik, ceramah ulama moderat, dan dialog antaragama dapat memperkaya wawasan masyarakat. Teknologi juga memungkinkan terjadinya komunitas virtual lintas geografis yang mendukung nilai toleransi. Kementerian Agama terus mendorong pengembangan aplikasi dan platform moderasi agar narasi moderat dapat menjangkau masyarakat luas. Tantangan utama adalah memastikan bahwa konten yang beredar diverifikasi oleh ahli sehingga tidak menyesatkan. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi dan komitmen terhadap moderasi, ekosistem digital dapat menjadi ruang edukasi yang konstruktif.
Pada akhirnya, transformasi pengetahuan agama menuntut adaptasi terus menerus. Peran ulama perlu diperluas sebagai pendidik digital yang mampu membimbing masyarakat. Masyarakat juga dituntut untuk aktif meningkatkan literasi digital dan memandang popularitas dengan kritis. Ketika pengetahuan agama ditransformasi secara sehat, paradox agama yang memisahkan retorika dari praktik dapat dieliminasi. Moderasi beragama hadir untuk mengarahkan transformasi ini menuju harmoni, bukan polarisasi.
Perubahan Sosial Budaya dan Generasi 2000
Presentasi menunjukkan bahwa ranah sosial dan budaya masyarakat mengalami pergeseran signifikan. Produksi kesadaran beragama kini berlangsung di ranah maya yang membentuk identitas baru. Pengalaman keagamaan tidak hanya dibentuk oleh ritual di ruang fisik, tetapi juga oleh interaksi virtual yang melintasi batas geografis. Dalam fenomena ini, istilah “kehidupan planetari” menggambarkan homogenisasi pola pikir global di tengah pergeseran lokal. Masyarakat merasakan perubahan yang cepat, sementara kebijakan publik kerap tertinggal dalam merespons dinamika tersebut. Perubahan ini menuntut adaptasi dari semua pihak agar nilai-nilai agama tetap relevan.
Generasi 2000‑an atau generasi Z tumbuh bersama internet. Mereka merepresentasikan kelompok yang paling akrab dengan teknologi dan media sosial. Pada satu sisi, mereka memiliki potensi besar menjadi agen perubahan. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka juga rentan terpapar ideologi eksklusif. Kementerian Agama menyadari potensi ini dan merancang program yang melibatkan generasi muda, termasuk penerbitan buku saku digital dan pembentukan duta moderasi[5][6]. Dengan melibatkan Gen Z secara aktif, negara berusaha menjadikan mereka sebagai motor moderasi beragama.
Perubahan sosial budaya juga terlihat dalam munculnya pola masyarakat dinamis yang mudah beralih dari satu topik ke topik lain. Media sosial menciptakan budaya “tab next” yang mendorong orang meninggalkan sebuah isu sebelum benar-benar memahaminya. Tuntutan informasi instan membuat refleksi mendalam semakin jarang. Fenomena ini berpotensi membuat masyarakat terpuruk karena tidak memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Moderasi beragama menekankan pentingnya memperlambat ritme konsumsi informasi agar nilai-nilai moral dapat diinternalisasi dengan baik. Pendidikan formal dan non-formal harus kembali menekankan pentingnya berpikir kritis dan mendalam.
Perubahan budaya turut mempengaruhi tanggapan kebijakan. Birokrasi yang lamban sering kali kalah cepat dibanding dinamika yang terjadi di lapangan. Aparat pemerintah cenderung merespons alih-alih berinovasi, sehingga kebijakan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perpres 58/2023 yang membentuk Sekber Moderasi Beragama menjadi contoh upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru[3]. Sekber bertugas merumuskan kebijakan, memantau implementasi, dan melakukan inovasi sosial budaya[7]. Kehadiran lembaga ini menandakan kesadaran negara bahwa kebijakan harus adaptif dan terkoordinasi.
Modernitas membawa dampak baik berupa kemajuan teknologi maupun risiko terkikisnya nilai tradisi. Di tengah perubahan, komunitas lokal memiliki peran penting sebagai penyangga nilai budaya. Budaya lokal yang mengedepankan harmoni, gotong royong, dan musyawarah dapat menjadi modal untuk menolak radikalisme. Kementerian Agama memfasilitasi program-program yang memadukan kearifan lokal dengan nilai moderasi, seperti dialog budaya dan pelatihan pemuda. Ketika nilai lokal dipertahankan dengan cara yang terbuka, masyarakat lebih siap menghadapi arus global yang heterogen.
Perubahan sosial budaya berkaitan erat dengan sistem pendidikan. Kurikulum di sekolah harus menyiapkan generasi muda menghadapi dunia yang terus berubah. Literasi digital, pembelajaran lintas budaya, dan edukasi kewargaan perlu diintegrasikan. Di samping itu, pendidikan agama harus memperkenalkan konsep moderasi sebagai bagian dari pelajaran sehari-hari. Dengan demikian, sekolah menjadi arena utama untuk menanamkan nilai toleransi, analisis kritis, dan kemampuan beradaptasi. Upaya ini penting untuk memastikan generasi mendatang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi perbedaan.
Nilai-nilai keluarga tetap menjadi fondasi dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Keluarga yang kuat mampu menanamkan identitas yang seimbang sehingga anggota keluarganya tidak mudah terbawa arus perubahan negatif. Penyuluh agama dari Kementerian Agama memberikan bimbingan untuk membangun keluarga harmonis yang mengedepankan dialog dan keterbukaan. Model pengentasan radikalisme menekankan keseimbangan antara kesadaran dan cara berpikir dalam kehidupan keluarga[8]. Dengan memadukan tradisi keluarga dan literasi digital, masyarakat dapat memanfaatkan perubahan sosial sebagai peluang untuk memperkuat harmoni.
Pada akhirnya, perubahan sosial budaya dan kemunculan generasi 2000‑an bukanlah ancaman bagi moderasi beragama, tetapi peluang untuk memperbarui cara pandang. Bila generasi muda dilibatkan dalam perumusan program, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaga kerukunan. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan ekosistem yang mendukung generasi ini. Dengan demikian, perubahan sosial budaya dapat diarahkan untuk memperkuat moderasi, bukan memicu radikalisme.
Kesiapsiagaan dan Tantangan Moderasi
Kesiapsiagaan terhadap radikalisme menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aktor. Presentasi menggarisbawahi konsep “blenderisasi agama”, yakni pencampuran elemen agama dalam budaya baru yang multifaset. Fenomena ini menandai transformasi pengalaman keagamaan menjadi lebih beragam dan adaptif, namun juga menimbulkan kebingungan identitas bagi sebagian orang. Moderasi beragama harus mampu membaca perubahan ini dan mengarahkan masyarakat agar memanfaatkan kreativitas budaya tanpa kehilangan nilai inti agama. Di samping itu, persaingan antara berbagai narasi keagamaan menuntut kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Generasi baru pemikir yang populer di media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Mereka sering kali lebih berpengaruh daripada otoritas agama tradisional karena jangkauan digital yang luas. Popularitas sebagai panutan menimbulkan risiko ketika tokoh-tokoh ini tidak memahami konteks sosial budaya dan hanya menyampaikan pandangan sempit. Kementerian Agama merespons tantangan ini dengan memperkuat peran penghulu dan penyuluh agama sebagai pendamping masyarakat[8]. Mereka diberdayakan untuk memberikan bimbingan yang lebih kontekstual, sehingga masyarakat tidak hanya mengikuti influencer, tetapi juga mendapatkan panduan dari tokoh yang berkompeten.
Konflik berbasis kata kunci menjadi fenomena yang melekat pada era media digital. Perdebatan agama di media sosial sering memanfaatkan istilah teologis tanpa pemahaman mendalam. Algoritme platform digital memperbesar jangkauan konten kontroversial sehingga konflik mudah meledak. Studi tentang brain rot menyoroti bahwa kemampuan untuk mencerna informasi kompleks melemah ketika orang terbiasa dengan konten instan. Hal ini membuat diskusi keagamaan sulit mencapai titik temu. Moderasi beragama harus masuk ke ruang tersebut dengan menghadirkan konten edukatif yang menjelaskan makna kata kunci secara kontekstual.
Peran teknologi humanoid atau kecerdasan buatan yang meniru manusia mulai merambah kehidupan keagamaan. Robot atau aplikasi berbasis AI dapat menjawab pertanyaan seputar ibadah dan hukum agama. Meskipun teknologi ini mempermudah akses pengetahuan, ada kekhawatiran bahwa jawaban yang diberikan tidak memperhitungkan konteks lokal. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa konten keagamaan yang diproduksi oleh AI berada di bawah pengawasan pakar. Jika tidak, radikalisme dapat memanfaatkan AI untuk menyebarkan ajaran eksklusif. Tantangan ini menuntut kolaborasi antara ahli teknologi dan ulama untuk memastikan keakuratan dan relevansi konten.
Kesiapsiagaan moderasi juga menuntut pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan misinformasi. Media sosial adalah ladang subur bagi berita palsu, termasuk yang bernuansa agama. Misinformasi dapat memicu kerusuhan apabila dibiarkan tanpa klarifikasi. Kementerian Agama bersinergi dengan berbagai lembaga untuk mengedukasi masyarakat tentang verifikasi informasi. Upaya literasi digital termasuk pelatihan cara memeriksa sumber, verifikasi gambar, dan memahami konteks berita. Masyarakat yang terlatih akan lebih sulit diprovokasi oleh narasi palsu dan lebih waspada terhadap upaya radikalisasi.
Moderasi beragama menghadapi tantangan untuk tetap relevan di era keterbukaan informasi. Publik sering menilai bahwa moderasi terlalu teoritis dan kurang praktis. Oleh sebab itu, diperlukan contoh nyata dari tokoh agama dan pejabat publik yang menunjukkan perilaku toleran dan bijak. Kebijakan pemerintah harus diiringi keteladanan agar masyarakat percaya bahwa moderasi bukan slogan kosong. Selain itu, program moderasi harus menjangkau kalangan marginal yang sering menjadi sasaran radikalisasi. Pendekatan berbasis komunitas diharapkan mampu menampung aspirasi mereka dan mengurangi ketidakpuasan.
Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional juga menjadi pilar kesiapsiagaan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik baik negara lain dalam menangkal radikalisme. Forum internasional tentang dialog antaragama menyediakan wadah untuk bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring moderasi global. Di dalam negeri, Sekber moderasi beragama memastikan sinergi antar lembaga dan menjaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri[3]. Kesiapsiagaan moderasi harus dirancang dengan strategi jangka panjang, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Secara keseluruhan, tantangan moderasi beragama sangat kompleks. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kehadiran negara dalam menyediakan layanan keagamaan yang inklusif, membangun literasi digital, dan memastikan bahwa ruang publik tidak didominasi oleh narasi ekstrem. Kesiapsiagaan yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar masyarakat siap menghadapi perubahan dan menangkal radikalisme.
Strategi Pengentasan Radikalisme
Pengentasan radikalisme memerlukan visi baru kehidupan keagamaan yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya modern. Presentasi menekankan bahwa paradigma baru harus dibangun di atas penghargaan terhadap keragaman dan upaya terus menerus untuk merawat harmoni. Paradigma tersebut mencakup pemaknaan ulang konflik, di mana perbedaan pandangan tidak lagi dianggap ancaman, tetapi kesempatan untuk belajar. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi kerangka yang memandang konflik sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Dengan merumuskan visi yang berpihak pada nilai kemanusiaan, masyarakat dapat melepaskan diri dari narasi radikal yang memecah belah.
Rekayasa sosial dan pikiran menjadi strategi yang diperlukan untuk menuntun generasi baru. Program pembelajaran harus dirancang untuk mendorong cara berpikir kritis, empatik, dan kreatif. Kementerian Agama melalui penyuluh agama terus mengadakan bimbingan kepada masyarakat, terutama di tingkat desa[8]. Melalui bimbingan tersebut, masyarakat diperkenalkan pada cara menghadapi perbedaan tanpa menghilangkan identitas keagamaan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya literasi digital yang menekankan pentingnya memilah informasi dan menghindari konten menyesatkan. Dengan demikian, rekayasa pikiran bukanlah indoktrinasi, tetapi pendidikan yang membebaskan.
Pemaknaan ulang konflik juga memerlukan perspektif global mind dan konsep one world. Masyarakat diminta memahami bahwa tantangan keagamaan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika global. Konflik di berbagai negara dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat melalui media sosial. Mengadopsi perspektif global memungkinkan kita melihat persamaan nilai kemanusiaan yang melintasi batas agama. Oleh karena itu, dialog internasional perlu diperkuat untuk memperkaya wawasan dan mengidentifikasi strategi pemecahan konflik yang adaptif. Indonesia dapat menawarkan model moderasi yang berakar pada nilai lokal sekaligus terbuka terhadap inovasi global.
Strategi pengelolaan konflik memerlukan dasar etika, nilai, dan moralitas baru sebagai fondasi jangka panjang. Etika baru ini menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Nilai tersebut dipadukan dengan ajaran agama yang mengutamakan kasih sayang dan toleransi. Pemerintah mendorong peran tokoh agama untuk menegaskan kembali nilai-nilai ini melalui khotbah, pengajian, dan media sosial. Di tingkat kebijakan, Sekber moderasi beragama memastikan agar program-program pemerintah menyentuh seluruh aspek masyarakat[7]. Kolaborasi antara etika keagamaan dan kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung resolusi konflik.
Peran pengambil kebijakan tidak bisa diabaikan. Mereka harus berpikir strategis dan berorientasi masa depan. Perpres 58/2023 memberikan dasar hukum bagi pembentukan Sekber yang mengoordinasikan seluruh program moderasi[3]. Melalui koordinasi ini, kebijakan tidak tumpang tindih dan sumber daya dialokasikan dengan efektif. Selain itu, pengambil kebijakan perlu memperhatikan evaluasi berkala untuk memastikan program moderasi beragama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan menjadi kunci agar masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan.
Keterlibatan keluarga menjadi aspek sentral dalam strategi pengentasan radikalisme. Model pengentasan menekankan perlunya keluarga memerhatikan perubahan tingkah laku anggota keluarga yang berkaitan dengan agama[8]. Keseimbangan antara kesadaran dan cara berpikir harus diciptakan agar keluarga tidak menjadi tempat berkembangnya paham ekstrem. Penyuluh agama memberikan panduan cara berdialog di dalam keluarga, mengajarkan toleransi, dan mengedukasi tentang bahaya takfirisme. Ketika keluarga berperan aktif, potensi radikalisasi dapat ditekan sejak awal.
Strategi pengentasan juga mencakup penguatan media sosial engagement. Kesadaran untuk tidak menjadikan media sosial sebagai pintu menuju takfir ditekankan dalam presentasi. Ini berarti setiap pengguna harus waspada terhadap konten provokatif, melakukan verifikasi, dan berpartisipasi dalam menyebarkan pesan positif. Pemerintah bekerja sama dengan platform digital untuk menandai konten berbahaya dan menyediakan fasilitas pelaporan. Selain itu, program edukasi bagi influencer dan kreator konten diarahkan untuk mempromosikan moderasi. Ketika narasi moderat mendominasi media sosial, pengaruh radikalisme dapat dipatahkan.
Pada akhirnya, strategi pengentasan radikalisme membutuhkan sinergi antara visi, rekayasa sosial, pemaknaan ulang, pengelolaan konflik, peran kebijakan, keterlibatan keluarga, dan adaptasi media sosial. Kesuksesan strategi ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Ketika strategi dijalankan secara terintegrasi, harapan untuk menciptakan Indonesia yang damai dan toleran semakin besar.
Kesimpulan
Radikalisme dan moderasi beragama adalah dua sisi mata uang yang menggambarkan dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia. Radikalisme muncul dari ketegangan identitas, ketidakpuasan sosial, serta pengaruh ideologi global yang menyusup melalui jejaring sosial. Moderasi beragama hadir sebagai respons yang mencoba menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan nilai kebangsaan. Esai ini telah meninjau berbagai aspek radikalisme mulai dari evolusi jejaring hingga homegrown terrorism, serta perubahan pengetahuan agama dan sosial budaya yang mempengaruhinya. Dengan memahami dinamika tersebut, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi radikalisme.
Data menunjukkan bahwa penggunaan internet yang tinggi membuka peluang tersebarnya konten radikal, sementara fenomena brain rot memperlemah kemampuan masyarakat dalam mencerna informasi. Di sisi lain, indeks kerukunan beragama yang meningkat memberi optimisme bahwa moderasi beragama mulai mengakar[1]. Meski demikian, kasus intoleransi yang masih terjadi menandakan pekerjaan rumah belum selesai[4]. Upaya pencegahan melalui KUA, Sekber, buku saku digital, dan penguatan literasi digital merupakan langkah konkret yang membutuhkan dukungan luas[2][3]. Dengan sinergi antar lembaga, narasi radikal dapat dikalahkan oleh narasi moderat yang konstruktif.
Strategi pengentasan radikalisme harus memperhatikan realitas masyarakat yang sangat majemuk. Pendekatan yang terlalu top‑down tanpa pelibatan komunitas akan gagal menjangkau akar masalah. Sebaliknya, program yang melibatkan keluarga, generasi muda, dan tokoh lokal terbukti lebih efektif. Kementerian Agama menyadari hal ini dengan melibatkan penghulu, penyuluh, dan duta moderasi dalam pelaksanaan kebijakan[8][6]. Upaya ini harus diimbangi dengan kebijakan publik yang adaptif dan terkoordinasi oleh Sekber[7]. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan moderasi.
Transformasi sosial dan digital mendorong perubahan cara masyarakat memahami dan mempraktikkan agama. Paradox agama menampakkan bagaimana diskusi keagamaan di ruang publik sering jauh dari implementasi. Oleh karena itu, moderasi menuntut pembelajaran berkelanjutan, literasi digital, dan pengelolaan konflik yang beretika. Jika semua pihak konsisten menjunjung nilai kasih sayang, keadilan, dan keterbukaan, maka moderasi dapat menjadi pilar yang kokoh dalam menghadapi ekstremisme. Kebijakan moderasi harus disertai dengan keteladanan dari para pemimpin agama dan pemerintah agar masyarakat melihat contoh nyata.
Dalam kerangka global, tantangan radikalisme yang dihadapi Indonesia tidak terpisah dari dinamika internasional. Interaksi dengan negara lain dan keterlibatan dalam forum global memperkaya wawasan tentang cara menangani ekstremisme. Indonesia dapat mengambil contoh baik dari negara lain sambil mempertahankan kearifan lokal yang mendukung moderasi. Kolaborasi internasional ini sejalan dengan konsep pemaknaan ulang konflik dan “one world” yang menempatkan seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, moderasi beragama juga menjadi kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.
Akhirnya, keberhasilan mengatasi radikalisme bergantung pada komitmen bersama. Pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat harus terus merawat dialog, membangun kepercayaan, dan memperkuat literasi digital. Perubahan generasi dan kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup diri, tetapi justru momentum memperkuat nilai moderasi. Kesadaran kolektif bahwa kebinekaan adalah rahmat akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang harmonis.
Esai ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya slogan, tetapi agenda nyata yang harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami kompleksitas radikalisme dan menerapkan strategi yang menyeluruh, Indonesia mampu menjaga persatuan dan menghadirkan keteladanan bagi dunia.
[1] [4] Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47
https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs
[2] [8] Kemenag Percepat Penerapan Early Warning System Potensi Konflik, Ini Strateginya
[3] [7] Kemenag: Perpres 58/2023 Wujudkan Moderasi Beragama Kian Kuat dan Kolaboratif
[5] [6] Kemenag Susun Buku Saku Moderasi Beragama bagi Gen-Z
https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-buku-saku-moderasi-beragama-bagi-gen-z-1lMSO

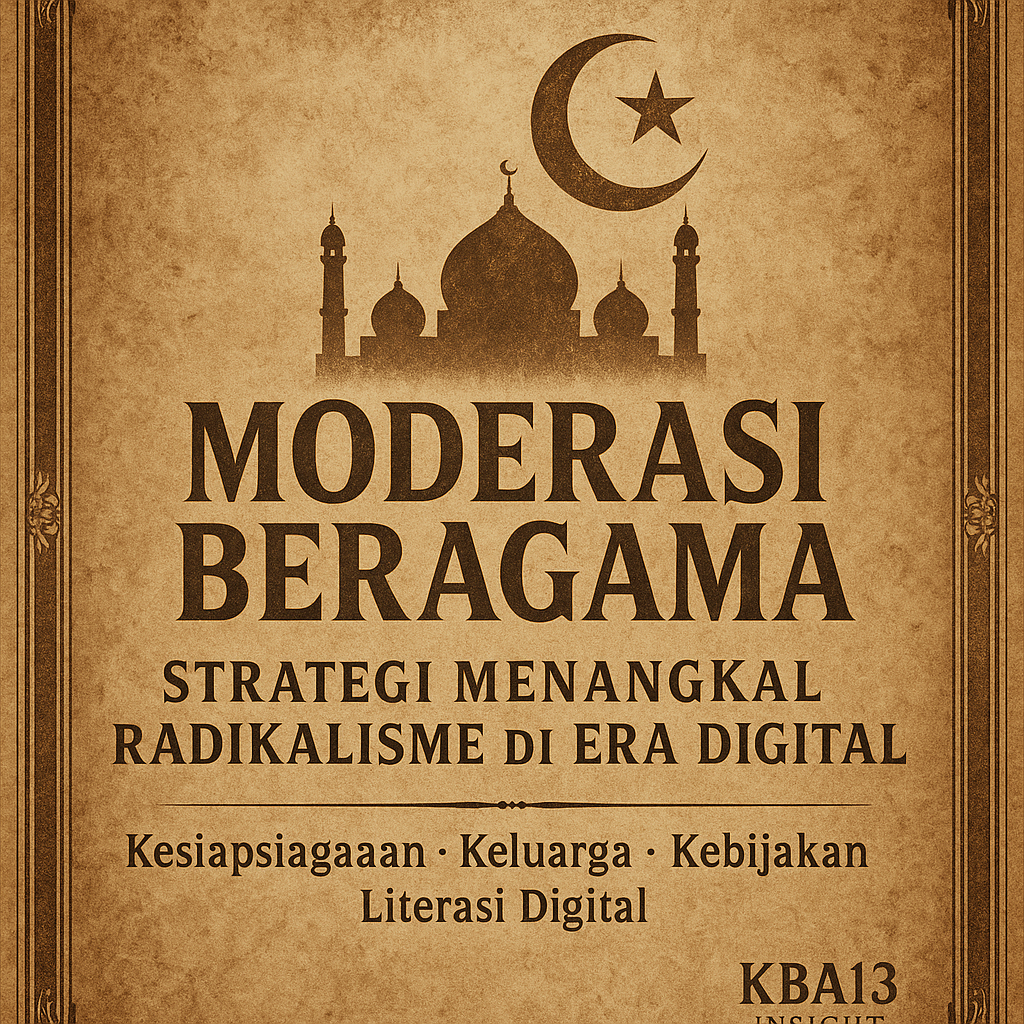

Leave a Reply