Pendahuluan
Dua dekade sudah Aceh menikmati udara damai setelah penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam peringatan 20 tahun damai, diskursus mengenai sejarah, peran tokoh, serta warisan intelektual perjuangan Aceh kembali mengemuka. Salah satu karya penting yang patut dibaca dalam konteks ini adalah buku Dari Rimba Aceh ke Stockholm karya Dr. Husaini M. Hasan, Sp.OG.
Buku ini bukan sekadar catatan pribadi, tetapi juga sebuah jendela untuk memahami dinamika politik, militer, dan diplomasi Aceh sejak era perjuangan bersenjata hingga panggung internasional. Ia menghadirkan kisah dari rimba belantara Aceh ke pusat diplomasi dunia, serta menggambarkan kedekatan penulis dengan Tengku Hasan Muhammad di Tiro, proklamator Aceh Merdeka.
Jejak Memoar: Dari Rimba Aceh hingga Diplomasi Global
Isi buku ini terbagi dalam 40 bab, mulai dari masa kecil Husaini Hasan, pengalaman mendampingi Hasan Tiro di rimba Aceh, hingga perjalanan diplomasi internasional di Swedia, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat.
Beberapa momen penting yang direkam, antara lain: Salah satu bagian paling dramatis dalam buku Dari Rimba Aceh ke Stockholm adalah kisah penyergapan Alue Beureunè pada tahun 1983. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah konflik Aceh, ketika pasukan GAM yang tengah bergerak di wilayah Pidie disergap oleh aparat keamanan Indonesia. Menurut catatan Husaini Hasan, penyergapan ini menimbulkan korban yang sangat besar, baik dari sisi pejuang maupun masyarakat sipil yang terjebak dalam operasi militer.
Penyergapan ini bukan hanya insiden militer, tetapi juga peristiwa politik yang menandai kerasnya respons negara terhadap gerakan separatis Aceh pada masa Orde Baru. Ia meninggalkan luka kolektif yang masih dirasakan hingga kini. Narasi dalam buku ini memperlihatkan detail penderitaan yang dialami para pejuang di hutan belantara, mulai dari keterbatasan logistik, kondisi fisik yang lemah, hingga tekanan psikologis akibat pengejaran yang terus-menerus. Dalam konteks 20 tahun damai, penyergapan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian yang dinikmati sekarang dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh generasi sebelumnya.
Pasca-penyergapan Alue Beureunè, para pejuang GAM yang selamat harus melakukan perjalanan panjang yang dikenal sebagai “Long March”. Husaini Hasan menggambarkan bagaimana perjalanan itu bukan sekadar mobilisasi militer, tetapi sebuah ujian daya tahan fisik, mental, dan spiritual. Para pejuang harus menembus rimba, melewati sungai, mendaki gunung, bahkan menahan lapar dan sakit dalam kondisi yang serba terbatas.
Long March ini menunjukkan dimensi kemanusiaan dari perjuangan bersenjata. Di balik narasi heroik, ada kisah kelelahan, pengkhianatan, kehilangan kawan seperjuangan, serta keteguhan iman. Bagi generasi Aceh hari ini, kisah Long March bukan hanya cerita perang, melainkan refleksi tentang ketahanan menghadapi kesulitan. Sebagaimana Aceh mampu bertahan melewati konflik, gempa, tsunami, dan kini memasuki era damai, kisah Long March memberi pelajaran bahwa daya tahan adalah modal utama membangun masa depan.
Salah satu kekuatan terbesar buku ini adalah penuturan mengenai diplomasi Aceh di luar negeri, terutama setelah Hasan di Tiro menetap di Swedia. Husaini Hasan menceritakan dengan detail bagaimana perjuangan Aceh tidak berhenti di hutan, melainkan berlanjut di ruang diplomasi internasional.
Swedia menjadi markas penting karena memberi suaka politik kepada Hasan di Tiro, yang memungkinkan gerakan Aceh memiliki basis aman untuk mengorganisasi diri. Terdapat jaringan diaspora Aceh, termasuk pendirian Australian Achehnese Association yang menjadi corong perjuangan di benua lain. Tidak hanya di Eropa, diskusi tentang Aceh juga menembus Washington, melalui audiensi dengan akademisi, politisi, hingga organisasi HAM internasional.
Diplomasi ini menunjukkan bahwa perjuangan Aceh bersifat glokal—berakar pada penderitaan lokal, tetapi mencari legitimasi di forum global. Pada masa damai hari ini, narasi diplomasi ini memberi pesan bahwa Aceh harus tetap hadir di panggung internasional, bukan lagi dengan isu separatisme, tetapi dengan agenda pembangunan, budaya, dan perdamaian.
Buku ini juga mengulas fase sulit yang jarang diungkap, yakni fragmentasi internal GAM yang dikenal dengan istilah GAM Pecah I dan II. Perpecahan ini bukan sekadar pertikaian personal, tetapi mencerminkan kompleksitas politik perlawanan. Sebagian faksi berbeda pandangan mengenai strategi, arah perjuangan, bahkan cara mengelola sumber daya perjuangan.
Fragmentasi ini menjadi tantangan besar bagi Hasan di Tiro dan para loyalisnya, termasuk Husaini Hasan, yang harus menjaga agar perjuangan tetap solid di mata dunia internasional. Dalam kerangka 20 tahun damai, fragmentasi internal GAM memberi pelajaran penting: bahwa persatuan politik Aceh adalah syarat utama untuk menjaga stabilitas pasca-konflik. Sayangnya, hingga kini dinamika politik lokal masih sering memperlihatkan polarisasi, terutama menjelang kontestasi Pilkada atau pembahasan soal Dana Otsus. Buku ini mengingatkan, bahwa sejarah perpecahan internal harus dijadikan pelajaran, bukan diulang kembali.
Program Pembangunan Aceh: Refleksi Pasca-Perjuangan
Yang menarik dari buku ini adalah bahwa Husaini Hasan tidak berhenti pada narasi perjuangan bersenjata dan diplomasi. Ia juga menuliskan gagasan tentang program pembangunan Aceh sebagai refleksi atas cita-cita yang diperjuangkan. Baginya, kemerdekaan atau perdamaian tidak ada artinya jika rakyat Aceh tetap miskin, tertinggal, dan terpinggirkan.
Program pembangunan yang digagasnya menekankan pada pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia menilai bahwa rakyat Aceh harus diberi akses yang adil terhadap sumber daya alam, sekaligus mendapatkan ruang untuk mengelola sendiri potensi daerahnya. Pandangan ini terasa relevan hingga kini, ketika Aceh menghadapi problem ketergantungan pada Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.
Dalam momentum 20 tahun damai, gagasan Husaini Hasan dapat dibaca ulang sebagai sebuah visi: bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan juga hadirnya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Buku ini dengan demikian menjadi semacam dokumen politik-intelektual yang menyeberangkan Aceh dari masa perang menuju masa pembangunan.
Lebih dari sekadar dokumentasi, buku ini memperlihatkan hubungan emosional dan strategis antara Husaini Hasan dan Hasan di Tiro. Hasan Tiro bahkan menulis:
“Dr. Husaini adalah kiriman Tuhan untukku. Ia punya kesetiaan dan keteguhan yang luar biasa, nilai yang paling penting bagi seorang pejuang dan tentara sekelas Napoleon.”
(The Price of Freedom, 1984).
Membaca Buku dalam Konteks 20 Tahun Damai Aceh
Kini, ketika Aceh memperingati 20 tahun damai, buku ini memberi refleksi mendalam. MoU Helsinki 2005 memang berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang telah menelan korban jiwa lebih dari 15.000 orang (data Komnas HAM, 2003). Namun, damai bukan hanya soal berhentinya peluru. Damai juga menuntut rekonsiliasi, pembangunan berkeadilan, dan pengakuan terhadap sejarah panjang perjuangan.
Buku Dari Rimba Aceh ke Stockholm menegaskan bahwa akar perjuangan Aceh bukan sekadar romantisme bersenjata, melainkan juga cita-cita politik dan keadilan sosial. Dalam perjalanan 20 tahun damai, banyak agenda yang masih menjadi PR bersama:
-
Keadilan ekonomi: Dana Otonomi Khusus Aceh yang mencapai Rp 214 triliun (2008–2023) sering dikritik tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
-
Pengelolaan sumber daya alam: Bagi hasil migas yang diatur dalam UUPA masih memunculkan perdebatan implementasi.
-
Rekonsiliasi sejarah: Generasi muda Aceh sering kali hanya mengenal damai tanpa memahami akar konflik.
Di sinilah pentingnya membaca memoar seperti karya Husaini Hasan. Ia menghadirkan pengalaman langsung, yang jika ditafsirkan ulang dalam kerangka kekinian, menjadi pelajaran berharga untuk menjaga perdamaian.
Warisan Intelektual dan Relevansi Buku
Buku ini bukan hanya memoar personal, melainkan juga bagian dari literasi politik Aceh. Dari sisi akademik, ia memperkaya kajian tentang gerakan perlawanan lokal, politik identitas, dan proses perdamaian internasional. Dari sisi publik, buku ini memberi narasi alternatif terhadap sejarah resmi negara, membuka ruang bagi pembaca untuk melihat Aceh dari kacamata para pelaku sejarah.
Membaca Dari Rimba Aceh ke Stockholm pada 20 tahun damai adalah sebuah ajakan untuk tidak melupakan masa lalu, tetapi juga tidak terjebak di dalamnya. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa damai adalah ruang untuk membangun cita-cita yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Penutup
Perdamaian Aceh hari ini adalah buah dari perjalanan panjang yang salah satunya direkam dengan baik dalam buku ini. Husaini Hasan berhasil membawa kita menelusuri lorong-lorong sejarah Aceh dari hutan ke diplomasi, dari peluru ke pena, dari konflik menuju damai.
Pada momen 20 tahun damai Aceh, membaca buku ini ibarat jejak intelektual—sebuah penghormatan kepada mereka yang telah berkorban, dan sekaligus pengingat bahwa perdamaian harus terus dirawat.


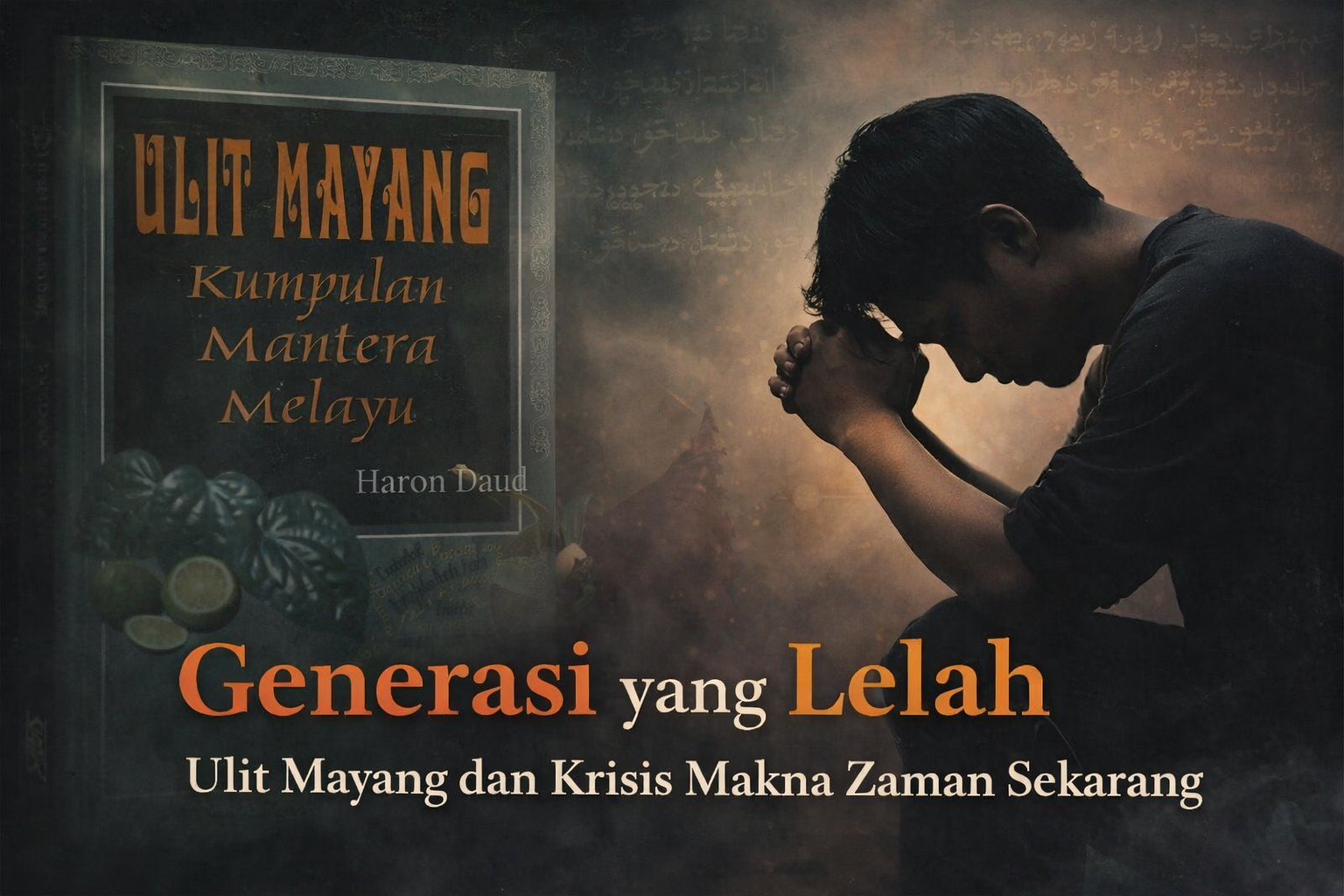




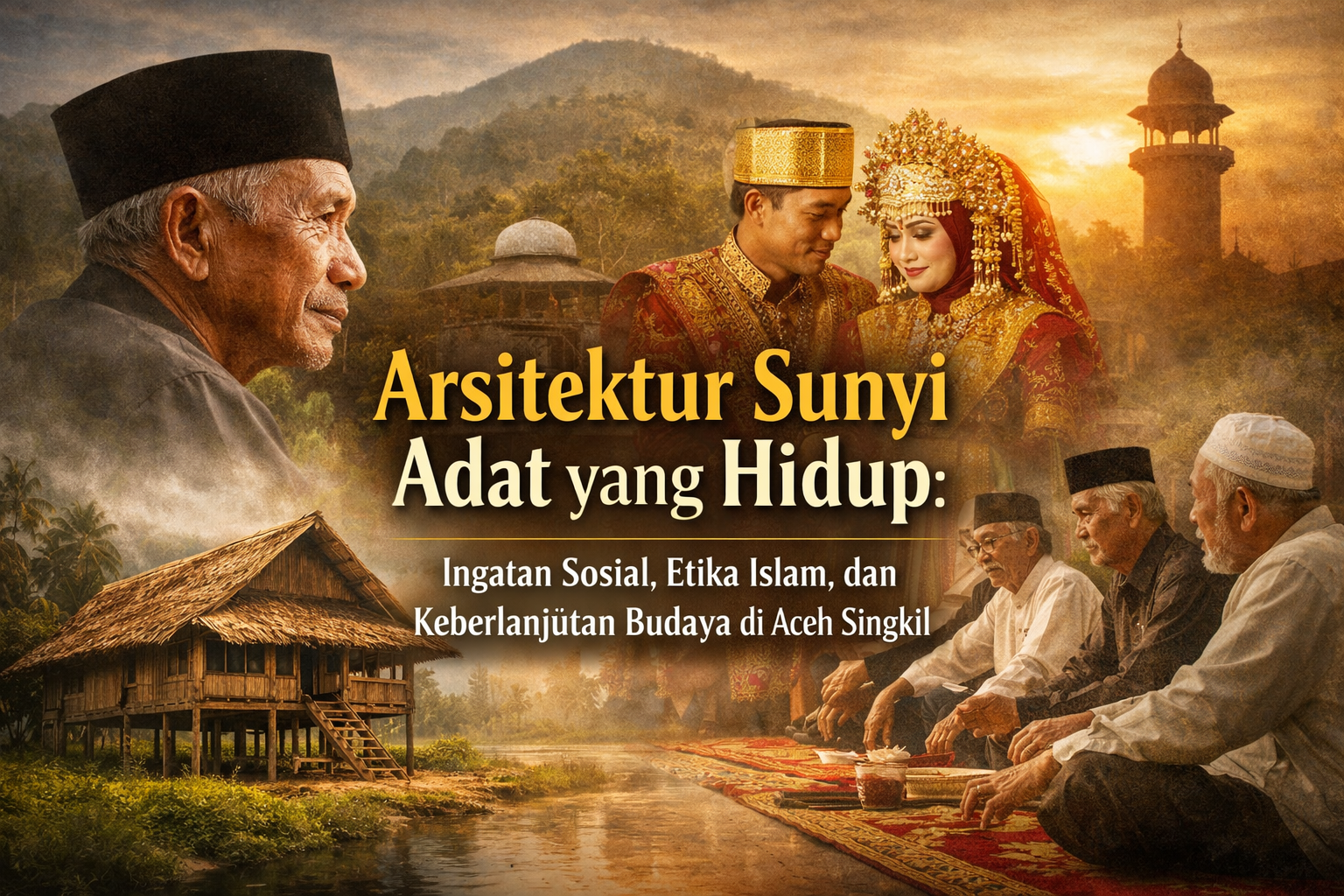
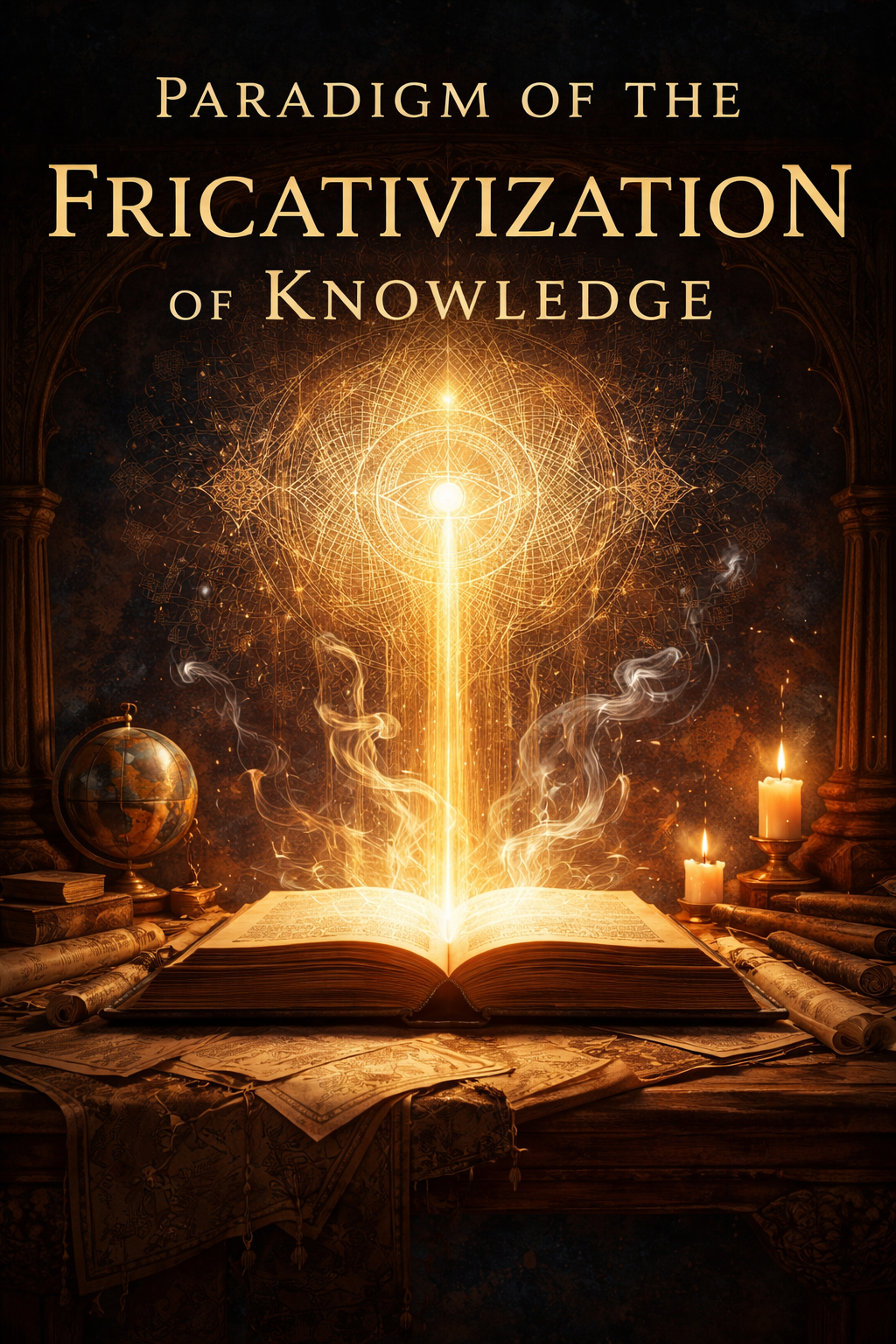
Leave a Reply