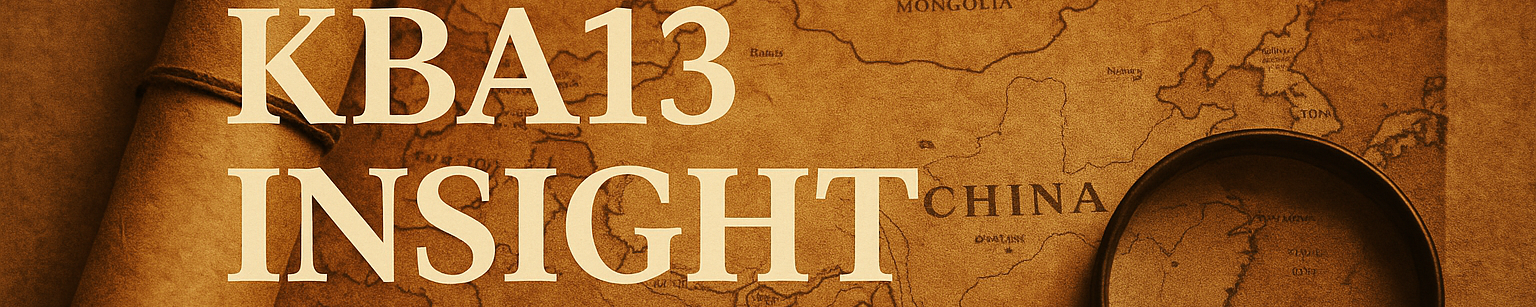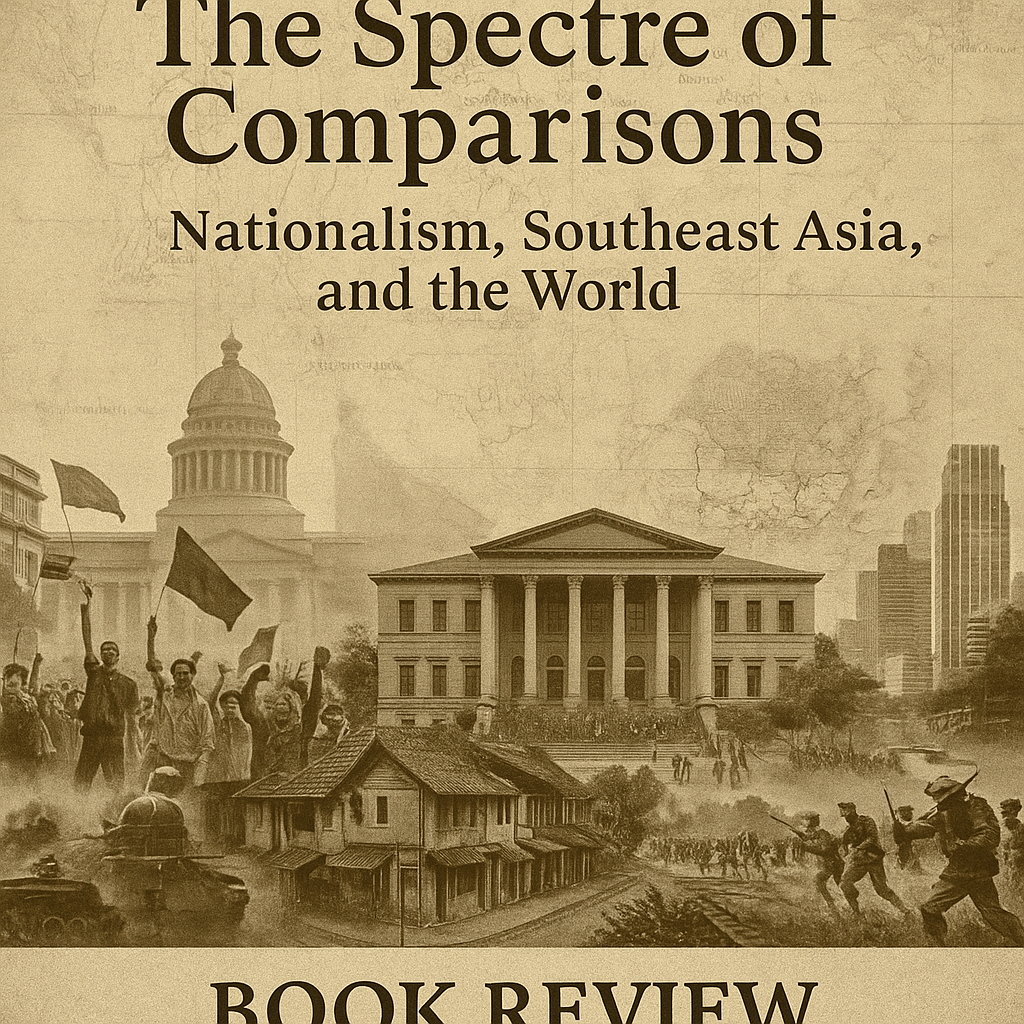Pendahuluan
Keluarga merupakan institusi sosial fundamental yang mengalami transformasi signifikan di era kontemporer. Perkembangan teknologi informasi, perubahan ekonomi, serta penetrasi budaya populer telah membawa dinamika baru dalam hubungan keluarga modern. Jika dahulu keluarga cenderung diidentikkan dengan peran tradisional – ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengasuh utama – kini konfigurasi peran tersebut semakin beragam. Muncul fenomena kakek-nenek yang mengambil alih pengasuhan cucu, ibu rumah tangga yang merambah ranah publik, hingga ayah yang dituntut lebih terlibat dalam urusan domestik. Di sisi lain, revolusi digital menjadikan teknologi informasi dan media sosial bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga, memblur batas antara ruang privat dan publik. Aktivitas yang dulu dianggap personal, seperti mendidik anak atau interaksi sehari-hari, kini kerap dipertontonkan di ranah online. Hal ini memunculkan isu-isu baru terkait privasi, etika sosial, dan perlindungan hukum keluarga di era digital.
Perubahan-perubahan tersebut menuntut kajian mendalam karena berdampak pada pembentukan identitas anggota keluarga, pola asuh, kualitas relasi orang tua-anak, hingga stabilitas institusi perkawinan itu sendiri. Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren meningkat; pada tahun 2021 tercatat 447.743 kasus perceraian (naik 53,5% dari 2020) dan menariknya sekitar 75% gugatan cerai diajukan oleh istri[1][2]. Data ini mengindikasikan adanya pergeseran dinamika kekeluargaan, di mana perempuan semakin berani mengambil keputusan keluar dari pernikahan yang dianggap tidak memuaskan. Fakta ini sejalan dengan konsep post-modern family, yaitu keluarga pasca-modern yang ditandai keragaman bentuk dan instabilitas lebih tinggi dibanding keluarga tradisional. Para sosiolog post-modern berpendapat bahwa dalam masyarakat kontemporer tidak ada lagi satu tipe keluarga yang dominan (seperti keluarga inti konvensional); sebaliknya terdapat pluralitas bentuk keluarga, sehingga generalisasi tentang fungsi keluarga sulit dilakukan[3]. Pilihan individual yang lebih bebas – didorong oleh fragmentasi sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi – menghasilkan berbagai pola keluarga: mulai dari meningkatnya lajang dan cohabiting, keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga sambung (stepfamilies), hingga keluarga lintas budaya[4].
Bertolak dari konteks di atas, makalah ini akan mengkaji isu-isu kontemporer dalam relasi keluarga modern. Pembahasan mencakup pergeseran peran dalam keluarga (termasuk peran kakek-nenek, ayah, dan ibu), adaptasi keluarga terhadap teknologi informasi, pergeseran ruang privat menjadi ruang publik melalui media sosial, perubahan relasi orang tua-anak di era digital, fenomena post-modern family, serta pengaruh ekonomi dan budaya populer terhadap kehidupan keluarga. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan-tantangan baru dalam hukum keluarga dan relasi kekeluargaan, sekaligus merumuskan implikasi etis maupun rekomendasi untuk merespons dinamika tersebut.
Pergeseran Peran Keluarga: Kakek-Nenek, Ibu, dan Ayah
Struktur keluarga Indonesia dewasa ini menunjukkan kecenderungan pergantian peran yang cukup mencolok. Keterlibatan kakek dan nenek dalam pengasuhan anak meningkat seiring perubahan pola keluarga modern. Penelitian Retno dkk. (2022) menemukan bahwa pengasuhan oleh kakek-nenek marak terjadi di Indonesia karena berbagai faktor, seperti perceraian orang tua, masalah kesehatan mental ibu (depresi), kematian orang tua, hingga faktor ekonomi yang memaksa orang tua bekerja sebagai tenaga kerja migran[5]. Dengan kata lain, kakek-nenek kerap menjadi pengasuh utama saat orang tua berhalangan hadir secara penuh. Keterlibatan aktif kakek-nenek dalam mendidik dan merawat cucu dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak[6]. Bahkan, beberapa studi menunjukkan peran kakek-nenek mampu membentuk kepribadian dan spiritualitas anak, terutama ketika mereka tinggal bersama sejak kecil[7][8]. Namun demikian, pola asuh “grandparenting” tidak lepas dari tantangan. Gaya pengasuhan kakek-nenek cenderung lebih permisif dan memanjakan, yang dapat berimbas negatif pada sosialisasi anak. Haryani dkk. (2022) melaporkan bahwa pola asuh permisif oleh kakek/nenek dapat menyebabkan anak menarik diri dan mengalami kesulitan bergaul dengan teman sebaya[9]. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan kakek-nenek mengenai pengasuhan optimal – misalnya melalui pelibatan mereka dalam program parenting – agar hubungan dengan cucu lebih baik dan perkembangan anak tetap optimal[10][11].
Peran ibu dalam keluarga kontemporer juga mengalami transformasi. Ibu tidak lagi semata-mata berperan sebagai pengurus rumah tangga, melainkan semakin banyak yang berkarir atau beraktivitas di ruang publik. Fenomena “dari ibu rumah tangga ke arena publik” menggambarkan mobilitas sosial perempuan yang meningkat, didukung oleh akses pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, muncul istilah parentsfluencer atau ibu yang menjadi figur publik di media sosial karena rutin berbagi konten seputar parenting, gaya hidup, maupun aktivitas keluarganya. Hal ini terkait dengan gejala sharenting (share + parenting) yang marak dewasa ini, yaitu praktik orang tua – umumnya ibu – membagikan konten digital tentang anak-anak mereka di media sosial[12]. Motif di balik sharenting sering kali berangkat dari niat baik: orang tua ingin berbagi kebahagiaan dan kebanggaan atas putra-putrinya. Namun, banyak orang tua tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut terhadap privasi dan jejak digital sang anak[13][14]. Foto atau video lucu anak yang diunggah hari ini bisa saja disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab, dan kelak ketika si anak beranjak dewasa, ia mungkin merasa risih karena dokumentasi masa kecilnya tersebar luas tanpa persetujuannya[15]. Oleh sebab itu, para pakar menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua agar bijak sebelum mengunggah sesuatu tentang anak di ranah publik digital[16][17]. Hak anak atas privasi perlu dihormati, dan orang tua idealnya meminta izin anak (jika sudah cukup usia) sebelum membagikan konten mengenai dirinya[18].
Sementara itu, peran ayah dalam keluarga modern mendapat sorotan tersendiri. Stereotip ayah sebagai breadwinner (pencari nafkah) semata mulai bergeser menuju figur ayah yang lebih terlibat dalam pengasuhan. Studi Mutiah dkk. (2025) mengungkap adanya perubahan paradigma peran ayah pasca diikutsertakannya para ayah dalam program “Sekolah Ayah”. Sebelum mengikuti program, banyak ayah berpegang pada konstruksi gender tradisional – merasa tugasnya cukup mencari uang dan disiplin keras kepada anak[19][20]. Seorang ayah partisipan mengaku, “Ah, udahlah saya mah mencari uang saja,” yang mencerminkan anggapan bahwa tanggung jawab pengasuhan adalah domain ibu[19]. Pola asuh yang diterapkan pun cenderung otoriter, misalnya keyakinan bahwa tanpa teriakan atau hukuman tegas, anak tidak akan patuh[20]. Namun setelah mengikuti Sekolah Ayah, terjadi transformasi pola pikir dan perilaku. Para ayah mulai mengadopsi pendekatan pengasuhan lebih demokratis dan empatik. Mereka menyadari bahwa ayah pun harus menunjukkan kelembutan dan kedekatan emosional dengan anak, tidak melulu keras[21]. Dalam wawancara, seorang ayah menceritakan kini ia rutin memeluk anaknya untuk menenangkan ketika anak dimarahi ibu, sesuatu yang sebelumnya jarang dilakukan[22]. Para ayah juga meningkat keterlibatannya dalam tugas domestik dan pendidikan anak: ada yang berbagi tugas mencuci piring dan baju dengan istri[23], hadir dalam rapat sekolah anak[24], serta terlibat dalam pengambilan keputusan bersama mengenai pengasuhan (misal membatasi waktu bermain gadget anak)[25]. Perubahan ini tidak hanya mempererat hubungan ayah-anak, tetapi juga menciptakan dinamika rumah tangga lebih seimbang dan mengurangi beban yang sebelumnya hanya dipikul ibu[26][23]. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wulan dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa kehadiran ayah yang aktif dalam pengasuhan berperan besar menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal[27][28]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran ayah di era modern berkembang menjadi lebih dari sekadar pencari nafkah; ayah diharapkan berperan sebagai pendidik, pengasuh, dan partner setara bagi ibu dalam mengelola rumah tangga.
Adaptasi Keluarga terhadap Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah pola interaksi dalam keluarga secara drastis. Munculnya internet, smartphone, dan media sosial menciptakan keluarga digital di mana komunikasi virtual melengkapi – bahkan kadang menggantikan – interaksi tatap muka. Studi Prasanti (2016) menunjukkan bahwa perubahan teknologi informasi memengaruhi cara hidup, cara beradaptasi, dan pola komunikasi keluarga di era digital[29]. Ketersediaan smartphone dan konektivitas internet yang masif memungkinkan anggota keluarga untuk selalu terhubung kapan pun dan di mana pun. Hal ini membawa dampak dua sisi: di satu pihak komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, di pihak lain muncul pola interaksi baru yang lebih individualistis. Penelitian Undip (2018) melaporkan bahwa penetrasi teknologi informasi dalam keluarga digital menghasilkan model kehidupan berprinsip lebih individualis dan ekonomis, serta dapat menciptakan “kehidupan yang kesepian di tengah keramaian”[30]. Paradoks ini terjadi ketika masing-masing anggota keluarga sibuk dengan gadget dan dunianya sendiri meski secara fisik berada dalam satu rumah. Psikolog anak Anna Surti Ariani mengingatkan bahwa orang tua maupun anak kini banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial dan bermain gadget, yang mengurangi waktu kebersamaan mereka[31]. Dengan kata lain, kualitas interaksi langsung antaranggota keluarga rentan menurun akibat distraksi perangkat digital.
Pengaruh TIK terhadap hubungan orang tua-anak juga menjadi perhatian. Chatlina dkk. (2024) dalam tinjauan pustakanya menyimpulkan bahwa penggunaan gawai dan teknologi canggih membawa dampak kompleks bagi kualitas hubungan sosial keluarga[32]. Ada dampak positif, misalnya peningkatan literasi digital pada orang tua dan anak, serta kemudahan berkomunikasi jarak jauh. Banyak keluarga merasakan manfaat teknologi untuk mempertahankan kelekatan ketika terpisah geografis – misalnya melalui video call antara anak dan orang tua yang bekerja di luar negeri, atau grup keluarga di aplikasi pesan yang menjaga intensitas komunikasi lintas generasi. Namun, dampak negatifnya juga signifikan: penggunaan TIK secara berlebihan dapat melemahkan interaksi sosial langsung dan memicu berbagai problem, seperti kecanduan screen time, menurunnya empati, hingga konflik akibat konten digital. Oleh sebab itu, literasi digital dipandang krusial. Orang tua perlu memahami pengaruh TIK terhadap kualitas hubungan dalam keluarga, sementara anak perlu dibimbing penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab[33]. Kerja sama antara keluarga dan institusi pendidikan penting untuk meningkatkan literasi digital anak, sekaligus menetapkan batasan yang wajar dalam penggunaan gawai[34][35]. Dengan strategi demikian, keluarga dapat memetik manfaat teknologi tanpa mengorbankan keharmonisan relasi antaranggota.
Salah satu wujud adaptasi keluarga terhadap teknologi adalah menjamurnya komunikasi virtual dalam keseharian. Hubungan virtual dalam berkeluarga tampak pada kebiasaan mengirim pesan instan antaranggota rumah meski berada di lokasi sama, interaksi lewat media sosial, hingga kehadiran smart home yang mengatur aktivitas domestik secara otomatis. Fenomena ini tentu memengaruhi dinamika emosional keluarga. Di satu sisi, tersedia sarana ekspresi dan koordinasi yang efisien (misalnya orang tua bisa memantau keberadaan anak remajanya melalui aplikasi, atau pasangan suami istri bertukar pesan mesra di tengah kesibukan kerja). Namun di sisi lain, ada kekhawatiran “keakraban semu” – keluarga merasa terhubung lewat layar, padahal kualitas kebersamaan nyata menurun. Nuruddin (2018) menyebut masyarakat kini memasuki era super-highway society, di mana komunikasi serba cepat namun rentan mengikis kedalaman interaksi[36]. Peningkatan intensitas komunikasi virtual harus diimbangi dengan menjaga kualitas quality time tanpa perangkat, misalnya dengan disiplin waktu bebas gawai saat jam keluarga, agar hubungan emosional tetap terpelihara.
Ruang Privat Menjadi Ruang Publik: Media Sosial dan Eksposur Keluarga
Perkembangan media sosial telah mengubah konsep ruang privat dalam keluarga. Dahulu, urusan keluarga dianggap wilayah pribadi yang hanya layak diketahui oleh kalangan sendiri. Namun kini, banyak keluarga secara sukarela memublikasikan kehidupan sehari-harinya ke hadapan khalayak luas melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Ngonten (membuat konten) keluarga menjadi tren populer, mulai dari vlog keseharian, tantangan bersama keluarga, hingga siaran langsung (live) aktivitas di rumah. Keluarga tidak lagi sekadar unit domestik, melainkan bisa bertransformasi menjadi public figure di dunia maya.
Tren vlog keluarga di YouTube merupakan contoh konkret bagaimana ruang privat berubah menjadi lahan publik dan bahkan ladang bisnis[37][38]. Konten vlog bergenre kehidupan keluarga semakin digemari audiens karena dianggap autentik dan menghibur semua kalangan[39]. Di Amerika Serikat terdapat keluarga “Shaytards” dengan jutaan pengikut, sedangkan di Indonesia fenomena Gen Halilintar menjadi pionir vlog keluarga sukses (12 juta lebih pelanggan). Menariknya, popularitas vlog keluarga bisa menghasilkan pendapatan yang menggiurkan. Sebagian orang tua vlogger bahkan meninggalkan pekerjaan kantoran karena mendapat cukup pemasukan dari iklan YouTube, kerja sama dengan merek, hingga penjualan merchandise[40]. Bagi mereka, membuat konten bersama anak-anak yang masih balita tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendatangkan kompensasi finansial. Namun, di balik tampilan ramah anak dan ceria, terdapat konsekuensi serius yang perlu dicermati.
Persoalan privasi anak menjadi isu utama dalam vlog keluarga. Ketika keluarga menjadikan kehidupan sehari-harinya sebagai tontonan publik harian, informasi pribadi anak – wajah, nama, kegemaran, kebiasaan – terekspos dan mudah diakses oleh siapa saja[41]. Meskipun YouTube kini memiliki kebijakan menonaktifkan kolom komentar pada kanal yang menampilkan anak di bawah umur, hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Publik tetap dapat menilai dan mengomentari kehidupan si anak melalui platform lain, atau sekadar menyimpannya untuk konsumsi sendiri. Orang asing pun dapat dengan mudah mengetahui lokasi rumah, sekolah anak, atau rutinitasnya dari petunjuk-petunjuk yang muncul di video. Ini jelas menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan psikis anak.
Selain itu, keharusan terus-menerus memproduksi konten demi menjaga popularitas menghadirkan tantangan etis tersendiri. Orang tua yang menjadikan vlogging sebagai pekerjaan penuh waktu harus senantiasa mencari ide baru dan menarik untuk disuguhkan ke penonton[42]. Tak jarang, demi konten yang dianggap lucu atau “viral”, orang tua mungkin melewati batas kenyamanan anak. Kasus ekstrem di kanal DaddyOFive (AS) menunjukkan bagaimana konten prank orang tua terhadap anak – yang melibatkan teriakan dan perlakuan kasar demi tontonan – berujung petaka: penonton melaporkan ke pihak berwenang hingga orang tua tersebut kehilangan hak asuh atas dua anaknya[43]. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa eksploitasi anak demi konten adalah bahaya nyata.
Dari perspektif hukum, anak-anak yang tampil dalam konten keluarga di media sosial berada pada area abu-abu. Secara legal, belum ada aturan tegas yang melindungi anak dalam konteks user-generated content. Aturan perburuhan untuk pekerja anak (misalnya larangan jam kerja berlebihan bagi aktor cilik) tidak berlaku dalam lingkungan informal seperti YouTube atau Instagram[44]. Akibatnya, anak vlogger tidak memiliki perlindungan jelas terkait jam keterlibatan, bagi hasil pendapatan, atau hak untuk berhenti tampil. Semua bergantung pada kebijakan orang tua. Padahal, potensi dampak jangka panjangnya tidak kecil: tekanan psikologis, hilangnya privasi masa kecil, hingga rekam jejak digital yang bisa memengaruhi kehidupan dewasanya. Orang tua yang menjalankan vlog keluarga perlu mempertimbangkan dengan serius moralitas dan psikologi anak ke depan[45]. Misalnya, pantaskah momen anak sedang sakit dibawa ke IG Live demi konten? Atau apakah nanti si anak akan senang melihat video dirinya menangis tantrum ditonton jutaan orang?[45]. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menuntut kepekaan etis orang tua vlogger.
Fenomena ibu curhat di media sosial juga menggambarkan bergesernya ruang privat menjadi konsumsi publik. Tidak sedikit istri atau ibu rumah tangga yang kini membuka masalah rumah tangganya di Facebook, Instagram, atau forum online. Mereka mungkin menceritakan konflik dengan suami, pertengkaran dengan mertua, kesulitan ekonomi keluarga, hingga kekecewaan pribadi, kepada khalayak dunia maya. Menurut Widdiya (2024), hal-hal yang dulu tabu dibicarakan di luar keluarga kini justru diumbar secara luas oleh para istri di media sosial[46]. Misalnya, seorang istri menulis status tentang suaminya yang berselingkuh atau keluhan tentang sikap keluarga pasangan. Fenomena ini bisa dipahami sebagai kebutuhan meluapkan emosi dan mencari dukungan psikologis dari lingkungan luar, mengingat tekanan hidup modern yang makin kompleks[47]. Namun, para pakar mengingatkan bahwa tindakan tersebut ibarat “membuka aib keluarga di depan umum”[48]. Dampak buruknya, privasi keluarga terlanggar dan masalah tidak terselesaikan dengan semestinya. Curhat di media sosial cenderung hanya menjadi pelarian sementara yang justru mengundang komentar nyinyir netizen[49], alih-alih solusi konstruktif. Ada ungkapan, “aib pasangan itu layaknya pakaian, membukanya di depan umum sama dengan menanggalkan busana di keramaian”[48] – ini menegaskan bahwa masalah internal seharusnya disalurkan ke pihak yang tepat (misal konselor, tokoh agama, atau langsung kepada Tuhan sesuai keyakinan) ketimbang dipublikasikan. Dari sudut pandang hukum keluarga, fenomena ini bisa merusak reputasi dan kehormatan keluarga, bahkan berpotensi menjadi bukti/pemicu konflik hukum (misal gugatan perceraian atau pencemaran nama baik). Oleh karenanya, etika penggunaan media sosial dalam mengungkap masalah pribadi menjadi diskursus penting. Harus ada kesadaran bahwa tidak semua hal pantas untuk “ditayang”-kan, apalagi menyangkut orang lain dalam keluarga yang mungkin tidak setuju masalahnya dipublikasikan.
Transformasi ruang privat ke ruang publik melalui media sosial menuntut etiket digital baru dalam keluarga. Unknown ethics atau norma-norma baru yang belum terumuskan jelas kerap muncul, misalnya: apakah wajar orang tua memasang CCTV dan menyiarkan aktivitas rumah 24 jam? Sejauh mana foto anak boleh diunggah tanpa melanggar hak anak? Bagaimana menjaga digital footprint keluarga agar tidak disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih mencari jawabannya seiring perkembangan teknologi. Satu hal yang mulai disepakati adalah perlunya digital parenting – orang tua mengedukasi diri tentang risiko dunia maya dan menetapkan aturan keluarga dalam bermedia sosial. Misalnya, sejumlah orang tua kini menerapkan aturan tidak mengunggah wajah anak secara frontal (hanya dari samping/belakang) untuk melindungi identitasnya. Ada pula yang rutin mengecek privacy settings akun keluarga, atau tidak membagikan lokasi real-time demi keamanan. Semua upaya ini merupakan adaptasi keluarga untuk tetap menjaga area privat di tengah derasnya arus publisitas digital.
Relasi Orang Tua dan Anak di Era Digital
Perkembangan teknologi dan perubahan sosial turut menggeser pola hubungan antara orang tua dan anak. Relasi orang tua-anak di era digital dicirikan dengan komunikasi dua arah yang lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya, namun juga menghadapi tantangan baru seperti kesenjangan digital (digital divide) dan perbedaan pemahaman nilai akibat pengaruh media luar.
Salah satu perubahan nyata adalah dalam arena sosial anak-anak. Dahulu, dunia sosial anak terutama dibentuk oleh interaksi di lingkungan sekitar – bermain dengan tetangga, teman sekolah, atau sepupu saat acara keluarga. Kini, anak-anak memiliki “dunia kedua” di ranah online. Relasi sosial anak-anak tidak lagi terbatas pada teman fisik; mereka bisa terhubung dengan gamer sebaya di belahan dunia lain, atau berinteraksi melalui komentar di kanal YouTube idola mereka. Media sosial, game online, dan platform digital menjadi ruang sosialisasi baru. Orang tua generasi sekarang dihadapkan pada tugas memantau pergaulan anak yang tak kasatmata di dunia maya, di samping pergaulan nyata mereka. Tinjauan di Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi (2024) menekankan bahwa penggunaan TIK oleh anak dapat memengaruhi pola perilaku dan interaksi sosialnya, baik positif maupun negatif[50]. Positifnya, anak melek teknologi cenderung lebih piawai mengakses informasi dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Negatifnya, anak bisa kehilangan beberapa keterampilan sosial dasar jika lebih banyak berkomunikasi lewat layar ketimbang tatap muka – misalnya kemampuan membaca ekspresi wajah, empati langsung, atau negosiasi konflik secara sehat.
Konsep me time dan staycation juga menarik dibahas dalam konteks relasi keluarga modern. Me time (waktu untuk diri sendiri) menjadi istilah populer yang menandakan pentingnya individu, termasuk orang tua, mengambil jeda dari rutinitas keluarga untuk merawat kesehatan mentalnya. Hal ini positif untuk mencegah stres, tetapi perlu diimbangi agar tidak mengurangi perhatian kepada anak. Sementara staycation – liburan di rumah atau di dalam kota – marak dipilih keluarga milenial sebagai alternatif liburan tradisional. Staycation biasanya melibatkan seluruh keluarga menikmati waktu berkualitas bersama tanpa harus bepergian jauh. Tren ini muncul selain karena alasan ekonomi, juga karena kemudahan teknologi (bisa work from home sambil liburan, hiburan tersedia via streaming, dll.). Baik me time maupun staycation mencerminkan upaya keluarga masa kini mencari keseimbangan antara kebersamaan dan kebutuhan individual.
Dalam ranah pendidikan dan pembentukan identitas anak, media sosial berperan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial menyediakan model pembelajaran dan inspirasi baru. Banyak anak dan remaja belajar keterampilan dari YouTube (misal memasak, bermain musik, DIY kerajinan) yang mungkin tidak diajarkan di sekolah atau oleh orang tuanya. Mereka juga menemukan role model idola di internet – bisa dalam sosok edukreator, atlet, musisi, atau selebritas dengan citra positif – yang memotivasi mereka berprestasi. Namun di sisi lain, banjirnya konten kesuksesan instan di media sosial memengaruhi mentalitas generasi muda. Terdapat keinginan untuk cepat sukses (terlihat dari banyaknya anak bercita-cita menjadi YouTuber atau Selebgram demi uang)[51]. Budaya instan ini bisa membuat anak kurang menghargai proses dan kerja keras bertahap. Selain itu, anak-anak terpapar standar hidup glamor para influencer yang kadang tidak realistis, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif berlebihan atau frustrasi jika tak tercapai.
Media sosial juga dapat memicu perilaku agresif pada anak dan remaja. Konten kekerasan atau ujaran kebencian yang tersebar bebas dapat ditiru, terutama bila anak belum dibekali filter moral kuat. Sebaliknya, ada pula fenomena Baper Society – generasi yang mudah “bawa perasaan” atau tersinggung. Penelitian Jawa Pos (2025) menyebut Gen Z dianggap lebih sensitif dibanding generasi sebelumnya, dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial[52]. Media sosial sering menampilkan versi ideal kehidupan yang memicu ekspektasi tidak realistis dan rasa insecure di kalangan remaja[53]. Akibatnya, mereka gampang merasa kurang percaya diri atau cemas jika hidupnya tidak seindah orang lain di dunia maya. Generasi ini juga kerap dijuluki “generasi stroberi” – mudah rapuh dan menghindari masalah[54], yang sebagian penyebabnya adalah lingkungan media sosial serba instan dan penuh validasi semu (like, komentar). Untuk mengatasi kecenderungan mudah baper, pakar menyarankan peningkatan literasi digital dan pendampingan orang tua dalam memaknai konten online[55]. Remaja perlu diajak memahami bahwa apa yang tampak di media sosial seringkali merupakan highlight reel kehidupan orang lain, bukan realitas sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak mudah iri atau rendah diri, dan mampu bersikap selektif terhadap opini netizen.
Relasi orang tua-anak masa kini juga mengalami negosiasi ulang dalam hal kontrol dan kepercayaan. Orang tua dihadapkan pada dilema antara memberi kebebasan eksplorasi di era terbuka, dengan tanggung jawab melindungi anak dari paparan negatif. Misalnya, banyak orang tua sekarang berusaha bersikap lebih open-minded terhadap pandangan dan pilihan anak (termasuk soal pendidikan, hobi, bahkan karier non-konvensional seperti content creator). Generasi muda cenderung menuntut otonomi lebih besar dan ruang untuk mengekspresikan diri. Pola asuh demokratis pun semakin diadopsi, di mana orang tua berperan sebagai mitra diskusi daripada figur otoritarian. Hal ini selaras dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya attachment yang sehat – hubungan emosional orang tua-anak yang hangat dan suportif.
Namun, pada beberapa kasus terjadi pembalikan peran: anak-anak yang memberi teladan digital bagi orang tua. Generasi yang lebih tua (termasuk orang tua atau kakek-nenek) acapkali gagap teknologi, sehingga anak-anak atau cucu justru menjadi mentor dalam penggunaan smartphone, media sosial, dll.[56]. Interaksi ini memperlihatkan potensi positif komunikasi lintas generasi, di mana terjadi saling belajar. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa cucu yang mengajarkan kakek-neneknya memakai teknologi dapat mempererat ikatan mereka dan meningkatkan rasa harga diri lansia karena mampu mengikuti perkembangan zaman[56]. Bagi keluarga Indonesia, hal serupa tampak dari fenomena orang tua bergabung dengan WhatsApp/Facebook berkat bantuan anak, atau kakek-nenek melakukan video call dengan kerabat jauh difasilitasi cucu. Meski demikian, generasi lebih tua kerap mengeluhkan “anak sekarang susah dinasihati dan lebih senang main HP”. Di sinilah diperlukan keseimbangan: teknologi harus jadi alat yang mempererat relasi keluarga, bukan penghalang komunikasi. Orang tua perlu proaktif terlibat dalam dunia digital anak (misal mengetahui aplikasi apa yang mereka pakai, menonton konten YouTube favorit anak bersama-sama) agar tercipta pemahaman bersama.
Pengaruh Ekonomi dan Budaya Populer terhadap Keluarga
Dinamikanya, perubahan ekonomi dan arus budaya populer global turut membentuk wajah keluarga kontemporer. Dari sisi ekonomi, gaya hidup modern yang serba cepat telah memengaruhi kebiasaan domestik keluarga. Contoh paling nyata adalah pergeseran dari memasak ke membeli. Jika pada generasi terdahulu memasak dan makan bersama keluarga setiap hari adalah suatu kewajaran – sekaligus momen bonding – kini semakin banyak keluarga urban yang mengandalkan layanan pesan-antar makanan atau makanan siap saji. Menurut laporan GrabFood tahun 2021, 72% keluarga Indonesia menggunakan layanan pesan-antar makanan online, dan keluarga dengan anak merupakan konsumen utama layanan tersebut[57][58]. Sebanyak 82% keluarga muda dengan anak dilaporkan memesan makanan online lebih dari 8 kali sebulan karena keterbatasan waktu untuk memasak[59]. Tren ini diperkuat selama pandemi COVID-19 ketika pilihan beraktivitas di rumah meningkat. Konsekuensinya, tradisi memasak di rumah menjadi berkurang dan aktivitas dapur sebagai pusat interaksi keluarga menurun. Bagi sebagian keluarga, hal ini efisien dan membuka kesempatan lebih banyak waktu untuk hal lain. Namun bagi yang lain, hilangnya kebiasaan memasak bersama mungkin berarti hilangnya salah satu sarana transfer nilai dan kebersamaan lintas generasi (misalnya resep turun-temurun nenek tidak lagi dipraktikkan cucu). Studi RRI (2019) menyebutkan bahwa di tengah gaya hidup modern nan sibuk, menemukan waktu untuk masak dan makan bersama keluarga menjadi tantangan[60]. Padahal, makan bersama diyakini para ahli sebagai salah satu faktor penguat keharmonisan dan komunikasi keluarga. Oleh karena itu, meski ekonomi memberikan kemudahan dalam bentuk jasa kuliner instan, keluarga dianjurkan tetap meluangkan waktu untuk sesekali memasak atau duduk makan bersama guna menjaga ikatan interpersonal.
Faktor ekonomi juga mendorong munculnya post-modern family dalam arti bentuk-bentuk keluarga non-tradisional. Tuntutan ekonomi sering memaksa anggota keluarga tinggal terpisah (misal salah satu orang tua kerja di luar negeri), membentuk rumah tangga transnational. Tekanan ekonomi pula yang kerap menjadi pemicu konflik rumah tangga dan perceraian – data BPS menunjukkan perselisihan dipicu problem ekonomi menempati salah satu faktor utama perceraian di Indonesia[61][62]. Implikasinya, banyak anak tumbuh dalam pola keluarga baru, entah itu keluarga orang tua tunggal, keluarga dengan ayah/ibu tiri, atau diasuh keluarga besar. Hal ini menantang hukum keluarga konvensional dalam hal pengaturan hak asuh, nafkah, dan waris, karena struktur yang tidak lagi homogam (satu ayah satu ibu kandung). Maka, urgensi penyesuaian regulasi muncul – misalnya seruan Menteri Agama agar UU Perkawinan direvisi untuk mengantisipasi tingginya perceraian dan melindungi kepentingan anak pascacerai[63].
Di samping ekonomi, budaya populer (pop culture) memiliki pengaruh besar pada keluarga, terutama generasi muda di dalamnya. Generasi milenial dan Gen Z tumbuh di tengah arus globalisasi budaya: gempuran musik, film, fashion, dan tren global yang diakses seketika melalui internet. Budaya populer membentuk nilai, gaya hidup, hingga cara pandang generasi ini terhadap keluarga. Kompasiana (2024) mencatat bahwa pengaruh budaya populer terhadap Gen Z mencakup pembentukan identitas, nilai sosial, konsumerisme, hingga cara berkomunikasi[64].
Dalam hal pembentukan identitas, remaja sering menggunakan elemen budaya pop untuk mengekspresikan diri. Contohnya, demam K-Pop melanda remaja di seluruh dunia termasuk Indonesia. Musik dan idol K-Pop memengaruhi gaya berpakaian, gaya rambut, bahkan bahasa gaul anak muda[65]. Banyak K-Pop stans (penggemar fanatik) mengidentifikasi diri mereka dengan grup idol tertentu dan mengadopsi nilai-nilai yang dipromosikan idolanya. Ini menunjukkan budaya pop menjadi alat bagi remaja mencari jati diri dan merasakan kebersamaan dengan komunitas lebih luas[66]. Dampaknya di keluarga, orang tua harus memahami referensi budaya anak agar terjalin komunikasi. Tak jarang, terjadi benturan ketika selera atau nilai budaya populer anak berbeda dengan nilai yang diharapkan orang tua. Misalnya soal cara berpakaian modis vs kesopanan lokal, kebiasaan maraton drama sampai larut malam, dsb. Di sinilah diperlukan dialog antar generasi – orang tua belajar apresiasi budaya pop yang disukai anak, sementara anak belajar kritis dan bijak dalam mengonsumsinya.
Budaya populer juga menggeser nilai dan pandangan sosial generasi muda. Konten film, serial, atau influencer sering mengangkat isu inklusivitas, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberagaman[67]. Generasi Z cenderung lebih terbuka dan progresif dibanding generasi sebelumnya karena paparan narasi beragam tadi. Misalnya, serial TV seperti 13 Reasons Why atau Euphoria yang mengangkat isu kesehatan mental, bullying, identitas seksual, berhasil memantik diskusi di kalangan remaja dan mengurangi stigma terhadap topik-topik tersebut[68]. Banyak remaja menjadi lebih empatik dan sadar masalah sosial berkat konten hiburan yang bermuatan pesan. Selain itu, influencer media sosial yang vokal tentang body positivity, lingkungan, atau anti-rasisme turut membentuk nilai-nilai Gen Z[69]. Figur seperti Lizzo dengan kampanye penerimaan tubuh, Gretha Thunberg dengan aktivisme lingkungan, atau content creator lokal yang mengedukasi soal kesehatan mental, menjadi panutan baru bagi remaja. Bagi keluarga, perubahan nilai ini berarti anak mungkin memiliki pendapat yang lebih kritis dan berbeda dari orang tua mengenai berbagai isu (contoh: anak mendukung kesetaraan gender secara penuh, sementara orang tua masih berpandangan tradisional). Konflik nilai semacam ini perlu dikelola dengan komunikasi terbuka. Orang tua sebaiknya menghargai kemajuan positif (misal anak jadi peduli lingkungan atau toleran terhadap perbedaan), sambil memberikan bimbingan agar tidak terjerumus pengaruh negatif (misal konsumerisme akut atau perilaku menyimpang yang juga bisa muncul dari budaya pop).
Selanjutnya, budaya populer mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan keluarga modern. Iklan dan tren global menciptakan standar baru tentang “keluarga bahagia” yang sering diukur secara material: rumah nyaman bergaya minimalis, kendaraan pribadi terbaru, liburan rutin ke destinasi eksotis, dan seterusnya. Media sosial memperparah tekanan ini dengan ajang pamer (show off) pencapaian atau kepemilikan. Banyak keluarga merasa perlu “keeping up with the Joneses” versi digital – misalnya, ketika melihat teman di media sosial selalu mengunggah foto liburan, keluarga lain jadi terdorong melakukan hal serupa agar tak ketinggalan. Hal ini dapat memacu semangat kerja keras, tapi juga rentan menimbulkan stres finansial dan kompetisi tidak sehat. Art of reputation di media sosial membuat keluarga-keluarga berlomba menampilkan citra paling ideal, meski realitasnya mungkin tidak seindah itu. Tantangan bagi keluarga adalah tetap berpijak pada nilai-nilai internal dan kebahagiaan nyata, bukan terobsesi mengejar validasi publik. Pop culture seharusnya difilter sebagai hiburan dan sarana kreativitas, bukan menjadi penentu utama nilai diri keluarga.
Berdasarkan narasi di atas, tampak jelas bahwa keluarga kontemporer berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalitas, serta antara ranah privat dan publik. Perubahan peran dalam keluarga menandakan adanya negosiasi ulang tanggung jawab dan otoritas. Kakek-nenek kembali diandalkan dalam pengasuhan, mengulang pola keluarga komunal tradisional tetapi dalam konteks berbeda (substitusi peran orang tua karena migrasi atau kesibukan kerja). Ini membawa manfaat, seperti pelestarian nilai-nilai kultural (kakek-nenek sebagai cultural carrier yang mewariskan tradisi keluarga)[70], namun juga membutuhkan penyesuaian pola asuh agar selaras dengan tantangan zaman (misal, kakek-nenek perlu memahami cara mendidik generasi digital). Ibu yang merambah sektor publik menandakan kemajuan kesetaraan gender, tetapi juga melahirkan pertanyaan: siapa yang mengisi kekosongan peran domestik? Apakah ayah siap keluar dari “zona nyaman”-nya dan berbagi tugas rumah tangga, ataukah beban tersebut dialihkan ke kakek-nenek dan asisten rumah tangga (ART)? Dari temuan yang ada, semakin banyak ayah bersedia terlibat, apalagi dengan dorongan edukasi seperti Sekolah Ayah[23]. Namun tidak sedikit pula ayah yang masih enggan berubah – mereka memilih bertahan dalam zona nyaman peran tradisional (fokus di karier saja), sehingga ibu terpaksa menjalani peran ganda. Dalam situasi demikian, risiko konflik dan kelelahan (burnout) ibu meningkat, berpotensi memicu friksi rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan sistemik untuk mendorong peran ayah yang lebih aktif, misalnya melalui cuti ayah, kampanye father involvement, dan teladan figur-figur publik ayah yang family-man.
Isu adaptasi teknologi memperlihatkan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap keluarga. Keluarga yang gagal beradaptasi dapat mengalami “digital divide” internal: misalnya anak fasih teknologi tapi orang tua tidak, sehingga pengawasan dan komunikasi tersendat. Sebaliknya, keluarga yang terlalu larut dalam dunia digital menghadapi ancaman disintegrasi emosi – hadir secara fisik namun absen secara sosial (fenomena alone together). Pembahasan menemukan bahwa solusi yang diusulkan para ahli meliputi: aturan waktu penggunaan gawai (screen time management), aktivitas keluarga bebas gawai, dan meningkatkan kualitas interaksi saat offline[35]. Sekolah dan komunitas juga sebaiknya dilibatkan untuk memberikan edukasi literasi digital menyeluruh. Regulasi pemerintah seperti gerakan literasi digital nasional menjadi langkah positif, meski implementasinya perlu menjangkau hingga level keluarga. Selain itu, adaptasi teknologi juga merambah aspek ekonomi keluarga – misalnya banyak keluarga kini memanfaatkan e-commerce untuk kebutuhan sehari-hari, anak belajar via platform online (edtech), dan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa dikerjakan dari rumah (freelance, remote work). Hal ini mengubah dinamika keseharian keluarga (orang tua di rumah belum tentu tersedia bagi anak karena work from home) sehingga butuh manajemen waktu dan ruang yang jelas di rumah.
Ruang privat vs publik adalah dilema besar era kini. Keluarga mesti menarik garis batas yang sehat: apa yang bisa dibagikan ke publik dan apa yang semestinya tetap privat. Dari pembahasan sharenting dan vlogging, jelas bahwa manfaat eksposur publik (popularitas, pemasukan, dukungan sosial) harus ditimbang dengan risiko (privasi, keamanan, hak anak). Mungkin perlu ada panduan etika atau bahkan regulasi khusus terkait eksploitasi anak di konten digital. Di Prancis misalnya, telah diusulkan RUU yang mewajibkan orang tua menyisihkan sebagian pendapatan untuk anak yang tampil di media sosial, serupa dengan perlindungan aktor cilik. Indonesia pun bisa mulai memikirkan payung hukum serupa untuk melindungi digital child labor. Selain itu, budaya curhat berlebihan di media sosial perlu digeser kembali ke keseimbangan yang wajar. Konseling perkawinan, dukungan komunitas ibu, dan forum-forum tertutup bisa menjadi alternatif agar para istri mendapat tempat berbagi tanpa harus membuka masalah di depan umum. Sifat “realitas” media sosial yang bias (banyak keluarga hanya menampilkan kebahagiaan, atau sebaliknya ada yang hanya curhat penderitaan) harus disikapi kritis oleh pengguna agar tidak terjerumus membandingkan diri secara tidak sehat.
Relasi orang tua-anak di era postmodern menuntut kolaborasi dalam belajar. Orang tua tidak bisa lagi mengandalkan pola “nasihat satu arah” dan berharap anak menurut begitu saja. Sebaliknya, orang tua perlu mau mendengar perspektif anak yang dipengaruhi zaman dan budaya berbeda. Misalnya, dalam hal karier: tak sedikit anak sekarang ingin berkarier di bidang yang unconventional (gamer profesional, YouTuber, desainer game, dll.) yang mungkin dianggap asing bagi orang tua. Daripada langsung menolak, orang tua sebaiknya mencari informasi dan mendiskusikan plus-minus secara terbuka. Ini akan membangun kepercayaan anak bahwa orang tua menghormati pilihannya, sekaligus memberi kesempatan orang tua mengarahkan dengan bijak. Demikian pula terkait pergaulan dan nilai-nilai, seperti telah diulas soal pengaruh budaya populer: orang tua perlu mengimbangi sikap progresif anak dengan pengalaman dan kearifan lokal yang mereka miliki, sehingga anak mendapat sudut pandang kaya sebelum mengambil keputusan. Hubungan yang dialogis dan suportif akan mencegah generation gap yang terlalu lebar.
Pengaruh ekonomi dan budaya populer terhadap keluarga tidak selalu negatif; banyak sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Keluarga dapat menggunakan budaya populer sebagai sarana bonding lintas generasi – misalnya menonton film Marvel bersama, karaoke lagu K-Pop bersama anak, atau mencoba resep viral TikTok bersama-sama. Aktivitas ini menjembatani selera berbeda dan menciptakan memori kolektif baru dalam keluarga. Dari sisi ekonomi, keluarga yang melek teknologi justru bisa lebih produktif dan efisien mengatur keuangan (contoh: memanfaatkan aplikasi budgeting, belanja online hemat promo, peluang bisnis rumahan via e-commerce, dll.). Tantangannya adalah memastikan bahwa adaptasi ekonomi dan budaya tidak menggerus nilai-nilai keluarga yang hakiki: cinta kasih, saling menghormati, dan kebersamaan. Keluarga sebagai institusi sosial harus berfungsi sebagai filter yang menyaring mana pengaruh luar yang boleh masuk dan mana yang ditolak, sesuai dengan norma dan identitas keluarga tersebut.
Terakhir, konsep post-modern family menegaskan bahwa kebijakan dan hukum harus ramah terhadap berbagai bentuk keluarga yang kini eksis. Baik keluarga inti tradisional, keluarga single parent, keluarga dengan orang tua sejenis (di negara yang mengakui), keluarga adopsi, hingga keluarga komunal, semuanya berhak atas perlindungan dan dukungan yang setara. Ini berarti hukum keluarga perlu adaptif – misalnya dalam hal hak waris untuk anak angkat, pengakuan wali bagi cucu yang diasuh kakek-nenek, atau prosedur perceraian dan mediasi yang mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas. Pendekatan hukum progresif dan ijtihad kontemporer (bagi masyarakat Muslim) diperlukan untuk menjawab problematika baru yang tidak terpikirkan oleh hukum lama. Sebagai contoh, isu anak hasil teknologi reproduksi (bayi tabung, surrogate mother) menantang definisi orang tua dalam hukum keluarga klasik. Demikian pula kasus-kasus yang timbul akibat interaksi di dunia maya, misalnya perceraian karena perselingkuhan virtual, kekerasan dalam rumah tangga berbasis teknologi (seperti penyadapan atau penyebaran data pribadi pasangan), semuanya menuntut respons hukum yang jelas.
Kesimpulan
Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi dewasa ini telah membawa keluarga ke lanskap baru yang sarat tantangan sekaligus peluang. Pergeseran peran anggota keluarga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap tuntutan zaman: kakek-nenek mengambil bagian lebih besar dalam pengasuhan, ibu semakin aktif di ranah publik, dan ayah mulai merangkul peran domestik. Adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi keniscayaan bagi keluarga modern, dengan upaya meningkatkan literasi digital guna menjaga kualitas interaksi dan melindungi anggota keluarga dari dampak negatif dunia maya. Batas antara ruang privat dan ruang publik kian tipis – keluarga harus bijak mengelola eksposur media sosial agar kehangatan internal tidak tergerus demi citra eksternal. Relasi orang tua dan anak mengalami dinamika baru: lebih egaliter dan komunikatif, namun juga dihadapkan pada jurang generasi yang diwarnai budaya populer global.
Budaya populer dan faktor ekonomi memengaruhi pola pikir dan gaya hidup keluarga, mendorong nilai-nilai baru yang progresif sekaligus menguji ketahanan nilai tradisional. Keluarga dituntut selektif menyerap pengaruh luar, sembari mempertahankan inti solidaritas dan kasih sayang. Dalam konteks hukum keluarga, segala perkembangan ini mengisyaratkan perlunya pembaruan kerangka legal dan kebijakan. Hukum keluarga harus adaptif dan inklusif, mampu mengakomodasi keragaman bentuk keluarga pasca-modern dan menyelesaikan konflik-konflik kontemporer (dari isu sharenting hingga perceraian digital) dengan adil.
Sebagai penutup, keluarga akan senantiasa menjadi pilar masyarakat, namun wajahnya akan terus berevolusi sesuai zaman. Keluarga Indonesia di era post-modern menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan globalisasi budaya, tetapi juga memiliki modal kuat berupa kearifan lokal dan ikatan kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi. Diperlukan sinergi antara nilai-nilai baru dan nilai lama, antara modernitas dan tradisi, agar keluarga tetap menjadi ruang pertama dan utama yang aman, nyaman, dan mendidik bagi setiap anggotanya. Dengan pemahaman mendalam dan kesadaran kolektif, isu-isu kontemporer hukum keluarga dapat diantisipasi dan diatasi, sehingga keluarga dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.
[1] [2] [61] [62] Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran
[3] [4] The Postmodern Perspective on the Family – ReviseSociology
https://revisesociology.com/2015/04/03/postmodern-perspective-family/
[5] [9] [10] [11] obsesi.or.id
https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/1023/pdf/6195
[6] [7] [8] repository.uinsaizu.ac.id
https://repository.uinsaizu.ac.id/26201/1/Skripsi%20Prio%20Afdi%20Nurahman%20PDF.pdf
[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Literasi Sharenting: Menjaga Jejak Digital Anak di Era Media Sosial – Website LLDIKTI Wilayah V
[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] obsesi.or.id
https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/6741/pdf/29177
[28] Fatherhood di Era Modern: Lebih dari Sekadar Pencari Nafkah
https://paud.fip.unesa.ac.id/post/fatherhood-di-era-modern-lebih-dari-sekadar-pencari-nafkah
[29] [30] [31] [36] ejournal3.undip.ac.id
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/24147/21900
[32] [33] [34] [35] [50] ojs3.unpatti.ac.id
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/komunitas/article/download/11688/8523/
[37] [38] [51] [70] Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga.pdf
file://file-LVth2mGjmKapkg2zCK3kVB
[39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] Sisi Gelap Vlog Keluarga di YouTube
https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2970
[46] [47] [48] [49] √ Pantaskah Istri Curhat di Media Sosial? – Kuntum Cahaya
https://www.kuntumcahaya.com/2024/07/pantaskah-istri-curhat-di-media-sosial.html
[52] [53] [54] [55] Mengapa Generasi Z Mudah Bawa Perasaan atau Baper dan Cara Mengatasinya – Jawa Pos
[56] Grandchildren Help Older Adults Use New Technologies: Qualitative …
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6715044/
[57] [58] 72 persen keluarga Indonesia gunakan layanan pesan antar makanan – ANTARA News
[59] Grab Rilis Tren Layanan Pesan-Antar Online di Indonesia 2022 …
https://mix.co.id/marcomm/news-trend/grab-rilis-tren-layanan-pesan-antar-online-di-indonesia-2022/2/
[60] Masak dan Makan Bersama Keluarga Dapat Menambah … – RRI
https://www.rri.co.id/hobi/814819/masak-dan-makan-bersama-keluarga-dapat-menambah-keharmonisan-rt
[63] Angka Perceraian Meningkat, Menag Usul UU Perkawinan Direvisi
[64] [65] [66] [67] [68] [69] Pengaruh Budaya Populer pada Generasi Z Halaman 1 – Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/goandro/667324fced641521fe21da42/pengaruh-budaya-populer-pada-generasi-z