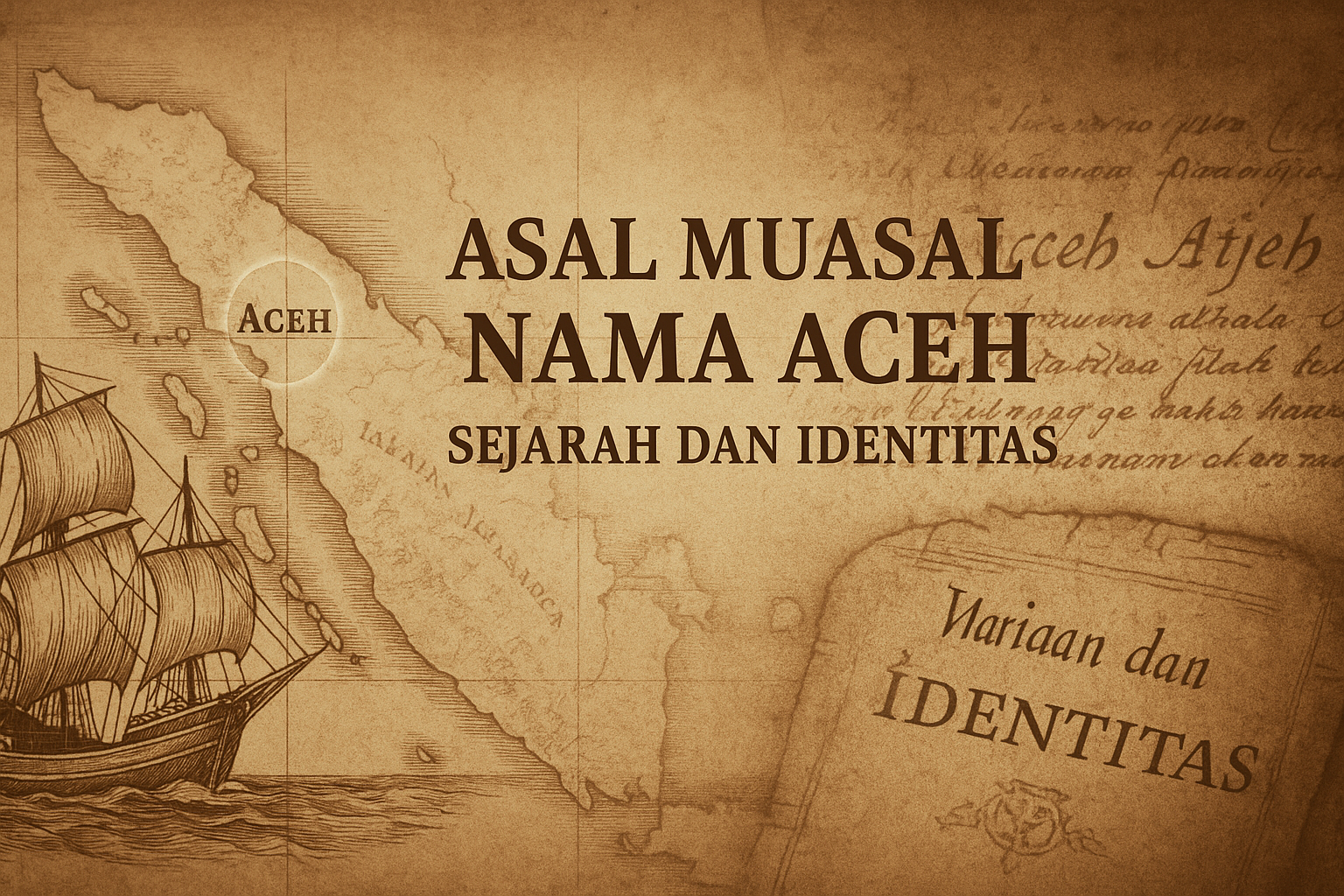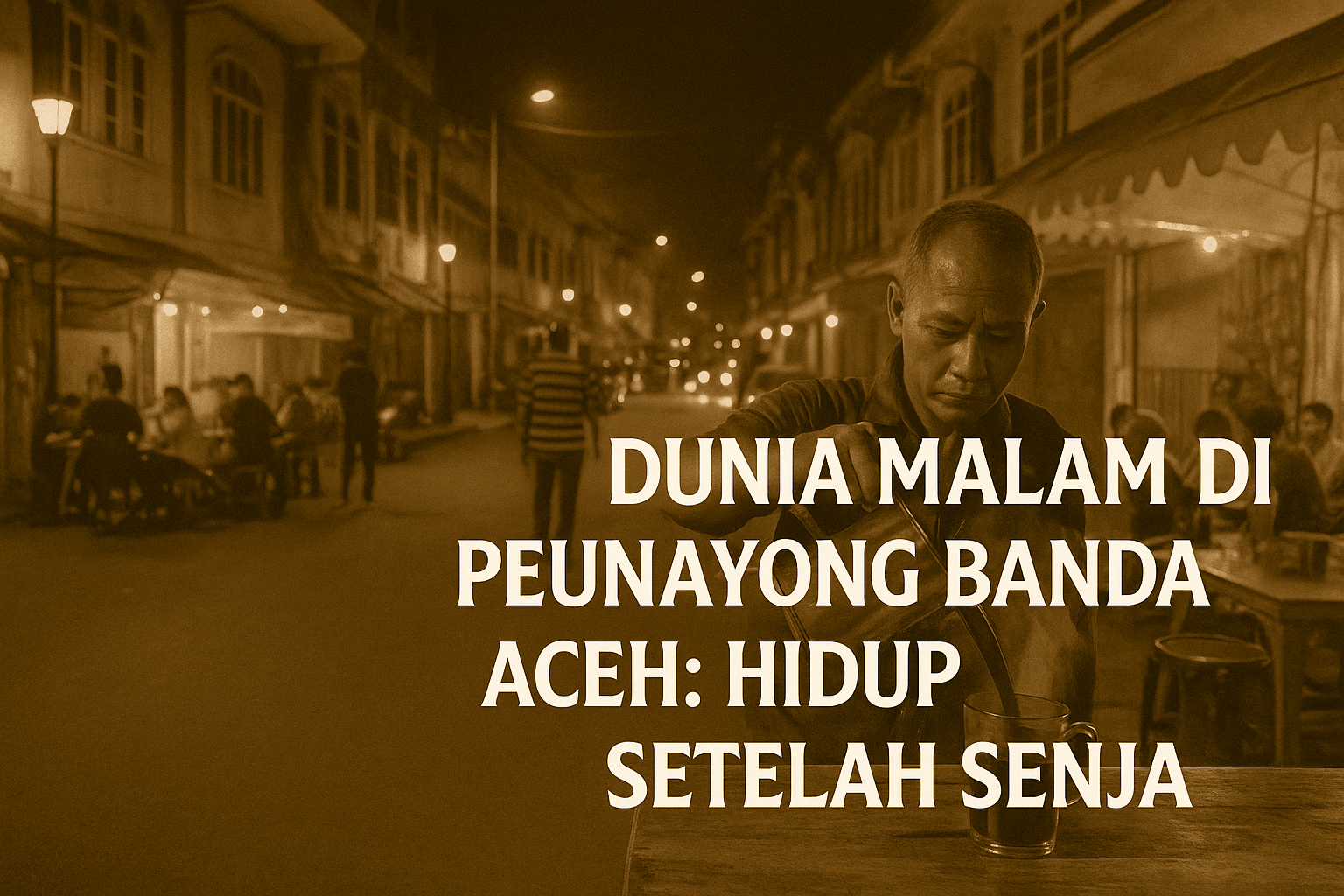Media Sosial = Panggung Flexing
Hari ini, media sosial udah kayak panggung besar tempat anak muda unjuk diri. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, hampir semua aktivitas bisa dijadiin konten. Upload story saat nongkrong, post foto OOTD, atau sekadar update sedang belajar di café—semua jadi cara buat ngasih tahu dunia: “Hei, ini loh aku.” Media sosial berubah jadi arena yang nggak pernah sepi, selalu ramai dengan berbagai gaya hidup yang dipamerkan.
Fenomena ini bikin istilah flexing makin populer. Flexing secara sederhana bisa dibilang sebagai pamer. Tapi dalam praktiknya, flexing bukan cuma soal barang mahal. Kadang flexing juga berupa gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, atau sekadar momen tertentu yang sengaja ditampilkan lebih keren dari aslinya. Dengan kata lain, medsos jadi cermin, tapi cermin yang udah dipoles.
Anak muda merasa kalau nggak update atau nggak posting sesuatu, hidupnya kayak nggak dianggap. Rasa takut ketinggalan atau nggak kelihatan eksis di timeline bikin banyak orang rela melakukan apa saja. Dari situlah flexing jadi semacam kebutuhan sosial, bukan sekadar keinginan.
Buat sebagian, flexing memang terasa wajar. Lagipula, siapa sih yang nggak mau dilihat keren? Tapi kalau dipikir lebih dalam, muncul pertanyaan: apakah semua yang kita pamerkan itu benar-benar milik kita? Atau cuma ilusi biar terlihat “wah” di mata orang lain? Pertanyaan ini sering saya pikirkan ketika scroll timeline, lihat teman-teman upload sesuatu, dan merasa ada jarak antara kenyataan dengan yang mereka tampilkan.
Jadi, sejak awal penting dicatat: flexing di medsos itu nyata, hadir dalam kehidupan sehari-hari, dan nggak bisa dipisahkan dari budaya remaja sekarang. Tapi apakah itu selalu positif? Belum tentu.
Level Flexing: Dari Thrift Sampai iPhone
Kalau kita perhatikan, flexing punya level masing-masing. Ada yang tampil dengan gaya sederhana tapi tetap keren, kayak outfit hasil thrifting. Meski belinya di pasar loak atau toko baju second, kalau pandai mix and match, hasilnya bisa keliatan mahal dan fashionable. Flexing thrift ini biasanya identik dengan kreativitas dan sense of style, bukan semata-mata uang.
Di sisi lain, ada level flexing yang main di kelas atas. Contohnya pamer iPhone seri terbaru, sneakers edisi terbatas, atau tas branded yang harganya bikin dompet langsung kering. Flexing jenis ini lebih banyak soal status sosial. Pesannya jelas: “Aku bisa beli ini, berarti aku beda dari kalian.” Dua dunia ini sama-sama flexing, cuma beda cara dan isi.
Aku sering lihat langsung perbedaan ini. Ada teman yang bangga upload OOTD thrift, lengkap dengan detail harga murah meriah tapi tampil kece. Ada juga teman lain yang nggak pernah absen update kalau habis beli gadget baru. Kadang malah sengaja kasih caption “Finally upgrade 😎” biar makin terlihat eksklusif.
Uniknya, meski beda kelas barang, keduanya punya tujuan yang sama: mencari pengakuan. Yang thrift ingin diakui kreatif, yang branded ingin diakui mapan atau “kekinian.” Jadi sebenarnya, semua kembali ke kebutuhan manusia buat merasa dilihat.
Fenomena ini bikin kita sadar bahwa flexing bukan soal seberapa mahal barangnya, tapi lebih ke seberapa besar orang ingin eksis. Bahkan barang murah bisa jadi bahan flexing, asalkan ditampilkan dengan percaya diri.
Flexing: Ekspresi Diri atau Lebay?
Salah satu sisi menarik dari flexing adalah bahwa ia bisa jadi ajang ekspresi diri. Banyak anak muda bangga menunjukkan hasil jerih payah atau kreativitas. Misalnya, flexing prestasi lomba, karya seni, atau outfit thrift yang dipadu dengan gaya personal. Di sini, flexing jadi bentuk kepercayaan diri: “Aku punya sesuatu yang layak dilihat orang lain.”
Tapi di sisi lain, flexing bisa kelewat lebay. Ada orang yang upload hampir semua aktivitasnya, sampai-sampai terasa dipaksakan. Akibatnya, alih-alih kagum, orang lain justru merasa risih. Flexing yang sehat memberi inspirasi, tapi flexing yang berlebihan bikin orang merasa terintimidasi atau malah jadi insecure.
Media sosial punya kekuatan besar buat ngasih ilusi. Yang ditampilkan biasanya cuma highlight, bukan keseluruhan hidup. Foto nongkrong di café bisa terlihat mewah, padahal kenyataannya cuma minum segelas kopi sambil nunggu waktu pulang. Flexing sering bikin orang lain lupa kalau realita nggak selalu seindah yang ada di layar.
Aku sendiri pernah ngerasain perasaan campur aduk ketika lihat timeline. Kadang iri, kadang minder, tapi kadang juga sadar: “Oh, ini cuma pamer.” Dari situ aku belajar bahwa flexing harus dilihat dengan kacamata kritis, jangan ditelan mentah-mentah.
Jadi, pertanyaan pentingnya: apakah flexing benar-benar ekspresi diri, atau cuma topeng untuk menutupi kekosongan? Jawabannya tergantung niat orang yang melakukannya.
Flexing yang Sehat, Flexing yang Berbahaya
Flexing sebenarnya nggak selalu buruk. Kalau itu hasil kerja keras sendiri, sah-sah aja dipamerkan. Misalnya, siswa yang pamer piala lomba debat atau foto di panggung wisuda. Itu flexing yang sehat, karena bukan sekadar gaya tapi juga pencapaian nyata.
Flexing karya atau outfit thrift juga bisa positif. Banyak anak muda justru mendapat apresiasi karena berani tampil beda dengan gaya unik. Flexing seperti ini malah memotivasi orang lain buat berani mengekspresikan diri tanpa harus selalu pakai barang mahal.
Tapi flexing bisa berubah berbahaya ketika jadi fake lifestyle. Misalnya, pamer barang branded hasil ngutang atau nyicil, cuma biar terlihat “wah” di media sosial. Akhirnya hidup jadi terjebak dalam lingkaran gengsi yang melelahkan. Bukan cuma dompet yang kena, mental juga bisa down karena terus merasa harus tampil sempurna.
Lebih parah lagi, fake flexing bisa memicu budaya pamer yang nggak sehat. Orang lain jadi merasa hidupnya “kurang,” lalu ikut-ikutan flexing palsu. Medsos pun jadi ladang persaingan gengsi, bukan lagi tempat berbagi.
Jadi intinya, flexing sehat bisa jadi inspirasi, tapi flexing berbahaya cuma bikin capek diri sendiri dan bikin orang lain salah menilai hidup kita.
Penutup: Eksis Tanpa Harus Palsu
Flexing di medsos udah jadi bagian nggak terpisahkan dari budaya remaja. Kita nggak bisa sepenuhnya nolak, karena medsos memang tempat unjuk diri. Tapi penting untuk tetap realistis dan nggak menjadikan flexing sebagai beban.
Eksistensi bukan ditentukan dari seberapa mahal barang yang dipamerkan, tapi dari seberapa jujur kita menjalani hidup. Lebih baik pamer karya nyata atau kebahagiaan sederhana, daripada fake lifestyle yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
Flexing boleh, asal nggak lebay. Jangan sampai hidup cuma sekadar soal bikin feed keren, tapi di belakang layar penuh tekanan. Ingat, hidup lebih luas daripada sekadar layar HP.
Saya pribadi percaya, yang bikin nyaman itu bukan sekadar keren di mata orang lain, tapi bisa jujur sama diri sendiri. Kalau flexing bikin bahagia dan nggak nyusahin, silakan. Tapi kalau flexing bikin capek, mungkin saatnya berhenti.
Karena pada akhirnya, dunia nyata lebih penting daripada dunia maya. Flexing boleh, tapi jangan lupa: hidup ini bukan panggung drama, melainkan perjalanan panjang yang lebih indah kalau dijalani apa adanya.
👉 Artikel ini ditulis oleh Qaishar, siswa kelas XII SMA Labschool Banda Aceh, yang suka mengamati gaya hidup anak muda di era medsos, lalu merenungkannya sambil ngopi di warkop kota.