Pendahuluan: Hegel dan Jalan Panjang Menuju Absolut
Membicarakan filsafat Jerman pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 tidak mungkin dilepaskan dari nama Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Sosok ini bukan hanya seorang filsuf yang produktif, tetapi juga pemikir yang berusaha menutup jurang besar yang ditinggalkan oleh Kant. Jika Kant menegaskan batas-batas rasio manusia, Hegel justru ingin melampauinya dengan membangun sebuah sistem yang mampu menampung seluruh kenyataan. John Shand dalam Philosophy and Philosophers menggambarkan bahwa inti dari filsafat Hegel adalah usaha untuk menunjukkan bahwa realitas sepenuhnya dapat dipahami, dan bahwa seluruh realitas pada akhirnya adalah ekspresi dari Roh Mutlak yang berpikir tentang dirinya sendiri (hal. 179–182).
Kelahiran Hegel di Stuttgart pada 1770, latar belakang pendidikannya dalam filsafat dan teologi di Universitas Tübingen, serta persahabatannya dengan Hölderlin dan Schelling, telah membentuk horizon intelektual yang luas. Shand menyebutkan bahwa Revolusi Prancis meninggalkan kesan mendalam baginya: revolusi itu menunjukkan daya rasio dalam sejarah, tetapi sekaligus memperlihatkan kegagalan jika rasio dipraktikkan secara abstrak, terlepas dari kondisi sosial riil (hal. 179). Dari sini Hegel mulai mengembangkan gagasan bahwa rasio tidak boleh dipisahkan dari sejarah, masyarakat, dan kehidupan bersama.
Di tangan Hegel, filsafat menjadi usaha untuk memahami kenyataan sebagai totalitas yang rasional. Ia menolak gagasan Kant tentang “things-in-themselves” yang tidak dapat diketahui. Menurut Hegel, apa yang dikatakan tak terjangkau itu justru kontradiktif, sebab dengan menyebut sesuatu sebagai “tak terjangkau” kita sudah mengaplikasikan konsep kepadanya. Dengan demikian, “noumenon” Kantian runtuh ke dalam kategori yang dapat diketahui. Shand menekankan, “The collapse through contradiction of the conception of the thing-in-itself leads inexorably to absolute idealism, and to the complete knowability of everything” (hal. 180). Inilah jalan menuju idealism absolut yang menjadi ciri khas sistem Hegel.
Bagi Hegel, kebenaran tidak ditemukan dalam fragmen-fragmen, melainkan dalam keseluruhan. Ia merumuskan adagium yang terkenal: “The truth is the whole.” Artinya, setiap bagian realitas hanya dapat dipahami jika ditempatkan dalam konteks keseluruhan. Jika kita mencoba memahami sesuatu secara terpisah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi. Karena itu, filsafat harus bergerak dari satu konsep ke konsep lain, menyingkap relasi-relasi yang saling bergantung, hingga akhirnya mencapai totalitas. Shand menulis, “Everything in the universe is understood through, in short, everything” (hal. 181).
Hegel juga menolak pemisahan mutlak antara subjek dan objek. Baginya, dunia luar bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dari kesadaran. Justru, kesadaran selalu sudah terhubung dengan objeknya. Pada tingkat tertinggi, subjek dan objek larut dalam kesatuan Roh Absolut, di mana pikiran hanya memikirkan dirinya sendiri. “The Absolute is the infinite self-thinking mind” (hal. 182). Dengan kata lain, realitas pada dasarnya adalah pikiran yang merefleksikan dirinya dalam berbagai bentuk: alam, sejarah, seni, agama, hingga filsafat.
Shand menggambarkan realitas Hegelian sebagai sebuah bola sempurna, di mana setiap bagian memantulkan bagian lain dengan simetri total. Analogi ini menggambarkan bahwa dalam Absolut tidak ada yang hilang, tidak ada yang berada di luar. Semua perbedaan, bahkan kontradiksi, dilestarikan di dalam identitas yang lebih tinggi. Kontradiksi bukanlah akhir dari pemikiran, melainkan justru motor yang mendorong dialektika menuju sintesis. Inilah yang membuat sistem Hegel menjadi tidak statis, melainkan selalu bergerak, berkembang, dan berproses.
Dengan demikian, pendahuluan filsafat Hegel menurut Shand adalah kisah tentang keberanian akal untuk mengklaim bahwa seluruh realitas dapat dipahami. Dari biografinya yang dipengaruhi Revolusi Prancis, dari kritiknya terhadap Kant, hingga gagasan tentang absolute idealism, kita melihat sebuah upaya besar untuk menyingkap rasionalitas sejarah dan dunia. Esai ini akan menelusuri lebih jauh bagaimana Hegel mengembangkan logika dialektis, bagaimana ia memandang kesadaran dan kebebasan, serta bagaimana sistemnya tetap memberi gema hingga hari ini.
Latar Intelektual Hegel dan Kritik atas Kant
Georg Wilhelm Friedrich Hegel lahir di Stuttgart pada tahun 1770 dari keluarga kecil kelas pegawai sipil yang berlatar belakang Lutheran. Pendidikan awalnya di Universitas Tübingen membawanya untuk mendalami filsafat sekaligus teologi. Di sanalah ia bersentuhan dengan dua figur yang kelak menjadi sahabat intelektualnya: Hölderlin, sang penyair, dan Schelling, sang filsuf. John Shand menekankan bahwa perjumpaan ini memberikan warna awal yang penting bagi horizon intelektual Hegel, yang sejak dini menggabungkan refleksi teologis, filsafat klasik, dan sensibilitas estetis ke dalam satu jalur pemikiran (hal. 179).
Situasi sejarah Eropa, khususnya Revolusi Prancis, juga meninggalkan jejak yang dalam bagi Hegel. Revolusi itu dipahami sebagai manifestasi rasio dalam sejarah, namun sekaligus menunjukkan bagaimana penerapan rasio secara abstrak dapat berujung pada kegagalan. Shand menulis bahwa Hegel melihat revolusi sebagai “momentous in its rigorous application of reason, but it was also a great failure because reason was applied in an abstract way that took no account of particular circumstances of the community” (hal. 179). Dari pengalaman ini, Hegel sampai pada kesimpulan bahwa rasio tidak bisa dipisahkan dari kenyataan konkret suatu komunitas.
Perjalanan intelektual Hegel tidak berhenti di Tübingen. Setelah sempat bekerja sebagai editor surat kabar dan mengajar di beberapa tempat, ia menulis karya besar pertamanya, The Phenomenology of Spirit. Dalam karya ini ia berusaha menggambarkan perjalanan kesadaran manusia menuju pengetahuan absolut. Pada tahun-tahun berikutnya, ia mengajar di Jena, Nuremberg, Heidelberg, dan akhirnya di Berlin. Pada 1821, ia menerbitkan The Philosophy of Right, karya yang memaparkan gagasannya tentang negara, hukum, dan kebebasan. Semua ini menunjukkan bahwa filsafat Hegel tidak pernah jauh dari konteks sosial dan politik zamannya (hal. 179–180).
Akar intelektual Hegel sangat dipengaruhi filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, juga para filsuf pra-Sokratik seperti Heraclitus dan kaum Eleatik. Dari mereka, ia menyerap pandangan bahwa realitas adalah suatu totalitas yang rasional dan bahwa perubahan merupakan bagian mendasar dari eksistensi. Namun pengaruh yang paling signifikan datang dari dua sumber: Spinoza dan Kant. Dari Spinoza, Hegel belajar mengenai pentingnya memandang kenyataan sebagai satu substansi tunggal yang bersifat rasional. Dari Kant, ia menerima inspirasi sekaligus kritik, sebab filsafatnya berkembang dari upaya melampaui batasan yang diajukan Kant tentang pengetahuan manusia (hal. 179).
Kritik Hegel terhadap Kant berfokus pada konsep “things-in-themselves” atau noumena. Menurut Kant, ada hal-hal yang tidak bisa diketahui karena berada di luar ranah pengalaman dan kategori-kategori akal budi manusia. Hegel menolak posisi ini. Baginya, jika sesuatu dikatakan tidak dapat diketahui, maka penyebutan itu sendiri sudah menerapkan suatu konsep, sehingga hal tersebut sebenarnya telah masuk ke dalam ranah pengetahuan. Shand menyatakan dengan jelas: “The collapse through contradiction of the conception of the thing-in-itself leads inexorably to absolute idealism, and to the complete knowability of everything” (hal. 180). Dengan kata lain, penolakan Kant justru membuka jalan bagi Hegel untuk menegaskan bahwa segala sesuatu dapat diketahui.
Bagi Hegel, filsafat tidak boleh berhenti pada batas-batas yang ditetapkan Kant. Tugas filsafat justru menunjukkan bagaimana seluruh realitas dapat dipahami secara rasional. Di sini, ia memperkenalkan gagasan absolute idealism, yaitu pandangan bahwa realitas sepenuhnya dapat diakses oleh pikiran karena realitas itu sendiri bersifat rasional. Konsekuensinya, tidak ada sesuatu pun yang berada di luar jangkauan konsep. Apa pun yang nyata, sejatinya sudah tunduk pada kategori rasio. Karena itu, menurut Hegel, filsafat harus bergerak melampaui sekadar menggambarkan fenomena; ia harus mengungkap logika yang mengatur totalitas realitas (hal. 180).
Dengan menolak pemisahan antara fenomena dan noumena, Hegel juga menghapus dikotomi tajam antara a priori dan a posteriori. Pengetahuan tidak lagi terbagi atas apa yang berasal dari pengalaman indrawi dan apa yang ditentukan oleh akal budi, melainkan dipahami sebagai hasil dari dialektika konsep-konsep yang saling mengoreksi dan melengkapi. Shand menekankan bahwa bagi Hegel, “reality in its entirety is not unknowable since things-in-themselves are beyond possible appearances and excluded” (hal. 180). Dengan demikian, Hegel meneguhkan bahwa realitas sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam kategori rasio.
Kesimpulannya, latar intelektual Hegel dan kritiknya atas Kant menjadi titik awal bagi pengembangan filsafat yang berpijak pada idealisme absolut. Dari pengaruh filsuf Yunani hingga inspirasi dari Spinoza, dari pengalaman Revolusi Prancis hingga penolakannya terhadap noumena Kant, Hegel membangun sebuah sistem filsafat yang tidak hanya berupaya memahami dunia, melainkan juga meyakini bahwa dunia sepenuhnya rasional dan karenanya dapat diketahui. Inilah fondasi yang akan menopang seluruh bangunan filsafat Hegel, dari logika hingga sejarah, dari kesadaran individu hingga roh objektif umat manusia.
Filsafat sebagai Jalan Menuju Roh Absolut
Bagi Hegel, filsafat bukanlah sekadar upaya intelektual untuk memahami konsep-konsep secara terpisah, melainkan suatu usaha menyeluruh untuk menangkap realitas sebagai sebuah totalitas. John Shand menekankan bahwa dalam pandangan Hegel, kebenaran tidak dapat ditemukan dalam fragmen-fragmen terisolasi, melainkan hanya dalam keseluruhan. Hegel menegaskan adagium yang kemudian terkenal: “The truth is the whole.” Artinya, sebuah entitas atau konsep tidak memiliki makna sejati kecuali dalam kaitannya dengan keseluruhan realitas yang lebih luas (hal. 181). Dengan demikian, filsafat memiliki tugas untuk selalu bergerak, menjalin keterhubungan, dan menyingkap relasi-relasi antara bagian-bagian yang berbeda.
Hegel berangkat dari keyakinan bahwa realitas sepenuhnya rasional. Jika Kant masih membedakan antara fenomena dan noumena, Hegel justru menghapus batas itu. Baginya, apa yang ada adalah sekaligus apa yang dapat dipikirkan. Realitas dan rasio tidak berada di dua wilayah terpisah, melainkan identik. Shand menulis, “The rational is the real and the real is the rational” (hal. 181). Ungkapan ini menjadi kunci untuk memahami keseluruhan sistem Hegel. Jika realitas bersifat rasional, maka filsafat adalah jalan untuk menyingkap pola-pola rasional itu.
Dengan pendekatan ini, Hegel menegaskan bahwa filsafat harus memandang segala sesuatu sebagai ekspresi dari satu prinsip tunggal: Roh Absolut. Absolut ini tidak berada di luar realitas, melainkan hadir dalam dan melalui realitas itu sendiri. Semua yang ada, mulai dari alam hingga masyarakat, dari seni hingga agama, merupakan cara-cara Roh Absolut mengekspresikan dirinya. Shand merumuskannya dengan singkat: “The Absolute is the infinite self-thinking mind” (hal. 182). Dengan kata lain, pada tingkat tertinggi, realitas hanyalah pikiran yang berpikir tentang dirinya sendiri.
Analogi yang digunakan Shand untuk menjelaskan konsep ini adalah sebuah bola sempurna. Dalam bola itu, setiap titik memantulkan titik lain, membentuk simetri total. Begitulah realitas menurut Hegel: tidak ada sesuatu pun yang berada di luar, tidak ada fragmen yang terisolasi, dan tidak ada perbedaan yang kekal. Semua bagian saling terkait, dan setiap kontradiksi justru dipelihara dalam kerangka totalitas. Kontradiksi bukanlah kelemahan, melainkan motor penggerak yang membawa pikiran menuju sintesis yang lebih tinggi.
Kebenaran bagi Hegel adalah proses, bukan keadaan statis. Pikiran manusia tidak dapat berhenti pada konsep tertentu karena setiap konsep akan menyingkap keterbatasan dirinya sendiri. Melalui kontradiksi-kontradiksi inilah pikiran dipaksa untuk bergerak menuju konsep berikutnya, hingga akhirnya mencapai totalitas. Shand menekankan bahwa “truth is not to be found in isolated fragments but only in the whole” (hal. 181). Maka filsafat selalu bersifat dinamis, bergerak maju, dan pada akhirnya bersifat teleologis, yaitu menuju pengungkapan penuh dari Roh Absolut.
Dalam sistem ini, filsafat juga mengambil posisi tertinggi dibanding bentuk-bentuk lain dari roh manusia, seperti seni dan agama. Jika seni mengekspresikan kebenaran melalui bentuk indrawi, dan agama menyingkapkannya dalam simbol-simbol keimanan, maka filsafat mengungkap kebenaran itu secara konseptual. Karena itulah Hegel melihat filsafat sebagai puncak perkembangan roh. Melalui filsafat, roh tidak hanya mengalami dirinya, tetapi juga memahami dirinya secara reflektif dan rasional.
Dengan demikian, filsafat bagi Hegel adalah jalan menuju Roh Absolut. Ia berfungsi bukan semata-mata untuk menjawab pertanyaan abstrak, tetapi untuk mengungkap struktur terdalam realitas itu sendiri. Kebenaran adalah keseluruhan, dan keseluruhan itu bersifat rasional. Melalui filsafat, manusia menyadari bahwa realitas tidak lain adalah pikiran yang berpikir tentang dirinya sendiri. Maka dari itu, filsafat Hegel selalu bersifat menyeluruh, reflektif, dan teleologis, dengan tujuan akhir mencapai pemahaman penuh tentang Roh Absolut.
Logika Dialektis: Being, Nothing, Becoming
Dalam sistem filsafat Hegel, logika bukan sekadar aturan berpikir formal sebagaimana dipahami dalam tradisi Aristoteles, melainkan jantung dari seluruh realitas. John Shand menegaskan bahwa logika tradisional yang hanya berfokus pada prinsip identitas dan nonkontradiksi tidak cukup untuk memahami dinamika realitas. Bagi Hegel, realitas senantiasa bergerak, berproses, dan berubah, sehingga logika yang tepat untuk menyingkapnya harus bersifat dinamis. Inilah yang melahirkan logika dialektis, suatu cara berpikir yang bertumpu pada kontradiksi dan pergerakan menuju sintesis (hal. 184).
Hegel memandang bahwa setiap konsep mengandung keterbatasan internal yang akan menuntun kepada konsep lain. Proses ini bukan kebetulan, melainkan gerak niscaya dari rasio itu sendiri. Shand menjelaskan bahwa logika Hegel bergerak dalam pola triadik: tesis, antitesis, dan sintesis. Bukan dalam arti mekanis, melainkan sebagai cara menunjukkan bahwa setiap konsep hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan negasi dan pengatasan diri (hal. 184). Dengan demikian, dialektika Hegel tidak berhenti pada oposisi, melainkan mengangkat perbedaan itu ke dalam kesatuan yang lebih tinggi.
Awal dari seluruh gerak dialektika Hegel terletak pada kategori paling sederhana: Being (Ada). Being dipahami sebagai kehadiran murni, tanpa sifat, tanpa determinasi, hanya “ada” dalam arti paling umum. Namun, karena Being tidak memiliki isi sama sekali, ia identik dengan Nothing (Tiada). Shand menyatakan, “Pure being has no determination, hence it collapses into nothing” (hal. 185). Di sinilah kontradiksi pertama dalam sistem Hegel: apa yang paling penuh justru kosong, dan apa yang paling nyata justru hampa.
Kontradiksi antara Being dan Nothing ini tidak menghasilkan kebuntuan, melainkan gerak menuju kategori baru: Becoming (Menjadi). Becoming adalah perpaduan antara Being dan Nothing, proses di mana ada dan tiada saling melampaui. Shand menulis, “The unity of being and nothing is becoming” (hal. 185). Dengan demikian, realitas pada dasarnya adalah proses, bukan substansi yang statis. Dunia tidak pernah berhenti pada ada atau tiada, melainkan selalu berada dalam gerak menjadi.
Dialektika Being–Nothing–Becoming menjadi model bagi seluruh perkembangan sistem Hegel. Setiap kategori yang muncul kemudian akan mengandung kontradiksi internal, yang mendorong ke kategori baru. Kontradiksi tidak pernah dipandang sebagai kegagalan logis, melainkan sebagai motor yang menggerakkan rasio menuju pemahaman yang lebih luas. Di sinilah logika Hegel berbeda secara radikal dari logika tradisional yang cenderung menghapus kontradiksi. Hegel justru memeliharanya, karena tanpa kontradiksi tidak ada perkembangan.
Selain itu, struktur Being–Nothing–Becoming memperlihatkan bahwa realitas bersifat temporal. Tidak ada yang sepenuhnya tetap, karena segala sesuatu mengandung potensi untuk berubah menjadi lawannya. Dalam Becoming, kita melihat bahwa waktu bukan sekadar dimensi eksternal, melainkan bagian dari struktur ontologis realitas. Segala sesuatu selalu dalam proses, bergerak dari ada menuju tiada, dan dari tiada menuju ada kembali.
Dengan demikian, logika dialektis Hegel bukan hanya teori tentang konsep, melainkan juga teori tentang realitas itu sendiri. Realitas dipahami sebagai totalitas yang bergerak melalui kontradiksi menuju sintesis. Dari Being, Nothing, dan Becoming, kita memperoleh gambaran bahwa yang paling sederhana pun sudah mengandung dinamika menuju perkembangan lebih lanjut. Logika dialektis ini kemudian menjadi fondasi bagi seluruh sistem Hegel, mulai dari filsafat alam hingga filsafat roh, dari kesadaran individu hingga sejarah umat manusia.
Dialektika Kesadaran: Dari Kesadaran ke Akal
Setelah meletakkan fondasi logika dialektis, Hegel menerapkannya dalam analisis tentang struktur kesadaran manusia. John Shand menjelaskan bahwa Hegel membedakan tiga tahap penting: kesadaran (consciousness), kesadaran-diri (self-consciousness), dan akal (reason). Tiga tahap ini bukan sekadar klasifikasi psikologis, melainkan gerak dialektis yang menggambarkan bagaimana roh manusia mencapai pengetahuan tentang dirinya sendiri. “Consciousness (the object is independent of self); Self-consciousness (the object is identical with subject); Reason (subject/object distinction is collapsed)” (hal. 188). Dengan demikian, perkembangan kesadaran adalah jalan menuju pemahaman tentang totalitas.
Tahap pertama adalah kesadaran (consciousness), di mana subjek memandang objek sebagai sesuatu yang independen, terpisah dari dirinya. Dalam tahap ini, manusia berhadapan dengan dunia luar sebagai realitas asing yang harus dipahami. Kesadaran masih bersifat dualistik: ada subjek yang mengetahui, ada objek yang diketahui. Shand menegaskan bahwa hubungan ini selalu menempatkan objek sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, di luar diri subjek (hal. 188). Dengan demikian, kesadaran awal selalu bersifat keterasingan, karena dunia dipahami sebagai sesuatu yang lain.
Tahap kedua adalah kesadaran-diri (self-consciousness). Di sini terjadi perubahan besar: subjek mulai melihat bahwa objek yang dihadapinya tidak sepenuhnya berbeda, melainkan identik dengan dirinya. Hegel menggambarkan tahap ini sebagai momen di mana subjek menyadari dirinya sebagai objek, dan objek sebagai dirinya. Shand menjelaskan, “Self-consciousness (the object is identical with subject)” (hal. 188). Artinya, hubungan dualistik antara subjek dan objek mulai larut, karena subjek menyadari bahwa realitas luar hanyalah cermin bagi kesadarannya sendiri.
Tahap ketiga adalah akal (reason). Pada level ini, perbedaan antara subjek dan objek sepenuhnya runtuh. Tidak ada lagi jarak antara yang mengetahui dan yang diketahui, karena keduanya menyatu dalam kesatuan totalitas. Shand merumuskan, “Reason (subject/object distinction is collapsed)” (hal. 188). Akal adalah momen ketika kesadaran mencapai kesatuan dengan realitas, karena yang rasional adalah yang nyata dan yang nyata adalah yang rasional. Dalam tahap ini, manusia tidak lagi terjebak pada keterasingan, melainkan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari totalitas rasional yang lebih besar.
Perkembangan dari kesadaran ke akal menunjukkan bahwa pengetahuan bukanlah akumulasi data tentang dunia luar, melainkan gerak dialektis menuju kesatuan dengan realitas. Hegel ingin menunjukkan bahwa manusia tidak selamanya terasing dari dunia, karena pada akhirnya ia menyadari bahwa dunia adalah ekspresi dari dirinya, dan dirinya adalah bagian dari dunia. Dalam tahap akal, manusia menemukan identitas terdalamnya sebagai bagian dari Roh Absolut.
Shand menekankan bahwa puncak dari gerak ini adalah momen ketika pikiran hanya memikirkan dirinya sendiri. “Thus we reach pure self-thinking thought, where the only object of thought is itself” (hal. 188). Inilah inti dari idealisme absolut Hegel: realitas pada dasarnya adalah pikiran yang berpikir tentang dirinya sendiri. Semua perbedaan antara subjek dan objek, antara dalam dan luar, akhirnya larut dalam refleksi diri yang total.
Dengan demikian, dialektika kesadaran bukanlah teori psikologi, melainkan gambaran metafisik tentang bagaimana roh mencapai pengetahuan absolut. Dari keterasingan dalam kesadaran, melalui refleksi dalam kesadaran-diri, hingga penyatuan dalam akal, manusia menempuh jalan dialektis menuju kesatuan dengan realitas. Perjalanan ini memperlihatkan bahwa pengetahuan sejati hanya mungkin jika perbedaan antara subjek dan objek akhirnya ditiadakan dalam totalitas rasional.
Roh Obyektif dan Sejarah Kebebasan
Hegel tidak berhenti pada analisis kesadaran individual. Gerak dialektis roh juga menemukan ekspresinya dalam kehidupan bersama manusia. Di sinilah muncul konsep Roh Obyektif (Objective Mind), yang oleh John Shand disebut sebagai “the public manifestation of spirit” (hal. 188). Artinya, roh tidak hanya hadir dalam kesadaran subjektif individu, melainkan juga dalam institusi, norma, hukum, dan sejarah umat manusia. Roh obyektif adalah cara roh mengekspresikan dirinya di ruang sosial, sehingga filsafat Hegel selalu terkait erat dengan politik, hukum, dan kebudayaan.
Shand menjelaskan bahwa bagi Hegel, sejarah dunia adalah proses dialektis di mana roh bergerak menuju kesadaran penuh akan kebebasan. Sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa, melainkan perjalanan teleologis yang diarahkan oleh nalar. Ia menegaskan bahwa roh hanya dapat mencapai pemahaman tentang dirinya melalui sejarah, karena sejarah adalah ruang di mana kebebasan dipraktikkan dan diwujudkan (hal. 188). Dengan demikian, sejarah bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari logika perkembangan roh.
Hegel menguraikan tiga tahap besar dalam sejarah dunia. Pertama adalah dunia Oriental, di mana hanya satu orang yang bebas, yakni sang despot. Di sini kebebasan masih bersifat terbatas, karena hanya penguasa yang dianggap memiliki kedaulatan penuh. Rakyat dipandang sebagai milik penguasa, sehingga roh belum menemukan dirinya sebagai kesadaran universal. Shand menuliskan ringkas: “Oriental world: only one is free (the despot)” (hal. 188). Tahap ini menggambarkan masyarakat yang masih terperangkap dalam absolutisme politik.
Tahap kedua adalah dunia Yunani, di mana beberapa orang bebas, khususnya warga negara yang bukan budak. Di sini, kebebasan mulai diperluas, tetapi tetap terbatas pada kalangan tertentu. Demokrasi Yunani, meski tampak membuka ruang partisipasi, tetap menyingkirkan budak dan kaum perempuan dari lingkaran kebebasan. Shand merumuskannya: “Greek world: some are free (citizens not slaves)” (hal. 188). Tahap ini memperlihatkan bahwa kebebasan belum bersifat universal, tetapi roh telah melangkah lebih maju dibanding dunia Oriental.
Tahap ketiga adalah dunia Germanik, di mana semua orang diakui sebagai bebas. Menurut Hegel, inilah puncak sejarah kebebasan, karena roh akhirnya mencapai kesadaran penuh bahwa kebebasan adalah hak universal. Shand menyebut: “Germanic world: all are free” (hal. 188). Kebebasan tidak lagi dilihat sebagai hak eksklusif bagi penguasa atau kalangan tertentu, melainkan sebagai prinsip yang melekat pada setiap individu. Dalam tahap ini, roh menyadari dirinya sebagai kebebasan yang bersifat rasional dan universal.
Dengan demikian, sejarah dunia bagi Hegel adalah perjalanan menuju kesadaran universal tentang kebebasan. Dari satu orang, ke beberapa orang, hingga akhirnya ke semua orang, roh bergerak melampaui keterbatasan demi mencapai kesadaran penuh. Proses ini bersifat niscaya, karena roh hanya dapat memahami dirinya melalui perkembangan sejarah. Shand menekankan bahwa bagi Hegel, sejarah bukan kebetulan, melainkan ekspresi dari logika internal roh (hal. 188).
Melalui konsep roh obyektif, Hegel menunjukkan bahwa kebebasan bukan sekadar persoalan individu, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Kebebasan harus terinstitusionalisasi dalam hukum, negara, dan masyarakat. Karena itu, filsafat sejarah Hegel tidak terlepas dari filsafat politiknya. Ia ingin menunjukkan bahwa perkembangan sejarah dunia merupakan jalan menuju kesadaran rasional universal, di mana kebebasan menjadi prinsip tertinggi kehidupan manusia.
Kebebasan sebagai Determinasi Diri dan Hukum Rasional
Puncak dari perkembangan roh obyektif dalam sejarah adalah kesadaran akan kebebasan. Namun, kebebasan dalam filsafat Hegel tidak dapat dipahami hanya sebagai ketiadaan paksaan atau kebolehan bertindak sesuka hati. John Shand menegaskan bahwa Hegel menolak pengertian kebebasan yang bersifat negatif, yakni bebas dari sesuatu. Sebaliknya, kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan universal. Shand merumuskannya: “Freedom is not absence of constraint but acting from self-determination” (hal. 188). Dengan kata lain, kebebasan adalah penentuan diri yang selaras dengan hukum akal budi.
Dalam kerangka ini, hukum tidak dipandang sebagai batasan eksternal yang mengekang kebebasan, melainkan sebagai ekspresi dari rasionalitas itu sendiri. Bagi Hegel, hukum adalah perwujudan dari kebebasan yang objektif, karena hukum merangkum prinsip-prinsip rasional universal yang diakui oleh komunitas. Kebebasan sejati hanya mungkin jika individu menginternalisasi hukum tersebut sebagai bagian dari dirinya. Shand menulis, “One is free only if one acts in accord with the laws of reason, i.e. with universal principles” (hal. 188). Maka, ketaatan pada hukum bukanlah paksaan, melainkan bentuk nyata dari kebebasan itu sendiri.
Hegel menggunakan gagasan tentang “organic community” untuk menjelaskan hal ini. Komunitas organik adalah masyarakat di mana individu tidak melihat dirinya sebagai entitas terpisah dari keseluruhan, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial yang rasional. Dalam komunitas seperti itu, individu dan masyarakat tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Shand menegaskan bahwa kebebasan hanya mungkin dalam komunitas yang mengatur dirinya sesuai dengan prinsip rasional, sehingga setiap individu menemukan dirinya di dalam keseluruhan (hal. 188).
Kebebasan sebagai determinasi diri ini juga terkait dengan gagasan Hegel tentang negara. Negara bukanlah alat penindasan, melainkan realisasi tertinggi dari kebebasan rasional. Di dalam negara, hukum dan institusi mewujudkan prinsip-prinsip universal yang memungkinkan setiap individu hidup bebas. Negara, bagi Hegel, adalah “aktualitas kebebasan” karena ia menyatukan kehendak individu dengan kehendak umum. Dengan demikian, individu bebas justru ketika ia hidup dalam kerangka hukum negara yang rasional.
Shand memperlihatkan bahwa kebebasan menurut Hegel bukanlah kebebasan individualistik, melainkan kebebasan yang bersifat etis. Seseorang bebas bukan ketika ia bertindak sesuai keinginannya sendiri, melainkan ketika ia bertindak sesuai prinsip yang dapat diakui oleh semua orang sebagai rasional. Dalam arti ini, kebebasan selalu bersifat universal, karena didasarkan pada hukum akal budi. Inilah yang membedakan kebebasan Hegel dari kebebasan liberal yang cenderung menekankan otonomi individu secara mutlak (hal. 188).
Dengan menekankan bahwa kebebasan adalah determinasi diri menurut hukum rasional, Hegel juga menunjukkan bahwa kontradiksi antara individu dan masyarakat dapat diatasi. Individu menemukan kebebasannya bukan di luar masyarakat, tetapi justru di dalamnya. Masyarakat yang rasional menyediakan ruang bagi individu untuk mewujudkan dirinya, sementara individu berkontribusi pada pemeliharaan rasionalitas masyarakat. Relasi ini bersifat dialektis: individu dan masyarakat saling membentuk, saling menentukan, dan saling mengafirmasi.
Akhirnya, konsep kebebasan dalam filsafat Hegel menutup lingkaran dari seluruh sistemnya. Dari logika dialektis hingga roh obyektif, semua bergerak menuju pengungkapan penuh tentang kebebasan. Kebebasan bukan sekadar hak, bukan pula sekadar kebolehan, melainkan inti dari rasionalitas itu sendiri. Shand menutup penjelasannya dengan menunjukkan bahwa kebebasan, bagi Hegel, adalah realitas yang ditentukan oleh diri sendiri, di mana individu dan masyarakat menyatu dalam hukum rasional universal. Dengan begitu, kebebasan sejati hanya ada ketika manusia hidup dalam harmoni dengan prinsip rasional yang bersifat universal dan abadi.
Kesimpulan: Hegel dan Warisan Filsafat Totalitas
Membaca kembali uraian John Shand tentang Hegel dalam Philosophy and Philosophers menyingkapkan betapa luas dan dalam bangunan filsafat yang diwariskan oleh sang pemikir Jerman. Dari latar intelektualnya yang dipengaruhi Revolusi Prancis, filsafat Yunani, Spinoza, dan terutama Kant, Hegel tampil sebagai sosok yang berusaha menyatukan segala kontradiksi ke dalam sistem menyeluruh. Ia tidak berhenti pada kritik terhadap Kant, tetapi melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa segala sesuatu pada akhirnya dapat diketahui karena realitas itu sendiri bersifat rasional (hal. 180). Inilah yang dikenal sebagai absolute idealism, yang menjadi inti sistem filsafatnya.
Hegel meletakkan prinsip bahwa “The truth is the whole” (hal. 181). Prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa dipahami dalam totalitas, bukan dalam fragmen-fragmen terpisah. Realitas dianalogikan sebagai bola sempurna, di mana setiap bagian memantulkan bagian lain, sehingga tidak ada yang terlepas dari keseluruhan. Bahkan kontradiksi sekalipun tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai motor yang mendorong perkembangan menuju kesatuan yang lebih tinggi. Dengan cara ini, filsafat Hegel menjadi dinamis, progresif, dan teleologis.
Melalui logika dialektisnya, Hegel memperlihatkan bahwa realitas tidak statis, melainkan selalu dalam proses. Dari kategori Being yang identik dengan Nothing, lahirlah Becoming sebagai perpaduan keduanya (hal. 185). Pola ini kemudian menjadi model bagi seluruh perkembangan konsep dalam sistem Hegel. Setiap konsep mengandung kontradiksi internal yang mendorong lahirnya konsep baru, hingga akhirnya menuju totalitas. Dengan logika semacam ini, Hegel berhasil menyusun sebuah filsafat yang bukan hanya teori tentang pikiran, melainkan juga teori tentang realitas itu sendiri.
Struktur dialektika juga diterapkan pada kesadaran manusia. Dari kesadaran yang melihat objek sebagai sesuatu yang terpisah, menuju kesadaran-diri yang menemukan identitas dengan objek, hingga akal yang menyatukan subjek dan objek dalam totalitas (hal. 188). Proses ini menunjukkan bagaimana roh manusia bergerak menuju pengetahuan absolut, di mana pikiran akhirnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Dengan demikian, dialektika kesadaran menjadi jalan menuju idealisme absolut, di mana realitas dan rasio identik sepenuhnya.
Lebih jauh, Hegel memperluas dialektika ke dalam ruang sosial dan sejarah melalui konsep roh obyektif. Sejarah dunia dipahami sebagai perjalanan roh menuju kesadaran kebebasan. Dari dunia Oriental yang hanya mengenal kebebasan seorang despot, ke dunia Yunani yang memberikan kebebasan bagi sebagian warga, hingga dunia Germanik yang mengakui kebebasan semua orang (hal. 188). Sejarah, bagi Hegel, bukan kebetulan, melainkan logika rasional yang bekerja di balik peristiwa-peristiwa manusia.
Kebebasan akhirnya menjadi inti dari seluruh filsafat Hegel. Namun, kebebasan bukan berarti bebas dari hukum atau batasan, melainkan kebebasan untuk menentukannya sendiri sesuai dengan prinsip rasional universal. “Freedom is not absence of constraint but acting from self-determination” (hal. 188). Dalam komunitas organik, hukum dan negara menjadi ekspresi tertinggi dari kebebasan, karena keduanya mewujudkan prinsip-prinsip universal yang memungkinkan individu menemukan dirinya di dalam keseluruhan. Dengan demikian, kebebasan sejati hanya dapat dicapai dalam kehidupan bersama yang rasional.
Warisan filsafat Hegel yang dipaparkan Shand adalah sebuah sistem yang menghubungkan logika, kesadaran, sejarah, dan kebebasan ke dalam satu totalitas. Filsafatnya menunjukkan bahwa realitas adalah rasional, bahwa kontradiksi adalah jalan menuju perkembangan, dan bahwa kebebasan adalah inti dari eksistensi manusia. Hingga kini, sistem Hegel tetap menjadi rujukan penting dalam filsafat, baik sebagai inspirasi maupun sebagai sasaran kritik. Apa yang ditawarkan Hegel adalah keberanian untuk berpikir menyeluruh, untuk melihat dunia sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kesadaran penuh tentang kebebasan.

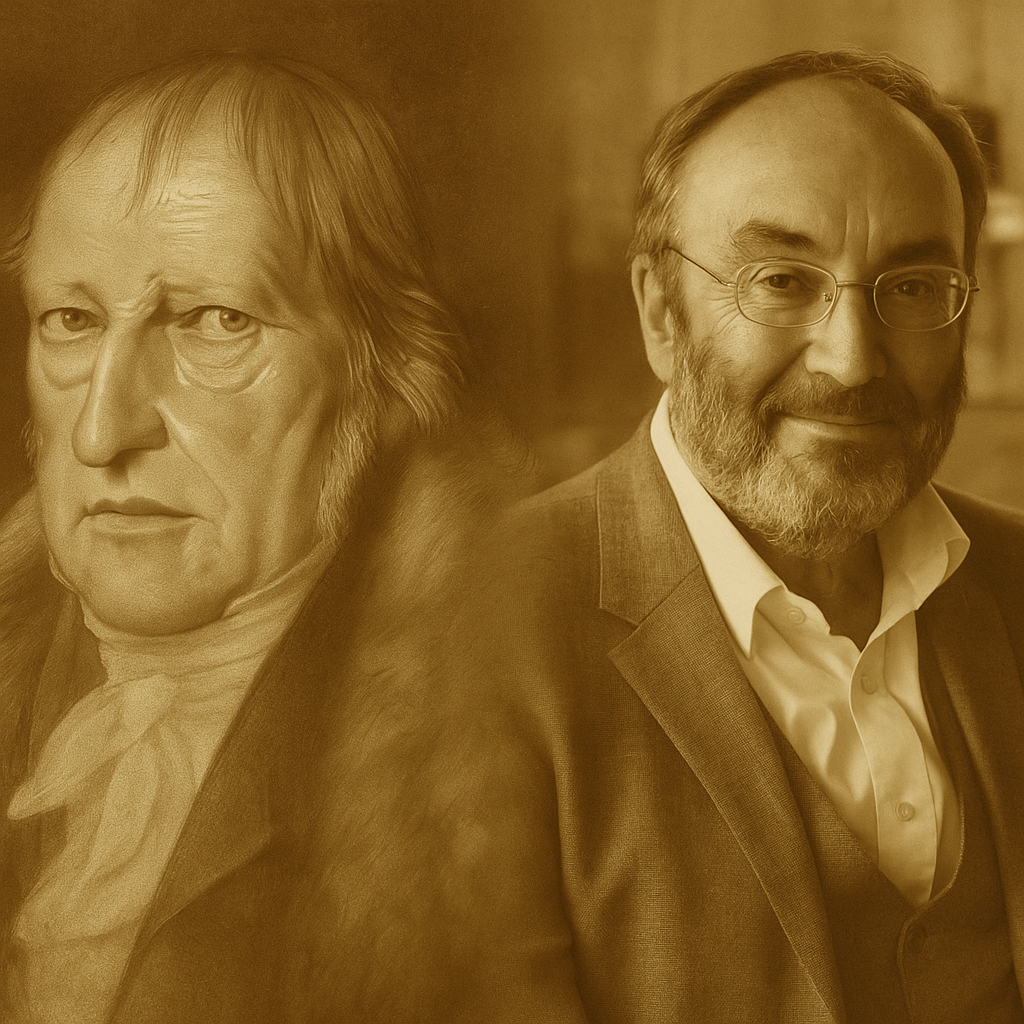

Leave a Reply