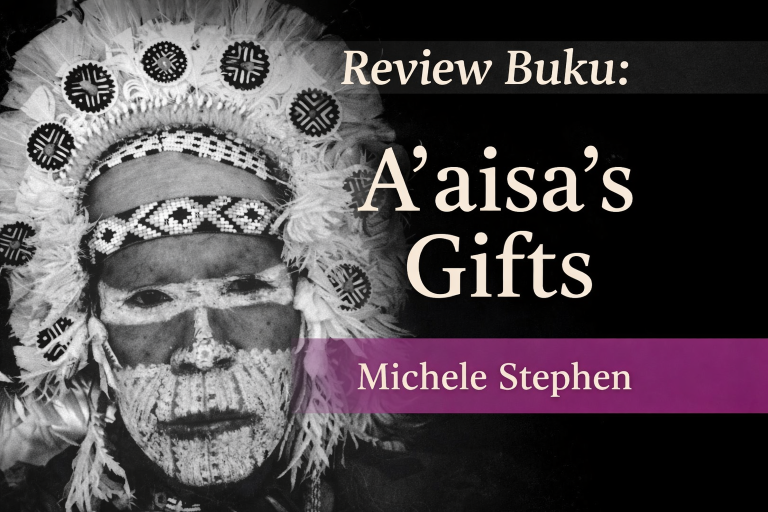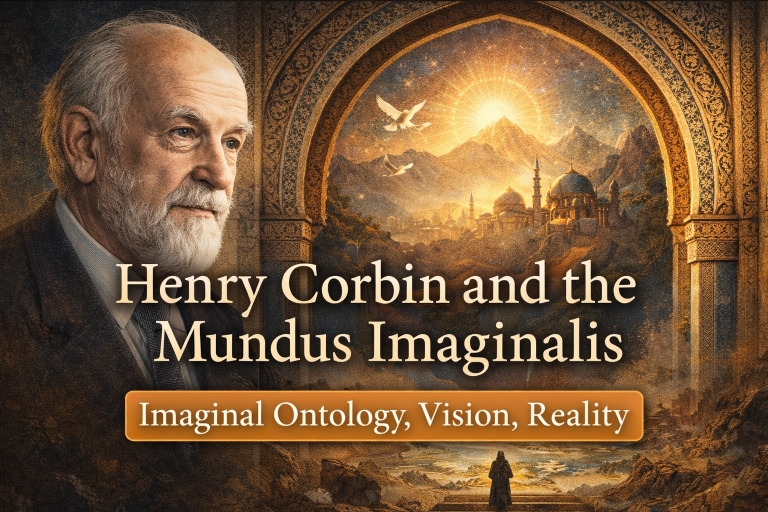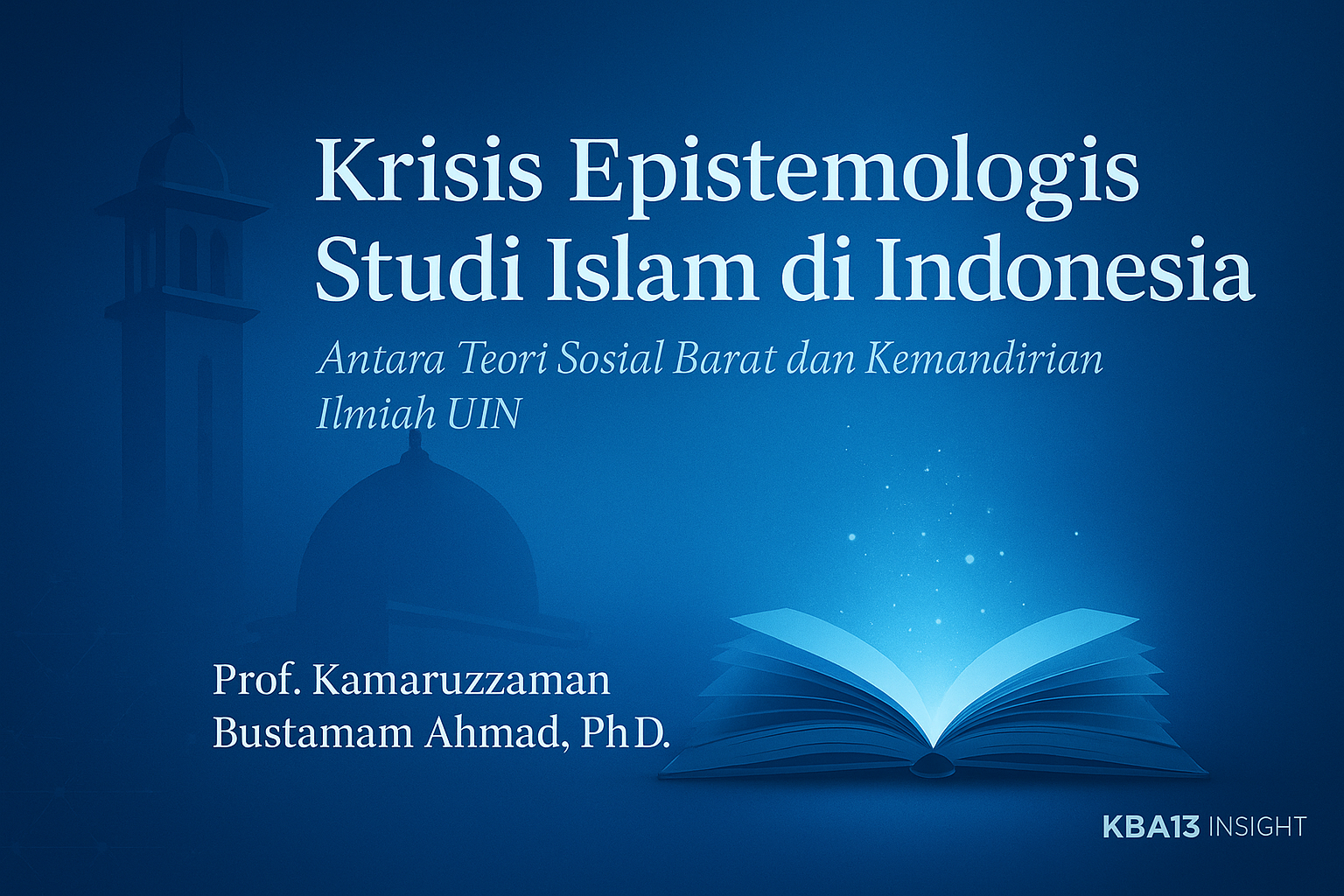
Krisis Epistemologis Studi Islam di Indonesia
Pendahuluan: Ketika Islam Dipahami dari Kacamata Orang Lain
Sejak dekade 1970-an, kampus Islam di Indonesia seperti IAIN dan UIN menjadi ruang pertemuan antara dunia ilmu agama dan ilmu sosial. Di masa itu, muncul semangat baru untuk memahami agama bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai konteks sosial. Pergeseran ini tidak muncul dalam ruang kosong; ia dipicu oleh proyek-proyek modernisasi pendidikan Islam yang didorong oleh kerja sama internasional. Para sarjana muda Indonesia mulai berkenalan dengan teori-teori sosial dari Barat seperti Weberianisme, Marxisme, dan strukturalisme. Dari sinilah terbentuk pandangan bahwa agama dapat dijelaskan melalui metodologi ilmiah yang netral dan empiris.
Namun, yang disebut netralitas ilmiah tersebut ternyata memiliki bias ideologis tersendiri. Ilmu sosial yang datang dari Barat dibangun atas sejarah panjang sekularisasi dan kritik terhadap institusi agama Kristen. Ketika paradigma itu diimpor ke dunia Islam, terjadi ketegangan epistemologis yang tak terhindarkan. Islam yang semula dipahami sebagai panduan hidup spiritual berubah menjadi objek analisis sosial yang seolah dapat diukur, diklasifikasikan, dan dievaluasi dengan instrumen empiris. Dengan cara demikian, posisi peneliti ditempatkan lebih tinggi daripada realitas umat yang ditelitinya.
Paradigma baru ini membawa dampak mendalam bagi arah studi Islam. Ia memang memperkaya perspektif metodologis, tetapi sekaligus menjauhkan keilmuan Islam dari akar spiritual dan etisnya. Banyak penelitian yang tampak canggih dalam teori, tetapi hampa dalam dimensi nilai. Umat Islam digambarkan sebagai masyarakat yang “bermasalah,” bukan sebagai komunitas yang sedang berproses menuju kesempurnaan iman. Dalam konteks ini, teori sosial Barat menjadi sejenis lensa yang mengubah wajah Islam agar tampak sesuai dengan logika modernitas sekuler.
Proses tersebut memperlihatkan dinamika kompleks antara adaptasi dan subordinasi. Di satu sisi, para akademisi Islam berusaha menyesuaikan diri dengan standar akademik global; di sisi lain, mereka sering kali kehilangan keberanian untuk mempertahankan fondasi epistemologi Islam. Akibatnya, penelitian yang dilakukan di kampus Islam lebih sering mengulang pola pikir Barat ketimbang melahirkan perspektif keislaman yang orisinal. Hal ini memperlemah posisi studi Islam di Indonesia dalam percakapan intelektual global karena tidak lagi memiliki keunikan epistemik.
Kondisi ini juga berimplikasi pada orientasi pendidikan tinggi Islam secara umum. Mahasiswa lebih diarahkan untuk “menguasai teori” ketimbang “menemukan makna.” Mereka didorong menjadi pengulas teori Barat, bukan pembangun teori Islam. Akibatnya, generasi baru ilmuwan Islam tumbuh dengan mentalitas kutipan: mereka mampu menyebut nama-nama besar, tetapi tidak mampu menemukan hubungan antara teori dan iman. Fenomena ini melahirkan jurang antara ilmu dan kesadaran spiritual.
Lebih dari sekadar masalah metodologis, ini merupakan krisis kesadaran diri umat Islam dalam ranah keilmuan. Ketika umat memandang diri mereka melalui kacamata orang lain, yang tampak hanyalah citra yang terdistorsi. Islam yang semula menjadi sumber nilai berubah menjadi objek kajian yang harus “dibedah” secara ilmiah. Pengetahuan pun kehilangan sifatnya sebagai jalan menuju kebenaran (al-haqq), dan bergeser menjadi sekadar instrumen analisis sosial.
Oleh karena itu, penting bagi generasi baru akademisi Islam untuk meninjau ulang hubungan antara teori, spiritualitas, dan realitas. Ilmu sosial dan humaniora tidak harus ditolak, tetapi perlu ditafsir ulang dalam bingkai nilai Islam. Hanya dengan cara itu studi Islam akan kembali pada fitrahnya: menjelaskan kehidupan tanpa kehilangan arah menuju Tuhan.
Universitas Islam dan Kecenderungan Kanan: Pusat Gerakan yang Disalahpahami
Isu tentang “gerakan Islam kanan” sering kali muncul dari penelitian akademik yang lahir di lingkungan kampus Islam itu sendiri. Sebutan “kanan” biasanya dipakai untuk mengklasifikasikan gerakan yang dianggap terlalu normatif, eksklusif, atau politis. Padahal, istilah tersebut tidak lahir dari pengalaman Islam, melainkan dari spektrum ideologi Barat pasca-Revolusi Prancis. Ketika label ini diterapkan ke konteks Indonesia tanpa penyesuaian epistemologis, muncul kesalahpahaman besar terhadap gerakan Islam lokal.
Di sejumlah kampus, gerakan mahasiswa yang menekankan ketaatan syariah atau aktivitas dakwah sering dicap sebagai “konservatif.” Padahal, fenomena itu tidak selalu berarti penolakan terhadap modernitas. Ia sering kali merupakan bentuk ekspresi religius yang lahir dari kegelisahan moral terhadap sekularisasi. Dalam banyak kasus, mahasiswa Islam yang aktif dalam kegiatan dakwah justru sedang mencari makna keislaman di tengah arus global yang serba cair. Namun, dalam pandangan sebagian akademisi, mereka dianggap mengancam “kebebasan berpikir.”
Labelisasi ini bukan hanya persoalan terminologi, tetapi juga bentuk kekuasaan epistemik. Dengan memakai kerangka teori Barat, peneliti memegang kendali atas definisi “normal” dan “abnormal.” Islam yang taat terhadap teks dianggap rigid, sementara Islam yang kompromistis dianggap progresif. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa teori sosial yang diadopsi masih membawa beban ideologis dari konteks asalnya. Akibatnya, studi tentang gerakan Islam lebih sering menjadi arena reproduksi stereotip daripada ruang pemahaman yang objektif.
Fenomena ini diperparah oleh lemahnya refleksi kritis di lingkungan akademik Islam. Banyak peneliti mengikuti arus dominan agar mudah diterima secara akademik. Mereka enggan mempertanyakan sumber bias yang terkandung dalam teori yang mereka gunakan. Dalam situasi seperti ini, muncul “kecanggihan metodologis” tanpa kedalaman makna. Penelitian tampak ilmiah, tetapi sebenarnya kehilangan ruh keilmuan yang sejati.
Jika ditelusuri, kesalahpahaman terhadap gerakan Islam juga muncul karena kegagalan memahami pengalaman spiritual para anggotanya. Setiap gerakan Islam memiliki dimensi batiniah yang sulit dijangkau oleh analisis rasional semata. Di sinilah pentingnya pendekatan empatik dan fenomenologis—melihat dari dalam, bukan menilai dari luar. Tanpa itu, penelitian hanya menghasilkan jarak antara peneliti dan objeknya.
Selain itu, muncul pula ketegangan antara peneliti dan masyarakat Muslim sendiri. Dalam banyak seminar, peneliti dari kampus Islam dipandang curiga oleh masyarakat karena dianggap membawa agenda tertentu. Ketidakpercayaan ini lahir dari pengalaman panjang di mana penelitian sering menghasilkan stigma. Jika akademisi tidak mampu mengembalikan penelitian sebagai ruang dialog, bukan penghakiman, maka jurang antara kampus dan umat akan semakin melebar.
Maka, membicarakan “gerakan kanan” tanpa memahami konteks spiritual dan sosialnya adalah bentuk ketidakadilan ilmiah. Kampus Islam seharusnya menjadi jembatan pemahaman, bukan sumber labelisasi. Jika penelitian diorientasikan pada pemahaman yang lebih empatik, maka studi Islam akan kembali menjadi wadah dialog antara akal dan iman.
Ketergantungan terhadap Teori Sosial Barat
Dalam dunia akademik kampus Islam, kemampuan mengutip nama-nama besar dari Barat sering dianggap sebagai tanda intelektualitas. Fenomena ini menimbulkan budaya ilmiah yang lebih menghargai kerumitan teoretis daripada kedalaman makna. Nama seperti Bourdieu, Foucault, dan Giddens menjadi jimat akademik yang menjamin “keabsahan ilmiah.” Namun di balik kekaguman ini tersembunyi krisis kemandirian intelektual. Teori-teori yang semula dirancang untuk menjelaskan masyarakat sekuler justru digunakan untuk menilai umat Islam yang memiliki sistem nilai berbeda.
Ketika teori sosial Barat digunakan tanpa pemahaman filosofis, penelitian kehilangan arah ontologisnya. Data lapangan dipaksa mengikuti struktur teori, bukan sebaliknya. Hasilnya adalah penelitian yang kaya data tetapi miskin penemuan. Banyak skripsi, tesis, dan disertasi di lingkungan kampus Islam berhenti pada tataran deskriptif-analitik karena teori dijadikan pagar yang membatasi imajinasi akademik. Dengan kata lain, ilmu sosial diperlakukan sebagai dogma baru, bukan alat dialog.
Masalah lain muncul ketika peneliti enggan melakukan kritik epistemologis terhadap teori yang digunakan. Mereka merasa cukup dengan “mengislamkan teori” melalui kutipan ayat atau hadis di bagian penutup penelitian. Upaya semacam ini tampak sebagai kompromi, padahal sesungguhnya ia mengukuhkan dominasi epistemik Barat. Islam hanya ditempatkan sebagai legitimasi moral, bukan sumber pengetahuan alternatif.
Ketergantungan terhadap teori luar juga menyebabkan proses pendidikan di kampus Islam menjadi sangat teoritis, namun tidak kontekstual. Mahasiswa belajar teori sosiologi agama, tetapi jarang berdialog dengan realitas sosial umat di sekitarnya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa ilmu harus tumbuh dari pengalaman dan penghayatan. Ketika ilmu dipisahkan dari kehidupan, ia kehilangan daya ubahnya. Inilah yang membuat banyak penelitian Islam terasa asing bagi masyarakat Muslim sendiri.
Sikap akademik semacam ini juga memperlemah posisi Indonesia dalam peta global studi Islam. Alih-alih melahirkan konsep baru dari pengalaman keislaman lokal, para peneliti justru menjadi pengikut tren teori global. Padahal, Islam Indonesia memiliki kekayaan sosial dan kultural yang dapat menjadi sumber pembaruan ilmu sosial. Ketika kampus Islam berani menggali nilai-nilai lokal dan spiritualitas masyarakat, akan muncul bentuk teori yang lebih relevan dengan kenyataan umat.
Masalah ini bukan sekadar soal teknik akademik, tetapi soal keberanian berpikir. Kemandirian intelektual tidak akan lahir dari kebiasaan meniru, tetapi dari kemampuan menafsir ulang. Islam menekankan pentingnya ijtihad sebagai ekspresi kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Jika semangat ijtihad diterapkan dalam riset sosial, maka teori tidak lagi menjadi penjara, melainkan tangga menuju kebijaksanaan.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah penolakan terhadap teori sosial Barat, tetapi reorientasi epistemologis. Peneliti Islam harus mampu menempatkan teori sebagai mitra dialog, bukan sumber kebenaran tunggal. Hanya dengan cara ini, studi Islam dapat berkembang menjadi disiplin yang kritis, mandiri, dan berakar pada nilai-nilai tauhid.
Krisis Meta-Teori dan Kemandekan Intelektual
Salah satu kelemahan paling mendasar dalam perkembangan studi Islam di Indonesia terletak pada absennya refleksi meta-teoretik. Meta-teori tidak hanya berarti kemampuan memilih teori, tetapi juga kemampuan memahami asumsi ontologis dan epistemologis yang melandasinya. Banyak penelitian di kampus Islam mengadopsi teori-teori sosial Barat tanpa meninjau ulang konteks kemunculannya. Padahal, setiap teori lahir dari pergulatan sejarah dan nilai yang spesifik. Ketika teori itu dipindahkan ke dunia Islam tanpa kritik, maka yang terjadi bukan dialog, melainkan kolonisasi pengetahuan yang halus.
Krisis meta-teori ini menyebabkan proses keilmuan di kampus Islam terjebak pada rutinitas metodologis. Peneliti sibuk mengumpulkan data, menganalisis variabel, dan menulis kesimpulan tanpa pernah bertanya: “mengapa saya menggunakan teori ini?” dan “dari mana asumsi ini lahir?”. Akibatnya, ilmu kehilangan arah filosofisnya. Ia hanya menjadi alat teknis untuk memenuhi standar akademik. Di sinilah terlihat bahwa riset Islam telah tergelincir ke dalam positivisme sempit, yang mengukur keberhasilan penelitian dari kelengkapan format, bukan kedalaman makna.
Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, ilmu tidak dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Para ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, dan Al-Farabi memahami ilmu sebagai sarana kontemplasi menuju kebenaran ilahiah. Proses berpikir (tafakkur) dan perenungan (tadabbur) adalah bagian dari perjalanan ruhani seorang peneliti. Namun dalam konteks kampus Islam modern, tradisi ini perlahan menghilang. Meta-teori digantikan dengan logika administratif. Penelitian tidak lagi menjadi ibadah intelektual, melainkan kewajiban birokratis demi akreditasi dan publikasi.
Fenomena ini juga memperlihatkan ketegangan antara tradisi ilmiah Islam dan orientasi akademik global. Di satu sisi, kampus Islam ingin diakui secara internasional dengan mengikuti standar sains modern; di sisi lain, ia kehilangan keotentikan epistemologisnya. Akibatnya, muncul bentuk “ilmu yang setengah matang”: tampak ilmiah di permukaan, tetapi rapuh dalam pondasi filosofis. Ilmu yang seharusnya memerdekakan justru menjadi alat subordinasi terhadap paradigma Barat.
Kemandekan intelektual ini tampak nyata dalam kurangnya upaya teorisasi di lingkungan kampus Islam. Sebagian besar penelitian berhenti pada tataran deskriptif, tanpa menjangkau wilayah reflektif dan normatif. Padahal, dari data yang kaya, semestinya dapat lahir teori-teori baru tentang masyarakat Muslim, spiritualitas, dan perubahan sosial. Ketika proses ini tidak terjadi, berarti ada yang salah dalam sistem berpikir ilmiah kita. Krisis meta-teori tidak hanya merugikan ilmu, tetapi juga melemahkan daya kreatif bangsa.
Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan keberanian epistemik untuk melakukan kritik terhadap teori dan membangun sintesis baru. Dialog antara ilmu sosial dan teologi Islam harus dilakukan secara sejajar, bukan subordinatif. Artinya, nilai-nilai Islam tidak boleh hanya menjadi “pemanis” moral dalam penelitian, tetapi harus menjadi sumber refleksi teoretis yang hidup. Ketika peneliti mampu memadukan analisis empiris dengan kedalaman spiritual, di sanalah ilmu Islam akan menemukan kembali jati dirinya.
Maka, kemandekan intelektual yang kini kita saksikan bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan epistemologis yang keliru. Selama penelitian hanya berfungsi menjelaskan data tanpa menafsirkan makna, selama teori lebih diagungkan daripada wahyu, maka ilmu tidak akan melahirkan kebijaksanaan. Saatnya kampus Islam menegakkan kembali tradisi theoria — kontemplasi ilmiah yang memadukan rasionalitas dan spiritualitas dalam satu kesadaran tauhid.
Data yang Kaya, Tapi Gagasan yang Mandul
Salah satu ironi terbesar dalam studi Islam di Indonesia adalah melimpahnya data empiris yang tidak berujung pada penemuan gagasan baru. Setiap tahun, ribuan mahasiswa dan dosen melakukan penelitian tentang berbagai aspek kehidupan umat Islam — dari ritual, ekonomi, hingga politik. Namun, hasilnya sering kali berhenti pada deskripsi yang datar. Data memang kaya, tetapi teori yang dihasilkan lemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelebihan kuantitatif belum tentu berarti kemajuan kualitatif dalam ilmu.
Masalahnya bukan pada kekurangan data, melainkan pada cara pandang terhadap data itu sendiri. Banyak peneliti memperlakukan data sebagai bahan untuk membuktikan teori, bukan untuk menemukan kebenaran baru. Padahal, dalam tradisi ilmu Islam, data atau fakta lapangan dipandang sebagai ayat kauniyah — tanda-tanda Tuhan di alam semesta yang harus direnungkan. Jika peneliti tidak memiliki kesadaran spiritual terhadap data, maka yang tersisa hanyalah angka, tabel, dan kutipan.
Dalam berbagai seminar akademik, sering muncul pemandangan serupa: peneliti menyajikan data lapangan, lalu para pengulas memaksanya untuk menyesuaikan dengan teori yang sedang populer. Di sinilah orisinalitas ilmiah hilang. Peneliti tidak berani menantang teori yang digunakan, karena takut dianggap “tidak ilmiah.” Akibatnya, penelitian Islam menjadi repetitif dan tidak melahirkan pembaruan paradigma. Ilmu sosial yang seharusnya terbuka terhadap realitas, justru berubah menjadi pagar bagi kebebasan berpikir.
Fenomena ini juga memperlihatkan hubungan yang timpang antara teori dan empiri. Seharusnya teori tumbuh dari refleksi terhadap data, bukan sebaliknya. Ketika teori didudukkan sebagai otoritas, maka data lapangan kehilangan suaranya. Padahal, realitas umat Islam di Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai spiritual yang unik. Jika peneliti berani mendengarkan “suara data,” maka akan muncul teori-teori baru yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Muslim Nusantara.
Kemandulan gagasan juga disebabkan oleh ketidakberanian akademisi untuk keluar dari pola pikir linear. Dalam banyak disertasi dan jurnal, struktur penelitian terasa monoton: latar belakang, teori, metode, hasil, dan kesimpulan. Hampir tidak ada ruang untuk refleksi, permenungan, atau improvisasi gagasan. Padahal, sejarah keilmuan Islam membuktikan bahwa kemajuan hanya lahir dari keberanian menafsir ulang dan melampaui batas-batas konvensional.
Masalah lainnya adalah absennya dimensi spiritual dalam proses penelitian. Ketika peneliti tidak melihat hubungan antara pekerjaannya dengan ibadah intelektual, maka penelitian hanya menjadi tugas administratif. Data dikumpulkan bukan untuk memahami, tetapi untuk memenuhi kewajiban akademik. Dengan cara demikian, ilmu kehilangan ruhnya. Islam memandang ilmu sebagai jalan menuju kesempurnaan jiwa (tazkiyah), bukan sekadar alat karier.
Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memahami hubungan antara data dan teori. Penelitian Islam harus berani melampaui deskripsi menuju kontemplasi. Data tidak boleh berhenti sebagai “pajangan empiris,” tetapi harus menjadi bahan perenungan yang memunculkan gagasan baru. Jika ini dilakukan, maka kampus Islam tidak hanya menjadi gudang data, tetapi juga mercusuar ilmu pengetahuan.
Studi Gerakan Islam: Dari Empati ke Stigmatisasi
Krisis epistemologis dalam studi gerakan Islam terlihat paling jelas pada hilangnya empati akademik. Banyak penelitian memperlakukan gerakan Islam sebagai objek eksotis yang harus dijelaskan, bukan sebagai ekspresi spiritual yang harus dipahami. Istilah seperti “radikal,” “konservatif,” atau “militan” sering digunakan tanpa konteks sejarah dan teologis yang memadai. Akibatnya, gerakan Islam dilihat dari luar, bukan dari dalam.
Dalam banyak penelitian, pendekatan yang digunakan cenderung reduktif. Aspek teologis dan moral gerakan Islam diabaikan, sementara aspek sosial-politiknya diperbesar. Gerakan yang berorientasi dakwah sering digambarkan sebagai ancaman terhadap demokrasi, padahal mereka lahir dari kegelisahan moral terhadap modernitas yang sekuler. Ketika penelitian kehilangan empati, maka hasilnya bukan pengetahuan, melainkan stigmatisasi.
Padahal, Islam mengajarkan bahwa memahami orang lain adalah bagian dari akhlak ilmiah. Peneliti tidak boleh menghakimi sebelum memahami konteks. Dalam pendekatan sufistik, ilmu diperoleh bukan hanya dengan observasi, tetapi juga dengan penyaksian batin (syuhud). Jika dimensi ini dihidupkan dalam studi gerakan Islam, maka akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang makna perjuangan, pengorbanan, dan keimanan dalam dinamika sosial.
Fenomena stigmatisasi ini juga memperlihatkan bias epistemik dari teori yang digunakan. Banyak konsep yang diambil dari pengalaman Eropa modern, di mana agama dianggap penghambat kemajuan. Ketika konsep ini diterapkan pada Islam, hasilnya adalah distorsi. Gerakan Islam dipaksa untuk sesuai dengan kategori “progresif” atau “reaksioner.” Padahal, dalam realitasnya, banyak gerakan Islam berfungsi sebagai kekuatan moral yang menjaga integritas masyarakat.
Selain itu, ketiadaan empati juga menyebabkan jarak antara peneliti dan masyarakat Muslim semakin lebar. Penelitian yang seharusnya menjadi jembatan dialog justru menjadi sumber ketegangan. Umat merasa diteliti, bukan diajak berbicara. Peneliti merasa netral, padahal ia membawa bias epistemik dari teori yang digunakannya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka studi Islam akan kehilangan kepercayaan publik.
Empati dalam penelitian bukan berarti kehilangan objektivitas, tetapi menemukan dimensi kemanusiaan dalam ilmu. Peneliti yang mampu menggabungkan nalar dan nurani akan menghasilkan karya yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menyentuh. Islam menempatkan ilmu dan rahmah sebagai dua sisi dari satu koin: pengetahuan yang sejati selalu mengantarkan kepada kasih sayang, bukan kecurigaan.
Dengan demikian, pembaruan studi gerakan Islam harus dimulai dari rekonstruksi kesadaran peneliti. Teori sosial harus dijadikan alat untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Ketika empati dikembalikan ke dalam disiplin ilmu, penelitian akan berubah menjadi jembatan spiritual antara peneliti dan realitas. Dari sinilah lahir ilmu yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menyembuhkan.
Keberanian Melawan Arus: Kritis terhadap Diri Sendiri dan Teori
Kemandirian ilmiah tidak mungkin lahir tanpa keberanian melawan arus. Dalam dunia akademik Islam, keberanian semacam ini sering kali dianggap “berbahaya” karena berpotensi mengguncang kenyamanan sistem yang mapan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap pembaruan ilmu selalu dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan asumsi lama. Dalam konteks studi Islam, keberanian ini berarti berani mengkritik teori Barat dan sekaligus berani mengoreksi cara berpikir sendiri.
Keberanian ilmiah bukan berarti penolakan total terhadap teori luar. Islam tidak anti-ilmu. Yang ditolak adalah mentalitas taklid epistemologis — sikap tunduk tanpa berpikir. Peneliti yang kritis justru harus mampu berdialog dengan teori Barat untuk menemukan titik temu yang adil. Dalam tradisi Islam, dialog semacam ini disebut muhaasabah al-‘ilm — evaluasi diri ilmiah yang melahirkan kebijaksanaan. Di sinilah letak tanggung jawab intelektual seorang ilmuwan Muslim.
Sayangnya, keberanian seperti ini masih langka di kampus Islam. Banyak peneliti lebih memilih aman: mengikuti teori yang sedang populer agar mudah diterima oleh jurnal bereputasi. Mereka lupa bahwa reputasi sejati bukan berasal dari akreditasi, tetapi dari kontribusi pemikiran. Ilmuwan sejati bukan pengikut tren, melainkan pencipta arah baru bagi peradaban ilmu. Dalam konteks ini, keberanian menjadi nilai spiritual yang menghidupkan intelektualitas.
Sikap kritis juga harus diarahkan kepada diri sendiri. Peneliti yang jujur tidak hanya meneliti orang lain, tetapi juga meneliti kesadarannya sendiri. Ia harus bertanya: apakah penelitiannya lahir dari pencarian kebenaran, atau sekadar memenuhi tuntutan karier? Dalam refleksi seperti ini, muncul kesadaran bahwa penelitian sejati selalu bersifat transformasional — ia mengubah peneliti menjadi manusia yang lebih sadar dan rendah hati.
Dialog epistemologis antara Islam dan Barat juga harus dilakukan secara proporsional. Barat memiliki kekuatan dalam analisis sosial, sementara Islam memiliki kedalaman spiritual dan moral. Ketika dua kekuatan ini bertemu secara setara, akan lahir paradigma ilmu yang baru: rasional sekaligus ruhani. Inilah bentuk ilmu yang tidak sekadar menjelaskan dunia, tetapi juga menuntun manusia untuk hidup lebih bermakna.
Keberanian melawan arus juga berarti berani menulis sesuatu yang tidak populer. Dalam dunia akademik yang dikuasai oleh birokrasi dan kompetisi, tulisan yang berbicara tentang nilai, iman, dan spiritualitas sering dianggap “tidak ilmiah.” Padahal, itulah inti dari keilmuan Islam. Ketika ilmuwan Muslim berani menulis dari nuraninya, ia sedang melanjutkan tradisi hikmah yang menjadi warisan para ulama.
Maka, tugas generasi akademik Islam hari ini bukan hanya melanjutkan penelitian, tetapi juga melanjutkan keberanian. Melawan arus bukan untuk menentang, tetapi untuk memurnikan niat ilmiah. Dengan keberanian yang jernih, kampus Islam akan kembali menjadi tempat lahirnya pemikir independen — mereka yang menulis bukan karena tuntutan, tetapi karena panggilan iman.
Menuju Paradigma Islamik Baru dalam Ilmu Sosial dan Humaniora
Jika peneliti Islam berani keluar dari ketergantungan epistemik dan mengembalikan spiritualitas dalam ilmu, maka akan lahir paradigma baru dalam studi Islam. Paradigma ini tidak menolak teori sosial Barat, tetapi menafsirkannya ulang dalam cahaya tauhid. Ia tidak melihat umat Islam sebagai masalah, melainkan sebagai sumber nilai dan kebijaksanaan. Inilah paradigma Islamik baru yang menempatkan iman dan ilmu dalam hubungan dialogis.
Paradigma ini akan mengubah cara kita memandang penelitian. Penelitian tidak lagi sekadar kegiatan administratif, tetapi ibadah intelektual. Proses riset menjadi jalan tazkiyah al-nafs — penyucian diri — di mana peneliti belajar memahami bukan hanya objek, tetapi juga dirinya. Dengan cara ini, ilmu sosial tidak lagi kering, karena di dalamnya mengalir nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan sebagaimana diajarkan Islam.
Dalam paradigma Islamik, teori tidak bersifat dominatif, melainkan partisipatif. Artinya, peneliti dan masyarakat yang diteliti berada dalam hubungan saling belajar. Penelitian menjadi dialog, bukan monolog. Dengan demikian, hasil riset tidak hanya berguna bagi dunia akademik, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi sumber data. Di sinilah muncul konsep ulama-intelektual — sosok yang memadukan kedalaman ilmu dengan ketulusan amal.
Paradigma ini juga menuntut redefinisi terhadap konsep objektivitas. Objektivitas dalam Islam bukan berarti bebas nilai, melainkan kesetiaan terhadap keadilan dan kebenaran. Seorang peneliti Muslim harus objektif karena ia bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada lembaga atau tren akademik. Dengan kesadaran ini, ilmu menjadi sarana tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar prestasi formal.
Lebih jauh lagi, paradigma Islamik membuka kemungkinan lahirnya teori-teori sosial yang berakar dari pengalaman keislaman lokal. Misalnya, konsep ukhuwah, barakah, dan syura dapat dijadikan dasar bagi teori sosial yang kontekstual dengan masyarakat Muslim. Ketika nilai-nilai Islam dijadikan sumber teori, maka ilmu pengetahuan tidak lagi asing bagi umat. Ia menjadi cermin kehidupan, bukan alat penilaian.
Paradigma baru ini juga mengajak ilmuwan Muslim untuk berpikir lintas disiplin. Ilmu sosial, humaniora, dan teologi harus disatukan dalam satu kesadaran tauhid. Inilah bentuk integrasi ilmu yang sebenarnya, bukan sekadar penggabungan administratif antar-fakultas. Dalam pandangan Islam, ilmu yang sejati adalah ilmu yang mampu menyingkap keteraturan ilahi di balik keragaman fenomena.
Dengan demikian, paradigma Islamik baru bukan sekadar proyek akademik, tetapi gerakan spiritual. Ia memanggil setiap peneliti untuk kembali ke fitrah ilmu: mencari kebenaran dengan rendah hati, menulis dengan kejujuran, dan menyampaikan dengan kasih. Ketika hal ini terwujud, kampus Islam di Indonesia akan menjadi pusat pencerahan — bukan hanya bagi dunia Muslim, tetapi bagi seluruh kemanusiaan.
Penutup: Dari Deskripsi Menuju Transformasi Ilmiah
Krisis epistemologis dalam studi gerakan Islam di Indonesia pada hakikatnya merupakan refleksi dari krisis kesadaran ilmiah di kalangan akademisi Muslim sendiri. Selama beberapa dekade, riset di kampus Islam terjebak dalam logika deskriptif—mencatat, melaporkan, dan mengutip—tanpa keberanian untuk menafsir ulang realitas dengan perspektif spiritual dan intelektual yang mendalam. Ilmu menjadi sekadar rutinitas administratif yang bertujuan memenuhi tuntutan akademik, bukan sarana untuk menemukan kebenaran. Padahal, dalam tradisi Islam, ilmu selalu berfungsi ganda: menjelaskan realitas lahiriah dan menuntun manusia menuju kesadaran batiniah tentang Tuhan.
Kecenderungan ilmuwan Muslim untuk memuja teori dan mengabaikan makna spiritual telah membuat penelitian Islam kehilangan ruh. Data dianggap lebih penting daripada hikmah, metode lebih diagungkan daripada niat, dan hasil riset lebih dihargai daripada proses penyucian diri dalam mencari ilmu. Akibatnya, penelitian yang dihasilkan sering terasa dingin dan steril, tanpa menyentuh aspek kemanusiaan yang menjadi inti dari Islam. Ilmu yang sejati seharusnya mengantarkan manusia kepada kebenaran, bukan sekadar memenuhi standar akademik yang ditetapkan dunia modern.
Transformasi ilmiah menuntut keberanian untuk mengembalikan ilmu kepada nilai dasarnya: mencari kebenaran karena Allah, bukan karena gengsi akademik. Proses ini dimulai dari kesadaran bahwa meneliti, menulis, dan berpikir adalah bagian dari ibadah. Dalam kerangka ini, peneliti tidak lagi melihat dirinya sebagai pengamat yang netral, melainkan sebagai bagian dari realitas yang ia teliti. Ia tidak berdiri di luar umat, melainkan berada di dalam denyut kehidupan umat. Ketika dimensi ini dihidupkan, penelitian akan berubah menjadi perjalanan spiritual yang menghidupkan jiwa peneliti sekaligus memperkaya masyarakat.
Generasi baru akademisi Islam harus berani keluar dari jebakan “peneliti netral” yang kehilangan empati. Mereka perlu membangun kesadaran bahwa riset tentang umat Islam bukanlah sekadar proyek intelektual, tetapi juga proyek kemanusiaan. Setiap teori yang digunakan, setiap data yang dikumpulkan, dan setiap kesimpulan yang ditulis harus menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai, moral, dan keadilan. Dalam Islam, ilmu tidak sah jika tidak membawa manfaat, dan manfaat tertinggi ilmu adalah memperbaiki diri serta masyarakat.
Transformasi ilmiah juga menuntut sistem pendidikan tinggi Islam untuk berubah. Kampus Islam tidak boleh hanya menjadi pabrik gelar dan jurnal, tetapi harus menjadi laboratorium nilai. Mahasiswa dan dosen harus dilatih untuk berpikir reflektif, tidak hanya reproduktif. Proses bimbingan akademik perlu diarahkan untuk menumbuhkan keberanian epistemologis—yakni kemampuan mempertanyakan teori, mengaitkan ilmu dengan iman, dan menemukan hikmah di balik data. Dengan demikian, setiap penelitian akan menjadi kontribusi nyata bagi pembaruan ilmu dan peradaban Islam.
Lebih dari itu, transformasi ilmiah adalah gerakan moral. Ia menuntut peneliti untuk jujur terhadap dirinya sendiri, tidak menulis demi pujian atau popularitas, tetapi demi kebenaran. Dalam dunia yang semakin pragmatis, kejujuran ilmiah menjadi bentuk jihad intelektual yang paling sunyi sekaligus paling mulia. Peneliti yang jujur tidak hanya menulis apa yang dilihatnya, tetapi juga menulis apa yang dirasakannya dalam cahaya iman. Di sinilah peran spiritualitas menjadi penting, karena tanpa iman, ilmu akan kehilangan arah; tanpa integritas, pengetahuan akan kehilangan makna.
Akhirnya, arah baru studi Islam di Indonesia harus bergerak dari deskripsi menuju transformasi. Artinya, penelitian Islam tidak cukup menjelaskan fenomena, tetapi harus mampu mentransformasikan kesadaran. Tugas utama akademisi Muslim bukan sekadar mencatat apa yang terjadi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat theoria—perenungan yang membawa manusia kepada Tuhan. Dengan cara ini, ilmu akan kembali pada fitrahnya: menjadi cahaya yang menuntun manusia memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Inilah misi sejati keilmuan Islam, yang menempatkan pengetahuan bukan hanya di kepala, tetapi juga di hati.