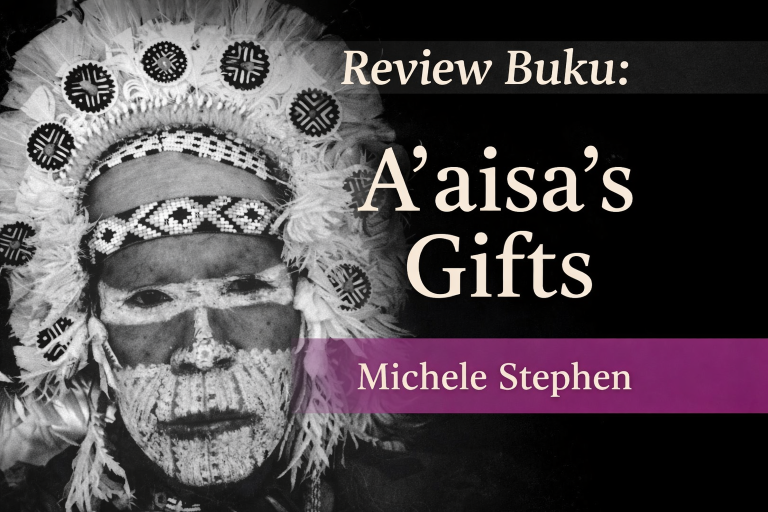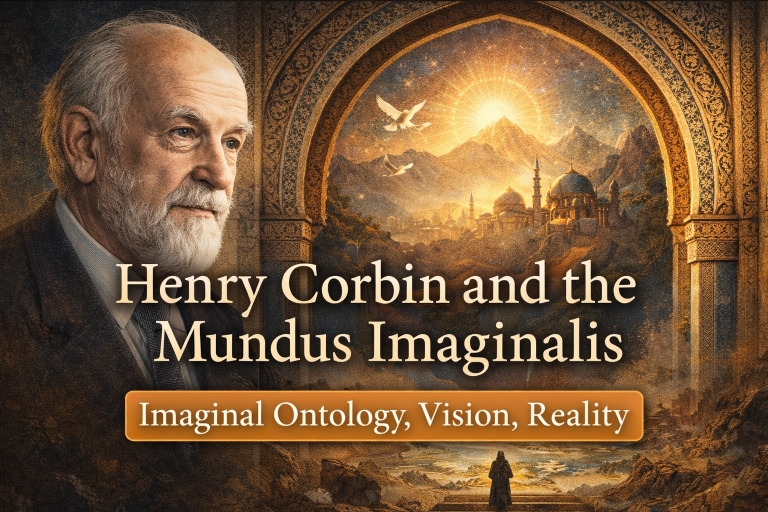Pendahuluan
Aceh selalu hadir sebagai ruang sejarah yang unik, di mana agama, tradisi, dan modernitas berpadu dalam satu panggung sosial. Masyarakat Aceh dikenal religius, tetapi juga kosmopolit, karena sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam wilayah ini menjadi simpul perdagangan internasional, pertukaran budaya, dan persinggahan para ulama (Reid, 2004). Kini, di tengah arus globalisasi abad ke-21, Aceh kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana menjaga identitas lokal tanpa menutup diri dari perubahan global?
Tulisan ini menawarkan lima skenario perkembangan masyarakat Aceh melalui analisis atas tiga konsep: budaya, agama, dan kosmopolitanisme.
Kembali ke Tradisi Lokal dengan Perspektif Global
Tradisi lokal Aceh merupakan harta karun sosial yang terbentuk melalui dialektika panjang antara sejarah, agama, dan bahasa. Sejak dulu, adat laôt, peumulia jamee, hingga seni didong dan rapa’i menjadi identitas yang membedakan Aceh dari kawasan lain. Namun, tradisi ini tidak bisa hanya dipertahankan dalam bentuk puritan, melainkan harus dibaca ulang melalui perspektif global.
Di sinilah konsep glokalisasi relevan. Roland Robertson (1992) memperkenalkan istilah glocalization untuk menggambarkan bagaimana komunitas lokal merespons globalisasi dengan cara yang khas. Jepang, misalnya, tetap mempertahankan tradisi sambil menjadi salah satu kekuatan terdepan dalam ICT (Robertson, 1992). Demikian pula, Korea Selatan menunjukkan kemampuan menjaga nilai budaya lokal sambil memimpin modernisasi (Hannerz, 1992).
Aceh dapat menempuh jalur serupa: menerima kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi menjadikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan adat syura sebagai bingkai. Dengan demikian, tradisi bukan hanya artefak masa lalu, melainkan modal sosial untuk menyongsong masa depan global.
Membangun Paradigma Baru
Perubahan masyarakat tidak selalu datang dari luar; sering kali lahir dari pergeseran cara pandang dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan posisi kamar mandi dalam rumah Aceh adalah contoh sederhana namun filosofis. Dulu, kamar mandi di depan rumah merepresentasikan keterbukaan sosial—tetangga bisa ikut memanfaatkannya, interaksi sosial terjalin alami. Kini, setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi, mencerminkan individualisme yang makin dominan.
Transformasi kecil ini menunjukkan pergeseran paradigma: dari keterikatan sosial menuju privatisasi. Jika paradigma masyarakat terus bergeser pada kenyamanan individual, maka solidaritas sosial akan terkikis. Inilah yang oleh Giddens (2002) disebut sebagai “konsekuensi modernitas” di mana relasi sosial berubah seiring perubahan ruang privat dan publik.
Aceh perlu membangun paradigma baru yang konstruktif dan progresif, di mana agama tidak sekadar simbol, melainkan kekuatan sosial yang merekatkan (Hefner, 2000), dan budaya berfungsi sebagai pengikat identitas kolektif. Paradigma baru ini akan menjadi fondasi untuk melawan isolasi sosial, sekaligus mengembalikan agama dan budaya sebagai poros kehidupan publik.
Mempraktikkan Agama sebagai Kekuatan Sosial
Sejarah Aceh menunjukkan bahwa agama selalu menjadi nadi masyarakat (Azra, 2004). Namun dalam praktik kontemporer, agama sering direduksi pada simbol-simbol hukum dan ritual, sementara fungsinya sebagai kekuatan sosial melemah. Fenomena “Muslim tanpa masjid” adalah kritik tajam bahwa agama hanya dipahami sebagai kewajiban individual, bukan pendorong solidaritas sosial.
Hefner (2000) menekankan bahwa Islam di Indonesia memiliki tradisi kuat dalam membentuk “Islam sipil” yang mendorong demokratisasi dan solidaritas sosial. Inilah yang seharusnya kembali diperkuat di Aceh. Kesuksesan religius tidak diukur dari jumlah jamaah haji atau banyaknya cambuk, melainkan sejauh mana agama menumbuhkan keadilan sosial, kejujuran birokrasi, dan kepedulian pada yang lemah.
Dengan demikian, grounding agama bukanlah pengulangan simbolik, melainkan menghidupkan nilai-nilai agama di sektor pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan. Agama harus kembali menjadi energi yang menyatukan, bukan sekadar alat kontrol.
Kosmopolis Religius
Kosmopolitanisme bukanlah konsep asing bagi Aceh. Pada abad ke-17, Sultan Iskandar Muda menjalin hubungan erat dengan Turki Utsmani, India, hingga Eropa (Reid, 2004). Ulama-ulama Aceh berkelana ke Mekkah, Madinah, dan Kairo, menjadikan Aceh bagian dari jaringan kosmopolitan Islam global (Azra, 2004).
Skenario keempat adalah menghidupkan kembali kosmopolis religius, di mana Aceh bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi juga bagian dari dunia Islam. Kosmopolitanisme yang dimaksud bukanlah sekularisme tanpa batas, melainkan keterbukaan yang berakar pada spiritualitas.
Hannerz (1992) mendefinisikan kosmopolitanisme sebagai keterampilan untuk berinteraksi lintas budaya tanpa kehilangan akar identitas. Dengan modal sejarahnya, Aceh dapat menjadi pusat dialog antaragama dan antarkebudayaan, dengan agama sebagai bingkai inklusif.
Momentum keterlibatan komunitas internasional pasca-tsunami 2004 adalah bukti bahwa Aceh memiliki daya tarik global. Kini, peluang itu harus diubah menjadi agenda strategis: menjadikan Aceh sebagai laboratorium kosmopolitanisme religius, di mana nilai-nilai Islam dipraktikkan dalam semangat menghargai kemanusiaan universal.
Tafsir Agama, Budaya Asing, dan Kosmopolitanisme
Skenario terakhir menegaskan pentingnya membuka ruang tafsir keagamaan yang progresif, menerima budaya asing secara selektif, dan merangkul kosmopolitanisme.
Azra (2004) mencatat bahwa tradisi tafsir keagamaan di dunia Melayu memiliki akar panjang, tetapi kini cenderung melemah. Di Aceh, ulama besar seperti Hasbi ash-Shiddieqy dan Ali Hasjmy pernah menulis karya monumental yang mengintegrasikan budaya dan agama. Namun, generasi setelahnya jarang melanjutkan tradisi intelektual serupa.
Padahal, al-Qur’an sendiri mendorong manusia untuk berpikir kritis (yatafakkarun). Tafsir agama bukanlah menafikan teks, melainkan menghidupkan ruang interpretasi sesuai kebutuhan zaman (Shamsul, 2001).
Selain itu, budaya asing tidak bisa dihindari. Tantangannya adalah bagaimana mengapresiasi budaya global tanpa kehilangan identitas. Di sinilah glokalisasi menjadi strategi: masyarakat menerima teknologi global, tetapi tetap menjaga akar lokal (Robertson, 1992).
Akhirnya, kosmopolitanisme religius adalah jawaban untuk masa depan Aceh. Ia bukan sekadar proyek elit, melainkan agenda kolektif masyarakat untuk menjadi bagian dari komunitas dunia sambil tetap menjaga syariat dan adat.
Penutup
Lima skenario ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh berada di persimpangan besar antara lokalitas dan globalitas, antara religiusitas dan kosmopolitanisme. Pertanyaannya bukan lagi apakah Aceh harus terbuka terhadap globalisasi, melainkan bagaimana Aceh bisa menjadi aktor aktif dalam mengolah globalisasi sesuai dengan nilai-nilainya sendiri.
Aceh pernah menjadi mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara (Reid, 2004). Kini, dengan refleksi kritis terhadap tradisi, agama, dan kosmopolitanisme, Aceh berpeluang menjadi model masyarakat religius kosmopolitan yang relevan bagi dunia kontemporer.
Daftar Pustaka
-
Azra, A. (2004). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
-
Giddens, A. (2002). Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. London: Profile Books.
-
Hannerz, U. (1992). Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning. New York: Columbia University Press.
-
Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.
-
Reid, A. (2004). An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra. Singapore: NUS Press.
-
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications.
-
Shamsul, A. B. (2001). A history of an identity, an identity of a history: The idea and practice of Malayness in Malaysia reconsidered. Journal of Southeast Asian Studies, 32(3), 355–366.