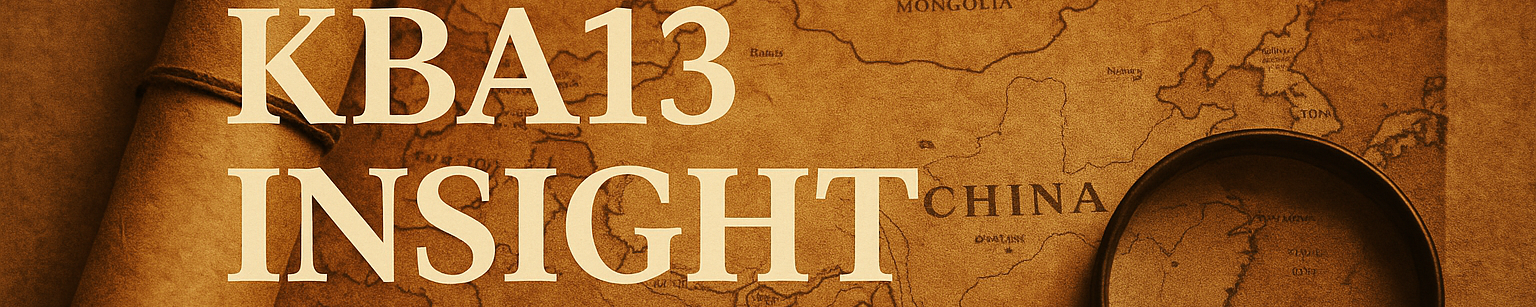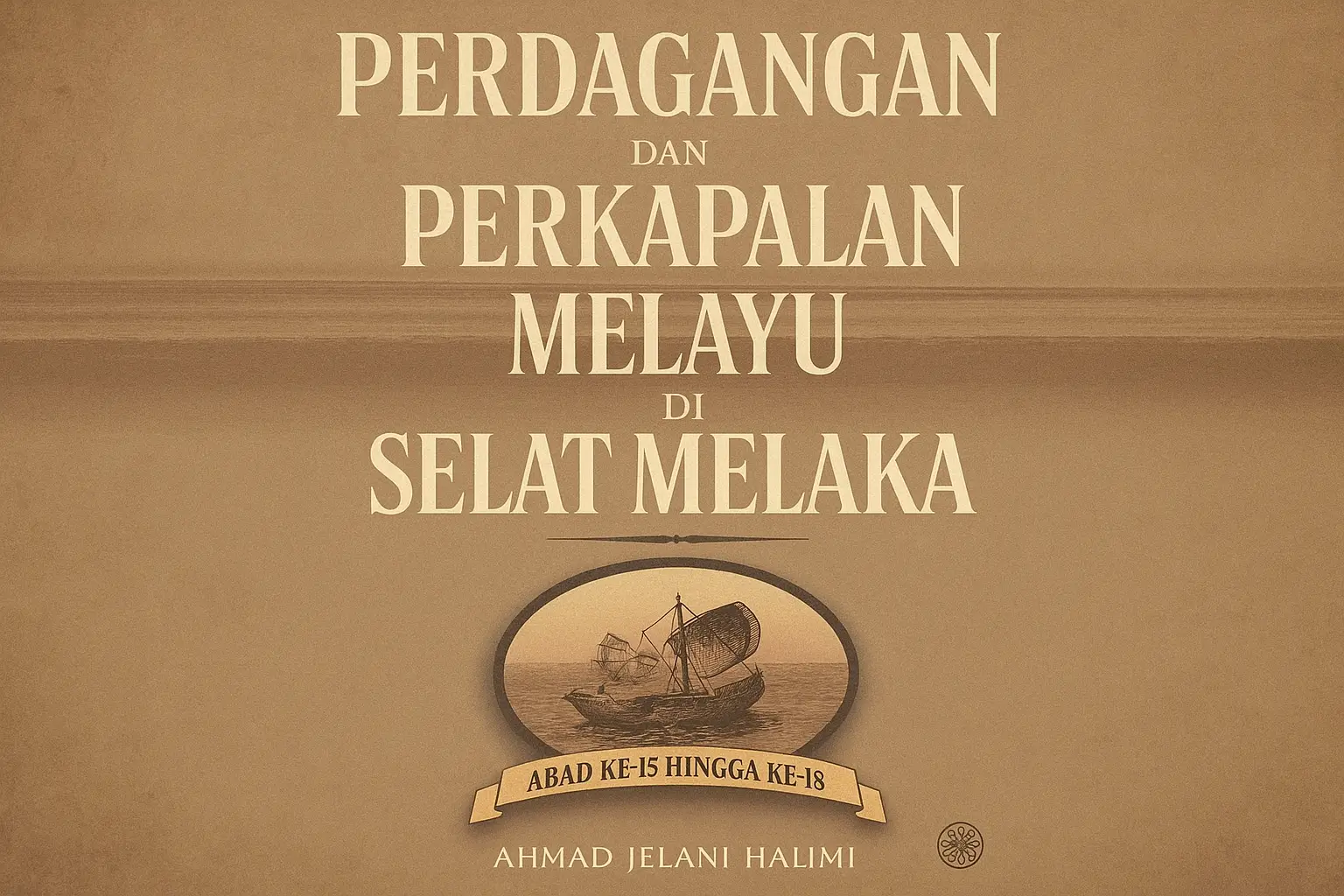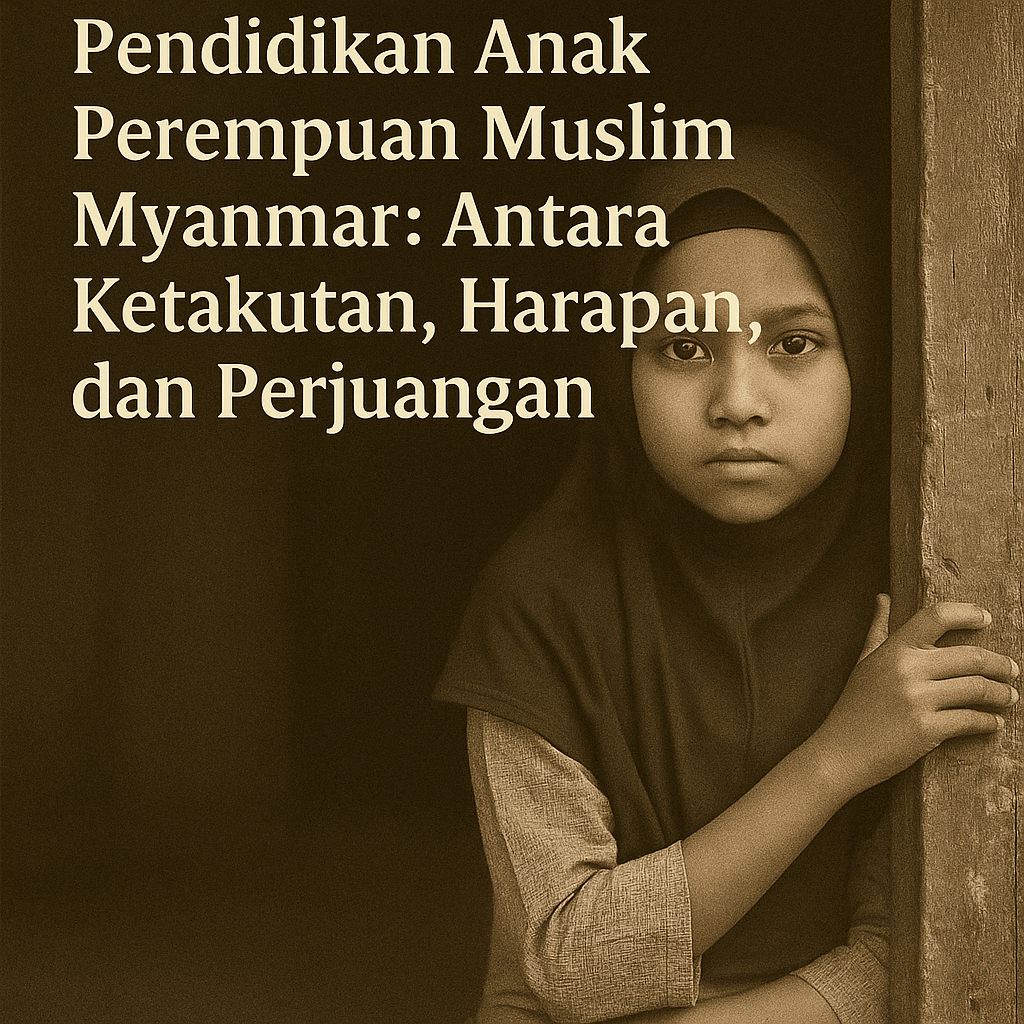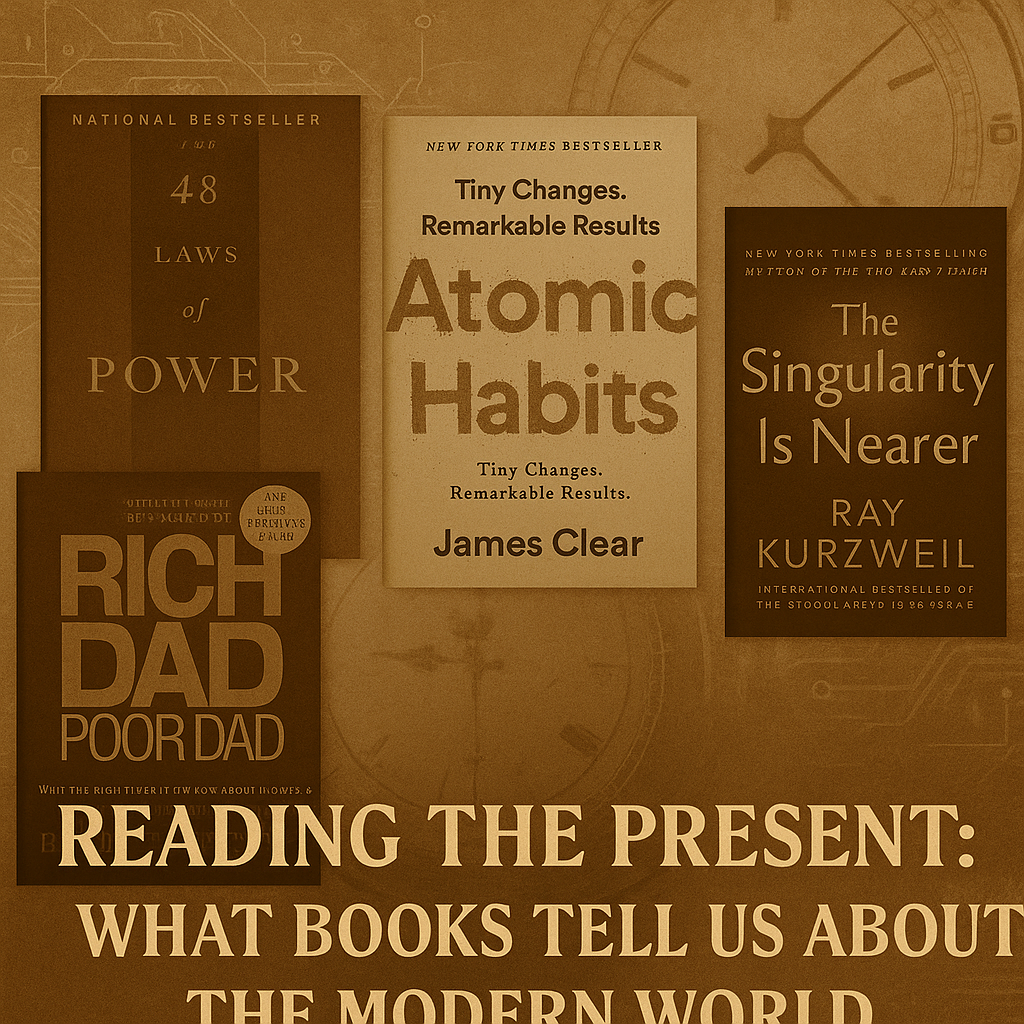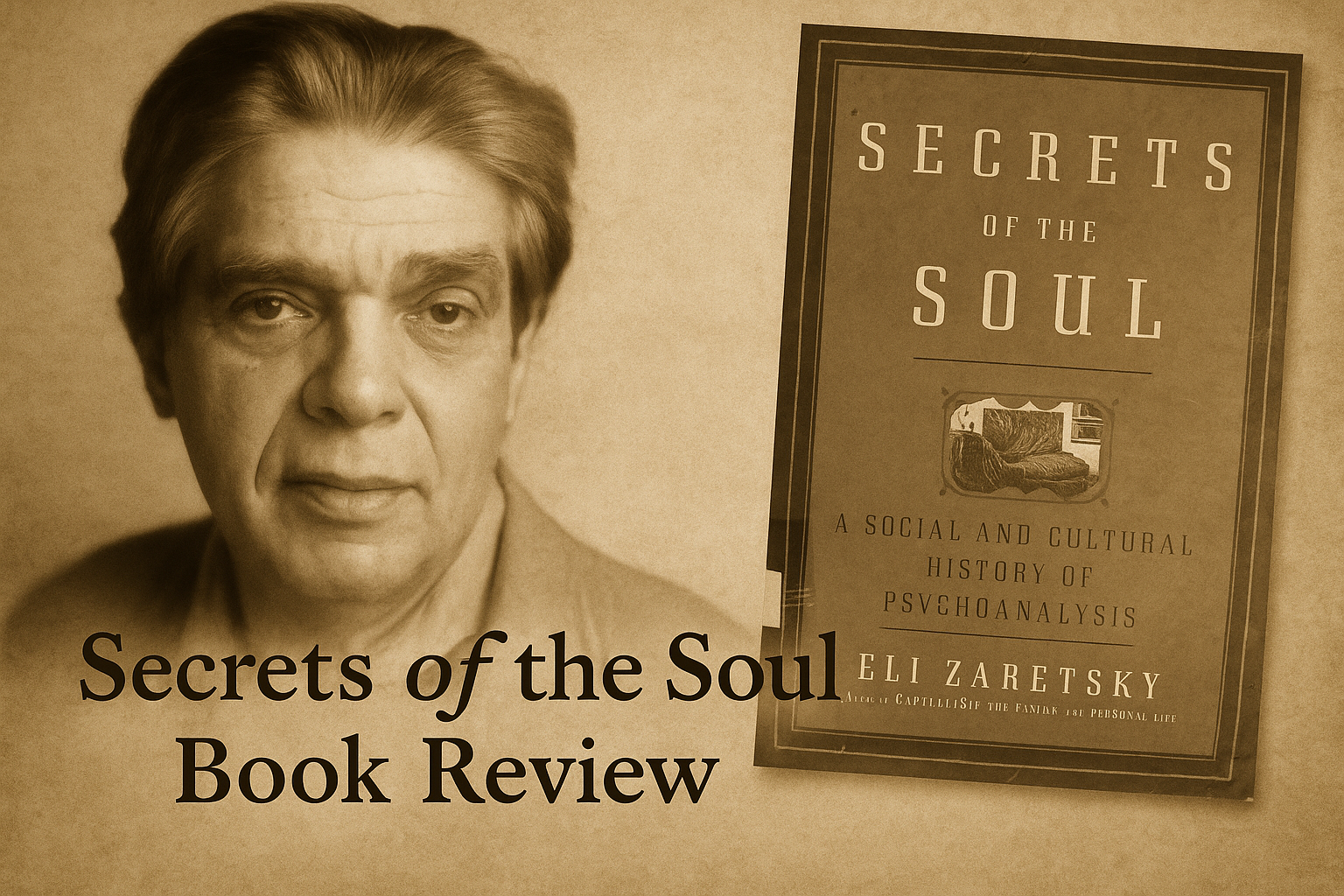Pendahuluan
Buku Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka karya Ahmad Jelani Halimi adalah salah satu karya penting yang mengupas sejarah maritim dari perspektif orang Melayu. Penulis mencoba mengisi kekosongan historiografi yang sering kali lebih banyak menonjolkan peran kolonial daripada peranan bangsa Nusantara itu sendiri. Selat Melaka, sejak berabad-abad, telah menjadi jalur laut vital dunia, dan buku ini memperlihatkan bagaimana posisi strategis tersebut membentuk dinamika perdagangan, politik, dan kebudayaan.
Ahmad Jelani menekankan bahwa perdagangan tidak bisa dipisahkan dari perkapalan, dan perkapalan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi serta struktur kekuasaan. Setiap kapal yang berlayar di Selat Melaka membawa lebih dari sekadar barang; ia juga membawa gagasan, budaya, dan bahkan agama. Dengan demikian, buku ini tidak hanya membicarakan kapal sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai agen peradaban.
Dalam kerangka keilmuan, karya ini memperlihatkan pendekatan yang lintas disiplin. Ia menggabungkan sejarah ekonomi, politik, dan maritim dengan antropologi dan hukum laut. Pendekatan semacam ini penting, sebab perdagangan dan perkapalan selalu bergerak di antara jalur formal dan informal, antara legalitas hukum negara dan praktik sehari-hari para pedagang.
Sejak abad ke-15, Selat Melaka telah menarik perhatian berbagai kekuatan dunia. Dari pedagang Arab, Gujarat, hingga Cina, semuanya singgah di pelabuhan-pelabuhan Melayu. Dinamika ini kemudian diperkaya dengan kehadiran bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda, yang membawa serta sistem monopoli dan kolonialisme. Ahmad Jelani menyoroti bahwa meski bangsa asing hadir dengan kekuatan besar, orang Melayu tetap memainkan peran sentral.
Pendahuluan buku ini juga menekankan bahwa membaca sejarah perdagangan Melayu berarti membaca sejarah Asia Tenggara sebagai bagian dari jaringan global. Apa yang terjadi di Selat Melaka selalu memiliki resonansi yang lebih luas: dari Lautan Hindi hingga Laut Cina Selatan. Dengan demikian, buku ini bukan hanya tentang sejarah lokal, melainkan juga sejarah dunia.
Buku ini juga menjadi refleksi kritis terhadap posisi Selat Melaka hari ini. Meskipun fokus utamanya pada abad ke-15 hingga ke-18, Ahmad Jelani secara implisit mengingatkan bahwa kepentingan geopolitik di kawasan ini tidak pernah hilang. Apa yang dahulu diperebutkan Portugis dan Belanda kini menjadi titik penting dalam jalur perdagangan modern.
Pendahuluan ini membuka cakrawala pembaca bahwa yang sedang mereka baca bukan hanya sejarah perdagangan, melainkan juga sejarah identitas bangsa. Orang Melayu membangun peradabannya melalui laut, dan buku ini adalah pengingat bahwa warisan itu tidak boleh diabaikan.
Perdagangan Awal Nusantara dan Kebangkitan Kesultanan Melaka
Sejarah perdagangan di Nusantara pada abad ke-15 tidak bisa dilepaskan dari posisi Selat Melaka sebagai nadi perhubungan antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Pada masa ini, perdagangan di kawasan Nusantara mulai menampakkan dinamika yang lebih kompleks, karena interaksi antara pedagang lokal, Asia, hingga Timur Tengah semakin intens. Para pedagang membawa rempah-rempah, kain, logam mulia, dan barang-barang mewah yang menjadi komoditas penting dalam pertukaran internasional.
Kesultanan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang disegani berkat kemampuan politik dan militernya dalam menjaga stabilitas kawasan. Di bawah kepemimpinan raja-raja Melaka, terutama Sultan Mansur Shah, pelabuhan Melaka tumbuh menjadi entrepot utama di Asia Tenggara. Keunggulannya terletak pada sistem yang terbuka bagi pedagang dari berbagai bangsa, yang diberi jaminan keamanan, perlindungan hukum, serta fasilitas pelabuhan yang teratur.
Melaka juga berhasil mengembangkan sistem administrasi perdagangan yang rapi. Pegawai-pegawai pelabuhan, syahbandar, dan aparat kerajaan memastikan arus barang berjalan lancar. Pajak dan bea masuk diatur secara proporsional, sehingga pedagang merasa dilindungi sekaligus terikat pada aturan. Kebijakan ini membuat Melaka berbeda dari pelabuhan lain yang sering kali tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum.
Selain faktor politik, faktor geografis juga berperan penting. Selat Melaka yang sempit dan menjadi jalur utama perdagangan dunia membuat siapa pun yang menguasainya memiliki posisi tawar tinggi. Melaka mampu memanfaatkan posisi strategis ini dengan baik, sehingga setiap kapal dari India, Arab, atau Cina hampir pasti akan singgah untuk berdagang, mengisi perbekalan, dan memperbaiki kapal.
Perdagangan Melaka bukan hanya soal komoditas, tetapi juga soal diplomasi. Kesultanan Melaka menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan regional, seperti Kesultanan Aceh, Demak, hingga kerajaan-kerajaan di India dan Cina. Hubungan ini menciptakan jaringan perdagangan yang tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga politis. Dengan kata lain, perdagangan di Melaka adalah juga alat pertahanan dan strategi ekspansi pengaruh.
Namun, kebangkitan Melaka tidak berlangsung tanpa ancaman. Kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 membawa perubahan besar dalam peta perdagangan. Portugis ingin menguasai jalur rempah-rempah dengan sistem monopoli, yang berbeda dari sistem terbuka yang diterapkan Melaka. Akibatnya, Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, menandai dimulainya era kolonialisme Eropa di kawasan ini.
Meskipun demikian, kebesaran Melaka tetap menjadi simbol kejayaan maritim Melayu. Sistem perdagangan yang mereka bangun menjadi model bagi pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara. Kejayaan ini menunjukkan bahwa bangsa Melayu memiliki kapasitas untuk mengelola perdagangan internasional dengan sistem yang modern, jauh sebelum dominasi kolonial mengubah struktur ekonomi kawasan.
Pelabuhan dan Pegawai Perdagangan Melayu
Pelabuhan Melaka pada abad ke-15 hingga ke-18 adalah jantung dari kegiatan perdagangan dunia Melayu. Ahmad Jelani menekankan bahwa kesuksesan Melaka sebagai entrepot internasional bukan hanya karena letak geografisnya yang strategis, tetapi juga karena sistem administrasi pelabuhan yang rapi dan efektif. Sistem ini melibatkan peranan pegawai pelabuhan Melayu yang dikenal sebagai syahbandar, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur lalu lintas kapal, memungut cukai, dan menjaga ketertiban niaga. Tanpa struktur pegawai yang kuat, mustahil Melaka mampu mengendalikan arus dagang internasional yang sangat padat.
Syahbandar di Melaka dibagi berdasarkan bangsa pedagang. Ada syahbandar khusus untuk pedagang dari India, dari Timur Tengah, dari Cina, dan untuk pedagang Nusantara sendiri. Sistem ini menunjukkan tingkat kecerdikan administratif Kesultanan Melaka. Dengan membagi syahbandar menurut asal bangsa pedagang, kerajaan bisa memastikan bahwa setiap komunitas merasa terwakili dan dilayani sesuai kebiasaan mereka. Inilah yang membuat pedagang asing nyaman singgah di Melaka, karena mereka tahu ada pejabat khusus yang mengerti budaya dan bahasa mereka.
Selain syahbandar, ada juga pegawai lain yang berperan dalam kelancaran perdagangan. Ahmad Jelani mencatat adanya peranan nakhoda besar, pengawas gudang, serta aparat keamanan yang memastikan kegiatan pelabuhan berjalan aman. Pelabuhan Melaka bukanlah pelabuhan liar di mana siapa saja bebas berdagang. Sebaliknya, ia adalah pusat perdagangan yang memiliki tata aturan jelas, dengan pengawasan yang ketat dari kerajaan. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Melayu sudah memiliki tata kelola maritim yang modern jauh sebelum kedatangan kolonial Eropa.
Keberadaan pegawai pelabuhan ini juga memperlihatkan betapa perdagangan di Melaka adalah bagian integral dari struktur pemerintahan. Raja dan para bangsawan Melayu tidak hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai regulator ekonomi. Pajak dan bea yang dipungut dari perdagangan digunakan untuk memperkuat pertahanan dan membiayai administrasi kerajaan. Dengan demikian, pelabuhan bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga sumber utama kekuasaan politik Melaka.
Ahmad Jelani menekankan bahwa sistem pelabuhan Melaka berfungsi sebagai model bagi pelabuhan lain di Nusantara. Kesultanan Johor, Riau, dan Aceh, misalnya, kemudian mengadopsi struktur serupa dalam mengelola perdagangan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan tradisi administratif Melayu yang menjadikan pelabuhan sebagai pusat kehidupan ekonomi sekaligus politik. Kejayaan maritim Melayu tidak hanya terlihat dalam jumlah kapal atau komoditas dagang, tetapi juga dalam kemampuan mereka membangun sistem pengelolaan pelabuhan yang berkelas internasional.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini juga menghadapi tantangan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris membawa model monopoli dagang yang berbeda dengan sistem terbuka Melaka. Syahbandar-syahbandar Melayu yang sebelumnya memegang kendali perlahan kehilangan pengaruh karena struktur perdagangan dipaksa tunduk pada kepentingan kolonial. Buku Ahmad Jelani menyoroti bahwa inilah titik balik, di mana pegawai pelabuhan Melayu yang sebelumnya menjadi simbol kedaulatan ekonomi mulai terpinggirkan oleh administrasi kolonial.
Meski demikian, warisan administrasi perdagangan Melayu tetap hidup dalam ingatan sejarah. Buku ini memperlihatkan bahwa peranan syahbandar dan pegawai pelabuhan bukan hanya bagian kecil dari birokrasi, melainkan inti dari keberhasilan perdagangan internasional di Selat Melaka. Tanpa mereka, mustahil Melaka bisa menjadi pusat perdagangan dunia. Dengan menekankan aspek ini, Ahmad Jelani mengingatkan pembaca bahwa identitas maritim Melayu tidak hanya dibangun oleh pelaut dan pedagang, tetapi juga oleh administrator pelabuhan yang berwawasan internasional.
Perkapalan Melayu: Teknologi dan Identitas Maritim
Ahmad Jelani memberi perhatian khusus pada perkapalan Melayu, karena bagi bangsa maritim seperti orang Melayu, kapal bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga lambang kedaulatan, kebanggaan, dan identitas. Kapal-kapal Melayu menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki tradisi teknologi yang kuat, yang memungkinkan mereka mendominasi perairan Nusantara dan terlibat langsung dalam perdagangan internasional. Kapal adalah perpanjangan tangan dari dunia Melayu dalam percaturan global, sehingga mempelajari sejarah perkapalan sama artinya dengan memahami jati diri bangsa.
Jenis kapal Melayu yang terkenal antara lain adalah jong, lancaran, penjajap, dan kelulus. Jong, misalnya, merupakan kapal besar dengan muatan ribuan ton, yang bahkan diakui oleh pelaut asing sebagai salah satu kapal terbesar pada zamannya. Kapal-kapal ini dibuat dengan teknik sambungan papan tanpa paku besi, melainkan menggunakan pasak kayu dan tali serat. Ahmad Jelani menunjukkan bahwa teknologi semacam ini bukan primitif, melainkan adaptasi cerdas terhadap kondisi laut tropis yang lembab dan mudah mengikis logam.
Selain jong, kapal lancaran dan penjajap lebih lincah, dipakai untuk pelayaran jarak dekat maupun operasi militer. Kapal-kapal kecil ini memungkinkan orang Melayu menguasai jalur-jalur sempit di perairan Selat Melaka, yang sering kali tidak bisa dilewati kapal besar bangsa asing. Fleksibilitas armada inilah yang memberi bangsa Melayu keunggulan dalam mengatur strategi dagang maupun pertahanan. Dengan kata lain, kombinasi antara kapal besar dan kapal kecil membentuk ekosistem maritim yang tangguh.
Kapal Melayu tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga dalam desain yang mencerminkan budaya. Hiasan pada haluan dan buritan, penggunaan layar segi empat maupun segitiga, serta simbol-simbol ukiran memperlihatkan bahwa kapal juga sarat makna spiritual. Bagi pelaut Melayu, kapal bukan sekadar mesin ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan kosmos budaya. Di sinilah terlihat bahwa laut dan kapal adalah bagian integral dari peradaban Melayu.
Dalam perdagangan, kapal-kapal Melayu mampu menjangkau India, Cina, hingga Laut Arab. Catatan Portugis dan Cina mengakui bahwa pelaut Melayu memiliki armada yang tangguh dan mampu bersaing dengan kapal asing. Ahmad Jelani menekankan bahwa orang Melayu bukan sekadar penonton dalam arus perdagangan global, tetapi aktor utama yang mampu mengirim dan membawa komoditas dari satu benua ke benua lain. Fakta ini sekaligus menepis anggapan bahwa bangsa Nusantara pasif dan hanya bergantung pada pedagang asing.
Namun, perkembangan perkapalan Melayu juga tidak lepas dari tantangan. Kedatangan Portugis dengan kapal-kapal artileri berat memperlihatkan perbedaan orientasi: bangsa Eropa memandang kapal sebagai alat ekspansi militer, sementara orang Melayu lebih melihatnya sebagai sarana perdagangan dan mobilitas sosial. Perbedaan ini kemudian memengaruhi peta kekuatan di Selat Melaka, di mana kapal Melayu lambat laun terdesak oleh teknologi meriam dan navigasi modern yang dibawa bangsa asing.
Meski demikian, warisan perkapalan Melayu tetap monumental. Kapal-kapal seperti jong menjadi ikon kejayaan maritim, yang hingga kini dipelajari oleh sejarawan dan arkeolog. Melalui pembahasan Ahmad Jelani, kita diajak melihat bahwa teknologi maritim Melayu bukanlah pinggiran, tetapi bagian penting dari sejarah global. Perkapalan inilah yang menjadikan bangsa Melayu mampu membangun jejaring dagang, mempertahankan kedaulatan, dan menegaskan identitas mereka sebagai bangsa laut.
Ancaman Perompakan dan Dinamika Lautan
Selat Melaka, selain menjadi jalur perdagangan internasional yang penting, juga terkenal sebagai kawasan yang rawan perompakan. Ahmad Jelani menegaskan bahwa perompakan bukan sekadar gangguan kecil, melainkan bagian integral dari dinamika lautan pada abad ke-15 hingga ke-18. Perompak muncul karena faktor sosial-ekonomi, politik, dan geografis yang saling terkait. Kondisi ini membuat setiap kapal dagang yang melintasi Selat Melaka selalu berada dalam ancaman, meskipun di sisi lain pelabuhan-pelabuhan besar berusaha menjaga keamanan.
Salah satu penyebab utama munculnya perompakan adalah ketimpangan ekonomi. Banyak kelompok masyarakat pesisir atau kepulauan kecil yang tidak terlibat langsung dalam perdagangan besar akhirnya memilih jalan perompakan sebagai mata pencaharian. Mereka menyerang kapal-kapal dagang untuk memperoleh barang, perbekalan, dan tebusan. Ahmad Jelani memperlihatkan bahwa fenomena ini bukanlah semata-mata kriminalitas, tetapi juga bentuk respons sosial terhadap ketidakadilan ekonomi yang muncul dari perdagangan internasional.
Selain faktor ekonomi, ada pula faktor politik. Dalam konteks persaingan antar kerajaan di Nusantara, perompakan kadang dipelihara atau bahkan dimanfaatkan oleh penguasa tertentu sebagai strategi untuk melemahkan pesaing. Kapal-kapal dagang milik kerajaan musuh bisa saja dijarah oleh kelompok perompak yang diam-diam mendapat perlindungan politik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa garis antara perompakan dan operasi militer sering kali kabur, sehingga sulit membedakan mana yang benar-benar kriminal dan mana yang berorientasi politik.
Geografi Selat Melaka juga mendukung aktivitas perompakan. Dengan pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya, selat ini menyediakan banyak tempat persembunyian. Perompak dapat dengan mudah bersembunyi setelah menyerang kapal dagang, kemudian muncul kembali di lokasi lain. Ahmad Jelani menekankan bahwa tantangan geografis ini membuat upaya pengamanan jalur pelayaran menjadi sangat kompleks, bahkan bagi kerajaan besar sekalipun.
Pihak kerajaan dan syahbandar berusaha menanggulangi perompakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperkuat angkatan laut lokal untuk mengawal kapal dagang. Selain itu, kapal-kapal dagang sendiri juga sering berlayar dalam konvoi demi keamanan. Namun, langkah-langkah ini tidak selalu berhasil, sebab perompakan telah menjadi bagian dari ekologi maritim Selat Melaka. Buku ini dengan jelas menunjukkan bahwa perompakan tidak bisa dipisahkan dari cerita perdagangan, karena keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama.
Kedatangan bangsa Portugis dan kemudian Belanda juga mengubah dinamika perompakan. Di satu sisi, mereka membawa kapal bersenjata lengkap yang mampu menekan perompak lokal. Namun di sisi lain, bangsa kolonial juga menerapkan kebijakan monopoli yang merugikan pedagang lokal. Akibatnya, sebagian masyarakat justru terdorong ke arah aktivitas ilegal, termasuk perompakan, sebagai bentuk perlawanan. Ahmad Jelani memperlihatkan bahwa perompakan pada era kolonial tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga simbol resistensi terhadap kekuasaan asing.
Pada akhirnya, perompakan di Selat Melaka adalah cermin dari dinamika laut itu sendiri: sebuah ruang yang cair, di mana perdagangan, politik, dan kriminalitas saling bertemu. Dengan membahas perompakan secara mendalam, Ahmad Jelani mengingatkan pembaca bahwa sejarah perdagangan tidak hanya berisi kisah kejayaan dan keuntungan, tetapi juga konflik, ancaman, dan ketidakpastian. Inilah yang menjadikan sejarah Selat Melaka begitu kaya, kompleks, dan relevan untuk dipelajari hingga hari ini.
Eropa di Selat Melaka: Portugis dan Perebutan Jalur Perdagangan
Kehadiran bangsa Portugis di Melaka pada tahun 1511 menandai babak baru dalam sejarah perdagangan di Selat Melaka. Ahmad Jelani menekankan bahwa kejatuhan Melaka ke tangan Portugis bukan sekadar peristiwa militer, tetapi juga perubahan besar dalam struktur perdagangan global. Portugis datang dengan agenda monopoli, berbeda dari sistem terbuka yang selama ini dijalankan oleh kerajaan Melayu. Tujuan mereka jelas: menguasai jalur rempah-rempah dan menjadikan Melaka sebagai basis utama kekuasaan di Asia Tenggara.
Sebelum Portugis datang, Melaka dikenal sebagai pelabuhan bebas di mana pedagang dari berbagai bangsa bisa berdagang dengan aturan yang adil. Namun, setelah Portugis berkuasa, sistem ini diubah. Mereka menetapkan pajak tinggi, mengatur siapa saja yang boleh berdagang, bahkan melarang kapal tertentu memasuki pelabuhan tanpa izin resmi. Ahmad Jelani menegaskan bahwa perubahan ini merusak harmoni yang selama ini membuat Melaka berjaya sebagai pusat perdagangan.
Kebijakan Portugis memicu perlawanan dari pedagang lokal maupun kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Aceh, misalnya, muncul sebagai pesaing kuat Portugis di Selat Melaka. Dengan membangun angkatan lautnya sendiri, Aceh berusaha menyaingi dominasi Portugis dan menarik pedagang yang tidak puas dengan kebijakan monopoli. Ahmad Jelani melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa bangsa Melayu dan Nusantara tidak pasif menghadapi kolonialisme, melainkan aktif menantangnya.
Selain itu, Portugis menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan kendali mereka. Pulau-pulau kecil di sekitar Selat Melaka menjadi sarang perlawanan, baik oleh perompak maupun kerajaan yang masih setia pada sistem perdagangan lama. Kondisi geografis yang rumit membuat Portugis sulit mengawasi seluruh jalur. Mereka mungkin menguasai benteng Melaka, tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan Selat Melaka.
Kehadiran Portugis juga membawa perubahan dalam teknologi militer di kawasan ini. Kapal-kapal mereka dilengkapi meriam berat, yang memberi keunggulan dalam pertempuran laut. Namun, keunggulan ini juga menimbulkan reaksi: kerajaan-kerajaan lokal mulai berusaha mengadopsi teknologi serupa. Dengan demikian, kehadiran Portugis mendorong modernisasi militer, meskipun prosesnya berjalan lambat dan tidak merata.
Ahmad Jelani mencatat bahwa meskipun Portugis berkuasa cukup lama di Melaka (1511–1641), mereka tidak pernah berhasil menciptakan stabilitas perdagangan seperti pada masa kesultanan Melayu. Mereka lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, reputasi Melaka sebagai pelabuhan internasional perlahan merosot, dan para pedagang mulai mencari alternatif lain, termasuk ke pelabuhan Johor, Aceh, dan Banten.
Pada akhirnya, bab Portugis dalam sejarah Selat Melaka memperlihatkan bahwa kekuatan kolonial Eropa datang bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan logika ekonomi baru: monopoli. Berbeda dari sistem terbuka yang dijalankan bangsa Melayu, monopoli ini merusak tatanan lama yang sudah mapan. Dengan analisis tajam, Ahmad Jelani menunjukkan bahwa kejatuhan Melaka bukan berarti kejatuhan total bangsa Melayu, karena mereka tetap menemukan cara untuk bertahan, melawan, dan beradaptasi dalam dinamika baru perdagangan global.
Abad ke-18: Transformasi Perdagangan Melayu
Abad ke-18 adalah periode transformasi penting dalam sejarah perdagangan Melayu di Selat Melaka. Ahmad Jelani menjelaskan bahwa meskipun Portugis telah lama terusir, dan Belanda kemudian tampil sebagai kekuatan dominan, bangsa Melayu tetap memainkan peran strategis dalam aktivitas perdagangan. Namun, pola perdagangan yang berlangsung pada masa ini berbeda dari abad-abad sebelumnya. Fokusnya bergeser dari sistem entrepot Melaka klasik menuju struktur perdagangan yang lebih tersebar, dengan pelabuhan-pelabuhan baru bermunculan di sekitar kawasan.
Pelabuhan Johor, Riau, dan Lingga, misalnya, berkembang menjadi pusat perdagangan yang menyaingi Melaka. Kehadiran pelabuhan ini membuktikan fleksibilitas bangsa Melayu dalam beradaptasi dengan situasi baru. Mereka tidak lagi bergantung pada satu pusat perdagangan, tetapi membangun jaringan pelabuhan yang lebih luas. Ahmad Jelani menekankan bahwa dinamika ini memperlihatkan ketahanan bangsa Melayu dalam menghadapi tekanan kolonial dan perubahan geopolitik.
Perdagangan pada abad ke-18 juga semakin terintegrasi dengan pasar global. Komoditas yang diperdagangkan tidak hanya rempah-rempah, tetapi juga timah, lada, dan hasil bumi lainnya yang sangat diminati oleh pasar internasional. Orang Melayu, baik sebagai pedagang maupun pelaut, tetap menjadi penghubung utama dalam rantai distribusi komoditas ini. Kehadiran mereka memastikan bahwa meskipun Belanda berusaha memonopoli perdagangan, jalur-jalur alternatif tetap terbuka.
Namun, masa ini juga ditandai dengan meningkatnya tekanan kolonial. Belanda, melalui VOC, mencoba memaksakan sistem monopoli yang ketat, serupa dengan apa yang pernah dilakukan Portugis. Ahmad Jelani menegaskan bahwa sistem ini tidak sepenuhnya berhasil karena keterbatasan Belanda dalam mengawasi seluruh jalur perdagangan. Orang Melayu tetap menemukan cara untuk menghindari monopoli, baik dengan melakukan perdagangan gelap, berlayar di jalur alternatif, maupun menjalin hubungan dengan pedagang asing di luar kendali VOC.
Selain tekanan kolonial, faktor internal juga memengaruhi transformasi perdagangan. Konflik politik di antara kerajaan-kerajaan Melayu, perebutan tahta, dan persaingan regional membuat perdagangan kadang terganggu. Namun, justru dalam situasi ini terlihat peranan pedagang independen yang semakin penting. Mereka beroperasi secara fleksibel, tidak selalu bergantung pada otoritas kerajaan, tetapi tetap menjaga hubungan erat dengan komunitas pelaut dan syahbandar.
Ahmad Jelani menyoroti bahwa transformasi abad ke-18 juga memperlihatkan perubahan dalam struktur sosial maritim Melayu. Peran bangsawan dan kerajaan dalam perdagangan mulai berkurang, sementara kelas pedagang dan pelaut semakin berpengaruh. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam distribusi kekuasaan ekonomi, yang lambat laun juga berdampak pada struktur politik di kawasan. Dengan kata lain, abad ke-18 adalah masa ketika bangsa Melayu mulai mengalami “demokratisasi” perdagangan dalam skala tertentu.
Akhirnya, abad ke-18 menjadi titik penting yang menegaskan bahwa meskipun bangsa Eropa mendominasi secara formal, bangsa Melayu tetap menjadi aktor penting dalam perdagangan Selat Melaka. Mereka mungkin tidak lagi menguasai pusat-pusat besar seperti pada masa Kesultanan Melaka abad ke-15, tetapi mereka berhasil mempertahankan keberadaan dan relevansi mereka dalam jaringan perdagangan global. Bagi Ahmad Jelani, inilah bukti nyata bahwa sejarah perdagangan Melayu tidak bisa direduksi hanya pada masa kejayaan klasik, melainkan juga pada kemampuan adaptasi mereka di tengah kolonialisme dan transformasi global.
Kesimpulan: Selat Melaka sebagai Poros Sejarah Global
Ahmad Jelani Halimi menutup karyanya dengan penegasan bahwa Selat Melaka tidak dapat dipandang hanya sebagai jalur air sempit yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Selat ini adalah poros sejarah global yang sejak berabad-abad telah menjadi pusat interaksi antarbangsa. Dari abad ke-15 hingga ke-18, Selat Melaka menjadi saksi bagaimana bangsa Melayu mengelola perdagangan, membangun perkapalan, serta mempertahankan identitas maritim di tengah arus kolonialisme. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa sejarah Melayu bukan sejarah pinggiran, melainkan bagian inti dari sejarah dunia.
Dalam perspektif Ahmad Jelani, kejayaan perdagangan Melaka pada abad ke-15 membuktikan bahwa bangsa Melayu mampu menciptakan sistem terbuka yang modern, jauh sebelum bangsa Eropa hadir dengan monopoli mereka. Pelabuhan Melaka adalah bukti bahwa konsep “globalisasi” sudah lama hadir di Asia Tenggara, di mana pedagang dari berbagai bangsa berinteraksi dalam aturan yang adil dan sistematis. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511 tidak berarti berakhirnya tradisi perdagangan Melayu, melainkan awal dari babak baru yang memperlihatkan daya tahan mereka dalam menghadapi kolonialisme.
Perkapalan Melayu yang ditulis dengan detail oleh Ahmad Jelani juga menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki tradisi teknologi yang tangguh. Kapal jong, lancaran, dan penjajap bukan hanya simbol ekonomi, tetapi juga identitas kultural. Kapal adalah rumah, ruang sosial, dan bahkan simbol spiritual bagi pelaut Melayu. Tanpa kapal, tidak ada perdagangan; dan tanpa perdagangan, tidak ada kebesaran Selat Melaka. Dengan kata lain, kapal adalah poros peradaban Melayu.
Fenomena perompakan yang sering dilihat sebagai sisi gelap perdagangan justru dipahami Ahmad Jelani sebagai bagian integral dari dinamika lautan. Perompakan muncul dari ketidakadilan ekonomi, konflik politik, dan kondisi geografis yang mendukung. Fakta bahwa perompakan tetap eksis meski ada upaya penindasan dari kerajaan maupun bangsa kolonial memperlihatkan bahwa laut adalah ruang yang cair, sulit dikontrol sepenuhnya. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana Selat Melaka adalah ruang kebebasan sekaligus ruang konflik.
Kehadiran bangsa Portugis dan Belanda memperlihatkan perubahan logika perdagangan: dari sistem terbuka menuju monopoli. Namun, Ahmad Jelani menegaskan bahwa dominasi Eropa tidak pernah sepenuhnya berhasil. Bangsa Melayu tetap menemukan cara untuk bertahan, baik melalui pelabuhan alternatif, perdagangan gelap, maupun perlawanan militer. Dengan demikian, meski secara formal kekuasaan bergeser, secara substansial bangsa Melayu tetap memainkan peran penting dalam menjaga arus perdagangan global.
Abad ke-18 menjadi periode transisi yang memperlihatkan adaptasi luar biasa bangsa Melayu. Meski kolonialisme semakin kuat, pelabuhan Johor, Riau, dan Lingga tetap menjadi simpul perdagangan penting. Pedagang independen semakin berperan, menunjukkan bahwa bangsa Melayu tidak hanya bergantung pada kerajaan, tetapi mampu membangun jaringan dagang yang otonom. Transformasi ini membuktikan bahwa bangsa Melayu tidak pernah pasif, tetapi selalu kreatif dalam menghadapi perubahan zaman.
Akhirnya, Ahmad Jelani menyimpulkan bahwa Selat Melaka adalah cermin dari sejarah manusia: ruang di mana perdagangan, politik, teknologi, dan budaya bertemu. Sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari bangsa Melayu yang menjadi pengelola utama kawasan ini. Buku ini adalah pengingat bahwa peran Melayu dalam sejarah dunia tidak boleh direduksi oleh narasi kolonial. Selat Melaka adalah milik dunia, tetapi jiwa yang menghidupinya sejak abad ke-15 hingga ke-18 adalah bangsa Melayu.