Pendahuluan
Laut Cina Selatan (LCS) adalah panggung geopolitik yang paling intens di Asia Tenggara. Laut ini bukan hanya soal perbatasan maritim, tetapi juga menyangkut masa depan tatanan kawasan yang sedang dipengaruhi secara mendalam oleh kebangkitan Cina. Dalam dua dekade terakhir, strategi Beijing semakin terlihat sistematis: membangun kekuatan maritim, memperkuat infrastruktur di pulau buatan, serta mengubah status quo menjadi realitas baru yang diterima secara de facto oleh negara-negara Asia Tenggara (Kaplan, 2014; International Crisis Group [ICG], 2023).
Namun, yang paling menarik dari dinamika ini adalah bukan hanya manuver Cina, melainkan sikap negara-negara ASEAN yang cenderung menghindari konfrontasi langsung. Meskipun beberapa negara—seperti Vietnam dan Filipina—menunjukkan resistensi terbatas, mayoritas tetap memilih jalur diplomasi, kompromi, atau bahkan keheningan strategis. Hal ini menunjukkan bagaimana hegemoni Cina perlahan diterima sebagai keniscayaan (Buszynski & Roberts, 2015; RAND Corporation, 2021).
Cina dan Strategi Hegemoni Maritim
Strategi Cina di LCS dapat dipahami dalam kerangka “salami slicing strategy”—yakni mengambil langkah-langkah kecil namun konsisten yang sulit ditolak oleh pihak lain, hingga akhirnya menciptakan perubahan besar (Friedberg, 2018). Beijing membangun pulau buatan, menempatkan instalasi militer, hingga memperluas zona ekonomi eksklusif secara sepihak dengan mengandalkan “Nine-Dash Line” yang kontroversial (Permanent Court of Arbitration, 2016).
Lebih dari sekadar kepentingan maritim, strategi ini adalah bagian dari visi “China Dream” Xi Jinping: menjadikan Cina sebagai kekuatan global pada pertengahan abad ke-21 (Shambaugh, 2020). LCS menjadi laboratorium awal untuk menguji kemampuan militer, diplomasi, serta manajemen opini publik internasional. Dengan mengontrol jalur perdagangan laut yang menyumbang lebih dari sepertiga perdagangan dunia, Cina tidak hanya memperoleh keuntungan strategis tetapi juga membangun posisi tawar global (Council on Foreign Relations [CFR], 2022).
ASEAN dan Politik Ambivalensi
Di hadapan strategi Cina yang semakin agresif di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN memperlihatkan pola yang dapat disebut sebagai politik ambivalensi—sebuah strategi yang tidak sepenuhnya menantang, namun juga tidak tunduk secara total. Ambivalensi ini mencerminkan keterbatasan internal ASEAN, sekaligus kebutuhan tiap negara menjaga kepentingan nasionalnya tanpa harus terjebak dalam konfrontasi langsung dengan Beijing.
Filipina menjadi contoh paling menonjol dari ambivalensi ini. Pada tahun 2013, Manila membawa kasus sengketa Laut Cina Selatan ke Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag, yang pada 2016 menghasilkan putusan penting: klaim “nine-dash line” Cina dinyatakan tidak memiliki dasar hukum internasional (Storey, 2017). Namun, kemenangan hukum tersebut ternyata tidak diikuti dengan konsolidasi regional atau penerapan efektif. Lemahnya dukungan ASEAN terhadap Filipina membuat Beijing dapat mengabaikan putusan itu tanpa konsekuensi nyata. Ambivalensi semakin jelas ketika Presiden Rodrigo Duterte, meski secara formal memegang kemenangan hukum, memilih menekankan kerja sama ekonomi dan investasi dengan Cina. Hal ini menegaskan bahwa hukum internasional seringkali menjadi senjata simbolik, namun kalkulasi pragmatis ekonomi dan politik tetap dominan (Heydarian, 2018).
Vietnam, sebaliknya, tampil sebagai negara paling vokal menentang ekspansi Cina. Hanoi memperkuat kapasitas militernya, terutama angkatan laut, sambil mempererat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, India, dan Jepang. Namun, Vietnam tetap menjaga kanal diplomasi dengan Beijing, menghindari eskalasi terbuka yang dapat merugikan stabilitas domestik maupun regional (Thayer, 2020). Sikap Vietnam merepresentasikan model “hedging strategy”—bermain di antara resistensi terbuka dan kerja sama pragmatis.
Malaysia, Brunei, dan Indonesia menunjukkan strategi yang lebih subtil, yang dapat disebut sebagai “diam aktif”. Ketiganya tidak melakukan perlawanan frontal terhadap Cina, melainkan menjaga klaim kedaulatan maritim mereka melalui patroli terbatas, penguatan hukum nasional, dan retorika diplomatik minimal (Sukma, 2021). Malaysia sering kali menolak memperbesar isu secara publik, meski laporan mengenai kehadiran kapal Cina di zona ekonominya terus berulang. Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim langsung dalam sengketa, tetap mempertahankan klaim di Natuna Utara melalui patroli militer dan pernyataan diplomatik, tanpa mengubah pola hubungan ekonominya dengan Beijing. Brunei bahkan lebih tenang lagi, memilih jalur diplomasi “low profile” demi stabilitas internal dan hubungan ekonomi yang menguntungkan.
Sementara itu, Singapura dan Thailand memainkan peran sebagai mediator netral. Kedua negara ini memandang stabilitas kawasan lebih penting ketimbang konfrontasi. Singapura, sebagai negara kota yang sangat bergantung pada keterbukaan jalur perdagangan, berusaha menjaga hubungan baik dengan Washington dan Beijing, serta aktif mendorong kerangka diplomasi multilateral ASEAN. Thailand pun cenderung fokus pada urusan domestik dan hubungan bilateral pragmatis dengan Cina, sambil menghindari keterlibatan langsung dalam konflik (Emmers, 2018).
Polanya jelas: ASEAN tidak menampilkan satu suara menghadapi Cina, melainkan kumpulan respons yang penuh ambivalensi—antara resistensi dan akomodasi, antara hukum internasional dan diplomasi bilateral, antara pragmatisme ekonomi dan kalkulasi strategis. Kondisi ini membuka ruang manuver yang semakin lebar bagi Beijing, yang memanfaatkan fragmentasi ASEAN untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan.
Ambivalensi ini bukan kelemahan semata, melainkan refleksi dari realitas geopolitik: tidak ada satu pun negara ASEAN yang mampu menghadapi Cina sendirian. Aliansi ASEAN pun tidak solid, sehingga setiap negara menyesuaikan sikapnya demi kepentingan domestik masing-masing (ASEAN Studies Centre, 2022).
Strategi “Menunda Konfrontasi”
Salah satu ciri paling khas dalam sikap ASEAN terhadap Cina adalah apa yang bisa disebut sebagai strategi “menunda konfrontasi”. Negara-negara di Asia Tenggara sadar penuh terhadap agresivitas Beijing di Laut Cina Selatan, baik melalui pembangunan pulau buatan, pengerahan kapal penjaga pantai, maupun diplomasi ekonomi yang bersifat koersif. Namun, alih-alih mengadopsi sikap keras secara kolektif, ASEAN lebih memilih respon tertunda—menunda konfrontasi langsung dengan alasan pragmatis. Ada setidaknya tiga alasan utama yang menjelaskan pilihan strategi ini.
Ekonomi sebagai Pengikat Utama
Hubungan ekonomi ASEAN–Cina berkembang sedemikian rupa sehingga konfrontasi terbuka justru dianggap merugikan semua pihak. Cina saat ini adalah mitra dagang terbesar hampir semua negara ASEAN. Nilai perdagangan ASEAN–Cina mencapai lebih dari $878 miliar pada 2021, menjadikan Beijing sebagai pilar sentral dalam rantai pasok regional (World Bank, 2021).
Keterikatan ini bukan hanya soal ekspor-impor, tetapi juga investasi dan infrastruktur. Melalui Belt and Road Initiative (BRI), Cina telah mengucurkan miliaran dolar untuk pembangunan pelabuhan, rel kereta, jalan tol, hingga kawasan industri di Asia Tenggara. Bagi banyak negara ASEAN, investasi ini mengisi kekosongan pembiayaan pembangunan yang tidak mampu ditutup oleh lembaga keuangan Barat.
Karena itu, setiap langkah konfrontatif terhadap Beijing berisiko menimbulkan shock ekonomi domestik. Filipina, misalnya, pernah mengalami tekanan dagang dari Cina setelah insiden Scarborough Shoal pada 2012, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi sektor perikanan dan perdagangan buah tropis. Pengalaman ini menjadi peringatan bagi negara lain: terlalu jauh melawan Cina bisa berarti sanksi dagang yang merugikan rakyat. Dengan demikian, ekonomi bertindak sebagai pengikat yang membatasi ruang manuver geopolitik negara-negara ASEAN.
Keterbatasan Militer ASEAN
Faktor kedua adalah jurang asimetri militer. Walaupun negara-negara ASEAN telah berupaya melakukan modernisasi alutsista, kesenjangan dengan kekuatan militer Cina tetap sangat besar. Laporan tahunan Military Balance yang diterbitkan International Institute for Strategic Studies (IISS, 2022) menegaskan bahwa anggaran pertahanan Cina melebihi gabungan seluruh anggaran pertahanan negara ASEAN.
Cina tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam teknologi. Armada laut Cina memiliki kapal perusak berteknologi mutakhir, kapal induk, serta sistem rudal anti-akses/area denial (A2/AD) yang dirancang untuk membatasi pergerakan musuh di Laut Cina Selatan. Sementara itu, negara-negara ASEAN menghadapi dilema klasik: keterbatasan anggaran, ketergantungan pada impor senjata, dan fragmentasi strategi pertahanan.
Sebagai contoh, Vietnam memang memperkuat armada kapal selamnya dengan membeli enam unit kelas Kilo dari Rusia, tetapi jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan kemampuan proyeksi kekuatan Beijing. Indonesia, Malaysia, dan Filipina pun menghadapi masalah serupa: alutsista yang menua, kemampuan logistik terbatas, dan koordinasi regional yang lemah. Dengan kondisi seperti ini, konfrontasi langsung dengan Cina bukan hanya tidak realistis, tetapi juga berpotensi kontraproduktif.
Ketidakpastian Amerika Serikat
Faktor ketiga adalah ketidakpastian Amerika Serikat sebagai penyeimbang utama di kawasan. Secara historis, Washington dipandang sebagai pelindung stabilitas Asia Tenggara melalui kehadiran militernya dan komitmen pada kebebasan navigasi (freedom of navigation operations). Namun, dalam praktiknya, komitmen AS kerap dipersepsikan fluktuatif.
Pemerintahan Barack Obama mengumumkan kebijakan Pivot to Asia, tetapi implementasinya terbatas karena terseret konflik di Timur Tengah. Donald Trump bahkan lebih parah: meskipun retorika anti-Cina keras, ia cenderung mengedepankan agenda America First, menarik diri dari kesepakatan Trans-Pacific Partnership (TPP), dan memunculkan keraguan di kalangan sekutu Asia (Campbell & Ratner, 2021). Joe Biden memang kembali menegaskan pentingnya Indo-Pasifik, tetapi negara-negara ASEAN tetap memandang komitmen AS tidak sepenuhnya bisa dijadikan sandaran, terlebih jika terjadi pergantian rezim politik di Washington.
Kondisi ini membuat ASEAN berhitung hati-hati. Mengandalkan AS terlalu dalam dianggap berisiko, karena dukungan tersebut bisa melemah sewaktu-waktu. Sebaliknya, terlalu frontal melawan Cina tanpa jaminan dukungan AS akan menjerumuskan negara-negara ASEAN ke dalam kerentanan strategis. Maka, pilihan paling aman adalah menunda konfrontasi, menjaga hubungan dengan kedua kekuatan besar, sembari memaksimalkan ruang diplomasi.
Karena itu, strategi “menunda konfrontasi” dipandang lebih rasional: menjaga hubungan baik dengan Beijing, sembari tetap membuka ruang kerja sama dengan kekuatan eksternal lain seperti AS, Jepang, dan Australia.
Dampak Jangka Panjang Strategi Cina di Laut Cina Selatan
Jika ditelaah dari perspektif jangka panjang, strategi Cina di Laut Cina Selatan (LCS) tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga transformasional. Langkah Beijing menyentuh berbagai level: dari pembentukan norma hukum internasional, perubahan dinamika ASEAN, hingga pergeseran struktur ekonomi-politik dan militerisasi kawasan. Empat dimensi berikut menggambarkan bagaimana konsekuensi strategi Cina akan mengakar dalam jangka panjang.
Hegemoni Normatif
Salah satu dampak paling signifikan adalah usaha Cina membentuk norma baru dalam hukum laut internasional. Klaim Nine-Dash Line yang secara konsisten ditegakkan oleh Beijing jelas bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama terkait konsep Exclusive Economic Zone (EEZ). Namun, melalui kehadiran berulang dan konsolidasi fakta di lapangan (fait accompli), Cina secara perlahan menciptakan preseden baru (Beckman, 2019).
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penolakan efektif, ada risiko bahwa klaim “alternatif” ini akan dianggap sebagai realitas hukum baru, bukan hanya sekadar anomali. Dengan kata lain, Cina tidak hanya menguasai wilayah laut secara fisik, tetapi juga menggeser epistemologi hukum maritim global. Bagi negara kecil, terutama di Asia Tenggara, ini adalah ancaman serius karena mereka kehilangan posisi tawar hukum di forum internasional.
Transformasi ASEAN
Strategi Cina juga membawa dampak sistemik pada integrasi kawasan ASEAN. Ketidakmampuan ASEAN untuk menghadapi agresivitas Beijing telah memperlihatkan kelemahan struktural organisasi ini: lambat dalam pengambilan keputusan, rentan terhadap fragmentasi, dan terikat prinsip non-interference yang seringkali melumpuhkan solidaritas kolektif.
Akibatnya, sentralitas ASEAN—sebuah konsep yang sejak lama dijadikan klaim identitas kawasan—perlahan berubah menjadi slogan tanpa substansi (Weatherbee, 2020). Beijing justru lebih efektif memainkan jalur bilateral, memanfaatkan relasi ekonomi dan politik dengan masing-masing negara untuk membelah konsensus regional. Filipina, Vietnam, dan Malaysia seringkali mengambil langkah berbeda dalam menghadapi Cina, sehingga ASEAN tidak pernah berbicara dengan satu suara.
Transformasi ini pada akhirnya melemahkan peran ASEAN sebagai institusi penyeimbang, menjadikannya sekadar forum diplomatik, bukan entitas strategis yang mampu melindungi kepentingan kolektif anggotanya.
Ketergantungan Ekonomi-Politik
Melalui Belt and Road Initiative (BRI), Cina tidak hanya mengamankan jalur maritim, tetapi juga membangun jejaring infrastruktur darat, laut, dan digital yang menjadikan negara ASEAN semakin terikat pada orbit Beijing (Rolland, 2017). Jalur kereta cepat, pelabuhan dalam, kawasan industri, hingga infrastruktur telekomunikasi 5G menjadi bagian dari ekosistem ketergantungan baru ini.
Ketergantungan tersebut bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga politik. Semakin besar peran Cina dalam pembangunan domestik suatu negara, semakin sulit bagi negara tersebut untuk mengambil posisi tegas terhadap Beijing dalam isu maritim. Mekanisme debt diplomacy atau diplomasi utang bahkan menciptakan risiko jangka panjang, sebagaimana terlihat dalam kasus Sri Lanka dengan Pelabuhan Hambantota. Walaupun tidak serta-merta terjadi di ASEAN, pola ini menjadi peringatan bahwa pengaruh Cina bisa mengikat negara melalui kombinasi insentif dan ketergantungan.
Dengan demikian, strategi Beijing di LCS bukan sekadar ekspansi maritim, tetapi bagian dari upaya membangun tatanan ekonomi-politik baru di Asia Tenggara.
Militerisasi Kawasan
Dimensi keempat adalah perubahan karakter LCS dari kawasan perdagangan menjadi arena militerisasi. Pembangunan pulau buatan di Spratly dan Paracel telah menghasilkan instalasi militer permanen, termasuk pangkalan udara, sistem radar, rudal jarak jauh, serta kehadiran kapal perang yang rutin berpatroli (O’Rourke, 2022).
Militerisasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan dengan negara-negara pengklaim lain, tetapi juga mengubah ekuilibrium keamanan kawasan. Dengan keberadaan pangkalan yang mampu menjangkau sebagian besar Asia Tenggara, Cina secara efektif memiliki keunggulan strategis yang dapat menghalangi akses militer asing—terutama Amerika Serikat—ke kawasan tersebut.
Dalam jangka panjang, militerisasi ini berpotensi menciptakan zona pengaruh eksklusif bagi Cina di Asia Tenggara, di mana kehadiran kekuatan eksternal semakin sulit, dan negara-negara kecil semakin terpaksa menyesuaikan diri dengan logika kekuatan Beijing.
Ketidakberanian Struktural ASEAN dalam Menghadapi Cina
Pertanyaan mengapa negara-negara ASEAN tidak berani menghadapi Cina secara langsung sesungguhnya berkaitan dengan ketidakberanian struktural. Bukan semata persoalan pilihan politik sesaat, melainkan keterikatan sistemik pada kondisi ekonomi, militer, dan politik regional yang membuat ASEAN berposisi defensif di hadapan Beijing. Tiga dimensi berikut menjelaskan akar masalah tersebut.
Ekonomi: Konsumen dari Pertumbuhan Cina
Secara ekonomi, negara-negara ASEAN adalah “konsumen” dari kebangkitan ekonomi Cina. Hubungan ini bersifat asimetris: sementara ASEAN menjadi pemasok bahan mentah, tenaga kerja, dan pasar bagi produk Cina, Beijing menjadi motor investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur di kawasan.
Data menunjukkan bahwa Cina telah menjadi mitra dagang terbesar hampir semua negara ASEAN sejak awal 2010-an. Bahkan, pada 2020, total perdagangan ASEAN–Cina mencapai lebih dari USD 680 miliar, melampaui hubungan dagang ASEAN dengan Uni Eropa maupun Amerika Serikat (ADB, 2021).
Konsekuensinya, menghadapi Beijing sama saja dengan mengguncang fondasi pertumbuhan domestik. Pemerintah ASEAN sadar bahwa konfrontasi terbuka berpotensi menghambat aliran investasi, pariwisata, serta proyek-proyek besar yang menjadi basis legitimasi politik mereka di dalam negeri. Dengan kata lain, Cina bukan hanya mitra dagang, tetapi juga “penyelamat ekonomi” yang sulit ditolak.
Militer: Ketimpangan Kekuatan dengan PLA Navy
Dari aspek militer, ketimpangan antara kekuatan Cina dan ASEAN sangat jelas. Bahkan jika ASEAN bersatu dalam sebuah koalisi hipotetis, mereka tetap tidak mampu menandingi People’s Liberation Army Navy (PLA Navy).
Cina kini memiliki salah satu armada laut terbesar di dunia, dengan kapal induk, kapal perusak berteknologi canggih, rudal hipersonik, hingga sistem anti-akses/area denial (A2/AD) yang secara langsung mengungguli kemampuan maritim negara-negara ASEAN (Cordesman, 2019).
Sebaliknya, kekuatan militer ASEAN bersifat terfragmentasi dan difokuskan pada kebutuhan domestik, bukan pada pertahanan kolektif. Vietnam memang meningkatkan belanja pertahanan dan mengakuisisi kapal selam dari Rusia; Singapura memiliki teknologi militer yang relatif maju; namun negara lain seperti Laos, Kamboja, atau Myanmar nyaris tidak relevan dalam dinamika keamanan maritim.
Hasilnya adalah jurang asimetri yang sangat lebar: PLA Navy bukan hanya lebih unggul, tetapi juga mampu menciptakan dominasi psikologis yang membuat ASEAN enggan melakukan konfrontasi militer langsung.
Politik: Jerat Prinsip “Non-Interference”
Secara politik, ASEAN terjebak dalam prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan internal negara anggota lain. Prinsip ini, yang awalnya menjadi fondasi stabilitas kawasan sejak berdirinya ASEAN, justru menjadi penghalang utama dalam merumuskan sikap kolektif terhadap Cina.
Ketika Filipina memenangkan gugatan arbitrase 2016 di Den Haag, ASEAN tidak pernah mampu mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas mendukung Manila. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas kawasan dikorbankan demi menjaga status quo (Acharya, 2017).
Selain itu, kecenderungan negara-negara anggota untuk mencari keuntungan bilateral dari Beijing memperparah fragmentasi politik ASEAN. Kamboja dan Laos, misalnya, secara konsisten menjadi penghalang konsensus ASEAN dalam isu Laut Cina Selatan karena ketergantungan ekonomi mereka yang tinggi pada Cina.
Dengan demikian, prinsip non-interference berubah menjadi bentuk “paralisis kolektif”, di mana ASEAN lebih memilih diam atau menghindar ketimbang menyusun strategi konfrontasi bersama.
Dalam situasi ini, hegemoni Cina tidak perlu dipaksakan dengan perang. Ia tumbuh dari kepasrahan dan kompromi negara-negara tetangga.
Kesimpulan
Strategi Cina di Laut Cina Selatan menunjukkan bagaimana sebuah kekuatan besar dapat membangun hegemoni tanpa harus menempuh konfrontasi total. Dengan strategi bertahap, Beijing berhasil mengubah realitas kawasan secara de facto. Sementara itu, negara-negara ASEAN memilih politik ambivalensi, menunda konfrontasi, dan mengandalkan diplomasi tanpa hasil yang signifikan.
Dalam jangka panjang, situasi ini akan mengarah pada normalisasi pengaruh Cina di Asia Tenggara. LCS tidak lagi hanya menjadi sengketa teritorial, melainkan simbol dari ketidakmampuan negara-negara kecil menghadapi sebuah kekuatan besar. Hegemoni Cina pada akhirnya diterima bukan karena legitimasi hukum, tetapi karena realitas politik dan ekonomi yang tidak terbantahkan.
Daftar Pustaka
Acharya, A. (2017). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. Routledge.
Asian Development Bank. (2021). Asian Development Outlook 2021. Manila: ADB.
ASEAN Studies Centre. (2022). The State of Southeast Asia Survey 2022. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Beckman, R. (2019). The South China Sea dispute and UNCLOS: A legal perspective. Ocean Development & International Law, 50(1), 34–53.
Buszynski, L., & Roberts, C. (2015). The South China Sea and Australia’s Regional Security Environment. Routledge.
Campbell, K. M., & Ratner, E. (2021). The China reckoning: How Beijing defied American expectations. Foreign Affairs, 97(2), 60–70.
Council on Foreign Relations. (2022). China’s Maritime Disputes. CFR Backgrounder.
Cordesman, A. (2019). China’s Military Modernization and Force Development. CSIS.
Emmers, R. (2018). Security strategies of middle powers in the Asia-Pacific. Australian Journal of International Affairs, 72(5), 450–466.
Friedberg, A. (2018). Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia. W.W. Norton.
Heydarian, R. J. (2018). The Rise of Duterte: A Populist Revolt against Elite Democracy. Palgrave Macmillan.
International Crisis Group. (2023). Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled Waters. Brussels: ICG.
International Institute for Strategic Studies. (2022). The Military Balance 2022. London: IISS.
Kaplan, R. D. (2014). Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific. Random House.
O’Rourke, R. (2022). China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities. Congressional Research Service.
Permanent Court of Arbitration. (2016). The South China Sea Arbitration Award. The Hague.
RAND Corporation. (2021). China’s Strategic Priorities in the South China Sea. Santa Monica: RAND.
Rolland, N. (2017). China’s Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative. National Bureau of Asian Research.
Shambaugh, D. (2020). Where Great Powers Meet: America and China in Southeast Asia. Oxford University Press.
Storey, I. (2017). The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions. ISEAS.
Sukma, R. (2021). Indonesia and the South China Sea: Between nationalist pressures and strategic ambiguity. Contemporary Southeast Asia, 43(1), 1–25.
Thayer, C. A. (2020). Vietnam’s defense policy in the South China Sea. Asian Security, 16(2), 119–137.
Weatherbee, D. (2020). International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. Rowman & Littlefield.
World Bank. (2021). East Asia and Pacific Economic Update: Rebuilding Better. Washington, DC.

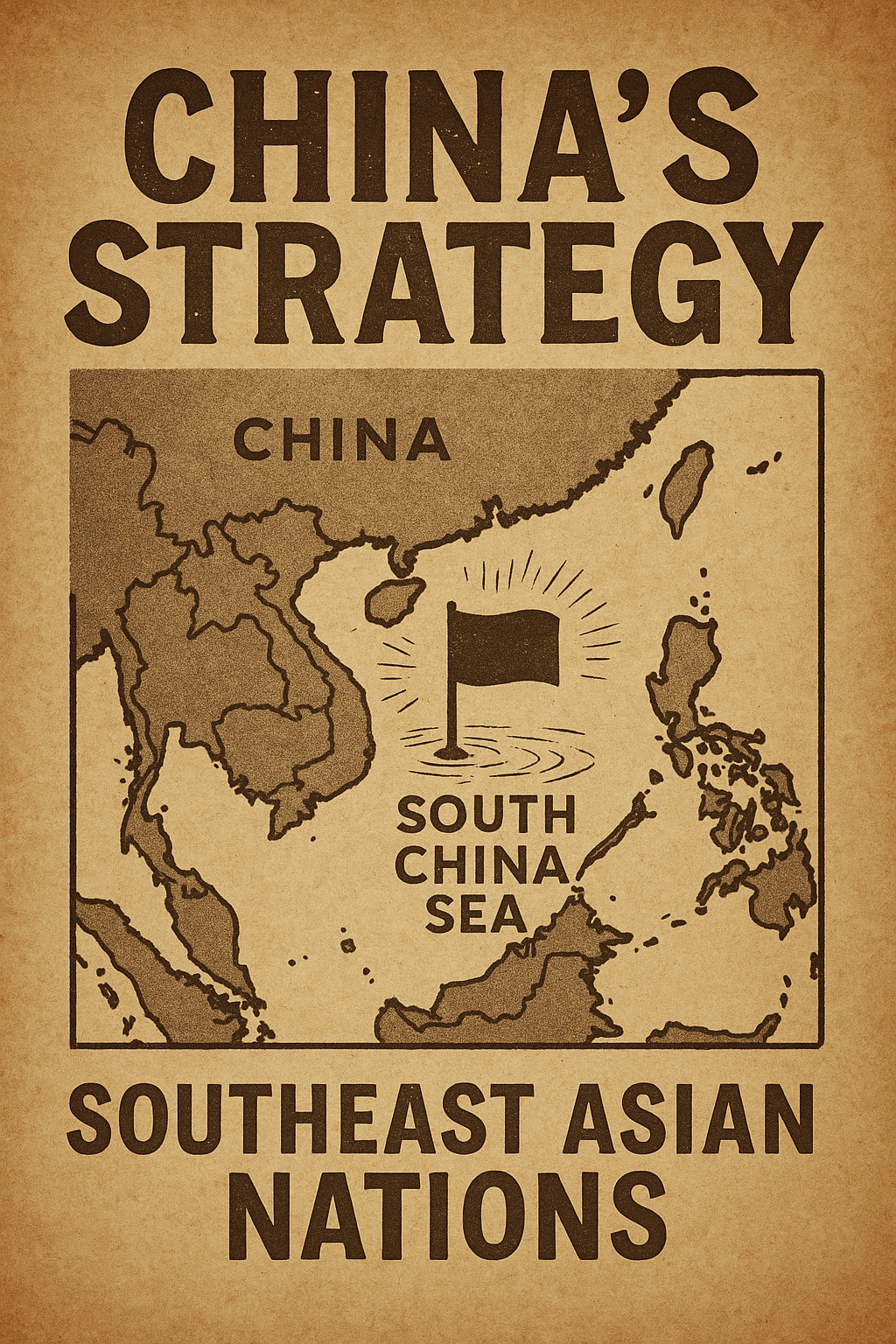
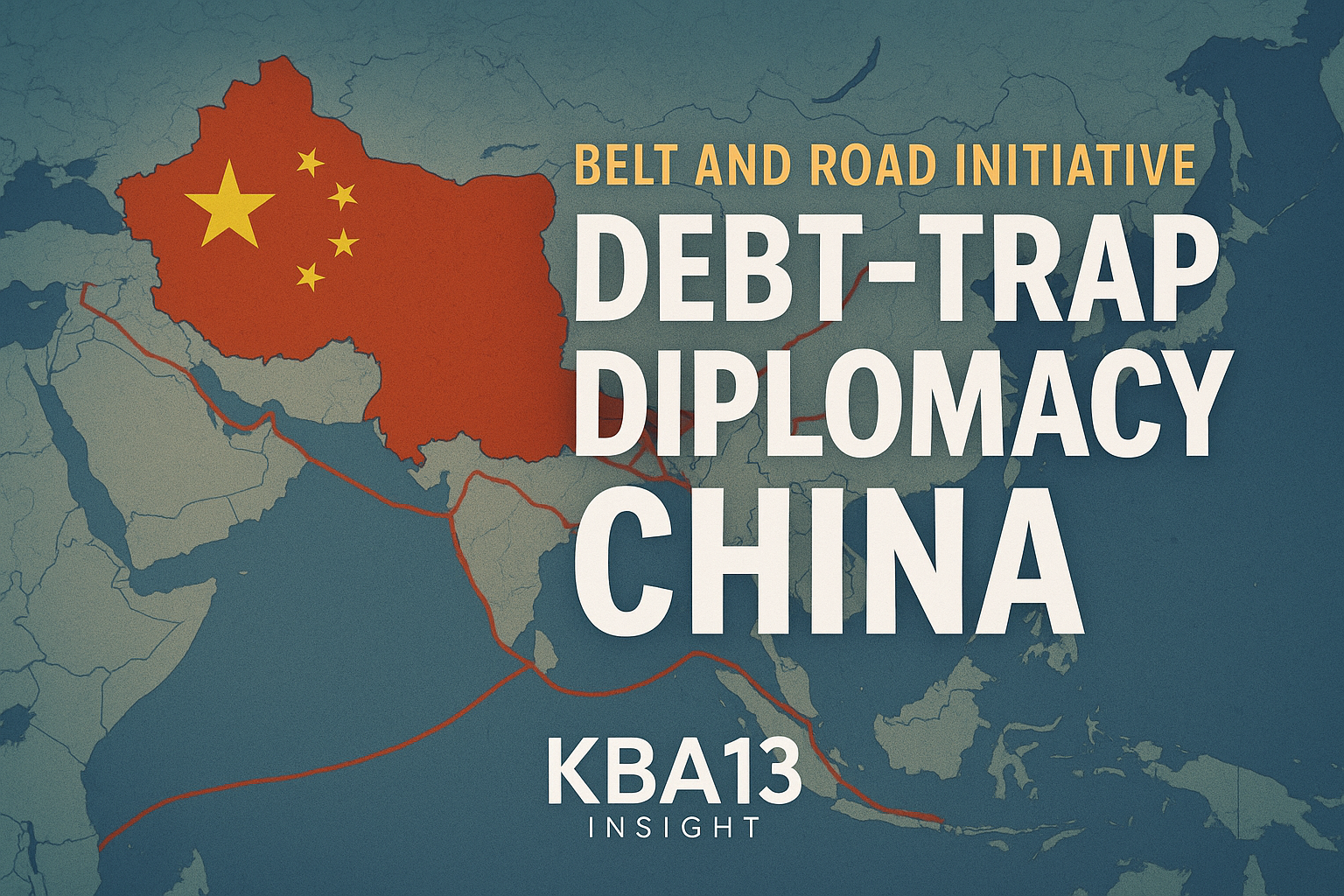
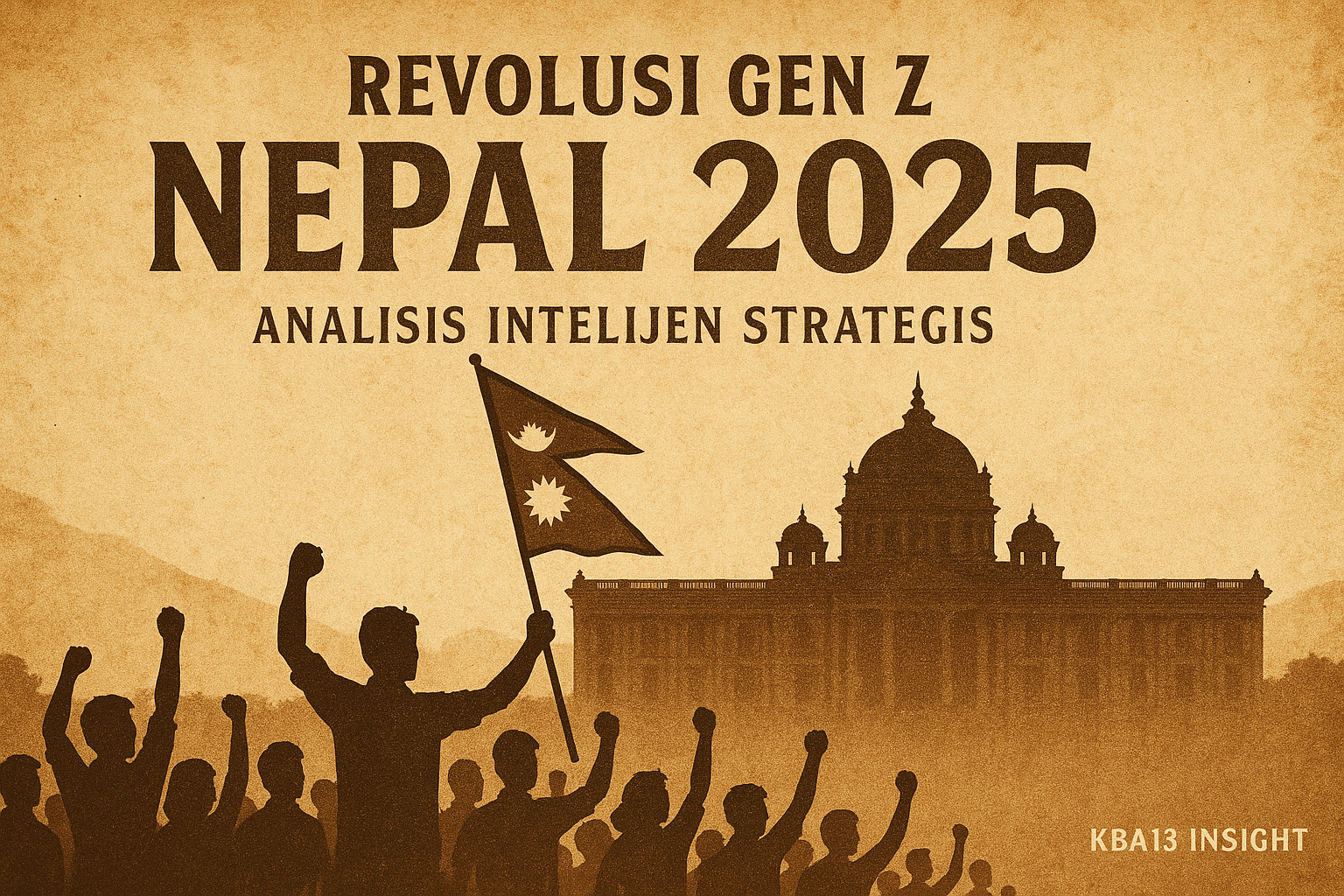



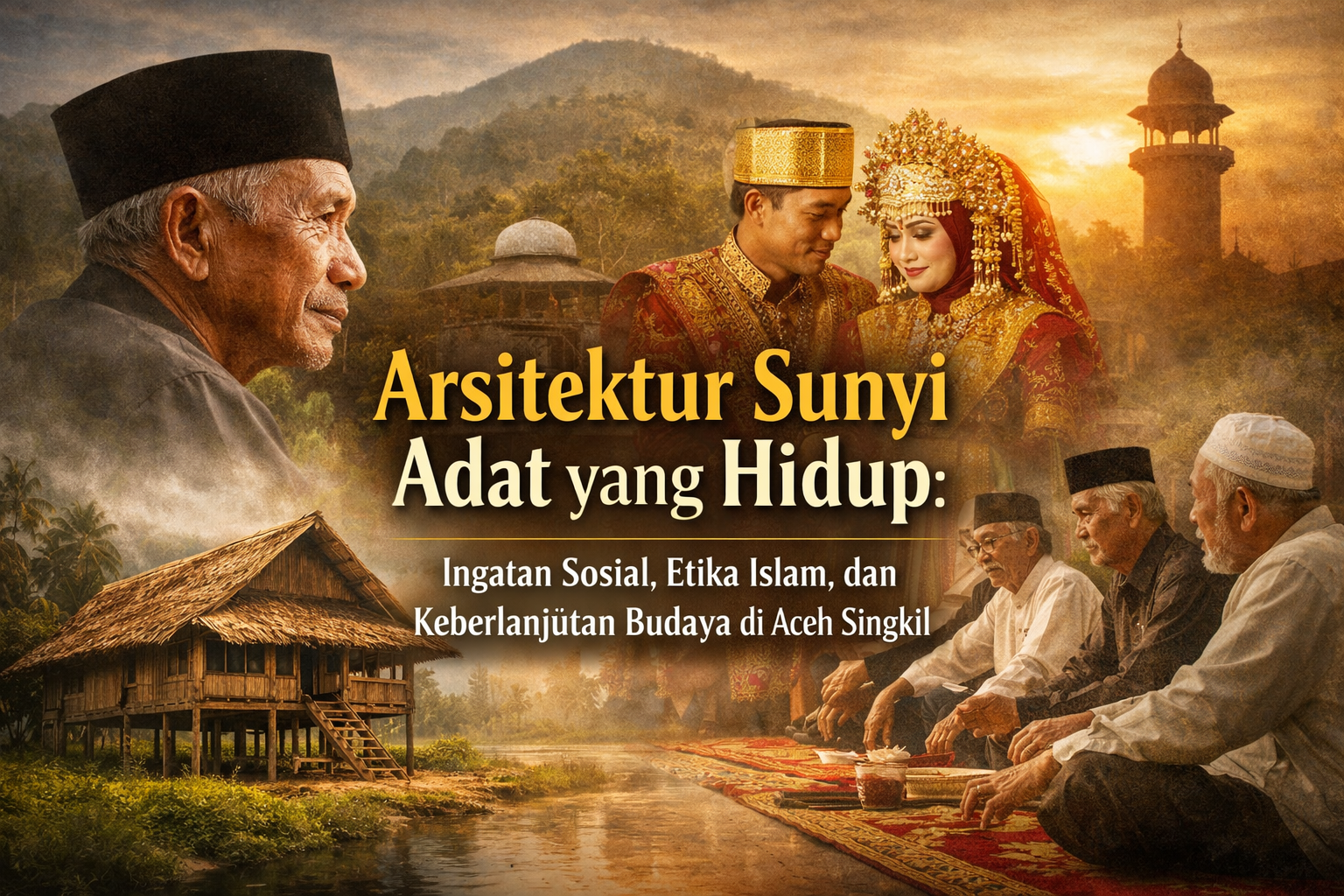
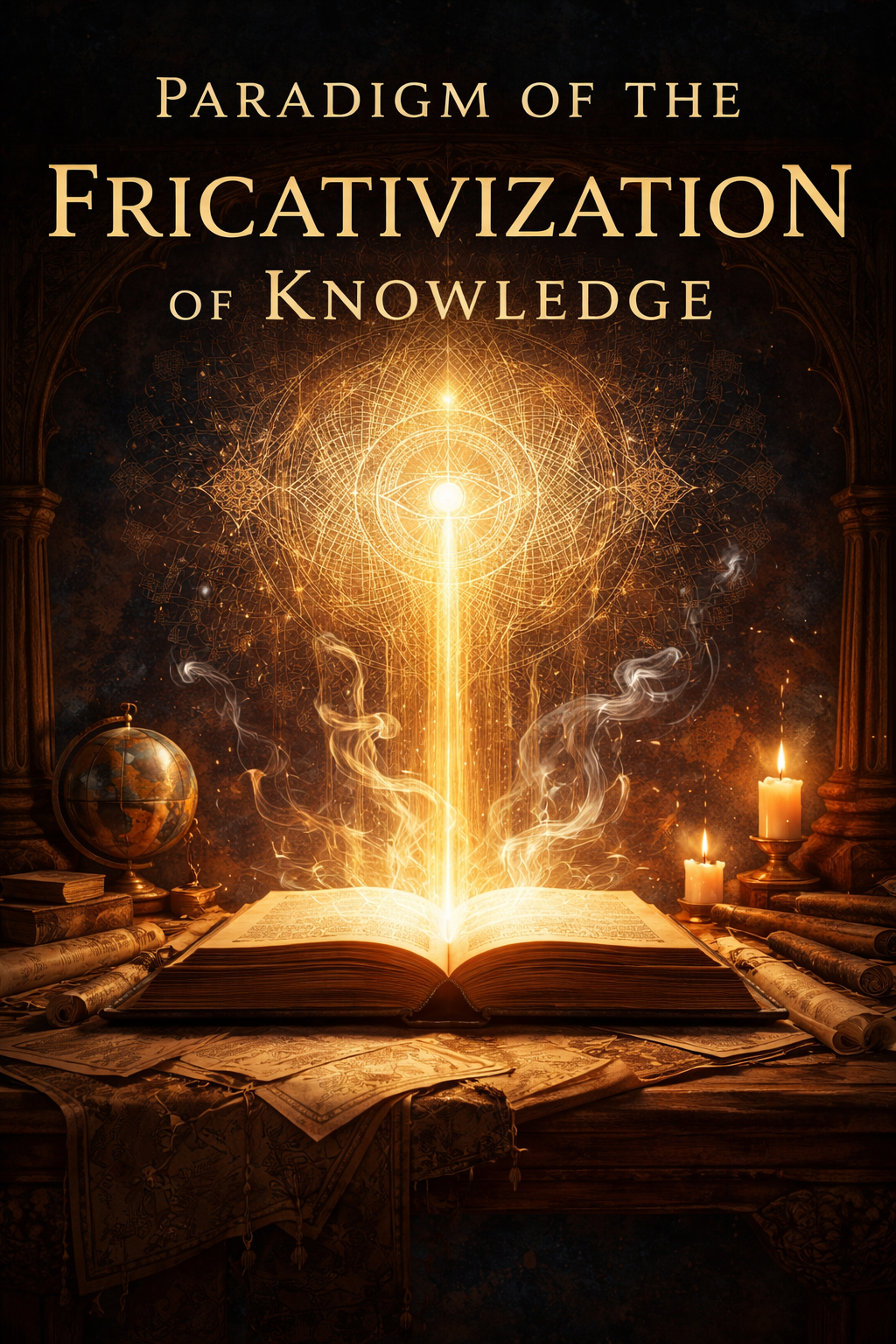
Leave a Reply