Pendahuluan: Mengapa MMO Penting untuk Membaca Modernitas
Modern Moral Order (MMO)—atau tatanan moral modern—adalah kunci untuk memahami bagaimana modernitas membentuk cara berpikir tentang moralitas, politik, ekonomi, dan ruang batin manusia. Dalam kerangka Charles Taylor, MMO menjelaskan pergeseran dari tatanan kosmik-hierarkis ke imajinasi sosial yang berpusat pada individu setara yang mencari manfaat bersama. MMO bukan sekadar istilah; ini lensa analitis untuk membaca mengapa “hak”, “kesejahteraan”, dan “non-dominasi” menjadi kata kunci peradaban atlantik modern.
Pentingnya MMO tidak berdiri sendiri; konsep ini berjalin-kelindan dengan gagasan “immanent frame” (kerangka keduniaan) yang membuat kehidupan sosial berjalan seolah cukup dijelaskan dan dibenarkan dari dalam dunia ini. Kerangka tersebut tidak otomatis meniadakan agama, tetapi mengubah “kondisi keberimanan” menjadi salah satu kemungkinan di antara pilihan bermakna lain dalam masyarakat plural. Konsekuensinya, perdebatan moral-politik tidak lagi bertumpu pada rujukan transenden tunggal, melainkan pada justifikasi publik yang diakui oleh para warga setara. l
Sebagai paradigma, MMO membantu memahami mengapa konsep “masyarakat” dipahami sebagai hasil konsensus dan kontrak antarmanusia, bukan pancaran dari hierarki kosmik. Di sini, legitimasi kekuasaan menuntut alasan yang dapat dibagikan tanpa mengandaikan doktrin teologis tertentu. MMO, dengan demikian, memetakan jalan dari tatanan sakral menuju tata kelola yang menuntut alasan publik dan pengakuan timbal balik.
MMO berfungsi sebagai “kapabilitas penjelas”: menjelaskan mengapa institusi modern—dari pengadilan, parlemen, hingga pasar—memerlukan legitimasi berbasis hak, bukan hak istimewa turun-temurun. Analisis risiko politik, kebijakan kesejahteraan, sampai debat bioetika kontemporer menjadi lebih terbaca ketika ditaruh di atas peta MMO.
Di tingkat budaya, MMO berkorelasi dengan “penegasan kehidupan biasa”—kerja, keluarga, kesehatan, pendidikan—yang dijadikan locus etika dan politik. Orientasi ini merombak skala nilai: kesalehan tidak lagi harus diukur lewat laku asketik melainkan juga lewat produktivitas, kemanfaatan, dan pengurangan penderitaan.
Pada saat yang sama, MMO memunculkan paradoks: semakin berhasil mengatur dunia, semakin kuat kecenderungan mengurung makna pada tataran imanen. Di sinilah keluhan tentang “penyihiran yang lenyap” (disenchantment) dan “diri yang terperisai” (buffered self) bergaung: modernitas kuat dalam kapasitas instrumental, tetapi rentan terhadap kekosongan makna.
Artikel ini mengusulkan pemakaian MMO sebagai alat evaluasi kebijakan, riset sosial, dan kerja-kerja intelektual keislaman di Indonesia—agar analisis publik tidak terjebak pada slogan, tetapi bertumpu pada peta genealogis modernitas yang kokoh.
Genealogi: Dari Perang Agama ke Grotius dan Locke
Genealogi MMO paling jelas muncul dari letupan perang agama Eropa abad ke-16–17. Kekacauan domestik-internasional memaksa para pemikir mencari dasar legitimasi politik melampaui klaim teologis sektarian. Dari krisis inilah kebutuhan akan “bahasa netral” tentang ketertiban dan keadilan modern memperoleh daya dorong.
Hugo Grotius merumuskan natural law yang—secara provokatif—tetap berdiri “sekalipun seandainya Tuhan tidak ada” (etiamsi daremus). Formulasi ini bukan ateisme, melainkan strategi konseptual untuk menambatkan norma internasional pada rasionalitas yang dapat diakses semua pihak lintas konfesi. Dengan cara itu, hukum perang-damai, kontrak, dan hak komersial memperoleh basis justifikasi non-sektarian yang kompatibel dengan dunia antarnegara modern.
John Locke mengangkat fondasi itu ke ranah hak-hak politik: hidup, kebebasan, dan milik sebagai hak kodrati yang mendahului negara. Kekuasaan yang sah adalah yang lahir dari persetujuan rakyat setara; negara dibatasi untuk melindungi hak, bukan mengilhamkan keselamatan jiwa. Surat tentang Toleransi menegaskan pemisahan yang sehat antara urusan negara dan keselamatan rohani, menutup celah bagi dogma tunggal sebagai dasar pemaksaan publik.
Dari Grotius dan Locke, terbentuk horizon baru tempat masyarakat dipahami sebagai ciptaan agen-agen setara, bukan miniatur kosmos. Legitimasi diukur melalui daya masuk akal dan penerimaan publik, bukan korespondensi dengan tatanan hierarkis metafisik.
Kerangka baru tersebut secara bertahap menyusup ke imajinasi sosial: kontrak, kewargaan, pasar, dan opini publik menjadi kosakata operasional modernitas. MMO, dalam pengertian ini, adalah “ruang moral bersama” tempat warga setara berunding tentang keadilan tanpa menuntut rujukan transenden tunggal sebagai prasyarat.
Genealogi MMO juga ditopang oleh “penjinakan” oligarki feodal: disiplin militer-birokratik, monetisasi ekonomi, dan rasionalisasi organisasi keagamaan. Modernitas tidak menghapus agama, tetapi menertibkan peran publiknya agar kompatibel dengan tatanan damai dan pertukaran.
Melalui proses ini, lahir kebutuhan akan institusi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga setara: konstitusi, pemilihan, dan yudikatif independen. MMO menuntut “alasan yang dapat dibagikan”, sehingga klaim otoritas harus mengambil bentuk yang dapat diuji dalam ruang publik.
Ringkasnya, genealogi MMO adalah strategi intelektual menghadapi kekerasan teologis—mendesain ulang dasar kebersamaan agar damai sosial dapat berdiri di atas justifikasi rasional yang dapat diakses semua.
Arsitektur Inti: Individu Setara, Manfaat Bersama, dan Instrumentalitas
Pertama, MMO berangkat dari individu setara sebagai unit dasar. Masyarakat dipahami sebagai konstruksi manusia untuk kebaikan bersama, bukan derivasi dari urutan kosmik yang given. Konsekuensinya, setiap klaim institusional harus lulus uji: apakah meningkatkan kemaslahatan para warga setara?
Kedua, prinsip normatif utama adalah rasa hormat timbal balik dan pelayanan antarsesama. Hak dan kewajiban dimaknai sebagai mekanisme pengakuan, bukan hadiah hierarki. Budaya “non-dominasi” menjadi horizon etik: kekuasaan yang sah meyakinkan melalui alasan, bukan memaksa melalui sakralitas.
Ketiga, diferensiasi sosial—kelas, profesi, birokrasi—dianggap sah secara instrumental sejauh melayani kepentingan umum. Tiada status ontologis yang melekat; struktur adalah alat untuk tujuan bersama. Inilah perbedaan tajam dengan tatanan pra-modern yang membenarkan hierarki sebagai bagian dari ordo tetap.
Keempat, MMO mengutamakan jaminan hidup dan akses sumber daya. Dari sinilah perumusan hak asasi modern, kebijakan kesejahteraan, hingga standar “due process of law” mendapatkan legitimasi moral. Hak tidak lagi bonus kultural, melainkan prasyarat tatanan yang adil.
Kelima, MMO bergerak dari peran interpretatif—membaca tatanan yang ada—menjadi preskriptif—menuntut realisasi aktif. Modernitas tidak cukup dijelaskan; modernitas menuntut program: pendidikan massa, kesehatan publik, keamanan sosial.
Keenam, meski Taylor mengakui ada “komponen ontik” (mis. martabat manusia), fondasi pengikat dalam masyarakat modern beroperasi sebagai pengakuan antarrasional—martabat bersama para agen otonom—alih-alih merujuk ke kosmos atau kehendak ilahi sebagai status normatif publik.
Ketujuh, arsitektur ini mengikat masyarakat ke dalam waktu sekuler. MMO mendorong sikap instrumental terhadap dunia—perencanaan, pengukuran, optimasi—seraya menyediakan bingkai etis agar instrumentalisasi tidak berubah menjadi dominasi.
Penanaman: Imajinasi Sosial, Disiplin, dan “Masyarakat Santun”
Taylor menegaskan bahwa MMO tertanam melalui tiga bentuk pemahaman diri sosial: ekonomi sebagai realitas terobjektifikasi, ruang publik, dan praktik pemerintahan-diri demokratis. Ketiganya membentuk “imajinasi sosial” yang membuat tindakan modern terasa masuk akal bagi pelakunya.
“Ekonomi” dipandang sebagai tatanan dengan hukum-hukumnya sendiri; kebijakan diperdebatkan melalui metrik produksi, harga, pekerjaan, dan kesejahteraan. “Ruang publik” menjadi arena pertukaran argumen, di mana otoritas diuji lewat alasan, bukan asal-usul. “Pemerintahan-diri” menuntut warga aktif yang memikul tanggung jawab kolektif.
Penanaman MMO diperkuat oleh rezim disiplin: sekolah, barak, birokrasi, dan pabrik. Rasionalisasi organisasi meningkatkan produktivitas sekaligus menundukkan perilaku pada standar “kesopanan” dan “peradaban”. Di sini damai sosial dan pembangunan ekonomi diposisikan sebagai tujuan moral bersama.
Dalam agama, terbentuk Deisme Providensial: Tuhan dipahami sebagai arsitek tatanan rasional yang menopang kebaikan bersama; fokus iman bergeser ke moralitas sipil dan keteraturan sosial. Efeknya ganda: agama kompatibel dengan tata-dunia modern, tetapi sekaligus berisiko menyempit menjadi moralisme utilitarian.
Budaya “masyarakat santun” menguat sebagai standar tata kelola yang baik, relatif independen dari otoritas gerejawi tertentu. Kesalehan publik diukur melalui ketaatan pada aturan bersama, bukan semata ritual komunal; “kekecewaan” (disenchantment) menjadi konsekuensi, tetapi juga membuka ruang toleransi.
Konsep MMO lalu mengalami perluasan—baik jangkauan maupun intensitas—dengan beragam “redaksi.” Rousseau menekankan kehendak umum dan pendidikan warga; Marx mengecam keterasingan dalam ekonomi kapitalis; keduanya memutakhirkan, mengkritik, dan mengusulkan rekayasa ulang tatanan demi emansipasi.
Akhirnya, penegasan “kehidupan biasa” menjadi ethos dominan: mengurangi penderitaan, memperluas kemakmuran, meningkatkan harapan hidup. MMO menilai kebaikan dari dampak nyata pada kesejahteraan warga, bukan dari koherensi metafisis sistem semata.
Sekularitas-3, Immanent Frame, dan Humanisme Eksklusif
Dalam peta Taylor, sekularitas punya tiga makna; yang relevan di sini adalah “sekularitas-3”: perubahan kondisi keberimanan. Modernitas menciptakan latar di mana iman menjadi salah satu opsi bermakna di antara yang lain, bukan horizon default. Transformasi ini tidak identik dengan ateisme; yang berubah adalah “bagaimana mungkin percaya”.
Immanent frame mengacu pada cara masyarakat mengoperasikan makna dan legitimasi dari dalam dunia ini—sains, ekonomi, hukum, opini publik—tanpa perlu mengandaikan referensi transenden untuk berjalan. Kerangka ini kompatibel dengan pluralitas keyakinan, tetapi cenderung menomorsatukan rasionalitas instrumental yang terukur.
Humanisme eksklusif muncul sebagai etika yang menambatkan martabat, kebebasan, dan kebaikan bersama pada kapasitas manusia. Etika ini mewarisi komitmen MMO akan ketertiban, hak, dan manfaat bersama, tanpa mengikat diri pada soteriologi keagamaan tertentu. Dalam praktik kebijakan, humanisme eksklusif sering menjadi bahasa bersama antarwarga dalam demokrasi liberal.
Penegasan “kehidupan biasa” meneguhkan prioritas pada pengurangan penderitaan, kesehatan publik, pendidikan, dan hak sosial. Rasionalitas kebijakan menilai kebaikan lewat dampak pada kesejahteraan, bukan sekadar kesahihan teologis. Orientasi ini membantu menghasilkan institusi kesejahteraan dan standar hak asasi modern.
Namun, immanent frame juga memunculkan rasa hampa: ketika semua nilai disubordinasikan ke hasil terukur, pengalaman “kepenuhan” moral-eksistensial melemah. Di sinilah Taylor dan para komentatornya membuka kemungkinan “rekoneksi” melalui seni, musik, dan praktik yang mengembalikan kedalaman makna tanpa harus meniadakan pencapaian modern.
Dari sudut pandang analisis kebijakan, sekularitas-3 menuntut literasi moral publik: keputusan bersama harus bertumpu pada alasan yang dapat diakses semua, seraya tetap membuka ruang bagi kontribusi tradisi religius sebagai sumber makna dan motivasi etis di ruang sipil.
Pada tataran global, format MMO paling mapan di masyarakat Atlantik Utara. Namun penyebarannya tidak seragam; resistensi, adaptasi kreatif, dan hibridisasi terjadi ketika MMO bersinggungan dengan tradisi non-Barat. Di titik ini, debat tentang “pasca-sekuler” dan “pluralisme nilai” menjadi relevan untuk manajemen perbedaan.
Redaksi, Ekspansi, dan Paradoks: Dari Rousseau sampai Marx
Rousseau menyuntikkan sensibilitas republikan: kedaulatan rakyat, kebajikan sipil, dan pendidikan sebagai mesin pembentukan warga. MMO menerima koreksi: kebebasan tidak cukup berarti “non-gangguan”; perlu pembentukan disposisi agar warga mampu mengejar kebaikan umum, bukan sekadar preferensi privat.
Marx menawarkan kritik struktural atas ekonomi modern—mengungkap keterasingan dan dominasi yang tersembunyi di balik bahasa kontrak setara. MMO dinilai gagal bila hanya menyandarkan keadilan pada persetujuan formal tanpa menilai kekuasaan material. Kritik ini memperluas MMO ke arah distribusi dan relasi produksi.
Ekspansi “hak” dalam modernitas—dari hak sipil-politik menuju hak sosial, ekonomi, dan kultural—menunjukkan bahwa MMO bersifat dinamis. Standar pengakuan bergeser seiring sensitivitas baru terhadap kerentanan dan ketimpangan. Ini memperkaya horizon keadilan sekaligus memicu tuduhan “inflasi hak”.
Paradoks muncul: semakin preskriptif dan komprehensif, MMO kerap menimbulkan kelelahan normatif. Negara kesejahteraan memerlukan kapasitas fiskal dan administrasi yang besar; ketika legitimasi moral tinggi, ekspektasi publik ikut melambung. Krisis fiskal dan populisme sering memanfaatkan jurang antara janji dan kemampuan.
Di sisi lain, agama menegosiasikan peran baru: bukan sebagai sumber monopoli kebenaran publik, melainkan mitra etis bagi tujuan kemanusiaan. Model ini menuntut kompetensi dialogis—kemampuan berbicara dalam bahasa alasan publik sembari memelihara kedalaman rohani.
Implikasinya, MMO bukan doktrin beku, melainkan arena kontestasi kreatif. Taylor menyarankan membaca modernitas sebagai “banyak kisah”—bukan garis lurus—dengan ragam jalan menuju koeksistensi antara iman, sains, dan demokrasi.
Implikasi Strategis: Kebijakan, Ruang Publik, dan Lintas-Peradaban
Dalam kebijakan, MMO menuntut perumusan tujuan publik yang dapat dibenarkan dengan alasan terbuka. Reformasi sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial mestilah bertolak dari martabat warga setara, bukan sekadar kalkulus biaya-manfaat. Standar HAM memberi pagar agar instrumentalisasi tidak melanggar pengakuan.
Untuk ruang publik, MMO menegaskan pentingnya infrastruktur deliberasi—media yang akuntabel, kebebasan berpendapat, dan literasi informasi—agar opini publik tidak disandera oligopoli informasi. Legitimasi kebijakan bergantung pada kualitas alasan yang beredar di ruang publik.
Di ranah ekonomi, MMO menafsir “ekonomi” sebagai tatanan yang diobjektifkan; karena itu, tata kelola pasar wajib memediasi antara efisiensi dan keadilan distributif. Krisis legitimasi muncul ketika pasar memproduksi ketimpangan yang merusak pengakuan setara antarkewarga.
Lintas-peradaban, penerjemahan MMO memerlukan kepekaan terhadap sumber-sumber moral lokal. Tradisi keagamaan, adat, dan kebijaksanaan komunitas dapat memberi energi normatif bagi tujuan modern—kesehatan publik, pendidikan, anti-korupsi—tanpa harus dihapus atau disubordinasikan secara sinis.
Dalam kajian keamanan, MMO membantu membaca “stabilitas” bukan sekadar absennya kekerasan, tetapi hadirnya institusi yang diakui adil oleh warga setara. Program deradikalisasi, misalnya, tidak cukup mengandalkan represi; lebih efektif jika meneguhkan pengakuan, partisipasi, dan peluang ekonomi yang fair.
Secara kultural, kritik terhadap “kekosongan makna” mengundang restorasi dimensi keindahan dan kedalaman. Seni dan tradisi spiritual dapat menjadi jembatan yang mengembalikan resonansi tanpa membongkar pranata rasional modern.
Pada akhirnya, MMO mengajak peradaban menyeimbangkan tiga hal: pengakuan, keadilan, dan efektivitas. Kegagalan menjaga salah satu akan memicu krisis legitimasi yang pada gilirannya membuka ruang bagi politik afektif yang anti-plural.
Penutup: Modernitas sebagai Latihan Pengakuan
MMO memberikan peta yang rapi untuk membaca modernitas: masyarakat sebagai hasil konsensus warga setara; legitimasi sebagai kerja alasan publik; dan keadilan sebagai pengakuan martabat bersama. Peta ini membantu menilai kebijakan, memampukan dialog antartradisi, dan menyiapkan ruang publik yang tahan uji.
Dalam horizon Taylor, tantangannya bukan memilih antara iman atau sekularitas, melainkan merawat ekologi makna di dalam immanent frame. Modernitas kuat mengatur dunia, tetapi rapuh menghadirkan kedalaman; tugas intelektual dan kebijakan adalah memastikan keduanya tidak saling meniadakan.
Untuk pembaca KBA13, pelajaran praktisnya jelas: perkuat alasan publik, pelihara pengakuan martabat, dan buat institusi bekerja. Di atas fondasi MMO, peradaban dapat menapaki jalur damai yang manusiawi tanpa kehilangan ruang transendensi yang menyehatkan.
Rujukan
-
Taylor, C. (2004). Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press. (Lihat ringkasan penerbit tentang tiga bentuk kultural: ekonomi, ruang publik, dan pemerintahan-diri). Duke University Press
-
Taylor, C. (2007). A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Teks penuh—edisi PDF daring). laisve.lt
-
Notre Dame Philosophical Reviews. (2008). Review: A Secular Age. (Ulasan akademik yang merangkum tesis utama Taylor). Notre Dame Philosophical Reviews
-
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2005/2023). Hugo Grotius. (Bahasan “etiamsi daremus” dan De Jure Belli ac Pacis). Stanford Encyclopedia of Philosophy
-
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2005/2020). Locke’s Political Philosophy. (Hak kodrati, kontrak sosial, toleransi). Stanford Encyclopedia of Philosophy
-
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2022). Philosophy of International Law. (Konteks Grotius dan fondasi hukum internasional modern). Stanford Encyclopedia of Philosophy
-
The New Yorker. (2024). How the Philosopher Charles Taylor Would Heal the Ills of Modernity. (Konteks kontemporer tentang krisis makna dan seni). The New Yorker
-
Partially Examined Life. (2018). Charles Taylor, Providential Deism and the Impersonal Order. (Penjelas sekunder tentang Deisme Providensial). Partially Examined Life
Catatan: Sumber primer Taylor dan entri Stanford Encyclopedia menjadi rujukan utama; sumber sekunder digunakan sebagai pendamping untuk memperjelas istilah teknis.



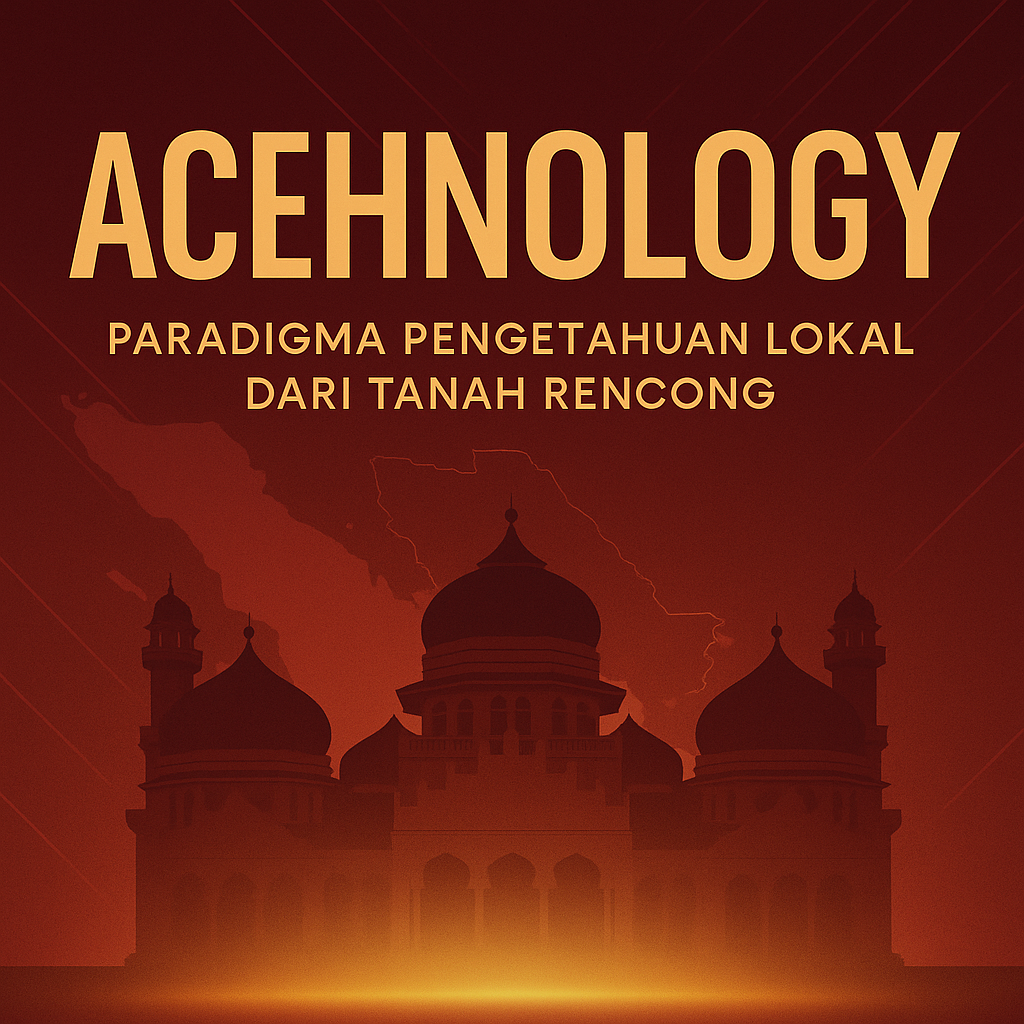
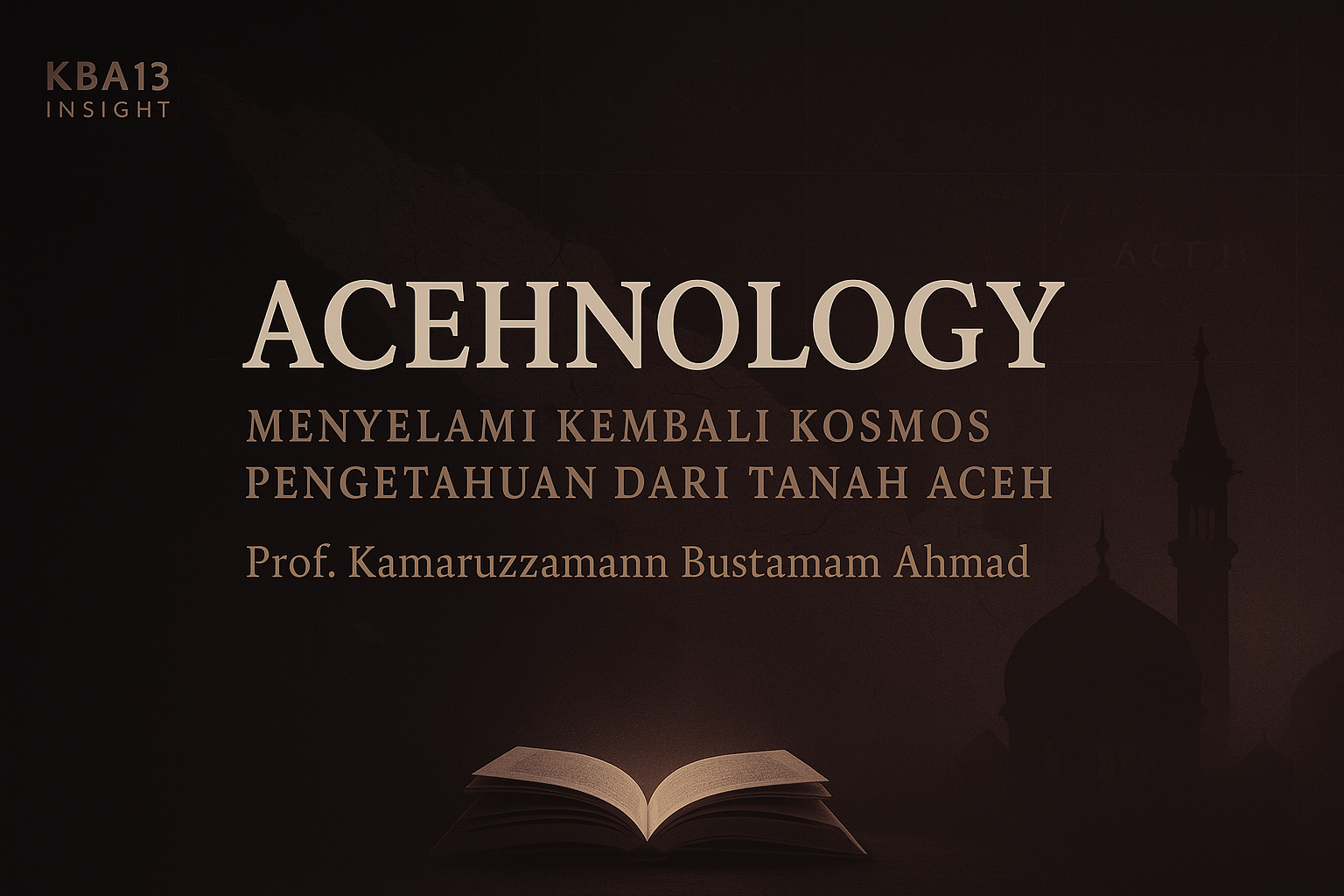
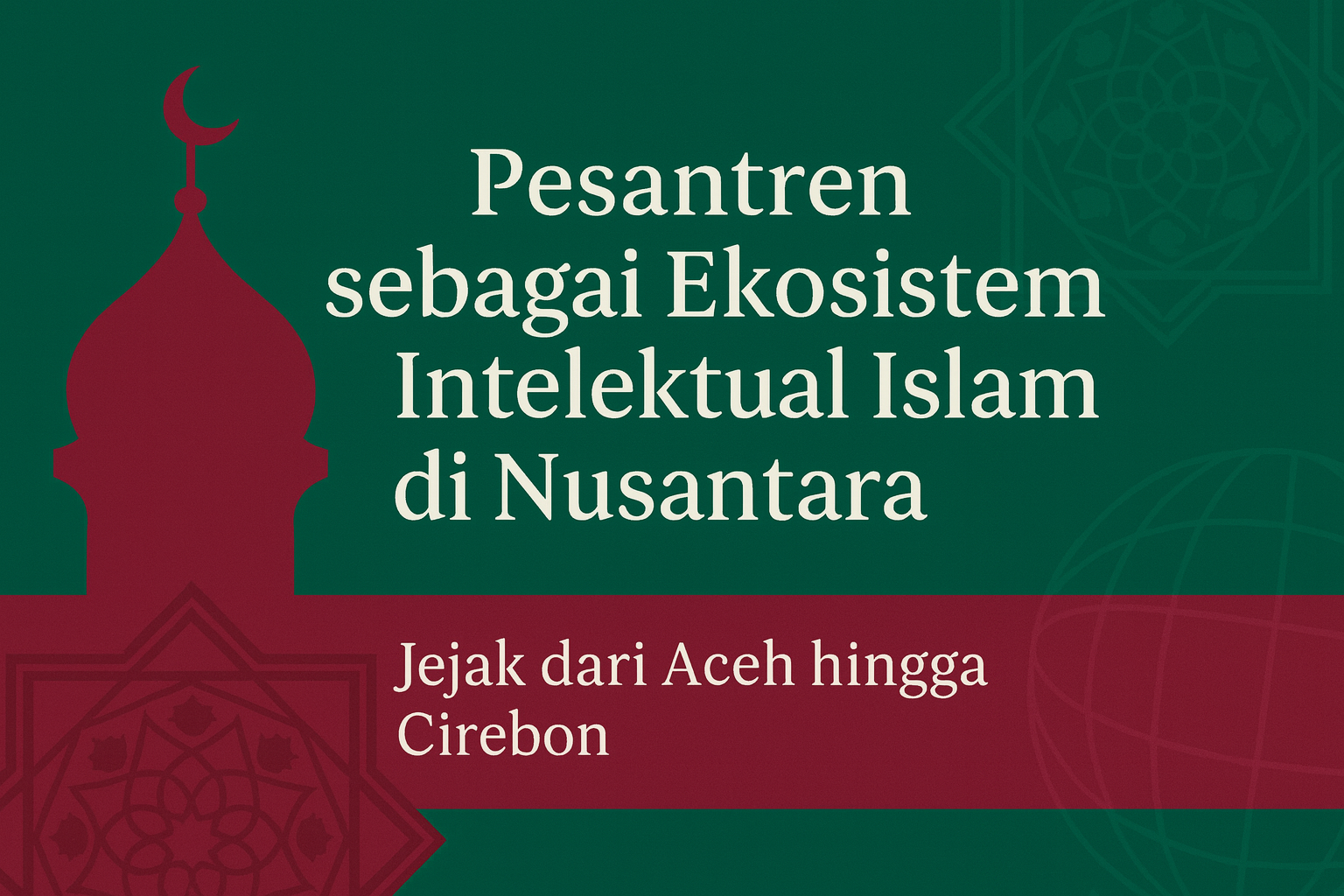




Leave a Reply