“Ilmu yang bermanfaat adalah yang menumbuhkan khashyah dan menggerakkan amal.” (Imam Al-Ghazali)
Pendahuluan
Ilmu sering berakhir sebagai tumpukan catatan, bukan energi pendorong untuk bertindak. Padahal tradisi intelektual Islam sejak awal memandang ilmu sebagai proses hidup: ia masuk ke jiwa membentuk makna, lalu keluar sebagai definisi yang jernih, metodologi yang teruji, dan kebijakan yang membumi. Tulisan ini mengajukan satu ajakan sederhana: mari mengembalikan ilmu—terutama fiqh—pada hakikatnya sebagai pemahaman yang mendalam (tafaqquh) yang melahirkan amal dan hikmah. Karena itu, langkah pertama adalah memulihkan disiplin batin dan intelektual yang membuat ilmu bertumbuh: menerima data dengan jujur, menenun makna dari pengalaman, lalu menajamkannya menjadi definisi operasional yang bisa diuji. Dari sini, tafaqquh bekerja lewat dua roda sekaligus—nash dan maqāṣid—agar pengetahuan tidak berhenti sebagai hafalan, melainkan berdaya guna dalam keputusan nyata untuk manusia.
Peralihan dari “paham” ke “mampu memaknai-ulang” menuntut latihan, merumuskan istilah, menimbang dalil, dan menafsir konteks tanpa kehilangan makna terhadap sumber. Di titik inilah ‘ilm, ma‘rifah, dan hikmah saling berkolaborasi. Kejernihan akal ditopang kebersihan niat, sementara kebijaksanaan lahir dari definisi yang tegas dan empati sosial. Hasil akhirnya bukan sekadar jawaban hukum, melainkan orientasi praksis dari ruang kelas hingga kebijakan public yang membuat fiqh kembali memandu peradaban, bukan hanya mengarsip pasal-pasal.
Fiqh: Ilmu yang Hidup dari Definisi ke Makna
Ilmu tidak lahir sebagai definisi yang kaku. Ia mula-mula hadir sebagai gambaran, analogi, dan intuisi—materi mentah yang memberi arah. Agar komunikatif, gambaran itu harus ditajamkan menjadi konsep dan definisi. Inilah jembatan antara ‘paham’ dan ‘mampu memaknai-ulang’. Banyak dari kita berhenti pada tahap pertama: merasa mengerti ketika mendengar. Tetapi ketika diminta menjelaskan ulang, apa lagi menuliskan kembali dengan rumusan yang eksplisit, kita biasa buntu karena proses penajaman belum selesai. Al‑Ghazali mengingatkan bahwa kejernihan batin adalah prasyarat kognitif: penyakit hati mengaburkan penilaian, sementara tazkiyah menolong akal menata prioritas. Dengan demikian, belajar yang sehat selalu bergerak dari menerima → memberi makna → mendefinisikan → menafsir‑ulang → memproduksi. Tanpa definisi, makna kabur; tanpa makna, karena bukanlah tujuan ilmu sekadar mengetahui, tetapi terbimbing untuk berbuat benar. Demikian di antara intisari etika ilmu dalam tradisi al‑Ghazali.
Karenanya, fiqh sebagai ilmu yang hidup bekerja dua arah; dari definisi yang presisi menuju makna yang mengarahkan. Di hilir, kita butuh rumusan operasional syarat, sebab, ‘illat agar putusan dapat diajarkan dan diuji. Di hulu, kita menjaga spirit maqāṣid agar definisi tidak kehilangan jiwa. Mekanismenya bukan tunggal: usul al-fiqh menyediakan alat seperti qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, sadd al-dharā’i, dan ‘urf untuk menautkan nash dengan realitas yang berubah. Siklusnya pun dinamis: taṣawwur (memahami objek) kepada ta`rīf (mendefinisikan) kepada ta`līl (menemukan illat) kepada tathbīq (menerapkan) kepada taqwīm (menilai dampak). Dengan cara ini, fiqh tidak berhenti di“apa hukumnya”, tetapi terus bergerak ke mengapa, bagaimana, dan sejauh mana keputusan ini menghadirkan keadilan. Hal ini agar perjalanan fiqh menjadi sebuah perjalanan dari kepastian istilah ke kedalaman makna yang melahirkan amal dan hikmah.
Fiqh sebagai Tafaqqquh Peradaban
Secara etimologis, fiqh berarti ‘pemahaman mendalam’. Pada fase formatif, fiqh tidak dipersempit menjadi daftar hukum positif, melainkan kemampuan menangkap makna syar‘i di balik nash dengan dukungan usul, kaidah, dan maqāṣid. Seiring kodifikasi, fiqh memperoleh kepastian metodis, namun bayang-bayang reduksi pun muncul. Fiqh disempitkan menjadi kompilasi pasal. Reposisi terjadi di mana fiqh sebagai tafaqquh yang menyinergikan nash, maqāṣid, dan konteks; menyatukan ‘ilm (data), ma‘rifah (pendalaman batin), dan hikmah (ketepatan tindakan). Para sufi seperti al‑Junaidi menegaskan bahwa pendalaman semestinya tetap terikat pada Kitab dan Sunnah; di sini, kedalaman spiritual bukan lawan dari rasionalitas, melainkan penjernih orientasi. Ketika fiqh kembali berakar pada tafaqquh, ia tidak hanya ‘menjawab pertanyaan hukum’, tetapi juga ‘mengarahkan peradaban’.
Agar tidak berhenti sebagai slogan, berikut tiga lanskap terapan yang menuntut fiqh berwajah tafaqquh menggabungkan data, maqāṣid, dan kebijaksanaan praksis, berikut disajikan tiga contoh kontemporer;
-
Fiqh Lingkungan
Selesai menata bingkai tafaqquh, mari turun ke lapangan kota: ruang tempat kebiasaan kecil berubah menjadi dampak besar. Sampah yang kita hasilkan tidak pernah “hilang”; ia hanya berpindah—ke selokan yang mampet, TPA yang penuh, udara yang mengandung asap pembakaran, dan pada akhirnya ke tubuh manusia yang rentan. Etika kebersihan bukan lagi urusan privat, melainkan ibadah sosial yang menuntut tata kelola: dari pemilahan di sumber, pengangkutan yang tertib, hingga insentif yang adil dan pengurangan di hulu. Dengan kacamata ini, pembahasan kita dimulai dari simpul terdekat sekaligus paling menentukan: pengelolaan sampah.
Di sini, fiqh bukan hanya pasal larangan, tetapi desain kebijakan berbasis maqāṣid (hifẓ al‑nafs, hifẓ al‑māl, hifẓ al‑nasl) yang terukur dampaknya. Dan di sinilah fiqh yang hidup menuntun dari definisi menuju makna: menautkan kaidah “lā ḍarar wa lā ḍirār” (tidak menimbulkan dan membalas mudarat) dengan maqāṣid seperti hifẓ al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan), hifẓ al-māl (menjaga harta/efisiensi sumber daya), dan hifẓ al-nasl (menjaga keberlanjutan generasi).
-
Keuangan Digital
Ekosistem dompet digital dan crowdfunding menggeser praktik Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari kotak amal fisik ke arsitektur data dan algoritma secara digital. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi “boleh/tidak” semata, tetapi bagaimana amanah dijaga, akuntabilitas dibuktikan, dan keadilan sasaran ditegakkan sesuai maqāṣid—khususnya hifẓ al-māl (menjaga harta dari kebocoran/inefisiensi) dan hifẓ al-nafs (menjaga jiwa/kesehatan penerima manfaat). Tafaqquh di ruang digital menuntut definisi operasional yang terukur: (1) ring-fencing dana (rekening terpisah, pencatatan real-time, bukti penyaluran yang dapat dilacak), (2) transparansi yang dapat diaudit (laporan periodik, audit syariah & finansial independen, publikasi biaya admin dan rasio penyaluran), (3) tata kelola data yang beradab (izin, minimasi data, keamanan & retensi jelas), serta (4) explainable algorithm pada penentuan prioritas penerima (kriteria kemiskinan, urgensi medis, risiko bencana) berikut uji bias dan mekanisme banding.
Selain itu, di hilir, keadilan distribusi perlu standar kebijakan: ambang minimal penyaluran ke tiap aṣnāf, batas biaya operasional, SLA penyaluran (mis. darurat ≤72 jam), serta impact metrics (pemulihan pendapatan/kesehatan) yang dievaluasi berkala. Di hulu, edukasi muzakki wajib menyertakan consent yang sadar (apa yang dikumpulkan, untuk apa), dan opsi preferensi penyaluran tanpa mengunci fleksibilitas lembaga saat terjadi kedaruratan (kaidah tasharruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah). Dengan kerangka ini, fatwa tidak berhenti sebagai “izin penggunaan aplikasi”, melainkan berbuah arsitektur amanah: proses, audit, dan algoritma yang menyalurkan zakat/infak secara tepat sasaran—adil bagi mustaḥiq, efisien bagi muzakki, dan selaras dengan maqāṣid.
-
Etika AI di Dunia Akademik
Penggunaan AI generatif di dunia akademik menuntut kerangka etika yang menggabungkan integritas ilmiah modern dengan prinsip-prinsip syariah. Di satu sisi, AI membantu literasi akademik: merapikan bahasa, merangkum literatur, memetakan argumen. Di sisi lain, risikonya nyata, yaitu plagiarisme terselubung (ghostwriting), distorsi pengetahuan akibat halusinasi model, reproduksi bias, ketimpangan akses, serta ketergantungan kognitif yang mengikis hifẓ al-‘aql (penjagaan akal). Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār mengarahkan agar manfaat tidak ditutup, tetapi mudharat harus ditutup rapat melalui tata kelola yang ketat. Dengan bingkai maqāṣid, kebijakan AI di kampus sebaiknya menilai dampak pada hifẓ al-dīn (kejujuran ilmiah), hifẓ al-‘aql (kecakapan nalar), hifẓ al-māl (efisiensi sumber daya), hifẓ al-nafs (keamanan data/pribadi), dan hifẓ al-‘irḍ (marwah akademik).
Di titik ini, fungsi fiqh dalam kerangka tafaqquh ialah mengubah nilai maqāṣid menjadi tata kelola operasional melalui langkah berjenjang: taṣawwur masalah (memetakan alur data, peran dosen–mahasiswa–platform, serta risiko), ta‘rīf (menetapkan definisi operasional apa yang dimaksud “bantuan AI”, “plagiarisme”, “data sensitif”), ta‘līl (menemukan ‘illat mudarat: penipuan ilmiah, pelanggaran amanah, erosi hifẓ al-‘aql), tathbīq (menerapkan kaidah: sadd al-dharā’i untuk menutup pintu kecurangan; maṣlaḥah mursalah untuk mengadopsi alat yang bermanfaat; qiyās yang menyamakan ghostwriting AI dengan bantuan pihak ketiga tanpa atribusi; serta pertimbangan ‘urf akademik tentang sitasi dan orisinalitas), lalu taqwīm (audit dan perbaikan berkala).
Dari sini lahir jalan keluar yang seimbang antara pencegahan dan pemanfaatan: kebijakan bertingkat yang membolehkan fungsi asistif namun melarang penyusunan penuh; kewajiban disclosure dan atribusi; pemeriksaan berbasis proses (log draf, oral defense); tata kelola data berprinsip minimasi dan non-retensi; mekanisme hisbah/komite etika untuk pengawasan; serta pengakuan AI sebagai assistive technology yang inklusif tanpa meniadakan capaian nalar inti. Kaidah “darʾ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ” memandu prioritas, sementara “al-aṣl fī al-ashyā’ al-ibāḥah” menjaga keterbukaan inovasi. Hasilnya adalah ekosistem amanah yang jujur, aman, dan tetap produktif.
Khatimah
Salah satu perwujudan dari ruang gerak dinamis dan universalisme Islam adalah mengembangkannya secara dinamis dan kreatif untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan hidup yang terus meminta etik dan paradigm baru. Dari titik inilah kita menapaki manhaj tafaqquh yang mengikat teks, maqāṣid, dan konteks menjadi arsitektur amal. Pengetahuan tidak berhenti pada legalistik, tetapi berwujud kebijakan operasional yang terukur. Itu tampak pada fiqh al-bī’ah (pengelolaan sampah dan kota), keuangan digital (amanah–akuntabilitas–keadilan sasaran), hingga etika AI (integritas, keamanan data, dan assessment berbasis proses).
Kaidah-kaidah seperti lā ḍarar wa lā ḍirār, darʾ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, dan taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah diterjemahkan ke mekanisme nyata: standar audit dan transparansi, pemilahan-sumber di hulu, non-retensi data dan minimasi data, serta pengawasan etika yang akuntabel. Kampus dan pesantren, lembaga fatwa dan regulator, dunia usaha dan masyarakat sipil, bertemu dalam satu ekosistem amanah yang menggerakkan ilmu menjadi amal. Dengan kompas itu, Islam tampil sebagai kekuatan tajdīd yang menumbuhkan keadilan dan keberlanjutan, seraya menjaga marwah ilmu; penutup ini, karenanya, bukan titik akhir, melainkan undangan kerja bersama—dari makna menuju definisi, dari definisi menuju hikmah yang membumi.
Pada akhirnya, ilmu akan berkembang bila ia menyatu dengan diri, lalu keluar kembali sebagai definisi yang tajam dan tindakan yang adil. Menghidupkan fiqh berarti menghidupkan proses itu: dari makna menuju definisi, dari definisi menuju hikmah. Tugas kita di kampus, pesantren, dan kantor adalah melatih diri bukan hanya ‘tahu’, tetapi ‘mampu memaknai‑ulang dan menghasilkan agar ilmu benar‑benar menerangi jalan, bukan sekadar memenuhi rak.

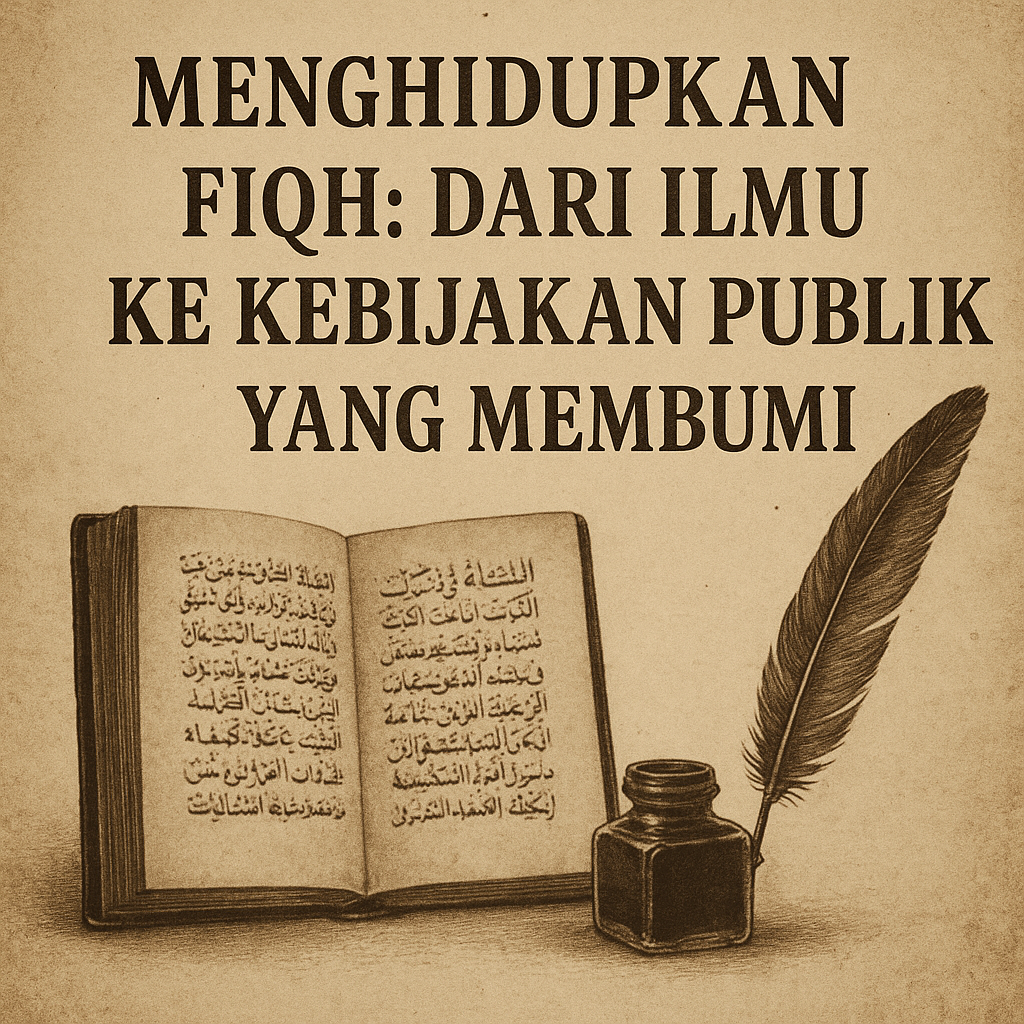


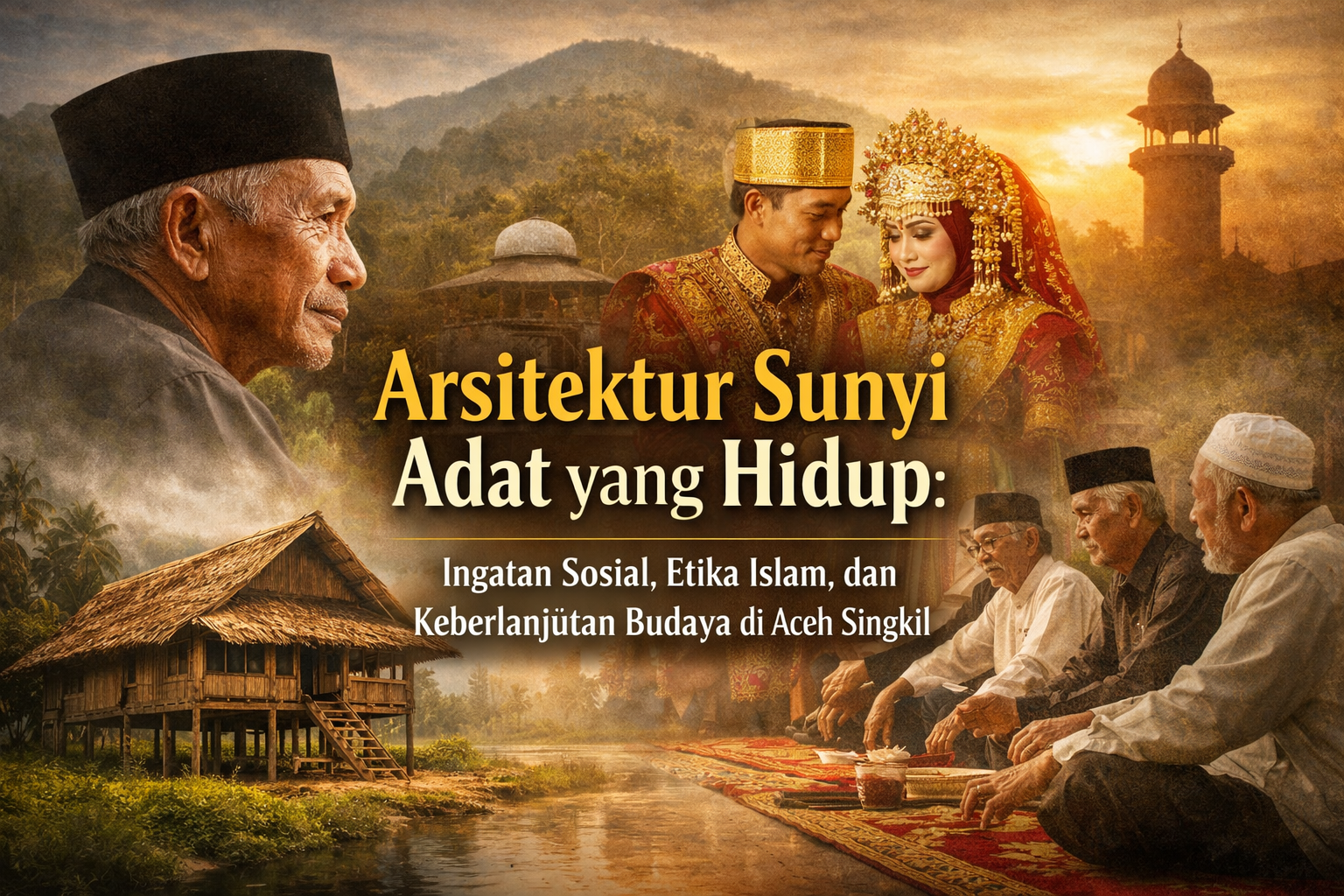
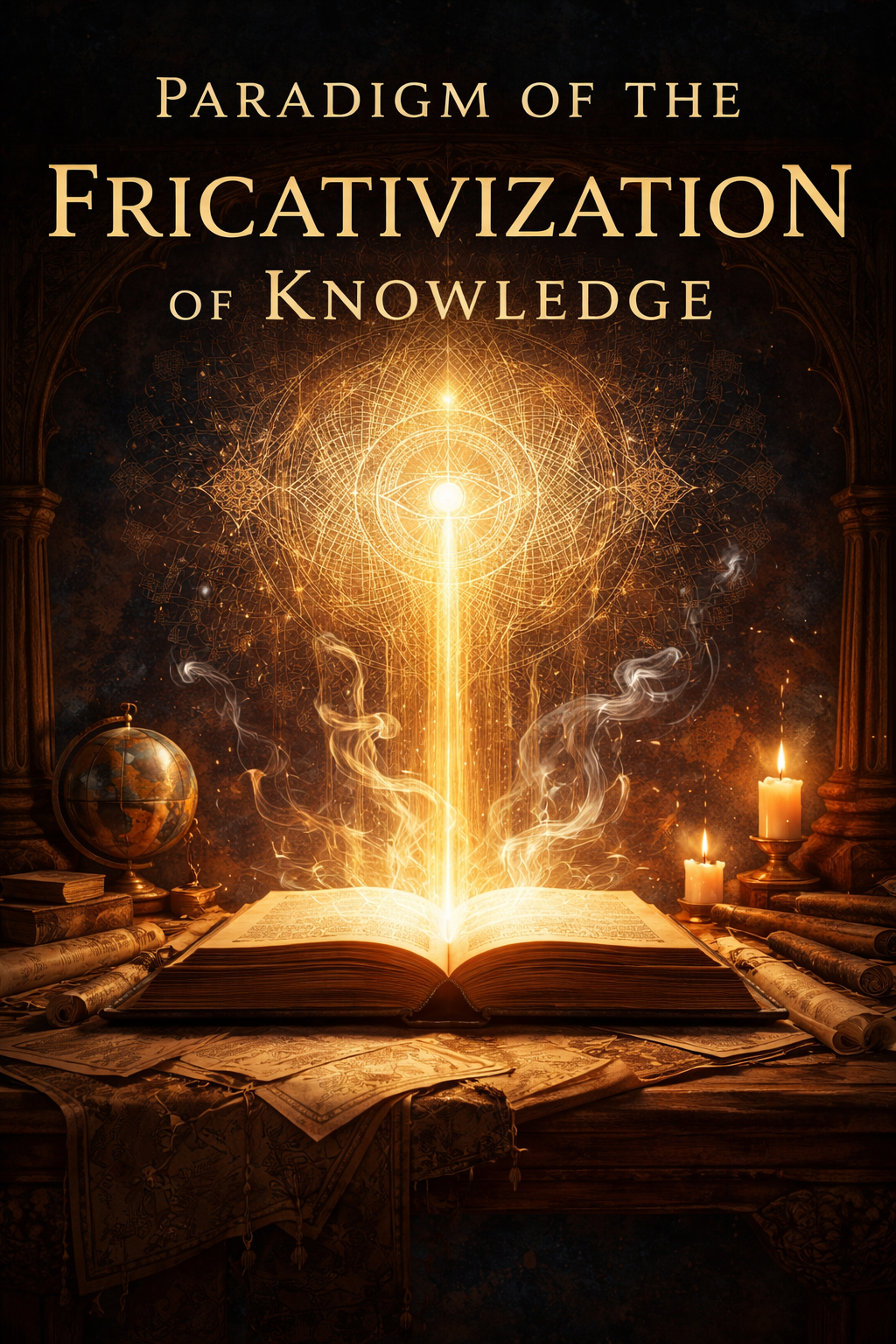
Leave a Reply