Dua dekade telah berlalu sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 2005, tetapi refleksi terhadap makna, capaian, dan arah perdamaian di Aceh tetap menjadi perbincangan penting. Bedah buku Dua Dekade Damai Aceh yang diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kamis (26/6/2025), menjadi forum intelektual penting yang menghadirkan pandangan-pandangan kritis dari akademisi dan praktisi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perdamaian Aceh.
Acara yang berlangsung di Aula Teater Museum UIN Ar-Raniry ini menghadirkan sejumlah pembicara utama, termasuk Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (Guru Besar Antropologi Agama dan Dekan FSH UIN Ar-Raniry), M. Adli Abdullah (praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik), Dr. Reza Idria (antropolog dan dosen FISIP Unsyiah), Muazzinah (aktivis dan peneliti isu gender-pascakonflik), dan Rasyidah (pemerhati HAM dan reintegrasi sosial). Kegiatan ini juga dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mursyid Djawas.
Pandangan Prof. Kamaruzzaman telah disampaikan secara utuh sebelumnya (lihat bagian atas). Intinya, ia memaknai Aceh sebagai laboratorium sosial perdamaian yang belum dimiliki negara secara utuh. Ia mendorong tafsir damai yang inklusif dan adil, serta memperingatkan bahaya jika negara terus memaksakan pendekatan Weberian yang struktural dan formal tanpa mengakui ingatan kolektif masyarakat Aceh yang Durkheimian—berbasis nilai, trauma, dan solidaritas moral.
Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad menyampaikan pandangan menyeluruh mengenai dinamika dan makna perdamaian di Aceh pasca-Helsinki. Pandangan ini tidak hanya merefleksikan aspek historis, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan politis dari proses perdamaian itu sendiri.
Aceh sebagai Laboratorium Perdamaian dan Lesson Learned Regional
Prof. Kamaruzzaman membuka pemaparannya dengan menegaskan bahwa pengalaman damai di Aceh telah menjadi rujukan empiris dan normatif bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bagi dunia akademik, Aceh adalah laboratorium sosial yang kompleks dan autentik dalam memahami bagaimana masyarakat pascakonflik membangun kembali tatanan sosial, ekonomi, dan politik mereka.
“Aceh bukan hanya wilayah yang pernah berkonflik. Ia kini menjadi referensi untuk memahami bagaimana negara, masyarakat, dan bekas kombatan membangun ulang kehidupan bersama dalam bingkai demokrasi dan keadilan sosial.”
Siapa Menikmati Damai? Siapa Aktor Utama?
Menurutnya, perdamaian di Aceh belum merata dalam distribusi hasil maupun maknanya. Pertanyaan seperti siapa yang menikmati perdamaian, siapa aktor sebenarnya dalam proses damai, dan bagaimana proses reintegrasi berlangsung merupakan isu-isu yang masih relevan hingga hari ini.
“Tidak semua kelompok menikmati perdamaian dengan cara yang sama. Ada yang menjadi pemenang dalam damai, ada yang tetap berada di pinggiran sejarah.”
Di sinilah pentingnya pendekatan kritis dalam memahami perdamaian. Damai bukan sekadar kondisi tanpa konflik, tetapi adalah medan tafsir, di mana tiap kelompok—baik elite politik, eks kombatan, korban sipil, perempuan, anak muda, hingga masyarakat adat—membaca dan menafsirkan damai secara berbeda-beda.
Politik Makna dalam Tafsir Damai
Prof. Kamaruzzaman menyampaikan bahwa perdamaian di Aceh telah memasuki fase kontestasi makna. Tidak ada satu definisi tunggal yang bisa memonopoli tafsir tentang damai. Sebaliknya, setiap kelompok memiliki narasi masing-masing tentang apa itu damai, apa maknanya, dan apa ekspektasi terhadapnya.
“Bagi sebagian, damai berarti proyek, dana hibah, atau jabatan. Bagi yang lain, damai adalah kembali berkebun, sekolah, dan hidup tanpa ancaman. Bagi sebagian korban, damai belum benar-benar hadir selama keadilan belum ditegakkan.”
Hal ini menciptakan keragaman tafsir yang harus dipahami secara sosiologis. Jika keragaman ini tidak dikelola secara inklusif, maka narasi damai akan berisiko menjadi eksklusif dan menjauh dari keadilan sosial.
Memori Kekerasan dan Ingatan Kolektif
Salah satu kontribusi pemikiran Prof. Kamaruzzaman yang paling menonjol adalah penekanannya pada memori sosial dalam masyarakat Aceh. Ia menyebut bahwa masyarakat Aceh mengalami situasi we forgive, but we cannot forget. Artinya, walau secara formal konflik telah berakhir, namun ingatan tentang kekerasan masih melekat dalam kesadaran kolektif masyarakat.
“Damai tidak menghapus trauma. Ia hanya membuka ruang baru untuk bernafas. Tetapi luka sosial, kehilangan, dan dendam struktural tetap hidup dalam narasi-narasi lokal, bahkan dalam diam sekalipun.”
Menurutnya, memori sosial ini perlu dikenali sebagai bagian dari proses rekonsiliasi yang belum selesai. Bahkan, jika negara gagal mengakui dan mengelola memori ini, maka akan muncul siklus apatisme, sinisme, atau bahkan konflik laten yang terus diwariskan secara kultural.
Aceh antara Bangsa dan Negara
Dalam kerangka yang lebih luas, Prof. Kamaruzzaman membedakan relasi Aceh dengan “bangsa Indonesia” dan “negara Indonesia”. Ia menyebut bahwa dalam narasi kebangsaan, Aceh memiliki tempat yang istimewa—sebagai wilayah Islam pertama, tempat perlawanan kolonial, dan pusat intelektualisme. Namun dalam praktik kenegaraan, Aceh justru mengalami marginalisasi struktural.
“Aceh selalu hadir dalam kisah kebangsaan Indonesia. Tapi tidak selalu dihargai dalam struktur kenegaraan. Kita dikenang dalam sejarah, tapi sering dilupakan dalam kebijakan.”
Ia menggambarkan hubungan Aceh dengan negara sebagai relasi yang penuh ketegangan: negara melihat Aceh dalam lensa keamanan, sementara masyarakat Aceh melihat dirinya sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Ketika konflik memuncak, negara hadir dengan pendekatan represif. Namun ketika damai terwujud, negara seringkali lambat dalam menyusun strategi integrasi yang bermartabat.
Antara Weber dan Durkheim: Ketimpangan Pendekatan
Salah satu gagasan paling orisinal yang disampaikan Prof. Kamaruzzaman adalah tentang perbedaan pendekatan antara negara dan masyarakat Aceh dalam membangun damai.
“Negara membangun damai dengan pendekatan Weberian—legal-formal, administratif, birokratis. Sementara masyarakat Aceh hidup dalam sistem Durkheimian—kolektivitas, nilai adat, solidaritas moral.”
Konsekuensinya, muncul ketimpangan dalam implementasi kebijakan: program-program reintegrasi dan pembangunan damai tidak sepenuhnya diterima atau dimiliki oleh masyarakat, karena pendekatannya tidak menyentuh logika sosial dan nilai-nilai lokal.
Damai sebagai Proses Sosial yang Belum Selesai
Sebagai penutup, Prof. Kamaruzzaman menegaskan bahwa perdamaian di Aceh adalah proyek jangka panjang yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan konsistensi. Ia menyebut bahwa damai bukan produk final, tetapi proses sosial yang terbuka dan terus berkembang. Proses ini membutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat dan negara, termasuk generasi muda, perempuan, dan kelompok marginal.
“Jika kita ingin membangun damai yang adil dan bermartabat, maka kita harus memahami damai bukan hanya dalam kerangka politik, tetapi juga dalam kerangka budaya, nilai, dan ingatan bersama.”







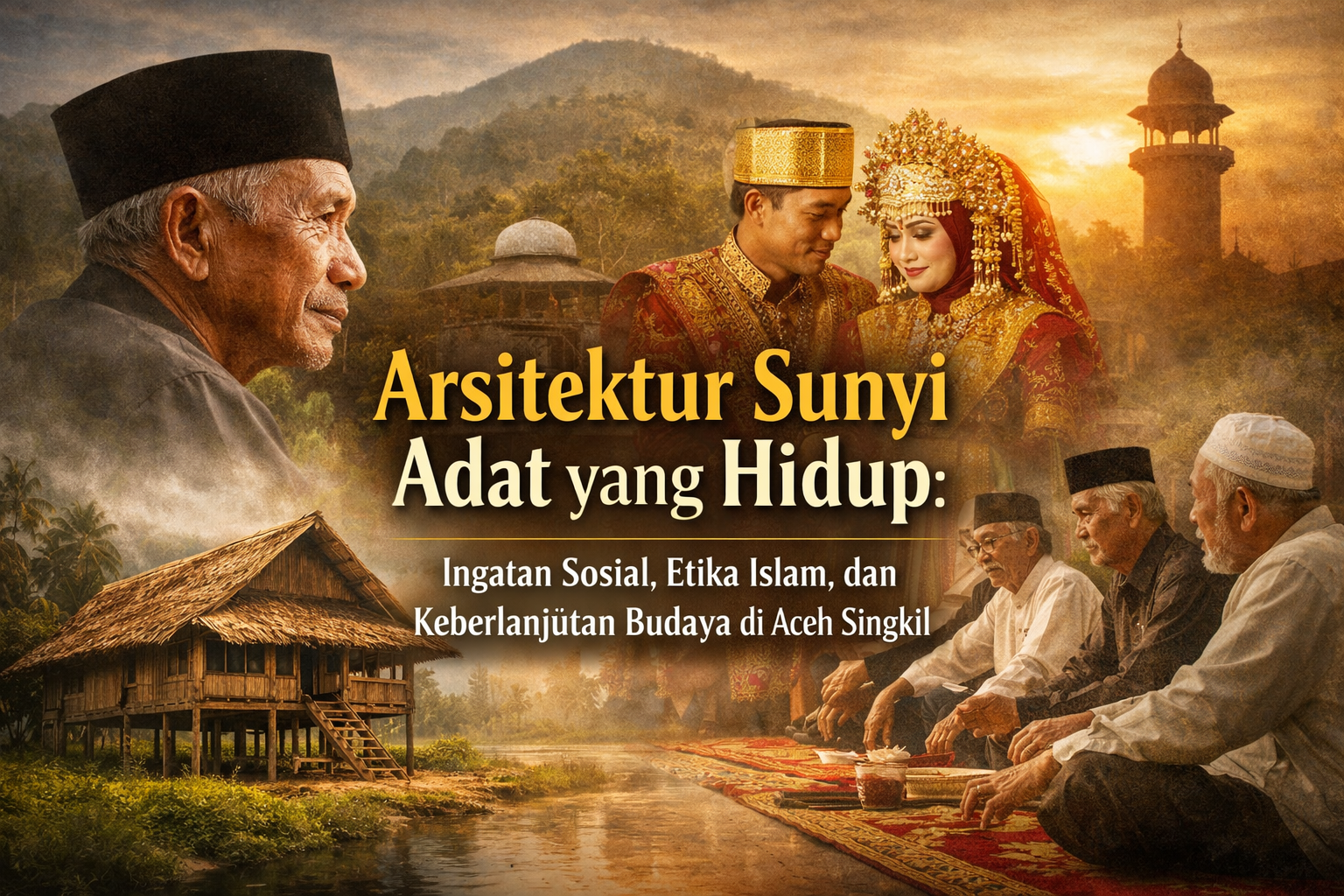
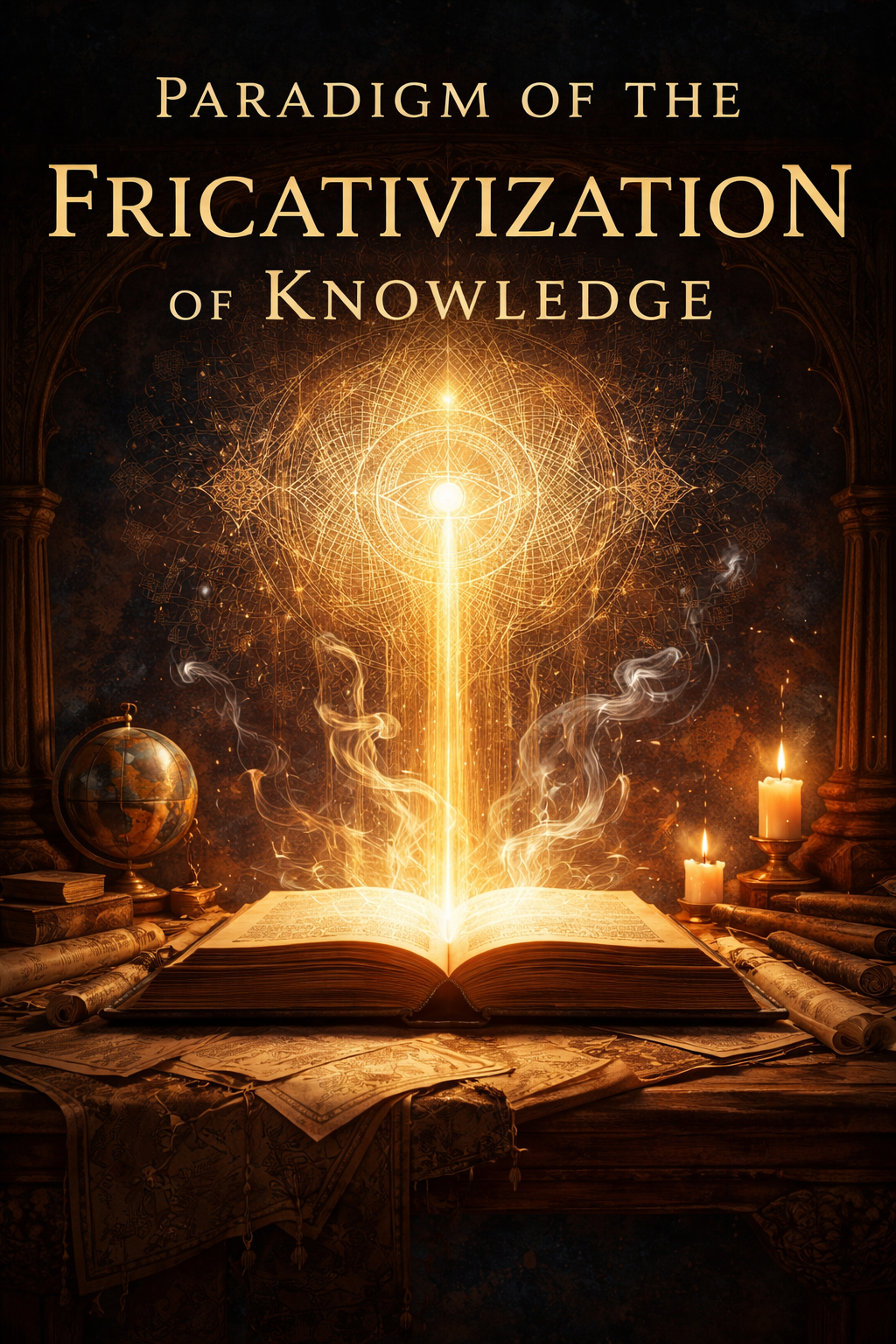
Leave a Reply