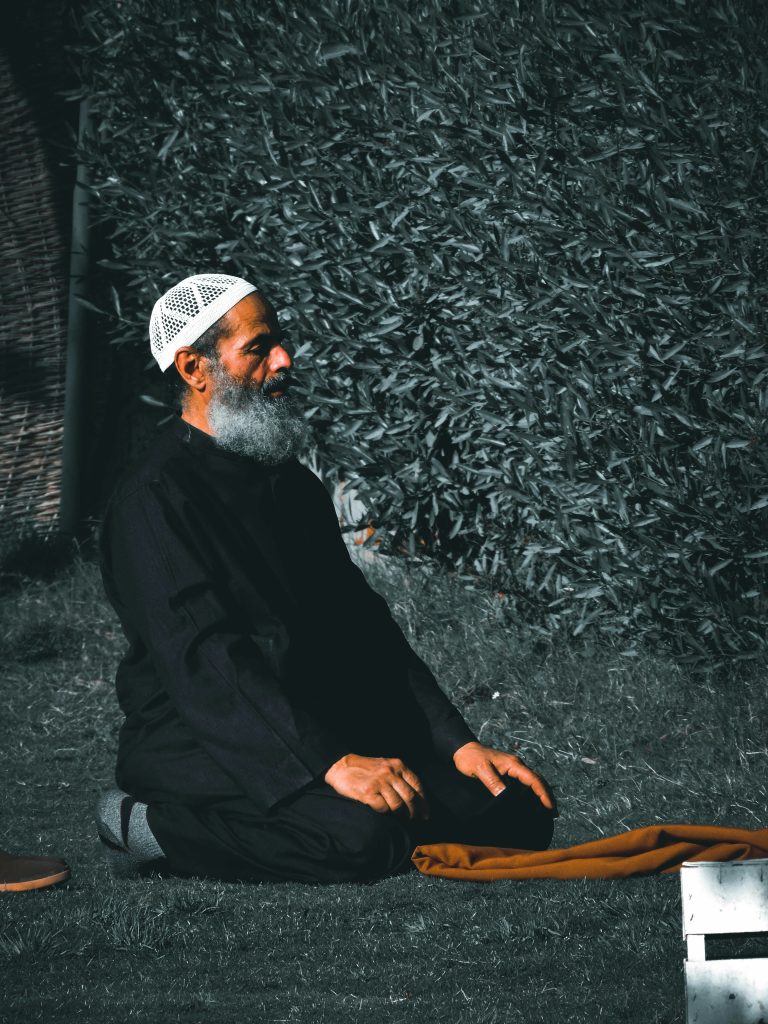Pendahuluan
Kita tengah menyaksikan kelahiran generasi yang tidak pernah benar-benar disiapkan dalam desain pendidikan agama kita—termasuk di lembaga-lembaga pesantren. Generasi 2010-an ini bukan hanya digital native, tetapi juga memiliki cara berpikir yang simultan: tidak terkotak dalam dikotomi otak kiri atau otak kanan. Mereka hidup dalam realitas ganda—realitas yang tak lagi memisahkan yang sakral dari yang sekuler, yang virtual dari yang aktual.
Mereka saleh tapi trendi. Mereka senyap, tapi berpikir tajam. Mereka cepat memutuskan sesuatu bukan karena dangkal, tetapi karena informasi telah tersedia tanpa perantara. Mereka tidak sedang menjauh dari agama, tetapi sedang merumuskan bentuk keberagamaan baru yang lebih selaras dengan kedirian mereka.
Pertanyaannya: apakah model pembelajaran agama hari ini, terutama di pesantren, mampu menjawab kebutuhan spiritual dan intelektual generasi ini?
Pesantren: Antara Tradisi dan Ketertinggalan
Pesantren masih dipercaya sebagai tempat terbaik membentuk pribadi Muslim yang saleh, beradab, dan cinta ilmu. Di sinilah adab dididik sebelum ilmu, dan akhlak dijunjung sebelum dalil. Namun dalam banyak kasus, pesantren justru terjebak pada pola pembelajaran yang hanya menekankan kesalehan dan kepintaran, tapi gagal membentuk integritas santri dalam menghadapi dunia digital.
Dalam sistem pendidikan pesantren, kesalehan ditakar dari ritual: shalat berjamaah, puasa sunnah, muroja’ah hafalan. Kepintaran diukur dari kemampuan membaca kitab kuning, menguasai gramatika Arab, dan menyampaikan ceramah. Semua itu penting, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan baru: bagaimana menjadi Muslim yang beradab dan kritis di tengah derasnya arus informasi dan budaya digital.
Kita melihat ironi besar: banyak santri yang alim di ruang kelas, tetapi kehilangan arah di media sosial. Mereka menyembunyikan kesalehannya dalam bilik asrama, tetapi membuka tabir pesonanya di Instagram. Mereka tahu adab majelis ilmu, tetapi bisa begitu sarkastik dalam komentar YouTube. Mereka fasih mengutip Al-Ghazali, tetapi tak mampu menahan diri saat bicara soal politik identitas di X (Twitter).
Apa yang salah? Salah satunya adalah ketiadaan kurikulum yang menjembatani nilai-nilai tradisi dengan realitas digital. Pendidikan pesantren gagal menyadari bahwa kesalehan hari ini tidak lagi hanya urusan ruang fisik, tetapi juga soal kehadiran di ruang virtual.
Guru dan Ustaz yang Tak Menyelesaikan Kesadarannya
Celakanya, banyak guru dan ustaz di lembaga-lembaga pendidikan agama belum selesai dengan kesadaran dan perilaku mereka sendiri. Mereka dibesarkan dalam budaya otoritas, tetapi hidup di tengah zaman yang menuntut otentisitas. Mereka diajarkan untuk ditaati, bukan untuk didengar. Mereka terbiasa memberi fatwa, bukan mendampingi pencarian makna.
Akibatnya, ketika menghadapi generasi simultaneous mind, para pengajar ini sering kehilangan pijakan. Mereka masih menggunakan logika lama untuk menjelaskan dunia baru. Mereka merasa cukup menyampaikan ayat dan hadis, lalu kecewa ketika murid-muridnya tidak tersentuh. Padahal, problem murid-muridnya bukan soal pengetahuan, tapi soal eksistensi.
Lebih parah lagi, sebagian ustaz juga membawa konflik batin mereka sendiri ke ruang kelas: antara religiusitas dan popularitas, antara kesalehan lisan dan ketidakkonsistenan perilaku. Mereka menuntut adab, tetapi tidak memberi teladan dalam komunikasi digital. Mereka mengutuk narsisme santri, tetapi diam-diam juga membangun citra religius palsu untuk followers mereka.
Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa membimbing generasi yang kritis, yang bisa mencium aroma kepalsuan dalam hitungan detik?
Pendidikan yang Gagal Menemani Keresahan
Kegagapan ini membuat pendidikan agama semakin kehilangan daya pikat. Ia tak lagi mampu menemani kegelisahan batin generasi baru. Ia hanya menjadi ruang hafalan, bukan tempat dialog. Ia menjadi perintah moral, bukan jalan spiritual. Maka tak heran, anak-anak muda ini mencari makna di luar: dalam podcast, kanal YouTube, bahkan forum-forum anonim yang memberi ruang mereka untuk bertanya tanpa dihakimi.
Padahal, generasi ini tidak butuh guru yang serba tahu. Mereka butuh guru yang bisa berkata, “Saya juga pernah bingung.” Mereka butuh ustaz yang bisa menangis bersama mereka, bukan hanya mengarahkan telunjuk.
Di sinilah krisis pendidikan agama menjadi nyata: antara model pembelajaran yang statis, dan realitas mental-spiritual yang cair.
Saatnya Mengintegrasikan Adab Digital dan Spiritualitas Otentik
Kita perlu berpikir ulang: apa sebenarnya yang ingin kita hasilkan dari pendidikan agama? Apakah sekadar santri yang taat perintah tapi tidak mampu berpikir? Apakah cukup menghasilkan murid yang rajin mengaji tapi labil dalam membangun citra diri di ruang digital?
Sudah saatnya adab digital dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama, terutama di pesantren. Santri harus dididik bagaimana menampilkan kesalehan secara otentik, bukan manipulatif. Mereka harus dibekali bukan hanya dengan dalil, tetapi juga dengan sensitivitas etika dalam interaksi virtual.
Lebih dari itu, para guru dan ustaz pun harus menjalani transformasi kesadaran diri. Mereka tidak cukup hanya menguasai teks-teks klasik, tetapi juga harus mampu menjadi penafsir dunia modern—dengan empati, kejujuran, dan kerendahan hati. Mereka harus berhenti merasa menjadi satu-satunya otoritas, dan mulai belajar menjadi kawan perjalanan spiritual generasi baru.
Penutup: Pendidikan Agama sebagai Ruang Perjumpaan, Bukan Perintah
Generasi 2010-an bukan generasi pembangkang. Mereka adalah generasi pencari. Mereka mencari makna, bukan fatwa. Mereka ingin hadir dalam agama yang mengerti batin mereka, bukan yang sibuk menakut-nakuti. Mereka rindu bimbingan yang manusiawi, bukan dominasi yang arogan.
Maka, tugas kita bukan lagi sekadar mengajar, tetapi menemani. Pendidikan agama masa depan harus menjadi ruang perjumpaan: antara guru dan murid, antara tradisi dan teknologi, antara kesalehan dan kecerdasan emosional.
Jika tidak, kita hanya akan mencetak generasi yang menghafal Tuhan, tapi kehilangan diri mereka sendiri. Yang fasih berbicara tentang surga, tapi gelisah menghadapi dunia.