Abstrak
Artikel ini mengkaji pemikiran Syaikh Abdallāh bin Bayyah dalam kitab Tanbīh al-Marāji‘ ‘alā Ta’ṣīl Fiqh al-Wāqi‘ (Peringatan bagi Rujukan tentang Mengukuhkan Fikih Realitas). Fokus pembahasan mencakup biografi ringkas Ibnu Bayyah, latar belakang lahirnya kitab ini di tengah krisis fikih kontemporer, serta metodologi yang ditawarkannya. Ibnu Bayyah mendiagnosis berbagai masalah dalam praktik fikih modern, seperti literalism (pemahaman tekstual sempit) dan gejala takfīr, dan menawarkan solusi melalui fiqh al-wāqi‘ (fikih realitas). Melalui analisis naratif-akademik, artikel ini membahas lima bagian utama: (1) krisis fikih kontemporer menurut Ibnu Bayyah; (2) metodologi menghadapi nash dengan prinsip-prinsip uṣūl, mencakup dua level interaksi dan tiga “lingkaran” metodologis bagi faqīh; (3) konsep taḥqīq al-manāṭ dan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai pendekatan kontekstual; (4) analisis isu takfīr dalam penafsiran QS al-Mā’idah oleh Ibnu Bayyah; dan (5) pentingnya fiqh al-wāqi‘ sebagai dasar moderasi Islam dalam merespons tantangan global. Setiap bagian menyertakan kutipan terjemahan dari teks asli kitab untuk memperkuat penjelasan, dengan analisis konseptual dan relevansi kontemporer dari gagasan-gagasan Ibnu Bayyah.
Kata Kunci: Fikih Kontemporer; Fiqh al-Wāqi‘; Moderasi Islam; Maqāṣid al-Sharī‘ah; Takfīr; Abdullah bin Bayyah.
Pendahuluan
Abdullāh bin Bayyah adalah seorang ulama terkemuka kelahiran 1935 di Mauritania[1]. Sejak muda ia mendalami berbagai disiplin keislaman – tafsir, hadis, fikih, uṣūl fikih, bahasa Arab – di bawah bimbingan ayahnya, Syaikh Maḥfūẓ bin Bayyah, yang juga ulama dan pemimpin persatuan ulama Mauritania[1]. Ibnu Bayyah kemudian melanjutkan studi hukum Islam di Tunisia dan pernah menjabat sebagai hakim syariah serta dosen studi Islam di Jeddah[2][3]. Dalam kancah pemikiran Islam kontemporer, ia dikenal sebagai sosok ulama moderat dan visioner, salah satunya melalui gagasannya bahwa Islam adalah “agama kasih sayang” (religion of compassion) yang mengedepankan perdamaian dan menolak kekerasan[4]. Pandangan tersebut konsisten tercermin dalam karya-karya tulis, fatwa, dan inisiatifnya yang selalu mempromosikan nilai moderasi dan perdamaian dalam Islam[5][6].

Gambar 1. Syaikh Abdallāh bin Bayyah, ulama Mauritania yang dikenal sebagai pemikir moderat dan pelopor gagasan fiqh al-wāqi‘. Foto diambil pada tahun 2009 saat beliau berbicara dalam sebuah forum nasional mengenai penanggulangan ekstremisme di Mauritania.
Kitab Tanbīh al-Marāji‘ ‘alā Ta’ṣīl Fiqh al-Wāqi‘ karya Ibnu Bayyah lahir dari keprihatinannya terhadap tantangan dan krisis yang dihadapi fikih Islam di era modern. Kitab ini diterbitkan pada 2014[7][8], periode yang ditandai dengan maraknya konflik atas nama agama, mis-interpretasi teks suci, dan menguatnya paham ekstrem seperti takfīrisme. Ibnu Bayyah memandang bahwa umat Islam abad ke-21 dihadapkan pada dua kecenderungan ekstrem: pertama, kecenderungan jumūd (statis) dalam berfatwa dengan hanya mengandalkan teks secara literal tanpa mempertimbangkan konteks zaman; kedua, kecenderungan ghulūw (berlebihan) seperti fenomena takfīr, yaitu mudah mengafirkan sesama Muslim yang berbeda pandangan[9][10]. Kedua hal ini berakar dari kelemahan dalam metode berijtihad: sebagian ulama atau aktivis agama tidak membekali diri dengan pemahaman realitas (wāqi‘) yang memadai, atau gagal memahami maksud keseluruhan syariat (maqāṣid al-sharī‘ah) sehingga menerapkan dalil secara serampangan. Akibatnya, muncul fatwa-fatwa dan tindakan keagamaan yang kurang bijak, baik yang terlalu kaku hingga tidak relevan dengan perkembangan zaman, maupun yang terlalu radikal hingga menyimpang dari prinsip rahmat dan keadilan Islam.
Ibnu Bayyah menilai bahwa problematika ini antara lain terlihat dari maraknya perselisihan politik dan sektarian yang berujung konflik bersenjata di berbagai negeri Muslim. Ia menyebut ironi menyedihkan bahwa “tidak ada umat hari ini yang lebih banyak dilanda pertumpahan darah melebihi umat [Islam] ini, di bawah slogan dan dalih yang tidak dibenarkan syariat dan tak diterima akal”. Padahal, ajaran Islam sejatinya menjunjung perdamaian; Ibnu Bayyah berulang kali menekankan bahwa keadilan dan kebaikan hanya bisa tumbuh dalam keadaan damai, bukan dalam situasi perang[11][12]. Berangkat dari kegelisahan tersebut, kitab Tanbīh al-Marāji‘ hadir sebagai seruan kepada para ulama dan pemegang otoritas fatwa (“marāji‘”) untuk kembali meneguhkan metodologi klasik yang terbukti berhasil namun dengan pembaruan penting: memasukkan pertimbangan realitas aktual (fiqh al-wāqi‘) dalam proses pengambilan hukum. Dengan kata lain, Ibnu Bayyah hendak “menyegarkan” tradisi uṣūl al-fiqh dengan menekankan relevansi konteks dan tujuan syariat, agar fikih Islam mampu menjawab tuntutan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya.
Struktur artikel ini terbagi menjadi beberapa bagian untuk mengulas pemikiran kunci Ibnu Bayyah dalam kitab tersebut. Bagian Bagian pertama akan menguraikan secara lebih spesifik apa yang dimaksud dengan krisis fikih kontemporer menurut Ibnu Bayyah. Selanjutnya, memaparkan metodologi yang ditawarkan Ibnu Bayyah dalam menghadapi teks-teks suci (Qur’an dan Hadis), meliputi prinsip-prinsip uṣūl yang digunakan, konsep dua level interaksi dengan nash, serta “lingkaran metodologis” yang harus dilalui seorang faqīh. Kemudian, kajian ini mengelaborasi pentingnya taḥqīq al-manāṭ (verifikasi illat hukum pada konteks faktual) dan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai pendekatan kontekstual untuk menjembatani teks dan realitas. Berikutnya, studi ini menghadirkan studi kasus isu takfīr dengan menelaah bagaimana Ibnu Bayyah menafsirkan ayat-ayat QS al-Mā’idah yang kerap disalahgunakan oleh kelompok ekstrem. Lalu, pembahanan akan mendiskusikan implikasi fiqh al-wāqi‘ sebagai landasan moderasi Islam dan respon proaktif terhadap tantangan global. Terakhir, bagian Kesimpulan merangkum temuan utama dan signifikansi praktis pemikiran Ibnu Bayyah bagi pengembangan fikih kontemporer. Seluruh bagian akan disertai kutipan terjemahan dari kitab Tanbīh al-Marāji‘ sesuai halaman yang relevan, guna menjaga kedekatan analisis dengan teks asli.
Krisis Fikih Kontemporer Menurut Ibnu Bayyah
Ibnu Bayyah memulai pembahasannya dengan diagnosis mengenai “krisis fikih” yang terjadi dewasa ini. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan disfungsi dalam praktek pengambilan hukum oleh sebagian kalangan Muslim kontemporer. Ia menyebut setidaknya tiga bentuk kejahilan atau ketimpangan dalam beragama yang berkontribusi pada krisis tersebut (yang rinciannya disebut di bagian sebelumnya dalam kitab).
Secara ringkas, tiga hal itu dapat dipahami sebagai: (1) Jahl bi al-naṣṣ – ketidaktahuan terhadap teks secara utuh, yaitu kecenderungan memahami dalil agama secara parsial dan literal tanpa mengindahkan dalil-dalil lain yang terkait maupun konteksnya; (2) Jahl bi al-wāqi‘ – ketidaktahuan terhadap realitas, yakni kurangnya pemahaman terhadap situasi zaman, kondisi sosial, dan implikasi penerapan hukum dalam kehidupan nyata; dan (3) Jahl bi al-maqāṣid – ketidaktahuan terhadap tujuan-tujuan utama syariat, sehingga hilang hikmah dan ruh keadilan dari penerapan hukum.
Ketiga jenis kelemahan tersebut, menurut Ibnu Bayyah, telah “menimbulkan pola ẓāhiriyyah (tekstualisme sempit) dalam berinteraksi dengan nash, yang menyimpang jauh dari metodologi orisinal [para ulama salaf]”. Dengan kata lain, banyak orang terjebak hanya melihat tekstual nash secara dangkal (ẓāhir) tanpa mau mendalami konteks dan makna substantifnya. Padahal, metodologi orisinal para sahabat dan ulama klasik selalu mengombinasikan antara kesetiaan pada teks dengan keluasan pemahaman konteks. Misalnya, para sahabat Nabi Muhammad ﷺ ketika berijtihad tak semata-mata berpegang pada lafaz literal nash, tetapi juga mempertimbangkan maslahat umum, kebiasaan setempat, dan kondisi khusus saat itu.
Ketika metodologi holistik semacam ini ditinggalkan, yang terjadi adalah kebingungan hukum: nash digunakan secara serampangan, sebagian kelompok menyimpulkan hukum hanya dari sepotong dalil (sementara mengabaikan dalil lain) sehingga melahirkan fatwa ekstrem atau kontraproduktif. Ibnu Bayyah menyoroti bahwa fiqh yang sehat seharusnya “tidak mengabaikan ta’ṣīl (pendasarannya) yang bersumber dari dalil-dalil ḥākimah (dalil pokok yang mengendalikan) dan praktik sejarah”. Artinya, dalam berfatwa harus memperhatikan kaidah umum Al-Qur’an-Hadis serta pengalaman panjang ulama salaf dalam menerapkan syariat sepanjang sejarah. Mengabaikan landasan historis ini akan membuat seseorang mudah tergelincir pada interpretasi menyimpang atau ekstrem.
Lebih jauh, krisis fikih tampak nyata dalam fenomena ghuluw fī al-dīn (berlebihan dalam beragama) seperti sikap mudah mengafirkan (takfīr) dan menyempal dari jamaah kaum Muslimin. Ibnu Bayyah menyebut gejala takfīr ini sebagai “fitnah” besar yang sesungguhnya merupakan “perang terhadap umat Islam sendiri”[13][14]. Kelompok-kelompok radikal mengusung slogan “al-ḥākimiyyah” (hanya berhukum dengan hukum Allah) secara serampangan untuk menuduh pemerintah atau Muslim lain sebagai ṭāghūt (musuh Allah) hanya karena perbedaan penerapan hukum[15]. Padahal, konsep ḥākimiyyah yang disalahpahami tersebut tidak terlepas dari kekeliruan menafsirkan dalil, khususnya ayat-ayat dalam QS al-Mā’idah tentang hukum Allah (yang akan dibahas di Bab IV). Menurut Ibnu Bayyah, praktik takfīr semacam itu bertentangan dengan prinsip Ahlus-Sunnah yang sangat berhati-hati dalam mengafirkan Muslim[16]. Ulama Ahlus-Sunnah hanya membolehkan vonis kafir bila ada bughyah al-bayān – bukti yang sangat jelas seperti terangnya matahari siang – bahwa seseorang memang mengingkari pokok ajaran agama[17]. Adapun mengafirkan orang yang masih shalat, mengucapkan syahadat, hanya karena dosa besar atau kekhilafan ijtihad, adalah penyimpangan yang dahulu diusung oleh sekte Khawarij dan telah ditolak konsensus ulama Sunni[18][19].
Singkatnya, Ibnu Bayyah mendiagnosa krisis fikih kontemporer sebagai krisis metodologi. Banyak masalah timbul bukan karena ajaran Islamnya yang kurang, tetapi karena metode memahami dan menerapkan ajaran itulah yang keliru. Maka, solusi yang ia tawarkan pun berfokus pada perbaikan metodologi berijtihad, dengan menekankan kembali elemen-elemen yang sering diabaikan: integrasi antar dalil (holistik), pemahaman konteks nyata, serta penghayatan tujuan syariat. Sebelum menawarkan metodologinya, Ibnu Bayyah mengingatkan bahwa seorang faqīh yang ideal harus mampu beroperasi dalam tiga “lingkaran” kajian saat berhadapan dengan nash: lingkaran tafsīr dan ta’wīl (menafsirkan teks dan menggali makna terdalamnya), lingkaran tanzīl (mengaitkan teks dengan realitas atau kasus konkret yang dihadapi), dan lingkaran taf‘īl (mengaktualisasikan hukum dalam praktik secara efektif). Jika salah satu lingkaran ini diabaikan, hasil ijtihad akan timpang. Pada bab berikut, akan dibahas bagaimana Ibnu Bayyah merumuskan metodologi ideal tersebut secara lebih terperinci.
Metodologi Menghadapi Nash – Prinsip Ushul, Dua Level Interaksi, dan “Lingkaran” Metodologis Faqīh
1. Prinsip-Prinsip Ushul dalam Pendekatan Ibnu Bayyah
Metode Ibnu Bayyah dalam berinteraksi dengan nash (teks Al-Qur’an dan Hadis) pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari manhaj para ulama klasik sejak zaman sahabat. Ia menegaskan, “manhaj kami beroleh inspirasi dari manhaj ulama Muslim sejak era Sahabat hingga kini dalam berinteraksi dengan wahyu Qur’an dan Sunnah”. Prinsip dasarnya ialah memastikan validitas dalil terlebih dahulu dan memahami maknanya dengan benar sebelum menerapkannya. Dalam konteks hadis, ini berarti memeriksa ketsiqahan sanad dan matan – suatu hadis harus dipastikan benar-benar berasal dari Nabi (tsābit al-wurūd) dan memiliki petunjuk makna yang jelas (waḍūḥ al-dilālah). Jika statusnya sahih dan maknanya ṣarīḥ (eksplisit), serta tidak terdapat dalil lain yang mu‘āriḍ (bertentangan) yang lebih kuat, barulah hadis tersebut dapat dijadikan landasan hukum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah uṣūl klasik: dalil yang kuat adalah yang menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan (qat‘ī), yaitu dalil dari Al-Qur’an atau Sunnah mutawātir atau Sunnah ṣaḥīḥah yang jelas maknanya dan tidak di-naskh (dihapus). Dalam hal dalil bersifat āḥād (berita tunggal) atau indikasi maknanya tidak tegas, maka statusnya ẓannī (dugaan) sehingga penerapannya membutuhkan ijtihad dan kehati-hatian, tidak boleh dipaksakan secara kaku seolah-olah qat‘ī.
Dengan filter validitas dan kejelasan makna ini, Ibnu Bayyah ingin menegaskan bahwa tidak semua teks bisa langsung dijadikan hukum tanpa telaah. Kesalahan sebagian pihak adalah memperlakukan dalil ẓannī seakan-akan qat‘ī, sehingga lahir vonis hukum yang gegabah. Sebagai contoh, ia mengutip pendapat al-Imām al-Iṣfahānī dalam Syarḥ al-Maḥṣūl yang menyatakan: “al-aḥkām mā thabata bi-adillah ḥaṣala al-‘ilmu bi-muqtaḍāhā” – “suatu hukum itu tegak berdasarkan dalil-dalil yang menghasilkan pengetahuan (yakin) akan tuntutannya”. Sementara hukum-hukum yang bersumber dari nash-nash ẓannī (seperti khabar āḥād yang sanad atau dalalah-nya mengandung kemungkinan berbeda) statusnya maẓnūnah (dugaan kuat) bukan ma‘lumah (pasti). Prinsip ini penting ditekankan agar kita tidak sembrono mengklaim keputusan Allah hanya bermodal pemahaman sepihak terhadap satu dua dalil yang sebenarnya belum pasti maknanya.
Selain itu, Ibnu Bayyah juga mengingatkan perlunya memperhatikan ijmā‘ (kesepakatan ulama) yang mapan. Jika suatu hal sudah disepakati ulama sebagai bagian dari ma‘lum min al-dīn bi al-ḍarūrah (ajaran agama yang aksiomatik), maka itu menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Contohnya, perkara-perkara pokok iman (rukun iman enam perkara) merupakan hal yang sudah ijmā‘; siapa pun yang mengingkarinya jelas kafir. Demikian pula perkara yang sangat masyhūr (mapan) dalam syariat dan tidak ada khilaf, mengingkarinya bisa jatuh pada kekufuran. Namun di luar hal-hal yang jelas itu, mayoritas masalah fikih adalah hasil ijtihad terhadap nash-nash ẓannī, sehingga ruang perbedaan pendapat terbuka. Kesadaran inilah yang terkadang hilang dalam sebagian diskursus keagamaan modern, sehingga perbedaan ijtihad sering disikapi dengan saling tuduh sesat bahkan kafir.
2. Dua Level Interaksi dengan Nash: Iman dan Amal
Setelah langkah awal memastikan validitas dalil dan memahami konteksnya, Ibnu Bayyah menjelaskan bahwa interaksi seorang Muslim dengan nash berlangsung pada dua mustawā (level). Pertama, mustawā al-īmān wa al-taṣdīq – yaitu level keimanan dan pembenaran batin terhadap wahyu. Pada tataran ini, setiap Muslim wajib mengimani kebenaran apa pun yang telah terbukti datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Bayyah mengutip firman Allah, “wa huwa al-ḥaqqu min rabbihim” – “…dan (Al-Qur’an) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka” (QS Muhammad [47]: 2), seraya menegaskan bahwa begitu suatu teks (terutama hadis) terverifikasi keasliannya secara qat‘ī, maka sikap seorang beriman adalah taslīm (menerima sepenuh hati) bahwa itu benar dari Allah, apapun isi hukumnya. Tidak boleh ada penolakan batin, karena menolak kebenaran wahyu berarti merusak iman. Dalam sejarah, para sahabat Nabi mencontohkan level ini: mereka menerima setiap ayat dan hadis yang shahih dengan iman dan takzim, yakin bahwa di dalamnya ada hikmah meski kadang tak langsung memahami.
Kedua, mustawā al-aḥkām al-‘amaliyyah – yaitu level pelaksanaan hukum-hukum praktis dalam kehidupan. Inilah level penerapan syariat dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pada level kedua inilah proses ijtihad dan pemahaman kontekstual sangat dibutuhkan. Ibnu Bayyah menjelaskan bahwa untuk dapat beramal sesuai nash, seseorang harus memahami nash tersebut dengan benar. Pemahaman menuntut tafsīr (penjelasan makna lahiriah teks) dan terkadang ta’wīl (penafsiran kontekstual atau figuratif bila makna lahiriah memerlukan penyesuaian dengan akal dan dalil lain). Dengan ungkapan lain, “li-kay na‘taqida aw na‘mal yajibu an nafham” – “agar kita bisa meyakini atau mengamalkan, kita harus memahami (teks itu) terlebih dahulu”.
Kebutuhan memahami konteks sebelum mengamalkan terlihat jelas dalam banyak contoh. Misalnya, perintah amar ma‘rūf nahy munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Secara tekstual, ini adalah kewajiban. Namun penerapannya tidak bisa asal: ada syarat-syarat agar tindakan nahi munkar efektif dan tidak menimbulkan mudarat lebih besar. Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya…” tetapi dilanjutkan dengan tingkatannya (dengan tangan, lisan, hati) tergantung kemampuan. Para ulama ushul merumuskan kaidah: “inkār al-munkar syarṭuhu allā yatatarrataba ‘alayhi munkar akbar” – mencegah kemungkaran disyaratkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi jika sebuah kemunkaran tidak dapat dicegah kecuali dengan risiko munculnya kekacauan yang lebih parah, maka haram hukumnya melakukan nahi munkar tersebut. Contoh lain, kewajiban jihad qitāl (perang defensif) dalam Islam pun selalu terikat konteks: tidak boleh dilakukan tanpa komando yang sah, pertimbangan maslahat, dan etika perang yang ketat. Inilah hal-hal yang masuk pada level kedua (implementasi), yang meniscayakan penalaran dan fleksibilitas, berbeda dengan level pertama (iman) yang sifatnya absolut.
Ibnu Bayyah menegaskan bahwa metodologinya “berangkat dari keyakinan bahwa syariat secara keseluruhan bagaikan satu kesatuan teks”. Maksudnya, setiap aturan praktis harus dipahami dalam kerangka utuh ajaran Islam secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Karena itulah, pada level penerapan, seorang faqīh harus membandingkan dalil-dalil, melihat mana yang umum-mana yang khusus, mana yang mungkin mengkhususkan yang lain, serta mempertimbangkan maqāṣid (tujuan akhir syariat) seperti keadilan, kemaslahatan dan rahmah. Ibnu Bayyah menyebut pendekatan ini sebagai “mencari harmoni antara ẓāhir nushūṣ dan realitas akal”, sehingga “indikasi tekstual dikalibrasi dengan keharusan rasional”. Dengan demikian, implementasi hukum menjadi relevan dan tidak kaku.
3. Lingkaran Metodologis Faqīh: Tafsir, Tanzil, dan Taf‘il
Sebagaimana disinggung di akhir Bab I, Ibnu Bayyah menguraikan bahwa faqīh yang ingin menerapkan fiqh al-wāqi‘ perlu melalui tiga tahapan konseptual (disebutnya da’irah atau lingkaran). Ketiga lingkaran itu memastikan interaksi yang komprehensif antara teks dan konteks:
- Lingkaran Pertama: Tafsīr dan Ta’wīl. Ini adalah tahap memahami teks. Seorang mujtahid harus melakukan ‘arḍ al-naṣṣ ‘alā al-lughah – memaparkan teks syariat pada kaidah bahasa Arab yang benar, mengkaji makna asal kata, struktur kalimat, konteks linguistik, serta kemungkinan makna majaz (metaforis) vs hakikat. Menurut Ibnu Bayyah, di sinilah diperlukan kecermatan: memahami jika ada lafaz yang musytarak (punya banyak arti), ‘ām (umum) atau khāṣ (khusus), mutlaq atau muqayyad, dan seterusnya. Misalnya, kata perintah “bunuhlah (قاتلوا)” dalam Al-Qur’an bisa bersifat umum, tapi perlu dilihat apakah ia muqayyad dengan sebab tertentu atau tidak. Contoh yang ia kemukakan adalah pandangan kelompok radikal yang menganggap ayat pedang (“fa-qtulū al-mushrikīn…” QS at-Taubah:5) menghapus 114 ayat lain tentang perdamaian[20]. Ini keliru karena mereka gagal memahami bahwa ayat tersebut terikat konteks perang defensif melawan musyrikin yang memusuhi, bukan perintah mutlak membantai non-Muslim dimanapun. Dalam lingkaran tafsir, mujtahid berupaya mengumpulkan seluruh ayat/hadis terkait suatu isu untuk memahami maksud utuhnya. Ibnu Bayyah mengingatkan: “jangan merumuskan hukum hanya berdasar dalil parsial (juz’ī) tanpa mempertimbangkan nilai universal syariat (kullī), dan jangan pula hanya berpegang pada prinsip global tanpa dasar dalil khusus”[21]. Keduanya harus seimbang. Sikap eklektik memilih satu dalil parsial dan mengabaikan yang lain adalah metode yang cacat (manhaj al-ijtzā’), sedangkan berpegang pada semangat umum tanpa nas konkret juga berbahaya. Oleh karena itu, lingkaran tafsir/ta’wil memastikan mufassir memadukan teks dengan konteks kebahasaan dan maqāṣid agar makna sejati teks tersingkap.
- Lingkaran Kedua: Tanzīl (Penerapan pada Realitas). Setelah memahami teks secara benar, tahap selanjutnya adalah menghubungkan teks dengan situasi nyata yang menjadi objek hukumnya. Inilah yang dalam uṣūl fiqh disebut taḥqīq al-manāṭ, yaitu proses memastikan bahwa illat atau syarat hukum terpenuhi dalam kasus konkret sebelum hukum dijalankan[22]. Ibnu Bayyah memandang tanzīl sebagai upaya menjawab pertanyaan: Bagaimana bunyi ketentuan syariat ini “diturunkan” pada keadaan sekarang? Pada tahap ini, realitas faktual harus diteliti secara mendalam (yang ia istilahkan fahm al-wāqi‘ – memahami realitas)[23]. Contohnya, jika teks mengatakan “hakim yang tidak menghukum dengan hukum Allah adalah kafir”, maka pada tahap tanzīl perlu dianalisis: apakah kondisi tidak berhukum dengan hukum Allah di suatu negeri Muslim masa kini persis sama dengan konteks ayat tersebut? Bagaimana sistem hukum, tekanan eksternal, dan keadaan umat saat ini? Apakah pejabat yang tidak menerapkan hudud otomatis kafir, padahal mungkin ia percaya wajibnya hudud tapi terhalang konstitusi negara? Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan bagian taḥqīq al-manāṭ yang esensial. Dalam fiqih klasik kita dapati implementasi taḥqīq al-manāṭ, misalnya keputusan ‘Umar bin Khattab untuk menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri di masa paceklik. Secara tekstual, surat al-Mā’idah:38 memerintahkan potong tangan pencuri. Namun ‘Umar melakukan tanzīl dengan melihat realitas: di masa kelaparan, banyak orang terpaksa mencuri makanan; memotong tangan dalam kondisi itu justru bertentangan dengan maqṣad syariat (memelihara jiwa). Kepekaan kontekstual seperti inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh Ibnu Bayyah. Beliau menyatakan bahwa produk ijtihad ulama terdahulu itu benar dan relevan pada masanya, tetapi “sebagaimana produk hukum lama sesuai konteks zamannya, produk hukum baru yang dibuat di masa kini – jika berdasarkan taḥqīq al-manāṭ yang benar – juga akan benar dan relevan”[24]. Dengan kata lain, perubahan konteks menuntut penyesuaian hukum tanpa keluar dari kerangka illat dan tujuan dasarnya. Tanpa tanzīl yang tepat, penerapan dalil bisa melenceng. Ibnu Bayyah memberi contoh: “sebuah teks atau produk hukum tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan realitas yang terjadi”, sebab jika teks hanya dipahami dan dijalankan secara tekstual belaka, itu bisa menghilangkan makna dan esensi syariat[25].
- Lingkaran Ketiga: Taf‘īl (Aktualisasi/Efektuasi). Tahap terakhir adalah mengoperasionalkan hukum dalam kehidupan masyarakat secara bijaksana. Ini mencakup penyusunan strategi, kebijakan, atau pedoman praktis agar hukum yang diterapkan mencapai tujuannya. Lingkaran ini menuntut keahlian dalam siyāsah shar‘iyyah (kebijakan publik Islami) dan fiqh al-awlawiyāt (skala prioritas). Ibnu Bayyah memandang bahwa setelah hukum ditetapkan sesuai konteks (lewat tanzīl), masih perlu dipikirkan faktor-faktor pendukung dan pencegah (muwānāt wa mawānī‘) dalam pelaksanaannya. Misalnya, kewajiban zakat sudah jelas dan kondisi memungkinkan (tanzīl ok), maka pada lingkaran taf‘īl tugas ulama/pemerintah adalah membuat mekanisme agar pembayaran zakat efektif, transparan, dan tepat sasaran. Begitu pula jika ditegakkan larangan suatu kemungkaran, perlu ada langkah pembinaan setelah penegakan hukum. Dalam konteks modern, lingkaran taf‘īl bisa berarti mempertimbangkan aspek hukum positif, HAM, kondisi global, sehingga penerapan syariat tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ibnu Bayyah mencontohkan pentingnya murā‘āt al-maṣāliḥ wa al-mafāsid (menimbang maslahat-mudarat) dalam tahap aktualisasi ini. Ia merumuskan kaidah: “Jika bertemu dua mudarat, hindarilah yang lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan; jika bertemu dua maslahat, dahulukan yang lebih besar meski harus mengorbankan yang lebih kecil”. Bahkan bila suatu tindakan mengandung sekaligus unsur maslahat dan mudarat, harus dilihat mana yang lebih dominan. Kaidah klasik yang dikutipnya: “apabila berkumpul suatu maslahat dan mafsadat dalam satu perkara, dan salah satunya lebih besar, maka yang lebih besar harus dimenangkan”. Prinsip ini berlaku kuat pada tataran implementasi kebijakan. Contoh konkrit: pelarangan sesuatu yang mubah demi mencegah mudarat (saddu al-żarī‘ah) bisa dilakukan pemerintah bila kemudaratan sudah meluas. Sebaliknya, sebuah kewajiban yang secara fiqh fardī (fikih individu) mesti ditegakkan bisa jadi ditangguhkan pada fiqh ijtimā‘ī (fikih sosial) jika menimbulkan kekacauan umum.
Dengan melewati tiga lingkaran di atas, seorang faqīh akan menghasilkan keputusan hukum yang tidak saja shar‘ī (sesuai dalil) tetapi juga wāqi‘ī (sesuai realitas). Ibnu Bayyah menyebut metode ini sebagai jalan tengah untuk mengoreksi dua tipe kecenderungan yang menyimpang: (a) Kelompok tekstual ekstrem – mereka yang hanya berkutat di lingkaran pertama (teks) tanpa mengindahkan konteks, sehingga melahirkan hukum kaku dan kadang kejam; dan (b) Kelompok liberal ekstrem – mereka yang terlalu menekankan konteks (mungkin melampaui lingkaran kedua) sampai-sampai menafikan kejelasan teks, sehingga berpotensi menyelewengkan hukum. Keduanya adalah ifrat dan tafrith yang dihindari. Adapun manhaj wasath (moderat) menurut Ibnu Bayyah adalah yang menghubungkan teks dan konteks secara sinergis. Ia mengistilahkannya membutuhkan “nazhar murakkab” – perspektif majemuk yang mengikat antara dalil-dalil syar‘i dan fakta-fakta empiris.
4. Kaidah-Kaidah Ushul Kontekstual (Mudadat al-Manhaj)
Dalam kitab Tanbīh al-Marāji‘, Ibnu Bayyah menguraikan beberapa mudadāt al-manhaj (ketentuan atau parameter metodologis) yang menjadi ciri pendekatannya. Beberapa di antaranya telah tersirat dalam penjelasan sebelumnya, namun dapat dirangkum sebagai berikut:
- Pandangan Syumuliyah (Holistik) terhadap Dalil.
Seperti telah disinggung, Ibnu Bayyah mewanti-wanti agar seorang mujtahid melihat syariat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Ia berkata, “النظرة الشمولية التي تعتبر الشريعة كلها بمنزلة النص الواحد” – “pandangan yang komprehensif yang menganggap seluruh syariat itu kedudukannya laksana satu teks (yang utuh)”. Maksudnya, jangan sampai seseorang menarik kesimpulan hukum hanya dari satu ayat atau hadis secara terpisah, tanpa memperhatikan ayat/hadis lain, kaidah umum, serta konsensus ulama. Banyak kekeliruan bersumber dari penggalian dalil secara sepotong-sepotong (manhaj al-ijtzā’). Misal kasus khawarij klasik: mereka membaca ayat “Lā ḥukma illā liLlāh” (tidak ada hukum kecuali milik Allah) secara terisolasi, lalu mengafirkan Ali bin Abi Thalib karena dianggap berhukum dengan arbitrase manusia. Mereka lupa bahwa Ali dan para sahabat lain memahami dalil tersebut bersama dalil-dalil lain (tentang keharusan persatuan, taat pemimpin, larangan bughat). Contoh lain di era kini, sebagian kelompok mengutip hadis tentang keutamaan jihad dan mati syahid lalu memaknai jihad hanya sebagai perang fisik dimana pun, padahal jihad memiliki banyak jenis dan konteks. Perspektif sempit semacam ini lahir dari absen-nya pandangan holistik. Karena itu Ibnu Bayyah menegaskan: “Barangsiapa belum menguasai sebagian besar cabang-cabang dalil, lalu ia hanya melihat sepotong di antaranya berdasarkan metode potong-memotong (ijtizā’), maka pasti ia akan salah memahami”. Pernyataan ini menggarisbawahi syarat klasik mujtahid: harus muḥīṭ bi al-shar‘ (menguasai khazanah syariat) secara luas, tidak cukup modal beberapa dalil. - Pertimbangan Ma’ālāt (Konsekuensi) dan Prinsip Maslahat-Mafsadah.
Parameter kedua ialah murā‘āt al-ma’ālāt, yaitu selalu mempertimbangkan akibat atau konsekuensi jangka panjang dari suatu fatwa atau tindakan hukum. Ibnu Bayyah menempatkan ini sebagai kunci fiqh al-wāqi‘. Dalam bahasa beliau: “لكي نتعامل يجب أن نقبل أن نبدّل رأينا تبعًا للمصلحة في مستوياتها المتعددة غايةَ التشريع وحكمةَ الأحكام” – “agar dapat berinteraksi (dengan realitas), kita harus siap mengubah pendapat kita sesuai kemaslahatan pada berbagai tingkatannya, demi mencapai tujuan syariat dan hikmah di balik hukum-hukum”. Ini tidak berarti mengubah prinsip agama, melainkan menyesuaikan pelaksanaan hukum dengan melihat skala kemaslahatan dan kerugian. Ibnu Bayyah mengutip kaidah klasik: “إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما; وإذا تعارضت مصلحتان رُوعي أسبهما تحقيقًا بتحصيل أعظمهما” – artinya “Jika bertemu dua kerusakan (mudarat) maka diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan; dan jika bertemu dua kebaikan (maslahat) maka diperhatikan yang lebih pasti tercapai dengan meraih yang lebih besar”. Kaidah lainnya: “المصلحة الكبيرة تُقدَّم على المصلحة الصغيرة، والمفسدة الكبيرة تُدرَأ ولو فاتت مصلحة صغيرة”. Implementasi prinsip ini banyak contohnya: membolehkan sesuatu yang haram karena darurat (menghindari mudarat besar), melarang yang mubah karena jadi wasilah ke haram (demi cegah mudarat), mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah ketika berbenturan, dsb. Ibnu Bayyah memandang pertimbangan maslahat-mafsadah bukan perkara tambahan, tapi bagian integral penetapan hukum dari dulu. Hanya saja, sebagian kalangan ekstrem mengabaikan ini – mereka mengeksekusi teks secara “kering” tanpa mempertimbangkan dampak. Misalnya kelompok ISIS yang menerapkan hudud (rajam, potong tangan) di tengah situasi kacau perang sehingga malah memperburuk citra Islam; jelas ini bertentangan dengan maqāṣid meski dalil teksnya benar ada. Karena itu, setiap mufti dan dai menurut Ibnu Bayyah wajib memahami fiqh maqāṣid agar tidak “yufawwitu ruh al-sharī‘ah” – menghilangkan spirit syariat dalam mengejar teks[25]. - Membedakan Khithāb Taklifi dan Waḍ‘i.
Kaidah metodologis berikutnya adalah at-tamyīz bayna al-khiṭāb al-taklīfī wa al-khiṭāb al-waḍ‘ī, yakni membedakan “teks perintah/larangan” dan “teks yang menetapkan kondisi/syarat hukum”. Khiṭāb taklīfī adalah segala dalil yang berisi tuntutan (seperti wajib, sunnah, haram, dsb.), sedangkan khiṭāb waḍ‘ī adalah dalil tentang sebab, syarat, penghalang, atau definisi status hukum (misal dalil “musafir boleh qoshor” menetapkan kondisi safar sebagai sebab rukhṣah). Ibnu Bayyah menekankan perbedaan ini karena kekeliruan memahaminya bisa fatal. Ia memberi contoh: amar ma‘ruf nahi munkar adalah tuntutan taklifi (fardu kifayah). Namun terdapat khithab waḍ‘i yang menjadi syarat: yaitu tidak menyebabkan kemungkaran lebih besar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka taklif tersebut tidak berlaku saat itu. Demikian pula perintah perang (qitāl) terhadap orang kafir memiliki syarat waḍ‘i: misalnya harus dipimpin Imam yang legitimate, karena tanpa komando akan jadi kekacauan. Jika syarat tersebut tak ada, hukum taklifi berperang tidak serta merta gugur (tetap ada secara teori) tetapi tanpa pemenuhan syarat ia tidak boleh dieksekusi. Prinsip ini sebenarnya simpel, namun kerap dilupakan kelompok radikal yang mengangkat senjata tanpa otorisasi ulama/pemerintah dengan dalih dalil perang di Al-Qur’an. Mereka lalai bahwa teks jihad perang dalam Qur’an selalu terkait kondisi tertentu (ada agresi musuh, ada pemimpin, dll.). Ibnu Bayyah menyatakan: “Khiṭāb waḍ‘ī adalah ‘lingkungan ushul’ bagi hukum taklifi yang mengitarinya dan membatasinya”. Artinya, nash taklifi tidak berdiri sendiri, ia dibatasi faktor-faktor waḍ‘i. Contoh waḍ‘i lain: sabab (sebab hukum) – seperti terbit fajar adalah sebab masuk waktu shalat Subuh. Tanpa sebab itu, taklif shalat subuh belum berlaku. Maka, harus jelas mana dalil yang bersifat syarat/penyebab dan mana yang perintah inti. Dalam praktik berfatwa modern, poin ini mengajarkan agar kita mempertimbangkan real-condition sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum. Fatwa misalnya tentang penegakan syariat di level negara, harus lihat syurūṭ sosial-politiknya; fatwa tentang kewajiban berpoligami misalnya, harus lihat adakah ‘illah yang terpenuhi. Dengan membedakan khithab taklifi-waḍ‘i, Ibnu Bayyah ingin menghindarkan sikap serampangan: menjalankan perintah tanpa peduli syarat, atau menetapkan status hukum tanpa mengindahkan konteks yang ditetapkan syariat. - Al-Jam‘ bayna al-Nuṣūṣ (Mengompromikan Dalil-Dalil yang Tampak Berkontradiksi).
Ibnu Bayyah sangat menekankan metode al-jam‘ wa al-tawfīq dalam menghadapi dalil-dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan. Ia menyatakan: “Innā muḥāwalata al-jam‘ bayna al-adillati hiya al-khaṭwah al-ūlā allatī yakhtuuhā al-mujtahid qabla al-lujū’ ilā wasa’il al-tarjīḥ” – “Upaya mengompromikan (menggabungkan) dua dalil yang lahirnya berkontradiksi merupakan langkah pertama yang harus ditempuh mujtahid, sebelum ia beralih ke cara-cara tarjih (memilih salah satu)”. Prinsip ini klasik dalam ushul, tetapi acapkali diabaikan oleh polemis zaman kini yang gemar mempertentangkan dalil untuk membenarkan kelompoknya. Misalnya, perbedaan pandangan tentang qunut Subuh atau tentang tafsir sifat Allah, kerap dibesar-besarkan seolah salah satu dalil pasti batil. Padahal bisa jadi semua dalil itu benar dengan konteksnya masing-masing. Ibnu Bayyah menyebutkan, para mujtahid salaf selalu mendahulukan jama‘ daripada tarjīḥ atau naskh. Hanya jika upaya kompromi benar-benar buntu, barulah salah satu dalil ditarjih (dikuatkan) atau dinyatakan mansukh (dihapus). Contoh jam‘ yang populer misalnya hadits-hadits tentang shalat tahiyyat al-masjid saat khatib khutbah: ada dalil Nabi menyuruh sahabat shalat 2 rakaat meski khutbah sedang berlangsung, ada pula hadis yang memerintahkan diam mendengar khutbah. Ulama mengkompromikan: yang terlarang adalah shalat sunnah mutlak berlama-lama ketika khutbah, tapi jika baru masuk masjid memang disunnahkan tahiyyat masjid sekadar 2 rakaat ringan agar tidak duduk tanpa shalat. Dengan jam‘ ini, kedua hadits diamalkan. Adapun mereka yang tidak memahami metode jam‘ mungkin akan langsung menafikan salah satunya. Dalam konteks fikih global masa kini, metode jam‘ berarti kita perlu sinkronisasi antara teks yang terkesan skriptural dengan nilai-nilai universal Islam. Misal, teks jihad vs teks perdamaian: semuanya harus dipahami utuh. Ibnu Bayyah dalam Mardin Conference (2010) menunjukkan salah satu bentuk jam‘: memadukan dalil tentang dār al-islām dan dār al-ḥarb dengan dalil ṣulḥ (perdamaian). Ia berpendapat konteks dunia modern yang terikat piagam PBB lebih sesuai disebut dār al-‘ahd (zona perjanjian damai) ketimbang dikotomi perang[26][27]. Dengan demikian ayat-ayat perang tidak hilang (tetap berlaku saat penyerangan terjadi), namun ayat-ayat damai lebih dominan di masa sekarang. Upaya reinterpretasi itu pada hakikatnya adalah jam‘: semua dalil diakomodasi sesuai penempatannya. - Membedakan Makna Istilah Berdasarkan Penggunaan Syari dan Urfi.
Kaidah selanjutnya, Ibnu Bayyah menekankan pentingnya munāsabat al-lughah wa al-‘urf – memahami istilah sesuai penggunaan syariat atau kebiasaan (konteks). Satu kata bisa bermakna berbeda tergantung konteks penggunaannya. Ia mencontohkan istilah “kāfir” dalam Al-Qur’an. Secara harfiah artinya “orang yang ingkar/tidak beriman”. Namun penggunaannya tidak selalu berarti kafir dalam arti murtad dari Islam. Ibnu Bayyah mengingatkan bahwa dalam QS al-Mā’idah ayat 44, ketika Allah berfirman “wa man lam yaḥkum bimā anzala Allāh fa ulā’ika hum al-kāfirūn” (barangsiapa tidak menghukum dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang kafir), kata “kafir” di sini tidak serta-merta bermakna kafir keluar dari Islam. Kaum Khawarij salah kaprah menjadikan ayat ini sebagai slogan mengafirkan setiap Muslim yang melakukan dosa besar atau yang tidak menerapkan hukum hudud. Ibnu Bayyah mengutip penjelasan Ḥabr al-Ummah (pakar umat) Ibn ‘Abbās ra. yang menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat “kufrun dūna kufr” – “ada kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam”. Maksudnya, kafir di ayat itu adalah kufur dalam pengertian kufr al-ni‘mah (mengingkari nikmat Allah atau syariat dalam tindakan, bukan dalam keyakinan). Pelaku dosa tersebut dianggap melakukan perbuatan kufur namun tetap Muslim fasik selama ia tidak meyakini halal perbuatannya[28]. Hal ini telah menjadi ijmā‘ Ahlus Sunnah: bahwa Muslim yang berdosa besar (selama masih mengakui kewajiban hukum Allah) tidak dihukumi kafir selama-lamanya[29]. Adapun Khawarij dahulu (dan takfiri modern) gagal memahami perbedaan konsep tersebut. Mereka menganggap “kafir” selalu berarti kafir akidah yang abadi di neraka, sehingga melabeli para pelaku dosa besar sebagai kafir dan halal darahnya. Kesalahan ini salah satunya akibat tidak melihat siyaq (konteks) Al-Qur’an dan asbāb al-nuzūl ayat. Ibnu Bayyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa QS al-Mā’idah:44-47 semula turun terkait ahli kitab (Bani Israil) yang menyembunyikan hukum Taurat[30]. Kemudian sebagian ulama menerapkannya pula pada Muslimin yang tidak menegakkan hukum, dengan tafsiran kufrūn dūna kufr tadi (selama tidak istihlal). Begitu pula kata ẓālim dan fāsiq pada ayat 45 dan 47 dari surah yang sama, ditafsirkan maknanya sebagai “dosa besar” bukan keluar dari agama. Contoh lain, kata jihad sering dipahami masyarakat hanya sebagai perang, padahal makna syarinya luas (termasuk jihad melawan hawa nafsu). Demikian pula “kalimatul kufr” dalam hadis bisa bermakna perkataan kufur namun pelakunya belum tentu murtad jika terpenuhi syarat udzur seperti jahil atau dipaksa. Semua ini mengajarkan agar kita tidak gegabah menerjemahkan istilah agama tanpa melihat bagaimana istilah itu digunakan dalam berbagai dalil. Ibnu Bayyah ingin umat memahami bahwa bahasa syariat sering menggunakan istilah gradatif. Dengan pemahaman istilah yang tepat, kita tidak akan mudah mengafirkan atau menghukumi sesat orang lain. - Murāja‘at al-Siyaqāt (Meninjau Kembali Konteks Historis Nash).
Terakhir, Ibnu Bayyah menggarisbawahi pentingnya selalu meninjau siyāq (konteks) dan sabāb nuzūl atau wurūd (sebab munculnya) suatu nash sebelum mengistinbat hukum darinya. Ini adalah adab dasar ahli tafsir: setiap ayat Quran turun dalam konteks tertentu, begitu pula hadis sering terucap merespons pertanyaan/keadaan spesifik. Memahami konteks ini dapat mencegah kesalahpahaman. Sebagai contoh, hadis Nabi “Barangsiapa mengganti agamanya, bunuhlah dia” sering dikutip untuk membenarkan kekerasan terhadap murtadin tanpa prosedur. Padahal konteks hadis itu diucapkan di masa perang, terkait pengkhianatan (seperti kasus orang murtad gabung musuh)[30]. Demikian pula ayat pedang QS at-Taubah:5 jika dilihat asbāb nuzūlnya, ditujukan pada periode perang melawan kaum musyrikin yang melanggar perjanjian. Dengan memahami konteks, kita tahu bahwa perintah di ayat itu sifatnya retaliatif-terbatas, bukan perintah membunuh non-Muslim sepanjang masa. Ibnu Bayyah mengajak para marāji‘ (otoritas fatwa) masa kini untuk jeli dalam hal ini. Ia memuji para sahabat Nabi dan imam mujtahid dahulu yang sering “melakukan murāja‘ah terhadap teks-teks dengan sudut pandang baru sesuai perkembangan zaman”. Para sahabat sendiri tak segan berdialog bila ada pemahaman tekstual yang tampak kontradiksi dengan realitas. Misalnya, Khalifah ‘Umar memeriksa ulang pemahaman tentang pembagian tanah taklukan di Irak (apakah harus langsung dibagi ke mujahidin sesuai zahir nash fa’i, atau dikelola negara demi kemaslahatan umum). Setelah diskusi mendalam dengan para sahabat lain dan meninjau ayat-ayat lain, diputuskan tanah itu tidak dibagi pribadi tapi menjadi milik negara untuk kesejahteraan bersama – ini contoh murāja‘at al-nuṣūṣ dalam konteks baru. Dengan sikap terbuka demikian, syariat Islam tetap dinamis dan aplikatif sepanjang zaman tanpa kehilangan prinsip.
Penjabaran panjang di atas menunjukkan bahwa metodologi Ibnu Bayyah dalam menghadapi nash sangat menekankan keseimbangan: antara teks dan konteks, antara dalil parsial dan tujuan universal, antara nalar dan literal, antara tsawābit (ajaran tetap) dan mutaghayyirāt (hal-hal yang berubah mengikuti kondisi). Ia sejatinya menghidupkan kembali semangat ushul fiqh klasik dengan penegasan khusus pada aspek realitas kekinian (itulah fiqh al-wāqi‘). Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana metodologi ini diterapkan dalam dua konsep kunci: taḥqīq al-manāṭ dan maqāṣid al-sharī‘ah, serta pada studi kasus isu takfīr dalam penafsiran QS al-Mā’idah.
Taḥqīq al-Manāṭ dan Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Pendekatan Kontekstual
Bab ini secara khusus membahas dua pilar penting dalam fiqh al-wāqi‘ menurut Ibnu Bayyah, yakni konsep taḥqīq al-manāṭ dan penggunaan maqāṣid al-sharī‘ah. Keduanya merupakan perangkat utama untuk menjembatani antara ketetapan teks dengan situasi konkret di lapangan.
1. Konsep Taḥqīq al-Manāṭ (Verifikasi Illat pada Kasus Konkret)
Istilah taḥqīq al-manāṭ secara sederhana berarti “memastikan (‘verifikasi’) ada-tidaknya illat atau kondisi yang menjadi landasan hukum pada objek yang akan diterapkan hukum”[22]. Dalam kerangka ijtihad klasik, setelah mujtahid menetapkan bahwa suatu illat adalah dasar dari hukum umum (takhrīj al-manāṭ), ia perlu meneliti setiap kasus nyata: apakah illat itu terpenuhi di sana atau tidak. Ibnu Bayyah menyebut taḥqīq al-manāṭ sebagai “proses menerapkan aturan tertulis ke dalam tempatnya yang tepat” dengan memahami alasan (illat al-ḥukm) dan situasi suatu masalah[31]. Proses ini tidak pernah usang dan “harus dilakukan oleh setiap mujtahid” di setiap masa[22].
Mengapa taḥqīq al-manāṭ penting? Karena kondisi manusia dan dunia selalu berubah. Suatu hukum yang ditetapkan teks pada situasi tertentu, mungkin membutuhkan penyesuaian saat situasinya berubah. Ibnu Bayyah memberikan analogi: “Fatwa tentang arah kiblat, misalnya, harus mempertimbangkan di mana posisi orang yang shalat dan di mana Ka’bah relatif terhadapnya”. Dalam teks, perintahnya sederhana: menghadap kiblat. Tapi realisasinya di lapangan perlu dicari arah yang tepat, dan bisa berbeda tergantung lokasi orang tersebut[32][33]. Contoh lain, Al-Qur’an memerintahkan menegakkan keadilan dan melarang kezaliman. Illat perintah ini jelas: keadilan adalah pilar masyarakat. Tetapi bagaimana bentuk konkrit keadilan di setiap konteks? Apakah adil itu mesti potong tangan pencuri dalam semua keadaan? Ternyata tidak, pada masa paceklik, memotong tangan justru dinilai tidak adil (karena orang mencuri karena lapar). Maka, taḥqīq al-manāṭ membawa kita pada kesimpulan bahwa illat hukum potong tangan (yaitu adanya pencurian normal di kondisi masyarakat cukup) tidak terpenuhi di masa paceklik; illat berubah, hukumnya pun ditangguhkan.
Ibnu Bayyah mengungkapkan bahwa taḥqīq al-manāṭ inilah yang membuat produk ijtihad ulama salaf tetap relevan di masanya, dan yang akan membuat produk ijtihad baru juga relevan di masa kini asalkan dilakukan dengan benar[24]. Ia mengkritik keras kelompok yang anti terhadap konsep ini, misalnya kelompok yang kukuh menerapkan mentah-mentah nash tanpa peduli perubahan konteks. Bagi Ibnu Bayyah, itu justru penyimpangan dari manhaj salaf. Para ulama dahulu sangat memperhatikan taghayyur al-azminah (perubahan zaman) dan ikhtilāf al-aḥwāl (perbedaan situasi). Bahkan ada qa’idah fikih masyhur: “lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah” – tidak diingkari bahwa hukum (dalam perkara ijtihadi) bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat. Tentu yang dimaksud berubah di sini bukan ushuluddin atau hal-hal qat‘ī, melainkan hal-hal furū‘ dan kebijakan kemasyarakatan.
Sebagai contoh modern: hukum bunga bank (riba). Para ulama kontemporer melakukan taḥqīq al-manāṭ terhadap fenomena bank: adakah illat riba (eksploitasi/zulm) dalam setiap transaksi bank? Bagaimana jika sistem ekonomi global sudah sedemikian rupa sehingga without interest malah sulit berjalan? Diskusi panjang melahirkan detil fatwa seperti bolehnya deposito dengan nisbah bagi hasil (dengan menilai illat berbeda dari riba klasik), atau rukhsah untuk Muslim minoritas memanfaatkan bank konvensional darurat. Ini menunjukkan taḥqīq al-manāṭ bekerja: illat riba itu apa? Apakah fixed interest rate? Atau eksploitasi? Apakah semua bunga = riba? Dengan menelaah konteks, bisa jadi disimpulkan tidak semua interest itu riba jika tidak memenuhi illat haramnya (misal tidak menindas dan ada kebutuhan).
Ibnu Bayyah juga menyinggung aspek al-‘urf (kebiasaan sosial) dalam taḥqīq al-manāṭ. Misalnya, nash melarang tabdzir (pemborosan). Tapi batas pemborosan tentu relatif, tergantung ‘urf masyarakat. Membelanjakan 1 juta untuk sebuah barang bisa dianggap boros di satu komunitas tapi biasa saja di komunitas lain. Mujtahid perlu melihat ‘urf setempat sebagai bagian dari konteks. “Al-‘ādah muḥakkamah” (adat kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum) adalah kaidah fikih yang sejalan dengan semangat taḥqīq al-manāṭ.
Pada intinya, taḥqīq al-manāṭ menuntut ulama memahami realitas secara mendalam dan ilmiah. Ibnu Bayyah mendorong kolaborasi lintas disiplin: ulama perlu wawasan ilmu sosial, ekonomi, politik, agar bisa menganalisis kondisi dengan akurat. Jika tidak, fatwanya mungkin secara teks benar tapi tak bisa dilaksanakan atau membawa mudarat. Di sinilah fiqh al-wāqi‘ benar-benar berperan – memastikan syariat membumi dalam tiap konteks dengan tetap berpegang pada illat dan maqasid.
2. Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Kerangka Berpikir
Maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat) melengkapi taḥqīq al-manāṭ dalam metodologi Ibnu Bayyah. Ia menempatkan maqāṣid sebagai kompas moral untuk menilai apakah suatu penetapan hukum telah sesuai ruh Islam atau belum. Tujuan tertinggi syariat Islam dikenal mencakup perlindungan lima hal pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ditambah sebagian ulama modern termasuk kehormatan dan lingkungan. Setiap hukum Islam hakikatnya bertujuan menjaga nilai-nilai pokok tersebut.
Ibnu Bayyah dalam kitabnya sering merujuk kepada maqāṣid, terutama konsep jalb al-maṣāliḥ (mengambil kemaslahatan) dan dar’ al-mafāsid (menolak kerusakan). Ia menyebut “ghāyat al-tashrī‘ wa ḥikmat al-aḥkām” – tujuan pensyariatan dan kebijaksanaan di balik hukum – harus selalu diperhatikan dalam berfatwa. Ini selaras dengan motto Ushul Fiqh klasik: al-ḥukm yadūru ma‘a al-‘illah wa al-maṣlaḥah. Bila maslahah (yang syar‘i) berubah, pendekatan hukum pun bisa diubah selama tidak keluar dari prinsip.
Dalam fiqh al-wāqi‘, penggunaan maqāṣid terutama tampak saat terjadi kasus-kasus kompleks yang secara tekstual hukum asalnya terlihat keras, namun mempertimbangkan maqāṣid bisa jadi diambil rukhshah. Contoh nyata misalnya masalah hubungan antarumat beragama di era modern. Secara tekstual, ada ayat tentang larangan loyalitas (al-walā’) kepada non-Muslim yang memusuhi Islam. Namun secara maqāṣid, tujuan syariat adalah menjaga dakwah dan perdamaian. Maka Ibnu Bayyah cenderung menganjurkan sikap kooperatif dengan non-Muslim selama dalam hal kebaikan, sebagai implementasi maqāṣid persaudaraan kemanusiaan. Pandangannya ini tergambar dalam pernyataannya: “Kami percaya bahwa peluang bagi keadilan untuk tumbuh ada ketika ada perdamaian, bukan perang”[34]. Pernyataan ini dibangun atas kesadaran maqāṣid: kedamaian adalah kondisi primer agar tujuan syariat (keadilan, kemakmuran) tercapai. Oleh karena itu, fatwa-fatwa dan inisiatif Ibnu Bayyah sangat bernuansa mendukung perdamaian dunia, seperti prakarsanya dalam Forum Promosi Perdamaian (Forum for Promoting Peace) tahun 2014 yang mengumpulkan ratusan ulama untuk mencegah konflik antarnegara Muslim[6]. Ia merasa menjaga nyawa (ḥifẓ al-nafs) dan persatuan umat (ḥifẓ al-dīn dalam makna kolektif) lebih utama daripada terus menerus mengobarkan semangat perang yang justru dimanfaatkan pihak musuh. Ini adalah penerapan maqāṣid dalam konteks politik global.
Contoh lain, dalam bidang muamalah modern: praktek asuransi konvensional secara tekstual mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang diharamkan hadis. Namun secara maqāṣid, asuransi bertujuan melindungi jiwa dan harta (sejalan dengan maqasid hifz al-nafs dan al-mal). Banyak ulama kontemporer termasuk Ibnu Bayyah cenderung mencari formulasi agar asuransi diperbolehkan secara syari (misal dengan konsep ta’min ta’awuni), alih-alih mengharamkan total yang bisa menutup kemaslahatan besar. Ini menunjukkan penggunaan maqasid sebagai pertimbangan.
Dalam kitab Tanbīh al-Marāji‘, Ibnu Bayyah mencontohkan juga pada level individu: bila menjalankan satu dalil akan mengakibatkan pelanggaran maqāṣid yang lebih besar, maka penetapan hukum perlu ditinjau. Ia menyitir kaidah Imam Ibn Taymiyyah: “ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين” – “bukan orang cerdas namanya jika hanya tahu membedakan baik dan buruk, tapi orang cerdas adalah yang tahu mana yang lebih baik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan.” Kaidah ini menuntun kita agar setiap keputusan selalu merujuk pada skala prioritas maqasid.
Implementasi konkrit maqasid dalam fikih pemerintahan misalnya: hukuman bagi pembangkang (bughat) bisa sangat tegas menurut fiqih (boleh diperangi). Namun maqasid mencegah pertumpahan darah mungkin mendorong pemerintah memilih negosiasi ketimbang langsung perang, meski ada dalil perangi bughat. Itu bukan berarti mengabaikan nash, melainkan mengamalkan nash lain (tentang islah/rekonsiliasi) demi maqasid lebih besar.
Dengan memahami maqāṣid, ulama juga bisa beristinbat hukum baru untuk masalah baru yang belum ada di teks. Misal regulasi tentang kejahatan siber, perlindungan data pribadi, lingkungan hidup – semua bisa digali hukumnya dengan acuan maqasid (karena melibatkan perlindungan jiwa, harta, kehormatan, dsb). Ibnu Bayyah sendiri aktif dalam fiqh minoritas (aqalliyyāt) yang sangat memerlukan pendekatan maqasid untuk menjawab situasi Muslim di negara non-Muslim. Dalam bukunya Sina‘at al-Fatwa, ia sering menyebut maqasid sebagai pedoman fleksibilitas berfatwa bagi minoritas, contohnya soal ucapan selamat hari raya agama lain demi kerukunan (boleh dengan niat mujamalah, karena maqasidnya mempererat persaudaraan selama tak melanggar akidah).
Secara ringkas, maqāṣid al-sharī‘ah dalam pandangan Ibnu Bayyah bukanlah hal terpisah dari dalil, melainkan ruh yang menjiwai teks. Ia berkali-kali menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan[35][36]. Maka jika ada interpretasi hukum yang nyata-nyata membawa kerusakan besar dan melawan prinsip rahmat, pasti ada yang salah dalam interpretasi itu. Memahami maqasid akan menuntun mufti untuk menghindari fatwa yang aneh dan membahayakan. Misalnya, fatwa ekstrem yang membolehkan bom bunuh diri dengan dalih jihad jelas menyalahi maqasid (karena membunuh diri sendiri dan sipil tak berdosa bertentangan dengan perlindungan jiwa). Itulah mengapa Ibnu Bayyah dan para ulama moderat gigih membantah legitimasi aksi teror. Mereka menunjukkan dalil-dalil syar‘i memang tak mendukung, dan secara maqasid pun hal itu merusak Islam dari dalam.
Dengan demikian, taḥqīq al-manāṭ dan maqāṣid al-sharī‘ah adalah dua sisi mata uang dalam metodologi Ibnu Bayyah: yang satu memastikan kesesuaian konteks (faktualitas), satunya memastikan kesesuaian tujuan (moral-spiritual). Keduanya membuat fiqh al-wāqi‘ yang ia gagas menjadi landasan kokoh untuk berijtihad secara tepat guna di era modern.
Analisis Isu Takfīr dalam Tafsir QS al-Mā’idah Menurut Ibnu Bayyah
Salah satu penerapan penting dari metodologi di atas adalah dalam menanggapi dalil-dalil yang sering diselewengkan oleh kelompok ekstrem untuk membenarkan takfīr (pemvonisan kafir terhadap Muslim lain). Ayat yang paling menonjol dalam hal ini ialah QS al-Mā’idah ayat 44, beserta ayat 45 dan 47, yang bunyinya berurutan: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir” (ayat 44), “…maka mereka itu adalah orang-orang zalim” (ayat 45), “…maka mereka itu adalah orang-orang fasik” (ayat 47). Sekilas, ayat-ayat ini berkesan sangat keras mengkafirkan, men-zalimkan, dan men-fasikkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah.
Kelompok takfīri (seperti Khawarij klasik, dan belakangan ini beberapa gerakan radikal) kerap menjadikan ayat 44 khususnya sebagai dasar slogan mereka bahwa setiap Muslim yang tidak menerapkan syari’at Islam (secara formal) adalah kafir keluar dari agama. Dengan itu mereka mengafirkan pemerintah Muslim yang tidak berhukum Islam secara penuh, mengafirkan hakim yang memakai hukum positif modern, bahkan mengafirkan masyarakat yang menerima sistem tersebut. Implikasi lebih jauh, mereka menganggap halal darah dan hartanya, serta merasa berjihad memerangi “thaghut” tersebut. Inilah ideologi yang menyuburkan terorisme yang mengatasnamakan “penegakan hukum Allah”.
Ibnu Bayyah, sebagai ulama wasathi, menolak mentah-mentah pemahaman seperti di atas. Dalam kitab Tanbīh al-Marāji‘, ia mengupas masalah ini dengan sangat hati-hati. Pertama, ia mengajak kita melihat konteks syariat dan ijmā‘ para ulama mengenai status pelaku dosa besar. Konsensus Ahlus-Sunnah wal Jama’ah sejak masa sahabat menyatakan “lā yukaffaru ahadun min ahl al-qiblah bi ẓanbin” – tidaklah menjadi kafir seorang Muslim pelaku dosa besar, selama ia masih mengakui kewajiban syariat tersebut[28]. Akidah Ahlus-Sunnah berbeda dari Khawarij (yang mengafirkan pelaku dosa besar) maupun Murji’ah (yang menganggap dosa sebesar apapun tidak masalah dalam iman, satu hal ekstrem lainnya). Ahlus-Sunnah berada di tengah: pelaku dosa besar disebut fāsiq (pendosa) tetapi masih Muslim selama bukan dosa yang jelas-jelas mengandung kekufuran akidah.
Selanjutnya, secara spesifik mengenai QS al-Mā’idah:44, Ibnu Bayyah mengutip tafsiran dari sahabat terkemuka, Ibnu ‘Abbās ra. Ibnu ‘Abbās menanggapi pemahaman Khawarij tentang ayat tersebut dengan berkata: “إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه” – “Itu (kafir dalam ayat tersebut) bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian maksud”, melainkan “kufrun dūna kufr” (kufur yang lebih rendah daripada kufur [akidah]). Dalam riwayat lain disebut, maksudnya adalah kufur ni‘mah (sikap ingkar/ tidak bersyukur atas nikmat Allah berupa syariat) – satu istilah yang menunjukkan dosa besar namun tidak mengeluarkan dari iman. Ibnu Bayyah menggunakan penafsiran ini sebagai landasan kuat bahwa “orang Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah (karena fasik atau mengikuti hawa nafsu) tidak serta-merta menjadi kafir murtad kecuali bila ia mengingkari kewajiban hukum Allah tersebut”. Perbedaan terletak pada sikap hatinya terhadap hukum itu: jika ia meninggalkan hukum Allah karena malas, atau takut, atau korupsi, itu dosa besar (fasik/zalim) tetapi selama ia tidak menghalalkan perbuatannya, ia masih dihukumi Muslim yang berdosa[37]. Sebaliknya, bila ia meninggalkan hukum Allah disertai keyakinan bahwa hukum Allah jelek atau tidak pantas, barulah ia jatuh kufur akbar. Pembeda ini sangat penting namun sering diabaikan kelompok takfiri.
Ibnu Bayyah juga menjelaskan bahwa pada kenyataannya, ayat 44 al-Mā’idah awalnya turun terkait Ahli Kitab (Yahudi Bani Quraizhah) yang menyembunyikan sebagian isi Taurat dan berhukum bukan dengan wahyu Allah[30]. Hal ini dikuatkan oleh riwayat di Shahih Muslim tentang sebab turunnya ayat tersebut: Nabi ﷺ pernah didatangi sekelompok Yahudi yang meminta beliau mengadili kasus zina pasangan bangsawan mereka. Mereka berharap Nabi akan memutuskan hukuman ringan, tetapi ternyata beliau menetapkan rajam sesuai Taurat. Yahudi itu protes, hingga Rasulullah meminta ditunjukkan Taurat, dan muncullah ayat bahwa mereka yang tak mau berhukum dengan wahyu Allah adalah kafir/zalim/fasik. Jadi konteks aslinya ditujukan untuk kecaman kepada ulama Yahudi yang curang terhadap kitab suci mereka sendiri[38]. Walaupun demikian, ulama kita memperluas maknanya sebagai peringatan umum juga bagi umat Islam. Namun perlu hati-hati dalam memperluas makna, jangan sampai melampaui maksud syariat.
Inti tafsiran moderat (Ahlus-Sunnah) terhadap ayat-ayat tersebut: istilah kafir, zalim, fasik dalam ayat 44-47 al-Mā’idah bukan tiga label yang terpisah untuk tiga golongan berbeda, melainkan tiga sifat yang mungkin terkumpul pada satu perbuatan: meninggalkan hukum Allah dalam putusan hukum adalah suatu kekufuran kecil (bukan kufur akidah), sekaligus kezaliman dan kefasikan[39]. Sifatnya kufur karena mengingkari perbuatan syukur (tidak menjalankan amanah hukum Allah berarti tidak mensyukuri syariat-Nya), sifatnya zalim karena melanggar hak-hak manusia dengan hukum selain Allah, dan sifatnya fasik karena merupakan dosa besar. Jadi bukan berarti ada klasifikasi “yang tidak berhukum dianggap kafir; atau kalau tidak kafir ya minimal zalim atau fasik”. Bukan begitu. Penafsiran yang benar menggabungkan ketiga ayat itu sebagai satu kesatuan sifat.
Ibnu Bayyah tentu menyadari bahwa orang awam sulit memahami nuansa “kufur kecil” vs “kufur besar” ini tanpa bimbingan ulama. Karena itulah, ia berkali-kali mengingatkan bahaya literalisme. “Bahaya takfīr ada pada memutlakkan istilah tanpa ilmu,” ujarnya. Ia mengajak para dai untuk menjelaskan kepada umat bahwa tidak semua ungkapan kufur di nash berarti kafir keluar dari Islam[40]. Banyak hadis menyebut kata “kafir” secara majaz: seperti “mencela orang Muslim itu kefasikan dan membunuhnya itu kekafiran” (HR. Bukhari-Muslim) – jelas maksud “kekafiran” di sini bukan murtad, melainkan dosa besar yang pelakunya terancam siksa. Demikian pula hadis “dua muslim yang berperang, yang membunuh dan terbunuh di neraka”, bukan berarti keduanya kafir, tapi melakukan dosa berat seolah perbuatan orang kafir. Ulama Salaf menakwilkan istilah-istilah demikian agar tidak disalahpahami oleh awam.
Melalui pendekatan maqāṣid, Ibnu Bayyah juga menunjukkan dampak buruk ideologi takfīr: ia memecah belah umat, mencabut nyawa tak berdosa, dan pada akhirnya melemahkan Islam secara keseluruhan[41][42]. Takfīrisme bagai “kanker” dalam tubuh umat[43]. Oleh sebab itu, ia berargumen, mustahil Islam yang rahmatan lil ‘alamin mengajarkan sesuatu yang membuat kehancuran internal seperti itu. Pasti ada yang keliru dalam pemahaman mereka. Dan kekeliruan utamanya adalah: tidak mengikuti metodologi yang benar dalam memahami teks. Mereka memotong ayat dari konteks, mengabaikan syarah para ulama, dan menolak mempertimbangkan maslahat.
Ibnu Bayyah juga mencontohkan koreksi terhadap penyimpangan penerapan dalil takfīr dengan kisah Fatwa Mardin. Ini terkait fatwa klasik Ibn Taymiyyah tentang negeri Mardin (yang dulu dikuasai Mongol non-Muslim tapi penduduknya Muslim). Ibn Taymiyyah mengatakan Mardin bukan dar Islam atau dar kufur sepenuhnya, harus disikapi dua sisi. Nah, teks fatwanya di versi cetak ternyata ada kesalahan cetak yang mengubah kata yu‘āmal (diperlakukan) menjadi yuqātal (diperangi)[44]. Kesalahan ini selama 100 tahun lebih dipakai kelompok radikal sebagai dalih memerangi pemerintah Muslim (karena menyangka Ibn Taymiyyah bilang “yang tidak berhukum syariat harus diperangi”). Ternyata setelah dicek manuskrip asli, tidak ada kata “diperangi” di situ, yang ada “diperlakukan sewajarnya”. Koreksi ini mengoreksi penumpahan darah selama satu abad yang diakibatkan salah baca satu kata[45]. Pelajaran penting: kesalahan kecil dalam memahami teks bisa berbuah kerusakan besar. Maka ketelitian metodologis bukan hal remeh, melainkan penentu keselamatan umat.
Dalam konteks Indonesia atau negara Muslim modern, pandangan Ibnu Bayyah memberi angin segar bagi upaya deradikalisasi. Bahwa menegakkan syariat tidak identik dengan memaksakan formalisasi hukum pidana Islam tanpa melihat situasi. Seorang hakim atau pejabat Muslim yang bekerja dalam sistem hukum modern tidak otomatis kafir, selama dia tidak menolak syariat secara prinsip. Umat juga tidak boleh sembarangan menuduh “pemerintah thaghut” hanya karena hukum positif. Yang perlu didorong adalah gradualisme penerapan nilai-nilai Islam melalui sistem yang ada, sembari berdakwah memperbaiki masyarakat. Itulah pendekatan moderat yang diusung Ibnu Bayyah dan ulama sejalan dengannya (seperti Yusuf al-Qaradawi, Ali Jum’ah, dsb.). Tak heran, Ibnu Bayyah berada di barisan depan dalam mengecam fatwa-fatwa ISIS dan sejenisnya[46]. Ia menulis Respon Ulama terhadap ISIS: Ini bukan jalan menuju surga[47], yang di dalamnya ia paparkan argumen Qur’an, hadis, hingga pendapat salaf bahwa aksi-aksi teror ISIS melanggar syariat. Pandangannya tentang jihad juga diluruskan: jihad bukan sekadar angkat senjata; jihad terbesar adalah mengekang hawa nafsu dan membangun peradaban manusia dalam ketaatan pada Allah[48]. Narasi seperti ini diambil langsung dari sumber klasik, namun disampaikan dengan konteks modern agar kaum muda tak terjerat propaganda simplistis kelompok ekstrem.
Dengan demikian, analisis Ibnu Bayyah terhadap isu takfīr dalam QS al-Mā’idah mencontohkan secara nyata bagaimana fiqh al-wāqi‘ beroperasi: ia memulai dengan rujukan dalil yang kuat (tafsir Ibn ‘Abbās, dsb.), memperhatikan konteks historis ayat, membedakan istilah secara cermat, serta menimbang akibat penerapan hukum (mafsadat takfīr). Hasilnya adalah pemahaman hukum yang adil, tidak ekstrim ke kiri atau kanan: tidak melonggarkan makna ayat hingga menganggap remeh dosa meninggalkan hukum Allah, namun juga tidak menggunakannya secara serampangan untuk mengafirkan pelaku dosa. Inilah sikap tawassuth (moderat) yang menjadi ciri Ahlus-Sunnah wal Jama’ah.
Fiqh al-Wāqi‘ sebagai Dasar Moderasi Islam dan Respons terhadap Tantangan Global
Setelah membahas aspek metodologi dan contoh penerapannya, pada bab terakhir ini kita akan melihat implikasi luas konsep fiqh al-wāqi‘ Ibnu Bayyah bagi kehidupan umat Islam global dewasa ini. Secara garis besar, fiqh al-wāqi‘ merupakan landasan bagi moderasi Islam (wasathiyyah) dan menawarkan kerangka untuk merespons tantangan-tantangan peradaban di era modern, antara lain isu konflik, kemajemukan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan globalisasi.
1. Fiqh al-Wāqi‘ dan Moderasi Islam
Moderasi Islam (al-wasaṭiyyah al-Islāmiyyah) adalah sebuah paradigma beragama yang seimbang: tidak ekstrim ke arah liberal-sekular yang meninggalkan prinsip agama, dan tidak ekstrim ke arah fanatik-radikal yang menolak hal baru dan bersikap keras terhadap perbedaan. Ibnu Bayyah dikenal sebagai tokoh pelopor moderasi dan perdamaian[49][6]. Konsep fiqh al-wāqi‘ yang ia usung sangat erat kaitannya dengan moderasi tersebut. Mengapa? Karena moderasi mensyaratkan pemahaman agama yang kontekstual, toleran, dan bijaksana, yang semuanya merupakan output dari fiqh al-wāqi‘ yang benar.
Pertama, fiqh al-wāqi‘ mencegah sikap kaku-literal dalam beragama. Seorang yang memahami realitas tidak akan memaksakan penafsiran tekstual jika memang kondisi tidak sesuai, melainkan mencari solusi syar‘i yang lebih sesuai konteks. Ini menjauhkan kita dari ekstrimisme literal (tajrīdī) ala kaum fundamentalis. Misalnya, tanpa fiqh al-wāqi‘, seseorang bisa bersikukuh bahwa non-Muslim harus selalu diperlakukan sebagai kafir harbi (musuh) berdasarkan beberapa teks klasik. Namun dengan fiqh realitas, ia sadar bahwa di dunia modern ada konsep nation-state, perjanjian internasional, hak kewarganegaraan, dsb., sehingga hukum hubungan dengan non-Muslim pun disesuaikan menjadi damai selama mereka damai. Ini adalah sikap moderat yang menghargai kemanusiaan, sesuai dengan semangat “lakum dīnukum wa liya dīni” (bagimu agamamu, bagiku agamaku) dan “la ikrāha fi d-dīn” (tak ada paksaan dalam agama).
Kedua, fiqh al-wāqi‘ juga mencegah sikap liberal yang gegabah dalam merombak hukum. Karena metode Ibnu Bayyah tetap berakar pada dalil yang sahih dan maqasid syar‘i, maka adaptasi hukum dilakukan dengan kerangka yang disiplin. Hal ini menjauhkan umat dari ekstrem lain, yaitu mengabaikan syariat dengan alasan konteks. Misalnya, karena paham konteks, bukan berarti kemudian menolak mentah-mentah hukum waris atau hudud sebagai tidak relevan. Fiqh al-wāqi‘ justru mencari bagaimana penerapan hukum-hukum qat‘ī ini bisa dicapai dengan hikmah di era kini tanpa menimbulkan kekacauan. Dalam beberapa hal mungkin berupa penangguhan (tanpa mengingkari status hukumnya), atau substitusi dengan sanksi lain yang mendekati maqasidnya bila benar-benar mustahil diterapkan literal saat ini. Sikap seperti ini berbeda dengan ekstrim liberal yang bisa saja langsung bilang “hukum potong tangan sudah tidak relevan, harus dihapus saja” – pandangan ini keluar dari jalur manhaj, sementara fiqh al-wāqi‘ akan berkata “hukum potong tangan adalah syariat, relevansinya dijaga dengan misalnya menjalankan fungsi pencegahan maksimal (ta’zīr) dan memberi syarat ketat sehingga nyaris tak terjadi kecuali betul-betul dibutuhkan)”. Inilah keseimbangan.
Ibnu Bayyah menyebut moderasi bermazhab dan moderasi berfatwa sebagai hal penting untuk mencegah perpecahan[50]. Ia tidak setuju dengan sikap anti-mazhab yang kerap jadi ciri ekstrim literal; baginya mazhab-mazhab fikih justru khazanah kaya yang bisa digali solusi sesuai konteks. Fiqh al-wāqi‘ memungkinkan kita mengambil rukhṣah dari mazhab lain saat dibutuhkan (dengan tetap ilmiah), sehingga solusi syariat selalu ada tanpa melanggar konsensus. Contohnya, di negeri minoritas Muslim, demi kemaslahatan kadang fatwa menggunakan pendapat minoritas (mazhab lemah) yang lebih ringan, asalkan ada dasarnya. Ini bagian moderasi.
Sebagai pelopor perdamaian, Ibnu Bayyah melalui fiqh al-wāqi‘-nya juga menawarkan paradigma “fiqh al-silm” (fikih perdamaian) sebagai bagian dari moderasi. Ia menyatakan, “tidak ada alasan bagi ulama dan pemimpin untuk tidak berupaya memadamkan api konflik demi menghentikan pertumpahan darah”[6]. Fikih perang dan jihad yang selama ini dominan dalam wacana kelompok keras, ingin ia imbangi dengan fikih perdamaian yang diambil dari nilai-nilai Islam tentang rekonsiliasi (ṣulḥ), memaafkan (afuww), dan hidup berdampingan (ta‘āyush). Semua itu bersumber dari Qur’an-Hadis juga, namun butuh fiqh al-wāqi‘ untuk mengedepankannya sesuai konteks dunia yang “perdamaian adalah norma, peperangan pengecualian”[51][27]. Moderasi menuntut kita mendahulukan aspek kasih sayang ketimbang kekerasan, sebagaimana sabda Nabi “Allah menyayangi orang yang penyayang; berbelas-kasihlah kepada penghuni bumi, niscaya penghuni langit mengasihimu”. Pesan ini sejalan dengan prinsip Ibnu Bayyah tentang Islam sebagai agama kasih sayang[4].
Secara internal, fiqh al-wāqi‘ membantu moderasi dalam fiqh khilafiyah (perbedaan pendapat). Orang yang memahami realitas sosial akan menghindari memperuncing perbedaan furū‘ yang bisa ditoleransi. Ia tahu mana prioritas yang lebih besar bagi umat. Contoh, fanatik mazhab vs persatuan: dengan fiqh kontekstual, kita tahu dalam masyarakat majemuk perlu sikap tasamuh, tidak boleh memaksakan satu pandangan fiqh saja. Itulah moderasi. Sedang yang tidak punya wawasan konteks bisa saja memperdebatkan hal kecil di mimbar sehingga memecah belah jamaah.
Pada akhirnya, fiqh al-wāqi‘ melahirkan etos fleksibilitas dalam beragama tanpa mengorbankan prinsip. Fleksibilitas inilah kunci moderasi. Ibnu Bayyah sering mengutip kaidah “al-dīn yusr” – agama itu mudah, dan “yurīdu Allāh bikumu al-yusr wa lā yurīdu bikumu al-‘usr” – Allah menghendaki kemudahan bukan kesukaran bagi kalian. Dengan memahami konteks, ulama dapat memberi fatwa-fatwa yang memudahkan umat (tentu dalam koridor syariat). Contoh sederhana: fatwa bolehnya menjama’ shalat bagi pekerja tertentu di negara non-Muslim karena kondisi kerja yang tak memungkinkan selalu shalat tepat waktu – ini fiqh realitas yang moderat, menghindarkan orang dari dua ekstrim: meninggalkan shalat vs memaksakan jam kerja hingga dipecat.
Dari uraian di atas, jelas bahwa fiqh al-wāqi‘ adalah salah satu pilar metodologis moderasi Islam. Bahkan bisa dikatakan, tanpa fiqh yang peka realitas, seruan moderasi akan kehilangan pijakan dalil. Ibnu Bayyah telah menunjukkan bahwa moderasi bukan sekedar slogan, tapi buah ijtihad para ulama yang mendalam ilmunya dan luas pandangannya.
2. Menjawab Tantangan Global dengan Fiqh al-Wāqi‘
Umat Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan global: konflik berkepanjangan di beberapa wilayah, terorisme, islamophobia, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kemerosotan moral, hingga isu lingkungan. Pemikiran Ibnu Bayyah menawarkan kerangka fiqh al-wāqi‘ untuk merespons semua itu secara proaktif.
Salah satu contohnya adalah dalam upaya mencegah konflik dan terorisme. Ibnu Bayyah meyakini, solusi kekerasan tidak akan menyelesaikan problem umat, justru memperburuknya[42]. Karena itu, ia menginisiasi dialog damai (seperti Mardin Conference 2010 yang melahirkan Mardin Declaration, dan Forum Perdamaian Abu Dhabi sejak 2014). Fiqh al-wāqi‘ di sini terlihat dari kemampuannya membaca peta dunia yang telah berubah: konsep klasik dār al-ḥarb vs dār al-islām tak bisa lagi diaplikasikan simplistis[26]. Dunia kini diatur oleh sistem negara bangsa dan hukum internasional, di mana perang bukan kondisi default. Maka, seruan jihad bersenjata global dianggapnya tidak relevan kecuali dalam situasi penjajahan nyata. Ia mendorong reinterpretasi doktrin jihad dan hubungan antarnegara sesuai kondisi kini (misalnya menerima konsep negara bangsa dan PBB sebagai wadah ishlah, bukan dianggap thaghut global). Ini membuat fatwa-fatwanya tentang politik internasional lebih realistis dan damai.
Dalam menghadapi islamophobia dan miskomunikasi dengan Barat, Ibnu Bayyah juga memanfaatkan fiqh al-wāqi‘. Ia aktif di forum dunia (misalnya di Forum Ekonomi Dunia, WEF[52]) untuk menjelaskan posisi Islam yang sebenarnya. Dengan wawasan realitas, ia memahami kekhawatiran Barat dan mencoba menjawabnya dengan narasi maqasid (Islam menghargai nyawa, melarang ekstremisme dsb). Ia juga menekankan fiqh al-aqalliyyāt (fikih minoritas) agar Muslim di Barat bisa berintegrasi tanpa kehilangan identitas, misalnya fatwa boleh patuh hukum setempat selama tidak suruh maksiat, dsb. Ini meredakan ketegangan global karena menunjukkan Islam kompatibel dengan modernitas damai.
Isu ekonomi dan keadilan global pun tak luput. Ibnu Bayyah sebagai pakar maqasid turut menyoroti problem riba global, kemiskinan di Afrika, dsb. Fiqh al-wāqi‘ mengajarkan pendekatan solutif: misal advokasi zakat internasional, keadilan perdagangan, hutang negara miskin, dan sebagainya. Ia pernah menyampaikan bahwa “krisis ekonomi dunia perlu solusi etis, dan prinsip Islam tentang keadilan transaksi bisa ditawarkan”. Dalam hal ini, ia mendukung keuangan Islam (Islamic finance) berkembang sebagai alternatif, tapi juga mengingatkan agar industri keuangan Islam tidak kehilangan ruh (harus pro-poor dan sesuai maqasid, bukan hanya ganti nama). Ini menunjukkan tanggung jawab global.
Di bidang hak asasi manusia, fiqh al-wāqi‘ berguna untuk memformulasikan pandangan Islam yang hāriṣ ‘ala al-ḥuqūq (menjaga hak-hak). Misalnya hak minoritas non-Muslim di negara Muslim: dengan fiqh konteks sejarah dan kini, Ibnu Bayyah mendukung konsep kewarganegaraan setara (muwaṭanah) yang mana non-Muslim berhak dilindungi tanpa diskriminasi, selama mereka loyal pada negara. Ini reinterpretasi dari konsep dzimmi klasik. Ulama seperti beliau dan Ali Gomaa di Mesir telah menandatangani Marrakesh Declaration 2016 yang menegaskan perlindungan penuh terhadap minoritas agama di negeri Muslim modern, berdasarkan Piagam Madinah. Langkah ini jelas dibimbing fiqh al-wāqi‘ untuk menjawab isu HAM global sekaligus merujuk preseden syari.
Isu lain, perkembangan teknologi dan sains: Fiqh kontemporer dihadapkan pada hal-hal seperti bioetika (kloning, bayi tabung), kecerdasan buatan, dsb. Prinsip fiqh al-wāqi‘ lagi-lagi krusial: ulama harus memahami sainsnya dahulu (fahm al-waqi’), baru berani berfatwa. Ibnu Bayyah menekankan pentingnya konsultasi dengan pakar di bidang masing-masing (ta‘āwun bayn al-‘ulamā’ wa al-khubarā’). Dalam Majelis Fatwa UEA yang ia pimpin, ia mengikutsertakan ahli sains untuk diskusi misalnya tentang vaksin, pandemi, dll. Hasilnya, fatwa keluar lebih akurat dan bisa diterima masyarakat luas. Ini bentuk responsif terhadap tantangan global kesehatan, lingkungan (seperti fatwa pelestarian lingkungan – UEA Council pernah keluarkan fatwa haramnya perburuan hewan terancam punah, dsb., selaras maqasid hifz al-bi’ah).
Pendek kata, fiqh al-wāqi‘ menjadikan hukum Islam “hadir” dalam percakapan global. Ia tidak eksklusif di menara gading teks, tapi terlibat mencari solusi masalah kemanusiaan. Ibnu Bayyah sering mengutip ayat “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran…” (Ali Imran:110). Ini berarti Islam harus proaktif menawarkan rahmat bagi dunia (rahmatan lil ‘alamin). Dengan metodologi yang tepat, Islam dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Moderasi dan fiqh realitas bukan tanda kelemahan agama, justru cermin keluwesan syariat yang berasal dari Yang Maha Tahu segala zaman.
Melalui gagasan-gagasannya, Syaikh Abdullāh bin Bayyah telah membuktikan bahwa ulama tradisional yang mendalam ilmu kitab kuning sekalipun mampu sangat relevan di abad 21 ketika ia menghidupkan jiwa ushul fiqh dalam memahami dunia modern. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika seorang jurnalis Mesir memuji Ibnu Bayyah sebagai “faqih yang mujaddid (pembaruan) pemikiran Islam menuju jalan tengah”[53]. Sumbangan terbesarnya terletak pada manhaj (metodologi) yang ditawarkan, yang memadukan kesetiaan pada teks suci dan keberanian menghadapi realitas.
Kesimpulan
Kitab Tanbīh al-Marāji‘ ‘alā Ta’ṣīl Fiqh al-Wāqi‘ karya Syaikh Abdullah bin Bayyah menawarkan sebuah manhaj tajdīdī (metodologi pembaruan) dalam ranah fikih dan fatwa kontemporer. Dalam tinjauan di atas, kita melihat bahwa Ibnu Bayyah memulai dengan keprihatinan atas krisis fikih – ditandai oleh pola pikir kaku-literal di satu sisi dan ekstrem-radikal di sisi lain – yang berakar dari kegagalan memahami nash secara holistik dan kontekstual. Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya kembali ke metodologi ushul fikih klasik namun dengan penekanan baru pada fiqh al-wāqi‘, yakni pemahaman mendalam terhadap realitas aktual sebagai bagian integral ijtihad.
Pokok-pokok metodologi Ibnu Bayyah meliputi: (1) memastikan otentisitas dan kejelasan dalil sebelum menjadikannya landasan hukum, (2) berinteraksi dengan nash pada dua level – iman (menerima kebenaran wahyu) dan amal (pelaksanaan praktis yang menuntut pemahaman dan kebijaksanaan), (3) melewati tiga lingkaran ijtihad: tafsir/ta’wil teks, tanzīl dalil ke konteks nyata, dan taf‘īl hukum secara efektif, (4) menerapkan kaidah-kaidah uṣūl seperti harmoni dalil parsial dan prinsip universal, mengutamakan maslahat dan mencegah mudarat, membedakan antara perintah taklifi dan syarat waḍ‘i, mengompromikan dalil yang tampak bertentangan, memahami istilah sesuai konteks syar‘i, serta selalu meninjau latar belakang turunnya nash. Semua itu bermuara pada penafsiran hukum yang tidak tekstualis sempit maupun liberal liar, melainkan moderat, elastis namun tetap berpegang teguh pada maqāṣid al-sharī‘ah.
Aplikasi konkret metodologi tersebut terlihat jelas dalam cara Ibnu Bayyah dan para ulama wasathiyyīn menanggapi isu-isu kontemporer. Studi kasus penafsiran QS al-Mā’idah:44 tentang takfīr menunjukkan bahwa dengan pendekatan kontekstual dan merujuk tafsir salaf (Ibn Abbas), kita dapat mencegah penyalahgunaan ayat untuk mengafirkan sesama Muslim sembarangan. Ibnu Bayyah menegaskan bahwa menuduh Muslim sebagai kafir bukan perkara ringan; dalil-dalil yang ada justru mengajarkan berhati-hati, menakwil kata “kafir” di beberapa nash sebagai “kufur kecil” (dosa besar) alih-alih kafir akbar. Sikap keseimbangan inilah yang menjaga umat dari perpecahan dan pertumpahan darah.
Lebih luas lagi, fiqh al-wāqi‘ menjadi fondasi keilmuan bagi moderasi Islam dan respon umat terhadap tantangan global. Dalam paradigma Ibnu Bayyah, syariat Islam mampu beradaptasi menjawab persoalan zaman – mulai dari konflik dan radikalisme, hubungan antaragama, hingga problem kemanusiaan modern – apabila para ulama mau menggunakan perangkat ushul (qiyas, maqasid, dsb.) dengan memperhatikan perubahan konteks. Hal-hal seperti kesetaraan warga negara, perdamaian internasional, hak asasi, ilmu pengetahuan modern, dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam melalui ijtihad yang berpedoman pada maqasid dan realitas. Pandangan ini memperkuat wajah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, sekaligus menepis propaganda pihak yang menganggap Islam kolot atau Islam bengis.
Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa karya Ibnu Bayyah ini menggemakan kembali pesan esensial dari tradisi hukum Islam: al-fiqh bukan sekadar mengetahui teks, tapi memahami bagaimana teks hidup di tengah manusia. Tanbīh al-Marāji‘ mengingatkan para marāji‘ (ulama panutan) untuk tidak tenggelam dalam pusaran teks hingga lupa konteks, pun tidak terbawa arus perubahan hingga lupa teks. Jalan tengahnya adalah ta’ṣīl fiqh al-wāqi‘ – melembagakan pemahaman realitas ke dalam disiplin fiqh. Dengan itu, diharapkan lahir generasi fuqaha baru yang memiliki basīrah (visi) tajam, fiqh yang luwes namun sahih, sehingga khazanah hukum Islam terus mampu memandu umat di era yang terus berubah tanpa kehilangan arah ilahi. Moderasi, toleransi, dan keadilan yang didamba pun dapat terwujud karena pijakan metodologisnya kokoh. Karya Ibnu Bayyah ini pada akhirnya bukan hanya telaah teks, tapi sebuah manifesto intelektual bagi pembaruan fikih menuju masa depan Islam yang lebih damai, relevan, dan membumi.
Daftar Pustaka
Abdullah bin Bayyah. (2014). Tanbīh al-Marāji‘ ‘alā Ta’ṣīl Fiqh al-Wāqi‘ (Peringatan bagi Rujukan tentang Mengukuhkan Fikih Realitas). Beirut: Markaz Namā’ li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt.
Al-Jifri, Habib Ali. (2014). The ideology of takfir must be confronted. The National (reposted on MuslimVillage.com)[41][51].
Asba’ul Hadeeth. (2013). The Correct Meaning of the Verse “And whoever does not judge by what Allah has revealed… (Al-Ma’idah: 44)”. [Online][28][30].
Bincang Syariah. (2018). Abdullah bin Bayah: Pelopor Moderasi dan Perdamaian[5][11].
Kalam Journal. (2020). Abdullah Haq al-Haidari et al., Radicalism and Religious Texts Understanding, Kalam Vol. 14 No.2[22][24].
Muslim 500. (2023). Shaykh Abdallah bin Bayyah – Bio. [Online][52].
Catatan: Seluruh terjemahan kutipan kitab Tanbīh al-Marāji‘ dalam teks di atas dibuat oleh penulis berdasarkan edisi bahasa Arab dan telah disesuaikan dengan konteks penulisan. Kutipan lainnya disertai rujukan sesuai format APA dan URL sumber jika daring.
[1] [2] [4] [5] [6] [11] [12] [34] [46] [47] [48] [49] Abdullah bin Bayah: Pelopor Moderasi dan Perdamaian | Bincang Syariah
https://bincangsyariah.com/khazanah/abdullah-bin-bayah-pelopor-moderasi-dan-perdamaian/
[3] Abdullah bin Bayyah – The Muslim 500
https://themuslim500.com/profiles/abdullah-bin-bayyah/
[7] Abdullah Bin Bayyah – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas
https://ms.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Bin_Bayyah
[8] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [31] [32] [33] ejournal.radenintan.ac.id
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/7454/4773
[9] [10] [26] [27] [35] [36] [41] [42] [43] [44] [45] [51] The ideology of takfir must be confronted
https://muslimvillage.com/2014/02/28/50648/ideology-takfir-must-confronted/
[13] فتنة التكفير حرب على الامة | معالي العلامة عبدالله بن بيه
https://binbayyah.net/arabic/archives/5003
[14] التكفير.. لماذا وكيف الخلاص؟! (1-2) | معالي العلامة عبدالله بن بيه
https://binbayyah.net/arabic/archives/272
[15] [18] قضيّة “الحاكميّة وتكفير المسلمين”.. تفكيك للجذر الذي انطلق من …
[16] التّكفيرُ وضوابِطُه | المجلس الإسلامي السوري
[17] [19] فتنة التكفير ملحوظا فيها مسلمات العقد الأشعري
[28] [29] [30] [37] [38] [39] THE CORRECT MEANING OF THE VERSE “..And whoever does not judge by what Allaah has revealed such are the disbelievers.” [Al-Maa’idah 44] | AsbaulHadeeth.com
[40] الإعلام بخطورة تكفير أئمة الإسلام .. (قواعد وأصول مهمة) (الجزء الأول)
[50] [PDF] Jurnal Hukum Islam – E-journal UIN Gusdur
https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/download/jhi_v23i1_5/jhi_v23i1_5/25755
[52] H.E. Abdallah bin Bayyah – The World Economic Forum
https://www.weforum.org/people/abdallah-bayyah/
[53] Egyptian Journalist Praises Moderate Cleric ‘Abdallah Bin Bayyah …

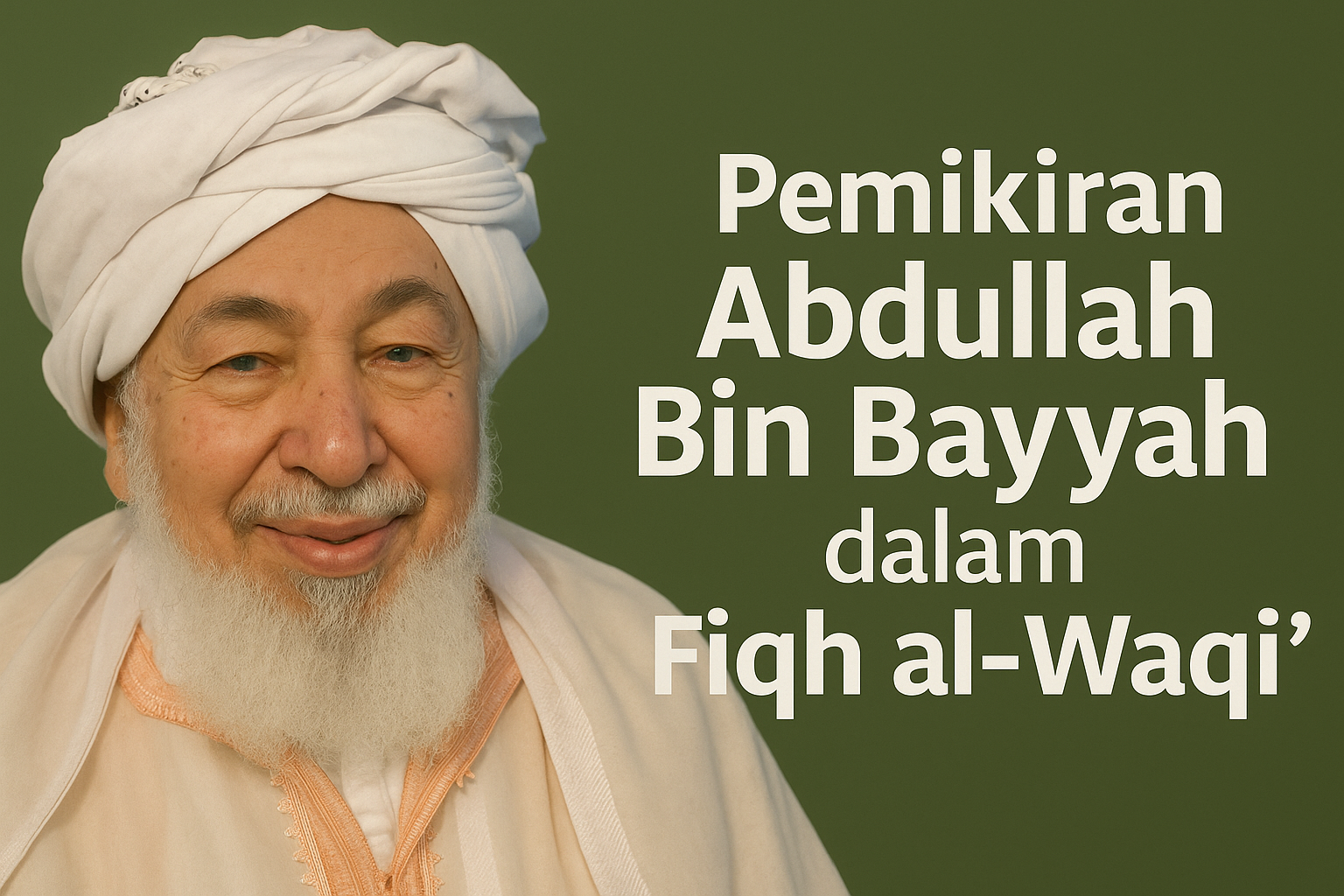
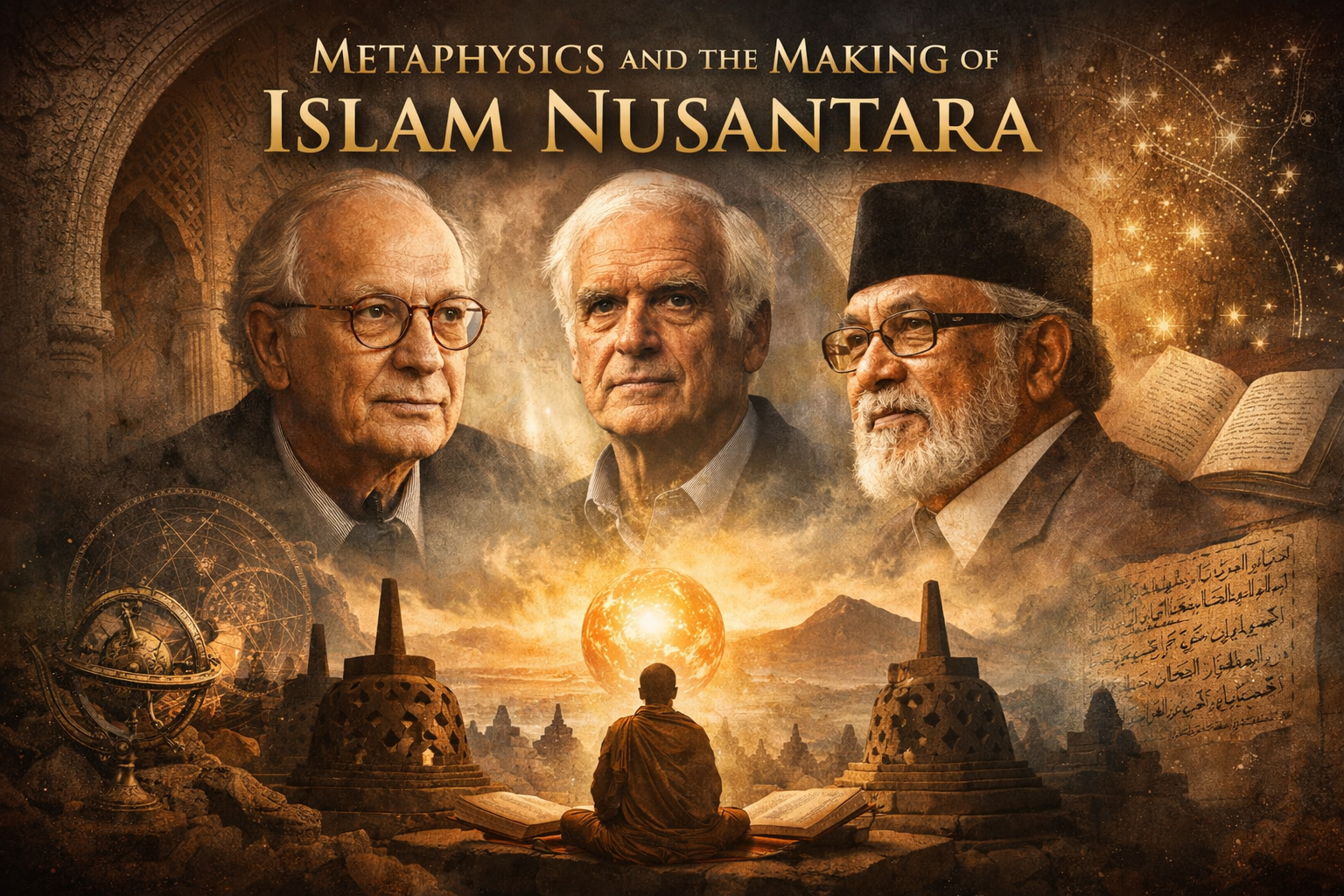
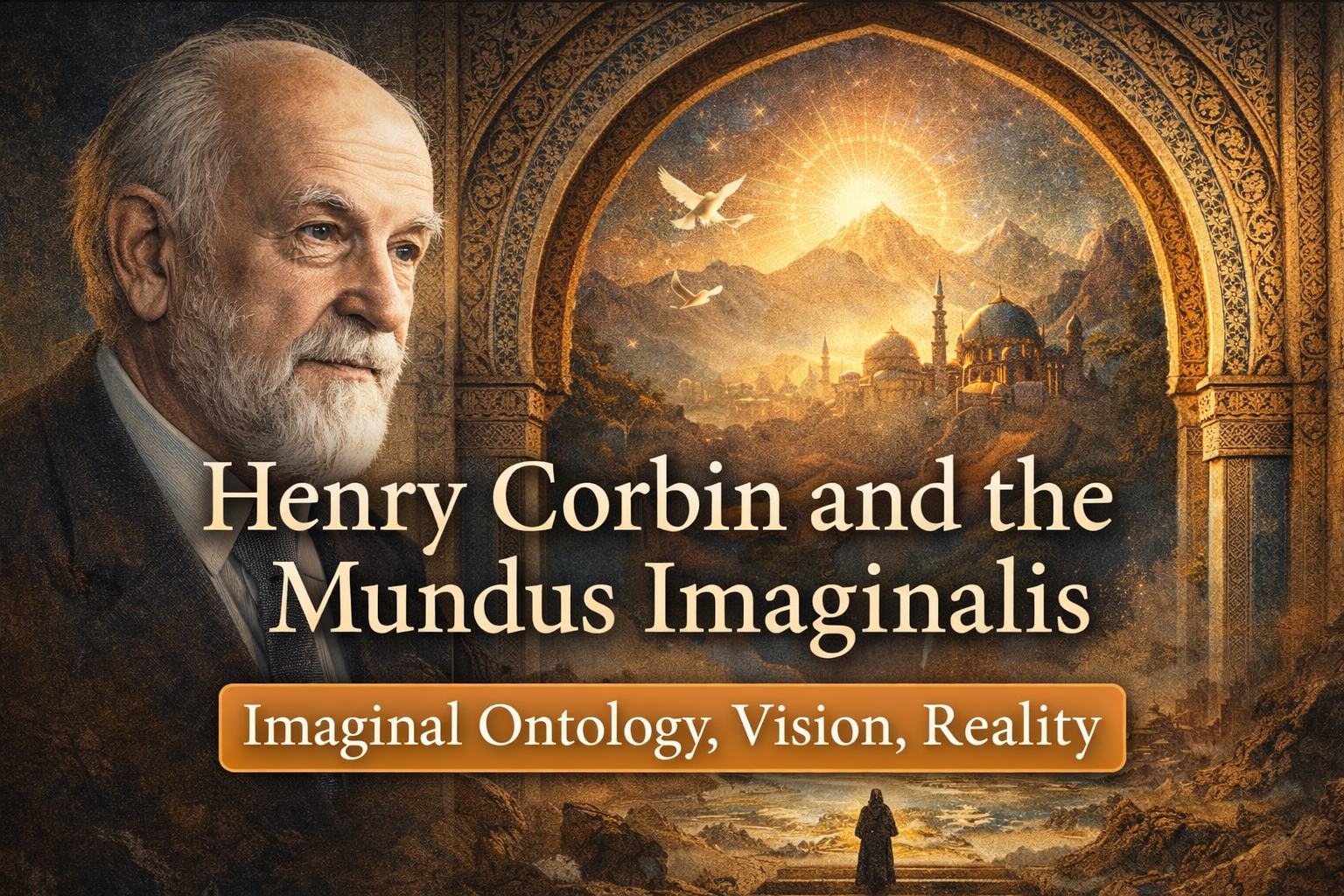



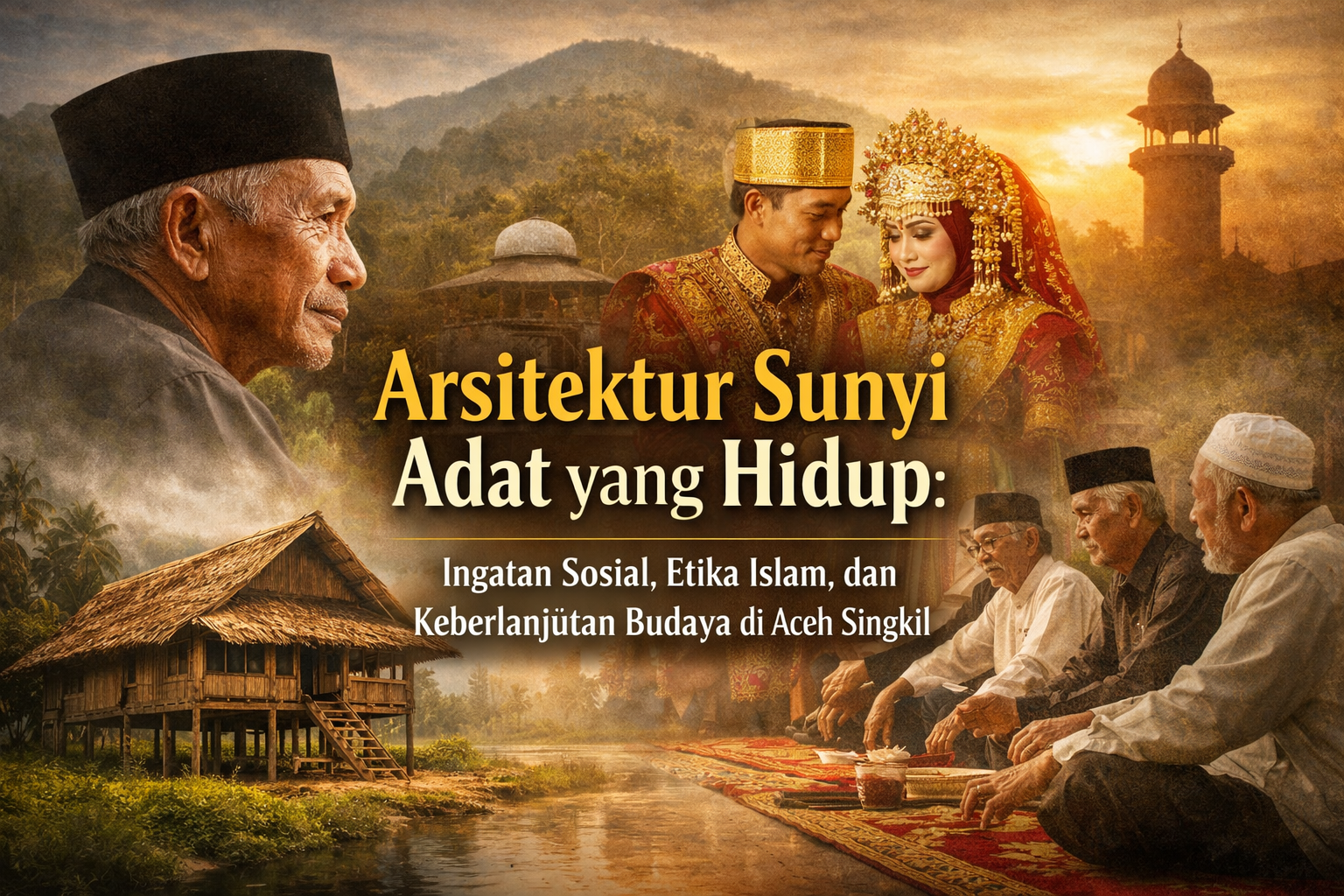
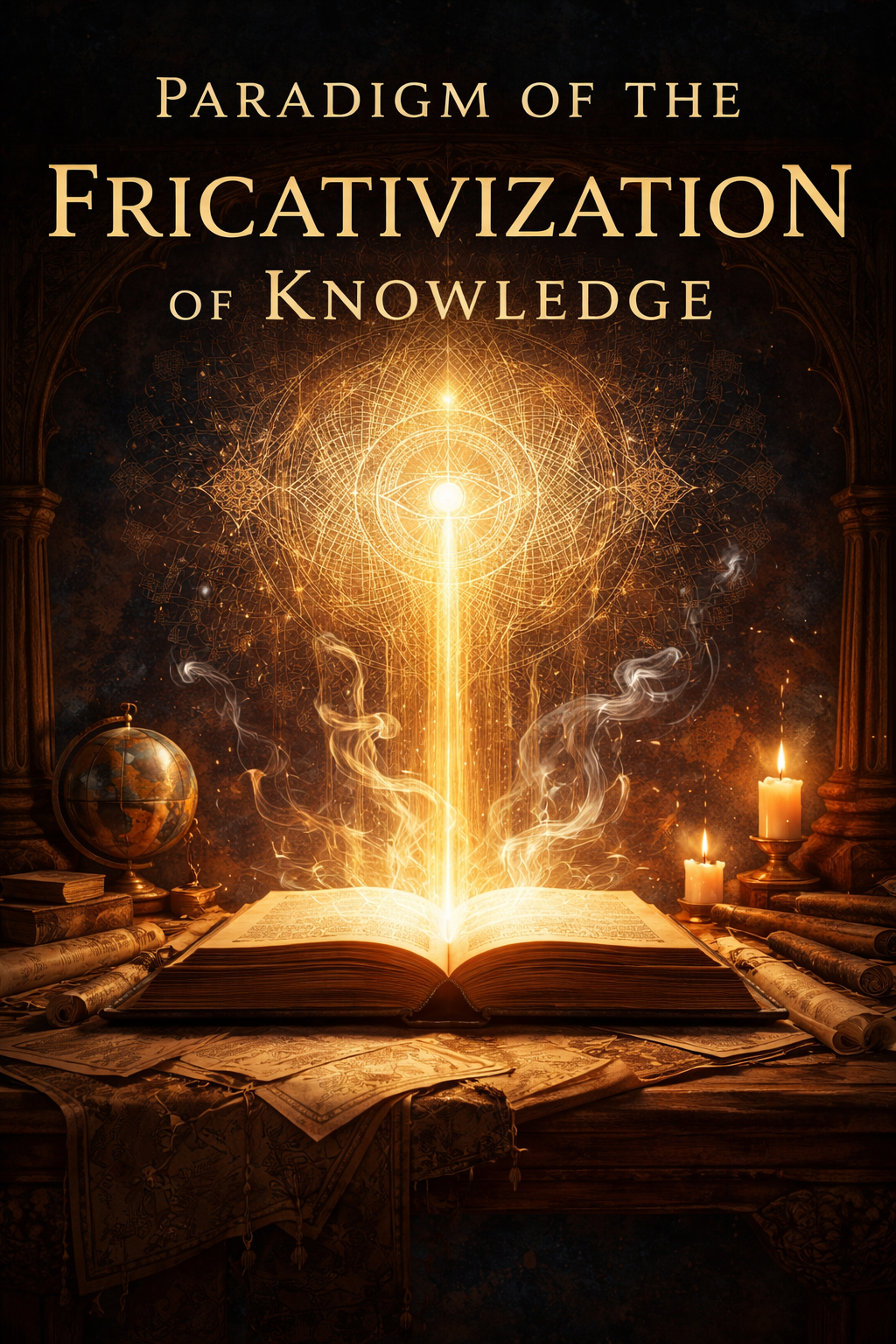
Leave a Reply