Your cart is currently empty!
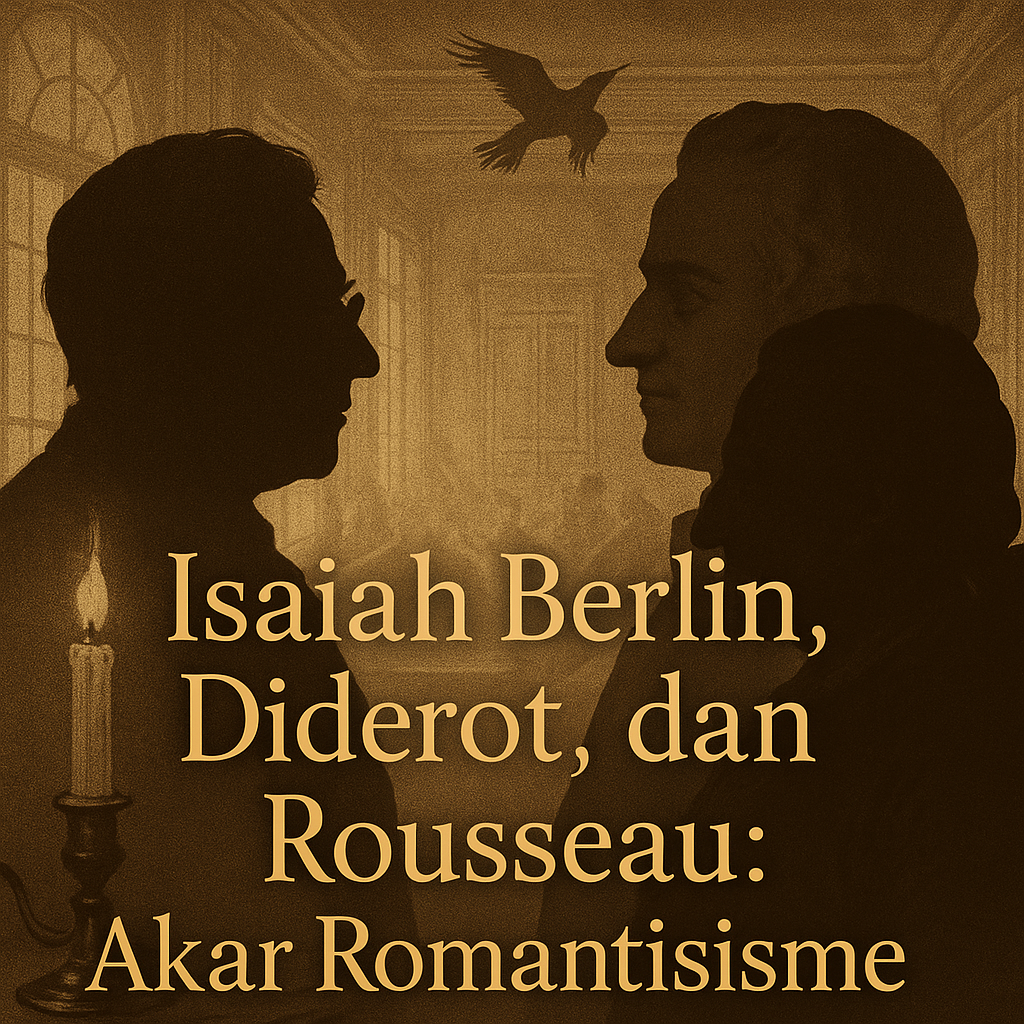
Isaiah Berlin, Diderot, dan Rousseau: Akar Romantisisme dari Pencerahan ke Revolusi Emosional
Pendahuluan: Berlin Membaca Akar Romantisisme
Dalam kuliah terkenalnya yang kemudian dibukukan dengan judul The Roots of Romanticism, Isaiah Berlin menelusuri salah satu pergeseran intelektual paling besar dalam sejarah Barat. Romantisisme, menurut Berlin, bukan sekadar gerakan seni, melainkan sebuah revolusi dalam cara manusia memahami diri dan dunia. Romantisisme merombak tatanan rasionalisme Pencerahan yang selama berabad-abad dianggap sebagai dasar peradaban modern.
Dalam esai ini, kita akan memusatkan perhatian pada dua figur kunci yang Berlin soroti: Denis Diderot dan Jean-Jacques Rousseau. Diderot, yang dikenal sebagai salah satu Encyclopédistes, ternyata membuka jalan menuju Romantisisme melalui gagasan tentang kejeniusan, irasionalitas, dan seni sebagai keberanian yang melampaui aturan. Rousseau, sebaliknya, muncul sebagai nabi apokaliptik yang menolak reformasi bertahap dan menyerukan kehancuran total terhadap masyarakat modern demi kembali pada kesederhanaan hati nurani.
Berlin membaca keduanya bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai tanda pergeseran sensibilitas yang melahirkan Romantisisme. Dari pengakuan Diderot atas kekuatan gelap manusia hingga seruan Rousseau untuk membakar habis masyarakat, kita melihat transformasi radikal dari rasionalisme menuju subjektivitas emosional.
Diderot dan Dimensi Gelap Kejeniusan
Diderot sebagaimana dikutip Berlin menyadari betul adanya kekuatan irasional dalam diri manusia. Ia menyatakan bahwa “there are unconscious depths in which all kinds of dark forces move, and he is aware that human genius feeds upon these” (hlm. 51). Pandangan ini menegaskan bahwa seni besar tidak dapat lahir hanya dari rasionalitas dan cahaya akal budi, melainkan membutuhkan kedalaman jiwa yang gelap, insting bawah sadar, dan dorongan yang tak dapat sepenuhnya dijelaskan. Konteks ini penting karena memperlihatkan bahwa bahkan di dalam lingkaran Pencerahan, ada pengakuan bahwa manusia tidak sepenuhnya bisa direduksi menjadi makhluk rasional.
Lebih jauh, Diderot menegaskan bahwa seni sejati membutuhkan keberanian, gairah, dan kemampuan untuk melampaui batas aturan. Ia berbicara tentang “the great genius, the great artist, something, a je ne sais quoi… which enables the artist to create these works of art in his imagination with a degree of sweep” (hlm. 51). Di sini, seni tidak lagi dipahami sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai hasil dorongan misterius yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Konsep je ne sais quoi menunjukkan bahwa dalam penciptaan seni, ada sesuatu yang tak terdefinisikan, yang menjadi ciri khas genius.
Isaiah Berlin membaca Diderot sebagai salah satu yang berani mengaitkan seniman jenius dengan para penjahat besar. Ia menulis tentang “the nearness to criminals of artists, because they both defy rules, they are both persons who are in love with power, magnificence and splendour, and kick over the traces of normal life” (hlm. 51). Perbandingan ini radikal karena menempatkan seniman dalam posisi subversif, tidak tunduk pada aturan masyarakat jinak, bahkan bisa dianggap berbahaya. Dengan demikian, genius dan kriminal berbagi sifat: keduanya melawan keteraturan dan menantang normalitas.
Dalam kerangka ini, Diderot juga membedakan antara manusia artifisial dan manusia yang penuh gairah. Ia menyebut “the artificial man, who belongs in society and conforms to the practices of society and seeks to please” sebagai figur karikatural abad ke-18 (hlm. 51). Sebaliknya, manusia yang sejati adalah mereka yang membawa insting gelap, liar, dan penuh risiko, yang jika dikendalikan dengan tepat dapat melahirkan karya besar. Konsep ini jelas membuka jalan bagi Romantisisme, yang menolak konformitas sosial demi keaslian batin.
Berlin membaca pandangan ini sebagai kritik terhadap rasionalisme mapan, khususnya aturan yang diletakkan oleh para teoritisi seni seperti abbé Batteux dan abbé Dubos. Diderot menegaskan bahwa “Genius of this type cannot be tamed, genius of this type has nothing to do with those rules” (hlm. 51). Seni agung justru lahir dari mereka yang berani menolak aturan, bukan dari mereka yang tunduk pada konvensi. Romantisisme kemudian akan mengangkat semangat ini sebagai prinsip utama: seni sejati lahir dari kebebasan, bukan dari keterikatan.
Dengan demikian, kita melihat bahwa dalam teks ini, Diderot bukan sekadar bagian dari tradisi Pencerahan yang rasional, melainkan juga seorang transisi yang membuka jalan ke arah Romantisisme. Ia memandang kejeniusan sebagai sesuatu yang liar, tak terduga, bahkan berbahaya. Dalam perspektif Berlin, inilah benih awal gagasan romantik tentang seniman sebagai figur yang melampaui batas moral konvensional.
Dari pembacaan ini, dapat disimpulkan bahwa Diderot meletakkan fondasi estetika baru: seni sebagai ekspresi dari kekuatan gelap manusia. Perspektif ini menggeser seni dari ranah keteraturan menuju ranah pemberontakan, dari rasionalitas menuju irasionalitas, dari kepatuhan menuju kebebasan.
Paean kepada Genius: Antara Kejernihan dan Kegilaan
Dalam teks Salon of 1765, Diderot menulis: “Beware of those whose pockets are full of esprit—of wit… They have no demon within them, they are not gloomy, or sombre, or melancholy, or silent” (hlm. 52). Di sini Diderot mengkritik seniman yang hanya mengandalkan kecerdikan dangkal tanpa kedalaman jiwa. Baginya, seniman sejati adalah mereka yang memiliki “demon within,” kekuatan batin yang gelap dan liar. Ini kembali menekankan perbedaan antara talenta biasa dengan genius sejati.
Diderot kemudian melukiskan sosok genius melalui metafora burung liar: “the lark, the chaffinch, the linnet, the canary… they chirp and twitter all the livelong day… and lo! at sunset they fold their head under their wing, and fall asleep. It is then that genius takes his lamp and lights it” (hlm. 52). Kutipan ini menggambarkan bahwa genius bukanlah sosok yang hidup di permukaan kehidupan sehari-hari, tetapi justru hadir di saat kegelapan, ketika dunia lain tertidur. Genius adalah figur malam, yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan.
Berlin membaca gambaran ini sebagai kontras antara talenta dan genius. Talenta adalah kemampuan teknis, sementara genius adalah kekuatan liar yang tak terkendali. Genius, tulis Diderot, adalah “this dark, solitary, savage bird, this untamable creature, with its gloomy melancholy plumage” (hlm. 52). Dengan kata lain, genius adalah makhluk asing dalam dunia yang tertata rapi, sebuah anomali yang sekaligus menjadi sumber karya agung.
Pandangan ini mencerminkan pergeseran dari estetika klasik yang menekankan keteraturan menuju estetika romantik yang menekankan keaslian dan kedalaman batin. Genius dipandang bukan sebagai hasil disiplin rasional, tetapi sebagai kekuatan alamiah yang tak dapat dijinakkan. Romantisisme kemudian mengadopsi gagasan ini dengan menempatkan seniman dalam posisi profetik: pembawa suara batin manusia yang paling dalam.
Dalam konteks Paris abad ke-18, pandangan Diderot adalah bentuk resistensi terhadap semangat rasionalitas yang mendominasi. Ia menyatakan bahwa “this is a paean to genius, in contrast with talent, in contrast with rules, in contrast with the vaunted so-called virtues of the eighteenth century” (hlm. 52). Dengan demikian, Diderot sebenarnya telah menantang fondasi estetika rasional yang saat itu diagungkan.
Berlin menekankan bahwa pernyataan ini membuka pintu bagi sensibilitas baru yang akan menjadi dasar Romantisisme. Genius adalah bentuk transendensi terhadap rasionalitas, sebuah lompatan ke dunia yang tidak dapat diatur oleh logika. Pandangan ini radikal karena menegaskan bahwa seni agung justru lahir dari ketidakteraturan, dari kegilaan yang produktif.
Dengan demikian, bagian ini memperlihatkan bagaimana Diderot mengangkat genius sebagai figur sentral dalam seni. Genius adalah makhluk malam yang membawa cahaya, liar, tak terkendali, dan penuh risiko. Pandangan ini secara langsung melawan etos keteraturan dan membuka jalan bagi pengagungan subjektivitas yang menjadi inti Romantisisme.
Rousseau dan Kritik terhadap Masyarakat Korup
Rousseau dalam teks ini diposisikan oleh Isaiah Berlin sebagai tokoh yang melampaui para Encyclopédistes. Berlin menulis: “It would be foolish to deny that Rousseau’s doctrine, Rousseau’s words, were among the factors which influenced the romantic movement” (hlm. 52). Artinya, Rousseau memang memainkan peran penting dalam membentuk sensibilitas romantik. Namun, Berlin juga memperingatkan bahwa perannya sering dilebih-lebihkan. Fokus utamanya bukan pada doktrin filosofis rasional, melainkan pada nada emosional dan moral yang terkandung dalam karyanya.
Rousseau menganggap masyarakat sebagai sumber kerusakan moral manusia. Ia menegaskan bahwa “We live in a corrupt society; we live in a bad, hypocritical society, where men lie to each other and murder each other and are false to each other” (hlm. 52). Bagi Rousseau, kebusukan masyarakat modern tidak bisa disembunyikan di balik retorika rasional atau hukum-hukum yang dibuat oleh kaum cendekiawan. Pernyataannya adalah sebuah dakwaan keras terhadap realitas sosial yang ia hadapi, khususnya Prancis abad ke-18.
Berlin menekankan bahwa Rousseau tidak sekadar mengkritik masyarakat dari luar, melainkan menyerang akar terdalam dari peradaban. Ia menyatakan bahwa “It is possible to discover the truth… by looking within the heart of the simple uncorrupt human being” (hlm. 52). Di sini Rousseau menolak epistemologi Cartesian yang berbasis rasionalitas formal, dan menggantinya dengan epistemologi hati nurani. Bagi Rousseau, kebenaran sejati tidak ditemukan melalui metode logika atau argumentasi intelektual, melainkan melalui kesederhanaan jiwa manusia yang murni.
Dalam konteks ini, Rousseau menawarkan paradigma baru: kembali kepada yang alami, kepada manusia yang tidak tercemar oleh kepalsuan masyarakat. Berlin menekankan bahwa ini adalah pergeseran radikal, karena bagi para philosophes, kebenaran dicapai melalui nalar kolektif, sementara bagi Rousseau, kebenaran dicapai melalui kesunyian batin yang murni. Romantisisme kemudian mengadopsi perspektif ini dengan menempatkan pengalaman subjektif sebagai sumber otoritas moral yang sah.
Rousseau juga menolak kemegahan rasionalisme Prancis. Berlin menyebut bahwa Rousseau melihat dirinya sebagai “a kind of dervish from the desert” (hlm. 53). Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rousseau memosisikan dirinya di luar arus utama kebudayaan Pencerahan, memilih untuk menjadi sosok asing, mistis, dan liar, ketimbang seorang rasionalis yang tertib. Posisi ini membuatnya dekat dengan sensibilitas Romantisisme yang mengagungkan keanehan, keterasingan, dan ketidakteraturan sebagai sumber kebenaran baru.
Namun, yang paling penting dari Rousseau adalah seruannya untuk meruntuhkan struktur sosial yang busuk. Berlin menulis bahwa “Rousseau believed that the whole cursed superstructure must be razed to the ground, that the entire wicked human society must be burnt to ashes” (hlm. 54). Ini adalah seruan apokaliptik yang melebihi para Encyclopédistes, yang masih berharap pada reformasi bertahap. Rousseau menghendaki kehancuran total agar dari abu lahirlah masyarakat baru yang murni.
Dari bagian ini, kita melihat bagaimana Rousseau membangun kritik sosial yang penuh api dan gairah moral. Ia bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang nabi peringatan, yang menyatakan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dengan menghancurkan kepalsuan yang ada. Dengan cara ini, Rousseau memberikan energi destruktif sekaligus kreatif bagi Romantisisme, yang selalu mencurigai keteraturan dan mencari kebenaran dalam kekacauan.
Rousseau, Emosi, dan Nada Romantik
Rousseau bukan hanya mengajukan argumen rasional, melainkan mengekspresikan emosi yang kuat. Berlin menulis: “When Rousseau begins describing his own particular states of mind and states of soul, when he begins describing the emotions which tear him apart, the violent paroxysms of rage or joy through which he goes, then he does use a tone which is very different” (hlm. 53). Gaya ini membuatnya berbeda dari para rasionalis abad ke-18. Rousseau menulis dengan darah, air mata, dan amarah.
Inilah yang membuat Rousseau lebih dekat dengan Romantisisme daripada Pencerahan. Bagi para Encyclopédistes, filsafat adalah tentang pengetahuan objektif. Tetapi bagi Rousseau, filsafat adalah cermin jiwa. Berlin menekankan bahwa “This is not the doctrine of Rousseau which was inherited by the Jacobins, or which in various forms entered into the doctrines of the nineteenth century” (hlm. 53). Dengan kata lain, yang diwarisi dari Rousseau oleh Romantisisme bukanlah doktrinnya, tetapi gaya emosional dan nada tulisannya.
Berlin memberikan contoh kutipan Rousseau yang terkenal: “I did not reason, I did not philosophise… I suffocated in the universe, I wanted to leap into the infinite… my spirit gave itself to swelling ecstasy” (hlm. 53). Kalimat ini memperlihatkan intensitas emosional yang tidak biasa bagi seorang filsuf abad ke-18. Kata-katanya meledak dengan ekstasi, keputusasaan, dan gairah—nada yang nantinya akan menjadi ciri khas Romantisisme.
Rousseau di sini melampaui batas wacana filosofis formal. Ia memperlihatkan bahwa menulis bukan hanya menyampaikan argumen, tetapi juga menyalurkan pengalaman personal yang intens. Dari sudut pandang Berlin, inilah yang membuat Rousseau begitu berpengaruh: ia menunjukkan bahwa filsafat bisa menjadi wahana pengungkapan diri yang penuh emosi, bukan hanya sarana argumentasi logis.
Berlin menekankan bahwa “Rousseau’s point was that nobody could love as Rousseau loved, nobody could hate as Rousseau hated, nobody could suffer as Rousseau suffered” (hlm. 53). Pernyataan ini menempatkan Rousseau sebagai figur unik, yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, pengalaman personal menjadi otoritas tunggal, tidak bisa digeneralisasi. Inilah salah satu inti Romantisisme: penekanan pada keunikan subjektif yang tak dapat diukur dengan standar universal.
Gaya ini memperlihatkan bahwa Romantisisme lahir bukan hanya dari teori filosofis, tetapi dari ekspresi emosional yang mengguncang. Rousseau menjadi teladan awal bahwa filsuf bisa menjadi penyair, bahwa teori bisa diungkapkan dengan bahasa air mata dan ekstasi. Dari sinilah romantisisme menarik inspirasi untuk menolak keteraturan klasik dan merayakan ledakan emosi manusia.
Dengan demikian, Rousseau memberi Romantisisme dimensi emosional dan personal yang tak dimiliki para pendahulunya. Ia mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang universal dan objektif, tetapi sesuatu yang unik, intens, dan hanya dapat dipahami dari dalam diri seseorang.
Rousseau sebagai Nabi Apokaliptik dan Perbedaan Metode dengan Kaum Pencerahan
Isaiah Berlin menegaskan bahwa Rousseau memandang masyarakat modern sebagai struktur yang harus dihancurkan total, bukan direformasi secara bertahap. Ia menulis: “Rousseau believed that the whole cursed superstructure must be razed to the ground, that the entire wicked human society must be burnt to ashes; then a new phoenix would arise, constructed by himself and by his disciples” (hlm. 54). Pernyataan ini menempatkan Rousseau dalam posisi apokaliptik. Ia bukan sekadar kritikus sosial, melainkan nabi penghancuran, yang menyerukan kehancuran total agar lahir masyarakat baru.
Berbeda dengan para Encyclopédistes yang percaya pada reformasi bertahap, Rousseau menolak ide perubahan perlahan. Berlin menulis: “The only difference was that the other Encyclopaedists in Paris believed this could be achieved by reform, gradually, by somehow converting the rulers to their point of view, by getting hold of an enlightened despot” (hlm. 54). Artinya, kaum Pencerahan masih memiliki keyakinan bahwa sistem lama bisa diperbaiki dengan pendidikan, persuasi, dan penggunaan akal sehat. Rousseau justru berpendapat bahwa akar dari masyarakat sudah busuk, sehingga tidak ada jalan selain membakarnya habis-habisan.
Pandangan Rousseau ini radikal karena menolak kompromi. Jika para rasionalis percaya pada kemajuan linear, Rousseau percaya pada lompatan revolusioner. Ia meyakini bahwa manusia hanya bisa kembali pada kebaikan sejati setelah semua kepalsuan hancur. Dalam hal ini, Rousseau memberikan justifikasi moral bagi semangat destruktif yang kelak mewarnai Romantisisme politik, dari Revolusi Prancis hingga gerakan-gerakan revolusioner abad ke-19.
Berlin menegaskan bahwa meskipun tujuan Rousseau dan para Encyclopédistes sama, yakni membangun masyarakat yang lebih baik, cara yang ditempuh sangat berbeda. Ia menulis: “But in principle what Rousseau and the other Encyclopaedists wished to do was the same, although perhaps their view of the appropriate methods may have differed” (hlm. 54). Perbedaan metode inilah yang membuat Rousseau menjadi figur kontroversial: tujuannya sejalan dengan Pencerahan, tetapi sarana yang diusulkannya jauh lebih ekstrem.
Rousseau dalam hal ini menyerupai figur profetik yang menghendaki lahirnya dunia baru dari abu kehancuran lama. Ia memandang bahwa masyarakat lama tidak hanya gagal, tetapi juga penuh dosa. Kehancurannya adalah syarat mutlak untuk lahirnya dunia baru. Konsep ini sangat dekat dengan sensibilitas religius, di mana sejarah dipandang sebagai drama moral yang berakhir dengan kehancuran dunia lama dan kelahiran dunia baru. Tidak heran jika Berlin melihat Rousseau sebagai sumber penting bagi nada apokaliptik Romantisisme.
Pandangan ini memperlihatkan bagaimana Rousseau menghubungkan moralitas dengan sejarah. Bagi para rasionalis, sejarah adalah kemajuan ilmu dan institusi. Bagi Rousseau, sejarah adalah kisah kejatuhan manusia dari keadaan alami menuju korupsi sosial. Oleh karena itu, jalan keluar tidak bisa dicapai dengan menambahkan sedikit perbaikan pada institusi, melainkan dengan kehancuran total. Hal ini menjelaskan mengapa Rousseau menjadi figur inspiratif bagi generasi revolusioner.
Dengan demikian, Berlin menempatkan Rousseau sebagai figur yang unik: seorang pemikir yang berbagi tujuan dengan Pencerahan, tetapi menggunakan metode yang sangat berbeda. Ia adalah jembatan menuju Romantisisme karena menggabungkan kritik moral yang keras dengan seruan apokaliptik untuk menghancurkan masyarakat lama. Dari titik ini, Romantisisme memperoleh energinya sebagai gerakan yang tidak hanya estetis, tetapi juga historis dan politis: sebuah hasrat untuk membangun dunia baru dengan cara meruntuhkan dunia lama.
Keunikan Rousseau dan Kontras dengan Rasionalisme Paris
Isaiah Berlin menggambarkan Rousseau sebagai figur yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Ia menulis: “He was unique. Nobody else could understand him, and only genius could understand another genius” (hlm. 54). Pernyataan ini menegaskan keyakinan Rousseau bahwa penderitaannya, cintanya, kebenciannya, dan ekstasinya tidak bisa diukur dengan standar umum. Ia merasa dirinya berbeda, dan hanya genius lain yang bisa memahami kedalaman pengalaman pribadinya. Inilah inti dari keunikan Rousseau: klaim subjektivitas absolut.
Pandangan ini berlawanan dengan semangat rasionalisme Paris abad ke-18, yang percaya pada keteraturan universal. Berlin menekankan bahwa Rousseau berhadapan dengan “reasonable men who did not becloud their understandings with unnecessary emotions and unnecessary ignorance” (hlm. 54–55). Artinya, kaum Encyclopédistes berusaha menyingkirkan emosi agar pikiran tetap jernih. Sebaliknya, Rousseau justru mengagungkan emosi sebagai jalan menuju kebenaran. Baginya, tanpa air mata, ekstasi, dan penderitaan, kebenaran tidak mungkin ditemukan.
Rousseau dengan sengaja mengontraskan dirinya dengan “logika dingin” para rasionalis. Berlin menulis: “What Rousseau does is to contrast with the so-called cold logic which he constantly complains about, with cold reason, the hot tears of shame, of joy or misery, or love, or despair” (hlm. 55). Dengan demikian, Rousseau menolak rasionalitas yang steril, dan memilih jalan emosional yang penuh gairah. Bagi Romantisisme, inilah warisan terbesarnya: legitimasi emosi sebagai sarana epistemologis yang sah.
Berlin juga mencatat bahwa karena sikap ini, Rousseau sering dicap sebagai seorang sofis. Namun, Hamann—yang kemudian disebut sebagai “the true father of Romanticism”—justru menyebut Rousseau sebagai sofis yang terbaik. Berlin menulis: “Hamann called him the best of the sophists— but still a sophist. Hamann was Socrates and Rousseau was a sophist; he was the best because he gave signs of understanding that all was not quite right with this elegant, rational, sane Paris” (hlm. 55). Dengan kata lain, meski dicap sofis, Rousseau dianggap penting karena ia mampu melihat keretakan dalam dunia yang tampak rasional dan mapan.
Rousseau menolak kemapanan Paris yang ia pandang penuh kepalsuan. Berlin menuliskan bahwa ia ingin “scrape off all the falsehood which had managed to accumulate upon them through the centuries” (hlm. 55). Ia percaya bahwa di balik lapisan kepalsuan itu masih ada “good human life, good men” yang bisa ditemukan. Namun untuk sampai ke sana, kebusukan lama harus dibersihkan habis. Pandangan ini memperlihatkan Rousseau sebagai seorang radikal moral yang tak puas dengan reformasi permukaan, melainkan menghendaki pembersihan total.
Kaum Encyclopédistes percaya bahwa reformasi dapat dicapai melalui pendidikan, despotisme tercerahkan, atau persuasi rasional. Rousseau menolak semua itu. Baginya, satu-satunya jalan adalah kehancuran total: “if only men could remove the bad society which had corrupted them, then they could live forever, in accordance with timeless precepts” (hlm. 55). Dengan kata lain, Rousseau mengusulkan revolusi moral yang radikal, sebuah ide yang jauh melampaui Pencerahan.
Melalui pembacaan Berlin, Rousseau tampak sebagai figur paradoks: ia berbagi tujuan dengan Pencerahan, tetapi metode dan nadanya membuatnya lebih dekat dengan Romantisisme. Ia tidak puas dengan akal budi yang dingin, melainkan menuntut air mata, ekstasi, dan kehancuran. Ia bukan sekadar seorang filsuf, melainkan seorang nabi apokaliptik yang menyerukan lahirnya dunia baru dari puing-puing dunia lama. Inilah keunikan Rousseau yang menempatkannya sebagai jembatan penting dari Pencerahan menuju Romantisisme.
Kesimpulan: Dari Diderot ke Rousseau – Jalan Menuju Romantisisme
Pertama, Diderot membuka pintu bagi sebuah pandangan baru tentang seni dan kejeniusan. Ia menolak anggapan bahwa karya besar lahir dari keteraturan dan aturan-aturan teknis. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa seni sejati bersumber dari kedalaman jiwa manusia, dari “demon within,” dari kekuatan gelap yang tidak dapat dijinakkan. Dalam membaca Diderot, Isaiah Berlin menunjukkan bahwa Romantisisme tidak lahir dari nol, tetapi berakar dalam ketidakpuasan yang muncul di dalam jantung Pencerahan sendiri.
Kedua, melalui perbedaan antara talenta dan genius, Diderot menekankan bahwa seniman agung sejajar dengan figur subversif, bahkan kriminal, karena keduanya sama-sama melanggar aturan. Genius adalah sosok yang tidak tunduk pada keteraturan sosial, melainkan makhluk liar yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Dengan ini, Diderot menyemai benih gagasan romantik tentang seniman sebagai pemberontak eksistensial. Pandangan ini menggeser seni dari keterampilan rasional menuju ekspresi subjektif yang penuh risiko.
Ketiga, Rousseau menambahkan dimensi moral dan sosial yang jauh lebih radikal. Ia melihat masyarakat modern sebagai korup dan penuh kepalsuan. Baginya, kebenaran tidak dapat ditemukan dalam sistem rasional yang rumit, melainkan dalam kesederhanaan hati nurani manusia yang murni. Seruannya agar seluruh “superstruktur terkutuk” dihancurkan menegaskan posisinya sebagai nabi apokaliptik, bukan reformis moderat. Berlin menekankan bahwa inilah nada khas Rousseau yang memberi Romantisisme energi destruktif sekaligus kreatif.
Keempat, perbedaan metode antara Rousseau dan para Encyclopédistes menyingkap jarak mendasar antara Pencerahan dan Romantisisme. Kaum Pencerahan percaya pada pendidikan, persuasi, dan despotisme tercerahkan sebagai jalan perubahan. Rousseau menolak itu semua. Ia menuntut kehancuran total, karena hanya dari abu dunia lama dapat lahir dunia baru yang murni. Dengan demikian, ia memberikan justifikasi moral bagi gerakan revolusioner yang kelak mewarnai sejarah Eropa.
Kelima, gaya emosional Rousseau juga memberi warisan penting bagi Romantisisme. Ia menulis dengan air mata, ekstasi, dan paroxysms of rage. Berlin menekankan bahwa yang diwarisi Romantisisme dari Rousseau bukanlah doktrinnya, melainkan nadanya—sebuah nada yang menempatkan subjektivitas personal sebagai otoritas tertinggi. Dengan gaya itu, Rousseau memperlihatkan bahwa filsafat bisa menjadi wahana pengungkapan diri yang penuh gairah, bukan sekadar arena logika.
Keenam, keunikan Rousseau terletak pada klaim bahwa hanya dirinya yang bisa memahami penderitaannya sendiri, dan hanya genius lain yang bisa memahami dirinya. Pernyataan ini adalah inti dari semangat Romantisisme: pengakuan atas keunikan pengalaman manusia yang tidak bisa digeneralisasi oleh hukum-hukum universal. Dengan demikian, ia menantang logika dingin Paris, menggantikannya dengan air mata, ekstasi, dan penderitaan sebagai sarana epistemologis.
Ketujuh, dari keseluruhan pembacaan Berlin atas Diderot dan Rousseau, kita melihat bahwa keduanya mewakili momen transisi dari Pencerahan ke Romantisisme. Diderot membuka jalan dengan pengakuan atas kekuatan gelap dalam seni, sementara Rousseau menyalakan api apokaliptik yang menolak reformasi demi kehancuran total. Bersama-sama, mereka menggeser filsafat dari dunia rasionalitas universal ke dunia subjektivitas, emosi, dan keberanian individual. Inilah akar sejati Romantisisme sebagaimana dibaca Berlin: sebuah gerakan yang lahir dari ketidakpuasan terhadap rasionalitas mapan, dan dari kerinduan akan keaslian manusia yang tak bisa dijinakkan.


Leave a Reply