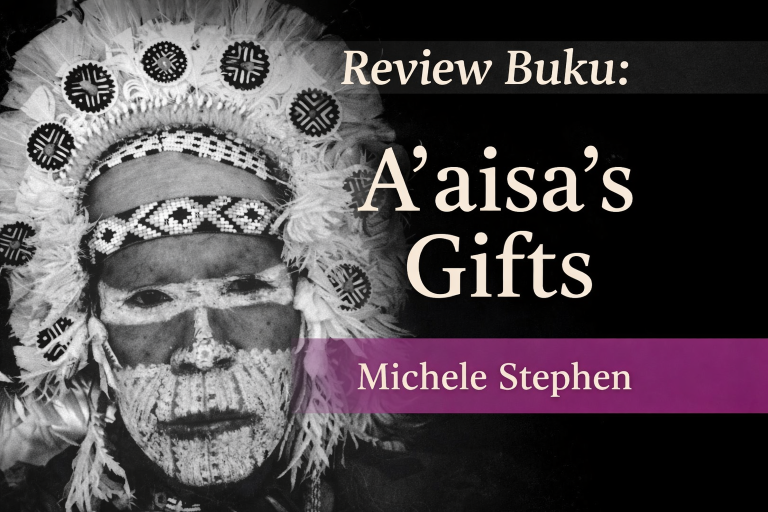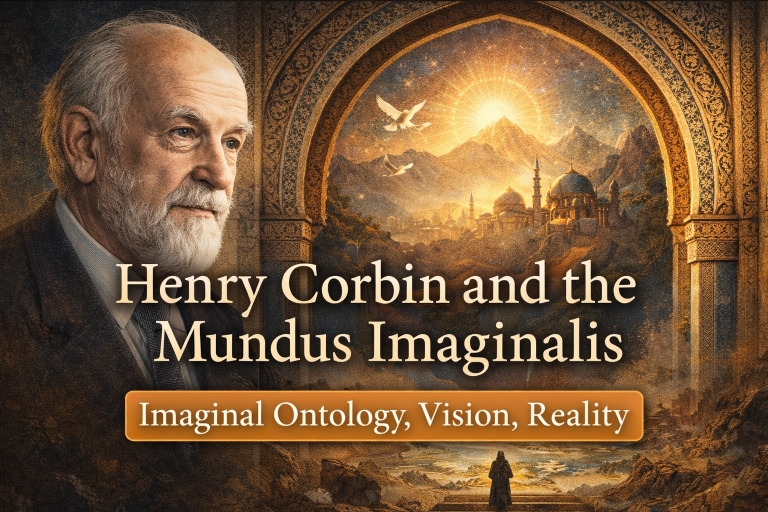Megawati Soekarnoputri dalam nuansa politik pasca-kepemimpinan, dengan simbol PDI-P, arsitektur kekuasaan negara, dan budaya Jawa yang mengiringi suksesi politik Indonesia
Selama seperempat abad terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibangun di atas tiga jenis modal politik yang saling menopang. Modal simbolik berupa warisan ideologis Sukarno menjadi sumber legitimasi historis dan emosional. Modal organisasional diwujudkan melalui kontrol penuh Megawati Soekarnoputri terhadap struktur partai, kaderisasi, dan ritus internal. Sementara itu, modal koalisi dibentuk melalui posisi tawar eksekutif–legislatif yang kuat dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Mietzner, 2013; Ambardi, 2009). Kombinasi ini menjelaskan mengapa PDI-P berhasil melewati krisis politik 1997–2001, konsisten menempati papan atas elektoral, dan berulang kali memanfaatkan akses terhadap sumber daya negara (Aspinall & Berenschot, 2019).
Pemilu 2024 mengubah konfigurasi ini secara mendasar. Pusat gravitasi kekuasaan berpindah kepada presiden baru, koalisi pemerintahan terbentuk tanpa PDI-P sebagai motor, dan mesin pembentuk narasi publik bergerak cepat di luar orbit politik warisan. Dalam situasi ini, dua keputusan strategis akan menentukan arah PDI-P lima tahun ke depan: pertama, pilihan model suksesi pasca-Megawati; kedua, bentuk hubungan partai dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya saling terkait, karena kalkulasi suksesi memengaruhi kalkulasi koalisi, begitu pula sebaliknya (Indikator Politik Indonesia, 2024).
Analisis ini menggunakan empat lensa teoretis. Pertama, hukum besi oligarki yang dirumuskan oleh Robert Michels (1911/2001) menjelaskan kecenderungan organisasi besar terkonsentrasi pada elite sempit, yang pada partai berbasis figur sering terwujud dalam bentuk dinasti politik (Aspinall & Sukmajati, 2015). Kedua, teori kelembagaan partai menurut Samuel Huntington (1968) dan Angelo Panebianco (1988) menekankan pentingnya proses, nilai, dan rutinitas yang terlembaga agar partai dapat bertahan melampaui figur pendiri. Ketiga, konsep patronase politik dari James Scott (1972) dan Paul Hutchcroft (1997) menunjukkan bagaimana akses terhadap sumber daya negara membentuk arah dan stabilitas organisasi politik. Keempat, literatur mengenai merek politik, seperti yang dijelaskan oleh Jennifer Lees-Marshment (2014), menggambarkan pentingnya kepemilikan isu dalam memenangkan hati pemilih di era politik modern.
Dari peta internal yang ada, PDI-P memiliki modal kuat berupa jaringan akar rumput yang luas, memori ideologis Sukarnoisme yang masih memiliki daya resonansi, serta kader teknokrat dan kepala daerah hasil dua siklus pemerintahan. Namun terdapat kelemahan struktural yang signifikan. Ritus suksesi belum pernah diuji tanpa Megawati, citra partai di kalangan pemilih muda dan kelas menengah digital melemah, dan mesin komunikasi sering kali reaktif serta terlalu terpusat (Tempo, 2024b; Indikator Politik Indonesia, 2024).
Dalam posisi ini, partai menghadapi pilihan sulit antara mendekat ke pemerintah untuk memperoleh patronase atau menjauh demi mempertegas identitas. Kedua opsi memiliki legitimasi politik masing-masing, namun bahaya terbesar justru ada pada ketidakjelasan posisi, ketika PDI-P berada terlalu dekat untuk berbeda tetapi terlalu jauh untuk berpengaruh (Aspinall & Berenschot, 2019).
Hubungan antara Megawati dan Prabowo dapat dibaca sebagai permainan berulang pada tiga sumbu utama. Pertama, pada sumbu kebijakan, titik temu paling alami terletak pada agenda kesejahteraan dasar, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur publik, dan penguatan modal manusia (Kompas, 2024d). Dalam area ini, PDI-P dapat mengambil posisi oposisi selektif, mendukung kebijakan pro-rakyat dengan indikator terukur, sambil menolak kebijakan yang melemahkan mekanisme pengawasan atau mengancam akuntabilitas fiskal (CSIS Indonesia, 2024). Kedua, pada sumbu organisasi, stabilitas internal sangat dipengaruhi oleh terbukanya akses birokrasi, posisi di komisi DPR, dan jabatan di BUMN bagi kader partai. Penutupan akses tersebut sering kali memicu fragmentasi dan keluarnya elite (Hutchcroft, 1997; SMRC, 2024). Ketiga, pada sumbu elektoral, pertanyaan utamanya adalah apakah pemerintah memberikan panggung isu bagi figur PDI-P untuk membangun profil publik atau justru menutup ruang tersebut.
Dalam skema yang realistis, PDI-P dapat memilih jalur koeksistensi kritis, yaitu bekerja sama dengan pemerintah pada agenda publik yang bermanfaat sambil tetap tegas pada prinsip konstitusi dan tata kelola. Strategi ini relatif mudah dikomunikasikan ke basis akar rumput sekaligus menjaga hubungan di tingkat elite (Lees-Marshment, 2014).
Skenario suksesi pasca-Megawati setidaknya mencakup empat kemungkinan. Pertama, Puan Maharani menggantikan sebagai ketua umum melalui mekanisme dinasti yang dilembagakan. Ini memberi stabilitas jangka pendek namun memerlukan pembuktian kemampuan Puan untuk mengubah citra dari sekadar pewaris menjadi pemimpin isu kebijakan (SMRC, 2024). Kedua, ketua umum berasal dari luar keluarga, dengan keluarga tetap memegang posisi simbolis sebagai penjaga ideologi. Skenario ini meningkatkan citra modern partai tetapi memerlukan kontrak kekuasaan yang tegas agar tidak menimbulkan konflik internal. Ketiga, kepemimpinan kolektif atau presidium yang menggabungkan Puan dengan figur elektoral kuat. Ini mengirim sinyal persatuan namun rentan terhadap kebuntuan pengambilan keputusan. Keempat, kegagalan mencapai kesepakatan yang memicu fragmentasi dan keluarnya kader ke partai lain, yang berpotensi menurunkan kapasitas partai hingga level liga kedua untuk jangka panjang.
Diferensiasi wacana menjadi elemen krusial dalam mempertahankan relevansi. Penelitian menunjukkan partai yang konsisten pada dua hingga tiga isu utama cenderung memiliki posisi lebih kuat dalam kompetisi politik (Lees-Marshment, 2014; Lobo & Curtice, 2015). Bagi PDI-P, dua isu utama yang direkomendasikan adalah kesejahteraan dan layanan publik, serta rule of law dan akuntabilitas fiskal. Isu pendukung dapat mencakup kedaulatan pangan–energi desa dan ekonomi digital–kerja masa depan.
Dalam 6–18 bulan ke depan, ada enam langkah taktis yang dapat menentukan arah partai. Pertama, mengumumkan kalender suksesi dengan aturan sengketa yang jelas. Kedua, membentuk shadow cabinet dan issue hubs yang memproduksi analisis kebijakan rutin. Ketiga, membangun war room komunikasi dengan pengukuran kinerja pesan. Keempat, meluncurkan program unggulan triwulanan yang terlihat manfaatnya oleh publik. Kelima, membangun kemitraan pengetahuan dengan universitas atau lembaga riset. Keenam, mengembangkan fellowship kader muda yang menghasilkan keluaran kebijakan teruji publik.
Relasi eksternal dengan NU, jaringan masyarakat sipil, dan mitra koalisi harus diperkuat melalui kemitraan programatik, bukan hanya simbolik. Fokusnya adalah pada agenda yang dapat diukur seperti program pesantren produktif, pengembangan ekonomi desa berbasis lingkungan, dan peningkatan keterampilan kerja (Kompas, 2024h).
Pengalaman internasional menunjukkan relevansi tiga kasus. Congress Party di India yang terlalu lama mengandalkan dinasti tanpa pembaruan kelembagaan akhirnya kalah bersaing dengan BJP yang lebih agresif dalam menguasai isu dan operasi digital (Chhibber & Verma, 2018). LDP di Jepang bertahan berkat proses suksesi yang terlembaga dan konsistensi kebijakan ekonomi (Krauss & Pekkanen, 2011). PT di Brasil berhasil pulih pasca-skandal dengan regenerasi kebijakan dan aliansi sosial lentur (Hunter, 2010).
Proyeksi hingga 2029 menawarkan tiga jalan besar. Jalan institusional dengan suksesi tertib dan konsistensi isu dapat menjaga PDI-P di posisi tiga besar. Jalan pragmatis dengan kedekatan taktis ke pemerintah namun diferensiasi isu tertentu dapat mempertahankan stabilitas meski berisiko kaburnya merek politik. Jalan krisis akibat kegagalan suksesi dapat menurunkan posisi partai secara drastis.
Rekomendasi eksekusi yang realistis meliputi penetapan kalender suksesi, pembentukan shadow cabinet, penguatan komunikasi strategis, peluncuran program unggulan, kemitraan pengetahuan, dan pemberdayaan kader muda dengan keluaran kebijakan yang jelas.
Megawati menutup era politiknya sebagai legenda yang menjaga api Sukarnoisme tetap menyala. Agar PDI-P tidak berhenti sebagai partai yang hidup dari legenda, ia harus bertransformasi menjadi lembaga yang terlembaga secara penuh, menegaskan diferensiasi kebijakan, dan menjaga disiplin organisasi. Koeksistensi kritis dengan Presiden Prabowo, yakni bekerja sama pada agenda publik yang bermanfaat dan bersikap tegas pada prinsip konstitusi, menawarkan jalur rasional untuk mempertahankan relevansi hingga 2029 dan seterusnya.
Daftar Pustaka
Ambardi, K. (2009). Mengungkap politik kartel: Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi. Jakarta: KPG.
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism and the state in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots. Singapore: NUS Press.
Chhibber, P., & Verma, R. (2018). Ideology and identity: The changing party systems of India. Oxford: Oxford University Press.
CSIS Indonesia. (2024). Prospek politik Indonesia pasca Pemilu 2024: Dinamika koalisi dan oposisi. Jakarta: Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.or.id
Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven, CT: Yale University Press.
Hunter, W. (2010). The transformation of the Workers’ Party in Brazil, 1989–2009. Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchcroft, P. D. (1997). The politics of privilege: Assessing the impact of rents, corruption, and clientelism on third world development. Political Studies, 45(3), 639–658. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00093
Indikator Politik Indonesia. (2024). Peta politik nasional pasca-Pemilu 2024. Jakarta: Indikator Politik Indonesia. https://indikator.co.id
Kompas. (2024a, February 15). Peta kekuatan politik pasca-Pemilu 2024. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024b, March 10). Tantangan oposisi di era Prabowo. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024c, April 2). Kekuatan jaringan politik PDI-P. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024d, April 15). Program kesejahteraan dan peluang oposisi selektif. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024e, May 8). Risiko politik dinasti bagi partai besar. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024f, June 1). Fragmentasi partai dan efek elektoral. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024g, July 5). Desa pangan mandiri dan inovasi kebijakan lokal. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024h, August 12). Kemitraan politik dan NU. Kompas.id. https://www.kompas.id
Kompas. (2024i, October 1). PDI-P di era Prabowo: Bertahan atau bertransformasi? Kompas.id. https://www.kompas.id
Krauss, E. S., & Pekkanen, R. (2011). The rise and fall of Japan’s LDP: Political party organizations as historical institutions. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Lees-Marshment, J. (2014). Political marketing: Principles and applications (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
Lobo, M. C., & Curtice, J. (2015). Personality politics? The role of leader evaluations in democratic elections. Oxford: Oxford University Press.
Michels, R. (2001). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy (E. Paul & C. Paul, Trans.). Kitchener: Batoche Books. (Original work published 1911)
Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi’s rise, democracy, and political contestation in Indonesia. Policy Studies, 72, 1–36. https://doi.org/10.1355/9789814762136-007
Panebianco, A. (1988). Political parties: Organization and power. Cambridge: Cambridge University Press.
Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. American Political Science Review, 66(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280
SMRC. (2024). Preferensi politik publik pasca-Pemilu 2024. Jakarta: Saiful Mujani Research and Consulting. https://saifulmujani.com
Tempo. (2024a, March 3). Prabowo–Megawati: Jalan koeksistensi atau oposisi. Tempo.co. https://www.tempo.co
Tempo. (2024b, May 21). Skenario suksesi PDI-P. Tempo.co. https://www.tempo.co
Tempo. (2024c, July 10). Rule of law dan peran oposisi. Tempo.co. https://www.tempo.co