Pendahuluan
Charles Taylor, dalam karyanya Sources of the Self, menempatkan The Expressivist Turn sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah kesadaran modern. Bab 21 menyingkap bagaimana filsafat alam di akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 menjadi medan transformatif, ketika alam dipandang bukan lagi hanya sebagai objek eksternal, melainkan sebagai sumber batiniah yang menyalurkan kebenaran, elan, dan suara diri. Taylor membuka bagian ini dengan menegaskan bahwa “Kant offers one form of modern internalization, that is, a way of finding the good in our inner motivation. Another comes with that family of views in the late eighteenth century that represents nature as an inner source” (hlm. 368). Dari sini jelas bahwa ekspresivisme tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berkembang dalam dialog dengan rasionalisme Kantian sekaligus dalam kritik terhadapnya.
Romantisisme menjadi laboratorium di mana gagasan alam sebagai sumber berkembang dan menemukan ekspresinya. Taylor menekankan bahwa “the picture of nature as a source was a crucial part of the conceptual armoury in which Romanticism arose and conquered European culture and sensibility” (hlm. 368). Alam dipahami bukan hanya sebagai latar, melainkan sebagai kekuatan yang memungkinkan individu menemukan suaranya. Rousseau, Herder, Goethe, hingga Hegel memainkan peran kunci dalam mengartikulasikan gagasan ini, dan Romantisisme kemudian menjadi arus dominan yang menembus seni, sastra, dan filsafat.
Namun, Taylor juga memperingatkan agar kita tidak menyederhanakan Romantisisme hanya sebagai kebangkitan kembali kultus alam. Ia menulis: “As the mention of Goethe and Hegel shows, this would be too simple. My claim is rather that the picture of nature as a source was a crucial part of the conceptual armoury…” (hlm. 368). Dengan kata lain, Romantisisme adalah sebuah gerakan multi-dimensi yang melibatkan estetika, etika, dan epistemologi sekaligus. Alam memang menjadi pusat, tetapi ia diartikulasikan dalam kerangka yang jauh lebih kompleks.
Sejak awal, teks ini juga menegaskan pentingnya membedakan Romantisisme dari neo-Klasikisme. Taylor mencatat: “Against the classical stress on rationalism, tradition, and formal harmony, the Romantics affirmed the rights of the individual, of the imagination, and of feeling” (hlm. 368). Dengan demikian, The Expressivist Turn adalah juga pemberontakan terhadap klaim universalitas dan harmoni formal yang mendominasi abad ke-18. Ia menempatkan individu dan ekspresinya sebagai sumber otoritas moral yang sah.
Pergeseran inilah yang kemudian membentuk sebuah horizon baru dalam budaya Eropa. Bagi Taylor, hal ini bukan hanya tentang seni atau estetika, tetapi tentang bagaimana manusia memahami dirinya sebagai makhluk moral. Alam sebagai sumber memberi manusia sarana untuk memahami bahwa moralitas tidak lagi harus bergantung pada hukum eksternal, melainkan dapat ditemukan dalam “suara batin” yang beresonansi dengan alam. “If we define Romanticism in this way, then its relation to the philosophies of nature as source can be clearly stated” (hlm. 368). Kalimat ini adalah kunci: Romantisisme menjadi saluran filosofis bagi gagasan alam sebagai sumber moralitas batiniah.
Karena itu, bab ini tidak sekadar mengulas sebuah gerakan budaya, melainkan mendekonstruksi basis konseptual dari modernitas itu sendiri. Taylor ingin menunjukkan bahwa The Expressivist Turn adalah salah satu jalan utama yang membuat modernitas menjadi apa adanya: sebuah peradaban yang menekankan otonomi individu, ekspresi diri, dan suara batin sebagai sumber otoritas moral.
Pendahuluan ini hendak menempatkan pembacaan kita pada posisi yang tepat: kita tidak sedang membicarakan Romantisisme sebagai gaya seni, tetapi sebagai transformasi filosofis yang membentuk struktur kesadaran modern. Untuk itu, kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana alam dipahami sebagai sumber, bagaimana Taylor membaca hubungan antara providensialisme dan ekspresivisme, bagaimana konsep alam bergeser dari eksternal ke internal, bagaimana etika dan estetika dilebur, serta bagaimana ekspresivisme membentuk pengertian kita tentang ekspresi diri.
Alam sebagai Sumber dalam Romantisisme
Romantisisme, menurut Charles Taylor, tidak dapat dipahami tanpa melihat perannya dalam membangun gambaran alam sebagai sumber. Alam bukan hanya sebuah lanskap yang dilukiskan oleh para seniman atau puisi yang diidealkan oleh para penyair, melainkan fondasi bagi sebuah filsafat baru tentang moralitas dan ekspresi. Taylor menulis: “The philosophy of nature as source was central to the great upheaval in thought and sensibility that we refer to as ‘Romanticism’, so much so that it is tempting to identify them” (hlm. 368). Dengan kalimat ini, Taylor menegaskan bahwa gagasan alam sebagai sumber adalah inti, bahkan hampir identik, dengan apa yang disebut sebagai Romantisisme. Namun, ia juga mengingatkan bahwa menyamakan keduanya secara total akan menyederhanakan kompleksitas yang ada.
Romantisisme memang muncul sebagai sebuah gerakan yang menolak tradisi neo-Klasik. Dalam pandangan neo-Klasik, harmoni formal, rasionalitas, dan keteraturan menjadi prinsip utama. Namun, para Romantis justru mengedepankan imajinasi, perasaan, dan hak individu. Taylor menegaskan: “Against the classical stress on rationalism, tradition, and formal harmony, the Romantics affirmed the rights of the individual, of the imagination, and of feeling” (hlm. 368). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Romantisisme bukan hanya tentang estetika, tetapi juga sebuah revolusi dalam cara pandang moral dan eksistensial.
Dalam hal ini, Rousseau menjadi titik awal yang menentukan. Ia menekankan kembalinya manusia pada alam sebagai jalan menemukan keaslian diri. Taylor menulis bahwa “Rousseau is naturally its point of departure, and its first important articulation comes perhaps in the work of Herder” (hlm. 368). Rousseau memandang alam sebagai keadaan murni, bebas dari korupsi sosial, dan inilah yang memberi inspirasi bagi generasi berikutnya. Herder kemudian melangkah lebih jauh dengan menekankan simpati universal yang menghubungkan semua makhluk hidup, yang kemudian menjadi inti dari filsafat alam sebagai sumber.
Herder tidak hanya berbicara tentang alam sebagai latar, tetapi sebagai simpati kosmik yang menembus segala sesuatu. Taylor mengutip langsung kalimat Herder: “Siehe die ganze Natur, betrachte die grosse Analogie der Schöpfung. Alles fühlt sich und seines Gleichen, Leben waltet zu Leben” (hlm. 369). Kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai: “Lihatlah seluruh alam, perhatikan analogi besar penciptaan. Segala sesuatu merasakan dirinya dan sesamanya, kehidupan mengalir ke kehidupan.” Di sini, alam dipahami sebagai jaringan kehidupan yang saling merasakan, sebuah organisme besar di mana manusia menjadi bagian integralnya.
Gagasan inilah yang membuat Romantisisme mampu menaklukkan budaya Eropa. Alam sebagai sumber tidak hanya memengaruhi filsafat, tetapi juga seni, musik, dan sastra. Taylor menulis bahwa dalam puisi para penulis Prancis seperti Lamartine dan Musset, suara batin mereka sering diekspresikan dengan menghubungkannya pada dorongan alamiah. Bahkan penyair Inggris seperti Wordsworth dan Blake menempatkan alam sebagai sumber inspirasi yang menyalurkan elan kehidupan. Taylor mencatat: “Sometimes the voice or impulse is seen as the impulse in us of nature, as the larger order and force are set. This was the case with some English writers, like Blake and in a different way also Wordsworth” (hlm. 369).
Namun, Romantisisme tidak sekadar melihat alam sebagai objek eksternal yang dikagumi. Alam dipahami sebagai cermin batin manusia. Ketika seseorang menulis puisi atau menggubah musik, ia tidak hanya menyalurkan imajinasi pribadinya, tetapi juga mengartikulasikan elan yang datang dari alam itu sendiri. Alam adalah sumber ekspresi, dan ekspresi manusia adalah medium tempat alam bersuara. Taylor menegaskan bahwa “feelings—these were the crucial justifying concepts of the Romantic rebellion in its various forms. They were indispensable to it” (hlm. 369). Dengan kata lain, perasaan bukan hanya sekadar pengalaman subjektif, melainkan bukti otentik bahwa manusia beresonansi dengan sumber kehidupan yang lebih besar.
Dari perspektif ini, Romantisisme menjadi lebih dari sekadar aliran estetika. Ia adalah sebuah filsafat hidup yang mengajarkan manusia untuk mendengarkan suara batin yang sejalan dengan alam. Alam bukan lagi sesuatu yang harus ditaklukkan atau dikendalikan, melainkan sesuatu yang harus didengarkan dan diinternalisasi. Alam adalah guru yang mengajarkan manusia bagaimana menjadi otentik, dan ekspresi adalah jalan untuk mewujudkan otentisitas itu. Dengan begitu, The Expressivist Turn dapat dipahami sebagai pergeseran besar dalam sejarah kesadaran manusia, ketika alam tidak lagi dipandang dari luar, tetapi dijadikan sumber dari dalam.
Providensialisme, Deisme, dan Ekspresivisme
Charles Taylor dengan jernih memperlihatkan bahwa gagasan alam sebagai sumber tidak hadir dalam ruang kosong. Ia lahir dari interaksi, kesinambungan, sekaligus pergeseran dari tradisi lama yang lebih menekankan providensialisme dan Deisme. Banyak penulis abad ke-18, sebelum ledakan penuh Romantisisme, melihat manusia sebagai bagian dari tatanan alam yang lebih besar, yang sering digambarkan sebagai tatanan providensial. Taylor menulis: “All these writers see human beings as set in a larger natural order, often conceived as a providential order, with which they should be in harmony” (hlm. 369). Dengan kalimat ini, ia ingin menekankan bahwa sekalipun Romantisisme menekankan ekspresi batin, ia tetap berada dalam kesinambungan dengan pandangan lama yang menekankan keselarasan kosmik.
Namun, Taylor juga menegaskan bahwa pergeseran mendasar segera terjadi. Jika providensialisme klasik menekankan keteraturan rasional yang ditetapkan Tuhan, ekspresivisme menggeser otoritas itu ke dalam diri manusia. Ia menulis: “The shift is towards a less intellectual view, which no longer places such reliance on proofs of divine creation from design but which can ground all this instead in inner conviction” (hlm. 370). Pergeseran ini sangat signifikan, karena kebenaran moral tidak lagi didasarkan pada argumen eksternal tentang desain ilahi, tetapi pada keyakinan batiniah yang lahir dari resonansi dengan alam. Dengan demikian, epistemologi moral beralih dari luar ke dalam, dari argumen teologis ke pengalaman subjektif.
Meski demikian, hubungan dengan Deisme tidak terputus sama sekali. Justru ekspresivisme dapat dilihat sebagai transformasi dari Deisme, bukan penolakannya secara total. Taylor menegaskan: “And indeed, a theory of nature as a source can be combined with some form of Christian faith, following the lead of Deism in which God’s relation to us passes mainly through his order, as we can see in Rousseau, and later in the German Romantics” (hlm. 370). Artinya, Deisme yang menekankan hubungan Tuhan dengan manusia melalui keteraturan ciptaan memberi landasan bagi Romantisisme untuk melangkah lebih jauh: keteraturan itu kini diinternalisasi dan dimaknai sebagai suara batin.
Rousseau menjadi contoh terbaik dari jembatan antara Deisme dan ekspresivisme. Dalam karya-karyanya, ia menekankan bahwa Tuhan dapat ditemukan bukan semata melalui argumentasi rasional tentang desain, melainkan melalui pengalaman batin yang murni. Dengan ini, Rousseau menggeser titik berat dari argumen intelektual ke perasaan. Hal ini kemudian diserap dan dikembangkan lebih lanjut oleh para Romantis Jerman, yang bahkan menganggap suara batin itu sebagai cara Tuhan berbicara melalui manusia. Taylor menegaskan bahwa di sini kita melihat kesinambungan antara tradisi Deis dengan ekspresivisme Romantis.
Pergeseran ini membawa dampak besar pada teologi modern. Tuhan tidak lagi dipahami hanya sebagai pencipta eksternal, melainkan sebagai elan yang hadir di dalam diri manusia. Taylor menulis: “God, then, is to be interpreted in terms of what we see striving in nature and finding voice within ourselves” (hlm. 371). Kalimat ini sangat penting karena menegaskan bahwa gagasan ekspresivisme tidak sekadar estetis, melainkan teologis. Ia menawarkan sebuah teologi batiniah di mana Tuhan hadir dalam perasaan manusia yang selaras dengan dorongan alam.
Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana ekspresivisme tetap membawa sisa-sisa warisan lama, namun dengan wajah yang sepenuhnya baru. Di satu sisi, ia melanjutkan tradisi providensialisme dan Deisme, yang menekankan hubungan manusia dengan keteraturan alam ciptaan. Tetapi di sisi lain, ia menolak bentuk argumen eksternal dan menggantikannya dengan otoritas batin. Tuhan tidak lagi diakses melalui pembuktian rasional, melainkan melalui suara hati yang resonan dengan alam. Inilah inti dari The Expressivist Turn: peralihan otoritas dari luar ke dalam, dari desain ke ekspresi.
Maka, hubungan antara providensialisme, Deisme, dan ekspresivisme bukanlah hubungan oposisi mutlak, melainkan dialektika. Romantisisme lahir dengan mewarisi kerangka lama, tetapi mengubah titik beratnya secara radikal. Alam tetap dipandang sebagai tanda, tetapi kini bukan lagi sekadar tanda eksternal tentang keberadaan Tuhan. Alam adalah sumber yang berbicara langsung ke dalam batin manusia. Dengan demikian, ekspresivisme tidak hanya memodifikasi warisan lama, melainkan membukakan jalan baru bagi pemahaman modern tentang moralitas, estetika, dan teologi.
Transformasi Konsep Alam: Dari Eksternal ke Internal
Perubahan paling signifikan yang ditangkap Charles Taylor dalam The Expressivist Turn adalah bagaimana alam dipahami tidak lagi semata-mata sebagai tatanan eksternal yang memberi bukti akan keberadaan Tuhan, melainkan sebagai sumber batiniah yang hidup dalam diri manusia. Taylor menulis: “God, then, is to be interpreted in terms of what we see striving in nature and finding voice within ourselves” (hlm. 371). Kalimat ini memperlihatkan sebuah pergeseran radikal. Tuhan tidak lagi ditempatkan jauh di luar diri manusia, melainkan diinternalisasi ke dalam pengalaman batin, dalam bentuk suara hati, dorongan, dan elan yang sejalan dengan kehidupan alam.
Sebelumnya, dalam kerangka providensialisme dan natural theology, argumen tentang Tuhan sering dibangun melalui desain ciptaan. Dunia yang teratur, penuh harmoni, dianggap sebagai bukti adanya Sang Pencipta. Namun, Romantisisme menolak mengandalkan argumen eksternal semacam itu. Taylor menulis: “The shift is towards a less intellectual view, which no longer places such reliance on proofs of divine creation from design but which can ground all this instead in inner conviction” (hlm. 370). Artinya, keyakinan kepada Tuhan dan kebenaran moral tidak lagi bersandar pada observasi eksternal, melainkan pada keyakinan batiniah yang lahir dari pengalaman manusia sendiri.
Dalam konteks ini, alam berubah dari object of contemplation menjadi source of expression. Alam tidak lagi hanya diamati, tetapi diinternalisasi dan dihayati sebagai bagian dari suara batin manusia. Taylor memperlihatkan bahwa gagasan ini berkembang kuat di tangan para Romantis Jerman. Alam dipahami sebagai kekuatan hidup yang menyalurkan dirinya melalui ekspresi manusia. Dengan demikian, setiap karya seni, puisi, atau tindakan moral bukan hanya ekspresi individual, melainkan perwujudan dari elan alamiah yang berbicara melalui manusia.
Perubahan dari eksternal ke internal juga tampak dalam cara perasaan (sentiments) diposisikan. Taylor menulis: “The good life is originally defined partly in terms of certain sentiments. This is why late-eighteenth-century sentimentalism, when it moved beyond the early influential formulations of Rousseau, found its natural home in the philosophies of nature as a source” (hlm. 372). Perasaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai efek sampingan kehidupan moral, tetapi sebagai dasar dari moralitas itu sendiri. Dengan kata lain, moralitas berakar dalam resonansi batiniah dengan alam.
Implikasi dari transformasi ini adalah melemahnya dikotomi klasik antara pengetahuan rasional dan pengalaman subjektif. Jika sebelumnya kebenaran dianggap hanya sah jika dapat dibuktikan secara rasional, maka ekspresivisme mengajarkan bahwa kebenaran juga dapat ditemukan dalam ekspresi batin. Perasaan, imajinasi, dan suara hati menjadi cara sah untuk memahami kebaikan dan keindahan. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa Romantisisme begitu menekankan pentingnya seni: seni adalah sarana utama untuk menyalurkan ekspresi yang bersumber dari alam.
Lebih jauh lagi, transformasi ini memperlihatkan bahwa manusia bukan lagi dipandang sebagai penonton pasif dari keteraturan kosmos. Manusia justru adalah agen yang aktif mengekspresikan sumber kehidupan itu. Dalam pengertian ini, alam tidak lagi berada di luar, tetapi hadir dalam diri manusia sebagai suara batin yang menuntun tindakan dan pemikiran. Alam menjadi bagian dari subjektivitas manusia. Taylor menekankan bahwa gagasan ini mendasari seluruh doktrin ekspresivis: pemenuhan kodrat manusia berarti mengekspresikan suara batin yang sebenarnya adalah gema dari alam.
Dengan demikian, transformasi konsep alam dari eksternal ke internal adalah inti dari The Expressivist Turn. Alam tidak lagi dipahami sebagai bukti objektif tentang desain ilahi, tetapi sebagai sumber subjektif yang beresonansi dalam batin manusia. Tuhan hadir bukan di luar, tetapi dalam diri, melalui perasaan, dorongan, dan ekspresi. Dari sinilah lahir sebuah paradigma baru yang akan mengubah wajah modernitas: paradigma ekspresif yang menempatkan subjektivitas sebagai pusat, tanpa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan tatanan kosmik yang lebih besar.
Etika, Estetika, dan Suara Batin
Charles Taylor menunjukkan bahwa salah satu implikasi paling radikal dari The Expressivist Turn adalah bagaimana ia mengaburkan batas antara ranah etika dan estetika. Dalam tradisi klasik, keduanya dipisahkan dengan jelas: etika mengatur kebaikan, sementara estetika mengatur keindahan. Namun, Romantisisme yang dibangun di atas gagasan alam sebagai sumber justru memperlihatkan bagaimana keduanya saling melebur. Taylor menulis: “This slide, along either of these paths, tends to dissolve the distinction between the ethical and the aesthetic” (hlm. 373). Dengan kata lain, moralitas dan seni tidak lagi bisa dipisahkan secara tegas, karena keduanya sama-sama berakar dalam pengalaman batiniah manusia yang beresonansi dengan alam.
Kehidupan baik, menurut Taylor, dalam kerangka ini tidak lagi didefinisikan semata oleh ketaatan terhadap hukum rasional atau aturan eksternal, tetapi oleh kualitas perasaan yang mendasarinya. Ia menulis: “The good life is originally defined partly in terms of certain sentiments” (hlm. 372). Perasaan bukan lagi sekadar aspek tambahan, melainkan bagian esensial dari kebaikan itu sendiri. Dengan demikian, moralitas berakar dalam pengalaman estetis: bagaimana manusia merasakan, mengalami, dan mengekspresikan hubungannya dengan dunia.
Hal ini sangat berbeda dengan model etika rasional Kantian yang menekankan universalisme hukum moral. Dalam Romantisisme, keaslian (authenticity) menjadi nilai tertinggi. Suara batin menjadi otoritas yang lebih kuat ketimbang hukum universal. Itulah sebabnya perasaan dan ekspresi menjadi ukuran keaslian moral. Taylor menunjukkan bahwa inilah mengapa sentimentalism akhir abad ke-18 menemukan rumahnya dalam filsafat alam sebagai sumber: moralitas menjadi persoalan ekspresi perasaan yang otentik, bukan sekadar kepatuhan rasional.
Peleburan etika dan estetika ini juga menjelaskan mengapa seni menjadi begitu penting dalam Romantisisme. Karya seni dipandang bukan hanya sebagai representasi keindahan, tetapi sebagai perwujudan kebenaran moral. Seorang penyair atau seniman yang mengekspresikan suara batinnya sesungguhnya sedang menyalurkan elan alamiah yang sama yang menjadi sumber moralitas. Taylor menekankan: “These were the crucial justifying concepts of the Romantic rebellion in its various forms. They were indispensable to it” (hlm. 369). Dengan kata lain, seni adalah bentuk pemberontakan terhadap keteraturan klasik, karena ia membuktikan bahwa perasaan dan imajinasi bisa menjadi sumber otoritas moral yang sah.
Lebih jauh, hubungan ini menegaskan bahwa kebenaran tidak lagi bisa dipisahkan dari keindahan. Apa yang indah adalah juga yang baik, dan apa yang baik adalah juga yang indah. Hal ini membawa dampak luas bagi kesadaran modern: moralitas menjadi pengalaman yang bersifat estetis, sementara estetika menjadi sarana untuk memahami moralitas. Taylor memperlihatkan bahwa inilah yang membentuk ciri khas budaya modern setelah Romantisisme: keyakinan bahwa seni dan moralitas saling menopang.
Dalam kerangka ini, suara batin menjadi pusat yang menghubungkan etika dan estetika. Alam sebagai sumber berbicara melalui perasaan, dan perasaan itu kemudian diekspresikan dalam bentuk seni, sekaligus membimbing kehidupan moral. Suara batin menjadi medium di mana alam, seni, dan moralitas bertemu. Maka, hidup baik bukan sekadar soal mengikuti aturan, tetapi soal hidup dalam keaslian ekspresi. Seperti ditegaskan Taylor, “fulfilling my nature means expressing an inner voice, the voice or impulse” (hlm. 374). Moralitas dan keindahan sama-sama berpangkal pada ekspresi diri ini.
Dengan demikian, The Expressivist Turn tidak hanya mengubah cara manusia memahami alam, tetapi juga mengubah cara manusia memahami kebaikan dan keindahan. Etika dan estetika tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling melebur dalam pengalaman ekspresif. Suara batin yang beresonansi dengan alam menjadi dasar bagi keduanya. Inilah yang menjadikan Romantisisme bukan sekadar gerakan seni, tetapi sebuah revolusi dalam kesadaran moral modern.
Ekspresivisme dan Ekspresi Diri Manusia
Charles Taylor menjelaskan bahwa inti dari The Expressivist Turn adalah pemahaman bahwa pemenuhan kodrat manusia berarti mengekspresikan suara batin. Ia menulis: “My claim is that the idea of nature as an intrinsic source goes along with an expressive view of human life. Fulfilling my nature means expressing an inner voice, the voice or impulse” (hlm. 374). Kalimat ini menjadi dasar bagi seluruh doktrin ekspresivis. Dengan kata lain, manusia baru dapat dikatakan hidup otentik ketika ia menyalurkan suara batin yang sesungguhnya merupakan gema dari alam sebagai sumber.
Konsep ekspresi di sini tidak dipahami sekadar sebagai tindakan komunikasi, tetapi sebagai manifestasi ontologis. Taylor memberi definisi: “To express something is to make it manifest in a given medium. I express my feelings in my face; I express my thoughts in the words I speak or write. I express my vision of things in the work of art, perhaps a novel or a play” (hlm. 374). Ekspresi adalah perwujudan nyata dari apa yang ada di dalam diri. Tanpa ekspresi, suara batin tetap terpendam, tidak menjadi nyata. Maka, ekspresi bukan tambahan, melainkan syarat mutlak bagi keberadaan manusia yang otentik.
Dalam kerangka ini, seni mendapatkan posisi yang sangat penting. Seni adalah medium utama ekspresi, tempat suara batin menemukan bentuknya. Seorang penyair, pelukis, atau musisi tidak hanya berkarya demi keindahan, tetapi sedang mewujudkan kodrat manusiawi. Taylor menegaskan bahwa karya seni bukan hanya representasi, melainkan ekspresi. Melalui seni, manusia menyalurkan pandangannya tentang dunia, perasaan terdalamnya, bahkan elan vital yang datang dari alam. Ekspresi seni dengan demikian menjadi bentuk tertinggi dari pemenuhan diri.
Ekspresivisme juga mengandung implikasi etis yang mendalam. Jika hidup baik berarti mengekspresikan suara batin, maka moralitas diukur dari keaslian ekspresi itu. Kehidupan yang palsu adalah kehidupan yang menekan atau memalsukan suara batin demi kepatuhan eksternal. Sebaliknya, kehidupan otentik adalah kehidupan yang berani menyalurkan dorongan batin yang sejati. Dengan cara ini, ekspresivisme menempatkan otentisitas sebagai nilai moral tertinggi. Seperti Taylor tunjukkan, inilah warisan Romantisisme yang terus hidup dalam kesadaran modern.
Namun, ekspresivisme tidak berarti subjektivisme tanpa batas. Taylor menekankan bahwa suara batin bukan hanya suara pribadi yang terlepas dari dunia, melainkan gema dari alam sebagai sumber. Dengan demikian, ketika manusia mengekspresikan dirinya, ia sesungguhnya juga mengekspresikan elan alamiah yang lebih besar. Ekspresi diri bukan isolasi, melainkan partisipasi dalam kehidupan kosmik. Di sinilah letak kekuatan ekspresivisme: ia menghubungkan subjektivitas dengan kosmos tanpa harus kembali pada model rasionalisme klasik.
Ekspresi diri manusia dalam kerangka ini juga berhubungan erat dengan kebebasan. Kebebasan bukan lagi dipahami sekadar sebagai kemampuan memilih secara rasional, tetapi sebagai kebebasan untuk menyalurkan suara batin. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan untuk hidup otentik, untuk mengekspresikan diri sesuai dengan dorongan batin yang selaras dengan alam. Dengan demikian, ekspresivisme mengubah pengertian kebebasan itu sendiri: dari kebebasan sebagai otonomi rasional menjadi kebebasan sebagai ekspresi otentik.
Akhirnya, Taylor memperlihatkan bahwa doktrin ekspresivisme ini tidak hanya membentuk cara manusia memahami seni dan moralitas, tetapi juga membentuk seluruh horizon modernitas. Pandangan bahwa hidup baik adalah hidup yang otentik, bahwa manusia harus mengekspresikan dirinya, bahwa seni adalah perwujudan terdalam dari jiwa manusia—semuanya adalah buah dari The Expressivist Turn. Alam sebagai sumber menjadi dasar dari seluruh pandangan ini, dan ekspresi menjadi jalan bagi manusia untuk menemukan dirinya sekaligus menyalurkan elan kosmik yang lebih besar.
Warisan dan Relevansi Kontemporer
Warisan paling penting dari The Expressivist Turn menurut Charles Taylor adalah pergeseran radikal dalam horizon kesadaran modern: dari menekankan tatanan eksternal menuju suara batin dan ekspresi diri. Apa yang muncul pada akhir abad ke-18 sebagai sebuah pemberontakan terhadap rasionalisme klasik ternyata membentuk kerangka kultural dan filosofis dunia modern. Taylor menegaskan bahwa gagasan alam sebagai sumber menjadi “indispensable” bagi Romantisisme dan seterusnya: “They were indispensable to it” (hlm. 369). Tanpa gagasan ini, sulit membayangkan bagaimana hak individu, imajinasi, dan perasaan dapat mengambil posisi sentral dalam kehidupan modern.
Salah satu warisan langsung adalah nilai otentisitas yang hingga kini menjadi ukuran utama moralitas personal. Kehidupan modern sering menekankan pentingnya “menjadi diri sendiri” atau to be true to oneself. Ini adalah gema jauh dari ekspresivisme yang dirumuskan para Romantis. Taylor mengingatkan bahwa bagi Romantisisme, memenuhi kodrat manusia berarti mengekspresikan suara batin: “Fulfilling my nature means expressing an inner voice, the voice or impulse” (hlm. 374). Dengan demikian, nilai otentisitas yang kini kita anggap wajar adalah hasil dari sebuah transformasi historis yang bermula pada The Expressivist Turn.
Warisan lainnya adalah posisi seni dalam kehidupan modern. Sejak Romantisisme, seni tidak lagi dianggap sekadar hiburan atau ornamen, tetapi sebagai medium otentik ekspresi diri. Dalam karya seni, baik puisi, musik, maupun lukisan, manusia menyalurkan visi batin dan elan kosmik yang berakar pada alam. Taylor menulis: “To express something is to make it manifest in a given medium. I express my vision of things in the work of art” (hlm. 374). Dengan pandangan ini, seni mendapatkan status baru sebagai sarana kebenaran, bukan hanya keindahan. Inilah yang menjelaskan mengapa seni modern begitu erat kaitannya dengan pencarian identitas dan otentisitas.
Dalam ranah religius dan teologis, warisan ekspresivisme juga sangat terasa. Gagasan bahwa Tuhan hadir dalam suara batin, bukan hanya dalam desain eksternal ciptaan, terus membentuk spiritualitas modern. Banyak bentuk religiositas kontemporer yang menekankan pengalaman batin dan hubungan personal dengan Tuhan berakar pada pandangan ini. Taylor mencatat pergeseran dari pembuktian intelektual menuju inner conviction (hlm. 370), dan pergeseran ini membuka jalan bagi bentuk spiritualitas yang lebih personal, emosional, dan ekspresif.
Relevansi ekspresivisme juga dapat dirasakan dalam krisis modern, terutama dalam bidang ekologi. Jika alam dipahami sebagai sumber batiniah, maka kerusakan ekologis bukan hanya masalah praktis, tetapi juga eksistensial. Krisis lingkungan dapat dimengerti sebagai krisis spiritual, karena manusia kehilangan hubungan dengan sumber batin yang menopang moralitas dan otentisitas. Dengan demikian, warisan Romantisisme yang menekankan alam sebagai sumber dapat menjadi dasar bagi etika ekologis kontemporer yang lebih mendalam.
Selain itu, gagasan ekspresivisme juga berpengaruh dalam filsafat eksistensialis dan fenomenologi abad ke-20. Pemikiran Heidegger tentang otentisitas, Sartre tentang kebebasan, dan Merleau-Ponty tentang tubuh sebagai pusat pengalaman, semuanya berhutang pada pandangan Romantis tentang ekspresi diri. Bahkan psikologi humanistik abad ke-20, dengan tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, menghidupkan kembali gagasan bahwa manusia harus mengekspresikan dirinya secara otentik agar dapat hidup baik. Semua ini memperlihatkan panjangnya resonansi dari gagasan Taylor tentang The Expressivist Turn.
Akhirnya, warisan ekspresivisme juga membentuk wacana budaya populer kita. Ide bahwa setiap individu memiliki suara unik yang perlu diekspresikan, bahwa seni adalah bentuk pencarian diri, bahwa otentisitas lebih penting daripada konformitas—semua ini adalah buah dari ekspresivisme. Taylor menunjukkan bahwa modernitas dibentuk oleh transformasi historis yang memberi otoritas baru pada suara batin. Dengan demikian, relevansi The Expressivist Turn tidak hanya bersifat akademis, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam cara kita berbicara tentang kebebasan, seni, agama, dan identitas.
Kesimpulan
Membaca The Expressivist Turn melalui kerangka yang diberikan Charles Taylor memperlihatkan bagaimana modernitas dibentuk oleh pergeseran radikal dalam cara manusia memahami alam, diri, dan Tuhan. Dari pandangan eksternal yang menekankan tatanan providensial dan bukti desain ciptaan, Romantisisme membawa kita ke arah internalisasi, di mana alam dipahami sebagai sumber batiniah yang berbicara melalui perasaan dan ekspresi manusia. Taylor menegaskan sejak awal bahwa “Kant offers one form of modern internalization… Another comes with that family of views in the late eighteenth century that represents nature as an inner source” (hlm. 368). Dengan kutipan ini, ia menempatkan Romantisisme sejajar dengan rasionalisme Kantian sebagai dua jalur besar internalisasi modern.
Gagasan tentang alam sebagai sumber menjadi pusat konseptual bagi pemberontakan Romantisisme terhadap rasionalisme klasik. Taylor menulis: “The picture of nature as a source was a crucial part of the conceptual armoury in which Romanticism arose and conquered European culture and sensibility” (hlm. 368). Tanpa pemahaman ini, kita tidak dapat menangkap alasan mengapa Romantisisme mampu menaklukkan imajinasi Eropa. Alam memberi legitimasi pada perasaan, imajinasi, dan suara batin sebagai sumber otoritas moral yang sah. Dengan cara ini, Romantisisme membentuk horizon baru dalam sejarah kesadaran manusia.
Transformasi besar ini tidak terputus dari tradisi lama, melainkan lahir dari dialektika dengan providensialisme dan Deisme. Taylor mengingatkan: “All these writers see human beings as set in a larger natural order, often conceived as a providential order, with which they should be in harmony” (hlm. 369). Namun, titik berat segera bergeser. Apa yang semula ditekankan sebagai tatanan eksternal, kini diinternalisasi sebagai keyakinan batin. Tuhan dipahami bukan lagi hanya melalui argumen desain, tetapi melalui suara hati yang beresonansi dengan alam: “God, then, is to be interpreted in terms of what we see striving in nature and finding voice within ourselves” (hlm. 371).
Implikasi pergeseran ini sangat luas. Moralitas tidak lagi berakar pada hukum eksternal, tetapi pada perasaan. Taylor menulis: “The good life is originally defined partly in terms of certain sentiments” (hlm. 372). Dengan demikian, sentimentalism abad ke-18 menemukan rumah barunya dalam filsafat alam sebagai sumber. Moralitas dan keindahan melebur menjadi satu. “This slide… tends to dissolve the distinction between the ethical and the aesthetic” (hlm. 373). Apa yang indah sekaligus yang baik, dan apa yang baik sekaligus yang indah. Inilah inti dari etika Romantis, yang berbeda tajam dari tradisi klasik.
Di sinilah ekspresivisme menemukan bentuk penuhnya. Hidup otentik berarti mengekspresikan suara batin. Taylor menegaskan: “Fulfilling my nature means expressing an inner voice, the voice or impulse” (hlm. 374). Ekspresi bukan hanya komunikasi, melainkan manifestasi kodrat manusia. “To express something is to make it manifest in a given medium” (hlm. 374). Dengan demikian, seni, moralitas, dan spiritualitas semuanya berpangkal pada ekspresi diri sebagai perwujudan alam yang berbicara melalui manusia.
Warisan ekspresivisme ini tidak berhenti pada Romantisisme. Ia membentuk modernitas hingga kini. Nilai otentisitas, posisi sentral seni, spiritualitas batin, bahkan etika ekologis kontemporer, semuanya dapat ditelusuri kembali pada transformasi yang dirumuskan Taylor sebagai The Expressivist Turn. Apa yang lahir sebagai pemberontakan terhadap rasionalisme klasik kini menjadi norma kultural yang kita anggap wajar: bahwa setiap orang memiliki suara batin unik yang harus diekspresikan, bahwa seni adalah sarana kebenaran, dan bahwa hidup baik adalah hidup otentik.
Pada akhirnya, The Expressivist Turn yang digambarkan Taylor adalah sebuah revolusi dalam kesadaran manusia. Ia memindahkan pusat otoritas moral dari luar ke dalam, dari desain ke ekspresi, dari hukum universal ke suara batin. Alam sebagai sumber adalah metafora besar yang memungkinkan pergeseran ini. Dengan mendengarkan suara alam dalam diri, manusia modern menemukan jalan baru menuju Tuhan, kebenaran, dan keindahan. Inilah warisan Romantisisme yang terus hidup hingga kini, membentuk horizon modernitas kita.

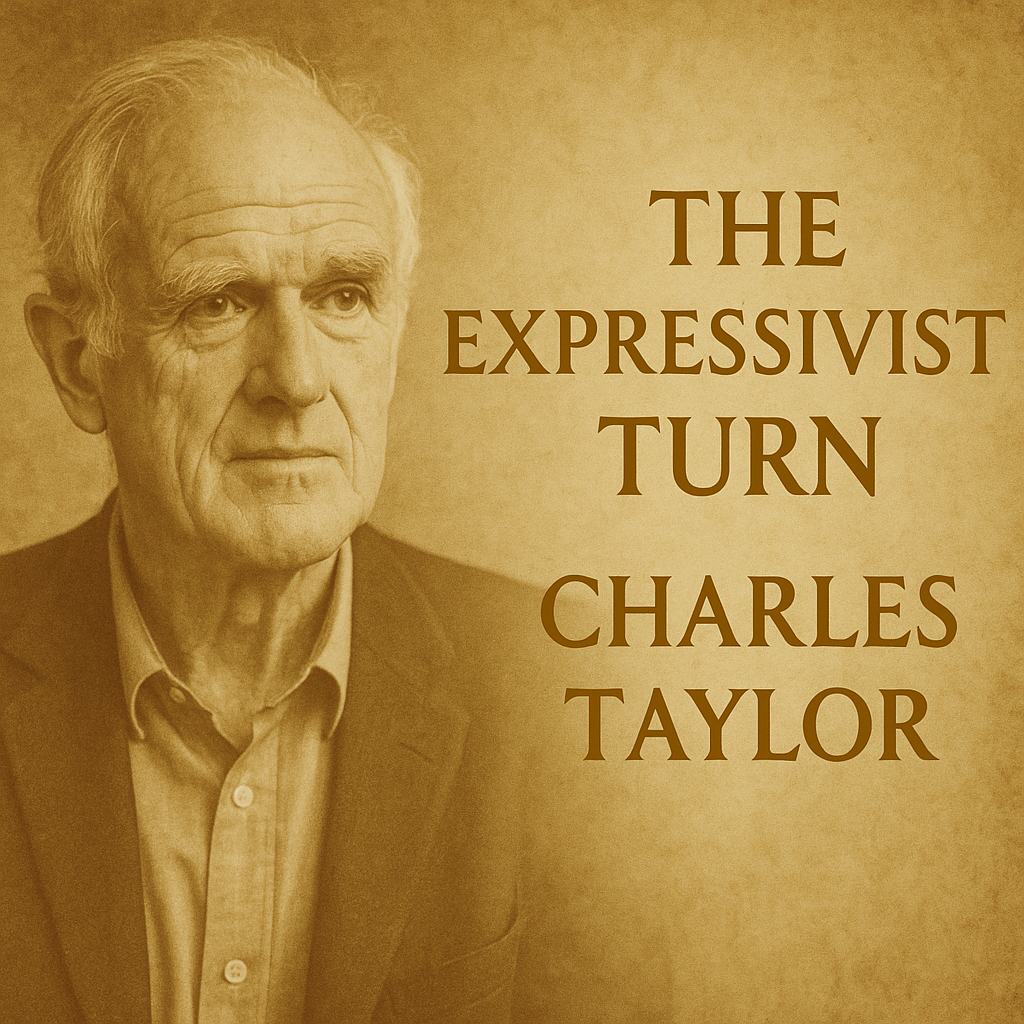

Leave a Reply