A. Pendahuluan
Tulisan ini hanya sebuah catatan di balik tirai yang sempat penulis rekam melalui ingatan shubuh dan menarasikannya kembali, –tentu bersama perspektif penulis– sebagai sebuah ikhtiar literasi untuk menjaga pemikiran seorang Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) yang sayang jika dibiarkan menghilang tanpa dicatat. Setiap Rabu Shubuh, KBA mengisi kajian di Masjid Kampus Fathun Qarib — masjid yang dikawal kepengurusannya oleh Ustadz Saifuddin A. Rasyid, sebagai Imeum Syiek atau Imam Besar di masjid tersebut. Dari ruang kecil inilah lahir perbincangan yang besar, yakni tentang fiqh, kekuasaan, dan sejarah intelektual Islam yang begitu kompleks. Kajian tersebut tidak sekadar pengajaran rutin, tetapi merupakan proses transmisi pengetahuan yang sarat refleksi epistemologis, di mana tradisi ilmiah Islam dikontekstualisasikan dengan realitas sosial masa kini. Catatan ini hadir bukan hanya untuk mendokumentasikan percakapan akademik seorang pemikir, melainkan juga untuk menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan kritis dapat tumbuh dari ruang spiritual yang sederhana — antara zikir dan berpikir, antara tradisi pesantren dan universitas modern.
Selaras dengan keilmuan dan kepakarannya, KBA menyampaikan materi hukum Islam dan fiqh yang saya rasakan direncanakan secara berseri dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang lintas disiplin antara teologi, sejarah, dan sosiologi pengetahuan. Dalam setiap pertemuan, ia tidak sekadar menjelaskan hukum dalam pengertian normatif, tetapi membukanya sebagai wacana intelektual yang hidup — bagaimana hukum Islam terbentuk, dipengaruhi, dan memengaruhi struktur kekuasaan politik sepanjang sejarah. Ia menempatkan fiqh sebagai hasil dari knowledge production dalam tradisi Islam, yang lahir melalui pergumulan panjang antara teks dan konteks, antara otoritas ilahi dan realitas manusia. Dengan gaya penyampaian yang tenang namun tajam, KBA mengajak jamaah memahami fiqh tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai refleksi budaya dan sistem pengetahuan yang memiliki sejarah sosialnya sendiri. Dalam pandangan beliau, memahami fiqh berarti menelusuri sejarah peradaban Islam, di mana para ulama bukan hanya ahli hukum, melainkan juga arsitek pemikiran dan penjaga moralitas umat.
Materi kajian KBA pagi ini menjelaskan dinamika hubungan antara fiqh, kekuasaan politik, dan produksi pemikiran hukum Islam dalam lintasan sejarah Islam klasik hingga kontemporer. Dengan menekankan pentingnya kajian Tarikh Tasyri’ KBA ingin menjelaskan bahwa fiqh tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara teks wahyu, konteks sosial, dan struktur kekuasaan. Intervensi politik terhadap fiqh melahirkan fenomena mazhab resmi negara, sekaligus mendorong lahirnya kelompok ulama independen yang mempertahankan otonomi keilmuan. Di sisi lain, munculnya ushul fiqh sebagai metodologi epistemologis menjadi penanda penting bagi pembentukan rasionalitas hukum Islam. Kajian ini juga mengkritik pendidikan fiqh modern yang cenderung deskriptif dan kurang kritis terhadap konteks sejarah dan sosial pembentuknya. Dengan menghidupkan pendekatan kritis-historis, fiqh dapat kembali dipahami sebagai ilmu yang dinamis, membumi, dan relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.
B. Pembahasan
Fiqh sebagai disiplin hukum Islam menempati posisi yang sangat sentral dalam peradaban Islam, sebab ia berfungsi bukan hanya sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan etika sosial dan spiritual bagi umat. Melalui fiqh, umat Islam memahami bagaimana prinsip-prinsip wahyu diterapkan dalam kehidupan nyata, mulai dari aspek ibadah hingga muamalah. Keberadaannya menjembatani antara teks Al-Qur’an dan realitas sosial manusia, menjadikan fiqh sebagai refleksi konkret dari ajaran Islam yang hidup. Namun demikian, fiqh tidak lahir secara tiba-tiba atau terlepas dari dinamika sejarah umat Islam. Ia tumbuh dan berkembang melalui proses panjang yang melibatkan dialog antara teks, realitas sosial, dan otoritas ulama. Karena itu, memahami fiqh berarti juga memahami bagaimana masyarakat Islam membentuk dan dibentuk oleh sistem nilai yang diatur dalam hukum-hukum tersebut.
Dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan fiqh selalu beriringan dengan konfigurasi kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Setiap periode pemerintahan Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Abbasiyah, maupun kesultanan regional, memiliki corak fiqh yang berbeda. Penguasa sering kali menjadikan mazhab tertentu sebagai dasar hukum negara untuk menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Sebagai contoh, mazhab Hanafi memperoleh posisi istimewa di bawah pemerintahan Abbasiyah karena dianggap paling rasional dan sistematis dalam menghadapi kebutuhan administrasi negara. Namun di balik hubungan itu, muncul pula ketegangan antara kekuasaan dan ulama yang ingin mempertahankan independensi keilmuan. Situasi ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya merupakan produk keagamaan, melainkan juga hasil interaksi politik yang membentuk arah dan orientasinya.
Keterkaitan antara fiqh dan kekuasaan menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar sistem normatif yang beku, melainkan suatu bentuk living law yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Para ulama, sebagai produsen pengetahuan hukum, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan tuntutan sosial. Melalui metodologi ushul fiqh, mereka berupaya menafsirkan kembali prinsip-prinsip hukum sesuai konteks masyarakat yang berkembang. Akan tetapi, pada saat yang sama, campur tangan politik seringkali mengubah arah perkembangan fiqh, menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam harus tunduk pada kekuasaan duniawi. Oleh karena itu, studi terhadap fiqh tidak cukup hanya memahami teks-teks hukumnya, melainkan juga harus menggali latar belakang sosial, politik, dan epistemologis yang membentuknya.
Dalam hal ini perkembangan fiqh dapat ditinjau melalui tiga kerangka besar yang saling berkaitan, yaitu genealogi ilmu fiqh, relasi fiqh dengan kekuasaan, dan fiqh sebagai produk pemikiran hukum. Pertama, secara genealogis, fiqh berkembang melalui perjalanan panjang dari masa sahabat hingga terbentuknya mazhab-mazhab besar dalam Islam. Fiqh bermula dari praktik ijtihad individual para sahabat Nabi yang menafsirkan wahyu berdasarkan kondisi sosial mereka, kemudian mengalami institusionalisasi pada masa tabi‘in dan tabi‘ut tabi‘in melalui munculnya pusat-pusat keilmuan seperti Madinah, Kufah, dan Basrah.
Dari proses ini lahirlah sistem metodologis yang terstruktur, yang kemudian dikenal sebagai ushul fiqh, terutama setelah Imam al-Syafi‘i menyusun Ar-Risalah sebagai karya monumental yang menegaskan hubungan logis antara nash dan akal dalam membangun hukum Islam. Melalui karya-karya ulama klasik, fiqh tidak lagi hanya berfungsi sebagai penetapan hukum, tetapi juga sebagai sistem berpikir yang mengatur bagaimana hukum itu harus diformulasikan dan diterapkan. Tradisi ini kemudian melahirkan keragaman mazhab yang tidak semata mencerminkan perbedaan pandangan hukum, tetapi juga menggambarkan variasi konteks sosial, geografis, dan politik di mana para ulama hidup. Dengan demikian, genealogi fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam tumbuh dari dialektika yang terus menerus antara teks, akal, dan realitas sosial umatnya, menjadikannya sebagai warisan intelektual yang dinamis dan berlapis sejarah.
Kedua, dalam konteks relasinya dengan kekuasaan, fiqh sering kali menjadi arena dialektika antara otoritas ulama dan legitimasi politik. Sejarah mencatat bahwa penguasa kerap menjadikan mazhab tertentu sebagai hukum resmi negara, seperti Abbasiyah yang mengadopsi mazhab Hanafi atau kesultanan Mamluk yang meneguhkan mazhab Syafi‘i, sementara sebagian ulama menolak kooptasi politik dan mempertahankan independensi keilmuan mereka. Dinamika ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai alat pengatur sosial dan simbol otoritas moral dalam masyarakat Islam.
Dalam kerangka tersebut, hubungan antara ulama dan penguasa membentuk pola yang saling memengaruhi: kekuasaan memerlukan legitimasi keagamaan untuk menjaga stabilitas, sementara fiqh memerlukan ruang politik yang kondusif agar dapat berkembang secara bebas. Di sinilah letak keseimbangan yang rapuh namun produktif dalam sejarah Islam, ketika hukum menjadi jembatan antara idealisme teologis dan pragmatisme politik. Relasi inilah yang terus menjadi bahan refleksi dalam studi hukum Islam kontemporer—bagaimana menjaga kemurnian nilai-nilai syariat tanpa menafikan realitas kekuasaan yang selalu hadir di balik setiap produksi hukum.
Ketiga, dalam perspektif epistemologi hukum, fiqh dapat dipahami sebagai hasil produksi pengetahuan hukum Islam — suatu proses intelektual yang melibatkan interpretasi, rasionalisasi, dan sistematisasi terhadap teks-teks suci dalam konteks sosial tertentu. Karena itu, fiqh bukanlah hukum ilahi yang bersifat absolut, melainkan konstruksi intelektual manusia yang berupaya memahami kehendak Tuhan melalui metodologi ijtihad. Pandangan ini menegaskan bahwa studi fiqh harus dilihat sebagai bagian dari dinamika pemikiran Islam yang terus bergerak antara teks, akal, dan realitas historis yang melingkupinya.
Dalam konteks inilah, fiqh menjadi ruang dialog antara keabadian nilai-nilai syariat dan dinamika pemikiran manusia yang terus berkembang. Melalui kesadaran epistemologis ini, studi fiqh tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun tradisi keilmuan Islam yang reflektif, progresif, dan selalu berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, untuk menghidupkan kembali fiqh sebagai ilmu yang relevan, setidaknya diperlukan tiga paradigma baru. Pertama, analisis kritis-historis, yakni memahami hukum dalam konteks sosialnya. Fenomena “tabaca, ta deungo, hana dawa” yang dikutip dari konteks Aceh — membaca dan mendengar tanpa daya kritis — mencerminkan stagnasi intelektual dalam studi fiqh modern. Banyak lembaga pendidikan Islam hanya mengajarkan fiqh secara normatif dan tekstual tanpa menggali konteks sosial atau historis yang melatarinya. Akibatnya, fiqh kehilangan daya reflektifnya terhadap perubahan masyarakat dan cenderung menjadi dogma yang kering dari makna sosial.
Kedua, diperlukan kajian kontekstual yang mampu menghubungkan hukum Islam dengan problematika masyarakat modern, seperti isu keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan transformasi teknologi. Dengan cara ini, fiqh tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan hukum masa lalu, melainkan sebagai wacana yang terus berinteraksi dengan realitas kontemporer. Ketiga, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fiqh dengan filsafat, sosiologi, politik, dan antropologi agar ia mampu menjawab persoalan manusia secara lebih komprehensif dan holistik.
Selain itu, otonomisasi keilmuan ulama menjadi keharusan, agar fiqh tetap terjaga dari kooptasi kekuasaan dan tidak kehilangan independensi moralnya. Ulama harus berdiri sebagai penafsir kebenaran yang berpihak pada keadilan, bukan sekadar sebagai corong legitimasi politik. Dengan pendekatan ini, fiqh dapat kembali berfungsi sebagai sumber etika sosial dan instrumen keadilan — bukan hanya perangkat legal-formal, melainkan juga wahana pembentukan kesadaran moral umat. Pada akhirnya, fiqh yang hidup adalah fiqh yang mampu berdialog dengan zaman, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa kehilangan akar spiritual dan tradisinya sendiri.
C. Penutup
Perkembangan fiqh tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan konteks sosial-historis yang melingkupinya. Perjalanan sejarah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah berdiri dalam ruang yang steril dari realitas sosial dan kekuasaan. Ia senantiasa tumbuh melalui dialektika antara teks wahyu, rasionalitas ulama, dan kondisi politik yang mengitarinya. Dalam konteks ini, fiqh dapat dilihat sebagai hasil dari proses kreatif dan reflektif umat Islam dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam sistem kehidupan nyata. Intervensi politik terhadap fiqh memang sering menimbulkan ketegangan antara independensi ulama dan kepentingan negara, namun pada saat yang sama, dinamika tersebut telah memperkaya tradisi hukum Islam dengan pelbagai corak pemikiran yang lahir dari pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami fiqh berarti memahami peradaban Islam itu sendiri — sebuah peradaban yang bergerak antara wahyu dan akal, antara idealitas ilahi dan realitas manusiawi.
Ke depan, tantangan terbesar studi fiqh adalah bagaimana menjadikan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan relevan tanpa kehilangan ruh spiritual dan moralnya. Diperlukan keberanian untuk menafsirkan ulang tradisi dengan tetap menghormati akar klasiknya, agar fiqh tidak terjebak dalam formalisme hukum, melainkan menjadi sumber etika sosial dan inspirasi keadilan universal. Dengan mengintegrasikan pendekatan historis, kontekstual, dan interdisipliner, fiqh dapat memainkan kembali peran transformatifnya sebagai kekuatan moral yang menuntun masyarakat menuju kemaslahatan bersama. Dengan demikian, fiqh bukan hanya warisan masa lalu, melainkan juga proyek intelektual yang terus bergerak di setiap zaman.

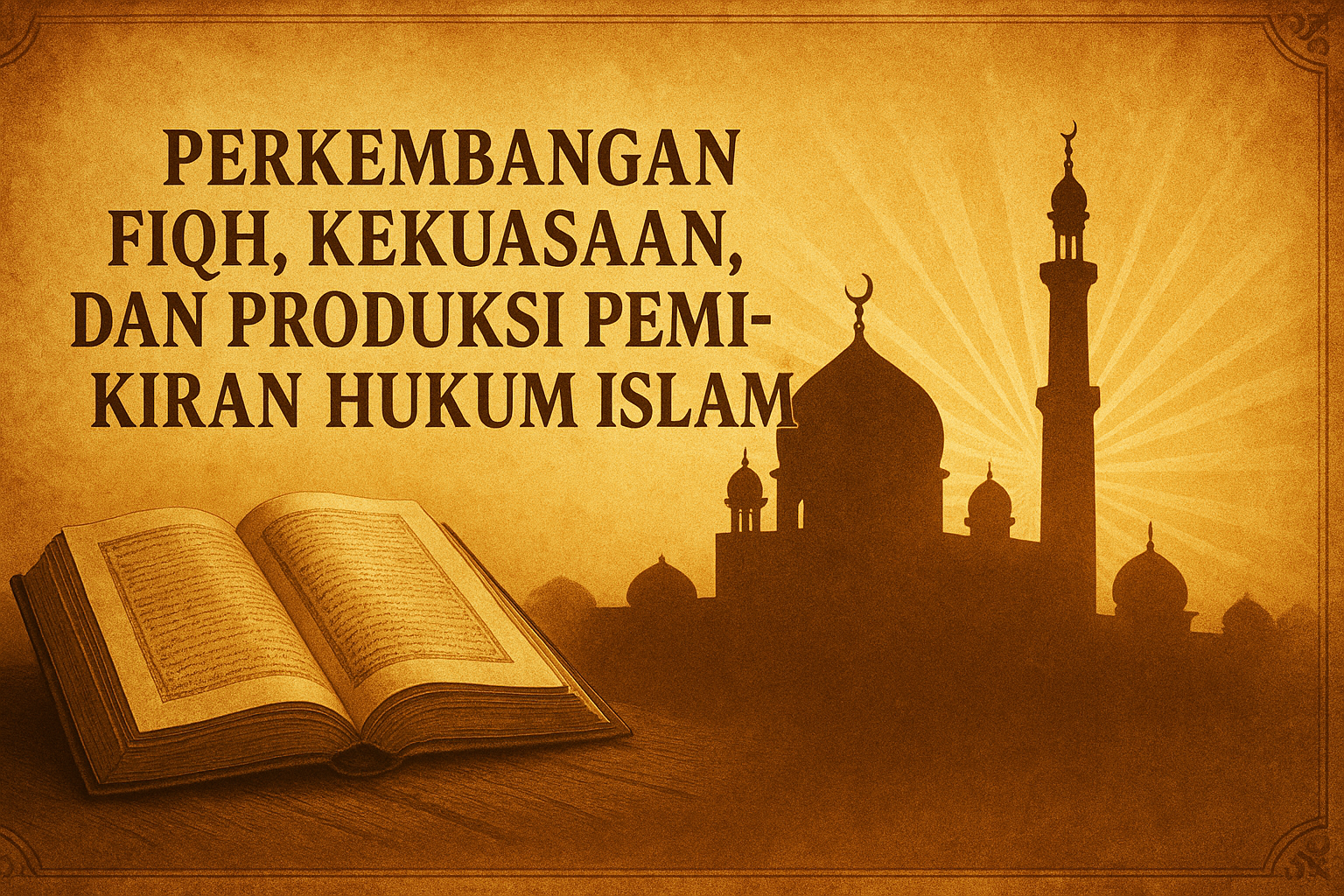

Leave a Reply