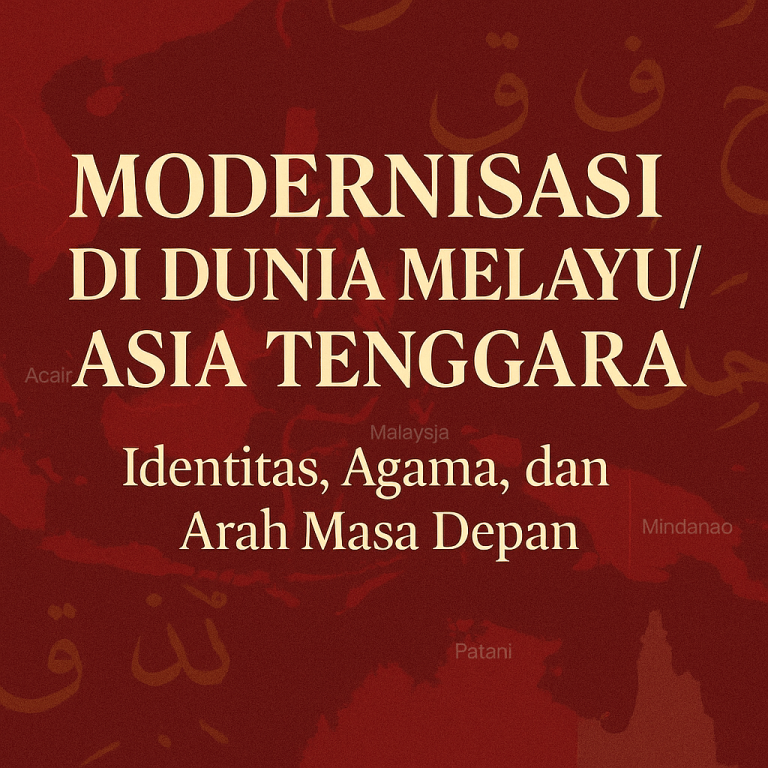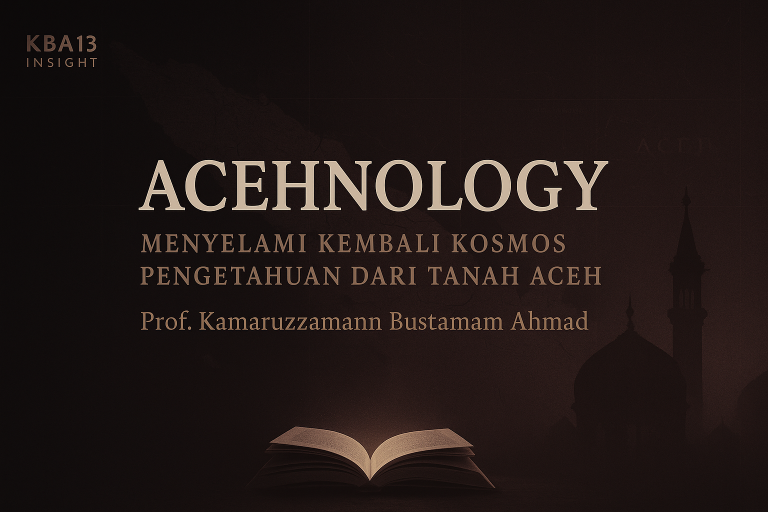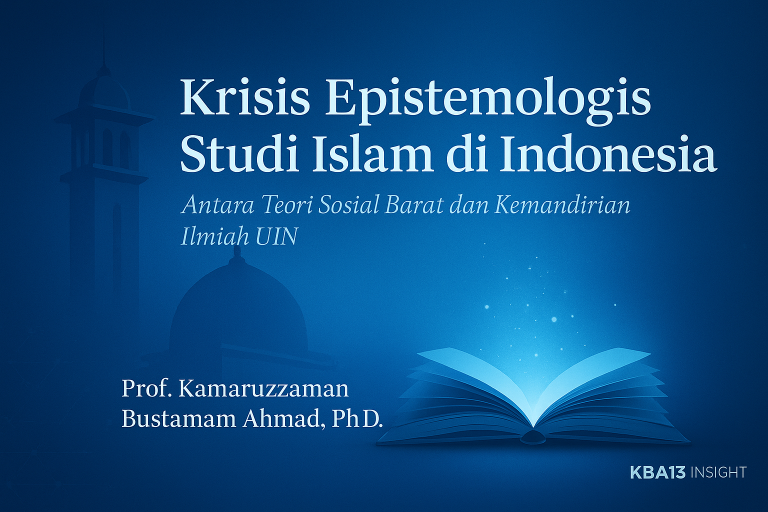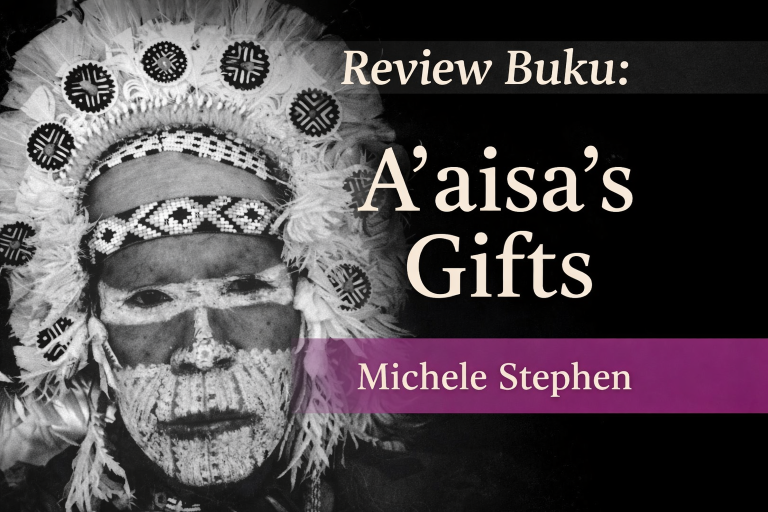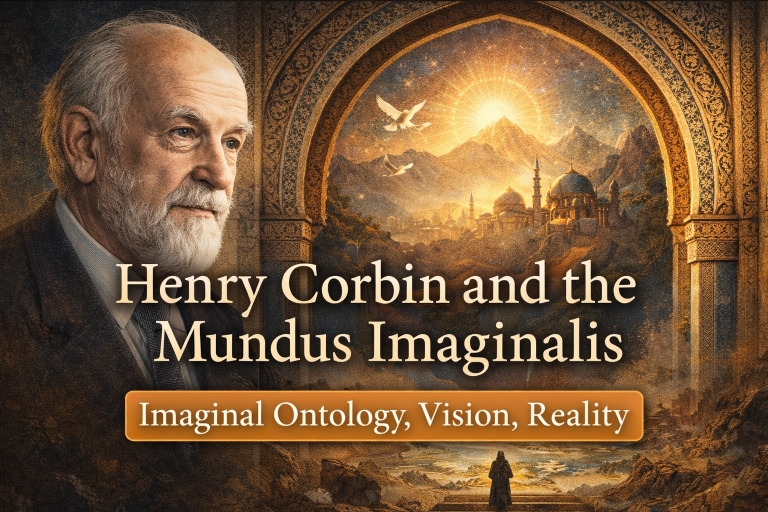Pendahuluan – Menyusuri Luka Bumi Pertiwi
Indonesia adalah negara kepulauan dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, menyimpan lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan yang dikenal secara global (FAO, 2020). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peta hijau itu kian terkoyak oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan proyek infrastruktur ekstraktif. Perubahan ini bukan sekadar transformasi ekonomi, melainkan juga transformasi ekologis dan sosial yang memengaruhi jutaan warga di berbagai pulau besar Indonesia (Margono et al., 2014).
Dalam perjalanan dari Samarinda, Sulawesi Tengah, Bengkulu, hingga Merauke, bentang alam Nusantara menampilkan wajahnya yang baru. Di Samarinda, Sungai Mahakam yang dulu menjadi jalur perdagangan rempah kini dipenuhi kapal tongkang pengangkut batubara yang berlayar siang-malam. Bahodopi di Sulawesi Tengah berubah menjadi “lorong industri” di mana truk tambang dan alat berat mendominasi jalanan. Bengkulu diselimuti debu batubara dari truk terbuka, membuat udara sesak dan kotor. Di Merauke, ratusan kilometer hutan Papua telah rata menjadi kebun sawit, meninggalkan garis-garis cokelat di peta satelit seperti luka yang menganga.
Fenomena ini sejalan dengan data Global Forest Watch yang mencatat bahwa Indonesia kehilangan rata-rata 1,47 juta hektare hutan setiap tahun antara 2001 dan 2019 (Global Forest Watch, 2021). Sebagian besar kehilangan ini terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit (Greenpeace Indonesia, 2021). Dalam konteks Papua, program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sendiri mencakup rencana pembukaan lahan hingga 1,2 juta hektare, sebagian besar di atas hutan primer dan lahan gambut (Ginting & Pye, 2013).
Situasi yang serupa ditemukan di provinsi Riau dan Kalimantan Barat, di mana bentang alam telah terfragmentasi menjadi petak-petak kebun sawit. Di Riau, lebih dari 60% daratan telah berubah menjadi perkebunan (Walhi Riau, 2020). Di Kalimantan Barat, pembukaan hutan di hulu sungai besar telah mengubah pola hidrologi, memicu banjir besar yang menenggelamkan permukiman warga (Walhi, 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa fenomena yang saya temui di perjalanan bukan kasus lokal, melainkan pola nasional yang berulang.
Pendahuluan ini menggarisbawahi bahwa kerusakan hutan di Indonesia bukanlah sekadar statistik, melainkan kenyataan hidup yang bisa disaksikan dari tepi jalan, dermaga, hingga udara. Perjalanan etnografis ini memberikan wajah manusia dan lanskap nyata bagi angka-angka deforestasi yang sering kita baca di laporan. Selanjutnya, kita akan menelisik lebih dalam bagaimana proses transformasi hutan ini berlangsung, dari hutan belantara menjadi hamparan kelapa sawit yang mendominasi ekonomi dan politik lokal di berbagai wilayah Nusantara.
Potret Kerusakan Hutan dan Transformasi Menjadi Sawit
Transformasi hutan Indonesia menjadi perkebunan kelapa sawit adalah salah satu perubahan lanskap terbesar di Asia Tenggara dalam setengah abad terakhir. Sawit, yang awalnya diperkenalkan sebagai tanaman komersial oleh kolonial Belanda pada awal abad ke-20, kini telah berkembang menjadi komoditas unggulan nasional (Potter, 2015). Namun, di balik nilai ekspor yang mencapai miliaran dolar, proses ekspansi sawit kerap melibatkan pembukaan hutan primer dan gambut yang berharga tinggi secara ekologis.
Di lapangan, proses ini terlihat jelas. Perjalanan darat dari Palembang menuju Riau memperlihatkan hamparan sawit sejauh mata memandang, hanya sesekali terputus oleh desa atau kanal drainase. Di Merauke, deru chainsaw dan buldoser menggantikan kicau burung cendrawasih. Truk-truk besar membawa tandan buah segar (TBS) dari pedalaman ke pabrik pengolahan, meninggalkan jalanan berdebu dan udara panas. Papan nama perusahaan—baik nasional maupun asing—berdiri di pinggir jalan, menandai konsesi yang mereka kuasai.
Menurut Global Forest Watch (2021), dari total deforestasi di Indonesia antara 2001–2019, sekitar 3,23 juta hektare terjadi di lahan yang kemudian menjadi perkebunan sawit. Di Kalimantan Barat, 23% kehilangan hutan primer terjadi dalam radius 5 km dari pabrik kelapa sawit (Gaveau et al., 2016). Konversi ini sering menggunakan metode tebang-bakar yang, meskipun ilegal, tetap terjadi di lapangan karena biaya rendah dan lemahnya pengawasan (Tacconi, 2016).
Jika dibandingkan dengan Malaysia, ekspansi sawit Indonesia lebih banyak melibatkan lahan gambut dan hutan primer, yang memiliki cadangan karbon lebih tinggi (Carlson et al., 2012). Di provinsi Riau, kombinasi pembukaan lahan sawit dan kebakaran gambut telah melepaskan jutaan ton CO₂ ke atmosfer setiap tahun, menyebabkan kabut asap lintas negara yang memengaruhi Singapura dan Malaysia (Field et al., 2009).
Potret kerusakan ini menunjukkan bahwa ekspansi sawit bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan krisis ekologis. Ia mengubah struktur tanah, siklus hidrologi, dan keanekaragaman hayati secara drastis. Dengan latar ini, kita dapat memahami bahwa masalah sawit tidak bisa dilihat sebatas peningkatan PDB atau volume ekspor—ia menyentuh inti keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Bagian berikut akan membedah dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang muncul akibat transformasi masif ini.
Dampak Ekologis dan Sosial-Ekonomi
Pembukaan lahan untuk kelapa sawit di Indonesia membawa dampak ekologis yang luas dan kompleks. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah hilangnya fungsi ekologis hutan primer sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim. Margono et al. (2014) mencatat bahwa hilangnya hutan primer Indonesia setiap tahun menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Konversi hutan menjadi kebun monokultur sawit juga mengurangi keanekaragaman hayati secara drastis. Banyak spesies endemik seperti orangutan, harimau Sumatra, dan burung cendrawasih kehilangan habitat alaminya, mendorong mereka ke ambang kepunahan (Meijaard et al., 2018).
Di lapangan, masyarakat sekitar kebun sawit sering menghadapi krisis air. Akar kelapa sawit yang dalam menyerap air dalam jumlah besar, mengurangi ketersediaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian lokal. Studi Obidzinski et al. (2012) di Kalimantan menunjukkan bahwa banyak desa mengalami sumur kering pada musim kemarau, memaksa warga membeli air bersih dengan harga tinggi. Selain itu, kanal-kanal drainase yang dibuat untuk mengeringkan lahan gambut mempercepat oksidasi tanah, meningkatkan risiko kebakaran, dan mengubah ekosistem rawa menjadi lahan kering yang rapuh.
Masalah hidrologi ini berkontribusi pada peningkatan banjir di wilayah hilir. Hilangnya tutupan vegetasi mempercepat limpasan air hujan (run-off), sehingga sungai lebih cepat meluap dan membawa sedimen dalam jumlah besar. Kasus di Kalimantan Barat pada 2020 adalah contoh nyata: banjir besar yang menenggelamkan ribuan rumah terjadi setelah bertahun-tahun pembukaan hutan di daerah aliran sungai untuk perkebunan sawit dan tambang (Walhi, 2021). Air sungai yang keruh tidak hanya mengganggu ekosistem perairan, tetapi juga menurunkan kualitas air untuk konsumsi manusia.
Dari sisi sosial-ekonomi, sawit memang menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan. Namun, sistem kemitraan yang diterapkan banyak perusahaan seringkali membuat petani kecil bergantung penuh pada harga pasar global yang fluktuatif. McCarthy et al. (2012) menemukan bahwa petani plasma kerap terjebak dalam utang jangka panjang untuk membiayai pembukaan kebun dan perawatan awal, sementara harga TBS yang mereka terima berada di bawah harga acuan pemerintah. Ketimpangan distribusi keuntungan juga mencolok: sebagian besar laba dinikmati perusahaan besar, sedangkan petani dan pekerja hanya menerima porsi kecil dari rantai nilai.
Kombinasi dampak ekologis dan ketidakadilan ekonomi ini menunjukkan bahwa ekspansi sawit, jika tidak diatur dengan ketat, dapat menjadi sumber kerentanan jangka panjang. Krisis air, banjir, kebakaran lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kemiskinan struktural dapat saling memperkuat, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Pemahaman ini menjadi landasan untuk membicarakan Indonesawit sebagai potret luka kolektif bangsa—yang akan dibahas pada bagian berikut.
Konsep Indonesawit: Potret Luka Kolektif
Istilah Indonesawit dapat dibaca sebagai metafora atas transformasi besar-besaran lanskap Indonesia dari hutan tropis menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit. Indonesia kini bukan hanya negara dengan hutan hujan tropis terluas di Asia Tenggara, tetapi juga produsen minyak sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 58% pasokan global (USDA, 2023). Keberhasilan ini sering diangkat sebagai prestasi ekonomi nasional, namun jarang dibarengi kesadaran penuh akan ongkos ekologis dan sosial yang menyertainya.
Narasi Indonesawit menyatukan dua wajah Indonesia yang kontras. Di satu sisi, ada klaim keberhasilan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan devisa yang mengalir dari ekspor. Di sisi lain, ada hilangnya hutan adat, pergeseran pola hidup komunitas lokal, dan kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan. Meijaard et al. (2020) menekankan bahwa tanpa mitigasi yang serius, model ekspansi sawit yang ada saat ini akan mendorong deforestasi lanjutan dan memicu krisis iklim.
Jejak sejarah kelapa sawit di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi ini bukan terjadi dalam semalam. Diperkenalkan pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda, kelapa sawit awalnya hanya dibudidayakan dalam skala terbatas di Sumatra Timur (Potter, 2015). Namun, setelah era Orde Baru, perkebunan sawit menjadi salah satu sektor prioritas nasional, didukung kebijakan transmigrasi dan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Di sinilah Indonesawit mulai terbentuk: kombinasi modal besar, kebijakan negara, dan tenaga kerja migran yang mengubah wajah ratusan ribu kilometer persegi lahan.
Dari perspektif etnografis, Indonesawit juga merekam perubahan kehidupan sehari-hari di desa-desa. Di banyak wilayah, sawit menggeser pertanian subsisten seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Perubahan ini mempengaruhi ketersediaan pangan lokal dan ketahanan pangan rumah tangga (Cramb & McCarthy, 2016). Lahan yang dulunya menjadi ruang interaksi sosial, ritual budaya, atau sumber obat tradisional kini berpagar kawat dan dijaga satpam. Hal ini tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga lanskap sosial dan budaya.
Konsep Indonesawit pada akhirnya adalah pengingat bahwa transformasi ekonomi yang masif selalu memiliki konsekuensi ganda. Ia menguntungkan sebagian pihak—terutama pemilik modal dan eksportir—namun membebankan biaya ekologis, kesehatan, dan sosial pada pihak lain, seringkali mereka yang suaranya paling lemah di arena politik. Inilah luka kolektif yang dimaksud: luka yang dibagi secara tidak merata, namun meninggalkan jejak mendalam di tubuh dan jiwa Nusantara. Bagian selanjutnya akan menelusuri sejarah dan jejak global kelapa sawit di Indonesia untuk memahami bagaimana pola ini terbentuk dan mengapa ia sulit diubah.
Sejarah dan Jejak Global Kelapa Sawit di Indonesia
Kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukan tanaman asli Nusantara. Ia berasal dari Afrika Barat, khususnya wilayah pesisir Guinea, dan dibawa ke Asia Tenggara pada abad ke-19 oleh ahli botani kolonial (Potter, 2015). Di Indonesia, perkebunan komersial pertama berdiri di Deli, Sumatra Timur, pada 1911, dikelola oleh perusahaan Belanda Deli Maatschappij. Awalnya, perkebunan sawit hanya memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik dan sebagian kecil untuk ekspor ke Eropa. Namun, fondasi inilah yang kelak menjadi cikal-bakal ekspansi besar-besaran pada abad ke-20.
Perubahan signifikan terjadi pada era Orde Baru (1966–1998), ketika pemerintah menetapkan sawit sebagai komoditas strategis nasional. Melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), negara memfasilitasi perusahaan besar untuk bermitra dengan petani transmigran, memberikan mereka lahan dan bibit, namun juga mengikat dalam pola kredit dan pemasaran yang terkendali (McCarthy et al., 2012). Dalam periode ini, luas perkebunan sawit melonjak dari kurang dari 300 ribu hektare pada awal 1970-an menjadi lebih dari 2,5 juta hektare pada akhir 1990-an (BPS, 2023).
Krisis ekonomi 1997–1998 dan liberalisasi sektor perkebunan memicu gelombang baru ekspansi. Investasi asing masuk dengan cepat, terutama dari Malaysia dan Singapura. Perusahaan-perusahaan multinasional mengakuisisi atau bermitra dengan pemain lokal untuk menguasai lahan dalam skala puluhan hingga ratusan ribu hektare. Sejak awal 2000-an, pasar ekspor minyak sawit meluas tidak hanya untuk pangan, tetapi juga bahan bakar nabati (biofuel), menyusul kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa dan negara lain (Obidzinski et al., 2012).
Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 14,5 juta hektare dan produksi lebih dari 46 juta ton per tahun (USDA, 2023). Sekitar 70% produksinya diekspor, terutama ke India, Tiongkok, Uni Eropa, dan Pakistan. Peran global ini membuat kebijakan sawit Indonesia menjadi sorotan internasional, baik dalam konteks perdagangan, lingkungan, maupun hak asasi manusia.
Namun, jejak global kelapa sawit ini juga memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, sawit dianggap sebagai tanaman berproduktifitas tinggi yang dapat menopang ekonomi negara berkembang. Di sisi lain, banyak studi—seperti Carlson et al. (2012) dan Meijaard et al. (2020)—menunjukkan bahwa ekspansi sawit di Indonesia sering mengorbankan hutan primer, gambut, dan keanekaragaman hayati. Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya mengurangi dampak sawit, tetapi juga mengubah pola pikir pembangunan yang terlalu bergantung pada ekspansi lahan.
Perspektif Akademik dan Data Terbaru
Kajian akademik tentang kelapa sawit di Indonesia memposisikan komoditas ini sebagai fenomena multidimensi: ekonomi, ekologi, politik, dan sosial. Margono et al. (2014) menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan primer di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil, dengan puncak kehilangan pada 2012–2014, sebagian besar dipicu oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Data ini dikuatkan oleh Gaveau et al. (2022) yang menemukan bahwa ekspansi sawit menyumbang hampir seperempat deforestasi total di Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Dari perspektif perubahan iklim, IPCC (2019) memperingatkan bahwa konversi lahan gambut untuk sawit melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, yang sulit diimbangi bahkan dengan produktivitas sawit yang tinggi. Lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah masif selama ribuan tahun, dan ketika dikeringkan, karbon itu dilepaskan ke atmosfer, memperparah pemanasan global. Studi Miettinen et al. (2017) mengestimasi bahwa lebih dari 40% perkebunan sawit di Sumatra dan Kalimantan berada di atas lahan gambut yang rentan.
Di sisi ekonomi, BPS (2023) mencatat bahwa pada 2022 nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai USD 30,3 miliar, menjadikannya komoditas ekspor nonmigas terbesar. Namun, Cramb & McCarthy (2016) mengingatkan bahwa distribusi keuntungan dari rantai pasok ini sangat timpang. Perusahaan agribisnis besar menguasai mayoritas keuntungan, sementara petani kecil dan buruh kebun menerima porsi yang jauh lebih kecil.
Dari perspektif tata kelola, penelitian Colchester et al. (2011) menyoroti lemahnya perlindungan hak masyarakat adat dan lokal dalam ekspansi sawit. Banyak konsesi diberikan di atas tanah ulayat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (free, prior, and informed consent / FPIC). Konflik lahan menjadi salah satu dampak sosial paling menonjol, dengan ribuan kasus tercatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setiap tahunnya.
Terakhir, perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya reformasi. Moratorium izin baru untuk perkebunan sawit yang diberlakukan pemerintah sejak 2018 hingga 2021 bertujuan membenahi tata kelola lahan dan meningkatkan produktivitas kebun yang ada. Namun, evaluasi Greenpeace Indonesia (2022) menunjukkan bahwa implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek penegakan hukum dan transparansi data konsesi. Fakta ini menggarisbawahi bahwa meski ada kemajuan kebijakan, tantangan struktural dalam industri sawit Indonesia masih sangat besar.
Penutup – Menimbang Ulang Arah Pembangunan
Transformasi hutan Indonesia menjadi hamparan sawit adalah salah satu kisah pembangunan paling dramatis di era modern Nusantara. Dari perspektif ekonomi, sawit telah menjadi mesin devisa negara, membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan di daerah-daerah terpencil. Namun, seperti yang diuraikan dalam berbagai bagian sebelumnya, keberhasilan ini datang dengan harga ekologis dan sosial yang tinggi. Indonesia berada di persimpangan jalan: melanjutkan model ekspansi berbasis lahan, atau beralih menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Perjalanan etnografis melintasi Samarinda, Bahodopi, Bengkulu, hingga Merauke memperlihatkan bahwa dampak sawit tidak hanya dapat dihitung dengan angka, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung: udara panas dan berdebu, sungai yang keruh, tanah yang kering, serta perubahan pola hidup masyarakat desa. Kesaksian lapangan ini sejalan dengan temuan ilmiah bahwa pembukaan hutan dan konversi lahan gambut untuk sawit memicu banjir, kebakaran, krisis air, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Margono et al., 2014; Meijaard et al., 2020).
Menimbang ulang arah pembangunan berarti menggeser fokus dari ekspansi menuju intensifikasi berkelanjutan. Produktivitas sawit rakyat masih dapat ditingkatkan melalui peremajaan (replanting) bibit unggul, perbaikan manajemen kebun, dan akses pembiayaan yang adil. Di sisi kebijakan, penguatan moratorium izin, sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO, serta perlindungan hak masyarakat adat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif industri ini (Colchester et al., 2011; Cramb & McCarthy, 2016).
Selain itu, strategi diversifikasi ekonomi daerah penghasil sawit perlu diperkuat. Bergantung hanya pada satu komoditas membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan pasar internasional. Investasi di sektor pertanian pangan, ekowisata, dan energi terbarukan dapat menjadi jalan keluar untuk menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan.
Akhirnya, Indonesawit harus menjadi cermin kolektif bangsa. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial akan menghasilkan luka yang sulit disembuhkan. Pilihan ke depan ada di tangan para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas: apakah kita akan terus menambah bercak “kurap” di peta satelit Nusantara, atau mulai merawat kembali paru-paru dunia yang masih tersisa untuk generasi mendatang.
Daftar Pustaka
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kelapa sawit Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Asner, G. P., Pittman, A. M., Trigg, S. N., & Adeney, J. M. (2012). Carbon emissions from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. Nature Climate Change, 3(3), 283–287. https://doi.org/10.1038/nclimate1702
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2011). Oil palm expansion in Indonesia: Problems and implications for forest and peatland. Bogor: Forest Peoples Programme.
- Cramb, R., & McCarthy, J. (2016). The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia. Singapore: NUS Press.
- (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Field, R. D., van der Werf, G. R., & Shen, S. S. P. (2009). Human amplification of drought-induced biomass burning in Indonesia since 1960. Nature Geoscience, 2(3), 185–188. https://doi.org/10.1038/ngeo443
- Gaveau, D. L. A., Pirard, R., Salim, M. A., Tonoto, P., Yaen, H., Parks, S. A., & Carmenta, R. (2016). Overlapping land claims limit the use of satellites to monitor No-Deforestation commitments and No-Burning compliance. Conservation Letters, 10(2), 257–264. https://doi.org/10.1111/conl.12256
- Gaveau, D. L. A., et al. (2022). Deforestation and industrial plantations development in Borneo. Scientific Reports, 12(1), 1–13. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07869-5
- Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting agribusiness development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 6(1), 160–182.
- Global Forest Watch. (2021). Indonesia deforestation rates & statistics. Retrieved from https://www.globalforestwatch.org
- Greenpeace Indonesia. (2021). Deforestasi untuk perkebunan sawit di Indonesia. Jakarta: Greenpeace Indonesia.
- Greenpeace Indonesia. (2022). Evaluasi moratorium sawit 2018–2021. Jakarta: Greenpeace Indonesia.
- (2019). Climate Change and Land: An IPCC Special Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. Nature Climate Change, 4(8), 730–735. https://doi.org/10.1038/nclimate2277
- McCarthy, J. F., Gillespie, P., & Zen, Z. (2012). Swimming Upstream: Local Indonesian Production Networks in “Globalized” Palm Oil Production. World Development, 40(3), 555–569. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.012
- Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S. A., Carlson, K. M., Juffe-Bignoli, D., & Brooks, T. M. (2018). Oil palm and biodiversity. A Situation Analysis by the IUCN Oil Palm Task Force. Gland, Switzerland: IUCN.
- Meijaard, E., Brooks, T. M., Carlson, K. M., Slade, E. M., Garcia-Ulloa, J., Gaveau, D. L., … & Sheil, D. (2020). The environmental impacts of palm oil in context. Nature Plants, 6(12), 1418–1426. https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w
- Miettinen, J., Hooijer, A., Tollenaar, D., Page, S. E., Malins, C., Vernimmen, R., … & Silvius, M. (2017). Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands. Environmental Research Letters, 12(10), 104002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa9ea3
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. Ecology and Society, 17(1), 25. https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125
- Potter, L. (2015). Managing oil palm landscapes: A seven-country comparison. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- (2023). Oilseeds: World markets and trade. Washington D.C.: United States Department of Agriculture.
- (2021). Analisis banjir Kalimantan Barat 2020. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Walhi Riau. (2020). Laporan tahunan 2020. Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.